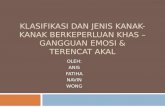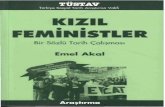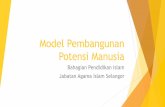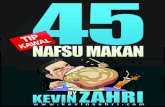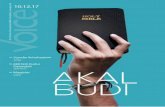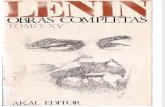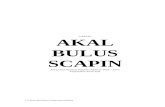AKAL, NAFSU DAN QOLBU DALAM TASAWUF
description
Transcript of AKAL, NAFSU DAN QOLBU DALAM TASAWUF
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hakikat manusia diciptakan dibumi ini adalah untuk beribadah kepada sang
pencipta, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-NYA dalam Qs. Adz-Dzariyaat
ayat 56,
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah (beribadah) kepada-Ku.
Di sisi lain, manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna sebab dilengkapi
dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada makhluk selain manusia, yaitu akal. Oleh
karena manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan sempurna, maka dalam
diri manusia terdapat semua hal yang terdapat pada makhluk selain manusia (nafsu) dan
bahkan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia (akal) dan
juga manusia dibekali dengan hati sebagai penyeimbang antara akal dan nafsu.
Di dalam Al-Quran dan Al-Hadits penunjukkan manusia banyak menggunakan
kata Nafs. Kata ini memiliki pengertian yang bermacam-macam sesuai dengan tempat
penyebutannya. Kata nafs terkadang diartikan sebagai diri (nafs), terkadang juga
diartikan sebagai nafsu (nafsu), terkadang juga diartikan sebagai akal (aql) dan
terkadang juga diartikan sebagai hati (qolb).1
Allah berfirman dalam Qs. Adz-Dzariyat ayat 20,
Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?
Oleh karenanya, dalam makalah ini kita akan membicarakan akal (aql), Nafsu (nafsu)
dan hati (qolb).
1Husein Husein Syahatah, Membersihkan Jiwa dengan Muhasabah, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003),
hlm. 3
-
2
BAB II
PEMBAHASAN
Seperti yang telah kita singgung pada latar belakang, bahwa manusia diciptakan
dengan membawa potensi bawaan, diantaranya nafsu, akal dan hati yang masing-masing
memiliki fungsi dan peran bagi manusia itu sendiri. Mengenai konsep nafsu, akal dan
hati, kita akan membahas melalui definisi dan suatu hal yang berkaitan dengannya,
A. Nafsu (nafs)
1. Pengertian Nafsu
Quraish Shihab berpendapat, bahwa kata nafs dalam al-Quran mempunyai aneka
makna, seperti sebagai sesuatu yang menggambarkan totalitas manusia sebagai suatu
yang merupakan hasil perpaduan jasmani dan ruhani manusia. Perpaduan yang
kemudian menjadikan yang bersangkutan mengenal perasaan, emosi, dan pengetahuan
serta dikenal dan dibedakan dengan manusia-manusia lainnya
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh)
orang lain atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan
dia Telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara
kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan
manusia semuanya. (Qs. Al-Maidah 32)
sesuatu yang menghasilkan tingkah laku,
Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Qs. Ar-Radu 11)
-
3
Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa nafs dalam konteks pembicaraan
manusia, menunjuk kepada sisi dalam manusia yang berpotensi baik dan buruk.2
Secara leksikal (bahasa) antara lain diartikan dengan jiwa, ruh, semangat, hasrat,
kehendak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, jiwa diartikan dengan: (1) ruh manusia
(yang ada di dalam tubuh dan menghidupkan) atau nyawa; (2) seluruh kehidupan batin
manusia (yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya) atau
keinginan.
Nafs dalam pengertian ini diasumsikan sebagai gerak imanen (gerak dalam) yang
bersifat qalbiyah (ke-hati-an), dan sebagai pusat grativasi manusia, pusat komando yang
mengatur seluruh potensi kemanusiaan. Nafs ini berisi impuls-impuls yang berupa rasa
sedih, rasa benci, rasa iri hati, yang terkumpul dalam hati. Nafs diciptakan oleh Allah
dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat
kebaikan dan keburukan.
2. Tingkatan Nafsu
Menurut al-Ghazali seperti yang dikutip oleh Amin Syukur, nafs mengandung dua
makna ganda, yaitu:3
a. Pertama, dimaksudkan berkolaborasinya kekuatan marah dan keinginan
biologis (syahwat) pada diri manusia.
b. Kedua, suatu perasaan halus (lathifah), yaitu jiwa manusia dan substansinya,
tetapi berbeda-beda sesuai dengan ahwal (kondisi-kondisi ruhani) masing-
masing. Inilah hakekat manusia yang membedakannya dari nafs. Jika ia
tunduk di bawah perintah dan jauh dari kegoncangan yang disebabkan nafsu
syahwat disebut dengan nafs muthmainah (jiwa yang tentram). Nafs inilah
yang merupakan hakikat manusia yang dapat mengetahui Allah dan seluruh
yang diketahuinya. Jika ketundukannya tidak sempurna, hemat al-Ghazali,
2 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 285-286.
3 Amin Syukur, Menggugat Tasawwuf, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 67
-
4
bahkan menjadi pendorong bagi nafsu syahwat dan memperlihatkan
keinginan kepadanya, maka nafs itu dinamai dengan nafs al-lawwama.4
Perumusan Al-Ghazali mengenai macam-macam nafs diatas, ini bersumberkan
pada ayat-ayat al-Quran, yaitu Sbb:
a. Nafs al-ammarah
QS. Yusuf: 53
Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), Karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyanyang.
b. Nafs al-lawwamah
QS. Al-Qiyamah: 2
Dan Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri)
Jika nafs tidak bisa tenang secara sempurna tetapi terus berusaha untuk
memerangi syahwatnya, maka itu dinamakan dengan nafs al-lawwamah, karena selalu
mencela pemiliknya ketika kendor semangat ibadahnya kepada Allah SWT. Atau bisa
dipahami bahwa nafs al-lawwamah ini adalah nafs yang masih labil, gelisah, terkadang
melakukan kebaikan dan terkadang masih melakukan kejahatan, akan tetapi ia selalu
sesal diri.
c. Nafs Muthmainnah
QS. Al-Fajr: 27-28
Hai jiwa yang tenang (27) Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.(28)
4 M. Yaniyullah Delta Auliya, Melejitkan Kecerdasan Hati dan Otak, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
: 2005), hlm. 136-137, lihat juga Husein Husein Syahatah (2003), hlm. 12-13
-
5
Nafs merasa tenang karena menjalankan perintah Allah SWT dan mampu
mengalahkan syahwatnya, maka ini dinamakan nafs muthmainnah (jiwa yang
tentram/tenang).
Para ahli tasawuf membagi perkembangan nafsu manusia menjadi tiga tingkatan:
a. Tingkat pertama manusia cenderung untuk hanya memenuhi naluri
rendahnya yang disebut dengan jiwa hayawaniyah/ kebinatangan (nafs
ammarah).
b. Tingkat kedua, manusia sudah mulai untuk menyadari kesalahan dan
dosanya, ketika telah berkenalan dengan petunjuk Ilahi, di sini telah terjadi
apa yang disebutnya kebangkitan rohani dalam diri manusia. Pada waktu
itu manusia telah memasuki jiwa kemanusiaan, disebut dengan jiwa
kemanusiaan (nafs lawwamah). Nafsu ini juga mencaci pemiliknya ketika
ia teledor dalam beribadah kepada Allah. Nafsu ini pula sumber
penyesatan karena ia patuh terhadap akal, kadang tidak.5 Berbeda dengan
nafs ammarah yang cenderung agresif mendorong untuk memuaskan
keinginan-keinginan rendah, dan menggerakan pemiliknya untuk
melakukan hal-hal yang negatif, maka nafs lawwamah telah memiliki
sikap rasional dan mendorong untuk berbuat baik. Namun daya tarik
kejahatan lebih kuat kepadanya dibandingkan dengan daya tarik kebaikan.
c. Tingkat ketiga adalah jiwa ketuhanan yang telah masuk dalam kepribadian
manusia, disebut jiwa ketuhanan (nafs muthmainnah). Al-nafs al-
muthmainah merupakan tingkatan tertinggi dari rentetan strata jiwa (an-
nafs) manusia, karena pada tingkatan ini manusia sudah terbebas dari sifat-
sifat kebinatangan dan penuh dengan cahaya ilahiyyah Tingkatan jiwa ini
hampir sama dengan konsep psikoanalisanya Freud yaitu Id, Ego, dan
Superego
5 Syekh M. Amin Al-kurdi, Menyucikan Hati Dengan Cahaya Ilahi, (terj. Muzammal Noer, judul asli :
Tanwir Al-Qulub Li Muamalati allam Al-Ghuyub), Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2003, hlm.145
-
6
Jika nafs tidak lagi melakukan perlawanan bahkan selalu mengikuti syahwatnya
dan bujukan setan, maka itu dinamakan dengan nafs al-amarah bi al-su.6 Dengan kata
lain bahwa nafsu ini cenderung kepada karakter-karakter biologis, cenderung pada
kenikmatan-kenikmatan hawa nafsu yang sebenarnya dilarang agama karena menarik
hati kepada derajat yang hina.7
Kecenderungan nafs adalah memaksakan hasrat-hasratnya dalam upaya untuk
memuaskan diri. Sedangkan akal berperan sebagai kekuatan pembatas sekaligus
penasihat bagi nafs, memberikan pertimbangan kepada nafs tentang tindakan-tindakan
positif yang seharusnya dilakukan dan tindakan-tindakan negatif yang harus dihindari.
B. Akal (Al-Aql)
Dalam kamus bahasa arab aql, berasal dari kata kerja aqala-yaqilu-aqlan.
(secara harfiah/etimologi)aql diartikan sebagai al-imsak (menahan), al-ribath (ikatan),
al-hijr (menahan), al-nahy (melarang) dan manu (mencegah).8 Maka yang disebut
Orang berakal adalah orang yang mampu menahan dan mengikat hawa nafsunya.
Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, akal mempunyai beberapa
pengertian yang berbeda, yaitu: (1) daya pikir (untuk mengerti, dsb); (2) daya, upaya,
cara melakukan sesuatu; (3) tipu daya, muslihat, dan (4) kemampuan melihat cara-cara
memahami lingkungan.9
Secara leksikal (bahasa), kata al-aql didalam Kamus Kontemporer Arab-
Indonesia merupakan sinonim bagi kata hija yang berarti pikiran, otak, dan alasan.
Sedangkan di dalam Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia kata al-aql juga berarti
Quwwah Al-Idrak (daya yang dapat menangkap, mempersepsi, memahami), qalb (hati),
al-dzakirah (ingatan), al-quwwah al-aqilah (daya atau kekuatan yang dapat berfikir)
al-fahm (pengertian).
6 Saad Hawwa, Pendidikan Spiritual, (Yogyakarta : Mitra Pustaka : 2006), cet. 1, hlm. 30-31 7 Syekh M.Amin al-Kurdi, menyucikan hati dengan Cahaya Ilahi, (terj. Muzammal Noer, judul asli :
Tanwir Al-Qulub Li Muamalati allam Al-Ghuyub), Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2003, Cet.I., hlm.144 8 Taufiq Pasiak, Revolusi IQ/EQ/SQ; Antara Neurosains dan Al-Quran, cetakan ke-5, Jakarta : Mizan,
2005,, hlm. 193
9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke-3, Jakarta : Balai
Pustaka, 1990, hlm. 14.
-
7
Menurut Imam al-Ghazali, kata al-aql memiliki empat hakikat, yaitu :
1. Pertama, sesuatu yang siap menerima pengetahuan teoretis dan mengatur
kepandaian berpikir yang tersembunyi.
2. Kedua, pengetahuan yang ada pada diri manusia sejak usia anak dapat
menentukan yang mungkin bagi yang perkara yang mungkin dan mustahil
bagi yang perkara yang mustahil. Pengertian ini, hematnya, sama dengan
hati, yaitu perasaan halus (lathifah).
3. Ketiga, pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman /empirik.
4. Keempat, kekuatan gharizah (insting) untuk mengetahui konsekuensi
berbagai masalah dan menahan keinginan untuk mendapatkan kelezatan
sesaat.10
Al-aql juga bisa dipahami dalam dua makna yaitu:
1. Otak yang berada di dalam kepala bagian belakang
2. Potensi lathifah robbaniyyah yang mempunyai potensi akademik,
mengetahui hakekat segala sesuatu.
Sedangkan manfaat/fungsi al-aql adalah potensi penyerapan pengetahuan,
membedakan baik dan buruk, dan jalan memperoleh iman sejati.
Akal yang diartikan sebagai energi yang mampu memperoleh, menyimpan dan
mengeluarkan pengetahuan. Sedang secara psikologis akal memiliki fungsi kognisi
(daya cipta). Kognisi adalah suatu konsep umum yang mencakup semua bentuk
pengalaman kognisi, seperti: mengamati, melihat, memperhatikan, berpendapat,
berimajinasi, berpikir, memprediksi, mempertimbangkan, menduga dan menilai.
Menurut Ibn Khaldun, keinginan untuk mengetahui segala sesuatu di luar diri
manusia merupakan naluri atau fitrah yang diberikan Allah SWT sehingga dengannya
muncullah ilmu pengetahuan. Socrates, seorang Filosof terkenal dari Yunani, meyakini
bahwa manusia akan mampu membuat strandarisasi sahih dan permanen
10
M. Yaniyullah Delta Auliya, Melejitkan Kecerdasan Hati dan Otak, (Jakarta : PT RajaGrafindo
Persada : 2005), hlm. 143
-
8
tentang kebenaran melalui akal yang sehat. Jika akal berfungsi baik, maka manusia
akan menjadi makhluk berkesadaran tinggi.11
Para filosof Barat telah melahirkan berbagai konsepsi mengenai akal, contohnya
Aristoteles, berusaha menciptakan hukum akal dengan mencipta suatu ilmu yang
disebut logika (mantiq).12
Usaha untuk mengetahui hakikat jiwa manusia sebagai saluran dalam mencapai
pengetahuan sebenarnya dilakukan para ulama Muslim di masa lampau. Ibn Sina dan
Ibn Khaldun, membuat tingkatan-tingkatan berpikir dari akal seorang manusia.
C. Qolbu (Al-Qalb)
Qalbu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi hati. Namun demikian, Hati
selain memiliki arti biologis (liver), juga memiliki pengertian sebagai sesuatu yang ada
di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat
menyimpan pengertian-pengertian (perasaan-perasaan).13
Al-Qalb berasal dari kata qalabu yang bermakna berubah, berpindah, atau
berbalik. Qalabu mengalami beberapa perubahan bentuk seperti inqalaba dan qallaba,
namun artinya masih sama. Menurut Ibn Sayyidah, al-qalb jamaknya qulb yang berarti
hati.14
Al-Qalb/Hati mempunyai dua makna yaitu:
1. Hati adalah salah satu anggota tubuh manusia yang terletak di bagian kiri
atas rongga perut, yang merupakan suatu anugerah Allah SWT. yang
diberikan kepada manusia. Yang mana mempunyai kedudukan dan fungsi
yang sangat penting dan utama, sebab hati berfungsi sebagai penggerak
dan pengontrol anggota tubuh lainnya. Apabila hatinya baik, maka
11
Taufiq Pasiak, Revolusi IQ/EQ/SQ; Antara Neurosains dan Al-Quran, cetakan ke-5, Jakarta : Mizan,
2005, hlm.28
12 Hasan Langgunung, Manusia dan Pendidikan; Suatu Analisa Psikologis, Fisafat dan
Pendidikan, Jakarta : Pustaka Al Husna Baru, 2004, hlm. 221.
13 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke-3, Jakarta :
Balai Pustaka, 1990, hlm. 301
14 Musa Asyarie, Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Islam, (Yogyakarta : Lembaga Studi Filsafat Islam : 1992) hlm. 108-109
-
9
anggota badan yang lainnya pun akan ikut baik, sedangkan apabila
hatinya jelek, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan ikut jelek. Dan
hati ini adalah hati yang berbentuk jasmani.
Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
dan Muslim,
.
Ingatlah bahwa di dalam tubuh terdapat sepotong daging.
Apabila ia baik, maka baiklah badan itu seluruhnya dan apabila ia
rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Ingatlah sepotong daging itu
adalah hati.
2. Makna al-Qalb yang kedua adalah lathifah Rabbaniyah Ruhaniyyah yang
memancarkan hangat dan mempunyai hubungan dengan daging ini. Dan
mampu melakukan peng-idrak-an. Idrak adalah memahami,
mempersepsikan. Misalnya perasaan sedih dan gembira. Yang berfikir
dan merenungkan itu adalah kekuatan batin yang disebut al-qalb. Dan hal
ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan hati. Sehingga
kalau ada sebutan Hatinya hancur maka yang disebut bukan jantungnya.
Tetapi, ada bagian jiwa seseorang yang hancur.
Pada kenyataannya, nafs yang tenang adalah hati yang paling dalam, yang oleh
para filosof disebut sebagai nafs rasional (nafs al-natiqa). Namun demikian, sebagian
besar manusia masih berada pada maqam sifat-sifat kebendaan (tab), tingkat nafs, dan
belum memiliki hati.
Hati adalah sebuah tempat antara wilayah kesatuan (ruh) dan daerah
keanekaragaman (nafs). Jika hati mampu melepaskan selubung nafs yang melekat
padanya dia akan berada di bawah pengaruh ruh; itulah yang dikatakan telah menjadi
hati dalam makna yang sebenarnya, telah bersih dari segala kotoran keanekaragaman.
Sebaliknya, jika hati dikuasai oleh nafs, dia menjadi keruh oleh kotoran
keanekaragaman nafs.
-
10
Qalbu memiliki insting yang disebut dengan al-nur al-ilahiy (cahaya ketuhanan)
dan al-bashirah al-bathiniah (mata batin) yang memancarkan keimanan dan keyakinan.
Qolbu ruhani ini merupakan bagian esensi dari nafs (jiwa) manusia, yang berfungsi
sebagai pemandu, pengontrol dan pengendali struktur nafs yang lain.
Apabila qolbu ini berfungsi secara normal maka kehidupan manusia menjadi baik
dan sesuai dengan fitrahnya, begitu pula sebaliknya. Baik buruknya tingkah laku
seseorang sangat tergantung pada pilihan manusia itu sendiri.
Dari sudut kondisinya, qolbu memiliki kondisi-kondisi tertentu :
1. Baik, yaitu qolbu yang hidup (hayy), selamat (salim) dan mendapat
kebahagiaan (al-saadah),
2. Buruk, qolbu yang mati (al-mayt) dan mendapat kesengsaraan (al-
saqawah), antara baik dan buruk yaitu qolbu yang hidup tetapi
berpenyakit (mardh).
-
11
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Konsep manusia dalam tasawuf terdiri dari nafsu, akal dan hati. Nafsu yang
menggerakkan manusia lebih kepada kejelekan, namun apabila manusia bisa menekan
dan bisa berada pada tidak dibawah pengaruh nafsu, maka ia akan terhindar dari
kejelekan, sebab nafsu dalam diri manusia menurut Al-Ghozali dibagi menjadi tiga,
yaitu nafsu amarah, nafsu lawwamah dan nafsu mutmainnah.
Sedangkan akal adalah kognisi atau kemampuan berfikir manusia yag
dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia untuk bisa menilai dan menimbang
baik buruknya prilaku yang dimunculkan oleh nafsu. Sehingga akal-lah yang kemudian
menjadi filter dari nafsu manusia.
Hati merupakan raja dalam diri manusia, dalam hadits shohih riwayat Bukhari dan
Muslim menjelaskan bahwa apabila hati dalam diri manusia itu baik, maka akan baik
semua yang ada pada diri tersebut. Namun sebaliknya, apabilahati itu kotor, jelek dan
rusak, maka kotor, jelek dan rusak-lah semua yang ada pada diri tersebut.