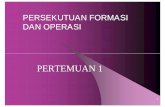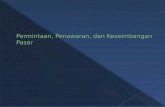jbptunikompp-gdl-s1-2007-asronnim10-6270-bab-ii.o-3.doc
-
Upload
surya-budi -
Category
Documents
-
view
216 -
download
2
Transcript of jbptunikompp-gdl-s1-2007-asronnim10-6270-bab-ii.o-3.doc
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Umum Kayu Lapis
Kayu lapis adalah papan yang dibuat dengan cara merekatkan beberapa lembar papan veneer. Veneer yang direkatkan jumlahnya ganjil, susunan merekatnya saling tegak lurus, serta proses pembentukannya di sertai dengan pengepasan (Kasmudjo, 1982).Sedangkan menurut SKI, kayu lapis adalah suatu produk panil-panil kayu yang diperoleh degan cara menyusun secara bersilangan dari lembaran-lembaran veneer yang dikombinasikan dengan papan, strip, papan partikel, papan serat, atau lainnya yang diikat dengan perekat bantuan perlakuan berupa pemberian panas.
2.1.1 Jenis-jenis Kayu Lapis
Berdasarkan proses pembuatan dan keperluannya kayu lapis dibedakan atas :
Kayu lapis biasa / commercial plywood, yaitu kayu lapis hasil olahan tahap pertama di pabrik dan belum mengalami pengolahan lebih lanjut. Secara keseluruhan masih memperlihatkan keadaan kayunya sendiri.
Kayu lapis indah / fancy plywood, yaitu kayu lapis yang permukaannya diproses lebih lanjut khusus untuk keperluan dekorasi dengan cara :
1. Diberi Veneer jenis kayu indah misalnya nyatoh, sonokeling, renyah, jatu, dll.
2. Dilapisi kertas beraneka warna (paper overlay)
3. Dilapisi dengan bahan sintetis seperti lembaran polivinil plywood.4. Diproses pahatan di mana permukaannya diproses secara mekanis.
Kayu lapis konstruksi / construksi plywood yaitu kayu lapis untuk keperluan seperti kayu lapis cetak beton (plyform), kayu lapis berelur jantan dan betina (tangue and groove plywood) dan kayu lapis berlapisan (overlaid plywood).
Berdasarkan jenis lembaran veneernya dibedakan :
Kayu lapis semua veneer (all veneer plywood)
Kayu lapis dengan inti papan lebar (lumber core board, batten board plywood)
Kayu lapis dengan inti kayu (all veneer plywood)
Kayu lapis dengan inti papan sedang (blockboard plywood)
Kayu lapis dengan inti papan sempit (trips plywood, lamin board plywood)
Kayu lapis dengan inti papan partikel (particle board plywood)
Kayu lapis dengan inti papan serat (fiber board plywood)
Kayu lapis dengan inti papan serbuk (hard board plywood)
Kayu lapis dengan inti bukan kayu (composite plywood)
2.1.2 Papan Laminasi
Papan laminasi merupakan nama suatu kelompok papan sambung, yang juga dikenal dengan joint board. Apabila jenis papan sambung ini dilapisi dengan veneer (biasanya dua lapis bawah dan dua lapis atas), maka sering disebut dengan lumber core board, yaitu jenis papan tiruan yang bagian tengah (core) berupa susunan strip kayu yang disusun menjadi papan lebar (lumber core). Dengan demikian maka papan sambung atau joint board disebut sebagai lumber core dari lumber core board.Berdasarkan ukuran ketebalan lumber core-nya, lumber core board dibedakan menjadi :
1. Battenboard: apabila tebal lumber core-nya lebih dari 25 mm
2. Blockboard: apabila tebal lumber core-nya antara 7 sampai 25 mm
3. Laminboard: apabila tebal lumber core-nya kurang dari 7 mm
Papan laminasi merupakan produk unit tambahan pada pabrik plywood. Karena produknya mempunyai ketebalan lumber core antara 7 25 mm (kebanyakan 9 14 mm) maka disebut sebagai blockboard. Dan pabriknya juga disebut pabrik blockboard.
2.1.2.1 Strip kayu, lumber core dan lumber core board
Strip kayu adalah individu-individu potongan kayu kecil atau strip kayu yang apabila disusun akan menghasilkan Lumber Core : papan laminasi : papan sambung : joint board.
Ukuran strip kayu bervariasi dengan :
Panjang: 30 150 cm
Lebar: 5 15 cm (sekarang dikembangkan minimal 1 inchi atau 2,54 cm)
Tebal: 13 25 mm (sekarang dikembangkan minimal 6 mm)
Strip kayu tersebut dapat dilakukan penyambungan (direkat) ke arah samping dan kearah ujung yang akan menghasilkan lumber core.
Strip kayu Jointboard
Gambar 2.1. Contoh individu kayu dan bentuk lumber core yang dihasilkan
Lumber core, seperti yang telah dijelaskan di muka apabila strip kayu tersebut disambung atau direkatkan ke arah samping dan ujung akan menghasilkan papan lebar yang disebut sebagai lumber core atau joint board.
Apabila diproduksi berupa papan sambung, maka lebar dan panjangnya minimal berukuran 30 x 50 cm atau kebanyakan 100 x 100 cm, tetapi apabila di inginkan untuk menghasilkan blockboard, maka ukuran yang lazim adalah mengikuti ukuran kayu lapis (plywood) yaitu panjang/lebarnya berukuran 3 9 feet.
Lumber core boars, dapat berupa battenboard atau laminboard. Maka sebagai papan balok harus tersedia lumber core, veneer face-back, dan vener cross band.
Gambar 2.2. Lapisan-lapaisan penyusun dan lumber core board yang dihasilkan (5 lapis).2.1.3 Proses Pembuatan Blockboard
Proses pembuatan blockboard pada dasarnya tidak terlalu rumit, terutama pada industri plywood. Bahkan pada proses pembuatan lumber core pun tergolong sederhana, dan dapat dibuat secara manual atau dengan menggunakan tangan.Secara umum proses pembuatan blockboard adalah sebagai berikut :
Penyiapan bahan baku berupa log inti atau bahan baku lainnya, yang mana harus di sesuaikan dengan kebutuhan.
Kemudian kayu digergaji untuk mendapatkan ketebalan kayu sesuai dengan keperluan yang telah ditentukan
Kayu dikeringkan dengan mesin pengiring dengan tujuan untuk mendapatkan kadar kayu 10 %. Di samping sebagai standar mutu pengiringan kayu juga sangat membantu pada saat perekatan.
Potongan yang sudah kering kemudian diratakan permukaannya dengan menggunakan mesin pengampelas, sesudahnya dipotong untuk mendapatkan ukuran panjang strip sesuai yang dibutuhkan atau sesuai dengan kondisi kayu itu sendiri
Potongan kayu yang sudah memenuhi ukuran panjang dan ketebalan dirajang untuk mendapatkan ukuran lebar strip kayu yang dibutuhkan
Strip kayu yang sudah ada selanjutnya disusun atau disambung ke arah panjang dan lebar sehingga dengan memberi perekat diantara sambungan yang ada akan di peroleh susunan strip kayu degan ukuran tertentu. Sampai tahap ini telah di peroleh produk berupa lumber core atau joint board. Pada tahap selanjutnya lumber core yang telah direkatkan dipress secara dingin dalam coldpress, dilanjutkan dengan pengepresan secara panas dengan cara memasukkan rekatan veneer dan lumber core tersebut di antara plat-plat baja panas. Kondisi press panas, tekanan di atas 15 kg/cm2, suhu di atas 1100 C (tidak boleh melebihi 17000 C) dan lama pengepresan di sesuaikan dengan bahan dan ketebalan, tidak lebih dari 30 menit
Rekatan veneer dan lumber core (calon blockboard) dikeluarkan dari mesin press panas sehingga di perokeh blockboard Blockboard selanjutnya dipotong pinggirnya sesuai ukuran final dengan gergaji potong dobel (double saw), kemudian dihaluskan (sanding) dan diperiksa kualitasnya (blockboard grading). Jika masih ada kerusakan dan memungkinkan diperbaiki maka bagian muka blockboard didempul agat kualitasnya meningkat
Pada tahap selanjutnya dapat dilakukan pengemplasan ulang pada blockboard yang diperbaiki. Pekerjaan perbaikan dan penghalusan ulang termasuk remanufacturing dan dapat juga dilakukan grading ulang
Dengan demikian telah di dapat sejumlah blockboard sempurna dan siap dipasarkan atau diperdagangkan. Penentuan kelas mutu, pemberian tanda merek, penghitungan dan pengepakan dilakukan sebelum blockboard tersebut dibawa ke gudang dan siap jual
2.2 Konsep Dasar Sistem Produksi
Proses industri harus dipandang sebagai suatu perbaikan yang terus menerus yang dimulai dari sederet siklus sejak adanya ide-ide untuk menghasilkan suatu produk, pengembangan produk, proses produksi sampai pada distribusi kepada pelanggan.Organisasi industri merupakan salah satu mata rantai dari sistem perekonomian secara keseluruhan, karena memproduksi dan mendistribusikan suatu produk. Produksi merupakan fungsi pokok dalam setiap organisasi, yang mencakup aktivitas yang bertanggung jawab untuk menciptakan nilai tambah input yang merupakan output dari setiap organisasi.
Produksi merupakan penciptaan atau penambahan faedah bentuk, waktu dan tempat atas faktor-faktor produksi yang lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. (Reksohadiprodjo dan Sudaewo, 1998).
Produksi adalah suatu bidang yang terus berkembang selaras dengan perkembangan teknologi, di mana produksi memiliki suatu jaringan hubungan timbal balik (dua arah) yang sangat erat kaitannya dengan teknologi. Produksi dan teknologi saling membutuhkan, kebutuhan produksi untuk beroperasi dengan biaya rendah, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan produk baru sudah merupakan kekuatan yang mendorong teknologi untuk melakukan terobosan dan penemuan baru. Produksi dalam sebuah organisasi dalam sebuah pabrik adalah inti yang paling dalam, spesifik, serta berbeda dengan bidang fungsional yang lain seperti keuangan, personalia dan lain-lain.
Sistem produksi merupakan sistem integral yang mempunyai karakter :
1. Mempunyai komponen atau elemen yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Hal ini berkaitan dengan komponen yang membangun sistem produksi tersebut.
2. Mempunyai tujuan yang mendasari keberadaannya, yaitu menghasilkan barang dan jasa berkualitas yang dapat dijual dengan harga kompetitif.
3. Mempunyai aktivitas, berupa proses transformasi nilai tambah menjadi keluaran secara efektiif dan efisien.
4. Mempunyai mekanisme yang mengendalikan pengoperasiannya berupa optimasi pengalokasiaan sumber daya.
2.3. Pengertian Mesin dan Tenaga Kerja
Menurut Manullang (1982), operasi sistem produksi membutuhkan modal. Salah satunya adalah mesin produksi. Perlengkapan dan mesin-mesin produksi dapat diklasifikasi baik dengan fungsi ataupun dengan pelaksanaan (operasi). Semua yang di klasifikasi oleh fungsi seterusnya dapat dibagi atas maksud umum (general purpose) dan maksud khusus (spesial purpose). Menurut cara pelaksanaannya dapat dibagi menjadi : dengan tangan, semi otomatis, sepenuhnya otomatis dan dibuat bergerak sendiri.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerja, baik didalam maupun diluar hubungan kerja untuk menghasilkan barang /jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk pengertian tenaga kerja di industri berarti setiap orang laki-laki maupun perempuan yang mampu, yaitu mempunyai kemampuan fisik maupun psikis dalam pengertian sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang telah terikat dalam perjanjian kerja antar pihak pengusaha dengan tenaga kerja yang bersangkutan, hak dan kewajiban antara pengusaha dan tenaga kerja (Marsudi,1992).
Tenaga kerja merupakan modal utama dan sangat esensial sebagai pelaksana dalam industri. Faktor tenaga kerja ini sangat mempengaruhi efesiesnsi produksi ataupun penekanan biaya.
2.4. Pengertian Produktivitas
Dalam doktrin pada konferensi Oslo (1984), tercantum definisi umum produktivitas semesta, yaitu : Produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal yang bertujuan untuk meyediakan lebih banyak barang dan jasa untuk lebih banyak manusia, dengan menggunakan sumber-sumber riil yang makin sedikit. Produktivitas adalah suatu pendekatan indesipliner untuk menentuka tujuan yang efektif, membuat rencana, aplikasi penggunaan cara yang produktivitas untuk menggunakan sumber-sumber secara efisien, dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi. Produktivitas mengikutsertakan pendayagunaan secara terpadu sumber daya manusia dan ketrampilan, biaya modal teknologi, manajemen, informasi, energi, dan sumber-sumber lain menuju kepada pengembangan dan peningkatan standart hidup untuk seluruh masyarakat (Sinungun, 1997).
Hermawan (1996), produktivitas sebagai salah satu tolak ukur teknis kinerja industri. Tolak ukur teknis ini menggunakan kinerja dan hasil fisik kegiatan. Produktivitas merupakan kemampuan menghasilkan barang dalam jumlah tertentu dalam periode waktu. Pengukuran kemampuan ini dilakukan terhadap mesin, tenaga, atau justru keseluruhan aktivitas industri.
Menurut Dipodiningrat (1999), bahwa hasil kerja dari tenaga kerja di pengruhi oleh :
1. Sumber daya manusia yang meliputi kemampuan dan kepribadian, pendidikan dan latihan, ketrampilan dan pengalaman.
2. Metode kerja yang meliputi sistem dan prinsip kerja, peraturan dan instruksi kerja.
3. Kesehatan tenaga kerja yang meliputi kesehatan mental dan toleransi stress serta kondisi fisiknya.
4. Motivasi yang ada pada tenaga kerja yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja, hubungan kemanusiaan dan adanya perangsang.
2.5. Konsep Dasar Sistem Produktivitas.
Menurut Mali (1978), menyatakan bahwa produktivitas tidak sama dengan produksi, tetapi produksi performasi kualitas dan hasil-hasil merupakan komponen dari usaha produktivitas.Sedangkan Sumanth (1985), menyatakan terdapat suatu konsep formal yang disebut sebagai siklus produktivitas (productivity cycle). Untuk dipergunakan peningkatan produktivitas terus menerus. Pada dasarnya konsep siklus produktivitas terdiri atas empat tahap, yaitu : (1) Pengukuran produktivitas, (2) Evaluasi produktivitas, (3) Perencanaan produktivitas, (4) Peningkatan produktivitas.
Indikator keberhasilan sistem industri itu di pantau melalui pengukuran produktivitas dan profitabilitas terus menerus, dimana pengukuran produktivitas atau memberikan informasi tertentu masalah-masalah internal dari sistem industri itu.
2.6. Pengukuran Produktivitas
Pengukuran produktivitas salah satunya dapat dilakukan dengan pengukuran kemampuan mesin dan tenaga kerja.Gasperz (1990), membuat model pengukuran produktivitas yang paling sederhana dengan pendekatan rasio input/output. Pengukuran produktivitas berdasarkan rasio ini akan mampu menghasilkan tiga jenis ukuran produktivitas, yaitu : produktivitas parsial, faktor total, dan produktivitas total.
Hermawan (1996), membagi pengukuran produktivitas dalam dua cara, yaitu secara nyata (real) dan secara baku (standar). Bahkan untuk mesin dikenal dengan istilah kapasitas, yaitu kemampuan kerja per satuan waktu. Terminasi lebih umum daripada produktivitas.
Produktivitas mesin. Produktivitas nyata mengukur kemampuan produksi suatu mesin dalam operasi normal. Pengukuran dilakukan dalam kondisi bisa tanpa pengendalian dan perlakuan tertentu. Produktivitas baku berdasarkan kemampuan kerja mesin bila dioperasikan dalam kondisi standar. Sejumlah fungsi dibakukan sebelum perlakuan pada pengukuran. Produktivitas terpasang adalah menduga produktivitas malalui data terpasang mesin.
Produktivitas tenaga kerja. Produktivitas kelompok menggambarkan kemampuan produksi sekelompok orang persatuan waktu dalam obyek pekerjaan yang sama. Produktivitas individu menggambarkan atau mengukur hasil kerja individu per satuan waktu. Pengukuran dapat dilakukan menurut berbagai tingkat faktor seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain.
2.7. Manfaat Pengukuran Produktivitas
Pengukuran tingkat produktivitas pada suatu perusahaan sangat penting, guna membandingkannya dengan standar produktivitas yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen, mengukur tingkat perbaikan produktivitas dari waktu ke waktu, serta dapat membandingkan produktivitas dengan industri sejenis.Terdapat beberapa manfaat pengukuran produktivitas dalam suatu organisasi perusahaan antara lain :
Perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya, agar dapat meningkatkan produktivitas melalui efisiensi penggunaan sumber daya.
Perencanaan sumber-sumber daya akan lebih efektif dan efisien melalui pengukuran produktivitas, baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang.
Tujuan ekonomis dan non ekonomis dari perusahaan dapat diorganisasikan dengan cara pemberian prioritas tertentu yang dipandang dari segi produktivitas.
Perencanaan tingkat produktivitas di masa mendatang dapat dimodifikasi kembali berdasarkan informasi tingkat produktivitas sekarang.
Strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan berdasarkan tingkat kesenjangan (gap productivity) yang ada antar tingkat produktivitas yang direncanakan (ekspectasi productivity) dan tingkat produktivitas yang diukur (actual productivity ). Dalam hal ini pengukuran produktivitas akan memberi informasi dalam mengidentifikasi masalah atau perubahan yang terjadi, sehingga tindakan kolektif dapat diambil.
Nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan suatu pengukuran menjadi informasi yang berguna untuk merencanakan tingkat keuntungan dari perusahaan itu sendiri.
Pengukuran produktivitas terus menerus akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk menentukan dan mengevaluasi perkembangan dan efektivitas dari perbaikan terus menerus yang dilakukan perusahaan.
2.8. Pengukuran Waktu Kerja
Pengukuran waktu kerja (time study) adalah suatu cara untuk menemukan waktu yang dibutuhkan oleh pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.
Reksohadiprojo dan Indriyo (1997), mendefinisikan time study sebagai pengamatan dan pencatatan waktu terus menerus yang dilakukan terhadap proses kerja dimana seluruh proses kerja tersebut dipisahkan menjadi elemen-elemen kerja. Tujuan metode ini adalah untuk menentukan waktu standar bagi suatu operasi yaitu waktu yang dibutuhkan oleh pekerja dengan metode khusus dan bekerja dengan tempo normal.
Metode pengukuran waktu kerja ada 3 macam, yaitu :
1. Continous Timing Method.
Konsumsi waktu diukur terus menerus mulai dari elemen kerja pertama sampai elemen kerja terakhir. Konsumsi waktu dibaca langsung pada stopwatch, waktu yang diperlukan untuk tiap elemen kerja diperoleh dari pengurangan pembacaan terakhir dengan pembacaan awal.
2. Repetitive Timing Method.
Pada metode ini pencatat dilakukan pada masing-masing elemen
3. Accumulative Timing Method.
Pencatat waktu untuk masing-masing elemen di baca langsung dengan menggunakan dua stopwatch.
Prosedur yang dipakai dalam time study bervariasi, tergantung pada jenis kegiatan yang akan diamati dan penggunaan data-data yang diperoleh. Prosedur yang biasa digunakan dalam penyusunan time study menurut Barnes, 1958 (Daryanto. A, 1977) adalah :
1) Mencatat informasi tentang pekerjaan dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut.
2) Penyusunan elemen-elemen kerja dan mencatat secara lengkap semua metode.
3) Pengamatan dan pencatatan waktu kerja operator.
4) Penentuan jumlah pengamatan yang diperlukan.
5) Melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa ulangan yang dilakukan cukup.
6) Menghitung hasil kerja operator.
7) Penghitungan kehilangan waktu (allowance) yang didapat.
8) Menghitung waktu normal dan standar.
Dalam praktek, maksud dan tujuan time sutdy adalah untuk menentukan dasar penentuan prestasi kerja tenaga kerja dan upah tenaga kerja (Soerjohadikoesoemo, 1971).
Waktu yang di gunakan dalam menyelesaikan pekerjaan dibedakan menjadi waktu umum dan waktu murni. Waktu umum adalah suatu pekerjaan yang tidak ada hubungannya langsung dengan pekerjaan pokok seperti istirahat, waktu pribadi, waktu bila ada kecelakaan kecil dan sebagainya. Waktu murni adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan pokok.
Derajat prestasi merupakan suatu angka yang dinyatakan dalam prosen yang menunjukan kecakapan atau ketrampilan rata-rata para pekerja atau karyawan. Dalam penentuan derajat prestasi ini adalah sukar dan tidak ada dasar yang cukup kuat untuk menjadi pegangan. Sedang menurut Sanyoto (1974) rating factor berkisar antara 80 % - 120 %. Menurut Direktorat Reboisasi dan Rehabilitasi departemen kehutanan yang bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 1997, faktor derajat prestasi bersumber pada pribadi pekerja yang ditentukan oleh enam faktor : 1). Jenis kelamin; 2). Umur; 3). Pendidikan; 4). Pengalaman kerja; 5). Jumlah keluarga; 6). Jarak rumah ke petak. Penentuan derajat prestasi seorang pekerja dari tabel derajat prestasi yang telah ditetapkan oleh dep kehutanan yang bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Universitas gadjah mada, sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu sifat pekerjaan yang dilakukan (berat atau ringan). Kemudian derajat prestasi seorang pekerja baru dapat dicari dengan mengalikan batas derajat prestasi masing-masing faktor (6 faktor) dengan memperhatikan klasifikasi variable yang ada dalam tabel derajat prestasi, untuk menilai kecakapan dan ketrampilan pekerja dinilai sangat tinggi dengan bobot angka 1 karena angka 1 menunjukkan angka sempurna.Koreksi dengan derajat prestasi mempunyai maksud agar waktu kerja pekerja adalah waktu normal yang menghasilkan prestasi normal. Yang di maksud dengan prestasi normal adalah prestasi dari rata-rata pekerja yang berpengalaman dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Tabel 2.1. Derajat Prestasi
NoKeteranganSifat Pekerjaan
BeratRingan
1
2
3
4
5
6
Jenis Kelamin
a. Laki-laki
b. Perempuan
Umur
a. < 25 tahun
b. 25-45 tahun
c. 45 tahun ke atas
Pendidikan
a. Tak sekolah
b. SD
c. SMP ke atas
Pengalaman Kerja
a. 0-3 tahun
b. 4-6 tahun
c. 6 tahun ke atas
Jumlah Keluarga
a. 1-3 orang
b. 4-5 orang
c. 5 orang ke atas
Jarak pabrik-rumah
a. < 2 km
b. 2-5 km
c. > 5 km0,96
1,03
0,96
0,99
1,03
0,96
0,99
1,03
1,03
0,99
0,96
1,03
0,99
0,96
0,96
0,99
1,031,03
0,96
1,03
0,99
0,96
0,96
0,99
1,03
1,03
0,99
0,96
1,03
0,99
0,96
0,96
0,99
1,03
Sumber : Direktorat Reboisasi dan Rehabilitasi Departemen Kehutanan
Veneer face
Veneer cross band
Lumber core
Lumber core board
Veneer cross band
Veneer face
PAGE 18