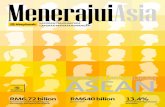laporan biokim karboksihemoglobin
-
Upload
ganda-edhi -
Category
Documents
-
view
141 -
download
14
Transcript of laporan biokim karboksihemoglobin
LAPORAN PRAKTIKUM BIOKIMIA KEDOKTERAN II
LAPORAN PRAKTIKUM BIOKIMIA KEDOKTERAN II
PEMERIKSAAN KARBOKSIHEMOGLOBIN
( HbCO )
Oleh :
Nama : Hayra Diah Avianggi
NIM
: K1A003073
Kelompok : IV
Asisten: Aswindar Adhi Gumilang
Dwi Adi Nugroho
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
PURWOKERTO
2004
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tujuan
1. Mengetahui kadar karboksihemoglobin (HbCO) dalam serum probandus.
2. Mengetahui kelainan-kelainan yang terjadi akibat keabnormalan kadar karboksihemoglobin.
B. Dasar Teori
Gas CO yang berasal dari proses pembakaran yang tidak sempurna dapat mengikat Hb membentuk HbCO. Ikatan ini sangat kuat, lebih kuat 200 kali daripada ikatan Hb dengan oksigen. Karbon monoksida (CO) mengikat heme yang tersendiri dengan kekuatan 25.000 kali lebih besar daripada kekuatan ikatan oksigen. Atmosfer udara mengandung CO dalam jumlah renik, dan katabolisme heme yang normal akan membentuk sendiri sejumlah kecil CO2. Mengapa CO (bukan O2) yang tidak menempati posisi koordinasi atom besi yang keenam pada mioglobin, karena pada lingkungan penghalang pada heme dalam mioglobin, arah pengikatan CO pada besi heme yang lebih disukai adalah tegak lurus terhadap cincin heme, bersama 3 buah atom (Fe, C, O). Arah ini bisa saja ditemukan pada heme tersendiri, namun ujung distal histidin dalam mioglobin secara sterikal merintangi pengikatan CO pada sudut ini. Hal ini memaksa CO untuk berikatan dalam bentuk konfigurasi yang kurang disukai dan menurunkan kekuatan ikatan heme. CO melebihi dua tingkat besaran hingga sekitar 200 kali lebih kecil daripada kekuatan ikatan heme O2. Sebagian kecil (sekitar 1%) mioglobin dalam keadaan normal akan terdapat dalam bentuk mioglobin-CO.
C. Alat Dan Bahan
Alat :
Tabung Reaksi ukuran 5 ml
Rak tabung reaksi
Spuit
Spatula
Torniquet
Mikro Pipet
Spektrofotometer
Kuvet
Bahan :
Sampel darah vena
EDTA
Amonia 0,1%
Sodium dithionit
D.Cara Kerja
1. Disiapkan 2 tabung reaksi seukuran 5 ml, masing-masing diberi label R1 (Reagen) dan SPL (Reagen Sampel).
2. Tabung R1 dipipetkan 20 ml larutan ammonia 0,1%.
3. Kemudian ditambahkan dengan 10 l sample darah, dicampur hingga homogen dan diamkan 10 menit.
4. Setelah 10 menit, dipipetkan 4 ml larutan yang berisi larutan ammonia 0,1% dan sample darah kedalam tabung SPL.
5. Ditambahkan satu spatula sodium dithionit (Na2S2O5) ke dalam tabung SPL, campur sampai homogen.
6. Absorbansi R1 dan SPL dibaca dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 578 nm.
7. Absorbansi R1 disebut (A) dan absorbansi standar SPL disebut ArHb.
E. Nilai Normal
CO endogen
: < 1%
Batas toleransi CO: 2% - < 5%
> 5%
: mulai timbul gejala/tidak normal/keracunan.
F. Rumus Perhitungan
HbCO = A x 6.08%
ArHb
BAB II
HASIL DAN PEMBAHASAN
A.HASIL
1. Hasil Perhitungan
Kadar HbCO
= ( A x 6,08 %
( Ar Hb
Kadar HbCO serum probandus = ( A x 6,08 %
( Ar Hb
= 0,020 x 6.08%
0,031
= 3,92 %
Kadar HbCO serum patologis = ( A x 6,08 %
( Ar Hb
= 0,039 x 6.08%
0,034
= 6,97 %
2.Hasil Pengamatan
Nama Probandus : Dwi Ratnawati
Umur Probandus : 20 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Tabel hasil pengamatan terhadap perubahan warna
Nama TabungSebelumSesudah
Tabung R1Kuning JernihBening kemerahan
Tabung SPLBening kemerahanLebih Kuning jernih
Absorbansi Tabung Sampel Probandus
Nama TabungAbsorbansi
Tabung R10,020
Tabung SPL0,031
Absorbansi Tabung Sampel Patologis
Nama TabungAbsorbansi
Tabung R10,039
Tabung SPL0,064
Gambar Tabung :
PERUBAHAN WARNA
Tabung Reagen Blanko
Tabung SPL
Tabung SPL + Sodium dithionit
B.PEMBAHASAN
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh praktikan saat melaksanakan percobaan, maka diperoleh hasil pengamatan, sebagai berikut :
a) Kadar HbCO pada serum probandus dikatakan normal, yaitu sebesar 3,92%. Karena hasil masih dalam batas toleransi CO sebesar : 2% - < 5%. Kadar karboksihemoglobin probandus normal, tetapi sedikit rendah karena disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah:
1. Probandus bukan perokok aktif (pasif).
Rokok pada dasarnya merupakan pabrik bahan kimia. Setiap satu batang rokok dibakar, akan mengeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia, seperti nikotin, gas karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrogen sianida, amoniak, akrolein, asetilen, bensen, metanol, uretan, bensal dehida, dan lain-lain. Secara umum bahan-bahan ini dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu komponen gas dan komponen padat/partikel. 1Dalam asap rokok yang membara karena diisap, tembakau terbakar kurang sempurna sehingga menghasilkan CO (karbon monoksida), yang disamping asapnya sendiri, tar dan nikotine (yang terjadi juga dari pembakaran tembakau tersebut) dihirup masuk kedalam jalan napas. 1
Asap samping sangat besar pengaruhnya bagi kesehatan perokok pasif, karena jumlahnya cukup banyak dan kadar bahan berbahaya yang dikandungnya cukup tinggi. Dari sebatang rokok yang terbakar akan dihasilkan asap samping dua kali lebih banyak daripada asap utama, karena asap samping terus-menerus dikeluarkan, sedangkan asap utama keluar jika sedang diisap. Jadi risiko kesehatan yang dihadapi perokok pasif hampir tidak ada bedanya dengan perokok aktif. 8
2. Probandus tidak tinggal dilingkungan perokok sehingga probandus dikatakan bukan perokok pasif.
Perokok pasif memperoleh 2 kali jumlah nikotin, 2 kali jumlah tar, dan 5 kali jumlah karbonmonoksida daripada perokok aktif. Orang yang menghisap asap rokok biasanya mendapat kesulitan bila bernapas dan bila mereka berada di ruang kecil dan tak berventilasi, perokok pasif biasanya mengalami sakit kepala, pusing, pingsan, sakit mata dan sakit tenggorokan. 1
3. Probandus sering menggunakan kendaraan bermotor sehingga dapat terjadi kemungkinan polusi gas CO.
Pada kendaraan bermotor bahan bakar merupakan salah satu faktor penyebab pencemaran tersebut. Komponen utama bahan bakar fosil ini adalah hidrogen (H) dan karbon (C). Pembakarannya akan menghasikan senyawa HC, CO, karbon dioksida (CO2), serta NOx pada kendaraan berbahan bakar bensin. Sedangkan pada kendaraan berbahan bakar solar, gas buangnya mengandung sedikit HC dan CO tetapi lebih banyak SO-nya. Dari senyawa-senyawa itu, HC dan CO paling berbahaya bagi kesehatan manusia. 8
4. Belum terjadi polusi pada angka yang menghawatirkan di purwokerto tempat tinggal probandus.
Karbon monoksida terdapat terutama dalam gas yang dikeluarkan motor bensin, pada tungku pembakaran yang pengaturan udaranya buruk dan pada gas kota yang dulu sering digunakan untuk memasak dan memanaskan ruangan. Dengan penggantian gas kota oleh gas bumi maka satu penyebab penting keracunan karbon monoksida dihilangkan. Meskipun demikian gas bumi yang umumnya terdiri atas metana, tidak 100% aman. Untuk mengoksidasi sempurna metana diperlukan oksigen kira-kira 4 X yang diperlukan untuk mengoksidasi gas kota. 8
b) Kadar HbCO pada serum patologis dikatakan tidak normal, yaitu sebesar 6,97%. Hasil yang didapatkan oleh praktikan melebihi batas toleransi dan diatas > 5%, dimana mulai timbul gejala keracunan. Sampel patologis yang dipergunakan dalam pemeriksaan kali ini adalah seorang perokok aktif.
Hasil pengamatan pada waktu praktikum dapat mengalami kesalahan hal ini dapat terjadi, disebabkan karena ;
Tabung kuvet tidak bersih, sehingga mempengaruhi nilai absorban
Tidak sesuai ukuran saat pengambilan reagen dengan mikropipet
Praktikan tidak teliti dalam memberikan tetesan pada masing-masing tabung (kesalahan menghitung tetesan)
Posisi penetesan salah (mengenai dinding tabung)
Alat yang digunakan kurang steril (bersih)
Adanya pembulatan angka saat perhitungan
Volume darah probandus yang diambil tidak tepat 10 l
Gejala-gejala klinis yang dapat muncul sesuai dengan kadar karboksi-hemoglobin yang dimiliki oleh seseorang, adalah :
0 -10%
: Tidak ada gejala.
10-20 %: Perasaan tegang pada daerah dahi, mungkin timbul sakit kepala ringan, dilatasi pembuluh darah.
20-30 %: Sakit kepala, selama tidur berdebar-debar.
30-40 %: Sakit kepala berat, perasaan lemas, pusing, gangguan penglihatan, mual, muntah , diare, ambruk (collaps).
50-60 %: Cenderung ambruk atau pingsan naik, frekuensi pernafasan dan nadi naik.
60-70 %: Koma dengan kelumpuhan sementara, kenaikkan kerja jantung dan pernafasan, mungkin terjadi kematian.
70-80 %: Denyut nadi lebih lemah dan pernafasan diperlambat, insufisiensi parnafasan berat, kematian. 6
Karbon monoksida adalah racun, karena ia mengikat ferromioglobin dan ferrohemoglobin sehingga menghalangi transpor oksigen. Dalam larutan, hem bebas mengikat CO 25.000 kali lebih kuat daripada O2. Akan tetapi afinitas hemoglobin dan mioglobin untuk mengikat CO ternyata hanya 200 kali lebih kuat daripada afinitas keduanya terhadap O2. 7
Gas beracun merupakan gas kimia yang berupaya menyebabkan kesan keracunan apabila gas tersebut masuk melalui paru-paru. Kesan keracunan boleh dilihat dalam jangka masa singkat (juga dikenali sebagai kesan mendadak atau akut).
Setelah memasuki badan, gas beracun mendatangkan kesan sama ada iritan (menyebabkan kecederaan sel-sel di tapak kemasukan), anestetik (menyebabkan kesan hilang kesedaran), kelemasan (mengalihkan oksigen sehingga mangsa tidak memperolehi oksigen mencukupi) dan kecederaan organ tertentu. 3Karbon monoksida bereaksi dengan hemoglobin membentuk karbon monoksihemoglobin (karboksihemoglobin). Afinitas hemoglobin untuk O2 jauh lebih rendah daripada afinitasnya terhadap karbon monoksida, sehingga menggantikan oksigen pada hemoglobin dan menurunkan kapasitas darah sebagai pengangkut oksigen. 7
Pengurangan afinitas karbon monoksida (CO) terhadap hemoglobin (Hb) dan mioglobin sangat penting dari segi biologis. Karbon monoksida merupakan bahaya potensial yang sudah ada jauh sebelum munculnya industri, karena senyawa ini dihasilkan secara endogen oleh sel sewaktu terjadi pemecahan hem. Tingkat pembentukan endogen karbon monoksida cukup untuk mnduduki 1% dari situs yang ada dalam hemoglobin dan mioglobin, suatu inhibisi yang secara umum masih dapat diterima. 7
Karbon monoksida (CO) yang terbentuk endogen ini seharusnya akan menyebabkan karacunan pasif apabila afinitas dua protein (hemoglobin dan mioglobin) terhadap CO sama seperti porfirin-besi bebas. Masalah ini diatas dengan dikembangkannya protein-hem yang mampu membedakan O2 dari CO dengan cara memaksa CO mengubah geometri ikatannya dengan akibat memperlemah afinitas. 7
Mioglobin membuat suatu lingkungan renik khusus yang memberikan kemampuan khusus bagi gugus prostetiknya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa fungsi suatu gugus prostetik diubah oleh lingkungan renik polipeptida tempat ia terikat. Sebagai contoh, gugus hem yang sama mempunyai fungsi yang cukup berbeda didalam sitokrom c. 7
Sitokrom c merupakan suatu protein yang berperan dibagian akhir rantai oksidasi dalam mitokondria pada seluruh organisme aerob. Dalam sitokrom c, heme lebih merupakan suatu pengemban electron reversible daripada pengemban oksigen. Heme mempunyai fugsi yang lain lagi dalam enzim katalase, yang mengkatalisis perubahan H2O2 menjadi air dan O2. 7
Pada darah banyak mengandung hemoglobin (Hb), suatu zat yang penting bagi tubuh untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Bila di dalam darah terdapat gas karbon monoksida (CO), maka hemoglobin akan lebih banyak terikat dengan karbon monoksida, karena daya ikat CO dengan hemoglobin 200-250 kali lebih kuat dari daya ikat oksigen dengan hemoglobin. Bila terdapat kadar CO yang berlebihan dalam darah, maka pada akhirnya kadar oksigen dalam darah akan turun dengan drastis. 2Karbon monoksida (CO) didalam darah berikatan dengan hemoglobin (Hb) darah membentuk karboksihemoglobin dan dalam jaringan gas ini berikatan dengan zat mengandung besi lain seperti mioglobin, sitokrom, sitokrom oksidase dan katalase. Paparan kadar tinggi karbon monoksida menyebabkan keracunan akut. 4Ikatan gas CO dengan hemoglobin disebut karboksihemoglobin (HbCO). Kadar HbCO erat kaitannya dengan infark jantung, angina pectoris. Dengan kadar HbCO 5%-10% menyebabkan gangguan metabolisme otot jantung,ketidaksanggupan belajar dan pandangan mata mengecil. Bila kadar HbCO 2,9-4,5% akan memberikan gejala nyeri dada ketika bergerak sedikit. Merokok satu batang per hari akan menghirup 20 ppm gas CO. 2Paparan CO berjangka panjang dapat mengakibatkan keracunan kronik. Gejalanya berupa nyeri kepala, gangguan daya ingat, penurunan hasil kerja, gangguan tidur, vertigo, emosi labil serta gangguan saraf pusat maupun perifer. Baik paparan akut maupun menahun, mempunyai efek membahayakan terhadap kesehatan. 4
Karbon monoksida biasanya terhasil semasa pembakaran bahan seperti kertas, kayu dan semasa enzim kendaraan dihidupkan. Gas ini mempunyai sifat tidak berwarna, berbau atau mempunyai rasa. Ia amat berbahaya apabila berkumpul dalam ruang atau kawasan tertutup. 3Karbon monoksida menimbulkan desaturasi hemoglobin, menurunkan langsung persediaan oksigen untuk jaringan seluruh tubuh termasuk miokard. CO menggantikan tempat oksigen di hemoglobin, mengganggu pelepasan oksigen, dan mempercepat aterosklerosis (pengapuran/penebalan dinding pembuluh darah). Dengan demikian, CO menurunkan kapasitas latihan fisik, meningkatkan viskositas darah, sehingga mempermudah penggumpalan darah. 5Karbonmonoksida (CO) dibentuk di dalam tubuh, gas ini diduga berfungsi sebagai messenger kimia otak. Dalam jumlah lebih banyak, gas ini bersifat racun. Diluar tubuh, gas ini terbentuk melalui pembakaran karbon yang tidak sempurna. Serta merupakan penyebab kematian yang lebih banyak dibandingkan gas yang lain. CO bersifat toksik karena dapat bereaksi dengan hemoglobin membentuk karbonmonoksihemoglobin (karboksihemoglobin, COHb), dan COHb tidak dapat mengambil O2. 6
Hemoglobin dan mioglobin menindas kecenderungan alami hem dengan menyelidik kristalografi sinar-X dan spektroskopi inframerah terhadap kompleks CO dan O2 dengan mioglobin dan dengan porfirin besi sintesis. Dalam kompleks CO yang berikatan sangat erat dengan porfirin besi murni, atom-atom Fe, C dan O tersusun lurus. Sebaliknya, dalam karbonmonoksimioglobin, sumbu CO membentuk sudut dengan ikatan Fe-C. Ikatan CO dalam bentuk yang lurus terutama dicegah secara sterik oleh histidin distal. 7
Sebaliknya, sumbu O2 membentuk sudut dengan ikatan Fe-O dalam oksimioglobin. Jadi, protein memaksa CO untuk membentuk sudut dan bukannya membentuk garis lurus. Bentuk geometris yang berupa lekukan pada globin ini memperlemah interaksi CO dengan heme. 7
Keracunan karbon monooksida CO dengan cara kompetitif mengikat tempat yang sama pada hemoglobin seperti halnya O2 dan memperlihatkan kerjasama serupa dan pengaruh bohr. Jumlah O2 yang dapat dibawa oleh Fe (II) molekul hemoglobin yang masih tersisa dan belum bereaksi akan berkurang jika ada CO pada salah satu sisa heme. 8
Selain itu, O2 yang berikatan dengan molekul-molekul hemoglobin yang mengandung CO, terikat lebih erat, menyebabkan pemindahan O2 dari molekul-molekul hemoglobin ke jaringan menjadi jauh lebih sulit. Sehingga pengaruh racun karbon monoksida lebih berat daripada sekedar yang dapat diperkirakan dari kadarnya dalam darah. 8
Karbonmonoksida bergabung dengan molekul hemoglobin pada tempat yang sama seperti oksigen dan karena itu dapat memindahkan oksigen dari hemoglobin. Kekuatan ikatannya kira-kira 200 kali kekuatan oksigen. Tekanan karbon monoksida hanya 0,4 mm hg dalam alveoli, 1/250 dari oksigen alveolus (Po2 100 mm Hg), menyebabkan karbon monoksida sama-sama bersaing dengan oksigen untuk bercampur dengan hemoglobin (Hb) dan menyebabkan separuh hemoglobin (Hb) dalam darah berikatan dengan karbon monoksida daripada dengan oksigen. Oleh karena itu, tekanan karbon monoksida yang sedikit lebih besar dari 0,4 mm Hg (kira 0,6 mmHg atau konsentrasinya kira-kira 0,1% dalam udara) dapat menyebabkan kematian. 7
Karbon monoksida terutama terdapat terutama dalam gas yang dikeluarkan motor bensin, pada tungku pembakaran yang pengaturan udaranya buruk dan pada gas kota yang dulu sering digunakan untuk memasak dan memanaskan ruangan. Dengan penggantian gas kota oleh gas bumi maka satu penyebab penting keracunan karbon monoksida dihilangkan. Bila pembakaran gas tidak benar menempatkannya atau aliran udara buruk maka pada pembakaran juga dapat terjadi sejumlah besar karbon monoksida. 6
Karbon monoksida Menimbulkan efek sistematik, karena meracuni tubuh dengan cara pengikatan hemoglobin yang amat vital bagi oksigenasi jaringan tubuh akaibatnya apabila otak kekurangan oksigen dapat menimbulkan kematian. Dalam jumlah kecil dapat menimbulkan gangguan berfikir, gerakan otot dan gangguan jantung. 4
Karbon monoksida mengandung tempat ikatan yang sama pada hemoglobin seperti oksigen maka dapat meniadakan kemampuan eritrosit untuk transpor oksigen. Kompleks hemoglobin dengan karbon monoksida disebut karboksi hemoglobin. Karbon monoksida benar-benar diikat secara bolak-balik (reversible) seperti oksigen, tetapi menunjukkan kecenderungan ikatan yang lebih kuat dari ikatan oksigen pada hemoglobin. 6
Karbon monoksida (CO) bergabung bersama dengan besar dalam ferro-hemoglobin dan ferromioglobin dan membentuk suatu kompleks yang sangat mirip strukturnya dengan oksihemoglobin dan oksimioglobin. Secara stereokimia, O2 dan CO2 saling berikatan sedemikian rupa sehingga atom Fe, C dan O tidak linier dan menghasilkan pengikatan oksigen yang optimum. 6
- --- Fe ----- Fe N
O C ------Fe
O His O His O C
Oksihemoglobin Karboksihemoglobin Karboksi besi porfirin
Darah yang bersifat alkali lemah, jika direduksi dengan sodium dithionit (Na2S2O4), oksihemoglobin akan diubah menjadi deoksihemoglobin, tetapi karboksihemoglobin tetap tidak terpengaruh. Oleh sebab itu apabila darah kurang begitu jelas, penentuan karboksihemoglobin memerlukan pengenceran sample darah dengan ammonium hidroksi. 7
Karbon monoksida mengikat besi porfirin bebas 25.000 kali lebih kuat daripada oksigen. Karena karbon monoksida dalam hemoglobin dan mioglobin dipaksa ada dalam struktur nonlinear yang kurang stabil maka pengikatan terhadap hemoglobin hanyalah 200 kali lebih kuat daripada oksigen. Sebaliknya sifat racun karbon monoksida akan dapat berakibat mematikan bagi yang mempunyai saturasi hemoglobin 4%-8%. 6
Selain pengikatan karbon monoksida yang sangat bersaing, sehingga mengurangi jumlah oksigen yang dapat dibawa ke jaringan-jaringan, hilangnya sifat kooperatif pengikatan oksigen akan berakibat oksigen terikat lebih erat pada hemoglobin yang berarti bahwa oksigen tidak akan mudah dilepaskan ke dalam jaringan.
Umur paruh karbon monoksida yang terikat pada hemoglobin jika seseorang sedang menghirup udara adalah sekitar 5 sampai 8 jam. Karbon monoksida akan dilepaskan cukup cepat dari hemoglobin jika diberi oksigen tambahan. 6APLIKASI KLINIS
Hepoksia
Gas karbon monoksida (CO), apabila seseorang tengah merokok, maka kandungan gas CO yang ada di dalam rokok tersebut akan ikut terhisap ke dalam paru-paru. Kemudian gas CO tersebut akan ikut dalam aliran darah termasuk aliran darah jantung. Terjadilah hepoksia karena darah kekurangan oksigen. Akibatnya jaringan tubuh juga akan kekurangan oksigen. 2
EnsefalopatiBila hipoksia menyerang otak, maka akan menimbulkan gangguan susunan syaraf pusat yang disebut ensefalopati. Apabila mengenai jantung dan darah disebut gangguan kardiovaskuler. 2
Aterosklerosis
Sel tubuh yang menderita kekurangan oksigen akan berusaha meningkatkan yaitu melalui kompensasi pembuluh darah dengan jalan menciut atau spasme. Bila proses spasme berlangsung lama dan terus menerus maka pembuluh darah akan mudah rusak dengan terjadinya proses aterosklerosis (penyempitan). Penyempitan pembuluh darah akan terjadi dimana-mana. Di otak, di jantung, di paru, di ginjal, di kaki, di saluran peranakan dan di ari-ari pada wanita hamil. 5
Sesak nafas dan penggumpalan darah
Gas CO dari asap kendaraan dapat meracuni darah. CO akan menyebabkan sesak napas dalam waktu singkat. unsur ini mendukung terikatnya CO pada Hb, hingga membentuk HbCO yang berdampak, berkurangnya O2 darah, sehingga seseorang menjadi sesak napas. 5
Nikotin, CO, dan bahan-bahan lain dalam asap rokok terbukti merusak endotel (dinding dalam pembuluh darah), dan mempermudah timbulnya penggumpalan darah. Penggumpalan atau penyumbatan dapat terjadi di otak, jantung, paru, kaki, alat kandungan dan alat vital. 5
Anoksia jaringan
Kurangnya jumlah oksigen yang dibawa ke jaringan dan hilangnya sifat kooperatif pengikatan oksigen yang berpengaruh pada ikatannya terhadap hemoglobin yang lebih erat sehingga tidak dilepas dalam jaringan. 5
LAMPIRAN
1.Bagaimana proses terjadinya keracunan CO ?
Jawab :
Keracunan karbonmonoksida sering digolongkan sebagai salah satu bentuk hipoksia anemic karena didapatkan defisiensi hemoglobin yang dapat mengangkut O2, namun kandungan hemoglobin di dalam darah tidak dipengaruhi oleh CO. Afinitas globin terhadap CO 200 kali lebih besar berkurang. 2
Inilah sebabnya mengapa penderita anemia yang mempunyai HbO2 50% dari jumlah normal masih dapat melakukan kerja fisik sedang, tetapi individu yang kadar HbO2 turun sampai taraf yang serupa akibat adanya COHb, menjadi tidak mampu melakukan kerja fisik. Adanya afinitas CO yang besar pada hemoglobin menyebabkan terjadinya pembentukan COHb progresif apabila Pco alveoli lebih besar dari 0,4 mm Hg. 2
Konsentrasi CO yang relatif rendah dalam atmosfer sudah dapat menginaktifkan sebagian besar hemoglobin, sebaliknya dengan menghirup oksigen murni dari udara. Penghilangan karbon monoksida dapat dipercepat. Pada kompleks karbon monoksida dipaksakan terbentuk oleh sisa histidin yang dekat letakya dengan gugus heme dalam rantai globin, karbo monoksida mengikat besi porfirin bebas sehingga atom Fe, C dan O linear. 8
Jumlah O2 yang dapat dibawa oleh Fe(II) molekul Hb yang masih tersisa dan belum bereaksi, akan berkurang jika ada CO pada salah satu sisa heme. Selain itu, O2 yang berikatan molekul-molekul hemoglobin yang mengandung CO, terikat lebih erat, hal ini menyebabkan pemindahan O2 dari molekul-molekul hemoglobin ke jaringan menjadi jauh lebih sulit. Sehingga pengaruh racun CO lebih berat dari pada sekedar yang dapat diperkirakan dari kadarnya dalam darah. Keracunan CO subakut memberikan gejala-gejala penyakit yang menyerupai gejala-gejala penyakit lain; sehingga diberi istilah peniru besar (great imitator). 8
2.Bagaimana gejala klinis keracunan CO ?
Jawab :
Gejala keracunan yang disebabkan gas karbon monoksida ialah sakit kepala, pening, pikiran keliru dan rasa mual. Apabila keracunan berlanjutan, maka akan hilang kesedaran dan boleh mengalami koma. Pernafasan dan pergerakan jantung akan terhenti dan meninggal. 5
Gejala permulaan yang khas berupa nyeri kepala, pusing, rasa kantuk, mual dan muntah. Tergantung pada kadar CO di udara dan lamanya paparan serta karboksihemoglobin darah yang dihasilkan, dapat terjadi pingsan, koma dan kematian. 5
Beberapa ciri orang yang mengalami keracunan karbon monoksida, di antaranya napas pendek disertai sakit kepala, terasa berat, pusing-pusing, dan pikiran menjadi kacau. Selain itu, penglihatan dan alat pendengaran juga terganggu atau mengalami kelemahan. Bila tingkat keracunannya lebih berat, dapat mengakibatkan pingsan dan diikuti dengan kematian. Keracunan karbon monoksida mengakibatkan CO akan mengikat hemoglobin sehingga kemampuan hemoglobin mengikat O2 berkurang. 3
KESIMPULAN
1. Probandus memiliki kadar karboksihemoglobin sebesar 3,92 % dan dapat disimpulkan ke dalam golongan batas toleransi CO.
2. Sampel patologis memiliki kadar karboksihemoglobin sebesar 6,97 % dan dapat disimpulkan ke dalam golongan mulai timbul gejala/ tidak normal/ keracunan.
3.Karbon monoksida adalah racun, karena mengikat feromioglobin dan ferohemoglobin sehingga menghalangi transpor oksigen.
4.Karbon monoksida bereaksi dengan hemoglobin membentuk karbon monoksihemoglobin (karboksihemoglobin).
5.Pada darah banyak mengandung hemoglobin, suatu zat yang penting bagi tubuh untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.
6.Karbon monoksida menimbulkan desaturasi hemoglobin, menurunkan langsung persediaan oksigen untuk jaringan seluruh tubuh termasuk miokard.7. Gas CO2 berasal dari proses pembakaran yang tidak sempurna dapat mengikat Hbmembentuk HbCO.
8.Ikatan Hb dengan CO sangat kuat, lebih kuat 200 kali dari ikatan Hb dengan oksigen.
9.Karbonmonoksida mengikat besi porfirin bebas 25.000 kali lebih kuat dari pada oksigen.
10. Gejala keracunan yang disebabkan gas karbon monoksida ialah sakit kepala, pening, pikiran keliru dan rasa mual. Apabila keracunan berlanjutan, maka akan hilang kesedaran dan boleh mengalami koma. Pernafasan dan pergerakan jantung akan terhenti dan meninggal.
DAFTAR PUSTAKA
1. A.V.Hoffbrand dan J.E.Petit. Hemoglobinopati. Dalam Kapita Selekta Hematologi. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 1996. Hal : 84.
2. Berita. Karbon Monoksida, [cited 2004, 1 screen]. Available from : URL : http//www.solusisehat.net
3. Bulletin. Racun, [cited 2004, 1 screen]. Available from : URL : http//www.prn2.usm.my
4.Harian. Karbon Monoksida, 2003 Februari. Available from : URL : http//www.suaramerdeka.com
5.Index. Desaturasi Hemoglobin, [cited 2004, 1 screen]. Available from : URL : http//www.jawapos.com
6.J. Ariens, et all. Kerja Toksik. Dalam : Yoke R Wattimena, dkk. TOKSIKOLOGI UMUM. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada (UGM), 1993 :109-113.7.Lubert Stryer. Potret Suatu Protein Alosterik. Dalam : Tim penerjemah bagian biokim, Muhammad Sadikin. BIOKIMIA Edisi 4 Volume 1. Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 1997 :150-151.
8.W. Reso Montgomery, et all. Struktur Protein. Dalam : Siti Dewiesah Ismadi. BIOKIMIA SUATU PENDEKATAN BERORIENTASI KASUS Jilid 1 edisi keempat. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada (UGM), 1993 : 148-153.