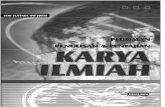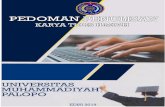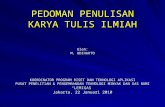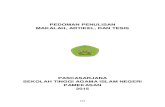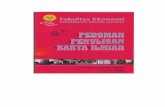Pedoman Penulisan Karya Ilmiah s1 Fapertapet Uinsuskariau 2011
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
-
Upload
sihol-simanjuntak -
Category
Documents
-
view
236 -
download
5
description
Transcript of Pedoman Penulisan Karya Ilmiah

PEDOMAN PENULISAN
KARYA ILMIAH
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
BATAM
2007

ii
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL ............................................................................................................ ii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... iii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1
1.1. Pola Umum Karya Ilmiah Skripsi ........................................................................ 1
1.2. Proposal Skripsi ................................................................................................... 13
1.3. Laporan Kerja Praktik .......................................................................................... 13
BAB II KEBAHASAAN .............................................................................................................. 15
2.1. Perhurufan ............................................................................................................ 15
2.2. Pengejaan Kata ..................................................................................................... 17
2.3. Pemenggalan Kata ................................................................................................ 19
2.4. Tanda Baca ........................................................................................................... 21
2.5. Penggunaan Istilah, Angka dan Lambang ............................................................ 26
2.6. Pemilihan Kata (Diksi) ......................................................................................... 29
2.7. Penataan Kalimat ................................................................................................. 31
2.8. Pengefektifan Paragraf ......................................................................................... 33
BAB III PENYAJIAN ILUSTRASI .............................................................................................. 35
3.1. Jenis Ilustrasi ........................................................................................................ 35
3.2. Penulisan Judul Tabel dan Gambar ...................................................................... 37
3.3. Penulisan Catatan Kaki dan Keterangan Tabel .................................................... 37
3.4. Penulisan Keterangan Simbol dan Gambar.......................................................... 38
3.5. Perujukan Tabel dan Gambar ............................................................................... 38
3.6. Interpretasi Tabel dan Gambar ............................................................................. 39
3.7. Contoh Tabel dan Gambar ................................................................................... 40
BAB IV KEPUSTAKAAN ............................................................................................................ 44
4.1. Pengacuan Pustaka ............................................................................................... 44
4.2. Penulisan Sumber Pustaka ................................................................................... 46
4.3. Penyusunan Daftar Pustaka .................................................................................. 48
4.4. Contoh Penulisan Sumber Acuan......................................................................... 54
LAMPIRAN ..................................................................................................................... 58

iii
DAFTAR TABEL
Halaman
1 Angka Romawi dan Angka Arab ..................................................................................... 26
2 Pengaruh pemberian jenis unsur hara terhadap tinggi tanaman jagung
(mm/hari) ......................................................................................................................... 40
3 Pengaruh pemberian jenis unsur hara terhadap tinggi tanaman jagung (mm) ................. 40
4 Luas bidang dasar sel kayu jati Purwakarta dan Cepu pada perbedaan lebar
lingkaran tumbuh (LT) ..................................................................................................... 41
5 Rata-rata daya serap air (%) papan semen partikel kayu kelapa sawit pada
beberapa panjang partikel dan perbandingan komposisi partikel dengan
semen ..................... ......................................................................................................... 41
6 Variasi penulisan nama pengarang dari sumber pustaka ..................... ........................... 51

iv
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
1 Contoh halaman sampul luar skripsi ................................................................................ 58
2 Contoh punggung sampul skripsi ..................................................................................... 59
3 Contoh pernyataan keabsahan skripsi .............................................................................. 60
4 Contoh abstrak ................................................................................................................. 61
5 Contoh halaman judul ...................................................................................................... 62
6 Contoh halaman pengesahan skripsi ................................................................................ 63
7 Contoh prakata ................................................................................................................. 64
8 Contoh riwayat hidup untuk skripsi ................................................................................. 65
9 Contoh daftar isi ............................................................................................................... 66
10 Contoh daftar tabel ........................................................................................................... 67
11 Contoh daftar gambar ....................................................................................................... 68
12 Contoh daftar lampiran .................................................................................................... 69

BAB I
STRUKTUR KARYA ILMIAH
Karya ilmiah1 kecuali naskah artikel jurnal diketik menggunakan kertas
HVS 80 g berukuran 21,0 cm x 29,7 cm (A4). Huruf yang digunakan ialah Times
New Roman dengan font 12 untuk teks. Judul bab menggunakan huruf dengan
font Times New Roman 14 sedangkan judul subbab dan sub-subbab dengan font
seperti teks, yaitu font 12. Semua judul dicetak tebal. Naskah diketik dengan spasi
2 pada halaman dengan pias 4 cm dari tepi kiri dan pias 3 cm dari kanan, atas,
serta bawah kertas. Naskah diketik dalam satu kolom dengan awal paragraf
menjorok 0,5 cm.
Pada dasarnya tidak ada batasan jumlah halaman minimal untuk karya
ilmiah, seperti laporan kerja praktik dan skripsi. Kualitas karya ilmiah lebih
ditentukan oleh bobot tulisan Anda, seperti keaslian, metode penelitian,
kedalaman pembahasan serta gaya tulisan yang digunakan. Dari sudut pandang
lain, untuk peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah,
seperti skripsi maka persyaratan minimum jumlah halaman skripsi ditetapkan
sebanyak 60 halaman.
1.1. Pola Umum Karya Ilmiah Skripsi
Secara umum, karya tugas akhir skripsi yang dijelaskan dalam bab ini
terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian pembuka, tubuh tulisan, dan bagian akhir.
1.1.1. Bagian Pembuka
Bagian pembuka terdiri atas: (1) halaman sampul, (2) pernyataan
keabsahan skripsi; (3) abstrak, (4) halaman judul, (5) halaman pengesahan, (6)
riwayat hidup, (7) prakata, (8) daftar isi, (9) daftar tabel, (10) daftar gambar, dan
(11) daftar lampiran. Unsur lain yang mungkin ada ialah daftar singkatan atau
glosari. Nomor halaman pada bagian pembuka dinyatakan dengan ―i, ii, iii, dan
seterusnya‖. Nomor halaman itu tidak dicantumkan pada halaman tersebut, namun
dinyatakan dalam Daftar Isi. Contoh bagian pembuka dapat dilihat pada Lampiran
1 sampai 12. Diantara sampul luar dan abstrak tidak perlu diberi kertas tambahan
yang sama dengan sampul luar dan halaman penyekat. Halaman penyekat juga
tidak diperlukan diantara bab.

2
a. Halaman Sampul
Warna sampul skripsi dan laporan praktik lapangan beragam bergantung
pada warna bendera fakultasnya. Skripsi dan laporan praktik lapangan dibuat dari
kertas jenis linen yang dilaminasi plastik. Pada sampul dicetak judul karya tugas
akhir, nama lengkap penulis, nomor pokok mahasiswa, logo Universitas Riau
Kepulauan, nama program studi, fakultas, universitas, kota dan tahun lulus
(Lampiran 1), bukan tahun wisuda.
b. Pernyataan Keabsahan Skripsi
Pernyataan mengenai skripsi dan sumber informasi merupakan suatu etika
ilmiah dan menghindari bentuk plagiat yang dinyatakan secara tertulis. Seorang
peneliti hendaknya dapat berlaku jujur terhadap penelitian yang dilaksanakannya
dan juga sumber informasi yang digunakan dalam karya ilmiah. Contoh
pernyataan ini dapat dilihat pada Lampiran 3. Halaman pernyataan mengenai
skripsi dan sumber informasi merupakan halaman pertama, diberi nomor ‖i‖ tetapi
tidak perlu dicantumkan pada halaman tersebut. Penulisan nomor halaman pada
bagian pembuka mulai dimunculkan pada halaman daftar isi.
c. Abstrak
Abstrak adalah bagian dari skripsi yang ditulis dalam bahasa Indonesia.
Laporan Praktik Lapangan tidak membutuhkan abstrak. Abstrak merupakan
ulasan singkat mengapa penelitian dilakukan, bagaimana penelitian dilaksanakan,
hasil yang penting-penting, dan kesimpulan (simpulan) utama dari hasil kegiatan.
Abstrak disusun dalam beberapa paragraf dan panjangnya tidak lebih dari
250 kata yang diketik satu spasi (Lampiran 4). Jangan menggunakan singkatan
dalam bagian ini kecuali akan disebutkan sekurang-kurangnya dua kali lagi.
Contohnya pada awal teks ‖Kromatografi Lapis Tipis‖ ditulis lengkap. Akan
tetapi bila istilah ‖Kromatografi Lapis Tipis‖ masih diperlukan dalam teks
abstrak, tulislah dulu ‖Kromatografi Lapis Tipis (KLT)‖, selanjutnya gunakan
singkatan KLT.
Dalam menyusun abstrak, tempatkan diri Anda sebagai pembaca. Mereka
ingin mengetahui dengan cepat garis besar pekerjaan Anda. Jika sesudah
membaca bagian ini pembaca ingin mengetahui perincian lain, mereka akan
membaca karya Anda selengkapnya. Penyajian abstrak selalu informatif dan

3
faktual. Untuk meningkatkan informasi yang diberikan, tonjolkan temuan dan
keterangan lain yang baru bagi ilmu pengetahuan dan suguhkan angka-angka.
Abstrak hanya memuat teks, tidak ada pengacuan pada pustaka, gambar, dan
tabel.
Abstrak diketik dengan spasi satu, termasuk judul. Kata ‖Abstrak‖ ditulis
dalam huruf kapital dan diletakkan di tengah. Nama lengkap penulis diketik
dengan huruf kapital dua spasi di bawah judul dan dimulai dari batas kiri, dengan
huruf kapital kecuali kata depan dan kata sambung. Judul dalam bahasa Inggris
diketik dengan huruf Italic di dalam tanda kurung. Selanjutnya, ‖dibimbing oleh
XXX‖ (nama lengkap pembimbing, tanpa gelar) yang ditulis dalam huruf kapital.
Teks abstrak disusun seperti menyusun paragraf.
Abstrak terletak pada halaman setelah pernyataan mengenai skripsi dan
sumber informasi, tidak diberi nomor halaman, dan tidak dimasukkan dalam
Daftar Isi. Abstrak dalam bahasa Inggris (kalau ada) ditempatkan setelah halaman
abstrak dalam bahasa Indonesia.
d. Halaman Judul
Halaman judul ditempatkan setelah abstrak. Nama penulis harus lengkap
dan jangan sekali-kali disingkat. Kalimat-kalimat yang ditulis pada halaman judul
harus simetri, dengan kata lain harus diletakkan di tengah-tengah daerah
pengetikan (Lampiran 5). Penulisan gelar pada halaman judul harus disesuaikan
dengan program studi dan peraturan yang berlaku.
e. Halaman Pengesahan
Halaman ini memuat judul, nama mahasiswa, nomor pokok mahasiswa,
nama program studi, nama dan tanda tangan para pembimbing, nama dan tanda
tangan ketua program studi dan dekan fakultas. Halaman pengesahan
ditempatkan setelah halaman judul.
f. Prakata
Prakata dapat memuat informasi kapan dan lama penelitian dilakukan,
lokasi, dan sumber dana penelitian bila biaya bukan berasal dari dana sendiri.
Pada masa sekarang ini seringkali penelitian melibatkan pihak lain. Nyatakan
terima kasih atas bantuan teknis dan saran yang Anda terima. Bila seseorang telah
membantu dalam hal-hal tertentu, nyatakan ini secara spesifik, misalnya saja

4
kepada teknisi dan laboran yang telah membantu penelitian Anda (Lampiran 7).
Dekan, ketua program studi dalam kapasitasnya sebagai pejabat tidak perlu
diberikan ucapan terima kasih seandainya bantuan yang diberikan memang sudah
menjadi kewajibannya. Hindari penomoran dan ungkapan yang berlebihan, seperti
‖Tanpa bantuan dan perhatian yang terus menerus dari Bapak XXX, tidak
mungkin penelitian ini dapat diselesaikan”. Selain itu, persantunan ini perlu
diungkapkan dengan serius, wajar, dengan tutur kata yang beradab, dalam gaya
bahasa yang tetap dijaga lugas, tanpa memuji-muji siapapun, dan tidak terkesan
main-main, misalnya ‖kepada mbak Ani, thanks”. Panjang prakata sebaiknya
tidak lebih dari satu halaman.
g. Riwayat Hidup
Riwayat hidup penulis dituliskan tidak lebih dari satu halaman. Di
dalamnya diuraikan tempat dan tanggal penulis dilahirkan, nama kedua orang tua,
pendidikan sejak sekolah menengah umum, riwayat pendidikan di Universitas
Riau Kepulauan, dan pengalaman kerja (jika ada, dengan menyebutkan secara
singkat jabatan yang dipangkunya).
h. Daftar Isi
Daftar isi disusun secara teratur menurut nomor halaman yang memuat
daftar tabel, daftar gambar, judul bab serta subbab, daftar pustaka, dan lampiran.
Keterangan halaman yang mendahului daftar isi tidak perlu dimuat dalam daftar
isi. Bab maupun subbab dapat diberi nomor sesuai dengan penulisannya dalam
tubuh tulisan (Lampiran 9).
Judul Daftar Isi diketik dengan huruf kapital dan ditempatkan di tengah-
tengah, dua spasi di bawah nomor halaman. Kata ‖Halaman‖ untuk menunjukkan
nomor halaman setiap bab atau subbab di ketik dipinggir halaman kanan yang
berakhir pada batas pinggir kanan, dua spasi di bawah kata ‖Daftar Isi‖. Susunan
daftar isi menyusul dua spasi di bawahnya. Bila daftar isi memerlukan lebih dari
satu halaman maka pengetikan diteruskan pada halaman berikutnya. Pengetikan
antarbab diantarai dengan dua spasi, sedangkan antar subbab satu spasi. Judul
setiap bab diketik dengan huruf kapital dan judul subbab hanya huruf pertama
setiap kata yang diketik dengan huruf kapital, kecuali kata depan dan kata
sambung.

5
i. Daftar Tabel dan Daftar Gambar
Daftar tabel dan daftar gambar tidak selalu diperlukan, kecuali bila lebih
dari dua tabel dan dua gambar dipakai dalam menyusun karya tulis. Daftar tabel
dan daftar gambar diketik pada halaman tersendiri dengan format seperti daftar
isi. Kata ‖Halaman‖ diketik di sebelah kanan, berakhir pada batas pinggir kanan.
Nomor tabel dan nomor gambar menggunakan angka arab. Nomor diketik tepat
pada awal permulaan batas pinggir kiri dua spasi di bawah ‖Daftar Tabel‖ atau
‖Daftar Gambar‖. Judul tabel atau gambar dalam daftar tersebut harus sama
dengan judul tabel atau judul gambar dalam teks. Akhir setiap judul tabel atau
judul gambar dihubungkan oleh tanda titik-titik dengan nomor halaman sesuai
dengan yang dijumpai dalam teks (Lampiran 10 dan 11). Di dalam teks, judul
yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi satu. Antara judul
tabel dan judul gambar diberi jarak dua spasi.
Daftar tabel diperlukan bila terdapat dua atau lebih tabel; demikian pula
halnya gambar dan lampiran yang hanya perlu dibuatkan daftarnya bila terdapat
dua atau lebih gambar dan lampiran dalam karya tugas akhir tersebut.
j. Daftar Lampiran
Sama seperti daftar tabel dan gambar, lampiran tidak perlu dibuat
daftarnya bila hanya ada satu dalam karya tulis Anda. Tata cara pengetikannya
sama dengan Daftar Tabel dan Daftar Gambar (Lampiran 12). Tidak perlu ada
pembedaan antara tabel lampiran atau gambar lampiran. Lampiran dapat berupa
tabel, gambar, atau teks, dan semuanya disusun dengan nomor urut sesuai dengan
urutan penyebutannya dalam tubuh tulisan.
1.1.2. Pedoman Penyusunan Judul Skripsi
Judul karya tugas akhir harus menarik, positif, singkat, spesifik, tetapi
cukup jelas untuk menggambarkan penelitian atau kegiatan yang dikerjakan. Judul
yang mengandung beberapa kata kunci untuk memudahkan pemayaran pustaka.
Dalam judul hindari kata-kata klise seperti penelitian pendahuluan, studi,
penelaahan, pengaruh, dan kata kerja pada awal judul. Judul (lebih tepatnya
‖topik‖) yang menggunakan kata-kata seperti itu masih dapat diterima dalam usul
penelitian. Setelah penelitian selesai, judul dapat diganti bila perlu. Nama latin

6
untuk makhluk yang sudah umum jangan digunakan dalam judul. Hindari
singkatan yang tidak perlu.
Pada umumnya, judul cenderung bersifat indikatif, artinya, merujuk pada
pokok bahasan dan bukan pada kesimpulan. Namun, kadang-kadang judul dapat
juga informatif, berupa ringkasan kesimpulan dalam beberapa kata.
Halaman persembahan tidak lazim terdapat dalam karya tugas akhir,
tetapi jika dianggap perlu dapat diletakkan sesudah halaman abstrak. Buatlah
ungkapan dalam halaman persembahan ini dengan kalimat sederhana, tidak lebih
dari satu kalimat atau satu bait, tanpa hiasan berupa gambar.
1.1.3. Tubuh Tulisan
Secara umum tubuh tulisan karya ilmiah kecuali untuk jurnal terdiri atas
(1) pendahuluan, (2) tinjauan pustaka, (3) metode penelitian, (4) hasil dan
pembahasan, dan (5) Penutup. Pada beberapa disiplin ilmu tertentu terdapat
pengecualian, misalnya dengan penambahan bab gambaran umum perusahaan
sebelum bab metode penelitian. Perubahan tubuh tulisan dalam karya ilmiah
mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh dekan fakultas. Setiap bab
dimulai pada halaman baru. Judul setiap bab diketik dengan huruf kapital. Nomor
halaman menggunakan angka arab dan ditempatkan di kanan atas halaman.
Halaman bab tidak perlu diberi nomor halaman.
Merancang bab merupakan hal yang tidak mudah. Batasi dua atau tingkat
dalam bab dan usahakan merata sehingga tidak ada subbab yang menempati lebih
dari delapan halaman. Hierarki bab yang digunakan mengacu kepada ketentuan
berikut:
a) Nama bab diketik dengan huruf kapital dengan jarak 4 cm dari pias atas.
Nomor urut bab ditulis dengan angka Romawi dan ditulis di tengah-tengah
kertas di atas nama bab, contoh: Bab I, Bab II, dan seterusnya.
b) Sub bab dan nomor sub bab dimulai dari batas pias kiri. Huruf awal setiap
kata ditulis dengan huruf kapital dan font tebal. Nomor sub bab ditulis dengan
angka arab dengan ketentuan angka pertama menunjukkan bab dan angka
kedua sub bab. Penulisannya dilakukan secara berurutan mulai dari angka
kecil. Sebagai contoh: 1.1.; 1.2.; 3.5.; dan lainnya.

7
c) Anak sub bab dimulai dari batas tepi kiri. Huruf awal setiap kata ditulis
dengan huruf kapital. Penulisan hirarki anak sub bab menggunakan angka arab
sebanyak tiga. Urutan angka berturut-turut menunjukkan bab, sub bab, dan
anak sub bab. Sebagai contoh: 1.1.1.; 1.1.2.; 2.5.1.; dan yang lainnya.
d) Hirarki berikutnya tidak dianjurkan dalam karya tulis skripsi. Jika diperlukan
dapat menggunakan huruf kecil yang dimulai dari a., b., c., dan seterusnya.
Huruf kapital hanya digunakan pada awal judul, kecuali untuk kata yang
penulisan awal katanya huruf kapital.
a. Pendahuluan
Bab pendahuluan biasanya memuat latar belakang yang dengan singkat
mengulas alasan mengapa penelitian dilakukan, tujuan, dan hipotesis (jika
dinyatakan secara eksplisit). Berikan alasan yang kuat, termasuk kasus yang
dipilih, alasan pemilihan, atau metode yang akan digunakan. Bab ini seyogianya
membimbing pembaca secara halus tetapi tepat lewat sepenggal pemikiran logis
yang berakhir dengan pernyataan mengenai apa yang diteliti dan apa yang
diharapkan dari padanya. Berikan kesan bahwa apa yang Anda teliti benar-benar
bermanfaat bagi ilmu pengetahuan atau pembangunan.
Tujuan Penelitian merupakan bagian ini mengakhiri bab pendahuluan yang
berisi pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Dalam menuliskan tujuan,
gunakan kata kerja yang hasilnya dapat diukur atau dilihat, seperti menjajaki,
menguraikan, menerangkan, menguji, membuktikan, atau menerapkan suatu
gejala, konsep, atau dugaan, atau bahkan membuat suatu prototipe. Dengan
demikian, kata ‖mengetahui‖ tidak layak dituliskan untuk tujuan penelitian.
Tujuan penelitian tidak selalu menggunakan subbab tersendiri.
b. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka memuat tinjauan singkat dan jelas atas pustaka yang
menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian. Pustaka yang digunakan
sebaiknya pustaka terbaru yang relevan dalam bidang yang diteliti. Untuk itu,
pustaka primer (buku ajar tidak termasuk pustaka primer) diutamakan. Jumlah
halaman bab ini usahakan tidak melebihi bab Hasil dan Pembahasan.

8
Uraian dalam tinjauan pustaka merupakan dasar untuk menyusun kerangka
atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Kumpulan pustaka yang relevan
dan mutakhir membantu Anda mengetahui dengan jelas status penelitian di bidang
tersebut. Kumpulan pustaka yang memadai pasti akan meningkatkan kepercayaan
diri Anda sewaktu memilih metode, melaksanakan penelitian, dan menyusun
argumentasi dalam bab Pembahasan. Pengacuan pada pustaka harus sesuai dengan
yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
c. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dapat berupa analisis suatu teori,
metode percobaan, atau kombinasi keduanya. Metode yang dipakai diuraikan
secara terperinci (peubah, model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik
pengumpulan dan analisis data, serta cara penafsiran). Hal lain yang perlu
diperinci ialah identifikasi tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme menurut
spesies atau galurnya. Pemasok bahan adakalanya perlu diutarakan terutama kalau
sumbernya tidak lazim. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif,
pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta
proses penafsiran hasil penelitian harus dijelaskan. Akan tetapi, jika metode
penelitian yang digunakan sepenuhnya mengikuti metode yang telah
dipublikasikan maka uraian yang sangat lengkap tidak diperlukan. Sebagai
gantinya, sebutkan saja sumber pustakanya. Bahan, alat, perubahan atau
modifikasi terhadap metode yang dipublikasikan perlu dijelaskan.
Jika jenis bahan tidak banyak, uraiannya dapat disatukan dengan metode
sehingga tidak diperlukan subbab khusus. Sumber bahan berupa perusahaan atau
individu maupun lembaga dapat dituliskan sepanjang hal itu sangat spesifik.
Namun penyebutan nama dagang perlu dihindari sebab karya ilmiah akan tampak
sebagai media iklan cuma-cuma. Merk instrumen analisis utama sering kali perlu
ditulis, misalnya ‖timbangan analitis‖ atau dapat ditulis lengkap ‖timbangan
analitis (Sartorius)‖. Penyebutan nama pembuat alat dimaksudkan untuk
menunjukkan kecanggihan atau ketelitian alat. Di sisi lain, jenis perkakas dan alat
seperti martil, gergaji, mistar, dan sejenisnya tidak perlu diperinci, tetapi dengan
sendirinya akan terungkapkan ketika Anda menjelaskan prosedur kerja. Jangan
membuat perincian dalam bentuk daftar seperti yang lazim tertera pada penuntun

9
praktikum. Ada baiknya Anda menggunakan bagan alir kalau cara penelitian
dianggap rumit dan dapat membingungkan pembaca.
Kegiatan yang dilakukan ditulis sesuai dengan urutan pengoperasiannya
dengan menggunakan kalimat pasif dan bukan kalimat perintah. Pernyataan ‖Ukur
dimensi kayu sesudah dikeringkan‖ sebaiknya ditulis ‖kayu dikeringkan lalu
diukur dimensinya‖.
d. Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian sewajarnya disajikan secara bersistem. Untuk
memperjelas dan mempersingkat uraikan, berikan tabel, gambar, grafik, atau alat
penolong lain. Data yang terlalu ekstensif perlu dibuat ikhtisarnya dan diulas
dengan kata-kata. Data yang terlalu rumit akan menurunkan keterbacaan dan
sebaiknya dilampirkan saja. Nomor tabel dan gambar yang harus disebut dalam
teks dan diletakkan tidak jauh dari teks bersangkutan. Kiat membuat dan
menampilkan ilustrasi ini dipaparkan pada bab tersendiri. Hasil yang diperolah
ditafsirkan dengan memperhatikan dan menyesuikannya dengan masalah dengan
hipotesis yang diungkapkan dalam pendahuluan.
Ada kalanya hasil penelitian dipisahkan dengan pembahasan menjadi bab
hasil penelitian dan bab pembahasan. Pemisahan atau penggabungan kedua bagian
ini sangat terngantung pada keadaan data dan kedalaman pembahasannya. Bila
kedua bagian ini digabung, pembaca sulit membedakan mana hasil perkerjaan
peneliti dan mana hasil dari pemayaran pustaka. Keutungan penyajian hasil secara
terpisah ialah format akan lebih rapi dan pembaca dipersilakan mengambil
kesimpulan terlebih dahulu untuk kemudian menbandingkannya dengan
kesimpulan penulis.
Sebelum menentukan apa yang harus ditulis dalam pembahasan, penulis
hendaknya membaca sekali lagi hipotesis atau tujuan penelitiannya. Cocokkan
harapan itu dengan hasil utama. Dalam bagian inilah dituntut kemampuan Anda
sebagai orang calon ilmuan. Jangan buang kesempatan ini dengan menciptakan
alur yang berputar-putar. Membahas tidak sekedar menyarikan hasil peneliti.
Sewaktu mengumpulkan data, mengolahnya dan menyusunnya dalam tabel,
dengan sendirinya Anda telah memiliki sejumlah gagasan ini disebut ’argumen’,
sebab Anda harus membenarkannya dihadapan segala sesuatu yang telah

10
diketahui dalam bidang yang diteliti. Anda pun diminta mengemukakan
keterbatasan yang ada dengan sejujurnya. Anda harus membandingkan dengan
hasil peneliti terdahulu, kemudian membuat pertimbangan teoritisnya. Dengan
demikian, maka pembahasan merupakan kesimpulan argumen mengenai
relevansi, manfaat, dan kemungkinan atau keterbatasan percobaan Anda, serta
hasilnya.
Setiap argumen dikembangkan dalam sebuah paragraf (alinea). Teknik
untuk mengembangkan argumen sama dengan menyusun paragraf yang baik.
Oleh sebab itu perlu dipikirkan memecah-mecah seluruh pembahasan menjadi
beberapa pokok yang diperkembangkan satu per satu. Jadi, setiap paragraf dalam
pengembangan argumen memuat tiga unsur, yaitu kalimat topik, pengembangan
penalaran, dan kesimpulan atau ringkasan bilamana paragraf berikutnya ingin
menampilkan gagasan yang berbeda.
Pembahasan merupakan tempat menulis mengemukakan pendapat dan
argumentasi secara bebas tetapi singkat dan logis. Pendapat orang lain yang telah
diringkas dalam pendahuluan (atau tujuan pustaka) tidak perlu diulang tetapi
diacu saja seperlunya. Dengan tidak meringkas lagi hasil penelitian dalam
pembahasan, ulaslah apakah hasil Anda memenuhi tujuan penelitian. Hubungkan
temuan dari penelitian Anda dengan pengamatan atau hasil peneliti sebelumnya
dengan jalan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaannya. Penulis
sebaiknya tidak menyatakan ‖....kesimpulan Nasution (1995) mendukung hasil
penelitian ini ....‖ (sementara Anda mengulas hasil penelitian Anda tahun 2001),
tetapi yang baik ialah ‖.... penelitian ini memperkuat kesimpulan Nasution (1995)
....‖. Arti temuan perlu dibentangkan dan dijelaskan dalam memperlus cakrawala
ilmu dan teknologi dengan cara mengekstrapolasi hasil, memberi implikasi pada
penerapannya, termasuk pula segi lain yang memerlukan pengkajian lebih lanjut.
Spekulasi kadang-kadang tidak dapat dihindari dan muncul dalam pembahasan,
namun hindari spekulasi yang terlalu jauh.
e. Penutup
Dalam bab penutup berisi kesimpulan skripsi dan saran (kalau ada).
Kesimpulan pokok dari keseluruhan penelitian hendaknya disusun secara hati-
hati. Kesimpulan memang memerlukan kecermatan luar biasa dan dibenarkan

11
memunculkannya tiga kali (sebaiknya dengan ungkapan yang berbeda-beda),
yaitu dalam pembahasan, kesimpulan, dan abstrak. Kesimpulan memuat ringkasan
hasil penelitian dan jawaban atas tujuan penelitian atau hipotesis. Dalam bab ini
bedakan antara dugaan, temuan, dan kesimpulan. Berbeda dengan abstrak yang
berupa paragraf dengan rangkaian kalimat yang terkesang ‖terpotong-potong‖,
kesimpulan dapat memuat uraian yang lebih luas dan mudah dibaca.
Dalam menarik kesimpulan, penulis harus kritis dengan memperhatikan
apakah kesimpulan yang dibuat dapat ditafsirkan secara lain. Cukup luaskah
perampatan (generalisasi) yang digariskan berdasarkan kesimpulan hasil,
pendapat, dan teori yang ada?
Saran yang dikemukakan seharusnya berasal dari hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan penelitian atau hasil penelitian. Ungkapan yang sering kali
muncul dalam saran ‖... agar penelitian ini dilanjutkan ...‖ barangkali dapat
dipertanyakan apakah hal ini memang perlu bagi dunia pengetahuan atau hanya
untuk kepuasan peneliti sendiri? Saran tidak selamanya harus ada. Di sisi lain,
disertasi di negara maju sering memunculkan satu bab berjudul Future Works
yang berisi saran tentang hal-hal yang perlu dikerjakan pada penelitian
selanjutnya. Uraian meliputi kelemahan atau kekurangan penelitian yang telah
dikerjakan dan yang perlu dilengkapi dan disempurnakan pada tahap berikutnya.
Untuk penelitian yang banyak berhubungan dengan kebijakan, sebaiknya
saran tidak dikemukakan secara eksplisit. Alasannya ialah bahwa setiap kebijakan
itu diterapkan setelah mempertimbangkan bukan saja segi ilmiah, melainkan segi
teknis dan politis, hasil penelitian biasanya hanya dibahas dari segi ilmiahnya saja.
1.1.4. Bagian Akhir
Bagian akhir karya ilmiah skripsi terdiri atas Daftar Pustaka (harus ada)
dan Lampiran (kalau ada).
a. Daftar Pustaka
Bab ini merupakan suatu daftar dari semua artikel dan pustaka lain yang diacu
secara langsung di dalam tubuh tulisan, kecuali bahan-bahan yang tidak
diterbitkan dan tidak dapat diperoleh dari perpustakaan. Teknik penulisan dan
pengacuan dijelaskan secara terperinci pada bab Kepustakaan.

12
Pencantuman pustaka selain merupakan suatu bentuk penghargaan dan
pengakuan atas karya atau pendapat orang lain juga sebagai etika ilmiah.
Pencantuman pendapat orang lain tanpa merujuk sumbernya akan mengesankan
plagiatisme. Komunikasi pribadi tidak termasuk dalam pustaka, bila diperlukan,
nyatakan hal ini dalam teks atau catatan kaki.
Catatan kaki berisi keterangan ringkas atas pernyataan dalam tubuh tulisan
yang kurang memadai bila dibuat dalam bentuk Lampiran. Dalam beberapa
bidang ilmu, catatan kaki juga dimanfaatkan untuk memuat pustaka yang diacu,
namun hal ini tidak dianjurkan dalam bidang sains. Penggunaan catatan kaki,
apalagi dalam jumlah banyak, akan menurunkan keterbacaan dan merusak
tampilan naskah.
Catatan kaki dipisahkan dari teks dengan garis mendatar sepanjang 5 cm.
Gunakan lambang non-numerik (*,#,§,...,...) untuk mengacunya.
b. Lampiran
Lampiran didahului oleh satu halaman yang hanya memuat kata
LAMPIRAN dan ditempatkan di tengah-tengah halaman. Halaman ini tidak diberi
nomor.
Lampiran merupakan tempat untuk menyajikan keterangan atau angka
tambahan. Di dalamnya dapat dihimpun cara penelitian, contoh perhitungan
statistik, penurunan rumus matematika, daftar pernyataan program komputer atau
bagan alirnya, spektrum senyawa, diagram rangkaian alat, tabel besar dari satu set
percobaan, peta, dan sebagainya yang kalau dimasukkan ke dalam tubuh tulisan
akan mengganggu jalan cerita. Bila jumlahnya lebih dari sebuah, lampiran perlu
diberi nomor. Jangan masukkan informasi penting dalam lampiran karena bagian
ini sering terlewatkan oleh pembaca. Meskipun judul gambar lazimnya ditulis di
bawah gambar yang bersangkutan, di dalam lampiran, judul gambar dapat
dituliskan sebagai judul lampiran.
Tabel yang terlalu rumit sangat mengganggu jalannya pembahasan. Oleh
sebab itu, buatlah tabel yang sederhana dan secukupnya untuk memperjelas
pembahasan di dalam teks; informasi selebihnya dapat dimasukkan ke dalam
lampiran. Ada kalanya data mentah dilampirkan untuk keperluan penelitian lebih

13
lanjut. Bila Anda terlalu sering meminta pembaca untuk melihat lampiran,
barangkali cara pembahasan Anda perlu direkonstruksi.
1.2. Proposal Skripsi
Proposal skripsi merupakan acuan dasar mahasiswa dalam melaksanakan
penelitian tugas akhir skripsi. Proposal skripsi disusun sebelum kegiatan
penelitian dilaksanakan.
Struktur penulisan proposal skripsi pada dasarnya mengacu kepada
penulisan karya ilmiah skripsi. Secara umum penulisan proposal skripsi berakhir
pada Bab tentang Metode Penelitian. Gambaran umum, susunan proposal skripsi
adalah sebagai berikut:
1.2.1. Bagian Pembuka
Bagian pembuka proposal skripsi terdiri dari: (a) halaman sampul, (2)
halaman judul, (3) halaman pengesahan, (4) prakata, (5) daftar isi, (6) daftar tabel,
(6) daftar gambar, dan (11) daftar lampiran.
1.2.2. Tubuh Tulisan
Secara umum tubuh tulisan proposal skripsi terdiri atas bagian: (1)
pendahuluan, (2) tinjauan pustaka, dan (3) metode penelitian.
1.2.3. Bagian Akhir
Bagian akhir proposal skripsi terdiri atas Daftar Pustaka (harus ada) dan
Lampiran. Dalam bagian akhir, lampirkan Jadwal Pelaksanaan (disusun dalam
bentuk bar-chart), serta lampiran Rencana Anggaran Biaya (rincian biaya yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi).
1.3. Laporan Kerja Praktik
Laporan Kerja Praktik dapat disusun secara perorangan atau kelompok.
Pada umumnya, bagian pembuka laporan kerja praktik tidak memuat Abstrak dan
Riwayat Hidup. Bagian-bagian lain ditulis dengan ketentuan yang sama dengan
tata cara penulisan skripsi. Dalam prakata, cantumkan kapan waktu pelaksanaan,
jadwal kerja, nama-nama pembimbing atau pendamping Anda selama berpraktik,
serta ucapan terima kasih.
Isi laporan dapat terdiri atas: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Keadaan
Umum xxx (tuliskan nama instansi tempat praktik), Kegiatan Praktik (dapat
terdiri atas satu atau beberapa bab), Kesimpulan atau Penutup, dan Daftar Pustaka.

14
Pedoman penulisan untuk bab Pendahuluan dan Tinjauan Pustaka dapat
mengacu pada tata cara penulisan skripsi sebagaimana yang telah diuraikan
sebelumnya. Untuk bab lain, dapat dilihat pada uraian berikut:
1.3.1. Keadaan Umum
Pada bab keadaan umum dapat dilaporkan sejarah tempat Anda berpraktik,
fasilitas kerja, kegiatan lembaga (misalnya bidang penelitian dan pengembangan,
atau kegiatan produksi di pabrik), struktur organisasi, tujuan lembaga, fungsi
lembaga, keadaan sumber daya manusia, dan hal lain yang dianggap perlu. Akan
sangat baik bila Anda mengemukakan ulasan, analisis, atau pandangan kritis
dalam mengamati lembaga tersebut.
1.3.2. Kegiatan Praktik
Hasil kerja dapat ditulis dalam satu atau beberapa sub bab bergantung pada
volume kerja atau jenis kegiatan Anda selama berpraktik. Misalnya seorang
mahasiswa berpraktik di dua unit dalam satu industri pengolahan minyak dapat
menuliskan dalam dua sub bab terpisah dengan judul ‖Kegiatan di Unit Produksi‖
dan ‖Kegiatan di Unit Penjaminan Mutu‖.
1.3.3. Penutup
Dalam bab penutup, Anda dapat menyimpulkan hal-hal yang berkaitan
dengan lembaga tempat berpraktik, hasil kerja Anda sendiri, maupun pengalaman
serta kesan semasa berpraktik.

BAB II
KEBAHASAAN
Mengingat pentingnya peran bahasa dsalam komunikasi, baik secara lisan
maupun tulisan, maka membutuhkan penggunaan bahasa yang efisien dan efektif.
Bahasa yang efisien ialah bahasa yang mengikuti kaidah tata bahasa yang
dibakukan atau yang dianggap baku, dengan mempertimbangkan kehematan kata
dan ungkapan. Kata baku disini berarti bahasa yang digunakan merupakan bahasa
yang benar dan patut jadi teladan untuk diikuti. Bahasa yang efektif disini ialah
bahasa yang mampu mencapai sasaran yang dimaksudkan.
2.1. Perhurufan
Seperti kebanyakan bahasa di dunia, bahasa Indonesia ditulis dengan huruf
Latin. Dua bentuk huruf Latin yang dikenal ialah huruf Romawi dan huruf miring.
Huruf latin dapat ditampilkan secara tipis, tebal, kecil, dan kapital.
2.1.1. Huruf Romawi
Huruf Romawi selalu berdiri tegak sehingga tulisan tangan yang bersifat
demikian sering dikatakan ―tercetak‖. Dalam dunia percetakan dan pengetikan
bentuk huruf inilah yang selalu dipakai secara bertaat asas. Kecuali ditentukan
lain, huruf Romawi (terutama yang berpenampilan kurus), hampir selalu dapat
dipergunakan untuk segala keperluan.
2.1.2. Huruf Miring
Huruf miring ditampilkan secara miring sering disebut sebagai huruf Italic.
Bentuknya seperti tulisan tangan. Karena keadaannya itu huruf miring sering
disebut juga sebagai huruf kursif. Kalau diketik atau ditulis tangan kemiringannya
ditandai dengan garis bawah tunggal. Huruf miring dipakai untuk:
1) Kata dan ungkapan asing yang ejaannya bertahan dalam banyak bahasa:
ad hoc, et al., in vitro.
2) Tetapan dan peubah yang tidak diketahui dalam matematika. Contoh n, i.
3) Nama kapal atau satelit: KRI Macan Tutul, Apollo 11.
4) Kata atau istilah yang diperkenalkan untuk diskusi khusus, misalnya
kakas, citraan.
5) Kata atau frase yang diberi penekanan.
6) Pernyataan rujukan silang dalam bentuk indeks: lihat, lihat juga.

36
7) Judul buku atau terbitan berkala yang disebutkan dalam tulisan.
8) Tiruan bunyi, contoh: Dari sarang burung itu terdengar kicau tu-ju-pu-lu-
tu-ju-pu-lu.
9) Nama ilmiah seperti genus, spesies, varietas, dan forma makhluk. Salacca
zalacca var. Amboinense. Akan tetapi, nama ilmiah takson di atas tingkat
genus tidak ditulis dengan huruf miring, seperti: Felidae, Moraceae.
Mucorales.
2.1.3. Huruf Kapital
Huruf kapital dipakai pada:
1) Huruf pertama pada awal kalimat.
2) Setiap kata dalam judul buku atau terbitan berkala, kecuali kata tugas,
seperti dan, yang, untuk, di, ke, dari, terhadap, sebagai, tetapi,
berdasarkan, dalam, antara, melalui, secara yang tidak terletak pada
posisi awal.
3) Nama bangsa, bahasa, agama, orang, hari, bulan, tarikh, peristiwa sejarah,
takson makhluk di atas genus, lembaga, jabatan, gelar dan pangkat yang
diikuti nama orang atau tempat.
4) Setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada judul buku dan
nama bangsa dan lain-lain seperti dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas,
sebagai contoh: Undang-Undang Dasar 1945, Perserikatan Bangsa-
Bangsa.
5) Nama-nama geografi seperti nama sungai, kota, provinsi, negara, dan
pulau. Akan tetapi huruf kapital tidak dipakai pada nama geografi yang
digunakan sebagai jenis (seperti kacang bogor, badak sumatera, garam
inggris, gula jawa), atau sebagai bentuk dasar kata turunan (seperti
keinggris-inggrisan, mengindonesiakan, pengaraban).
6) Penulisan nama orang pada hukum, dalil, uji, teori dan metode, misalnya:
hukum Dalton, uji Duncan, metode Epstein, atau analisis Fourier. Untuk
penamaan rancangan, proses, uji , atau metode yang tidak diikuti nama
orang ditulis dengan huruf kecil, misalnya: uji morfometri, uji moralitas,
atau rancangan acak lengkap. Apabila penamaan tersebut akan disingkat,
maka singkatannya menggunakan huruf kapital, sebagai contoh:

37
rancangan acak lengkap (RAL), proses hierarki analitik (PHA), atau
metode imunodifusi ganda (MIG).
2.1.4. Huruf Tebal
Huruf tebal sering digunakan untuk judul atau tajuk (heading). Selanjutnya
bentuk huruf ini dapat dipakai untuk nama ilmiah takson yang baru ditemukan
atau diusulkan pertama kali. Vektor dan matriks dalam matematika pada
umumnya juga ditampilkan dengan huruf tebal. Dulu nomor jilid buku dan
terbitan berkala biasa ditulis dengan huruf tebal, tetapi kebiasaan ini sekarang
mulai ditinggalkan.
2.1.5. Huruf Yunani
Selain huruf Latin, dalam tulis menulis karya ilmiah sering digunakan
huruf Yunani. Beberapa huruf kapital Yunani sama dngan huruf Latin, tetapi
semua huruf kecilnya mempunyai bentuk yang sangat berbeda. Huruf Yunani
banyak dipakai dalam rumus matematika (πr2), lambang astronomi (deklinasi δ),
satuan ukuran (μm), istilah kimia (β-amilase) atau kedokteran (γ-globulin).
2.2. Pengejaan Kata
Sejak diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada
tahun 1972, semua huruf dalam abjad Latin secara resmi sudah menjadi huruf
bahasa Indonesia. Oleh karena sudah termasuknya semua huruf itu, sering terjadi
kesalahan yang disebabkan oleh tindakan hiperkorek. Kata pernafasan, misalnya,
secara salah acapkali dieja pernapasan. Pasca (yang dalam ejaan lama ditulis
pastja) adakalanya dieja dan dilafalkan paska.
Adakalanya kita menaati (perhatikan: bukan mentaati) sistem ejaan yang
disempurnakan itu, dalam penulisan kata berimbuhan sering terjadi penggantian
huruf. Dengan berpedoman pada pola mentaati itu, kita harus menulis
menerjemahkan (bukan menterjemahkan), mencolok (bukan menyolok),
mengubah (bukan merubah atau merobah), terkecuali untuk mengkaji. Begitu
pula, kita harus menulis penerapan (bukan penterapan), dikelola (bukan dilola),
dan seterusnya.
Oleh karena semua huruf latin diterima sebagai huruf Indonesia, penulisan
kata serapan dari bahasa asing pada umumnya sudah dapat dilakukan mendekati
bentuk aslinya. Untuk itu memang perlu dilaksanakan penyesuaian Pedoman

38
Umum Pembentukan Istilah yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa dan Kamus
Besar Bahasa Indonesia. Beberapa masalah sering dijumpai dalam kasus
penggunaan huruf atau pengejaan istilah serapan seperti dicontohkan berikut ini.
1) Berhati-hatilah dalam memakai huruf f dan v, yang adakalanya
dipertukarkan atau diganti dengan huruf p (negatif bukan negatip; aktif,
aktivitas; bukan aktip, aktifitas; provinsi, bukan propinsi).
2) Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal adanya konsonan kembar
(klasifikasi, bukan klassifikasi; efektif, bukan effektif, tetapi ada massa
disamping masa yang mempunyai perbedaan makna).
3) Huruf y sekarang adalah pengganti huruf j dulu, jadi tidak dapat dipakai
sebagai pengganti huruf i lagi (hipokotil, bukan hypokotil; analisis, bukan
analisa, analysis, atau analysa.
4) Huruf x hanya dipakai di awal kata, di tempat lain diganti ks (xilem, bukan
silem atau ksilem; taksonom, bukan taxonomi; kompleks, bukan komplex
atau komplek.
5) Huruf h pada gugus gh, kh, rh, th dihilangkan, sedangkan huruf ph
menjadi f dan ch menjadi k (sorgum, bukan sorghum; kromatografi, bukan
khromatograph, rhitme, bukan rhitma; metode, bukan methode atau
metoda; morfologi, bukan morphology atau morpologi).
6) Beberapa kata sulit yang selalu ditulis secara salah karena penulis tidak
mengetahui bentuk bakunya, antara lain ialah kualitas, bukan kwalitas;
jadwal bukan jadual; sintesis, bukan sintesa; amoeba bukan amuba;
projektor, bukan proyektor; atmosfer, bukan atmosfir atau atmosfera;
varietas, bukan varitas; bir, bukan bier; automatis, bukan otomatis;
mikrob, bukan mikroba atau mikrobe sebab dibakukannya aerob; standar
dan standardisasi, bukan standarisasi.
7) Nama-nama ilmu tertentu berakhiran –ika (sistematika, bukan sistematik
atau sistimatik); karena bukan ilmu maka dibakukanlah kosmetik dan
antibiotik, bukan kosmetika dan antibiotika; begitu juga tropik, bukan
tropika atau tropis, karena dibakukannya Samudera Pasifik.
8) Dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa dalam bahasa Indonesia satu bentuk
kata dapat berfungsi sebagai kata benda (botani—botanical/botanically).

39
Oleh karena itu, department of genetics—jurusan genetika; plant genetic
resources—sumber daya genetis tumbuhan dan bukan sumber daya
genetik tumbuhan atau sumber daya genetis tumbuhan, genetical
evidence—bukti genetika, bukan bukti genetis atau bukti genetik.
Berdasarkan analogi, untuk memadankan biological process dibakukan
dengan proses biologi (lebih baik lagi: proses hayati), bukan proses
biologis atau proses biologik; enteropathogenic Escherichia coli menjadi
Escherichia coli enteropatogen.
2.3. Pemenggalan Kata
Dalam penulisan kita selalu dibatasi oleh bidang yang disyaratkan, oleh
karena itu kata kadang-kadang tidak dapat ditulis secara utuh. Kata-kata yang
demikian harus dipenggal menurut suku katanya.
Berikut beberapa cara pemenggalan suku kata:
1. Kata Dasar
a. Jika ditengah kata ada vokal berurutan, pemenggalan dilakukan antara
kedua vokal itu. ( - V/V -); misal:
ma-af ba-ik du-et
Apabila vokal berurutan tersebut berupa diftong, maka pemenggalan tidak
dilakukan di antara vokal tersebut ( - V/V/--); misal:
sau-da-ra bukan sa-u-da-ra
pan-tai bukan pan-ta-i
b. Jika di tengah kata ada huruf konsonan dan gabungan konsonan di antara
dua buah huruf vokal maka pemenggalan dilakukan sebelum konsonan
(KV – KV); misal:
pe-rut ta-bu
ta-nya su-nyi
c. Jika di tengah kata ada konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan
di antara dua konsonan tersebut ( - K/KK -); misal:
Mak-lum ger-tak
Mik-ro mig-ra-si
Kecuali ng, kh, sy, dan ny yang berupa satu bunyi dianggap sebagai satu
suku kata, misal:

40
de-ngan makh-luk
i-sya-rat bu-nyi
d. Jika konsonan berurutan lebih dari dua buah, pemenggalan dilakukan
sesudah konsonan pertama ( - K/KK -); misal:
in-struk-si, kon-kret, kon-kre-si
2. Semua imbuhan dan partikel dianggap suku kata, termasuk pada imbuhan
awalan yang mengalami perubahan bentuk, sehingga imbuhan dapat dipenggal
dari kata dasarnya.
Misal: me-ramu me-nya-pu
Men-coba pem-belah-an
Catatan:
a. Akhiran –i dan kata yang diawali vokal tidak dipenggal, contoh yang salah
misalnya:
Mengakhir-i, a-nak, i-kan
b. Kata yang berimbuhan sisipan pemenggalannya dilakukan sebagai berikut,
misal:
te-lun-juk ge-ri-gi
ge-me-tar
c. Imbuhan yang berasal dari bahasa asing tidak dianggap sebagai imbuhan
melainkan sebagai suku kata itu sendiri sehingga pemenggalannya
mengikuti aturan pemenggalan kata dasar. Misalnya spor-ti-vi-tas, bukan
sportiv-itas, ak-li-ma-ti-sa-si bukan ak-li-mat-isasi atau peng-ak-li-
mat-an
3. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat
digabung dengan unsur lain, pemenggalan dilakukan:
a. di antara unsur-unsur itu, atau
b. pada unsur gabungan itu sesuai kaidah-kaidah di atas.
Misal : bio-logi, bi-o-lo-gi
mikro-biologi, mik-ro-bi-o-lo-gi
pasca-sarjana, pas-ca-sar- ja-na
budi daya, bu-di da-ya

41
2.4. Tanda Baca
2.4.1. Tanda Titik (.)
Tanda titik selalu
dipakai
1) pada akhir kalimat;
2) pada singkatan tertentu (A.P.Nasution, gb., hlm., S.Si.);
3) di belakang angka dan huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar (8.0,
8.1, 8.1.1, 8.1.2);
4) sebagai pemisah angka jam dan menit yang menunjukkan waktu atau
jangka waktu (pukul 13.30; 2.30.15 jam);
5) sebagai pemisah bilangan angka ribuan atau kelipatannya yang
menunjukkan jumlah (210.848 sel).
Tanda titik tidak dipakai
1) di belakang angka atau huruf terakhir dalam suatu bagan, ikhtisar, atau
daftar (8.1, 8.1.1, 8.1.2);
2) untuk menyatakan pecahan persepuluhan (untuk itu pakailah koma
sehingga setengah ditulis 0,5);
3) untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak
menunjukkan jumlah (tahun 1995, halaman 2345, NIP 130367078);
4) pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi dan
tabel.
2.4.2. Tanda Titik Terangkat ( · )
Dalam beberapa bidang ilmu di tempat tanda titik digunakan titik terangkat,
yaitu ketika :
1) menulis gugus air dalam senyawa kimia (CuS04.SH20);
2) menunjukkan perkalian sebagai pengganti tanda x, misal k x g x (a+2)
dapat dicetak sebagai kg (a+2) atau k·g·(a+2);
3) menyingkatkan ikatan kimia pengganti tanda ikatan baku (R--CH3 dapat
ditulis R·CH3);
4) memberikan petunjuk cara pemenggalan kata dalam kamus
(per·bu·nga·an, sin·tas·an );
5) menunjukkan ekspresi genetika (AA·BB·AB·);

42
6) mengganti tanda elipsis dalam matematika, untuk meluruskannya dengan
tanda pengoperasian (x1, x2···x3).
2.4.3. Tanda Koma (, )
Tanda koma dipakai :
1) untuk menyatakan pecahan persepuluhan atau di antara rupiah dan sen
yang dinyatakan dengan angka (seperempat ditulis dengan 0,25;
Rp25,50);
2) untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu deret (nitrogen, fosforus,
kalium);
3) untuk memisahkan unsur-unsur sintaksis dalam kalimat;
4) untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar
pustaka (Dalimunthe P. Anatomi Tumbuhan. Batam: Unrika Press);
5) di antara nama, alamat serta bagian-bagiannya; tempat dan tanggal; nama
tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan (Dekan Fakultas
Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Jalan Batu Aji Baru, Batam;
Batam, 2 Mei 1999).
6) di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk
membedakan dari singkatan nama diri atau keluarga (Dr. H. Amarullah
Nasution, S.E,MBA,DBA).
Tanda koma untuk memisahkan nama pengarang dan tahun dalam
pengacuan kepustakaan boleh tidak digunakan. Misalnya (Nasution, 2000) boleh
ditulis sebagai (Nasution 2000). Dalam pedoman ini dianut penulisan tanpa koma.
2.4.4. Tanda Titik Koma (;)
Tanda titik koma merupakan tanda koordinasi dan dipakai untuk
memisahkan unsur-unsur sintaksis yang setara, atau dalam deret yang di dalamnya
sudah mengandung tanda baca lain (Saya datang; saya lihat; saya menang).
1. Tanda Titik Dua (:)
Titik dua dipakai untuk:
1) menandakan pengutipan yang panjang, misalnya "Bandingkan dengan
keterangan pembatas yang pemakaiannya tidak diapit koma: Semua
siswa yang lulus ujian mendaftarkan namanya pada panitia ";

43
2) memperkenalkan senarai;
3) menandakan nisbah (angka banding);
4) menekankan urutan pemikiran di antara dua bagian kalimat lengkap.
5) memisahkan judul dan anak judul;
6) memisahkan nomor jilid dan halaman dalam daftar pustaka (Academica 3:
20-24);
7) memisahkan tahun dan halaman kalau pengacuan halaman dilakukan pada
sistem Nama-Tahun dalam teks;
8) memisahkan bab dan ayat dalam kitab suci (Surat Al Baqarah: 183).
2. Tanda Tanya (?)
Tanda tanya dipakai pada akhir pertanyaan langsung, atau untuk
menunjukkan keragu-raguan dalam suatu pernyataan (Karena ketiadaan pem-
banding, untuk sementara bambu ini sebaiknya dideterminasi sebagai
Gigantochloa? atroviolacea).
3. Tanda Seru (!)
Tanda seru hampir tidak pernah dipakai dalam kalimat tulisan ilmiah.
Adakalanya tanda itu dipergunakan untuk menunjukkan bahwa suatu bahan bukti
penelitian dilihat langsung oleh penulisnya:
Scleroderma dictyospora dipertelakan oleh Patouillard (1898) berdasarkan
spesimen Massart 445 (P!) yang dikumpulkan di Jawa tahun 1882.
4. Tanda Hubung (-)
Tanda hubung dipakai untuk:
1) menyambung bagian-bagian tanggal, misal: 17-8-1945;
2) merangkaikan se- dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf
kapital (se-Indonesia), ke- dengan angka (abad ke-21), angka dengan -
an (tahun '90an);
3) memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan (ber-evolusi
vs. berevolusi, dua-puluh lima-ribuan, 20 x 5.000 vs. dua-puluh-lima-
ribuan, 1 x 25.000);
4) memenggal kata tertentu (lihat Pemenggalan Kata).

44
5. Tanda Pisah (-, --, ---)
Bergantung kepada panjangnya terdapat tiga macam tanda pisah, yaitu tanda
pisah em (panjangnya sama dengan lebar huruf kapital M atau setinggi jenis
huruf. yang digunakan, diketik dengan dua tanda hubung --), tanda pisah en
(panjangnya setengah tanda pisah em, diketik dengan tanda pisah -), dan tanda
pisah 3-em.
1) Tanda pisah em dipakai untuk membatasi penyisipan kalimat yang tidak
terkait erat dengan kalimat induknya;
2) Tanda pisah en dipergunakan untuk menunjukkan kisaran (halaman 15-
25, panjangnya 24,5-31,0 mm). Jangan menggunakan tanda pisah en
bersama perkataan dari dan antara, atau bersama tanda kurang (dari
halaman 15 sampai 25, bukan dari halaman 15-25, antara tahun 1945
dan 1950, bukan antara tahun 1945-1950, -4 sampai -60C, bukan -4 - -
60C).
3) Beberapa majalah menggunakan tanda pisah 3-em dalam daftar pustaka
alih-alih mengulang nama pengarang lama (entry) sebelumnya. Jangan
memakai tanda 3-em dalam naskah, tetapi ulangi penyebutan nama-
nama pengarang.
6. Tanda Kurung ((...))
1) Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan yang
bukan bagian integral pokok pembicaraan. Misalnya, ‖Pengujian
selanjutnya terhadap salah satu noda nomor 4) memberikan dugaan
senyawa yang terkandung dalam media kultur jamur z adalah senyawa
seskuiterpen”.
2) Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya dalam
kalimat dapat dihilangkan. Misalnya, ‖Fraksi etil asetat dapat
dipisahkan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT)
preparatif”.
3) Tanda kurung (atau tanda kurung tutup) dipakai untuk menunjukkan
penomoran yang dimasukkan dalam kalimat. Misalnya:
Ketiga langkah itu ialah (a) mitosis, (b) meiosis, (c) penggandaan inti.

45
Kebutuhan dasar manusia ialah 1) pangan, 2) sandang, 3) papan, 4)
kesehatan, dan 5) pendidikan.
7. Tanda Kurung Siku ([...])
Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit:
1) huruf atau kata yang ditambahkan pada kalimat kutipan;
2) keterangan dalam kalimat yang sudah bertanda kurung.
8. Tanda Petik (”...”)
Tanda petik dipakai untuk mengapit:
1) petikan atau kutipan pembicaraan langsung;
2) judul karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat;
3) istilah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus.
9. Tanda Petik Tunggal (’...’)
Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit:
1) petikan yang tersusun dalam petikan lain;
2) makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing (survive
’sintas’, survival ’sintasan’).
10. Tanda Elipsis (...)
Tanda elipisis dipakai untuk menunjukkan bahwa ada bagian yang
dihilangkan pada suatu kutipan (”Pola distribusi pemasaran ... berdasarkan
pengamatan cuplikan”).
11. Tanda Garis Miring (/)
Tanda garis miring dipakai untuk mengganti:
1) tanda bagian atau menunjukkan bilangan pecahan (1/2 = 0,5);
2) kata tiap (125 ton/ha).
Tanda garis miring tidak dipakai untuk menunjukkan pilihan (atau).
12. Tanda Ampersan (&)
Tanda ampersan berfungsi sebagai pengganti tanda dan bila bentuk lebih
singkat diinginkan. Tanda ini dianjurkan dipakai dalam pengacuan pustaka sebab
membantu mengurangi pengulangan. Bentuk penulisan "... (Panshin & de
Zeew1969)." tampak jauh lebih rapi bila dibandingkan dengan bentuk "...
(Panshin dan de Zeew 1969)... ".

46
Selain itu, penggunaan tanda ampersan juga memecahkan keraguan dalam
penyusunan nama-nama pengarang tulisan berbahasa asing, terutama kalau diacu
dalam penyusunan daftar pustaka untuk tulisan berbahasa Indonesia. Secara
bertaat asas kata dan harus digunakan untuk menggabung nama-nama pengarang
tanpa memperhatikan bahasa karangan yang diacu.
2.5. Penggunaan Istilah, Angka dan Lambang
Konsep dasar dalam mencipta istilah baru dalam pelbagai bidang ialah
Pedoman Umum Pembentukan Istilah, sesuai dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 0389/U/1988. Dalam pedoman tersebut
dianjurkan untuk menggunakan kosakata bahasa Indonesia terlebih dulu. Apabila
dalam bahasa Indonesia tidak ada kosakata yang tepat atau mendekati maka
barulah berturut-turut dicari padanannya dari kosakata bahasa serumpun, dan
terakhir dari kosakata bahasa asing (terutama bahasa Inggris). Segi tata bahasa
telah tersedia padanannya, sehingga pengguna tinggal mencarinya dalam
Glosarium Biologi, Fisika, Kimia, dan Matematika (termasuk Statistika).
Keempat glossarium itu diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa pada tahun 1993, sedangkan untuk bidang yang lain dapat dicari
padanannya pada masing-masing bidang ilmu. Senarai istilah ilmu dasar tersebut
cukup memadai untuk digunakan.
Penulisan angka dan bilangan dalam tulisan ilmiah biasanya menggunakan
satuan dasar yang dianut secara universal yaitu Satuan Sistem Internasional (biasa
disingkat SI dari Systeme International ’d’Unites). Berikut ini akan diterangkan
secara ringkas pedoman umum dalam penulisan angka dan bilangan yang diambil
dari beberapa literatur termasuk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Angka adalah suatu simbol yang dapat dikombinasikan untuk menyatakan
suatu bilangan. Ada 10 angka Arab, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, dan 9. Untuk
keperluan penomoran halaman bagian depan tulisan biasanya digunakan angka
romawi dengan huruf kecil. Bilangan adalah pernyataan dalam bentuk numerik
atau kata-kata dari suatu penghitungan, pencacahan, atau pengukuran; sebagai
contoh: 547,2; 6 juta; 1.54 x 106. Bilangan ini dapat dibentuk dalam angka
Romawi dengan mengkombinasikan 7 huruf yang nilai-nilainya diperlihatkan
dalam tabel berikut:

47
Tabel 1. Angka Romawi dan Angka Arab
Angka Romawi Angka Arab
I, i 1
V, v 5
X, x 10
L, l 50
C, c 100
D, d 500
M, m 1000
Catatan:
Suatu tanda garis di atas huruf menyatakan bahwa nilai bilangan itu dikalikan
1000, misalnya V = 5000.
Dalam tulisan ilmiah, penulisan dengan angka-angka Arab lebih disukai
dibandingkan dengan uraian kata bilamana bilangan itu dikaitkan dengan sesuatu
yang dapat dihitung atau diukur, contohnya: 5 buku, 10 rumah. Contoh lain yang
juga mengikuti aturan ini adalah: 3 hipotesis, 7 sampel, 328 asam amino dan lain-
lain.
Secara umum, angka dalam laras bahasa teks digunakan untuk:
1. menyatakan lambang bilangan atau nomor (10 untuk bilangan sepuluh)
2. menyatakan jumlah yang mendahului satuan ukuran (24 g, 19 m, 13 jam,
100 ha, 27oC)
3. menyatakan nilai uang, tanggal, waktu, halaman, penunjukan urutan yang
diawali ke-, persentase (Rp25,50; 1 Januari; pukul 07.15; halaman 150;
abad ke-21; 25%)
4. menunjukkan jumlah yang berkaitan dengan manipulasi matematika
seperti rasio (perbandingan) dan faktor perkalian, (12 dikalikan 5, suatu
faktor 2, 5:1, 1000 kali (atau ‖1000 x‖)
5. menunjukkan satuan pada bilangan kisaran (5-10 cm, 35-500C)
6. menomori karangan dan bagiannya (Bab IV, Pasal 5, halaman 13)
Penggunaan angka untuk menyatakan termasuk atau sampai dengan dapat
menggunakan tanda pisah en atau kata ’sampai’. Penggunaan tanda pisah en biasa
digunakan dalam tabel; sementara penggunaan kata ‖sampai’ dipakai dalam teks;
misalnya ‖laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1997 sampai 1999”.

48
Tanda desimal dalam bilangan dapat dinyatakan dengan koma atau titik.
Jika dalam tulisan menggunakan titik sebagai tanda desimal, sebaiknya memberi
catatan penjelas pada awal ditemukan tanda desimal. Catatan penjelas dapat
dilakukan dengan memberikan catatan kaki pada bilangan ini. Penulisan bilangan
dengan tanda desimal mengikuti aturan sebagai berikut:
1. Bilangan dengan angka panjang dapat ditulis dalam tiga-tiga kelompok
dan antara kelompok diberi tanda pisah desimal, misalnya:
2,3 untuk dua koma tiga
2.500.000 untuk dua juta lima ratus ribu.
Dalam penulisan teks yang mempunyai deret angka dengan desimal maka
antara angka desimal dipisahkan dengan titik koma, misalnya:
Luas hutan mangrove di Indonesia pada tahun 1982, 1993, 2002
berturut-turut ialah 4,25; 3,70; dan 3,25 juta hektar.
2. Jangan mengawali bilangan desimal dengan tanda koma, tetapi selalu
diawali dengan angka, misalnya:
0,35 atau 0.35 bukan ,35 atau .35
0.2753 x 104
bukan ,2753 x 104
3. Dalam daftar atau tabel yang bilangannya hanya terdiri atas angka (tanpa
desima) dapat dituliskan dalam kelompok-kelompok tiga angka yang
dipisahkan oleh spasi tanpa menggunakan tanda koma ataupun tanda titik,
misalnya 1 234 567 (bukan 1.234.567)
Aturan penulisan lambang bilangan dilakukan sebagai berikut:
1. Bilangan utuh
12 dua belas
25 dua puluh lima
250 dua ratus lima puluh
2. Bilangan pecahan
¼ seperempat 10% sepuluh persen
2/3 dua pertiga 3,6 tiga enam persepuluh
3. Penulisan kata bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut:
bab IV abad XXI
bab ke-4 abad ke-21

49
bab keempat abad kedua puluh satu
4. Penulisan bilangan yang mendapat akhiran –an mengikuti cara sebagai
berikut:
Tahun 30-an
5. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis
dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara
berurutan, seperti dalam rincian dan pemaparan, misalnya:
Pak Umar membersihkan taman itu sampai tiga kali sehari.
Diantara 50 orang mahasiswa yang ada di kelas ini, 20 orang karyawan
swasta, 28 orang pegawai negeri dan 2 orang wirausaha.
6. Lambang bilangan di awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu
susunan diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan
satu atau dua kata, tidak terdapat lagi di awal kalimat, misalnya:
Dua puluh rumah terendam banjir saat hujan kemarin
Bukan: 20 rumah terendam banjir saat hujan kemarin (sebaiknya
ditulis ‖Saat hujan kemarin 20 rumah terendam banjir‖
7. Angka yang menunjukkan bilangan bulat yang besar dapat dieja sebagaian
supaya lebih mudah dibaca, misalnya:
Keluarga korban kebanjiran tersebut telah menerima bantuan 2 juta
rupiah.
8. kalau bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus
tepat, misalnya:
Bersama ini kami kirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas
juta rupiah)
Bersama ini kami kirimkan uang 15.000.000,00 (lima belas juta)
rupiah.
2.6. Pemilihan Kata (diksi)
Seorang terpelajar diharapkan menguasai kosakata umum serta
seperangkat peristilahan bidang ilmu yang ditekuninya. Ia pun diharuskan
mengetahui tata perlambangan, akronim dan singkatan, beserta satuan pengukuran
yang lazim dipakai oleh bidang spesialisasinya. Pemilihan kata yang tepat dalam
kalimat akan memberikan pengertian yang jelas dan nalar bahasa yang benar.

50
Pemakaian kosakata dan peristilahan terpilih juga menentukan corak dan mutu
keteknisan tulisannya, karena makin tinggi jumlah kosakata yang dipakai makin
ilmiah sifat tulisannya.
Kata memiliki kekuatan (word power) yang setara dengan warna dalam
lukisan, nada dalam musik, atau bentuk dalam ukiran, salah, kurang tepat,
tidak benar, atau keliru semuanya memiliki makna yang serupa tetapi pengaruh
pemakaiannya amat berlainan. Dalam setiap bahasa memang terdapat seperangkat
sinonim, yaitu kata-kata yang tidak selamanya sama artinya. Ongkos, sewa,
upah, belanja, biaya, anggaran adalah kata-kata yang bersinonim yang
masing-masing mempunyai bidang makna dan pengertian khusus.
Perbaikan khasanah kosakata dapat dicapai dengan banyak membaca, lalu
mempelajari kata-kata yang sulit dengan pertolongan kamus. Jika kita melihat
kata hutan dalam kamus umum, akan terungkap beberapa macam makna yang
dimiliki-nya, baik sebagai kata benda (hutan jati), kata kerja (menghutankan),
kata sifat (ayam hutan, menghutan), dan bentuk-bentuk turunannya
(kehutanan, perhutanan, penghutanan) lengkap dengan artinya. Jika
penyimakan diteruskan ke kamus istilah, akan terdapat bentukan perhutanian
yang dipadankan dengan istilah Inggris agroforestry. Jadi dengan bantuan
kamus umum dan kamus istilah, akan dapat diketahui jenis, medan makna,
variasi, cara pemakaian, dan penjabaran kata untuk kemudian dipahami dan
dikuasai dengan baik. Permainan teka-teki silang dapat dijadikan pengisi waktu
yang berpotensi menambah kekayaan kosakata seseorang.
Pemekaran jumlah kosakata yang dikuasai seseorang akan memungkin-
kannya mengatasi salah satu kendala utama dalam menulis, yaitu menemukan kata
yang tepat. Kalau dijumpai kesulitan (masalah, persoalan, problem,
keraguan,dilema…) cantumkan pilihan seperti dilakukan di sini. Dalam
memperbaikai naskah nanti akan dapat dipilih (dicari, diambil, diseleksi,
diganti, dipertimbangkan …) kata yang paling sesuai. Oleh karena itu,
kemampuan mengukur kekuatan (ketelitian memilih dan kepiawaian
menyusun) kata akan menghasilkan tulisan ilmiah yang hidup dan dapat
menjadi sebuah adikarya.

51
Frase baku dalam kalimat bahasa Indonesia masih belum diperhatikan
oleh kebanyakan penulis, seperti frase:
Salah Seharusnya
terdiri dari terdiri atas
tergantung pada bergantung pada
bertujuan untuk x bertujuan x
membicarakan tentang x berbicara tentang atau membicarakan x
antara x dengan y antara x dan y
dalam menyusun dalam penyusunan
dibanding dibandingkan dengan
Penulis juga sebaiknya menghindari kata yang berlebihan seperti
(se)rangkaian, (se)kumpulan, kelompok yang diikuti oleh kata ulang. Tuliskan
saja misalnya ”(se)rangkaian molekul” bukan ”(se)rangkaian molekul-
molekul”; para responden, beberapa sampel, banyak unsur.
Kata yang bersinonim sebaiknya dihindari pemakaiannya secara
bersamaan:
Salah Seharusnya
disebabkan karena disebabkan oleh
agar supaya agar atau supaya
dalam rangka untuk dalam rangka atau untuk…
setelah…kemudian… setelah…
contoh jenis batuan misalnya… contoh batuan ialah…atau
misalnya
baik…ataupun… baik…maupun…
Seseorang bebas menentukan kata yang tepat untuk mengungkapkan
gagasannya dalam tulisan. Akan tetapi, dalam penggunaan istilah bidang ilmu
penulis harus taat pada kata atau istilah yang sudah dibakukan; istilah tidak
dapat diragamkan.
2.7. Penataan Kalimat
Kalimat Indonesia mempunyai ciri pendek, pasif, dan sederhana.
Susunannya dapat diputarbalikkan dangan mempermutasikan tempat kata-
katanya tanpa mengubah artinya, kecuali untuk memberikan penekanan
maknanya. Misalnya,‖penelitian terhadap X dilakukan oleh Corbes pada tahun

52
1928‖ atau ‖Corbes pada tahun 1928 melakukan penelitian terhadap X‖. Kalimat
yang baik harus memiliki kesatuan pikiran yang bulat dan utuh, serta terhadap
koherensi diantara unsur-unsurnya. Contoh kalimat yang memiliki struktur yang
berbeda dan dapat berdiri sendiri, namun memiliki persamaan makna ialah
‖Peningkatan bea impor barang elektronik yang memberatkan industri
perakitan komputer merupakan penyebab kenaikan harga penjualan komputer‖
dan ‖Penyebab kenaikan harga penjualan komputer adalah peningkatan bea
impor barang elektronik yang memberatkan industri perakitan komputer‖ atau
‖Kenaikan harga penjualan komputer disebabkan oleh peningkatan bea impor
barang elektronik yang memberatkan industri perakitan komputer‖. Oleh karena
itu, kalimat yang sempurna akan mampu berdiri sendiri terlepas dari konteksnya,
serta mudah dipahami maksudnya. Kalimat dalam suatu makalah manajemen
industri yang berbunyi ‖Terhadap kapasitas produksi yang lebih besar dan atau
sumber bahan baku berbeda caranya‖ bukanlah merupakan contoh untuk ditiru.
Keefektifan kalimat akan meningkat jika kita mampu memilih kata dan
meragam kan konstruksinya. Menempatkan kata pada posisi yang tepat akan
menghidupkan kalimat. Kalimat adakalanya dapat lebih diefektifkan bila
beberapa kalimat pendek digabung dan bagian-bagain yang setara disejajarkan
atau dipertentangkan, atau disusun dengan menekankan hubungan sebab-akibat.
Akan tetapi, penggabungannya harus dilakukan secara berhati-hati agar tidak
berlebihan sehingga kalimat menjadi berkepanjangan, rancu, dan maksudnya
tidak langsung dapat ditangkap. Untuk itu tanda baca yang tersedia hendaklah
dimanfaatkan sepenuhnya. Ini akan memberi peluang untuk membuat kalimat-
kalimat suatu tulisan itu segar dan menarik serta berseni sehingga enak dibaca.
Harus diakui bahwa penyajian tulisan ilmiah tidaklah dimaksudkan untuk
menghasilkan karya sastra. Akan tetapi ini bukanlah alasan untuk menbuat suatu
tulisan kering dan membosankan untuk dibaca.
Kekurangcermatan memahami fungsi kata dalam kalimat sering
menghasilkan kalimat yang rancu. Kesalahan lain yang sering dijumpai ialah
penalaran yang tidak logis, seperti dijumpai akibat kemubasiran penggunan kata
dari dalam contoh kalimat ‖Dari Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa......‖
yang seharusnya dikatakan ‖Gambar 1 menunjukkan bahwa.....‖. Kesalahan

53
serupa sering terjadi pada penyimpulan ‖Berdasarkan hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa....‖ yang cukup baik jika disajikan menjadi ‖Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa.....‖.
Adapun kalimat bahasa Indonesia yang baku mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut;
2.8. Fungsi tata bahasa selalu dipakai taat asas dan tegas maka subjek dan
predikat selalu ada (‖para peneliti pergi ke lapangan percobaan‖ bukan
‖para peneliti kelapangan percobaan‖).
2.9. Pemakaian ejaan dan istilah resmi secara bertaat asas;
2.10. Bersih dari unsur dialek daerah, variasi bahasa indonesia, dan bahasa
asing yang belum dianggap sebagai unsur bahasa Indonesia, kecuali untuk
istilah bidang ilmu tertentu.
Dalam penulisan ilmiah, gaya penulisan yang beremosi perlu dihindari.
Oleh karena itu ungkapan seperti ‖kesimpulan amat berarti‖, ‖temuan
mahapenting ‖, atau ‖hasil sangat menarik‖ harus dihindari. Jadi kalau akan
menyatakan bahwa yang akan diceritakan itu menarik , buatlah hal itu betul-
betul menarik dengan cara menyampaikan hasil pemikiran secara rasional.
2.8. Pengefektifan Paragraf
Pengamatan terhadap mahasiswa Indonesia masih sulit untuk membuat
paragraf secara efektif. Kegagalan ini terjadi karena tidak dipahaminya fungsi
paragraf sebagai pemersatu kalimat yang koheren serta berhubungan secara
sebab-akibat yang disertai dengan alasan yang makul dan objektif untuk
menjelaskan suatu kesatuan gagasan atau tema. Olah karena itu, sering dijumpai
tulisan yang sukar dipahami sebab tidak jelas pemisahan bagian-bagianya untuk
menghasilkan argumen yang menyakinkan. Kesulitan seseorang melalui
penulisan juga disebabkan oleh tidak diketahuinya adanya fungsi paragraf
pembuka, paragraf penghubung, serta paragraf penutup.
Paragraf dapat didefinisikan sebagai satu unit informasi yang memiliki
pikiran utama sebagai dasarnya dan disatukan oleh ide pengontrol. Kalimat-
kalimat dalam suatu paragraf harus saling berkait secara utuh untuk membentuk
satu kesatuan pikiran. Suatu paragraf yang baik ialah paragraf yang mampu

54
mengarahkan dan membawa pembaca memahami dengan baik kesatuan
informasi yang diberikan penulis melalui ide-ide pengontrolnya.
2.8.1. Ide Pengontrol
Ide pengontrol atau pengendali ide merupakan pusat ide yang bentuk
dalam satu kalimat. Dengan demikian, ide pengontrol merupakan ringkasan dari
semua informasi yang terkandung dari paragrafd tersebut. Jadi ide, pengontrol
akan membatasi ide-ide yang dapat masuk kedalam suatu paragraf. Ide
pengontrol yang disusun dalam suatu kalimat disebut sebagai kalimat topik.
2.8.2. Kalimat Topik
Kalimat topik merupakan sebuah kalimat yang mengandung pikiran
utama dan ide yang akan dibentuk dan diterangkan oleh kalimat-kalimat yang
ada dalam paragraf. Kalimat topik dapat diletakkan di awal, di tengah, atau di
akhir paragraf. Akan tetapi, kalimat topik pada umumnya diletakkan di awal
karena penulis akan lebih mudah menentukan informasi apa saja yang akan atau
tidak akan dimasukkan ke dalam paragraf. Di samping itu, pembaca juga akan
segera mengetahui apa yang diceritakan oleh paragraf tersebut dengan mudah
dan cepat. Jadi, kalimat topik merupakan suatu kalimat yang lengkap, bersifat
umum dan menyatakan topik masalah yang akan dibahas serta ide pengontrol
yang akan menentukan kalimat-kalimat berikutnya untuk membentuk suatu
paragraf. Kalimat-kalimat yang mendukung kalimat topik dalam suatu paragraf
sesuai dengan ide pengontrol disebut kalimat pendukung.
Sebagai pedoman dalam pengecekan (baik tidaknya paragraf) beberapa
pertanyaan berikut diantaranya dapat diajukan:
1) Apakah topiknya jelas?
2) Apakah paragraf sudah mempunyai kalimat topik? Kalau tidak apakah
dapat dinyatakan secara implisit (tersirat)?
3) Apakah paragraf sudah jelas dan ide pengontrolnya terfokus?
4) Apakah paragraf sudah utuh, semua kalimat pendukung mendukung ide
pengontrol?
5) Apakah paragraf sudah koheren, kalimat disusun secara logis dan
mengalir secara lancar?
Apabila semua pertanyaan tersebut dijawab YA, maka dapat dikatakan bahwa
paragraf tersebut sudah baik.

BAB III
PENYAJIAN ILUSTRASI
Ilustrasi merupakan suatu bentuk penyajian informasi dalam bentuk tabel,
grafik, diagram alir, foto atau gambar dan sejenisnya. Dengan ilustrasi, informasi
dapat disajikan lebih efektif dan penggunaan kalimat yang terlalu panjang dapat
dihindari sehingga pembaca dapat memahami tulisan lebih mudah. Prinsip yang
harus diingat dalam pembuatan ilustrasi ialah bahwa ilustrasi harus menarik dan
secara otomatis dapat menjelaskan tentang apa yang ingin disampaikan.
Didalam tulisan karya ilmiah, semua ilustrasi dalam bentuk tabel
dinyatakan sebagai tabel, sedangkan ilustrasi dalam bentuk grafik, diagram alir,
foto dan gambar dinyatakan sebagai gambar.
3.1. Jenis ilustrasi
Sebagaimana yang telah dijelaskan diawal, terdapat beberapa bentuk
ilustrasi yang lazim digunakan dalam karya ilmiah. Penjelasan penggunaan
ilustrasi dijelaskan di bawah ini.
3.1.1. Tabel
Ilustrasi dalam bentuk tabel digunakan untuk memberikan informasi hasil
penelitian atau lainnya dalam bentuk tabel. Hal ini biasanya digunakan bila
peubah yang diperhatikan cukup banyak dan tidak sama satuannya. Tabel dapat
diubah ke dalam bentuk grafik dengan mengkonversi satuan peubah-peubah
menjadi satuan yang sama (dalam satuan persen) atau gabungan dua sumbu Y
yang berbeda satuannya. Tabel yang terlalu rumit atau terlalu banyak data yang
disajikan perlu dihindari kerena hal ini akan mengganggu jalannya pembahasan.
Oleh sebab itu, data yang akan disajikan di dalam tabel ialah yang memang
diperlukan dan dapat menguatkan serta memperjelas pambahasan di dalam teks.
Data lainnya dapat dimasukkan ke dalam lampiran. Ada kalanya data mentah
dilampirkan untuk keperluan peneliti yang akan datang. Selanjutnya dalam suatu
tabel semua data yang dicamtumkan harus jelas satuannya dan ditempatkan pada
kepala tabel.

3.1.2. Gambar
Pemilihan penyajian data hasil penelitian dalam bentuk grafik, diagram
alir, foto, atau gambar dalam karya ilmiah perlu dipertimbangkan dengan
memperhatikan relevensinya dengan topik penelitian yang dilakukan.
3.1.3. Grafik
Penampilan grafik dapat disajikan dalam berbagai bentuk, misalnya:
(1) Histogram yang biasanya digunakan untuk membandingkan hasil atau nilai.
Histogram dapat digunakan dalam bentuk vertikal atau horizontal.
(2) Diagram lingkar (pie chart)
Digunakan apabila penulis tidak mementingkan besaran komponen secara
tepat tetapi lebih mementingkan hubungan berbagai komponen dan komposisinya.
(3) Grafik garis
Digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara dua peubah yaitu
peubah takbebas di sumbu Y dan peubah bebas di sumbu X. Dengan peubah
takbebas berubah sesuai dengan perubahan peubah bebas.
(4) Grafik lain
Seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan peralatan lainnya,
banyak jenis ilustrasi yang dikembangkan dalam bentuk tiga dimensi, misalnya
peta kontur.
3.1.4. Diagram Alir
Ilustrasi ini digunakan untuk menunjukkan tahapan kegiatan atau
hubungan sebab akibat suatu aktivitas atau keterkaitan antara satu kegiatan atau
proses dengan proses lainnya (analisis sistem).
3.1.5. Foto atau Gambar
Ilustrasi ini digunakan untuk memberikan gambaran yang konkret kepada
pembaca tentang proses yang berlangsung, keadaan di lapangan dan lain
sebagainya. Penggunaan foto atau gambar hasil cetak printer lebih baik daripada
penggunaan hasil cetak yang dilekatkan di karya ilmiah. Hal yang perlu
diperhatikan dalam penggunaan ilustrasi ini ialah penggunaan foto yang terlalu

37
banyak yang dapat membuat tulisan Anda seperti album harus dihindari. Jika
dalam karya tulis ilmiah memerlukan foto atau gambar
Dalam pembuatan foto hal yang perlu diperhatikan ialah penyajian
informasi skala karena foto yang ditampilkan umumnya sudah tidak mempunyai
skala yang sama dengan obyek aslinya. Caranya ialah dengan meletakkan
penggaris ataupun petunjuk lainnya yang ukurannya sudah umum diketahui di
dekat contoh atau obyek foto.
3.2. Penulisan Judul Tabel dan Gambar
Dalam penulisan judul tabel dan gambar, beberapa hal yang harus
diperhatikan ialah bahwa judul tabel atau gambar:
a. merupakan kalimat pernyataan tentang tabel dan gambar secara ringkas
b. memberikan informasi singkat yang dapat dipahami oleh pembaca tanpa harus
membaca tubuh tulisan
c. menyatakan kunci-kunci informasi
d. merupakan kalimat yang berdiri sendiri dan dapat menerangkan arti tabel atau
gambar.
e. Bila diperlukan, pada tabel atau gambar, nyatakan penulisan satuan atau
keterangan yang diperlukan.
Judul tabel seperti: ―Keteguhan tekan beton yang diuji‖ sangat tidak memadai.
Judul yang lebih baik misalnya:
―Tabel x. Keteguhan tekan (g/cm2) beton dengan penambahan zat
pengeras dan kontrol‖
Judul tabel diletakkan di atas tabel dengan diawali oleh huruf kapital tanpa
diakhiri dengan tanda titik. Sedangkan judul gambar --yang dapat berupa satu
kalimat atau lebih--diletakkan di bawah gambar diawali oleh huruf kapital serta
diakhiri dengan tanda titik.
3.3. Penulisan Catatan Kaki dan Keterangan Tabel
Tabel adakalanya memerlukan catatan kaki dan/atau keterangan. Catatan
kaki dan keterangan pada tabel dapat berupa: (a) informasi tentang keterbatasan
yang ada pada data, (b) data bersifat nyata secara stastistik, dan (c) hasil penelitian
orang lain. Petunjuk catatan kaki biasanya berupa simbol non numerik seperti *,†,

38
dan lain-lain yang ditulis superskrip atau tidak superskrip. Catatan kakinya ditulis
dibawah tabel dengan font 10 (lihat Tabel 4).
Petunjuk catatan kaki diletakkan pada bagian tabel yang memerlukan
informasi tambahan tersebut. Petunjuk catatan kaki ini yang diletakkan pada judul
tabel atau diletakkan pada salah satu kolom. Catatan kaki yang diletakkan pada
judul tabel berlaku untuk seluruh data, sedangkan bagian tertentu, catatan kaki
tersebut hanya berlaku untuk bagian yang bersangkutan saja. Misalnya, petunjuk
catatan kaki tersebut hanya berlaku data pada kolom atau baris dimaksud.
Keterangan tabel biasanya berupa keterangan tambahan, misalnya untuk
menjelaskan singkatan yang digunakan dalam tabel (lihat Tabel 4). Catatan kaki
untuk menyatakan sumber data dilakukan dengan cara menuliskan nama penulis
dan tahun, seperti halnya dalam penulisan acuan pustaka. Kalau data disajikan
sudah dimodifikasi atau sudah diolah maka digunakan kata ―menurut‖ atau
―diolah dari‖ atau ―diadaptasi dari‖ dan kemudian diikuti dengan nama penulis
dan tahun penulis.
3.4. Penulisan Keterangan Simbol Gambar
Setiap gambar biasanya mempunyai simbol. Setiap simbol harus diberi
keterangan. Ukuran simbol dan keterangan harus proporsional dengan ukuran
gambar dan dapat dibaca dengan jelas. Simbol dan keterangannya dapat
diletakkan dimana saja pada gambar, misalnya sudut kiri gambar atau pada sudut
lainnya atau bisa juga pada judul gambar.
3.5. Perujukan Tabel dan Gambar
Setiap tabel atau gambar yang ada dalam tulisan ilmiah harus dirujuk atau
muncul dalam teks. Kata rujukan tabel atau gambar ditulis sebelum tabel atau
gambar dan berada pada halaman yang sama. Apabila tidak memungkinkan, maka
tabel atau gambar dapat muncul pada halaman berikutnya.
Selanjutnya perujukan yang tidak disertai dengan keterangan perlu
dihindari. Misalnya :
―Hasilnya dapat diilihat pada Tabel 3‖
atau
―Hasilnya disajikan pada Tabel 3‖

39
Pernyataan yang lebih baik ialah:
―Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih untuk
menyimpan uang di bank dengan tujuan keamanan dan kemudahan
transaksi‖.
Perujukan yang tertalu sering terhadap lampiran juga perlu dihindari, karena hal
tersebut akan mengganggu konsentrasi dan kenyamanan pembaca.
3.6. Interpretasi Tabel dan Gambar
Yang perlu diingat dalam pembuatan ilustrasi ialah walaupun terhadap
tabel atau gambar, Anda tetap membuat teks yang sejalan. Aturannya yaitu
ilustrasi harus dapat dibaca tanpa teks dan sebaliknya. Ini tidak berarti bahwa teks
harus mengemukakan data yang sama dengan tabel atau gambar. Misalnya jika
dalam tabel tertera indeks pembangunan manusia di kota Batam menempati
urutan ke lima terbaik secara nasional‖ maka dalam teks dapat ditulis:
―….indeks pembangunan manusia di Batam termasuk tinggi dibandingkan
kota lain di Indonesia‖
Teks memberi peluang untuk menguatkan aspek penting dari tabel yang terutama
akan dibahas. Jarang sekali semua angka yang tertera dalam tabel sama
pentingnya. Jadi dalam teks Anda dapat menekankan bagian yang penting saja.
Sebagian pedoman umum, interpretasi tabel atau gambar dapat dilakukan
melalui tiga tahapan. Pola berikut ini dapat diterapkan walaupun ada pengecualian
untuk beberapa kasus.
SPESIFIK
Deskripsi tabel atau gambar
Interpretasi (pembandingan dan kontras)
Kesimpulan
UMUM
Dari pola di atas terlihat bahwa struktur bergerak dari yang spesifik ke
lebih yang umum. Jadi, dalam menginterpretasi tabel atau gambar, hal pertama

40
yang harus dilihat ialah deskripsi dari tabel serta angka dan pola dari gambar.
Kedua, dilakukan interpretasi terhadap data yang tersaji dengan cara memahami
pola atau kecenderungan yang terlihat pada tabel atau gambar. Ketiga, dilakukan
penarikan kesimpulan. Hal yang harus dihindari dalam penyajian ialah
menyatakan sesuatu yang sudah jelas dapat dibaca pada tabel atau gambar karena
hal tersebut akan merupakan pengulangan.
3.7. Contoh Tabel dan Gambar
3.7.1. Tabel
Dalam pembuatan tabel, hal yang harus dilakukan ialah menulis satuan
yang jelas dari data yang ditampilkan. Kadangkala satuan dari judul kepala tabel
dan satuan dari data tidak dapat dibedakan dengan jelas. Sebagai contoh yang
salah ialah Tabel 2.
Tabel 2. Pengaruh pemberian jenis unsur hara terhadap tinggi tanaman jagung
(mm/hari)
Perlakuan Umur tanam (dalam hari)
5 15 25
Unsur hara A 50 730 1250
Unsur hara B 70 625 1100
Unsur hara C 40 750 1550
Unsur hara D 60 520 1150
Judul Tabel 2 membingungkan pembaca karena penulis menceritakan
tinggi tanaman jagung sedangkan satuan dalam kurung menyatakan laju
pertumbuhan. Selain itu, judul kepala tabel juga menyatakan satuan hari, sehingga
pembaca mungkin menduga bahwa satuan tersebut merupakan satuan dari data
yang ditampilkan dalam tabel. Contoh tabel yang lebih baik dapat dilihat pada
Tabel 3.
Tabel 3. Pengaruh pemberian jenis unsur hara dan umur tanam terhadap tinggi
tanaman jagung (mm)
Hari ke Jenis unsur hara
A B C D
5 50 70 40 60

41
15 730 625 750 520
25 1250 1100 1550 1150
Cara penulisan satuan dalam tabel terdiri atas beberapa bentuk, bergantung
pada banyaknya peubah (variabel) dan cara peletakan peubah tersebut pada tabel
(lihat Tabel 4 dan 5). Selain itu pembuatan garis pemisah antara data baik menurut
baris ataupun kolom juga bergantung kepada banyaknya peubah dan data yang
akan ditampilkan. Perlu diperhatikan untuk mengupayakan agar data yang
ditampilkan mudah dimengerti tanpa harus melihat teks, dan jangan terlalu banyak
membuat garis pemisah.
Tabel 4. Luas bidang dasar sel kayu jati Purwakarta dan Cepu pada perbedaan
lebar lingkaran tumbuh (LT)
Lebar LT
(µm)
Parenkim Inisial
(mm2)
Jari-jari
(mm2)
Pori (mm2) Fiber (mm
2)
Jati P u r w a k a r t a
<500 0,64
0,18
0,65 0,84
501-1000 0,83 0,44
1,02 3,45
1001-3000 1,19 1,14 2,37 9,98
>3000 0,64 2,90 5,37 27,5
Jati C e p u
<500 0,65
0,18 0,59 0,82
501-1000 0,92 0,43 1,11 3,22
1001-3000 1,37 1,12 2,81 9,42
>3000 0,74 2,79 5,73 26,2
† Banyaknya contoh uji masing-masing lokasi pertumbuhan Cepu dan Purwakarta sebesar
16 pohon
Tabel 5. Rata-rata daya serap air (%) papan semen partikel kayu kelapa sawit
pada beberapa panjang partikel dan perbandingan komposisi partikel
dengan semen
Panjang partikel
(A)
Komposisi partikel dengan semen (B)
B1 (1 : 3,00) B2 (1 : 3,25) B3 (1 : 3,50)
A1 (3 cm) 28,92 a
A
26,55 b
A
23,40 c
A
A2 (4 cm) 27,23 a
A
24,31 b
B
20,65 c
B
A3 (5 cm) 23,14 a
B
20,25 b
C
16,91 c
C
A4 (6 cm) 21,48 a
B
19,43 b
C
19,14 b
B

42
Catatan : Angka-angka sebaris yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dan angka-angka selajur
yang diikuti oleh huruf besar yang sama berbeda tidak nyata menurut uji DNMRT pada taraf nyata
5%
3.7.2. Gambar
Gambar dapat disajikan dalam bentuk histogram (Gambar 1 dan 2),
diagram lingkar (Gambar 3), atau grafik garis (Gambar 4). Sama seperti pada
tabel, satuan dan judul gambar dan satuan dari data pada gambar harus dapat
dibedakan dengan jelas.
a. Histogram dua sumbu dan dua dimensi
0
10
20
30
40
50
60
70
19 22 25 28 31
Umur (Tahun)
Ber
at B
adan
(kg)
L
P
Gambar 1. Rata-rata berat badan mahasiswa UNRIKA berdasarkan umur dan jenis
kelamin (L=laki-laki dan P = perempuan).
b. Histogram tiga sumbu dan tiga dimensi
1020
3040
C
P0
10
20
30
Gambar 2. Pertumbuhan diamater jati Cepu (C) dan Purwakarta (P) pada
beberapa umur tanam.
Umur (tahun)
Dia
met
er (
mm
)

43
c. Diagram lingkar
10%
20%
30%
30%
10%
Perkantoran
Jalur Hijau
Perumahan
Industri
Pertanian
Gambar 3. Persentase penggunaan lahan di pulau Batam tahun 1996 (BPS 2000)
d. Grafik garis
0
20
40
60
80
100
120
150 250 350 450 550 650
Tinggi (cm)
Dia
met
er (
cm)
Meranti
Keruing
Gambar 4. Hubungan tinggi pohon (cm) dan diameter pohon (cm) pada jenis
kayu meranti dan keruing.

BAB IV
KEPUSTAKAAN
Dalam penyusunan karya ilmiah, pengarang sebaiknya mencari sumber
acuan dari pustaka primer, seperti jurnal, monograf, dan tulisan asli lainnya.
Sebaliknya, buku ajar berupa diktat kuliah, textbook, dan penuntun praktikum
hendaknya dihindari karena tujuan utama buku tersebut sebagai bahan pengajaran
yang berisi ulasan pengetahuan secara umum.
Penulisan yang cermat tentang kepustakaan akan mempermudah pembaca
dalam menelusuri kembali masalah yang dicarinya dari sumber pustaka tersebut.
Pengacuan yang umum dilakukan mengikuti sistem Nama-Tahun (sistem
Harvard) dan sistem Nama-Nomor (sistem Vancouver). Untuk keseragaman karya
tulis di Universitas Riau Kepulauan, sistem pengacuan kepustakaan yang
digunakan adalah sistem Nama-Tahun.
4.1. Pengacuan Pustaka
Sistem pengacuan pustaka harus digunakan secara konsisten dalam tubuh
tulisan, tabel, dan gambar dalam suatu karya ilmiah; kemudian disenaraikan pada
akhir tulisan atau dalam ―Daftar Pustaka‖. Dalam sistem Nama-Tahun nama
pengarang yang diacu dalam tubuh tulisan hanyalah nama keluarga atau nama
akhir pengarang yang diikuti tahun publikasinya. Pengacuan pustaka
menggunakan sistem ini lebih disukai oleh pengarang karena lebih mudah
menambah dan mengurangi acuan dalam tubuh tulisan maupun daftar pustaka jika
dibandingkan dengan sistem Nama-Nomor. Sistem ini juga dengan cepat dapat
memberikan informasi kemutakhiran pustaka yang diacu melalui tahun publikasi.
Namun demikian sistem Nama-Tahun memiliki kerugian pada pengacuan ganda,
terutama apabila sumber acuan yang digunakan cukup panjang.
Cara pengutipan pustaka dapat menggunakan pengutipan langsung
maupun pengutipan secara tidak langsung. Pengutipan langsung merupakan
bentuk pengutipan dari pustaka (buku, jurnal, laporan penelitian, dan sejenisnya)
yang penyajian kalimatnya persis sama dengan sumber yang dikutip. Sedangkan
pengutipan tidak langsung, kalimat yang dikutip dapat menggunakan kalimat yang
tidak persis sama tetapi maksud dan tujuannya tidak bertentangan dengan sumber
yang dikutip.

45
4.1.1. Pengutipan Langsung
Pengutipan langsung menggunakan ketentuan sebagai berikut:
1) Jika kutipan tidak lebih dari tiga baris, kutipan diketik dengan huruf
miring (italic) dengan jarak 2 (dua) spasi dan diberi tanda petik. Sebagai
contoh:
Hartono (1998) mengemukakan bahwa, ―Investasi adalah penundaan
konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisisen selama
periode waktu tertentu”.
2) Jika lebih dari tiga baris, kutipan diketik dengan huruf italic pada garis
baru dengan jarak 1 (satu) spasi tanpa tanda petik. Sebagai contoh:
Berikut ini adalah pendapat Fabozzi dan Mondigliani (1992) tentang risiko
portofolio:
One way to evaluate the risk of a portfolio is by estimating the extentto
which future portfolio return. This is measured by variance of
theportfolio‘s return and is called the total portfolio risk. Totalpoprtfolio
can be decomposed into two types of risk: systematic riskand unsystematic
risk.
4.1.2. Pengutipan Tidak Langsung
Pengutipan tidak langsung dalam karya tulis ilmiah disesuaikan dengan
paragraf kalimat yang digunakan dengan mencantumkan sumber pustaka.
Penulisannya dapat digunakan pada awal, tengah atau akhir paragraf tanpa
menggunakan huruf italic.
Bergantung pada susunan kalimat, cara penulisan dalam tubuh tulisan
dapat mengikuti contoh berikut:
Purwanto (1991) mengemukakan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan
proses kognitif yang mendapat dukungan dari fungsi ranah psikomotorik.
Atau
Belajar pada hakikatnya merupakan proses kognitif yang mendapat dukungan
dari fungsi ranah psikomotorik (Purwanto 1991).

46
4.2. Penulisan Sumber Pustaka
Jika sumber pustaka menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun publikasi
maka penulisan tahun saja pada umumnya sudah cukup untuk acuan.
Pengacuan pustaka yang ditulis oleh dua pengarang seperti ―Budi dan
Anto‖ pada tahun 2001 diacu sebagai Budi dan Anto (2001), atau (Budi & Anto
2001). Jangan menggunakan tanda ampersan (&) untuk menggantikan kata ―dan‖
dalam suatu kalimat tubuh tulisan, kecuali pada sumber acuan dalam tanda
kurung.
Untuk nama pengarang yang terdiri atas tiga orang atau lebih maka hanya
nama keluarga atau nama akhir pengarang pertama saja yang ditulis dan diikuti
dengan kata ―et al” (singkatan dari et alii). Dalam pedoman ini kat ―et al” tetap
dipertahankan dan dicetak dengan huruf italic, tidak diubah menjadi ―dkk‖
(singkatan dari dan kawan-kawan). Sebagai contoh, artikel yang ditulis oleh Umar
B, Agus G, dan Hadi S yang dipublikasikan pada tahun 1995 diacu sebagai: Umar
et al. (1995) atau (Umar et al. 1995).
Sebagai pedoman umum dalam pengacuan pustaka dapat mengikuti kaidah
sebagai berikut:
1) Pengarang yang sama menulis pada tahun yang berbeda;
Jika terdapat lebih dari satu pustaka, yang ditulis oleh pengarang yang
sama pada tahun yang berbeda, pengacuan ditulis sesuai dengan urutan
tahun terbit, misalnya Purwanto (2001, 2002) atau (Purwanto 2000, 2001).
Tahun terbit yang satu dan yang berikutnya dipisahkan oleh koma dan
spasi.
2) Pengarang yang sama menulis pada tahun yang sama;
Pengacuan terhadap dua atau beberapa pustaka yang ditulis oleh
pengarang yang sama pada tahun yang sama dilakukan dengan menambah
huruf ―a‖ untuk yang pertama, ―b‖ untuk yang kedua, dan seterusnya
setelah tahun. Penambahan huruf ―a’, ―b‖, dan seterusnya didasarkan pada
urutan waktu publikasi, sebagai contoh: Gunawan (1999a, 1999b).
3) Pengarang yang mempunyai nama keluarga yang sama menulis pada tahun
yang sama;

47
Jika pengarang mempunyai nama keluarga yang sama untuk suatu
publikasi yang terbit pada tahun yang sama maka tahun publikasi diberi
tanda ―a’, ―b‖ dan seterusnya sehingga perbedaan sumber pustaka tersebut
menjadi jelas. Sebagai contoh: (Purwanto 1999a, 1999b) untuk sumber
pustaka yang ditulis oleh Purwanto A pada tahun 1999 dan Purwanto I
pada tahun yang sama.
4) Lembaga sebagai pengarang;
Nama lembaga yang diacu sebagai pengarang sebaiknya ditulis dengan
bentuk singkatannya. Misalnya untuk mengacu tulisan yang diterbitkan
pada tahun 1999 oleh Biro Pusat Statistik ditulis BPS (2000) atau (BPS
2000). Dalam Daftar Pustaka ditulis sebagai [BPS], tetapi dalam tubuh
tulisan tanda kurung siku ini tidak ditampilkan.
5) Tulisan tanpa pengarang;
Sebaiknya acuan yang tidak memiliki nama pengarang di dalam tubuh
tulisan dan Daftar Pustaka dituliskan dengan nama institusi yang
menerbitkannya. Acuan tanpa pengarang dapat juga dituliskan sebagai
Anonim (1999) atau (Anonim 1999) dan dalam Daftar Pustaka ditulis
[Anonim], namun sebaiknya penggunaan kata anonim ini dihindari.
6) Pengacuan ganda
Bila dua artikel atau lebih dengan pengarang berbeda yang diacu
sekaligus, maka penulisannya dalam tubuh tulisan didasarkan pada urutan
tahun publikasinya, misalnya: (Anto et al. 2001; Salim 2002); Siswardjono
1999; Kasim 2000; Hamdan 2001a. Pengacuan ganda menggunakan tanda
titik koma dan spasi untuk memisahkan pengarang yang berbeda.
7) Pustaka sekunder
Untuk artikel yang tidak dibaca langsung dari sumbernya (pustaka
sekunder) maka digunakan kata ―cit.‖. Cara penulisannya dengan
menyebutkan nama pengarang dan tahun publikasi dari pustaka sekunder
dan primer, contoh: Coster 1927, cit. Martawijaya et al. 1995). Dalam
Daftar Pustaka yang dituliskan adalah sumber pustaka sekunder.
Pengacuan pustaka sekunder dalam karya ilmiah sebaiknya dihindari.

48
8) Komunikasi pribadi
Dalam keadaan tertentu yang membutuhkan pendapat dari narasumber
yang sudah dikenal kepakarannya maka penulisan acuan dalam tubuh
tulisan dilakukan dengan menulis nama keluarga yang diikuti inisialnya,
waktu dan tipe informasi yang semuanya dituliskan dalam tanda kurung,
contoh: Dahlan A 8 April 2007, komunikasi pribadi). Pengacuan
komunikasi pribadi tidak dianjurkan dalam karya ilmiah dan tidak perlu
dituliskan dalam Daftar Pustaka.
4.3. Penyusunan Daftar Pustaka
Pada bagian akhir sebuah karya tulis ilmiah terdapat Daftar Pustaka yang
dibuat berdasarkan susunan sistem pengacuan pustaka tertentu. Penyusunan daftar
pustaka yang digunakan di Universitas Riau Kepulauan menggunakan sistem
Nama-Tahun yang disusun menurut abjad nama pengarang.
Isi daftar pustaka hanya mengacu kepada pustaka yang terdapat di dalam
tubuh tulisan. Dengan demikian sumber acuan yang terdapat di dalam Daftar
Pustaka harus ada di dalam tubuh tulisan.
Kepustakaan harus dinyatakan dengan lengkap agar memudahkan
pembaca menelusuri kembali. Informasi tentang kepustakaan ini sebaiknya
dicocokkan kembali dengan pustaka aslinya. Penulisan kepustakaan yang salah
atau tidak lengkap tidak akan banyak gunanya dan secara tidak langsung akan
menunjukkan mutu pengarangnya.
Dalam penulisan nama pengarang yang digunakan ialah nama keluarga
atau nama akhir pengarang yang diikuti inisial nama pertama dan nama tengah
tanpa tanda baca. Nama keluarga dan nama inisial ini dipisahkan satu spasi. Nama
pengarang yang lebih dari lima orang cukup diwakili oleh pengarang yang
pertama saja diikuti kata et al, seperti halnya pengacuan dalam tubuh tulisan untuk
pengarang yang jumlahnya lebih dari dua orang.
Urutan pustaka dalam daftar pustaka didasarkan pada urutan abjad dan
huruf awal nama keluarga pengarang pertama. Selanjutnya huruf abjad dan nama
pengarang pertama tersebut didasarkan pada urutan abjad huruf per huruf ke
kanan dan dilanjutkan dengan nama inisialnya; diikuti nama keluarga pengarang
berikutnya yang urutan abjadnya didasarkan pada nama keluarga nama keluarga

49
baru inisialnya. Bila dua atau lebih pustaka memiliki susunan nama keluarga
pengarang yang persis sama maka urutannya didasarkan pada tahun penerbitan.
Berikut ini penjelasan urutan komponen-komponen yang diperlukan untuk
menulis Daftar Pustaka secara terperinci, mulai dari nama pengarang, tahun
terbit, judul, nama jurnal, volume, nomor dan halaman untuk sumber acuan dan
jurnal. Demikian juga untuk sumber pustaka dari buku dan lainnya.
4.3.1. Jurnal
a. Nama Pengarang.
Nama pengarang pada artikel dalam suatu karya ilmiah serta cara
penulisan kepustakaannya bervariasi bergantung pada nama pengarang. Nama
pengarang ditulis dengan nama keluarga yang diikuti inisial nama pertama dan
nama tengah tanpa tanda baca. Nama keluarga dan inisial dipisahkan dengan satu
spasi (Tabel 6); nama pengarang berikutnya dipisahkan satu sama lain dengan
tanda koma dan spasi. Tanda titik diberikan untuk membedakan keterangan nama
pengarang dan tahun terbit.
Perlu ditegaskan bahwa nama pengarang yang diacu harus sama dengan
yang tertera pada artikel aslinya. Jika pengarang bernama Andi M pada satu
artikel dan Andy M pada artikel yang lain, janganlah mengubah nama untuk
ketaatasasan.
Untuk menyederhanakan pengacuan menggunakan sistem Nama-Tahun
dalam tubuh tulisan, nama lembaga yang berperan sebagai pengarang perlu
didahului singkatannya yang ditempatkan dalam tanda kurung siku. Penulisan
lembaga ini dilakukan secara hierarki dan dimulai dari yang tertinggi. Yang
dimaksud yang tertinggi disini ialah lembaga yang paling relevan dan
bertanggung jawab terhadap isi dari suatu dokumen. Dengan demikian, bentuk
singkatan hanya diperlukan untuk lembaga tadi. Misalnya untuk susunan ―Otorita
Batam‖ cukup ditulis [OB] Otorita Batam.
b. Tahun Terbit.
Tanda titik diberikan setelah tahun publikasi atau tahun publikasi yang
diikuti huruf a, b, dan seterusnya.

50
Tahun yang dicantumkan dalam daftar pustaka ialah tahun terlaksananya
penerbitan. Untuk jenis karya ilmiah skripsi, tesis dan disertasi, yang ditulis ialah
tahun seseorang memperoleh surat keterangan lulus, sedangkan untuk paten ialah
tahun diterbitkannya hak paten.
c. Judul Artikel
Judul yang dikutip harus sama dengan judul pada publikasi asli. Hanya
huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital di dalam artikel yang
digunakan untuk kasus tertentu, misal singkatan yang telah baku (seperti USDA,
WHO, UNICEF, DNA) dan nama takson organisme mengikuti tata nama ilmiah.
Huruf kapital juga digunakan untuk awal kata yang di dalam kalimat selalu ditulis
dalam huruf kapital, misalnya dalam bahasa Jerman semua kata benda
menggunakan huruf kapital.
Pada judul artikel yang disertai dengan sub judul maka penulisan judul
utama diakhiri dengan tanda titik dan diikuti dengan anak judul yang merupakan
kalimat baru sehingga penulisan sub judulnya diawali dengan kata awal pertama
pada sub judul dimulai dengan huruf kecil, tidak menggambarkan huruf kapital.
d. Nama Jurnal
Nama jurnal yang hanya terdiri dari satu kata tidak disingkat (misal
Academia, Hayati, Science, Nature) namun umumnya nama jurnal ditulis dalam
bentuk singkatannya di dalam daftar pustaka. Singkatan nama jurnal dapat dirujuk
dari World List of Periodicals.
Berikut ini ditampilkan beberapa pedoman singkatan nama jurnal ilmiah:
1) Pada umumnya kata kata disingkat dengan menghilangkan sekurang-
kurangnya dua huruf terakhir dari kata tersebut. Perkecualian menyingkat
dengan menghilangkan huruf-huruf yang di tengah terjidi pada Ctry
(Country), Jpn (Japan), Natl (National), dan Ztg (Zeitung). Singkatan
sebaiknya diakhiri dengan huruf mati. Biol. dan bukan Bio. untuk biologi
2) Kata-kata dengan akar kata yang sama disingkat menjadi bentuk
singkatan yang sama, misalnya Chem untuk Chemistry, Chemical, dan
Chemists; tetapi, jika terdapat perbedaan huruf pada pokok kata maka
singkatannya menjadi berbeda, contonya:Bull (Bulletin), Bul (Buletin),
Bol (Boletin), Boll (bollettino).

51
3) Kata yang mempunyai akar kata yang sama disingkat berbeda:Trans,
Transplant, Transp, dan Transl masing-masing untuk Transactions,
Transplantations, Transport, dan Translation.
4) Kata dengan akar kata yang biasa disingkat (seperti Nat untuk Nature),
jika merupakan unsur pertama suatu kata majemuk ditulis lengkap. Nat
singkatan untuk Nature, tetapi Naturforsch tidak disingkat.
5) Kata yang terdiri dari atas lima atau enam huruf biasanya disingkat,
kecuali kata yang umum seperti Blood, Child, Drugs, Enzyme, dan Plant.
6) Singkatan pada judul jurnal tidak menggunakan kata depan, sambung,
penunjuk, dan tanda-tanda baca kecuali bila menggunakan bagian dari
suatu istilah. Misal In Vitro Cellular and Development Biology disingkat
menjadi In Vitro Cell and Dev Biol.
Tabel 6. Variasi penulisan nama pengarang dari sumber pustaka
Variasi Nama Pengarang
Berdasarkan Negara
Nama Pengarang Penulisan Kepustakaan
(1) (2) (3)
Nama keluarga pengarang
yang mempunyai satu nama
keluarga
Constantine J. Alexopoulus Alexopoulus CJ
Nama Indonesia dengan
sistem nama keluarga
Amarullah Nasution Nasution A
Nama Indonesia yang diikuti
nama suami
Rini Andika Andika A
Nama Indonesia terdiri atas
satu kata
Soekarno Soekarno
Nama Indonesia terdiri dari
dua suku kata atau lebih
Agustina Cahyaningrum
Nadia Khaira Ardi
Budi Utomo Andika Mulia
Cahyaningrum A
Ardi NK
Mulia BUA
Nama pangkat kekeluargaan
atau nama keluarga majemuk
John Doc Sr.
H. Vanden-Brink
Doc JSr
Vanden-Brink H
Nama Prancis dengan kata de,
de la, des, du, le, la, les
A de Bary
V du Bary
J le Beau
Bary A de
Bary V du
Beau J le
Nama Belanda: kata-kata
seperti de, van, van den, van
der, serta von pada nama
Jerman, do pada nama Brazil
ditempatkan pada unsur
terakhir dari nama
Kees de Vries
A van der Haar
Vries K de
Haar A van der
Nama Hungaria selalu dimulai
dengan nama keluarga yang
diikuti dengan nama kecilnya
Farkas Karoly
Bartok Bela
Farkas K
Bartok B
Kata pada nama Arab seperti
Abdul, Abdoul, Abu, Aboul,
dan Ibn dinilai sebagai bagian
nama keluarga
Hassan Fahmy Khalil
Ali Abdel Aziz
Ali Ibn Saud
Khalil HF
Abdel-Aziz A
Ibn-Saud A

52
(1) (2) (3)
Nama India, kata Sen dan Das
digabung dengan nama
keluarga
BC Sen Gupta
AD Das Gupta
Sen Gupta BC
Das Gupta AD
Nama Vietnam dan Thailand Nguyen Cao Ky Nguyen-cao-ky
Nama Cina selali diawali
dengan nama keluarga; jika
nama dihubungkan dengan
tanda (-) nama tersebut
merupakan nama inisialnya
Go Ban Hong
Kin-Ying To
Go BH
To KY
Nama Burna biasanya hanya
satu kata, tetapi dapat pula
didahului bentuk penghormatan
U
U Thant Thant U
Huruf pertama dari setip kata yang disingkat ditulis dengan hurif kapital.
Seluruh tanda tanda baca yang ada pada nama jurnal dhilangkan; bentuk singkatan
diikuti satu spasi dan bukan dengan tanda titik.
e. Nomor volume dan halaman
Nomor volume atau jilid dari jurnal ditulis dengan huruf Arab setelah
nama jurnal yang dipisahkan dengan sepasi dan langsung tanpa sepasi diikuti
tanda titik dua dan nomor halaman lengkap (114-120 untuk menyatakan halaman
114 sampai dengan 120, bukan 114-20) yang diakhiri tanda titik.
Misalnya:J Biol chem 193:114-20
Nomor volume yang tidak menggunakan angka Arab, misalnya volume
XXVI diubah menjadi 26.
Nomor terbitan biasanya terdapat pada jurnal dan ditulis dengan angka
Arab. Angka tersebut diletekkan dalam tanda kurung setelah nomor volume yang
semuanya ditulis langsung tanpa spasi. Misal 27(6):8-16. Nomor terbitan tidak
perlu dicantumkan bila penomoran halaman berkesinambungan dalam satu
volume. Misalnya Hayati volume 7 nomor 3 halaman 91-95 ditulis Hayati 7:91-
95, bukan Hayati 7(3):91-95.
f. Suplemen.
Suplemen artikel tambahan yang terdapat pada suatu terbitan dari suatu
volume ditunjukkan oleh suatu singkatan Suppl (Supplement).

53
4.3.2. Buku
Penyusunan daftar pustaka dari sumber buku ditulis dengan urutan: nama
pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat penerbitan, dan nama penerbit. Pada
dasarnya keterangan untuk menulis nama pengarang dan tahun penerbitan sama
seperti jurnal, sedangkan untuk keterangan lain adalah sebagai berikut:
a. Judul Buku
Judul buku ditulis dengan setiap kata diawali dengan huruf kapital kecuali
kata depan dan kata sambung.
b. Edisi
Keterangan tentang edisi ditempatkan setelah judul dan ditulis misalnya
―Ed ke-3‖. Walaupun dalam buku aslinya tercantum misalnya ―Third Edition‖,
pada penulisan daftar pustaka pasangan kata itu perlu diubah menjadi ―Ed ke-3‖.
Tulisan ―New revised edition‖ yang dijumpai pada sumber pustaka, pada
penulisan daftar pustaka disingkat menjadi ―Ed rev‖. Edisi pertama yang tidak
diikuti dengan edisi berikutnya tidak perlu diidentifikasi sebagai ―Ed ke-1‖, tetapi
kemudian diketahui terbit edisi baru maka buku edisi pertama itu perlu dinyatakan
dengan ―Ed ke-1‖.
c. Tempat Penerbitan
Tempat penerbitan dapat dijumpai pada halaman judul buku yang diacu.
Bila tercantum beberapa tempat penerbitan, nama tempat yang pertama kali ditulis
digunakan untuk menyusun daftar pustaka. Bilamana kota tempat buku diterbitkan
tidak tercantum dalam buku, tetapi dapat dikenali dari penerbitnya maka nama
kota itu ditulis dalam tanda kurung siku. Bila tempat penerbitan sama sekali tidak
diketahui maka dituliskan tempat tidak diketahui dalam tanda kurung siku:
[tempat tidak diketahui].
d. Nama Penerbit
Penerbit adalah perusahaan komersial atau lembaga pemerintah/swasta
yang melaksanakan penerbitan dari suatu buku. Nama penerbit biasanya
tercantum dalam pada halaman judul. Untuk lembaga yang bertindak sebagai
penerbit, pengarangnya diawali dengan dengan jenjang yang paling tinggi, yang
paling relevan dan bertanggung jawab terhadap isi buku tersebut kemudian diikuti
jenjang di bawahnya.

54
e. Halaman
Nomor halaman dicantumkan atau tidak bergantung pada pengacuan yang
diterapkan. Bila nomor halam ditampil dan pengacuan dilakukan terhadap
keseluruhan buku, tuliskan misalnya ―525 hlm‖ untuk buku yang pada halaman
terakhirnya tertulis angka 525. Bila pengacuan dilakukan terhadap bagian tertentu
dari buku misalnya dari halaman 23 sampai 35, maka penulisannya ialah ―23-35‖;
atau untuk pengacuan terbatas pada halaman 54 ditulis ―hlm 54‖.
f. Prosiding
Penyusunan daftar pustaka untuk prosiding ditulis dengan menampilkan
nama pertemuan. Nama pertemuan ditulis dengan setiap awal katanya
menggunakan huruf kapital kecuali kata sambung. Nama pertemuan dipisahkan
dari tempat dan waktu pelaksaan pertemuan masing-masing dengan tanda titik
koma dan spasi. Waktu pelaksanaan pertemuan dinyatakan dalam urutan ―tanggal
bulan dan tuhun‖; nama bulan disingkat hingga terisi tiga huruf yang pertama dan
tanpa tanda titik.
4.4. Contoh Penulisan Sumber Acuan
Contoh umum penulisan sumber acuan untuk sistem Nama-Tahun dalam
daftar pustaka disajikan di bawah ini dengan didahului teladan penyusunannya.
4.4.1. Teladan Umum untuk Jurnal
Nama pengarang, Tahun terbit, Judul artikel. Nama jurnal. Nomor volume (nomor
terbitan):halaman
a. Satu pengarang
Bhat KM. 2000. Timber quality of teak from managed tropical plantations with
special reference to Indian plantations. Bois et foréts des tropiques 263:6-15.
b. Dua pengarang
Bhat KM, Priya PB. 2004. Influence of provenance variation on wood properties
of teak from the western Ghat region in India. J Iawa 25:273-282.
c. Lebih dari dua pengarang
Briand CH, Poslunszny U, Larson DW. 1993. Influence of age and growth rate
on radial anatomy of annual rings of Thuja occidentalis L. Int J Plant Sci
154:406-411.
d. Lebih dari lima pengarang
Soille P et al. 2001. Tree ring area meassurements using morphological image
analysis. Can J For Res 31:1074-1083.

55
e. Setiap terbitan dimulai dengan halaman baru
Eliel EL. 1976. Stereochemistry since LeBel and van’t Hoff.: bagian II. Chemistry
49(3):8-13
f. Organisasi sebagai pengarang
[SSCCCP] Scandinavian Society for Clinical Chemistry and Clinical Physiology,
Committee on Enzyme. 1976. Recommended method for the determination of
γ-glutamyltransferase in blood. Scand J Clin Lab Invert 36:119-125.
g. Artikel tanpa pengarang
[Anonim]. 1972. Silviculture and Management of Teak. Int J Plant Sci
154(3):406-411.
h. Artikel khusus
Artikel khusus dapat berupa editorial, komunikasi singkat, catatan penelitian, ulas
balik, ulasan.
Sosromarsono S. Tungau merah jeruk, Panonychus citri (McGregor): pendatang
baru di Indonesia [komunikasi singkat]. Bul HPT 9:38-39
i. Hasil penelitian yang akan dipublikasikan tetapi belum terbit
Keterangan tentang hasil penelitian yang belum terbit, namun sudah disetujui akan
terbit dalam suatu jurnal dituliskan tanpa menyebut tahun, judul artikel, dan
nomor volume.
Nasution AP. Academia, siap terbit.
4.4.2. Teladan Umum untuk Buku
Nama pengarang [atau editor]. Tahun terbit. Judul buku. Tempat terbit: Nama
penerbit
a. Buku dengan pengarang
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
b. Buku dengan editor
Ridout B, Wedd K, editor. 2001. Timber Decay in Buidings: The consevation
approach to treatment. Ed ke-2. London: Spon Press
c. Buku dengan lembaga atau organisasi sebagai pengarang
[Depdikbud] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed ke-2. Jakarta:
Balai Pustaka.
d. Buku dengan volume yang berjudul
Wijayakusuma MH, Dalimartha S, Wirian AS. 1998. Tanaman Berkhasiat Obat di
Indonesia. Volume ke-4. Jakarta: Pustaka Kartini.

56
4.4.3. Teladan Umum untuk Prosiding
Nama pengarang. Tahun terbit. Judul artikel. Di dalam: Nama editor. Judul
publikasi atau nama pertemuan ilmiah atau keduanya; Tempat pertemuan,
Tanggal pertemuan. Tempat terbit: nama penerbit. Halaman artikel.
Bacilieri R, Alloysius D, Lapongan J. 2000. Growth performance of teak. Di
dalam: Chan HH, Matsumoto K, editor. Proceeding of the Seminar on High
Value Timber Species for Plantation Establishment-Teak and Mahoganies;
Sabah, 1 – 2 Dec 1998. Japan: JIRCAS Report 16: 27-34.
4.4.4. Teladan Umum untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi
Nama pengarang. Tahun terbit. Judul [jenis publikasi]. Tempat institusi: nama
institusi yang menganugerahkan gelar.
Maiyatun. 2007. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Metode
Penerapan Pembelajaran Diskusi Kelompok pada Kompetensi Dasar Dalil
Pythagoras di Kelas VII SMP Negeri I Belakang Padang Batam TA
2006/2007 [skripsi]. Batam: Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan.
Dalimunthe P. 2005. Pertumbuhan Diameter Kayu Jati: Pengaruh iklim dan
topografi terhadap sifat fisis dan mekanis [tesis]. Bogor: Institut Pertanian
Bogor, Sekolah Pascasarjana.
4.4.5. Bibliografi
Nama penghimpun. Tahun terbit. Judul [jenis publikasi]. Tempat terbit: nama
penerbit
Gluckstein FP, Glock MH, Hill JG, penghimpun. 1990. Bovine somatotropin
[bibliografi]. Bethesda: National Library of Medicine, Reference Section.
4.4.6. Paten
Nama penemu paten, kata ―penemu‖; lembaga pemegang paten. Tanggal publikasi
(permintaan paten) [tanggal bulan tahun]. Nama barang atau proses yang
dipatenkan. Nomor paten.
Muchtadi TR, penemu; Institut Pertanian Bogor. 9 Mar 1993. Suatu proses untuk
mencegah penurunan beta karoten pada minyak sawit. ID 0 002 569.
4.4.7. Surat Kabar
Nama pengarang. Tanggal bulan tahun terbit. Judul. Nama surat kabar: Nomor
halaman (nomor kolom).
JPNN. 26 November 2007. Mendesak, regulasi sumber daya air. Batam Pos:18
(Kolom 1-2)

57
4.4.8. Publikasi Elektronik
Isi artikel dalam format elektronik dapat berubah isinya sehinggal tanggal akses
diperlukan dan penulisannya dalam tanda kurung siku. Penulisan tanggal ini
dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang terjadi dengan tanggal publikasinya.
[LTRR] Laboratory of Tree-Ring Research. 2001. Dendrochronology.
Laboratory of Tree-Ring Research. USA. The University of Arizona.
http://www.ltrr.arizona.edu/dendrochronology.html [18 Peb 2004].