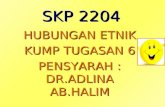Etnonesia #mei
-
Upload
ahmad-zaenudin -
Category
Documents
-
view
236 -
download
6
description
Transcript of Etnonesia #mei

ETNONESIAETNONESIA.ORG - MEI 2014
MENCARI TEMPAT BERMAIN BOLA
• China, Cina, Tionghoa• Nasionalisme di Long Nawang• Orang Utan, Orang Terbuang

2 ETNONESIA
ETNONESIALocal Exploration
ETNONESIA merupakan organisasi non-profit yang bertujuan memberikan pe-mahaman perihal kajian-kajian dalam ranah sosial, kultural, geografi, antariksa, dan sains. Menerbitkan Majalah ETNONESIA setiap bulannya sebagai jurnal re-smi bagi seluruh kalangan masyarakat. Eksplorasi lokal merupakan misi kami, dalam upaya memahami setiap jengkal kehidupan bermasyarakat setiap umat manusia dulu, kini, dan nanti.
China, Cina, Tionghoa hal...6Oleh Dian Putri
Mencari Tempat Bermain Bola hal..11 Oleh Subagja Sutisna
Bom dan Sakit Jantung hal..20 Oleh Wieldan Akbar
Sajian Utama
EDITOR IN CHIEF: AHMAD ZAENUDIN, EDITOR: MOHAMAD BHISMA, PHO-TO EDITOR: HANY AFRILIYAN, EDITORIAL STAFF: AGUS KUSUMAATMA-JA, SABRIYANI ANGGITA, DESIGNER: TIARA PITALOKA.
ETNONESIA

DARI EDITOR
3 ETNONESIA
Memahami Kenangan
Kenangan, itulah yang hendak disajikan dalam edisi ini. Terutama tentu saja kenangan kita saat masa kanak-kanak. Bermain bola adalah salah satu kenangan yang pernah kita ala-mi. Meskipun saya cukup yakin, banyak diantara Anda yang ku-rang suka dengan sepakbola. Tumpukan sandal atau sepatu, tidak mengenakan alas kaki, hujan-hujanan, bola plastik dan kontroversi seputar gol atau tidak adalah serpihan-serpihan ke-nangan dari masa lalu, masa dimana kita asik bermain bola. Edisi ini mencoba menghadirkan itu semua, dalam bingkai ironi dan narasi kekinian, kita coba memasuki masa itu. Dan tentu saja, itu hanyalah kenangan. Seperti yang tersaji dalam sajian utama edisi ini, urbanisasi menjadi jembatan pemisah kenan-gan-kenangan tersebut yang semakin hilang. Selain itu, dalam edisi ini mencoba melihat sejarah bagaimana China, Cina, dan Tionghoa dihadirkan dalam seja-rah kolektif masyarakat Indonesia. semangat menghargai per-bedaan paling tidak merupakan misi kami. Setelah di edisi lalu menyajikan perihal Orang Arab di Indonesia. Semoga saja, da-lam edisi-edisi yang kami hadirkan, ada pemahaman yang bisa dipelajari. Semoga.
Ahmad ZaenudinEditor in Chief

JELAJAH
4 ETNONESIA
Apakah film Saving Pri-vate Ryan merupakan ki-sah nyata? Benar bahwa film tersebut diilhami dari kisah nyata dan lantas didramatisasi selayaknya sebuah film. Sergeant Frederick “Fritz” Niland adalah anggota pasukan 101st Airborne’s 501st Parachute Infantry Regiment, ia diterjunkan di wilayah Normandi pada tanggal 6 Juni, 1944. Ketiga saudara Niland tersebar dalam berbagai unit di kemiliteran. Technical Sergeant Robert Niland merupakan prajurit di the 82nd Airborne Division. Sementara Lieutenant Preston merupa-kan prajurit the 4th Infantry Division, dan Techni-cal Sergeant Edward Niland merupakan seorang pilot di the Army Air Force. Tiara Pitaloka.
Surat kabar lokal memberitakan tentang kisah keluarga Niland.

JELAJAH
5 ETNONESIA
Orang Utan, Orang Terbuang mungkin itu-lah frase yang tepat meng-gambarkan keadaan Orang Utan. di tahun-tahun awal eksplorasi ke wilayah peda-laman Kalimantan, banyak Orang Utan yang dijad-ikan spesimen untuk diba-wa ke Eropa sebagai upaya para naturalis mempela-jari keanekaragaman fau-na dunia. Sayang, mereka menggunakan cara-cara tak berpri”kehewanan”. Natu-ralis Italia bernama Odoar-do Beccali pergi ke pedala-man Kalimantan. Disana ia “membedah” Orang Utan. Penduduk lokal percaya, roh Orang Utan menggang-gu kehidupan mereka pasca Beccali melakukan risetn-ya tersebut. Kini? Tentu tak jauh berbeda. pembukaan hutan sebagai areal kelapa sawit merupakan salah satu penyebab merosotnya pop-ulasi Orang Utan. Mohamad Bhisma.
Populasi Orang Utan kini hanya 1/7 jumlah Orang Utan 75 tahun lampau. Deforestasi yang kian menggila merupakan penyebab utama Orang Utan “menyusut”.

ETNIS CINA merupakan salah satu etnis yang mengisi
keberagaman Indonesia. Belakangan, panggilan untuk merujuk
orang Cina “dikembalikan” pada penyebutan asalnya yakni
Tionghoa. Dan untuk menyebut Republik Rakyat Cina sebagai negara
leluhur etnis Cina di Indonesia diubah kembali menjadi Republik
Rakyat Tiongkok. Merunut sejarah, penggunaan Cina sebagai sebuah
etnis dan Republik Rakyat Cina sebagai rujukan penyebutan negara
yang berlaku di Indonesia merupakan buah dari tragedi Gerakan 30
September ---beberapa menyebutnya Gestok, Gerakan 1 Oktober---
Leo Suryadinata dalam sebuah tulisannya Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme, menyatakan
bahwa penggunaan istilah Cina memiliki nada merendahkan dan
menghina. Hal ini dikarenakan bahwa Cina adalah negara penganut
komunisme yang menyebabkan tragedi G30S terjadi. Dan sebagai
rangkaian “pemusnahaan” unsur-unsur komunis, segala hal yang
berhubungan dengannya juga akan dihancurkan, termasuk Tionghoa
atau Tiongkok yang selalu dianggap melekat dengan komunis.
China, Cina, Tionghoa
Memahami Tionghoa dari ungkapan “sekali Cina tetap Cina”
Teks olehDian Putri
6 ETNONESIA

Timbulnya rasa tidak senang bukan hanya dimiliki mereka
para keturunan Tionghoa di Indonesia, melainkan juga
menyebar di negeri leluhur Orang Tionghoa pula. Dan
perihal rujukan istilah Cina atau China sebagai rujukan bagi
Orang Tionghoa, bersumber dari nama sebuah dinasti
bernama Ch’in. Ialah sebuah dinasti pertama yang berhasil
menyatukan dinasti-dinasti kecil menjadi sebuah kesatuan
yang sekarang kita ketahui sebagai Republik Rakyat
Tiongkok. Penyatuan dinasti-dinasti tersebut, dalam kajian
sejarawan terjadi sekitar tahun 200 M.
Sedihnya, diskirminasi Orang Tionghoa yang ada di
Indonesia bukan hanya berawal dari peristiwa G30S
tersebut. Dalam sebuah buku berjudul Batavia, Masyarakat Kolonial Abad XVII karya Hendrik Neimeijer menyatakan
dalam penelusuran sejarahnya bahwa diskriminasi yang
dialami Orang Tionghoa di Indonesia atau Hindia Belanda
telah berlangsung sejak lama. Memusatkan tempat tinggal
Orang Tionghoa di Batavia kala itu merupakan salah
satu strategi bagaimana pemerintah Hindia Belanda
“mengamankan” mereka. Dalam karya tersebut, Hendrik
memaparkan bahwa salah satu sifat yang kurang disukai
Belanda dalam kurun waktu itu adalah bahwa Orang
Tionghoa terkenal dengan kelicikannya. Sebisa mungkin,
pemerintah Hindia Belanda akan menjauhi segala perkara
dengan Orang Tionghoa.
Dalam tulisan lainnya, Odoardo Baccari dalam Wondering in Great Forests of Borneo mengisahkan perjalanannya ke
padalaman Kalimantan. Disana, ia yang seorang saintis
Italia tersebut menerangkan bahwa masyarakat Dayak
yang ditemuinya kala itu memiliki banyak koleksi kepala-
kepala orang Tionghoa. Dan dalam kenyakinannya, 7 ETNONESIA

Odoardo percaya bahwa orang-oang Tionghoa yang hidup
disekitaran masyarakat Dayak dibenci oleh para pribumi
tersebut. Bahkan dalam perkiraannya, orang Dayak tak
akan sungkan jika hendak memenggal kepala orang-orang
Tionghoa tersebut.
CINA WURUNG, LONDO DURING, JAWA TANGGUNG
merupakan sebuah ungkapan untuk menggambarkan
keadaan etnis Tionghoa di Indonesia. Mereka, dalam
pandangan umum masyarakat selalu dikatakan bukan Orang
Indonesia dan dianggap “Orang Lain”. Sementara, dalam
sejarah kolonial Belanda, toh mereka tak mendapatkan
perlakuan yang istimewa. Bahkan, dalam banyak kasus
mereka diperlakukan layaknya seorang pribumi. Di masa
Orde Baru, Orang Tionghoa dianggap tidak cocok dengan
“kepribadian nasional”. Dalam kebijakan pemerintahan
masa Orde Baru, asimilasi merupakan jalan keluar satu-
satunya bagi Orang Tionghoa yang ingin menjadi warga
negara Indonesia, selain daripada itu, mereka akan
menerima cap sebagai “Cina Totok”. Dan dalam masa-
masa itu, ada dua haluan Orang Tionghoa dalam merespon
program pemerintahan Orde Baru, yakni menyembunyikan
kecinaan mereka atau biasa disebut “Orang Kasno”
dan mereka yang menyangkal kecinaan mereka atau
yang biasa disebut sebagai “Orang Kirno”. Meskipun
belakangan, saat kekuasaan Orbe Baru runtuh, Presiden
Gus Dur mengambalikan status Orang Tionghoa akan
kebebasannya.
Penting utnuk diketahua perihal Orang Tionghoa ini
adalah siapakan mereka sesungguhnya? Dari negeri
Tiongkok bagaian mana mereka berasal? Untuk menjawab
pertanyaan ini, sebuah buku berjudul Cina Khek di Singkawan 8 ETNONESIA

karya Hari Poerwanto memberikan gambaran yang baik.
Dalam penelitiannya, Hari memperkirakan bahwa suku
Hokkian dari provinsi Fujian merupakan Orang Tionghoa
pertama yang datang ke Nusantara. Hal ini didasarkan
pada sensus penduduk yang dibuat pemerintaha kolonial
Belanda pada tahun 1930. Dalam tahun-tahun sebelum
itu, perkiraan yang didapat tidak terlampau jauh berbeda.
Sementara perihal alasan Orang Tionghoa datang ke
Nusantara, paling tidak hipotesis yang paling umum
diketahui adalah urusan perdagangan. Catatan pada masa
pemerintahan Dinasti Song di negeri Tiongkok memberikan
informasi bahwa telah terjalan hubungan perdagangan
dengan Kepulauan Nusantara yang berlangsung sejak
abad ke 3. Sedangkan di masa sebelum abad ke 3, seperti
diceritakan Fa Hian, seorang pendeta Budha yang melawat
ke berbagai negara termasuk ke Nusantara memberitahukan
bahwa dalam erjalanannya di Nusantara, tak diketemukan
Orang Tionghoa. Dan secara umum, Orang Tionghoa
yang berada di Nusantara dan beberapa wilayah asia
tenggara lainnya disebuat sebagai “Cina Nanyang”. Istilah
Nanyang memiliki arti Lautan Selatan. Maksudnya, istilah
ini merujuk pada wilayah-wilayah di semenanjung Indo
Cina, semenanjung Melayu, dan Indonesia. Di abad ke 14,
istilah yang sering dipakai adalah Nan Hai atau Si Nan Hai.
STEREOTIP dalam melihat Orang Tionghoa sudah menjalar
bak akar kayu jati yang kokoh. Dalam ungkapan masyarakat
umum, terindikasi adanya ungakapan “sekali Cina tetap
Cina”. Hal ini bukan tanpa sebab. Dalam penalaran Hari
Poerwanto salah satu penyebab hal demikian terjadi adalah
adanya sikap kurang bergaul dengan masyarakat sekitar
di tubuh Orang Tionghoa sendiri. Mereka seakan memiliki 9 ETNONESIA

kehidupannya sendiri dan terlepas dari masyarakat tempat
tinggal mereka. Mahandis Y. Thamrin dalam tulisannya
berjudul Sang Naga di Barat Jakarta yang dimuat majalah
National Geographic Indonesia mengemukakan “kisah lain”
dari streotip yang selama ini kita dengar tentang Orang
Tionghoa. Dalam tulisannya, Mahandis memaparkan
bagaimana kehidupan masyarakat “Cina Benteng”
terbentuk baik dengan lingkungan sekitarnya. Kultur leluhur
yang terbawa dalam perjalanan panjang ke Nusantara,
tersusun rapih dalam balutan merekat dengan identitas
“kebentengannya”.
Sayangnya, lain “Cina Benteng” lain “Cina Lainnya”.
Keberuntungan ekonomi yang didapatkan rata-rata Orang
Tionghoa di Indonesia merupakan salah satu faktor penting
stereotip yang hingga kini masih terjaga. Masyarakat
(pribumi) masih kadung menganggap bahwa tanah yang
mereka pijak adalah milik mereka seutuhnya. Siapa-siapa
yang bukan merupakan “pemilik” dan ternyata terlihat
makmur akan dicap sebagi biang dari kesengsaraan yang
mereka alami. Banyak contoh kasus yang pernah terjadi di
negeri ini untuk membuktikan hal demikian. Bahkan hingga
kinipun, masyarakat Indonesia terlanjur susah untuk dididik
menerima perbedaan dengan baik. Alasannya mudah saja,
“sekali Cina tetap Cina”.
10 ETNONESIA

MENCARI TEMPAT BERMAIN BOLA
Ketika pembangunan menghalangi permainan, lahirlah sebuah industri bernama industri bola.

Suatu siang saya mencoba menelusuri jejak-jejak
kenangan masa kecil saya. Tentu tak semua
kenangan masa kecil yang akan saya jelajahi. Paling
tidak, salah satu kenangan masa kecil saya yang cukup
membuat saya terkesan hingga kini akan saya jelajahi. Tak
lain kenangan tersebut adalah bermain. Dan bermain bola
bersama teman-teman merupakan salah satu saat-saat
terindah dalam hidup saya.
Main bola bukan cuma sekedar permainan. Di negeri
penggila bola ini, bermain bola sudah terlanjur menjadi
tradisi yang saban generasi terus dimainkan. Memasuki
masa-masa peralihan, bermain bola juga masih sering
dilakukan. Atau lebih tepatnya tetap melestarikan bermain
bola dengan cara yang berbeda. Apalagi kalau bukan
menonton bola. Ramainya televisi, baik yang gratisan
maupun berbayar membuat semuanya menjadi mungkin.
Kenangan-kenangan tentang bermain bola terus terpelihara
dan terus terjaga.
SELEPAS SEKOLAH USAI DI SIANG HARI, biasanya saya
dan teman-teman tak langsung pulang. Paling tidak, 1-3
jam saya habiskan bersama teman di sebuah lapangan
bola kecil yang berjarak 15 menit berjalan kaki dari sekolah
kami. Tak ada kemuraman dari raut muka kami kala itu,
pelajaran yang sulit dan seramnya wajah guru kami, tak
menyurutkan raut keceriaan saat kami akan bermain
bola. Memang bukan sepakbola ala FIFA dengan segala
aturannya yang hendak kami lakukan. Bermain bola khas
anak-anak dengan aturan yang “disesuaikan” merupakan
ciri khas bermain bola anak-anak. Lapangan yang
dimaksud tentu bukan lapangan dengan ukuran standar
dengan instrumen-instrumen standar pula. Cukup sepetak 12 ETNONESIA
Teks olehSubagja Sutisna
Foto olehAgus Kusumaat-
maja dan Kholidah Zia

lahan kosong dengan tumpukan sendal dan sepatu
sebagai gawangnya, bermain bola sudah bisa dilakukan.
Aturannya, selain bola sepak dan kaki, tentu saja tak boleh
ketinggalan: Keceriaan.
Saya ingat ketika itu, saya dan teman-teman tak selalu
menggunakan sepatu untuk bermain bola. Paling banter,
hanya menggunakan sandal untuk bermain adalah
kenyamanan tersendiri yang bisa disuguhkan. Tentu,
bertelanjang kaki adalah sebuah kelaziman dalam bermain
bola, ala kami anak-anak dahulu. Cerita tentang kaki yang
terluka dan berdarah merupakan cerita biasa yang tak akan
menyurutkan niat kami bermain bola. Kalaupun luka, lalu
apa artinya cuaca buruk semisal hujan. Permainan tetaplah
permainan. Keceriaan harus tetap dilanjutkan.
Sayang, itu cuma kenangan. Dalam kenyataan yang saya
lihat. Sisa-sisa kami pernah bermain bola memang telah
semankin pudar. Apalagi, sepetak lahan kosong yang
dahulu kami gunakan untuk bermain bola telah berubah
menjadi bangunan kokoh. Bukan cuma satu lahan, tapi
banyak lahan yang saya ketahui dulu merupakan tempat
bermain bola anak-anak, kini telah berubah. Apalagi
kalau bukan berubah menjadi bangunan perumahan atau
perkantoran. Seakan sebuah peringatan sudah tertulis
dengan rapih: Tak ada lahan untuk bermain bola.
Semakin kencangnya urbanisasi dan semakin tingginya
taraf hidup masyarakat menjadi “tragedi” tersendiri bagi
anak-anak. Kebanyakan, jika anak-anak ingin bermain
bola, tak ada tempat lain selain jalan-jalan kompleks
yang digunakan. Dan jika bermain bola di “area”
tersebut dianggap berbahaya, satu-satunya tempat yang 13 ETNONESIA

Sebuah lapangan bola dibuat untuk digu-nakan masyarakat di wilayah Malaysia.

Para pemuda bermain bola di atas lapangan. Di Indonesia, lapangan sepakbola kian langka. Lain dengan di Malaysia.

bisa digunakan apa lagi kalau bukan lapangan Futsal.
Sayangnya, lapangan Futsal yang kini menjamur tak sama
dan sebangun dengan lahan kosong yang dijejali sendal
sebagai tiang gawang, Futsal merupakan sebuah industri
bermain, industri olahraga.
TAK ADA YANG GRATIS DI NEGERI INI, merupakan sebuah
ungkapan yang sudah umum terdengar dalam masyarakat
Indonesia. Ungkapan tersebut merupakan buah dari keadaan
bagaimana negeri ini dijalankan. Terutama menyangkut
hajat hidup orang banyak. Dan dalam ungkapan tersebut,
rujukan utamanya tentu saja “kencing bayar”. Ironisnya,
bukan cuma perkara hajat saya masyarakat Indonesia
diharapkan membayar, sekedar memberikan raut keceriaan
bagi anak-anak juga demikian. Dan dalam hal ini, Futsal
adalah kebahagian yang harus dibayar anak-anak kini.
Futsal merupakan sebuah varian sepakbola. Dimainkan
dalam versi resminya, 5 lawan 5 dan menggunakan
lapangan yang telah distandarisasi. Kebanyakan, lapangan
Futsal berada di dalam ruangan. Terlebih, dalam ruangan
tersebut telah dikondisikan suasana yang nyaman lengkap
dengan penyejuk ruangan dan lapangan sintetis yang
bersertifikat.
Tentu ada harga yang harus dibayarkan untuk segala
fasilitas yang diberikan. Paling tidak, lebih dari Rp. 100.000
untuk satu jam bermain di atas lapangan Futsal harus
dikeluarkan. Itu belum memperhitungkan biaya membeli
minuman di area Futsal dan jangan pula lupa membayar
uang parkir saat kita hendak pulang. Harga juga tergantung
waktu, makin malam, makin tinggi biaya yang harus
dikeluarkan. Menurut pengelola, itu adalah waktu favorit 16 ETNONESIA

pengguna lapangan Futsal. Di dalam lapangan Futsal,
tentu saja kita tak harus menumpuk sandal atau sepatu
menjadi tiang gawang. Sudah ada dengan baik dan bagus
tiang disana. Dan jangan pula cemas kala cuaca buruk
menerjang. Karena dimainkan dalam ruangan, bermain
bola di lapangan Futsal jelas memberikan nuansa yang
berbeda. Nuansa yang dibayar oleh uang tentu lain dengan
nuansa gratisan. Jika bermain di lapangan Futsal, hujan,
badai, ataupun apapun tak akan menghalangi niat bermain
bola. Tapi, itulah kelemahannya. Kenangan tetap hanya
menjadi kenangan. Suasana bermain bola di lapangan
terbuka sulit diraih anak-anak kini.
SIANG ITU, SELEPAS SEKOLAH USAI saya menemui
beberapa anak-anak SD yang bermain bola. Mereka
mengaku datang dari sebuah kampung di pinggiran kota
Bandung. Tujuannya tak lain untuk bermain bola. Taman
Persib sudah kadung terkenal di Kota Bandung jauh
sebelum taman tersebut diresmikan. Bak bunga yang
sedang mekar dan anak-anak bagaikan seekor lebah, tentu
banyak akan hinggap diatasnya. Sayang, taman tersebut
hanya berjumlah satu unit. Tak ada taman serupa. Belum
lagi, taman tersebut belum diresmikan. Dari pengamatan
saya, hanya beberapa kelompok saja yang diperbolehkan
bermain sebelum taman benar-benar diresmikan. Belum
lagi ada sebuah aturan, taman bisa dipergunakan sesudah
melakukan “booking” terlebih dahula pada panitian.
Meskipun gratis, sulit bagi anak-anak SD seperti yang
saya temui siang itu untuk mengakses panitia “booking”
tersebut.
“Lapangannya digembok” ujar salah seorang anak kepada
saya. Dari balik pagar mereka hanya bisa menerawang 17 ETNONESIA

taman bola yang bagus tersebut. Kesal hanya bisa
menyaksikan taman dari balik pagar, mereka duduk
sebentar di sebuah warung di pinggir jalan. Dan seperti
anak-anak kebanyakan, habis kesal, terbitlah keceriaan.
Lahan kosong di samping taman bola tersebut mereka
pergunakan untuk bermain bola. Dan keciriaan tumbuh
lagi di raut muka mereka. Sebuah ironi, di negeri pecinta
bola. Tak ada lagi lahan kosong untuk bisa dipergunakan
anak-anak untuk bermain bola. Dan bagaimana mungkin,
uang jajan (anak-anak SD) harus mereka sisihkan untuk
patungan menyewa lapangan Futsal.
Kalau sudah begini, jangan salahkan tak ada anak yang
berniat menjadi pemain bola profesional.
18 ETNONESIA

Taman Persib merupakan nama yang diberikan untuk sebuah lapangan di Jl. Supratman, Bandung. Dibuat sebagai upaya “menyegarkan” ruang bermain bola di tengah pesatnya pembangunan di Kota Bandung.

BOM &SAKIT JANTUNG
Nasionalisme di Long Nawang

Tulisan ini merupakan sebuah kisah nasionalisme.
Kisah ini dimulai ketika rombongan dari Universitas
Indonesia, yang terdiri dari Dave Lumenta (Dosen),
Shindunata (Peneliti Puska), dan ketiga mahasiswa, Zia,
Feni, dan Saya Sendiri, masuk ke desa Long Nawang
pada tanggal 12 Agustus 2014. Kami berniat untuk melihat
ritus tujuh belasan di perbatasan, yang konon sakral di
perkotaan (dapat dilihat dengan upacara di institusi negara
seperti Istana Negara, Kementrian, Markas TNI-POLRI,
Sekolah Negeri, dll). Kami sampai sore hari, setelah
berjibaku dengan lumpur, karena menarik mobil jalan rusak
di Panggung (Malaysia). Semua beristirahat di hari itu,
maklum kelelahan mendera kami semua.
Hari kedua dan ketiga berjalan dengan perjalanan mencari
data oleh anggota tim penelitian. Semua dirasa normal-
normal saja. Namun tidak bagi saya, sesampai di Long
Nawang, saya merasa sangat takjub kepada desa ini.
Jalanan sudah beraspal, jembatan besi besar pun sudah
ada untuk menghubungkan jalan, puskesmas 24 jam sudah
ada, SD-SMA negeri sudah ada (meski masih kekurangan
guru). Wah, sudah lengkap ini desa, cukup “maju”
pembangunannnya”, ujar saya dalam hati. Pembangunan
infrastruktur publik memang gencar dilakukan oleh
Kabupaten Malinau, Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara).
Lanjut berjalan keliling desa, mata pun melirik kearah
Markas Polisi dan Tentara.
Ada agen-agen pengaman negara. Saya tidak membenci
mereka dan negara, akan tetapi hanya merasa Indonesia
agak lebay (baca: berlebihan) dalam menjaga tiap jengkal
tanah dan airnya. Sebelumnya kami memang pergi lebih
dahulu ke Long Busang, Desa Kenyah (Sub Etnis Dayak) 21 ETNONESIA
OlehWieldan Akbar

yang berada di Malaysia, dapat dikatakan tetangga Long
Nawang. Beda sekali dengan Long Nawang, di sana tidak
ada yang namanya tentara maupun polisi. Dahulu memang
ada, di garda tedepan pebatasan malaysia, dekat Tapak
Megah, ada kamp tentara, dan pos perbatasan tak resmi
dibangun. Namun umurnya tidak lama, hanya berkisar lima
tahunan, tentaranya tidak betah hidup di alam “liar”, begitu
pendapat Agen Laling, warga Long Busang.
Pasca kaburnya tentara dari pos batas, pemerintah
Malaysia menjaga kedaulatan negaranya dengan suplai
barang subsidi yang lancar. Memang akses telah terbuka
ke Kapit, memudahkan warga Long Busang dan Long Unai
untuk pergi membeli barang (subsidi dan non subsidi ke
Kapit. Hal ini membuat loyalitas warganya secara tidak
langsung terjaga. Patok batas pun hanya di cek beberapa
kali dalam setahun oleh Polis Diraja Malaysia, begitulah
yang saya ketahui dari warga Long Busang. Kembali
lagi ke Long Nawang, hal ini sangat berbeda. Mereka
sulit mendapatkan barang murah. Akses ke Long Bagun
yang dapat tembus ke Samarinda masih dalam proses
pembukaan jalan (saat kami meneliti kesana). Sehingga
warga Long Nawang masih mengandalkan beli barang-
barang maupun sembako lewat pesawat kecil yang terbang
dari Samarinda ke Long Ampung (Dekat Long Nawang).
Harga avtur yang tidak murah menyebabkan harga angkut
barang menjadi mahal, dan tentunya harga menjadi
berkali-kali lipat. Saya beri contoh, Rokok Sampoerna Mild
tujuh belas ribu rupiah (di Jakarta masih empat belas ribu),
dan barang yang jarang laku seperti Air Mineral Aqua, bisa
berkali-kali lipat harganya dari Jakarta, dua puluh ribu
untuk ukuran sedang (600 ml). Harga yang cukup tinggi 22 ETNONESIA

Suasana Upacara Bendera Long Nawang.

membuat mereka harus membeli sembako hingga Minyak
(Bensin dan Solar) ke kamp balak Tapak Megah, desa
tetangga (pemerintah menyebutnya negara tetangga),
Long Busang, bahkan hingga ke Kapit. Mereka menjadi
penumpang “gelap” bersama Kenyah Long Busang
ke Kapit, mungkin itulah perkataan negara jika mereka
mengetahui transaksi transnasional ini.
Kontras memang, pertahanan yang dibangun kedua
negara. Malaysia dengan distribusi material, berupa logistik
kebutuhan sehari-hari. Indonesia? Cukup dengan distribusi
diskursus nasionalisme, bersama penjaga kedaulatan
NKRI, yakni TNI dan POLRI. Bisa dibayangkan betapa
pengagum nasionalisme dan TNI akan terhenyuh ketika
melihat realita ini secara “live” dari TKP. Entah kenapa
saya melihat warga Long Nawang lebih membutuhkan
distribusi material seperti Long Busang, untuk bertahan
hidup, daripada sekedar diskursus Kedaulatan NKRI dan
jago-jagoan ala TNI. Saya menyetujui pendapat Ishikawa
(Antropolog Jepang) yang melihat inskripsi sebuah negara
ke warga perbatasan sebenarnya bukan lewat diskursus,
tapi instrumen material. Ada benarnya, mengingat
diskursus hanya cocok untuk masyarakat yang dekat
dengan pusat pemerintahan, sementara yang jauh, harus
dapat diperlihatkan “fisik” kehadiran negara. Indonesia
memang hadir secara fisik, lewat infrastruktur tadi, plus
aparat keamanan, tapi belum kepada kebutuhan pokok
warga perbatasan. Padahal, “kesetiaan” mereka akan
terjaga dan terjamin, jika kebutuhan pokok mereka terjaga,
menurut hemat saya.
Berbicara soal jago-jagoan, inilah inti ceritanya. Pada hari
kelima kami di Long Nawang, (tepat tanggal 16 agustus 24 ETNONESIA

2013) sehari sebelum ritus kenegaraan itu dijalankan, ada
kejadian yang sangat menarik. TNI akan menggelar atraksi
pada tanggal 17 agustus. Hemm, penasaran juga apa
atraksi yang akan mereka pertunjukkan. Ternyata aksi yang
akan dipentaskan adalah bagaimana TNI memberantas
terorisme yang mengancam keamanan negara. Dalam
teaterikal tersebut, digambarkan pimpinan pemerintahan
diculik sekelompok teroris, dibawalah mereka ke markas
teroris tersebut. Kisah mencapai babak final ketka pasukan
TNI mengendarai motorcross membebaskan pimpinan
tersebut dan membom markasnya. Cerita tersebut saya
ketahui pada tanggal 17 Agustus. Kembali ke sesi latihan,
pada sore itu sedang ada lomba volly tujuh belasan. Saya
dan dua kawan mahasiswa lainnya sedang asik nonton
dari halaman belakang rumah yang kami tumpangi. Tiba-
tiba permainan bola volly dihentikan, dan ada suara
pemberitahuan agar segera menjauh dari lapangan
sepakbola, karena akan diadakan latihan atraksi untuk
tujuh belasan.
“Duar!” Dentuman keras sangat memekik telinga itu
terdengar. Jantung saya berdetak lebih cepat. Rumah kami
yang dari kayu pun bergetar cukup keras untuk bebrapa
detik. Semua orang kaget meski sudah diberi tahu. Sontak
semua warga keluar, penasaran dengan dinamit yang
ditanam ke dalam tanah yang dahsyat tadi. Bekasnya
lubang cukup besar. Saya mendengar salah seorang kapten
upacara besok berkata, “Ini masih satu lho we (Ibu), besok
kita ledakkan tiga!”. Perkataan jenis apa itu, semacam
tidak punya lingkar kepala (umpat saya dalam hati). Saya
sebagai warga Jakarta saja marah dengan dentuman bom
itu, terlebih dengan perkataan si kapten, apalagi warga
sini. Benar saja dugaan saya, seorang warga protes ke 25 ETNONESIA

pimpinan PASPAMTAS (Pasukan Pengaman Perbatasan)
atas perilaku mereka. “Anda itu kira-kira dong! Disini
banyak orang tua (lansia), dan orang sakit jantung. Mau
bikin warga sini mati semua? Sekali lagi saya beri denda
adat kalian!”, hardik orang tersebut kepada si kapten.
Perkataan tersebut saya dapatkan dari We Lencau, Ibu di
rumah kami, bercerita menggambarkan percakapan tadi
lengkap disertai ekspresinya. “Memang itu TNI tidak kira-
kira, itu tadi saudara saya yang beri peringatan, maklum
kakak saya yang perempuan menderita jantung, dan tadi
langsung jantungan”, papar We Lencau, warga Long
Nawang.
Akhirnya pertunjukkan 17 Agustus tidak menggunakan
tiga TNT, hanya menggunakan satu, itupun saya kira daya
ledaknya yang tidak besar macam kemarin. Mungkin si
kapten takut kena denda adat, satu batalion takut dengan
perkara adat. Memang untuk urusan hukum, adat lebih
dominan daripada hukum negara, sekali lagi, ini desa adat.
Upacara berjalan cukup hikmat. Sesuai dengan prosedur
kenegaraan. Camat pun datang, Tapi dengan pelat mobil
Sarawak. Maklum saja, untuk membeli mobil seharga
Jakarta, jalan satu-satu ke desa (negara) tetangga. Warga
pun menonton tidak juga antusias, biasa saja, bahkan
lebih ramai saat menonton datun julut (kontes menari).
Entah apa yang ada di benak mereka semua. Saya hanya
dapat menduga mereka tidak tertarik dengan ritus asing
Indonesia ini, atau mereka tidak mengerti apa guna itu
semua (upacara tujuh belasan). Diskursus kedaulatan
negara atau NKRI harga mati memang tidak sampai ke
mereka.
Jika Ben Anderson mengatakan kapitalisme cetak (koran, 26 ETNONESIA

majalah, dsb) yang menyatukan komunitas hantu bernama
Bangsa, disini tidak berlaku (koran tidak sampai ke Apo
Kayan). Sekali lagi, memang kenapampakan material
lah yang hadir diperbatasan. Ada sisi positif seperti
infrastruktur kesehatan, pendidikan, jalan. Tapi ada juga
yang dirasa tidak begitu “relevan” bagi kehidupan mereka,
seperti Markas Tentara (Markas Polisi masih lebih berguna
menurut hemat saya, untuk pengamanan sipil). Apa yang
mereka lihat dan rasakan secara materil, itulah gambaran
negara. Sedangkan gambaran material kebutuhan pokok
sehari-hari mereka adalah Sarawak, yes Malaysia. Lalu
pertanyaannya, untuk apa Pasukan Loreng itu diletakkan di
Long Nawang dan pintu-pintu desa Lainnya di Apo Kayan,
jika pihak lawan (Malaysia) saja tidak punya Markas disisi
sebelahnya (Panggung)? Mungkin itulah yang disebut
Nasionalisme, Entahlah.
27 ETNONESIA

Seorang petugas sedang memperbaiki jaringan telefon. “Rumit ka-belnya, tapi ada kode-kode tertentu” menurutnya. “Pekerjaan jadi lebih mudah” tambahnya. Foto oleh Effendy Firmansyah.

Seorang pedagang sedang mengikat Iket Kepala dengan pola “Be-rambang Semplak” Edisi Maret lalu diulas bagaimana Iket menjadi ladang bisnis tersendiri. Foto oleh Ahmad Zaenudin.

Bagaikan seekor ayam, kendaraan pun dibuatkan “kandang” oleh pemiliknya. Foto oleh Effendy Firmansyah.