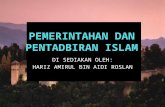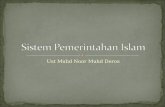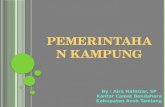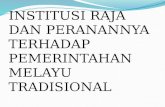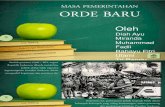Hak Transgender untuk Berpartisipasi dalam Pemerintahan
-
Upload
margaretha-quina -
Category
Documents
-
view
620 -
download
1
Transcript of Hak Transgender untuk Berpartisipasi dalam Pemerintahan
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Demokrasi ialah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk
rakyat.1 Sebagaimana disebutkan John Locke dalam teori kontrak sosial,2 untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama yang kemudian diwujudkan dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi tiap negara.3 Sehubungan dengan ini, muncul pula suatu hak bagi warga negara untuk mengambil bagian dalam suatu pemerintahan, yang disebut sebagai hak turut serta dalam pemerintahan. Hak ini muncul untuk menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.4 Dalam suatu negara, tak dapat diabaikan pula bahwa selalu terdapat kaum minoritas. Salah satu fenomena yang cukup mengundang perbedaan pendapat, namun nyata keberadaannya, adalah kaum Transgender.5 Di belahan dunia manapun, Transgender, yang termasuk dalam kelompok LGBTI yang merupakan kaum minoritas selalu
menghadapi persoalan yang sama dengan titik berat pada aspek sosialbudaya dan penerimaan masyarakat dibandingkan permasalahan dariPernyataan ini merupakan kutipan terkenal dari Abraham Lincoln, Lihat: Thomas Goebel, A Government By the People: Direct Democracy in America, 1890-1940, (New York: The University of North Carolina Press, 2002), hlm. 34. 2 Harus diingat bahwa paling tidak terdapat tiga macam teori kontrak sosial masingmasing dikemukakan oleh John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseu yang masing-masing melahirkan konsep negara yang berbeda-beda. Lihat George H. Sabine, A History of Political Theory, Third Edition, (New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 517 596. 3 Jimly Asshiddiqie, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005, hlm. 1. 4 Ibid., hlm. 3. 5 Arti dari kata transgender telah meluas sejak pertama kali didengungkan. Virginia Prince mendefiniskan transgender secara sederhana sebagai seseorang yang hidup penuhwaktu dalam peranan gender yang berbeda dengan anatomi tubuhnya. Paisley Currah, Richard M. Juang, dan Shannon Minter, Transgender Rights, (Minnesota: University of Minnesota Press, 2006), hlm. 4.1
1
segi hukum.6 Namun, sebagai suatu konsekuensi praktis hubungan sosialpolitik-hukum, konsekuensi sosial seringkali mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang tidak jarang berpengaruh pula pada hukum. Sebagai kelompok minoritas, kaum Transgender tentunya juga memiliki hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Namun, paralel dengan permasalahan sosial-budaya yang dihadapinya, eksistensi Transgender tak jarang terganjal secara hukum. Salah satu permasalahan yang Penulis cermati ialah adanya pencantuman klausa Sehat jasmani dan rohani dalam berbagai persyaratan administratif pendaftaran jabatan publik maupun wakil rakyat, bahkan sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Berdasarkan pemikiran tersebutlah, Penulis memutuskan untuk mengangkat masalah tersebut dalam karya tulis ini.
1.2.
Pokok Permasalahan Dalam karya tulis ini, penulis mencoba mencari jawaban atas
pertanyaan berikut: 1. Bagaimana hukum nasional maupun internasional memberikan perlindungan pemenuhan hak turut serta dalam pemerintahan, khususnya bagi transgender? 2. Bagaimana klausul Sehat jasmani dan rohani telah berpengaruh terhadap pemenuhan hak turut serta dalam pemerintahan kaum transgender?
1.3.
Tujuan Penulisan
1. Mengetahui sejauh mana perangkat hukum nasional maupun internasional telah memberikan perlindungan pemenuhan hak turut serta dalam pemerintahan, khususnya bagi transgender; 2. Mengetahui pengaruh klausul Sehat jasmani dan rohani terhadap pemenuhan hak turut serta dalam pemerintahan kaum transgender.
6 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 433.
2
BAB II PEMBAHASAN DAN ANALISIS
2.1.
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan Sebagai Hak Asasi Manusia John Locke memberi pengertian hak asasi manusia sebagai hak
yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak).7 Hak turut serta dalam pemerintahan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional, sebagaimana akan dipaparkan dalam uraian di bawah. Satu hal yang penting untuk diketahui, hak turut serta dalam pemerintahan ini merupakan hak yang dapat dibatasi. Pembatasan ini berpijak dari berhadapannya hak-hak asasi seseorang dengan hak orang lain, sehingga hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat.8 Pembatasan mengenai hak asasi manusia dalam bidang tertentu ini diamini pula dalam konstitusi Indonesia, yaitu pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945, yang secara limitatif membatasi nonderogable rights.9 Hak untuk turut serta dalam pemerintahan tidak termasuk dalam kategori tersebut, dan demikian merupakan hak yang dapat dibatasi. Selain itu, dalam Pasal 28 J ayat (2), disebutkan pula mengenai kewajiban setiap orang untuk tunduk dalam pembatasan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam menjalankan hak dan kewajibannya tersebut.10
Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 223. 8 Budiyanto, Kewarganegaraan, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 66 9 Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diberbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." 10 Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil7
3
Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan terwujud dalam empat hal berikut:11
a) Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; c) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan
pemerintahan; d) Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.2.
Instrumen Hukum yang Menjamin Hak Turut Serta dalam Pemerintahan Baik secara internasional maupun nasional, hak untuk turut serta
dalam pemerintahan diakui sebagai hak asasi manusia. Hak ini termasuk dalam kategori hak-hak sipil dan politik, yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut. 2.2.1 Jaminan Hak Turut Serta dalam Pemerintahan Dalam
Instrumen Internasional Hak untuk turut serta dalam pemerintahan merupakan hak yang secara internasional diakui dan dijamin pemenuhannya.12 Dalam tataran internasional, setidaknya secara universal dalam dua dokumen berikut.sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." 11 Aim Abdulkarim, Kewarganegaraan, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama), hlm. 8788. 12 Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hakhak Asasi Manusia, (Jakarta: Buku Obor, 2006), hlm. 112.
4
Yang pertama ialah Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) menyatakan: "(1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara bebas. (2) Setiap orang berhak atas akses yang sama untuk memperoleh pelayanan umum di negaranya. (3) Keinginan rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah; keinginan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilakukan secara berkala dan sungguh-sungguh, dengan hak pilih yang bersifat universal dan sederajat, serta dilakukan melalui pemungutan suara yang rahasia ataupun melalui prosedur pemungutan suara secara bebas yang setara."13 Ketentuan senada dapat ditemukan pula dalam pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut ICCPR).14 Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum. Indonesia merupakan negara peserta dari ICCPR15 sehingga terikat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam ICCPR dan mengimplementasikan dalam perundang-undangan nasionalnya. Sedangkan ketentuan-
ketentuan dalam DUHAM telah dilihat sebagai hukum kebiasaan internasional yang dipatuhi oleh seluruh negara di dunia.
United Nations General Assembly, Universal Declaration on Human Rights, diadopsi pada 10 December 1948 di Paris, Perancis. 14 UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), tertanggal 16 Desember 1966. 15 Indonesia telah meratifikasi ICCR dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)13
5
2.2.2.
Jaminan Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan Dalam Instrumen Nasional Dalam tataran nasional, Indonesia menjamin dan melindungi
pemenuhan hak turut serta dalam pemerintahan pula. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 D ayat (3) bahwa Setiap warga negara berhak memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan.16 Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia17 menjamin pula hak turut serta dalam pemerintahan ini dalam satu bagian tersendiri, Bagian Kedelapan yang mencakup pasal 43 dan pasal 44. Pasal 43 menyatakan, (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Dan dalam pasal 44 juga dinyatakan perlindungan terhadap hak turut berpartisipasi dalam hal pengajuan pendapat dan usulan, Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2.3.
Partisipasi Transgender Dalam Permerintahan Sebagai Warga Negara dan Kelompok Minoritas
Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 388616 17
6
Dalam berdemokrasi, oposisi dan minoritas berhak untuk menyuarakan pandangan mereka dan mempunyai pengaruh (yakni bukan semata-mata memperoleh kursi atau suaranya terwakili) di dalam prosesproses pengambilan kebijakan.18 Kelompok yang minor, yang tertekan, subultern, memerlukan jaminan untuk berbicara dengan suara-suara mereka sendiri, dan dengan cara itu kelompok-kelompok ini berusaha mendapatkan jaminan kebebasan politik dan meraih pemahaman atas perbedaan yang mereka miliki.19 Hak turut serta dalam pemerintahan merupakan bentuk konkrit partisipasi kaum minoritas dalam pemerintahan, dan merupakan hak yang menentukan bagaimana suatu pemerintahan dibentuk. Ini yang akan menjadi dasar bagaimana hak-hak lainnya dijamin, termasuk pula hak-hak dari kaum minoritas, dan di antaranya ialah kaum Transgender sendiri. Salah satu perlindungan terhadap kaum Transgender ialah Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity (selanjutnya disebut Yogyakarta Principles).20 Di antaranya, Yogyakarta Principles mendeklarasikan, Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak. Setiap manusia dengan orientasi seksual dan identitas gender mereka berhak menikmati semua hak asasi mereka. Setiap orang berhak menikmati HAM tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Setiap orang berhak atas kesetaraan dimata hukum dan perlindungan undangundang tanpa adanya diskriminasi yang atau yang tidak mempengaruhi penikmatan HAM. Hukum juga melarang
18 Timothy D. Sisk, et. al., Demokrasi di Tingkat Lokal: Buku Panduan Internasional IDEA Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Kepemerintahan, (Jakarta: Ameepro, 2002), hlm. 31-33. 19 Gayatri Chakravorty Spivak, Donna Landry, dan Gerald M. MacLean, The Spivak Reader: Selected Works of Gayatri Chakravorty Spivak, (New York: Routledge, 1996), hlm. 233. 20 Mengikuti pertemuan para ahli di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, Indonesia, pada 6-9 November 2006, 29 ahli dari 25 negara dengan berbagai latar belakang dan keahlian terkait hak asasi manusia secara penuh tanpa terkecuali mengadopsi Prinsip Yogyakarta ini. Yogyakarta Principles Official Websites. Sumber: http://yogyakartaprinciples.co.id
7
diskriminasi semacam itu dan menjamin perlindungan yang setara dan efektif terhadap diskriminasi bagi setiap orang.21 Hal di atas mencakup pula hak Transgender untuk turut serta dalam pemerintahan. Memang patut diakui bahwa dalam beberapa lembaga, partisipasi Transgender telah diakomodasi dengan baik.22 Namun, secara umum, partisipasi Transgender dalam jabatan-jabatan publik dan pemerintahan masih sangatlah kecil. Dalam sub-bab di bawah, akan dibahas mengenai salah satu fenomena yang membatasi Transgender untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
2.4.
Sehat Jasmani dan Rohani Sebagai Pembatasan Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan Sebagaimana telah diuraikan di atas, hak turut serta dalam
pemerintahan
merupakan
hak
yang
dapat
dibatasi.
Salah
satu
pembatasan yang selalu ditemukan, baik dalam persyaratan lamaran kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, calon legislatif dan jabatan-jabatan publik lainnya ialah sehat jasmani dan rohani. Contohnya, dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Pemilu)23 mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam pasal ini, ditetapkan bahwa bakal calon harus memenuhi persyaratan sehat jasmani dan
Prinsip 1 dan Prinsip 2 Yogyakarta Principles Misalnya dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "Komnas HAM"), di mana Yulia Rettoblaut (Ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia) dan Nancy Iskandar (Ketua Forum Komunikasi Waria Cabang DKI Jakarta) yang mencalonkan diri sebagai anggota Komnas HAM periode 2007-2012 dan lolos hingga tahap pertama dan kedua. Eddie Riyadi, "Kaum Waria Menuntut Pengakuan Sebagai Warga", Majalah Asasi, Edisi Januari-Februari 2007 23 Indonesia, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008, LN No. 51 Tahun 2008.21 22
8
rohani. Begitu pula dalam persyaratan peserta pemilu untuk memilih anggota DPD24 yang juga berlaku bagi bakal calon anggota DPD.25 Pembatasan ini sendiri bukan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, apabila menilik rasio dari pembatasan ini di mana partisipasi dalam pemerintahan dan posisi sebagai pejabat publik mensyaratkan kecakapan, yang salah satu indikatornya ialah jasmani dan rohani yang sehat. Namun, ketika berbicara mengenai transgender sebagai kelompok rentan dan marginal, maka relevan untuk melihat kewajiban negara untuk memberikan perhatian yang lebih bagi kelompok ini.26 Perlu dilihat pula ketentuan dalam Pasal 27 ICCPR yang menyatakan, negara harus mengambil langkah-langkah untuk menciptakan kondisi menyenangkan yang memungkinkan orang-orang yang tergolong kelompok minoritas untuk mengungkapkan ciri khas mereka dan untuk menetapkan kewajiban bagi negara untuk mendorong kegiatan ekonomi dan sosial tertentu yang dilakukan oleh komunitas minoritas.27 Salah satu caranya ialah dengan meninjau kembali pengaturanpengaturan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam
penerapannya, termasuk pula ketentuan ini. Permasalahan tidak akan timbul apabila dalam implementasi ketentuan ini kesehatan jasmani dan rohani dipersepsikan secara sama tanpa menganggap transgender sebagai suatu penyakit, fisik maupun mental. Namun, yang sering terjadi ialah adanya suatu persepsi bahwa transgender ialah suatu cacat mental, yang tak dapat disangkal masih melekat dalam pemikiran masyarakat Indonesia, tak terkecuali dalam lembaga-lembaga publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Arus Pelangi Rido Tiawan, pemerintah masih belum bersikap adil terhadap
Pasal 11 dan 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pasal 67 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 26 Nicholas Turner dan Nanako Otsuki, The Responsibility to Protec Minorities and the Problem of the Kin-State, United Nations University Polici Brief, No. 2, 2010. 27 Pasal 27 International Covenant on the Civil and Political Rights24 25
9
keberadaan waria, terutama dalam hal perlakuan diskriminatif ketika akan bekerja di sektor formal.28
2.5.
Persepsi Publik Tentang Transgender: Cacat Mental Atau Hak Determinasi Gender? Sebagian besar institusi mensyaratkan adanya tes kesehatan
atau surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani sebagai bukti dari kesehatan jasmani dan rohani. Tidak ada patokan yang jelas mengenai kriteria Sehat Jasmani dan Rohani jika dihubungkan secara langsung dengan transgender. Tak jarang, persepsi mengenai transgender sebagai gangguan mental mempengaruhi penilaian mengenai kesehatan ini. Perlu dilihat pula bahwa tes kesehatan ini biasanya dilakukan oleh dokter umum yang tidak memiliki kompetensi untuk menentukan seorang transgender merupakan seseorang yang mengalami gangguan mental atau fisik, atau tidak. Selain itu, dalam syarat kesehatan tersebut pada umumnya juga tidak dicantumkan secara rinci kriteria kesehatan yang harus dimiliki oleh peserta.29 Transgender, menurut Pakar Kesehatan Masyarakat dan pemerhati waria dr. Mamoto Gulton, adalah subkomunitas dari manusia normal. Bukan sebuah gejala psikologi, tetapi sesuatu yang biologis. Kaum ini berada pada wilayah transgender: perempuan yang terperangkap dalam tubuh lelaki.30 Kaum pembela hak ini menyatakan bahwa transgender bukanlah suatu bentuk penyimpangan seksual,
Ninin Damayanti, "Waria Minta Perlakuan Diskriminatif Dihapus: Ketika Melamar Kerja, Orientasi Seksual Mereka Jadi Kendala", Koran Tempo, Sabtu, 15 Desember 2007 29 Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nadhatul Ulama Jombang (Lakpesdam NU Jombang), Ikatan Penyandang Cacat Jombang Sesalkan Syarat Kesehatan Jasmani dan Rohani dalam Tes CPNS, tanggal 12 November 2010, Website Resmi Lakpesdam NU Jombang: http://www.lakpesdamjombang.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=574:ikatan-penyandang-cacat-jombang-sesalkan-syarat-kesehatan-jasmanidan-rohani-dalam-tes-cpns&catid=7:hot-news 30 Kompas, 7 April 200228
10
melainkan hak orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender.31 Namun, dalam pemerintahan sendiri pun belum terdapat kesepakatan mengenai klasifikasi Transgender dalam kerangka
kesehatan. Departemen Sosial mengklasifikasikan transgender sebagai gangguan mental di bawah Undang-Undang Penyandang Cacat dengan mengalokasikan dana bantuan sosial yang disyaratkan undangundang ini dalam pos penyandang cacat.32 Sementara, berbagai publikasi dari non-governmental organizations (NGO) yang bergerak dalam bidang hak-hak transgender terus menerus menyoroti berbagai persepsi yang melekat dalam aparatur pemerintahan yang merugikan transgender dalam usahanya untuk memperoleh jabatan publik ataupun berpartisipasi secara umum dalam pemerintahan dalam bentuk-bentuk lainnya, misalnya yang paling sederhana, dalam pemilihan umum.
2.6.
Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum: Di Balik Lemahnya Efektivitas Perlindungan Transgender Dalam menganalisis fenomena ini, Penulis menggunakan teori
Lawrience Friedman mengenai efektivitas sistem hukum. Berdasarkan teori tersebut, efektivitas sistem hukum dibentuk berdasarkan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.33 Dari segi struktur hukum34, patut diakui bahwa di Indonesia, belum ada kesepakatan mengenai pengakuan keberadaan
International Gay and Lesbian Human Rights Commission, Human Rights Abuses Against Sexual Minorities in Indonesia, November 2007, hlm. 3. 32 Indonesia, Undang-undang tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1997, LN tahun 1997 Nomor : 9, TLN Nomor : 3670. Lih: International Gay and Lesbian Human Rights Commission, Human Rights ..., hlm. 5 33 Tiga unsur subsistem hukum ini diambil dari Lawrence W. Friedman, American Law. An Introduction, (New York: W.W. Norton and Company, 1984), juga dalam Lawrence W. Friedman, A History of American Law (New York: Simon and Schuster, 1973). 34 Struktur dari sebuah sistem adalah kerangka tengkoraknya, yang merupakan bentuk permanen, tubuh institusional dari sistem, jam rigid tangguh yang menjaga proses mengalir di dalam batasannya. Lawrence W. Friedman, American Law: An Invaluable Guide To The Many Faces of the Law, And How It Affects Our Daily Lives, (New York: W.W. Norton &31
11
Transgender di mata hukum. Perlindungan terhadap Transgender mulai dari akar administratifnya pun masih belum jelas di Indonesia. Hal ini berdampak secara struktural terhadap perlindungan Transgender. Dapat dikatakan, Transgender merupakan area abu-abu di mana berbagai aspek masih diliputi kekosongan, termasuk pula dalam pengaturan mengenai hak turut serta dalam pemerintahan ini. Dalam hal substansi hukum35, tidak ada sanksi yang tegas, baik administratif maupun pidana, yang diberikan bagi institusi ataupun individu yang melakukan pelanggaran atau diskriminasi terhadap transgender dalam kaitannya dengan tafsir atas persyaratan Sehat jasmani dan rohani dalam mewujudkan partisipasinya dalam
pemerintahan. Hanya dalam Undang-Undang Penyandang Cacat dapat ditemukan bentuk perlindungan berupa jaminan pekerjaan sesuai derajat kecacatan, yang sebenarnya termasuk dalam kategori hak atas penghidupan yang layak dan juga seharusnya tentu tidak dapat dijadikan dasar bagi hak kaum transgender ini.36 Selain itu, tidak terdapat kriteria yang jelas mengenai kriteria kesehatan fisik dan mental minimal yang dapat dijadikan pegangan dan berlaku secara umum dan nasional bagi seluruh bidang pemerintahan. Sedangkan budaya hukum37 merupakan faktor terkuat yang melatarbelakangi adanya fenomena ini. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum menerimaCompany, 1984), hlm. 1-8. dan pada Legal Culture and Social Development, Stanford Law Review, (New York, 1987), hlm. 1002-1010 serta dalam Law in America: a Short History, (New York: Modern Library Chronicles Book, 2002), hlm. 4-7 35 Substansi terdiri dari aturan-aturan substantif dan aturan mengenai sebuah institusi harus berlaku, Ibid. 36 Pasal 14 Undang-Undang Penyandang Cacat berbunyi Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan. Atas pelanggaran dari ketentuan ini, dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan dan/atau pidana denda maksimal Rp 600jt berdasarkan Pasal 28. 37 Budaya hukum mensistematikakan kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide, dan ekspektasiekspektasi mereka. Budaya hukum menunjuk pada pelabuhan dari kebiasaan-kebiasaan dari budaya umum, opini-opini dari cara-cara berlaku dan berpikir yang mengikat kekuatan sosial terhadap hukum dan dalam cara tertentu, Lawrence Friedman, Legal Culture, ..., Ibid.
12
kaum Transgender sebagai golongan minoritas yang harus dilindungi hak-haknya. Partisipasi Transgender dalam jabatan publik belum mendapatkan dukungan masyarakat luas, bahkan berpotensi
mendulang kontroversi dari lembaga-lembaga garis keras yang mengatasnamakan agama maupun sosial.38 Transgender masih dipandang sebagai fenomena sosial yang tidak wajar bahkan dikategorikan penyimpangan mental. Hal seperti ini tentu akan membawa permasalahan baik bagi personal Transgender itu sendiri maupun bagi lingkup sosialnya.
2.7.
Objektivitas Lembaga Publik: Akses Transgender Terhadap Partisipasi dalam Pemerintahan Melihat tiga permasalahan yang saling berhubungan di atas,
maka usaha yang harus dilakukan demi terpenuhinya hak transgender untuk turut serta dalam pemerintahan, terkait dengan syarat sehat jasmani dan rohani pun, harus menyentuh ketiga unsur hukum yang saling berkaitan tersebut. Pertama, diperlukan pemahaman yang selaras, terutama dari lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia, mengenai kedudukan transgender di mata hukum Indonesia dan bahwa transgender bukanlah suatu bentuk penyakit. Selanjutnya, harmonisasi atas peraturan-peraturan dan kebijakan publik perlu dilakukan disertai dengan pengaturan kewenangan yang selaras pula. Kedua, diperlukan pengaturan sanksi yang tegas, baik bagi aparat maupun lembaga, yang terbukti melakukan diskriminasi terhadap transgender dengan mengatasnamakan syarat sehat jasmani dan rohani. Diperlukan pula sebuah instrumen yang berlaku umum dan nasional yang menjamin hak-hak transgender, di antaranya ialah hak turut serta dalam pemerintahan. Instrumen tersebut dapat berupa38 Katrina Roen, Transgender Theory and Embodiment: The Risk of Racial Marginalisation, Journal of Gender Studies, Vol. 10, No. 3, (2001), hlm. 8.
13
Undang-Undang seperti yang diberikan bagi golongan minoritas penyandang cacat ataupun wanita. Dalam instrumen tersebut perlu menegaskan bahwa transgender bukanlah merupakan suatu penyakit, dan bahwa ke-transgender-an seseorang adalah terlepas dari kriteria sehat jasmani dan rohani. Ketiga, memandang untuk membentuk secara suatu lebih budaya hukum yang
transgender
bermartabat,
diperlukan
sosialisasi baik bagi masyarakat maupun bagi lembaga-lembaga dalam pemerintahan itu sendiri. Motivasi bagi kaum transgender untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan juga merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Meskipun berat, jika tidak dijalankan seluruhnya, efektivitas hukum akan sangat sulit tercapai karena tiadanya kesinambungan dan keselarasan antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Karena itu, dibutuhkan partisipasi dari seluruh warga masyarakat, NGO, dan terutama pemerintah sendiri dalam memperbaiki keberadaan
transgender dalam partisipasinya di pemerintahan.
14
BAB III PENUTUP
3.1.
Simpulan Transgender belum menjadi pertimbangan khusus dalam hukum
Indonesia yang mengatur mengenai hak turut serta dalam pemerintahan, sekalipun tidak pula dilarang. Dalam hampir tiap persyaratan jabatan publik atau keikutsertaan dalam pemerintahan, selalu disyaratkan sehat jasmani rohani, yang masih belum terdapat pemahaman secara umum mengenai kaitannya dengan transgenderisme di Indonesia. Klausul Sehat jasmani rohani secara umum telah menghambat kaum transgender untuk turut serta dalam pemerintahan. Permasalahan terbesar ialah dari segi budaya hukum, yang disertai dengan tiadanya perlindungan khusus dalam substansi hukum dan permasalahan hukum yang struktural dengan akar pengakuan hukum akan transgender sendiri.
3.2.
Rekomendasi Dalam mengatasi permasalahan ini, Penulis menyarankan
adanya upaya yang terpadu untuk menciptakan kesepahaman dalam hal budaya hukum, struktur hukum, dan substansi hukum bahwa transgender bukanlah suatu penyakit jasmani ataupun rohani: 1. Dalam hal budaya hukum, dengan mengadakan sosialisasi terutama terhadap aparat pemerintahan mengenai hak
transgender untuk turut serta dalam pemerintahan; 2. Dalam hal substansi hukum, dengan memberikan sanksi yang tegas bagi diskriminasi transgender untuk turut serta dalam pemerintahan dengan berbasiskan klausul sehat jasmani rohani; 3. Dalam hal struktur hukum, dengan mengakui dan memberikan perlindungan yang terpadu dan selaras bagi transgender dalam peraturan perundang-undangan.15