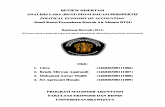3 Disertasi Revisi Asli
-
Upload
abinya-faiz -
Category
Documents
-
view
140 -
download
10
description
Transcript of 3 Disertasi Revisi Asli
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................................i
PERNYATAAN KEASLIAN ...................................................................................ii
PENGESAHAN REKTOR......................................................................................iii
DEWAN PENGUJI...................................................................................................iv
PENGESAHAN PROMOTOR.................................................................................v
NOTA DINAS ...........................................................................................................vi
ABSTRAK................................................................................................................xii
KATA PENGANTAR.............................................................................................xiv
DAFTAR TRANSLITERASI.................................................................................xx
DAFTAR ISI.............................................................................................................xxi
BAB I: PENDAHULUAN........................................................................................1
A. Latar Belakang Masalah.........................................................................1B. Permasalahan: Pertanyaan dan Hipotesis..............................................13C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.............................................................16D. Survei Literatur.....................................................................................20E. Landasan Teoretis.................................................................................28F. Metodologi dan Pendekatan..................................................................30G. Sistematika Penulisan...........................................................................36
BAB II: HERMENEUTIKA AL-QUR’AN...........................................................38
A. Al-Qur’an Sebagai Wahyu dan Teks....................................................38B. Jalan Memahami al-Qur’an: Metodologi Tafsir...................................63
1. Pendekatan Naqlī (tradisional-skriptural).........................................692. Pendekatan ‘Aqlī (Rasional)............................................................723. Pendekatan Linguistik dan Sastra.....................................................764. Pendekatan Hermeneutika Multikultural: Tafsir Kritis....................80
C. Tafsir/Ta’wīl : Penalaran atas Wahyu...................................................94
BAB III:YAHUDI DALAM TRADISI ISLAM...................................................104
A. Yahudi Sebuah Nama yang Kompleks...............................................104B. Yahudi di Tanah Arab: Tarik Menarik Peradaban..............................114C. Kebencian terhadap Yahudi................................................................121D. Bias dalam Tafsir................................................................................148
xxi
BAB IV: PRESENTASI AL-QUR’AN TENTANG YAHUDI: TEKS DAN KONTEKS..........................................................................152
A. Narasi Kehidupan Bangsa Yahudi......................................................1531. Dari Keturunan Khalīl Allāh...........................................................1542. Perbudakan di Mesir.......................................................................1623. Exodus dan Pengembaraan di Sinai................................................1754. Kehidupan di Kanaan......................................................................188
B. Pandangan Keagamaan Umat Yahudi................................................2081. Monoteisme.....................................................................................2092. Perjanjian dengan Tuhan.................................................................2183. Siapa Umat Pilihan?........................................................................2324. Tentang Kehidupan di Akhirat........................................................246
C. Mentalitas dan Intelektualitas Umat Yahudi.......................................2591. Membangkang dan Membunuh para Nabi......................................2602. Berdalih dan Berhilah.....................................................................2713. Tidak Konsisten dalam Beragama..................................................2864. Materialistik....................................................................................292
BAB V: HUBUNGAN YAHUDI-MUSLIM DALAM KONTEKS PLURALISME AGAMA........................................................................296
A. Islam dan Pluralisme Agama..............................................................299B. Problem Teologi Islam.......................................................................310
1. Konsep Tah}rīf...............................................................................3112. Konsep al-Nāsikh wa al- Mansūkh.................................................323
C. Kebenaran dan Salvation....................................................................333D. Cita-cita Perdamaian...........................................................................343E. Adakah Genuine Pluralism?...............................................................351
BAB VI:P E N U T U P.............................................................................357
A. Kesimpulan...........................................................................................357B. Saran.....................................................................................................359
BIBLIOGRAFI.........................................................................................................362
LAMPIRAN.................................................................................................................I
CURRICULUM VITAE
xxii
BAB IPENDAHULUAN
FUTURE historians, it has been said, will look back upon the twentieth century not primarily for its scientific achievements but as the century of the coming-together of peoples, when all mankind for the first time became one community.1
A. Latar Belakang Masalah
Sejak abad 20 telah mulai muncul kesadaran umat manusia tentang adanya
kesatuan global, yakni adanya ketergantungan satu umat dengan lainnya dan
keperluan akan saling memahami serta memberi respek antara sesama manusia,
meski memiliki pandangan atau ideologi berbeda. Sekat-sekat budaya, agama dan
nasionalitas mulai runtuh – sebuah fenomena yang sebelumnya tidak pernah
terbayangkan, baik oleh tukang ramal atau para ilmuwan. Persoalan pluralisme
agama mulai mencuat ke permukaan dan dibicarakan secara serius oleh berbagai
kalangan, termasuk agamawan sendiri. Jika sebelumnya perbedaan agama acap kali
mengantarkan para pemeluk agama yang satu memusuhi pemeluk agama yang lain
dan bahkan saling menumpahkan darah, maka di zaman yang disebut “global” ini
mereka niscaya dituntut untuk saling menghargai dan menghormati, sebab jika tidak
maka dikhawatirkan destruksi dan malapetaka akan semakin menjadikan dunia ini
bagai neraka. Dunia sudah sangat fragile: mudah dibangun; lebih mudah lagi
1Wilfred Cantwell Smith, “Comparative Religion: Whither—and Why?”, dalam Mircea Eliade and Joseph M. Kitagawa (ed.), The History of Religions: Essays in Methodology, (Chicago: The University of Chicago Press, 1959), 33.
1
2
dihancurkan. Namun demikian, membangun kesadaran diri dan menempatkan diri
secara proporsional di tengah-tengah globalisme peradaban dunia tidaklah mudah.
Diperlukan banyak energi untuk usaha tersebut dan diperlukan usaha keras setiap
pemeluk agama untuk sukses mengukuhkan diri sebagai bagian dari umat manusia
yang rindu akan persaudaraan dan perdamaian.
Akhir-akhir ini, dalam konteks dan harapan idealitas kehidupan seperti
tersebut di atas, hubungan Yahudi-Muslim ternyata semakin ditantang oleh berbagai
persoalan politik dan ideologi. Perebutan wilayah geografis dan kekuasaan politik di
Timur Tengah, yang melibatkan berbagai kepentingan internasional, telah
memainkan peran penting dalam menumbuhkan kesan semakin negatif pada masing-
masing pihak terhadap pihak lain dan bahkan telah merambat ke dalam pikiran dan
suasana hati banyak orang di dunia ini, baik Yahudi maupun Muslim, akibat dari
provokasi dan ketakutan (fear) yang ditiupkan ke dalam jiwa kebanyakan orang
awam secara tidak henti-hentinya oleh mereka yang terlalu berambisi dan ingin
menang sendiri. Akibatnya, agama dan kekerasan seolah-olah tidak dapat lagi
dipisahkan; kemerdekaan telah diartikan sebagai kemampuan mengalahkan dan
menundukkan lawan. Pada saat-saat agama telah dijadikan alat untuk kepentingan-
kepentingan tertentu, maka tidak ada jalan bagi seseorang untuk “membebaskan diri”
dari kemelut tersebut melainkan dengan cara mengklarifikasi pemahamannya
terhadap agama itu sendiri. Upaya memberikan klarifikasi inilah yang merupakan
titik keresahan awal yang mendorong penulis melakukan studi ini.
3
Agama adalah wilayah perbincangan yang amat luas. Karena itu studi ini
dibatasi pada kajian ayat-ayat al-Qur’an tentang Yahudi.2 Dengan kata lain, dapat
dijelaskan bahwa wilayah “garapan” yang dipergunakan untuk tulisan ini adalah
studi al-Qur’an, dengan mengangkat salah satu sisi pandang kitab suci tersebut
tentang sebuah komunitas yang mungkin dapat dikatakan unik3 dalam sejarah umat
manusia, yaitu Yahudi.
Sebagai sebuah teks – seperti teks-teks lainnya juga – Kitab Suci al-Qur’an
memiliki sifat-sifat kesejarahan dan kebudayaan tersendiri yang khas. Kekhususan
atau keunikan al-Qur’an terletak pada kenyataan bahwa ia adalah teks yang aktif
merespon sejarah, budaya dan realitas lingkungan masyarakatnya. Diturunkan di
tengah-tengah masyarakat jahiliah dan kaum Ahli Kitab (Ahl al-Kitāb), al-Qur’an
bersikap kritis dan juga korektif terhadap berbagai gagasan dan konsep-konsep
tradisional yang dianggap melanggar garis-garis kebenaran dan keadilan primordial
yang telah digariskan Tuhan. Sekurang-kurangnya ada tiga umat yang dihadapi al-
Qur’an pada saat ia diturunkan, yaitu kaum penyembah berhala, orang-orang Yahudi
dan orang-orang Nasrani/Masehi. Semua kelompok ini telah memiliki konsep-konsep
2Yahudi yang dimaksudkan di sini adalah umat Yahudi dalam pengertian luas, termasuk Bani Israil serta tradisi dan ajaran yang mereka anut.
3Al-Qur’an menyebut bangsa Yahudi sebagai umat pilihan (Q.S. al-Dukhān: 32). Namun ulama Islam umumnya menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa mereka (bangsa Yahudi/Israel) adalah umat pilihan pada zamannya. Maksudnya, sekarang mereka bukan umat pilihan lagi, sebab “zaman Yahudi” telah berlalu, sedangkan sekarang adalah “zaman Islam.” Jadi yang dianggap umat pilihan sekarang adalah kaum Muslim. Pencermatan terhadap pandangan tersebut memperlihatkan adanya bias kultural di dalamnya. Dalam kenyataannya, sampai sekarang Yahudi masih eksis dan merupakan bangsa yang diperhitungkan, baik dalam bidang ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Lagi pula, sesungguhnya peradaban tidak dapat dibatasi dengan garis-garis geografis dan sejarah. Istilah “zaman Yahudi” dan “zaman Islam” dapat membingungkan, tidak jauh berbeda dari istilah “negara Yahudi” dan “negara Islam”; yang terakhir ini terkait dengan politik. Politik atau kekuasaan juga sering “mengacaukan.” Barangkali akan lebih tepat jika mufassir (ulama Islam) memberikan penjelasan lain yang lebih mengacu pada prinsip-prinsip universal.
4
keagamaan yang mapan, sehingga al-Qur’an bersikap sangat hati-hati, namun juga
sangat tegas, dalam menghadapi mereka. Banyak tradisi Arab sebelum Islam yang
diadopsi al-Qur’an dengan memberikan beberapa modifikasi, seperti perkawinan,
tata krama dalam kehidupan sosial dan sistem peribadatan di sekitar Tanah Haram.
Di samping itu ada juga kritik-kritik yang dilancarkan secara evolutif, seperti yang
berkaitan dengan larangan mengkonsumsikan khamr. Kritik yang berkaitan dengan
konsep-konsep teologi dan dasar-dasar kemanusiaan disampaikan al-Qur’an secara
lebih tegas dan bahkan keras. Dalam hal ini al-Qur’an tanpa kompromi menolak,
misalnya, penyembahan berhala, konsep ketuhanan Isa Almasih dan klaim orang-
orang Yahudi sebagai umat pilihan (semata-mata karena beridentitas Yahudi). Secara
umum dapat dikatakan bahwa al-Qur’an, di samping telah membentuk sebuah
pandangan keagamaan tersendiri, juga telah membangun sebuah sikap keagamaan
tertentu terhadap penganut agama lain yang ikut terlibat dalam interaksi sosial-
budaya sepanjang sejarah kelahiran Islam, yakni sepanjang proses sejarah turunnya
al-Qur’an.
Kaum Ahli Kitab, terutama kalangan Yahudi, adalah komunitas yang
termasuk menonjol keterlibatannya dalam perkembangan pembentukan keyakinan
Islam. Kelompok ini sering kali berhadapan dengan Nabi, baik dalam suasana
keakraban maupun permusuhan. Komunikasi dan interaksi mereka dengan Nabi dan
kaum Muslim telah menyebabkan banyak ayat al-Qur’an turun memberi respon, dan
hubungan ini dalam beberapa hal berakhir dengan konflik. Memang harus diakui
bahwa pada dasarnya yang menjadi sasaran awal al-Qur’an adalah situasi kota
5
Mekkah dengan kehidupan para elitnya yang korup,4 namun kemudian, tidak
terhindarkan, masyarakat Yahudi dan Nasrani ikut terlibat, sebab dalam pandangan
al-Qur’an manusia sesungguhnya adalah umat yang satu.5 Untuk mengajak manusia
melaksanakan kebaikan dan meninggalkan tindakan-tindakan jahat dan tidak
bermoral, pertama sekali yang harus dilakukan adalah meyakinkan mereka akan
adanya konsekuensi-konsekuensi dari semua perbuatannya: kebaikan akan dibalas
dengan pahala yang besar, sedangkan kejahatan akan mendatangkan malapetaka
yang sangat merugikan. Karena itu al-Qur’an selalu menekankan pentingnya beriman
kepada Allah dan hari akhirat serta beramal saleh. Berangkat dari keyakinan inilah
persoalan-persoalan teologi mulai muncul, dan para penentang Nabi di Mekkah
sering kali menjadikan orang-orang Yahudi sebagai konsultan mereka untuk
mendapatkan argumentasi melawan Nabi. Akibatnya, al-Qur’an kemudian bukan
hanya mengkritik konsep-konsep teologi orang Yahudi yang dianggap menyimpang
tetapi juga “membongkar” berbagai perilaku mereka dalam sejarah.
Nabi Muhammad pada awalnya menaruh harapan besar pada orang-orang
Yahudi sebagai pendukung bagi agama yang sedang beliau dakwahkan, sebab beliau
menganggap mereka memiliki basis keyakinan yang bersumber pada ajaran yang
sejalan dengan agama yang beliau bawa. Interaksi Nabi dan kaum Muslim di satu
pihak dengan kaum Yahudi di pihak lain kemudian menjadi intens, dan wahyu pun
turun memberikan berbagai tanggapan, mengkritik dan pada akhirnya bahkan
mengecam tindakan-tindakan mereka yang ternyata tidak seperti diharapkan, yakni
4Fazlur Rahman “Islam’s Attitude Toward Judaism,” The Muslim World, Vol. LXXII, No. 1, January, 1982, 1.
5Q.S. al-Baqarah: 213.
6
justeru menjadi penentang utama terhadap risalah yang dibawa Nabi.6 Perkembangan
sikap al-Qur’an terhadap Yahudi ini menarik, karena ia bergerak seiring dengan
perkembangan kondisi politik dan pembentukan masyarakat Muslim masa awal. Lagi
pula, ini menjadi indikasi bagi watak historisitas (kesejarahan) teks al-Qur’an –
sebuah wacana kontemporer yang tampak masih hangat diperdebatkan. Namun, yang
lebih penting di sini adalah kenyataan bahwa karena demikian seringnya al-Qur’an
menyebut tentang Yahudi, tidak jarang kaum Muslim menganggap al-Qur’an telah
cukup memadai sebagai referensi untuk mengetahui apa yang perlu diketahui
mengenai Yahudi tanpa memerlukan sumber-sumber lain. Fenomena ini merupakan
keresahan berikutnya (barangkali keresahan yang lebih bernada akademik) yang
menggerakkan keinginan penulis melakukan studi ini: bahwa kajian tentang ayat-
ayat mengenai Yahudi dalam al-Qur’an perlu ditelaah kembali dengan semangat dan
pendekatan yang lebih “objektif” dan ilmiah.
Studi al-Qur’an dapat disebut sebagai kajian yang independent, namun ia
sangat luas dan memiliki hubungan yang erat dengan berbagai studi Islam lainnya
seperti fikih, hadis, dan sejarah. Karena itu – di samping karena keberadaannya
sebagai sumber utama ajaran Islam – al-Qur’an sangat penting dikaji, dan menempati
posisi sentral dalam studi Islam. Al-Qur’an sebagai teks kitab suci selalu dapat
ditafsirkan, selalu membuka peluang yang besar bagi telaah hermeneutika dan
6Beberapa riwayat menyebutkan bagaimana misalnya orang-orang Yahudi melakukan konspirasi dengan kaum musyrik Mekkah untuk menentang Nabi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan atau bahkan menyulut api pertikaian; pada kesempatan lain juga diriwayatkan sejumlah ayat al-Qur’an diturunkan dalam rangka meresponi secara langsung sikap negatif orang-orang Yahudi terhadap Islam dan Nabi Muhammad (misalnya riwayat sabab al-nuzūl [sebab turun] ayat Q.S. al-Baqarah: 80-98, al-Isrā’: 85 dan al-Kahf: 83). Lihat misalnya karangan Abū al-H{asan ‘Alī al-Wāh}idī, Asbāb al-Nuzūl, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994/1414), 15-17, 163, 167.
7
berbagai upaya rekonstruksi terhadap makna dari pesan-pesan Ilahi yang terkandung
di dalamnya. Beragam kitab tafsir telah ditulis dari zaman ke zaman, yang mencoba
menggali makna-makna di balik teks, dengan menggunakan pendekatan yang
berbeda-beda dan penekanan pada spesialisasi masing-masing. Ibn ‘Arabī,7 misalnya,
telah menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan pendekatan teosofinya, al-Rāzī8
dengan pendekatan filosofisnya, dan Sayyid Qut}b9 dengan pendekatan sastranya.
Kekayaan literatur dalam studi al-Qur’an sangat massive: semua persoalan
kelihatan sudah pernah dibahas dan mungkin bahkan telah “tumpang-tindih.”
Quranic literature, kata ‘Abdullah Yūsuf ‘Alī, is so voluminous that no single man
can compass a perusal of the whole.10 Baik Muslim maupun non-Muslim, seperti
dikatakan Fazlur Rahman, telah menghasilkan karya yang cukup banyak mengenai
al-Qur’an.11 Lalu apakah al-Qur’an perlu dikaji kembali? Belum cukupkah literatur
yang kaya raya tersebut menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk memahami
al-Qur’an? Jika ilmu pengetahuan dan perkembangan budaya manusia tidak pernah
berhenti, maka semestinya teks-teks kitab suci, yang berbicara dengan bahasa
universal, juga selalu dapat dikembangkan dan dimaknai kembali dalam paradigma
7Muh}y al-Dīn Ibn ‘Arabī, Tafsīr Ibn ‘Arabī, (Beirut: Dār al-S}ādir, t.t.), 2 Volume.
8Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Mafātih} al-Ghayb, (Mekkah: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1990), 32 Volume.
9Sayyid Qut}b, Fī Z{ilāl al-Qur’ān, (Beirut: Dār Ih}ya’ al-Turāth al-‘Arabī, 1971), 8 Volume; Terdapat juga Fī Z{ilāl al-Qur’ān, Edisi CD-ROM, (Jordan: Arabic Textware), 4012 halaman.
10‘Abdullah Yūsuf ‘Alī, The Meaning of the Holy Qur’ān, (Maryland: Amana Corporation, New ed. 1992), xv.
11Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), xi.
8
baru. Dalam dunia ilmu selalu terbuka celah untuk dimasuki, selalu ada teori untuk
ditinjau ulang, dan selalu ada statemen yang perlu direvisi dan diperbaiki.
Menafsirkan kembali ayat-ayat al-Qur’an yang telah pernah ditafsirkan berulang kali
adalah konsekuensi logis dari kesadaran akan perkembangan ilmu pengetahuan dan
perubahan sosial-budaya manusia tersebut.
Mengapa Yahudi dalam al-Qur’an? Persoalan tentang Yahudi telah menjadi
topik penting bukan hanya karena jarang diangkat secara serius dalam diskursus
keislaman dengan pendekatan yang objektif dan apresiatif, tetapi juga karena sering
kali disalahpahami, diperalat untuk kepentingan politik tertentu serta dipandang
penuh kecurigaan. Yahudi sebagai sebuah agama menempati posisi yang tersudutkan
dalam wacana dialog antar agama kontemporer, sampai saat-saat yang paling
terakhir, khususnya dialog Yahudi-Islam.12 Begitu pula Yahudi sebagai sebuah
bangsa atau ras telah tercabik-cabik oleh kebencian dan tercampak bagai sampah
dalam sejarah dan pergumulan politik bangsa-bangsa di dunia. Sejarah Eropa penuh
dengan lumuran darah bangsa Yahudi,13 dan literatur Islam juga tidak sunyi dari
12Sementara dialog Yahudi-Kristen (dan Juga Islam-Kristen) telah sangat banyak berlangsung, dialog Islam-Yahudi mengenai persoalan-persoalan kontemporer hampir bisa dikatakan tidak terjadi, di antara lain sebagai akibat dari berbagai ketegangan politik sejak pembentukan negara Israel. Lihat Louis Jacobs, The Jewish Religion: A Companion, (Oxford: Oxford University Press, 1995), 273.
13Sejak orang-orang Nasrani Eropa bergerak dengan semangat Perang Salib pada abad XI banyak sekali orang-orang Yahudi yang dipaksa masuk agama Nasrani atau dibunuh secara massal sebagai upaya balas dendam: Yahudi dikatakan telah membunuh Tuhan mereka (Yesus). Kebencian ini terus berlangsung sampai abad modern yang puncaknya adalah peristiwa the Holocaust: pembunuhan massal terhadap (laki-laki, perempuan dan anak-anak) Yahudi dalam bentuk yang sangat mengerikan oleh Nazi Jerman – sebuah skandal kemanusiaan yang, barangkali, terdahsyat sepanjang sejarah. Lihat Hamid Basyaib, “Perspektif Sejarah Hubungan Islam dan Yahudi,” dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), Passing Over: Melintas Batas Agama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 352-360. Lihat juga Lewis M Hopfe dan Mark R. Woodward, Religions of the World, (New Jersy: Prentice Hall, 1998), 275-286. Namun perlu dicatat bahwa masih ada polemik tentang sikap Nasrani mengenai peristiwa the Holocaust. Perlu juga dipertanyakan motif
9
cercaan dan kutukan terhadap bangsa tersebut.14 Yahudi telah menjadi simbol Iblis,
dan seluruh kejahatan, baik politik, ekonomi ataupun lainnya di dunia ini dianggap
tidak lain melainkan rekayasa orang-orang Yahudi. Ini adalah pemandangan yang
amat menyedihkan dan perlu dicermati ulang dengan penuh kehati-hatian dan pikiran
terbuka. Nilai-nilai kemanusiaan dan kesucian dalam budaya dan komunitas mana
pun pada dasarnya harus diselamatkan, dengan segala upaya, sekecil apa pun upaya
tersebut dimiliki.
Mengapa al-Qur’an yang dijadikan titik keberangkatan? Sejumlah ayat al-
Qur’an, sebagaimana telah disinggung di atas, telah mengkritik kaum Yahudi atau
Bani Israil, atau Ahli Kitab secara umum.15 Tetapi di samping itu terdapat pula ayat-
ayat yang menempatkan mereka secara netral dan bahkan memuji.16 Tetapi para
komentator Muslim tradisional telah sering kali menakwilkan ayat-ayat yang terakhir
ini untuk mengalahkan yang pertama,17 atau mereka menggeneralisasikan ayat-ayat
yang mungkin berbicara secara spesifik mengenai sebuah komunitas Yahudi tertentu
dominan yang telah memicu peristiwa tersebut: apakah politik, ekonomi, agama atau sentimen rasial. Semuanya tentu ada dengan kadar yang berbeda.
14Dalam sebuah konferensi yang diadakan oleh The Academy of Islamic Research Universitas al-Azhar pada tahun 1968, misalnya, orang-orang Yahudi berulang kali dirujuk sebagai “musuh Tuhan,” “musuh kemanusiaan,” atau “anjing-anjing kemanusiaan.” Lihat D. F. Green (ed.), Arab Theologians on Jews and Israel, (Genève, 1974), khususnya halaman 2. Contoh lain adalah risalah Ibn H}azm yang berbunyi: Al-Radd ‘alā ibn al-Naghrīla al-Yahūd, la‘anahu Allah, seperti dikutip oleh Camilla Adang, Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible from Ibn Rabban to Ibn Hazm, (Leiden: E. J. Brill, 1996), 67. Buku-buku dalam bahasa Indonesia juga sudah banyak disusun, baik dalam bentuk orisinal, terjemahan atau saduran, yang mengungkapkan berbagai cercaan terhadap Yahudi dengan merujuk pada literatur Islam dan al-Qur’an. Misalnya, Drs M. Thalib telah menyusun sebuah buku yang disadur dari tafsir al-Marāghī dengan judul 76 Karakter Yahudi dalam al-Qur’an, (Solo: Pustaka Mantiq, t.t.). Semua karakter yang dimaksudkan adalah sifat-sifat negatif dan cercaan semata.
15Misalnya Q.S. al-Baqarah: 140 dan Āli ‘Imrān: 67.
16Misalnya Q.S. al-Baqarah: 62; Āli ‘Imrān: 64 dan al-Dukhān: 32.
10
kepada semua umat Yahudi. Pandangan-pandangan mereka patut – atas dasar
universalitas pesan-pesan al-Qur’an – dikritisi atau ditelaah ulang, dan mereka dapat
saja diragukan sebagai telah membangun sebuah penafsiran yang berlandas pada
penilaian yang fair dan objektif. Maka mengkaji teks al-Qur’an yang berbicara
tentang Yahudi dan Bani Israil untuk merekonstruksi tafsiran terhadap teks tersebut
dalam paradigma baru yang relevan dengan semangat pluralitas adalah sebuah
tuntutan bagi mereka yang mendahulukan keterbukaan daripada fanatisme,
persaudaraan daripada permusuhan. Terlebih lagi, semua orang dapat menyaksikan
bahwa konflik “Arab-Israel” sampai sekarang belum kunjung selesai – sebuah
tragedi yang telah melahirkan ekstremisme di kedua belah pihak. Kaum Yahudi
mengklaim Palestina sebagai tanah mereka yang dijanjikan Tuhan dengan “sertifikat
suci” yang turun dari langit, meski, menurut Ahmad Deedat,18 ironis sekali bahwa 75
% dari mereka tidak percaya pada Tuhan. Sementara itu kaum Muslim, di satu sisi
menilai pendudukan Israel di Palestina sebagai sebuah penjajahan yang bersamanya
ikut mengalir kepentingan imperialisme Barat, dan di sisi lain melihat kenyataan
tersebut sebagai sebuah tantangan yang menuntut semangat “jihad” untuk membela
kebenaran Islam dan melawan “Yahudi terkutuk, musuh Tuhan dan musuh manusia
sepanjang zaman.” Tetapi satu hal penting dicatat, bahwa para sarjana Muslim,
seperti yang dikatakan al-Faruqi, perlu berhati-hati untuk tidak mencampuradukkan
antara Judaism dan Zionism. Dismantling the Zionist state does not necessarily mean
17Fazlur Rahman, Major Themes, khususnya Appendix II, 166. Lihat juga M. Amin Abdullah, “Al-Qur’an dan Pluralisme dalam Wacana Posmodernisme,” Profetika, (Vol.1, 1 Januari 1999), 7.
18Ahmad Deedat, Dialog Islam dan Yahudi: Damai atau Terus Konflik, terj. Djamaluddin Albunny, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1991), 47-48.
11
the destruction of Jewish lives or properties.19 Zionisme adalah sebuah gerakan yang
sangat kompleks dan bahkan dianggap sebuah paradoks yang sangat berbahaya oleh
kalangan Yahudi ortodoks sendiri.20 Seperti yang terjadi dalam hampir semua
gerakan politik, agama selalu ditarik ke depan oleh sebagian orang (mungkin karena
prejudice, fanatik atau kepentingan-kepentingan lain) untuk dijadikan “perisai” bagi
interes personal atau kelompok, dan sebagai pemberi justifikasi bagi segala sesuatu
yang diinginkan. Berbagai faktor politik, ekonomi dan sosial budaya ternyata telah
memainkan perannya dalam hermeneutika para sarjana Muslim (juga non-Muslim,
tentunya). Ini bukanlah fokus tulisan ini, tetapi termasuk persoalan menarik dan perlu
mendapatkan perhatian serius untuk kajian lebih jauh.
Kajian ini difokuskan pada analisis terhadap presentasi al-Qur’an tentang
Yahudi. Seperti telah disebutkan, al-Qur’an berbicara sangat banyak tentang Yahudi,
dan sepertinya, umat inilah yang telah menyita perhatian yang lebih serius dan
intensif dari kitab suci Islam dibanding umat-umat lain, selain umat Islam sendiri;
bahkan ketika al-Qur’an berbicara mengenai Ahli Kitab (Ahl al-Kitāb), pada
umumnya yang dimaksudkan adalah umat Yahudi.21 Al-Qur’an kelihatannya bukan
hanya merespon sikap kaum Yahudi pada zaman Nabi Muhammad, tetapi juga
membeberkan sejarah mereka yang panjang, pandangan keagamaan mereka, dan
19Ismail R. Al-Faruqi, “Islam and Zionism,” dalam John L. Esposito (ed.), Voices of Resurgent Islam, (Oxford: Oxford University Press, 1983), 262.
20Ravitzky Aviezer, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, trans. Michael Swirsky and Jonathan Chipman, (Chicago: Chicago University Press, 1996), 10.
21Hal ini akan jelas ketika ayat-ayat tentang ahl al-Kitāb dilihat dalam konteks atau sebab turunnya, seperti dikatakan Syarif Khalīl Sukkar ketika menulis Muqaddimah untuk karya ‘Afīf ‘Abd al-Fattāh} T{abbārah, Al-Yahūd fī al-Qur’ān, (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1986), 7.
12
berbagai tingkah laku mereka sepanjang sejarah, baik positif maupun negatif. Karena
itu sebuah penelaahan yang cermat sangat diperlukan untuk menjelaskan kembali
bagaimana hubungan al-Qur’an dengan orang-orang Yahudi dan bagaimana al-
Qur’an mempersepsikan mereka sebagai sebuah bangsa dan juga sebagai sebuah
komunitas keagamaan.
Sampai pada poin ini dapat dikatakan bahwa Yahudi mendapat tempat yang
“spesial” dalam Kitab Suci al-Qur’an. Kenyataan sejarah juga menunjukkan bahwa
mereka inilah satu-satunya kelompok keagamaan yang paling intens berinteraksi
dengan Nabi Muhammad sebagai pembawa al-Qur’an. Dengan kata lain, mereka
adalah kelompok yang ikut berperan dalam membentuk milieu masyarakat penerima
al-Qur’an. Lebih jauh lagi, para komentator Muslim juga telah secara ekstensif
mengutip tradisi Yahudi untuk memenuhi lembaran-lembaran karya tafsir mereka,
meski validitas tindakan ini masih dalam ikhtilāf. Fakta-fakta ini menjadi alasan bagi
pentingnya menelaah kembali perspektif al-Qur’an tentang Yahudi, mengingat telah
memburuknya hubungan umat ini dengan kaum Muslim pada masa-masa terakhir.
Proyek ini merupakan sebuah studi untuk mengeksplorasi persoalan tersebut
di atas dalam kaitannya dengan isu-isu kontemporer tentang pluralisme agama. Kitab
suci agama (al-Qur’an) di sini dijadikan basis atau titik keberangkatan karena ia (al-
Qur’an, dan juga kitab suci semua agama) adalah sumber yang paling potensial untuk
menjelaskan dan mengembangkan berbagai wacana yang berkaitan dengan isu
keagamaan termasuk pluralisme agama; dan sebaliknya, ia bahkan dapat juga
menjadi sangat potensial untuk dijadikan pengundang petaka, konflik, provokasi dan
bahkan permusuhan antar umat beragama. Hanya dengan pemahaman yang
13
“komprehensif dan utuh” terhadap kitab suci, pokok-pokok ajaran agama akan dapat
ditemukan secara lebih jelas dan jernih, yang pada dasarnya sangat kondusif untuk
dialog antar agama dan wacana “keberagamaan manusia.”22 Inilah latar belakang
yang mendorong penulis melakukan kajian ini: untuk mengkonstruksi kembali
pandangan al-Qur’an tantang “orang lain,” the other, khususnya Yahudi, sekaligus
sebagai kritik diri (self criticism) bagi kaum Muslim, dan juga untuk
menyumbangkan tambahan khazanah pemikiran yang dapat dijadikan pertimbangan
dalam memposisikan diri atau membuat pemetaan diri di tengah-tengah kehidupan
global, dengan cara yang lebih “berwawasan.”
B. Permasalahan: Pertanyaan dan Hipotesis
Yahudi, di hampir seluruh dunia Arab dan Muslim, telah menjadi simbol
segala kejahatan. “Yahudi bangsa terkutuk” demikian dominan mempengaruhi
pikiran kebanyakan Muslim dewasa ini, terlebih sejak munculnya konflik Arab-Israel
yang sampai sekarang belum kunjung selesai.23 Kemunculan negara Israel pada abad
modern (1948)24 bukanlah awal dari kebencian antara kedua umat ini. Kebanyakan
Muslim bahkan mencari legitimasi bagi kebencian tersebut dengan merujuk pada
22M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 63.
23Seorang penulis Aceh bahkan memberi judul bukunya Jahudi Bangsa Terkutuk: Lukisan Kedjahatan Mereka dalam Sejarah, dalam rangka merespon konflik Arab-Israel di Timur Tengah. Lihat A. Hasjmy, Jahudi Bangsa Terkutuk: Lukisan Kedjahatan Mereka dalam Sejarah, (Banda Atjeh: Pustaka Faraby, 1970).
24Ian J. Bickerton dan M.N. Pearson, The Arab-Israeli Conflict, (Melbourn: Longman Cheshire, 2nd edition 1990), 93.
14
peristiwa pengusiran kaum Yahudi Medinah oleh Nabi Muhammad, tanpa
menjelaskan konteks sosial-politik pada waktu itu, atau merujuk kepada al-Qur’an
dengan penakwilan yang lebih bernada emosional ketimbang proporsional.
Diskriminasi dan prejudice terhadap kelompok yang disebut dengan ahl al-dhimmah
(kafir zimmi), terutama sekali sebagai hasil tafsiran para fuqahā’ dan sarjana Muslim
pada masa awal Islam (bahkan sampai sekarang) juga ikut bertanggung jawab atas
hubungan Muslim-Yahudi seperti sekarang ini.25 Kebencian yang telah “menyejarah”
seperti ini perlu ditelaah ulang secara kritis. Dalam dunia yang semakin global,
kesadaran akan pluralitas dengan sendirinya akan berkembang, dan setiap kelompok
tidak bisa memposisikan dirinya sebagai yang superior. Semangat inilah yang
mengusik pemikiran penulis mengenai pandangan al-Qur’an tentang Yahudi yang
dalam sejarah Islam telah diposisikan sebagai kaum terkutuk. Jika Yahudi adalah
terkutuk, bukankah – sebagai konsekuensi logisnya – berarti dunia ini harus
dibersihkan dari jenis masyarakat atau bangsa tersebut? Apakah pandangan seperti
ini realistis? Apakah tidak bertentangan dengan al-Qur’an itu sendiri yang tidak
membeda-bedakan manusia atas dasar suku bangsa,26 tidak memaksa manusia
memeluk agama,27 dan bahkan respek terhadap ahl al-Kitāb (yang umumnya adalah
orang Yahudi)?
Dari uraian di atas, beberapa pertanyaan dapat dirumuskan sebagai berikut:
1). Apa yang menjadi dasar kritik al-Qur’an terhadap orang-orang Yahudi dan sejauh
25Barakat Ahmad, Muhammad and the Jews: A Re-Examination, (New Delhi: Vikas Publishing House, 1979), 4.
26Q.S. al-H{ujurāt: 13.
27Q.S. al-Baqarah: 256.
15
mana kritik-kritik tersebut memberikan implikasi penolakan Islam (al-Qur’an)
terhadap validitas agama mereka? 2). Apakah kritik al-Qur’an ditujukan kepada
semua kaum Yahudi, atau tidak mungkinkah kritik-kritik tersebut hanya ditujukan
kepada Yahudi tertentu yang berada di Arab pada zaman turunnya al-Qur’an? 3).
Wajarkah, apabila diuji dengan semangat ajaran al-Qur’an, dikatakan Yahudi bangsa
terkutuk atau umat paling keji di dunia ini?
Atas dasar pertanyaan-pertanyaan di atas, beberapa hipotesis diajukan di sini:
1). Kritik-kritik al-Qur’an terhadap umat Yahudi pada dasarnya mengacu pada
landasan seruan al-Qur’an sendiri yang bersifat universal, egaliter, terbuka dan
menekankan prinsip-prinsip moral dan keadilan. Al-Qur’an mengkritik orang-orang
Yahudi karena perilaku mereka yang dianggap telah melanggar prinsip-prinsip dasar
tersebut. Lebih jauh mereka dikecam, bahkan disebut sebagai kafir karena berbagai
pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap Islam dan Nabi Muhammad. 2).
Orang-orang Yahudi yang menjadi sasaran kritik al-Qur’an adalah sangat partikular,
yakni orang-orang Yahudi (Medinah) zaman Nabi Muhammad. Karena itu kritik-
kritik tersebut tidak dapat digeneralisasi kepada semua Yahudi di dunia sepanjang
sejarah. Dengan kata lain, bahwa kaum Yahudi, setelah diaspora, telah membentuk
kelompok-kelompok tertentu di berbagai belahan dunia dengan tradisi dan tafsiran
mereka masing-masing atas ajaran agama yang mereka warisi dari Nabi Musa;28
tidak semua mereka memiliki pandangan yang sama, dan kaum Yahudi di Arab,
setelah melalui proses sejarah yang panjang, tentu saja membangun sikap dan
pandangannya sendiri tentang agama. 3). Al-Qur’an telah menunjukkan respek dan
sikap bersahabat terhadap kaum Ahli Kitab, maka alangkah tidak pantas bagi kaum
28Louis Jacob, The Jewish Religion, 123.
16
Muslim memilih jalan lain dalam bersikap terhadap mereka. Al-Qur’an telah
menyeru mereka dengan lembut: ya ahl al-Kitāb ta‘ālaw ilā kalimah sawā’,29 maka
sepantasnya kaum Muslim selalu membuka ruang dialog dalam menyelesaikan
konflik dengan mereka. Al-Qur’an memang pernah menyebutkan bahwa Tuhan telah
mengutuk umat Yahudi,30 tetapi ini harus diperjelas: Yahudi yang mana, kapan dan
dalam konteks yang bagaimana? Seperti telah disebutkan di atas, hal ini tidak dapat
digeneralisasi secara sembarangan, karena al-Qur’an sebenarnya tidak mengenal
kutukan rasial atau kecaman diskriminatif.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Kajian ini diharap dapat memberikan kontribusi dalam bidang studi al-Qur’an
(Qur’anic studies). Sebuah pemahaman baru mengenai pandangan al-Qur’an tentang
Yahudi dicoba untuk dikonstruksikan kembali dalam konteks kontemporer,
khususnya dengan mempertimbangkan isu-isu mengenai pluralisme agama. Para
sarjana Muslim klasik telah banyak sekali membuat statemen negatif mengenai kaum
Yahudi dengan merujuk pada al-Qur’an dan sabda-sabda Nabi. Namun berbagai
telaah yang dilakukan baik oleh para sarjana Muslim maupun non-Muslim
kontemporer terhadap al-Qur’an telah melahirkan nuansa yang berbeda. Jika yang
pertama berbicara dalam kerangka berpikir eksklusif maka yang terakhir lebih
cenderung inklusif. Tujuan dari studi ini, tegasnya, mencoba memberikan
29Q.S. Āli ‘Imrān: 64.
30Misalnya Q.S. al-Mā’idah: 13.
17
pemahaman dan penjelasan yang lebih proporsional dan kritis mengenai persoalan
tersebut di atas.
Dimensi lain dari kontribusi kajian ini lebih mengacu ke arah pembentukan
sikap kelompok beragama itu sendiri. Sebuah sikap yang adil sangat ditentukan oleh
sebuah pemahaman yang jernih. Jika penulis boleh mengklaim bahwa hasil studi ini
akan memberikan sebuah pemahaman yang lebih clear mengenai Yahudi dalam al-
Qur’an, maka ini akan sangat membantu kaum Muslim dan juga umat Yahudi dalam
menata hubungan mereka yang lebih kooperatif untuk membangun dunia masa depan
yang lebih damai. Ini mungkin terdengar berlebihan, tetapi sesungguhnya banyak hal
kecil bila dilakukan secara bersama-sama dan dengan sungguh-sungguh akan
menjadi hal besar dan diperhitungkan, bahkan dapat mengubah dunia dan sejarah.
Konflik atau permusuhan sering kali muncul dari pandangan negatif terhadap
yang lain (the other). “Kita” menjadi sebuah identitas yang eksklusif, karena “kita”
bukan “mereka.” Identitas selalu dikukuhkan dengan memposisikan diri berhadapan
dengan yang lain,31 dan identitas itu terbentuk dalam sebuah proses sejarah, didukung
oleh vested interest sejumlah atau sekelompok orang. Jika teori ini benar maka
sejarah Islam juga ikut bertanggung jawab atas konflik-konflik antar agama. “Kita” –
kita dalam kelompok atau agama mana pun – sangat sulit menerima orang lain, the
other, sebagai partner yang sejajar. “Kita” selalu menganggap diri superior dan yang
lainnya adalah kelompok kelas dua, kelas tiga dan sebagainya. Kaum Muslim selalu
mengklaim dirinya sebagai kelompok yang paling toleran, dengan merujuk pada
“fakta” bahwa jika umat Islam berada di bawah kekuasaan umat lain, maka mereka
31James G. Carrier (ed.), “Introduction,” Occidentalism: Image of the West, (Oxford: Clarendon Press, 1995), 3.
18
akan berada dalam tekanan dan diperlakukan secara tidak adil; sedangkan jika umat
Islam yang berkuasa maka umat lain akan mendapatkan kebebasan dan pengamanan
yang memadai. Namun, toleransi dalam pengertian seperti ini tidak cukup kuat untuk
menjadi landasan membangun dunia yang semakin global dan plural. Karena itu
Bernard Lewis barangkali tepat ketika mempertanyakan apa yang dimaksud dengan
“toleran?” Apakah toleran berarti without persecution atau without discrimination?32
Saling bermusuhan antar penganut agama yang berbeda bukanlah problem
hubungan antar agama, tetapi problem penganut agama itu sendiri. “Kita” selalu
takut kepada “orang lain” karena “kita” merasa superior, dan kehadiran “orang lain”
akan menciptakan semacam gangguan keamanan (insecurity),33 yang dapat merusak
tatanan budaya, tradisi, keyakinan atau apa pun yang “kita” anggap telah mapan dan
final. Perasaan inilah yang sesungguhnya menjadi problem keagamaan paling
penting,34 dan studi ini – meski tidak berpretensi memecahkan problem tersebut –
akan merupakan salah satu upaya ke arah yang diharapkan itu.
Seperti telah disebutkan di atas, dialog dengan Yahudi hampir-hampir saja
tabu dalam pandangan masyarakat Muslim. Lebih jauh lagi, dialog Yahudi-Kristen
juga terhambat oleh berbagai kendala, tidak selancar dialog Islam-Kristen dalam
beberapa dekade terakhir. Padahal Yahudi, Nasrani/Kristen dan Islam adalah tiga
saudara (the three sisters) yang seharusnya bekerja sama membangun dunia yang
lebih damai. Ketiga agama monoteis ini memiliki potensi yang besar dalam
32Bernard Lewis, Islam in History: Ideas, People, and Events in the Middle East, (Chicago: Open Court Publishing Company, 2nd Edition 1993), 148.
33Rita M. Gross, “Religious Pluralism: Some Implications for Judaism,” Journal of Ecumenical Studies, No. 26, Winter 1989, 38.
34Ibid., 30.
19
membangun peradaban dunia. Jika ketiganya terus menerus berseteru, maka yang
akan disaksikan adalah dunia yang semakin terpuruk di masa mendatang. Karena itu,
kajian ini – yang berupaya menelaah pandangan kitab suci umat Islam tentang
Yahudi dengan menggunakan pendekatan hermeneutika dan paradigma pluralisme
agama – diharapkan dapat merupakan sebagian dari upaya awal ke arah
pembangunan tersebut.
Sebagai agama yang mengajak kepada kedamaian dan kebaikan, Islam sudah
semestinya memiliki pandangan yang jelas terhadap keragaman tradisi umat
manusia. Tafsiran kaum Muslim terhadap ajaran Islam sepanjang sejarah telah
dipengaruhi oleh berbagai perkembangan politik dan budaya, karena itu tidak mesti
dianggap selalu tepat dan benar atau telah final. Berhadapan dengan masa depan
yang lebih global, persoalan keberagaman adalah hal yang tidak dapat dielakkan.
Barangkali penelitian seperti ini dapat memberikan sumbangan bagi secercah
harapan untuk membangun pandangan yang lebih kondusif bagi kaum Muslimin
untuk hidup damai bersama umat lain dengan tradisi yang berbeda.
D. Survei Literatur
Sangat banyak tulisan, baik yang dikerjakan oleh para sarjana Muslim atau
non-Muslim, tentang Yahudi dalam kaitannya dengan Islam, Nabi Muhammad dan
al-Qur’an. Namun sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang secara spesifik
membicarakan topik ini dalam perspektif tafsir al-Qur’an, dengan melihat langsung
apa kata kitab suci ini tentang Yahudi, dan memberikan analisa dan elaborasi yang
20
memadai. Para penulis Muslim yang bersimpati, atau sekurang-kurangnya bersikap
netral, terhadap agama lain telah melahirkan banyak karya cemerlang, yang menatap
ayat-ayat al-Qur’an di bawah cahaya pluralisme agama. Akan tetapi sebuah telaah
yang memfokuskan diri pada pengembangan yang lebih luas dalam melihat ayat-ayat
tentang Yahudi (dan tentu saja juga tentang berbagai topik lain) masih sangat
dibutuhkan.
Mohammed Arkoun telah menulis sebuah topik yang agak umum mengenai
masalah ini: “Explorations and Responses: New Perspectives for a Jewish-Christian-
Muslim Dialogue,” namun memberikan nilai yang substansial bagi metodologi
comparative religion. Ia menekankan pentingnya pemahaman kembali makna wah}y
(revelation) dalam ketiga agama tersebut: sebagai kalam Tuhan, manifestasinya
melalui Nabi-nabi kaum Israel, Yesus dan Muhammad, serta sebagai a determining
force in the history of the communities of the Book/book.35
Sebuah karya yang lebih awal adalah Major Themes of the Qur’an oleh
Fazlur Rahman. Buku ini menampilkan topik-topik mendasar tentang pesan-pesan al-
Qur’an. Sejauh yang penulis ketahui, ini adalah karya terbaik yang mengulas ayat-
ayat al-Qur’an di bawah tema-tema tertentu secara komprehensif. Pada bagian
terakhir buku ini dimuat dua Appendix yang relevan dengan rencana studi yang
dilakukan untuk disertasi ini, terutama sekali Appendix II. Di sini Fazlur Rahman
mengulas pandangan al-Qur’an tentang Ahl al-Kitāb (Ahli Kitab): Yahudi, Nasrani
dan S{ābi’īn. Meskipun dengan keras menolak eksklusivisme dan konsep bangsa
pilihan, al-Qur’an, demikian jelas Fazlur Rahman, berulang kali menyatakan
35Mohammed Arkoun, “Explorations and Responses: New Perspectives for a Jewish-Christian-Muslim Dialogue,” Journal of Ecumenical Studies, No. 26, Summer 1989, 526.
21
pengakuannya terhadap eksistensi orang-orang baik dalam komunitas lain seperti
Yahudi dan Nasrani.36 Mengutip Q.S. al-Baqarah: 148 dan 177, Fazlur Rahman
menegaskan bahwa nilai positif dari keberagaman agama adalah bahwa mereka
saling berlomba dalam kebaikan.37
Tulisan lain Fazlur Rahman yang lebih relevan dengan proyek studi ini
adalah “Islam’s Attitude Toward Judaism.” Argumen yang dikemukakan Fazlur
Rahman di sini tidak jauh berbeda dari sebelumnya, bahwa al-Qur’an telah
menempatkan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai komunitas yang memiliki dokumen
wahyu sendiri dan dipanggil dengan nama “Ahl al-Kitāb.” Mereka diajak untuk
melaksanakan ajaran Taurat dan mereka diberikan otonomi sendiri dalam hal agama
dan budaya. Namun al-Qur’an terus mengajak mereka kepada Islam dan memandang
Yesus sebagai seorang Nabi.38 Fazlur Rahman juga dengan tegas menyatakan sangat
menyayangkan situasi politik yang telah menimbulkan kondisi yang sangat tidak
kondusif bagi persahabatan Islam-Yahudi sejak pendirian negara Israel, di mana
Barat sangat berperan dalam menciptakan atmosfer ini. Padahal, kata Fazlur
Rahman, sekitar tiga belas setengah abad setelah zaman kenabian, hubungan kedua
umat ini bukan hanya damai tetapi juga sangat kooperatif dan bermakna.39
Fazlur Rahman dan Mohammed Arkoun, seperti telah didiskusikan sekilas di
atas, telah menulis secara ekstensif tentang al-Qur’an dan di sana-sini menyinggung
36Fazlur Rahman, Major Themes, 166.
37Ibid., 167.
38Fazlur Rahman, “Islam’s Attitude Toward Judaism,” The Muslim World, No. 1, Vol. LXXII, January 1982, 5.
39Ibid., 6.
22
hubungan antar agama serta pandangan al-Qur’an terhadap umat lain. Namun, seperti
telah disebutkan, kajian yang mendalam mengenai tema-tema spesifik dengan
pendekatan dan metode yang mereka terapkan masih sangat diperlukan.
Sebuah karya menarik lain yang menyinggung topik studi ini adalah the
Qur’anic Concept of History oleh Mazheruddin Siddiqi. Bab IV buku ini khusus
berbicara mengenai komentar al-Qur’an tentang sejarah Yahudi. Buku ini
memberikan berbagai informasi berharga, dan komentar-komentar para mufassir
seperti Ibn Katsīr, al-Rāzī dan al-Alūsī dirujuk secara mendetil. Namun concern
buku ini mengenai sejarah semata, sehingga diperlukan telaah lebih lanjut untuk
memahami makna sejarah yang relevan dengan pluralisme agama.40
Patut juga disebutkan di sini sebuah buku yang ditulis oleh Farid Esack,
Dosen Senior dalam bidang Agama di Universitas Western Cape, Afrika Selatan, al-
Qur’an, Liberation and Pluralism. Esack menggunakan pendekatan hermeneutik
dalam membahas ayat-ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan agama dan
pembebasan. Buku ini pada dasarnya berbicara tentang perjuangan masyarakat
Afrika Selatan melawan diskriminasi apartheid (perbedaan ras). Di sini Esack
melihat bahwa perjuangan melawan kezaliman telah menumbuhkan suatu
pemahaman tersendiri dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dalam konteks
pluralisme agama di tengah-tengah masyarakat Muslim Afrika Selatan. Esack secara
panjang lebar mendiskusikan bagaimana sikap al-Qur’an terhadap pemeluk agama
lain, the Other. Ia sangat menyadari bahwa telah muncul dua pandangan yang
ekstrem dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara mengenai
40Mazheruddin Siddiqi, The Qur’anic Concept of History, (Delhi: S. Sajid Ali for Adam Publishers and Distributors, 1994).
23
pemeluk agama lain: Para sarjana Muslim liberal telah meninggalkan ayat-ayat yang
mengecam the Other, sementara kaum tradisionalis dan konservatif telah mengambil
jalan yang disebut dengan forced linguistic, yang memaksa teks-teks inklusif untuk
memproduksikan makna-makna eksklusif.41 Esack menekankan pentingnya
pemahaman yang jernih mengenai masalah ini dengan jalan mempertimbangkan
berbagai konteks sejarah ayat-ayat tersebut. Buku ini telah menyediakan sebuah
tafsiran yang genius tentang pandangan al-Qur’an terhadap kaum non-Muslim,
termasuk Yahudi. Namun buku ini sangat terbatas; ia hanya berbicara dalam konteks
hermeneutika pembebasan.
Buku yang banyak memberikan informasi bermanfaat bagi kajian ini adalah
Ahl al-Kitāb: Makna dan Cakupannya, 42 karya Muhammad Galib M. Buku ini
memberikan informasi mengenai jumlah ayat-ayat yang relevan, pendapat para
ulama, penjelasan semantik terhadap kata-kata dan sebagainya. Buku ini tentu saja
tidak memberikan analisis memadai dari sudut pandang hermeneutika. Artikel yang
senada namun lebih kritis dan relevan dengan kajian ini adalah tulisan Ismatu Ropi
“Wacana Inklusif Ahl al-Kitāb.”43 Ismatu mengkritik pandangan para sarjana Muslim
klasik tentang umat lain, termasuk Yahudi. Pandangan tersebut, menurutnya,
dibangun atas “setting kultural dan suasana religius masa itu.” Lebih lanjut, kata
Ismatu, telah terjadi pula “penyempitan makna” dalam memahami pandangan al-
Qur’an tentang agama lain, sebagai upaya membangun dan mengukuhkan citra diri
41Farid Esack, Qur’an, Liberation and Pluralism, (Oxford: Oneworld Publication, 1998), 147.
42Muhammad Galib M., Ahl al-Kitāb: Makna dan Cakupannya, (Jakarta: Paramadina, 1998).
43Ismatu Ropi, “Wacana Inklusif Ahl al-Kitāb,” Paramadina, Vol. 1 No. 2, 1999, 88.
umat Islam sebagai umat atau komunitas baru pada waktu itu.44 Tulisan ini cukup
menarik, namun tentu saja sangat terbatas dan tidak dielaborasi secara luas dan
mendalam. Tulisan lain yang juga mengarah pada studi ini adalah “Pandangan al-
Qur’an terhadap Bigetisme Yahudi dan Kristen” oleh Hamim Ilyas.45 Penulis ini
berangkat dari kehendak untuk membantah kritikan sementara orientalis, terutama
sekali W. Montgomery Watt, terhadap al-Qur’an mengenai bigetisme Yahudi dan
Kristen. Watt menolak tuduhan al-Qur’an mengenai hal ini dengan alasan tidak
ditemukannya bukti-bukti tersebut dalam literatur Yahudi dan Kristen.46 Hamim
membantah, bahwa absennya sebuah peristiwa sejarah dalam catatan tradisi tertentu
tidak bisa menjadi alasan untuk menolaknya ketika ia diungkap oleh tradisi yang
lain. Argumen kemudian mengacu pada upaya pembelaan terhadap kebenaran al-
Qur’an, namun dengan pengakuan bahwa pernyataan al-Qur’an itu tidak bisa
digeneralisasikan pada semua Yahudi dan Kristen. Artikel ini, meski hanya terfokus
pada persoalan keesaan dan keberanakan Tuhan (bigetisme), dapat menjadi salah
satu dukungan bagi ide-ide pembentukan argumen dalam studi yang penulis lakukan.
Pendekatan yang digunakan Hamim juga hampir sama dengan yang penulis terapkan,
namun tulisan tersebut belum menyentuh aspek pluralisme agama secara mendalam.
44Ibid., 93.
45Hamim Ilyas, “Pandangan al-Qur’an terhadap Bigetisme Yahudi dan Kristen,” al-Jāmi’ah, No. 62/XII/1998.
46Lihat W. Montgomery Watt, Muhammad’s Mecca, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1988), 45.
24
25
The Qur’an and the “Other” yang ditulis oleh Abderrahmane Lakhsassi47
menaruh perhatian yang sangat serius terhadap wacana keberagaman agama dan
dialog antar agama. Lakhsassi menganalisa enam mufassir Muslim, dari al-T{abarī
sampai Sayyid Qut}b dan Fazlur Rahman, dan menyimpulkan bahwa al-Qur’an
sangat fleksibel dan terbuka untuk dikaji sepanjang zaman atau sesuai dengan
konteks sosiokultural mufassirnya. Dalam wacana studi al-Qur’an kontemporer,
demikian menurut Lakhsassi setelah menunjukkan sejumlah alasan, para sarjana
Muslim semestinya meninggalkan doktrin “umat pilihan” dan tuduhan tah{rīf karena
tidak lagi relevan dengan konteks kontemporer di mana pluralisme agama telah
merupakan sebuah kenyataan. Ia mengingatkan bahwa to play with such double
edged doctrines is playing with fire; the wielder of the doctrine can hurt the other but
does not realize that, sooner or later, he also can get hurt.48 Lakhsassi telah
mengungkapkan alasan-alasan yang kuat mengapa kaum Muslim harus
meninggalkan klaim-klaim doktrinalnya yang bersifat eksklusif dan mengkaji
kembali al-Qur’an secara lebih terbuka dan kontekstual. Objek yang menjadi bidikan
analisis Lakhsassi tentu saja berbeda dari concern studi yang penulis ajukan, namun
berbagai argumentasi yang ia tampilkan sangat mendukung.
Mengenai kitab-kitab tafsir, dari klasik hingga modern, tidak perlu
diungkapkan secara mendetil di sini, karena secara umum mereka mengadopsikan
pandangan yang sama tentang posisi teologis penganut agama selain Islam: Bahwa
siapa pun yang tidak memeluk Islam setelah kedatangan Muhammad sebagai utusan
47Abderrahmane Lakhsassi, “The Qur’an dan the “Other”,” dalam Leonard Swilder, Theoria → Praxis: How Jews, Christians, and Muslims Can Together Move from Theory to Practice (Leaven: Peeters, 1998).
48Ibid., 118
26
Tuhan tidak akan selamat. Akan tetapi, ironisnya, di sisi lain, berbagai elaborasi
terhadap kisah-kisah dalam al-Qur’an diambil dari sumber-sumber Yahudi. Analisis
terhadap kitab-kitab tafsir tidak dilakukan di sini, namun kitab-kitab tafsir yang
relevan akan dirujuk dan ditanggapi secara kritis dalam pembahasan nanti. Walaupun
demikian, ada dua buah buku mengenai topik ini perlu disebutkan, yakni al-Yahūd fī
al-Qur’ān karya ‘Afīf ‘Abd al-Fattāh} T{abbārah49 dan Muh{ammad wa al-Yahūd
karya Muh}ammad Ah}mad Barāniq dan Muh}ammad Yūsuf al-Mah}jūb.50 Buku
pertama mengulas ayat-ayat tentang Yahudi dengan pendekatan yang lebih objektif
namun tetap dalam bingkai eksklusivisme. Bagian ketujuh buku ini secara khusus
mendiskusikan ayat-ayat yang mengingatkan kaum Yahudi untuk berlaku lurus dan
bersikap teguh dalam menjalankan perintah kitab (agamanya), namun pada akhirnya
sang penulis menegaskan bahwa hanya yang memeluk Islam di antara mereka yang
selamat.51 Buku yang kedua lebih mengacu pada sejarah dan sikap kaum Yahudi
dalam berinteraksi dengan Nabi Muhammad dan kaum Muslim. Ayat-ayat al-Qur’an
dibahas secara baik namun sangat selektif dan kurang fair. Hanya berbagai
karakteristik negatif Yahudi yang ditonjolkan. Kedua buku ini sangat membantu
memberikan petunjuk bagi berbagai informasi yang diperlukan untuk studi yang
penulis lakukan, tetapi keduanya tetap berbeda secara substansial dan metodologis
dari studi yang dilakukan untuk disertasi ini.
49‘Afīf ‘Abd al-Fattāh} T{abbārah, al-Yahūd.
50Muh}ammad Ah}mad Barāniq dan Muh}ammad Yūsuf al-Mah}jūb, Muh}ammad wa al-Yahūd, (Kairo: Mu’assasah al-Mat{bū‘āt al-H}adīthah, t.t.).
51‘Afīf ‘Abd al-Fattāh} T{abbārah, al-Yahūd, 60-65.
27
Penelitian disertasi ini berada pada posisi bidang tafsir, yakni sebagai kajian
terhadap al-Qur’an dengan penalaran kritis, terbuka dan berupaya untuk “bebas” dari
keterikatan pada dogma-dogma tradisional. Dengan demikian, kajian ini, meskipun
difokuskan pada ayat-ayat tentang Yahudi, diupayakan menjadi sebuah model atau
paradigma pemikiran tafsir “baru,” yang mempertimbangkan berbagai sisi pemikiran
serta merujuk pada aplikabilitas tindakan manusia dalam realitas kehidupan.
E. Landasan Teoretis
Pendekatan untuk penelitian ini didasarkan atas landasan pemikiran bahwa al-
Qur’an adalah sebuah teks – dalam pengertian, ia telah terucap dan tertulis, dan telah
menjadi bagian dari realitas di “bumi” – yang lahir dalam sebuah proses sejarah. Ia
tidak muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba (out of the blue), tetapi bergelut
dengan proses gerak manusia dalam ruang dan rentangan waktu. Al-Qur’an bisa
dikatakan sebagai sebuah respon Ilahi atas keresahan dan pergelutan manusia dengan
dirinya dan alam semesta dalam rangka mencari makna hidup dan kebenaran. Ia
hadir karena adanya kreativitas manusia, dan karena itu ayat-ayatnya harus
dijelaskan dalam konteks tersebut. Al-Qur’an berbicara kepada sebuah masyarakat
tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Ini mengimplikasikan bahwa ayat-ayatnya
berbicara dengan keterbatasan bahasa dan sejarah. Sejarah telah berlalu dan bahasa
(kata-kata) tetap sebagaimana adanya, tetapi makna di balik peristiwa dan kata-kata
selalu dapat dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
peradaban manusia. Kata-kata dalam al-Qur’an tetap sama, tetapi makna yang
28
dipahami manusia dapat berubah, seperti kata Heschel: words remain, while
meanings are subject to change.52
Keterbatasan bahasa dan sejarah tidak berarti telah meninggalkan al-Qur’an
sebagai kitab suci dalam pasungan waktu masa silam. Teks al-Qur’an tetap
sebagaimana adanya, tetapi makna terdalam dari pesan-pesannya akan selalu
memantulkan sinyal ke luar untuk dicerapi oleh manusia sesuai dengan
perkembangan nalarnya. Al-Qur’an berbicara dengan semangat kemanusiaan dan
bersifat universal, karena ia memang dimaksudkan untuk menjadi “petunjuk bagi
manusia.”53 Ini terbukti dari banyaknya pernyataan al-Qur’an yang diungkapkan
dalam bentuk figuratif, simbolik dan bersifat general. Memang ada ayat-ayat al-
Qur’an yang sangat spesifik dan partikular, tetapi ia terkait dengan event, dan harus
dipahami dalam konteksnya. Dalam hal ini al-Qur’an berarti terbuka untuk terus
menerus dikaji dan relevan untuk semua umat pada setiap zaman: Artinya, sebagai
teks kitab suci, maknanya selalu dapat direinterpretasikan sesuai dengan semangat
perkembangan kehidupan yang dihadapi manusia.
Agama, seperti kata Heschel, more than a creed or an ideology and cannot be
understood when detached from acts and events.54 Jadi al-Qur’an sebagai kitab suci
agama juga harus dipahami dalam kondisi yang sama. Makna yang terkandung di
dalamnya selalu terkait dengan “events” baik secara langsung atau tidak langsung.
Dengan memahami dan menerobos ke dalam kesadaran Nabi Muhammad sebagai
52Abraham Joshua Heschel, God in Search of Man: A Philosophy of Judaism, (New York: The Noonday Press, 1998), 9.
53Q.S. al-Baqarah: 185.
54Abraham Joshua Heschel, God in Search, 7.
29
penerima wahyu (penyampai al-Qur’an) dan kondisi sosial masyarakat pada
zamannya, seseorang dapat menemukan realitas yang tersembunyi di balik mereka.
Al-Qur’an, seperti telah disebutkan pada bagian awal bab ini, memuat sangat
banyak ayat-ayat tentang kisah, pandangan keagamaan dan karakteristik kaum
Yahudi. Ini mengisyaratkan intensifnya hubungan mereka dengan Nabi Muhammad.
Namun hampir sepanjang sejarah Islam, seperti terungkap dalam berbagai kitab tafsir
dan berbagai literatur Islam lainnya, hubungan ini selalu dipandang dalam bentuk
negatif. Terlebih, mereka dipandang sebagai penganut agama yang telah mansūkh
dan bahkan memusuhi Islam. Tetapi sejak menjelang abad ke 21 banyak perubahan
dalam tatanan sosial budaya telah terjadi sebagai akibat dari industrialisasi dan
teknologi informasi yang semakin maju dan mengglobal. Kenyataan pluralisme
agama tidak terelakkan. Maka dengan sendirinya pemahaman keagamaan atau
penafsiran kembali teks-teks kitab suci juga harus dilakukan. Memahami kembali
statemen-statemen al-Qur’an tentang Yahudi dengan berlandas pada jalan pikiran
seperti tersebut dalam beberapa paragraf di atas adalah sebuah alternatif. Dengan
kata lain, pembacaan kembali terhadap kitab suci perlu dilakukan dengan paradigma
baru – mungkin dapat disebut sebagai paradigma sosial dan multikultural.55
Dasar-dasar teoritis ini disebutkan, dimaksudkan untuk memberikan
gambaran umum tentang pemikiran yang akan dijadikan pegangan untuk
menjelaskan metodologi dan pendekatan seperti yang didiskusikan pada bagian
berikut.
55Penjelasan lebih jauh, lihat halaman 85 ff.
30
F. Metodologi dan Pendekatan
Apakah ada metodologi terbaik dalam memahami al-Qur’an? Ketika ditanya
tentang tafsir al-Qur’an yang paling baik, H{asan al-Bannā menjawab: “Hatimu!
Hati orang Mukmin adalah tafsir terbaik terhadap Kitab Allah.” Kemudian al-Bannā
melanjutkan: “dan metode pemahaman [al-Qur’an] yang paling mendekati
[kebenaran] adalah dengan jalan seseorang membacanya dengan tadabbur (penuh
perhatian/konsentrasi) dan khusyū‘ (tunduk/penuh penghayatan) serta memohon
petunjuk dari Allah disertai dengan kesungguhan mengerahkan seluruh kemampuan
pikiran pada saat membacanya.”56 Lebih jauh al-Bannā menekankan pentingnya
pemahaman terhadap sejarah hidup Nabi dan sejarah turunnya al-Qur’an untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap ayat-ayat al-Qur’an.
“Pemahaman” itu, kata al-Bannā, adalah cahaya yang terpancar dari lubuk hati.57
Al-Bannā, seorang pemikir Muslim kontemporer serta tokoh dan pendiri
gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn di Mesir, sebenarnya telah mengindikasikan
pentingnya pendekatan hermeneutik dalam memahami al-Qur’an. Di antara kata
kunci dalam hermeneutika adalah “pemahaman.” Al-Bannā memang tidak
mengungkapkannya dengan bahasa yang digunakan dalam wacana pemikiran filsafat
Barat modern dan dengan istilah “analisis teks”, tetapi, seperti terlihat dalam paragraf
di atas, al-Bannā telah mengungkapkan hal tersebut dengan baik sekali dalam bahasa
peradaban populer masyarakatnya sendiri. Al-Bannā kelihatan sama sekali tidak
tertarik dengan apa yang disebut dengan the rules of interpretation seperti yang 56H{asan al-Bannā, Risālatān fī al-Tafsīr wa sūrah al-Fātih}ah, (Beirut: Mansyūrāt
al-‘Ashr al-H}adīth, 1972), 36.
57Ibid., 37.
31
dipahami ulama klasik atau juga kebanyakan ulama zamannya. Ia lebih
mementingkan keterbukaan – yang terindikasi dari istilah khusyū‘ (tunduk [kepada
kebenaran], tidak mendahulukan kepentingan pribadi) yang ia gunakan – dan
independensi, dengan berpegang pada prinsip bahwa setiap “mukmin” memiliki
kapasitas untuk memahami al-Qur’an; dan kapasitas tersebut sangat ditentukan oleh
proses dialektika seseorang dengan sejarah, lingkungan sosial dan peradaban.
Dengan jalan demikian, tafsir ayat-ayat al-Qur’an akan merupakan produk
hermeneutika, produk dari kesadaran subjektif seseorang untuk memberi makna
terhadap teks, produk yang merupakan bagian dari sejarah dan peradaban itu sendiri.
Pandangan Al-Bannā di atas dikemukakan untuk menjelaskan bahwa pada
dasarnya seperti itulah sketsa metodologi yang penulis ingin terapkan untuk
penelitian ini. Penulis sepakat dengan al-Bannā dalam hal memberikan kebebasan
dan ruang gerak yang longgar bagi penafsir atau mufassir untuk mengekspresikan
apa yang ia pahami dari al-Qur’an. Akan tetapi hal ini menimbulkan persoalan ketika
orang memahami kebebasan tersebut sebagai tanpa aturan. Ketika setiap orang
“bertanya kepada hatinya,” mungkin saja masing-masing hati itu akan memberikan
jawaban berbeda. Lalu bagaimana mengukur kebenarannya?
Karena itu penulis perlu mempertegas bahwa penelitian ini dilakukan dengan
menempuh beberapa langkah tertentu, seperti akan dijelaskan di belakang nanti.
Namun sebelumnya perlu dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam
disertasi ini lebih mengacu pada interpretasi teks atau hermeneutika serta gabungan
pendekatan-pendekatan lain, seperti sejarah dan perbandingan. Ada beberapa poin
yang dirasa penting dikemukakan berkaitan dengan teori dalam hermeneutika
32
tersebut: Pertama, teks tidak bisa dijadikan sebagai objek seperti dalam penelitian
atau analisis sains. Ia diperlakukan sebagai buah karya, yang berbicara, yang
memiliki dunia tersendiri, di mana seseorang harus siap meninggalkan dunianya jika
mau masuk ke sana. Teks tidak dipahami melalui apa yang disebut dengan “anatomy
of criticism,” tetapi melalui “humanistic understanding.”58 Ia tidak dibedah untuk
diketahui isinya, tetapi diselami untuk dihayati bersamanya makna-makna yang ia
kandung. Seperti dikatakan Palmer, dalam penelitian harus dibedakan antara
“object” dan “work” (karya), baik karya manusia atau karya Tuhan. Karya harus
dilihat sebagai karya; ia memiliki sentuhan kemanusiaan yang sarat nilai dan makna.
Memahami makna yang lebih filosofis dari sebuah karya itulah yang menjadi fokus
hermeneutika.59 Karena itu dalam memahami sebuah “karya” atau teks diperlukan
kepekaan historis dan humanistik yang tajam. Sehubungan dengan kerangka berpikir
ini al-Qur’an tidak ditafsirkan semata-mata dengan menggunakan the rules of
interpretation yang kaku, seperti dalam pengertian tradisional (meskipun ini tetap
dipertimbangkan), tetapi lebih pada philosophical elaboration of understanding.
Artinya sebuah pernyataan dipahami dengan melihat berbagai kemungkinan yang
dapat mempengaruhi maksud pengarang dan makna yang terkandung dalamnya.
Kedua, seperti telah dikemukakan di atas, teks selalu berkaitan dengan
events. Jadi, proses sejarah yang melahirkan sebuah teks merupakan faktor yang
sangat penting untuk dijadikan pertimbangan. Ini tidak hanya dengan melihat asbāb
58Richard E. Palmer, Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer, (Evanston: Northwestern University Press, 1969), 7.
59Ibid., 7-8.
33
al-nuzūl dalam makna klasik, tetapi juga dengan menerapkan analisis sejarah secara
kritis.
Ketiga, teks juga harus dilihat sebagai bahasa dan simbol yang diungkapkan
dalam suatu waktu dan tempat tertentu. Waktu dan tempat inilah yang perlu
diterobos untuk mendapatkan makna dan pemahaman yang lebih terang dan relevan
dengan zaman sekarang,60 yang dalam istilah Ferguson disebut to span the gap
between the past and present.61 Dalam hal ini tidak berarti al-Qur’an direduksi dan
dipaksakan sesuai dengan kehendak kekinian, tetapi ia dijembatani dengan
menggunakan fasilitas pengetahuan dan pengalaman modern. Penafsir yang hidup
hari ini dapat memaknai teks al-Qur’an yang turun sekian abad silam dengan
memberi makna baru pada teks tersebut tanpa merusak makna dasarnya.62 Barangkali
model pendekatan yang penulis terapkan di sini masih dalam kerangka metodologi
yang disebut Amin Abdullah dengan al-ta’wīl al-‘ilmī63 atau, sebut saja, dalam istilah
lain “mengolah teks, melacak makna.”64 Dengan kata-kata yang lebih sederhana,
kajian ini penulis sebut dengan istilah “tafsir kritis” dan pendekatannya adalah
60Machasin, “Sumbangan Hermeneutika terhadap Ilmu Tafsir,” Makalah Diskusi, Forum Cendekia Muda, Lembaga Studi Agama dan Demokrasi (èLSAD), Surabaya, 2002.
61Duncan S. Ferguson, Biblical Hermeneutics: An Introduction, (London: SCM Press, 1986) p. 3.
62Abū Zayd mengatakan bahwa manusia adalah kā’in tārikhī (historical being), yang mampu menempatkan diri dalam proses sejarah secara dinamis. Sejarah, bagi manusia, bukan hanya sekedar fakta masa lalu “yang berdiri di sana” (qā’im hunāk), tetapi merupakan kenyataan yang terus berubah. Di sinilah peran hermeneutika, yaitu membantu manusia memahami fakta masa lalu dengan memberi makna yang lebih bermanfaat untuk hari ini. Lihat Nas}r H{āmid Abū Zayd, Isykāliyyāt al-Qirā’ah wa Āliyyāt al-Ta’wīl, (al-Dār al-Baid}ā’: al-Markaz al-Tsaqāfī al-‘Arabī, cet. III, 1994, 28.
63M. Amin Abdullah dkk., Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga - Kurnia Kalam Semesta, 2002), 1.
64Ibid., 39.
34
“hermeneutika multikultural.”65 Dalam tafsir ini, yang paling dominan adalah
kepekaan kemanusian, sebuah kepekaan yang mesti tumbuh dari berbagai
pengalaman dan pengetahuan serta pergelutan manusia dengan kehidupan, sejarah
dan peradaban.66
Dalam rangka memenuhi tuntutan metodologis seperti tersebut di atas, maka
langkah-langkah yang ditempuh untuk penelitian ini dapat diringkaskan kembali
sebagai berikut: Pertama, penulis mengumpulkan ayat-ayat al-Qur’an tentang
Yahudi yang terdapat dalam berbagai surat, terutama dalam surat al-Baqarah, dan
membagi-bagikannya dalam topik-topik tertentu. Ayat-ayat tersebut dianalisa
terutama sekali, pada tahap awal, dengan mempelajari pandangan ulama atau para
mufassir untuk didiskusikan dan dikritisi. Untuk tujuan ini yang dirujuk adalah kitab-
kitab tafsir, sejarah dan buku-buku lain yang relevan. Ini mesti dilakukan sebagai
langkah awal karena siapa pun tidak mungkin berangkat dari kekosongan.
Pandangan-pandangan yang sudah ada perlu dijadikan landasan pijakan untuk
membangun sebuah pemikiran baru.
Kedua, penulis melakukan perbandingan antara berbagai statemen al-Qur’an
dengan pandangan-pandangan dan catatan sejarah dalam literatur Yahudi, terutama
sekali kitab Bible Yahudi (Hebrew Bible).67 Artinya, penulis tidak hanya melihat
65Penulis mengadopsi istilah “tafsir kritis” dari Gregory Baum, Religion and Alienation: A Theological Reading of Sociology, (New York: Paulist Press, 1975), 195. Sedangkan istilah “hermeneutika multikultural” (multicultural hermeneutics) penulis pinjam dari Douglas Jacobsen, “Multicultural Evangelical Hermeneutics and Ecumenical Dialogue”, Journal of Ecumenical Studies, Vol. 37, No. 2, Spring 2000, 133.
66Penjelasan lebih jauh mengenai pendekatan kepada al-Qur’an (hermeneutika al-Qur’an) akan dibahas dalam bab dua.
67Kutipan Bible Yahudi (Hebrew Bible) dalam disertasi ini diambil dari terjemahan bahasa Inggris oleh Jewish Publication Society, 1917.
35
pada teks dan konteks ayat-ayat al-Qur’an, tetapi juga berupaya menemukan
bagaimana pandangan Yahudi tentang diri mereka, yakni dengan merujuk pada kitab
suci mereka dan karya-karya sarjana mereka yang otoritatif. Hal ini dianggap
penting, sebab dalam al-Qur’an beberapa kali disebutkan: “... اليهود dan“) ”وقالت
orang-orang Yahudi berkata ….”).68 Maka sekurang-kurangnya perlu dipelajari
bagaimana pandangan orang Yahudi mengenai “tuduhan” al-Qur’an tersebut, untuk
menemukan makna yang lebih tepat dari statemen-statemen al-Qur’an mengenai hal
itu. Langkah ini tidak dilakukan secara mendetail dan menyeluruh, tetapi secara
umum dan terkait dengan topik-topik yang relevan saja, karena yang diperlukan di
sini adalah menemukan contoh-contoh dalam rangka memperkaya argumentasi untuk
perdebatan dan diskusi selanjutnya.
Ketiga, sebagai konsekuensi logis dari metodologi dan pendekatan yang
digunakan untuk penelitian ini, seperti telah dijelaskan di atas, pandangan-pandangan
Muslim tradisional tentang Yahudi, atau pemahaman mereka mengenai ayat-ayat al-
Qur’an tentang Yahudi, akan dikritisi atau ditinjau ulang dengan menghadapkannya
dengan berbagai fakta lain dan pandangan-pandangan lain yang berbeda. Pada
akhirnya, tafsiran ulang terhadap ayat-ayat tersebut dilakukan dengan menggunakan
pertimbangan-pertimbangan yang lebih kritis, terbuka dan lebih aplikatif terhadap
realitas kehidupan di zaman ini.
G. Sistematika Penulisan
68Lihat Q.S. al-Baqarah: 113; al-Mā’idah: 18 dan 64; dan al-Tawbah: 30.
36
Langkah-langkah metodologis tersebut di atas tidak sepenuhnya
mencerminkan sekuens atau urutan dan sistematika penulisan disertasi ini.
Sistematika penulisan lebih berpijak pada the logic of academic mode. Penulis
memulai penulisan dengan mengemukakan alasan-alasan pengkajian dan sejauh
mana ia dapat dianggap krusial dan menarik. Pada bagian pertama ini juga dijelaskan
model pendekatan atau metodologi yang diterapkan, serta beberapa preview landasan
teoretis yang menjadi fondasi penelitian.
Bagian kedua berbicara lebih jauh mengenai landasan teoretis tersebut.
Dalam hal ini, tulisan difokuskan pada teori-teori studi al-Qur’an terutama sekali
yang berbasis pada paradigma pemikiran kontemporer. Teori-teori inilah yang
menjadi bingkai pemikiran yang didiskusikan pada bab selanjutnya.
Bab ketiga adalah bagian awal atau pengantar ke inti proyek penelitian ini,
yakni tentang Yahudi dalam tradisi Islam. Lalu diteruskan dengan bab empat yang
mengeksplorasi dan mendiskusikan secara lebih mendalam mengenai pandangan al-
Qur’an tentang Yahudi. Walaupun hanya dibagi kepada tiga sub bab saja, bab ini
menggunakan proporsi yang cukup signifikan. Analisis lebih jauh tentang eksplorasi
yang dilakukan dalam bab empat diperdalam pada bab lima, yaitu bab yang memuat
kritik dan konstruksi ulang nalar pemikiran keagamaan yang penulis resahkan. Di
sinilah studi al-Qur’an diperdebatkan dan didialogkan dengan nalar pengetahuan dan
pengalaman kehidupan kontemporer. Atas dasar kajian dan diskusi dalam bab-bab
sebelumnya, beberapa kesimpulann dirumuskan dan dimuat dalam bab khusus yaitu
Penutup. Di samping itu, beberapa saran atau rekomendasi juga disampaikan dalam
bab terakhir ini.
37
BAB IIHERMENEUTIKA AL-QUR’AN
BAB ini berisi telaah atas beberapa teori dan konsep tentang tafsir al-Qur’an.
Analisis difokuskan pada metode-metode yang telah secara umum dikenal,
dibincangkan dan diterapkan di kalangan mufassir Muslim. Berangkat dari itu,
penulis mendiskusikan kerangka pikir dan struktur penalaran al-Qur’an yang
digunakan dalam kajian ini. Penjelasan dimulai dengan sebuah refleksi ulang tentang
wahyu, lalu perbincangan secara mendetil mengenai perdebatan dalam cara
memahami al-Qur’an. Pada bagian terakhir bab ini didiskusikan kembali wahyu itu
sebagai firman Tuhan dan tafsir sebagai penalaran manusia atasnya.
A. Al-Qur’an Sebagai Wahyu dan Teks
Al-Qur’an adalah wahyu dari Tuhan. Ini telah menjadi keyakinan umat Islam.
Umat beragama mana pun percaya bahwa kitab sucinya adalah wahyu dari Tuhan.
Namun ketika pertanyaan diteruskan: apa itu wahyu?, maka jawaban akan muncul
beragam. Wahyu terkait dengan sesuatu yang sakral, yang Ilahi dan sering kali
dianggap tidak tersentuh oleh nalar manusia. Wahyu berdiri sendiri di luar nalar, di
batas mana manusia harus tunduk tanpa tanya dan “membungkam” dengan tulus.
Karena itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan wahyu dan bagaimana
38
menempatkan kitab suci di tengah-tengah peradaban tidaklah gampang. Wahyu
adalah firman Tuhan dan karena itu kitab suci mengandung nilai-nilai kesakralan,
keagungan dan bahkan mitos-mitos yang berkelindan di sekitarnya. Berbicara
tentang kitab suci memerlukan “kehati-hatian” di samping “kejujuran” dan
“keberanian”, sebab di belakangnya telah berdiri sekelompok umat yang memujanya;
merusak nilai-nilai kesucian pada sebuah kitab suci sama dengan menyakiti mereka.
Karena itu berbicara tentang kitab suci memerlukan ketulusan hati, keterbukaan dan
tindakan-tindakan yang adil. Al-Qur’an, sebagai kitab suci umat Islam, juga tidak
terkecuali. Ia tidak hanya dibaca dan dipelajari oleh umatnya, tetapi bahkan dipuja
secara berlebihan oleh sebagian mereka. Namun, apa pun sikap yang diambil oleh
setiap individu atau sekelompok umat terhadap kitab sucinya sangat ditentukan oleh
bagaimana ia memaknai “kesucian” dari kitab suci tersebut. Umat Islam percaya
bahwa al-Qur’an adalah firman atau kalam Tuhan; tetapi apa yang dimaksudkan
dengan “firman” dan apa yang dimaksudkan dengan “Tuhan” serta bagaimana
hubungan keduanya dengan manusia, dapat saja berbeda-beda dalam konsepsi setiap
individu; ada yang memahaminya secara literal dan ada yang memahaminya secara
lebih mendalam dan filosofis. Pengalaman hidup (khususnya lagi pengalaman
keagamaan), pengetahuan dan lingkungan peradaban sangat berperan dalam
membentuk pandangan dan pemahaman tersebut. Jadi untuk mendefinisikan al-
Qur’an diperlukan eksplanasi yang lebih kompleks, tidak dapat diputuskan dengan
kesimpulan hitam-putih, meskipun bagi kaum Muslim secara umum hal ini sudah
sangat jelas: bahwa al-Qur’an adalah tuntunan hidup, sebuah petunjuk yang
diturunkan Tuhan untuk menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat.
39
Siapa pun yang berbicara tentang wahyu ataupun mengkaji al-Qur’an perlu
menyadari kondisi ini. Kitab suci adalah bagian dari iman dan kesalehan itu sendiri.
Meskipun al-Qur’an perlu dipelajari dengan pendekatan ilmiah, konteks masyarakat
yang mengimani kitab suci ini juga tidak dapat diabaikan. Namun demikian,
penjelasan lebih jauh diperlukan di sini. Kajian-kajian kontemporer telah melahirkan
interpretasi baru dan mengkritik cara pandang lama terhadap kitab suci. “Kebenaran”
tentang sebuah kitab suci – bahkan terhadap apa pun – ternyata tidak semata-mata
harus bergantung pada keyakinan orang-orang yang mengimaninya. “Keimanan”
bukan tidak mungkin salah; apa yang “diimani” hari ini dapat saja berubah besok;
sebuah keyakinan dapat saja “digugat,” didialogkan kembali dan diperkaya.
Dalam berbagai literatur Islam, al-Qur’an sering didefinisikan sebagai firman
Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk bagi
manusia, dan membacanya adalah ibadah. Dalam al-Wād{ih{ fī ‘Ulūm al-Qur’ān
disebutkan bahwa “al-Qur’an adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang
mengandung mukjizat, yang diwahyukan kepada Muhammad s.a.w. melalui Jibrīl
a.s.; ia diriwayatkan secara mutawātir, ditulis dalam mus}h{af dan membacanya
adalah ibadah; ia dimulai dengan surat al-Fātih{ah dan diakhiri dengan surat al-
Nās.”1 Banyak definisi telah diberikan mengenai al-Qur’an, namun pada esensinya
ada satu unsur yang paling penting dalam pendefinisian tersebut yaitu bahwa al-
Qur’an adalah wah{y dari Tuhan.2 “Ia (al-Qur’an) tidak lain melainkan wahyu yang
1Mus}t}afā Dīb al-Bighā dan Muh}yi al-Dīn Dīb Mastū, al-Wād{ih{ fī ‘Ulūm al-Qur’ān, (Damsyiq: Dār al-Kalim al-T{ayyib, 1996), 15.
2Ibid., 16.
40
diwahyukan.”3 Al-Qur’an adalah kalām atau firman Tuhan, bukan kata-kata manusia;
ia merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad, karena ia melemahkan atau
mengalahkan siapa saja yang menandinginya. Al-Qur’an4 menantang orang-orang
yang mendustakannya dan menegaskan bahwa karya-karya mereka tidak akan pernah
sanggup menandingi ayat-ayat al-Qur’an, walaupun seluruh manusia dan jin
bersekutu untuk melakukannya. Demikian juga dalam ayat yang lain5 al-Qur’an
membantah tuduhan sebagian orang yang mengatakan bahwa ia telah diajarkan oleh
seseorang kepada Muhammad – padahal, demikian al-Qur’an menjelaskan, orang
tersebut adalah seorang ‘ajam sedangkan al-Qur’an diturunkan dengan bahasa Arab
yang terang. Di sini, dengan mengacu pada keunggulan dan keunikan kandungan dan
bahasanya, al-Qur’an ingin membuktikan bahwa ia bukanlah karya manusia
(Muhammad) tetapi ia datang dari Yang Maha Kuasa.
Al-Qur’an adalah wahyu (revelation). Artinya, dalam pengertian populer, al-
Qur’an adalah inspirasi yang datang dari luar diri Nabi Muhammad, yakni dari
Tuhan, bukan ciptaan Nabi. Sang Nabi hanyalah medium untuk mengungkapkan
kehendak dari Tuhan yang Maha Gaib dan menyampaikan pesan-pesan-Nya kepada
sekalian manusia. Nabi tidak pernah mengarang al-Qur’an. Tuhanlah yang telah
memasukkan ayat-ayat itu ke dalam hati Nabi, baik secara langsung maupun dengan
perantaraan malaikat. Ayat-ayat itu datang dan terhunjam ke dalam hati Nabi melalui
sebuah proses yang begitu cepat dan rahasia. Karena itu ia disebut wah}y (wahyu),
yaitu sebuah komunikasi atau penyampaian pesan yang terjadi sangat cepat dan
3Q.S. al-Najm: 4.
4Q.S. al-Baqarah: 23-24, Yūnus: 38, Hūd: 13, al-Isrā’: 88.
5Q.S. al-Nah}l: 103.
41
rahasia. Akan tetapi bagaimanakah proses kedatangan wahyu tersebut dan bagaimana
hubungannya dengan diri Nabi, telah menjadi bahan perbincangan yang
menimbulkan banyak kontroversi.
Banyak teori telah dikemukakan tentang wahyu, baik klasik maupun modern,
baik oleh kalangan Muslim maupun non-Muslim. Para sarjana Muslim lebih banyak
berpijak pada hadis-hadis secara harfiah dan cenderung mengabaikan aspek-aspek
historis dan rasional. Sementara itu, para sarjana non-Muslim umumnya lebih banyak
dipengaruhi oleh prakonsepsi mereka yang dilatarbelakangi oleh tradisi Yudeo-
Kristiani walaupun lebih cenderung rasional dan menekankan pentingnya aspek
kesejarahan. Akan tetapi yang menjadi problem adalah: apakah teori-teori tersebut
cukup memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan? Semua perbincangan
ilmiah tentang al-Qur’an tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kedua basis historis dan
rasional, karena dua landasan itulah yang dapat menjelaskan secara baik watak dan
posisi al-Qur’an sebagai sebuah kitab suci atau wahyu dalam konteks kehidupan
manusia sebagai makhluk peradaban. Akan tetapi aspek ideologis dan etikal-moral
para pelaku sejarah juga tidak boleh dikesampingkan. Untuk itu perhatian akan
diberikan terlebih dahulu pada hubungan wahyu itu dengan Nabi.
Tidak ada kesangsian bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan
ajarannya dengan sebuah keyakinan yang mantap bahwa dirinya adalah utusan
Tuhan, dan apa yang telah ia bacakan kepada para pengikutnya itu, yakni al-Qur’an,
adalah wahyu dari Tuhan. Keyakinan yang tidak tergoyahkan ini terlihat dari sikap,
perilaku dan watak perjuangan yang digerakkan Nabi sejak awal sampai ia wafat.
Kenyataan ini sangat penting dijadikan catatan sebab berbagai argumentasi tentang
42
kewahyuan Kitab Suci al-Qur’an berbasis pada keyakinan Nabi Muhammad bahwa
ia (wahyu tersebut) diturunkan dari Tuhan. Seandainya Nabi Muhammad memiliki
sedikit saja keraguan tentang wahyu yang ia terima itu, maka dengan sendirinya
seluruh argumentasi lain tentang karakteristik risalah yang dibawanya akan porak
poranda dan juga perjuangan yang ia gerakkan tentu telah kandas.
Nabi Muhammad, sejauh interpretasi yang dapat diberikan atas sejarah
hidupnya, tidak pernah menunjukkan sebuah ambisi akan kekuasaan atau posisi yang
tinggi di tengah-tengah masyarakatnya. Ia juga tidak pernah bercita-cita melakukan
sebuah revolusi, perubahan sosial atau membangun sebuah peradaban yang bertujuan
untuk mengharumkan namanya. Muhammad memang tampak dengan jelas
memberikan perhatian dan kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat yang
menggelisahkan dan mempunyai harapan akan adanya sebuah perubahan, namun
tidak berarti ini dapat ditafsirkan sebagai sebuah cita-cita yang secara duniawi
ambisius. Tidak ada bukti yang jelas bahwa sang Nabi telah menyusun sebuah
program atau strategi perjuangan yang konkret untuk menguasai kota Mekkah.
Kenyataan justeru menunjukkan sebaliknya. Nabi Muhammad bahkan khawatir atas
peristiwa yang dikenal dengan penerimaan wahyu pertama itu. Pembawa wahyu
yang datang ke dalam visi Muhammad itu menggetarkannya dan ia menyangka
bahwa sebuah alamat buruk telah menimpa dirinya. Isterinyalah (Khadījah) yang
menenteramkan hatinya dan mengatakan bahwa ia tidak mungkin didatangi oleh
spirit yang jahat sementara ia adalah seorang yang senantiasa berbuat baik dan jujur.
“Mana mungkin Tuhan mencelakaimu: Engkau selalu memelihara persaudaraan,
43
menanggung beban orang lemah, membantu fakir miskin, menghormati tamu dan
senantiasa membela kebenaran.”6
Pernyataan yang dikemukakan oleh Khadījah di atas telah merupakan
karakteristik umum pandangan masyarakat Arab pada waktu itu. Kehormatan dan
kemuliaan akhlak dalam tradisi Arab sejak sebelum Islam adalah inti dari semangat
dan kekuatan masyarakat tersebut. Dalam konteks peradaban tradisional seperti
inilah Muhammad dilahirkan, dibesarkan dan tumbuh menjadi sosok yang dikenal
sangat santun, jujur dan berkepribadian mulia. Kenyataan ini juga menjadi sumber
kekuatan bagi Muhammad dan para pengikutnya dalam berpendirian bahwa ia adalah
seorang Utusan Allah.
Al-Qur’an dengan tegas mendeskripsikan kepribadian Muhammad sebagai
penyandang budi pekerti yang sangat agung.7 Di samping itu al-Qur’an
mengindikasikan bahwa Muhammad hanyalah penyampai berita dari Tuhan. Ia tidak
memiliki kepentingan pribadi apa pun dari aktivitas kenabiannya itu. Muhammad
tidak perlu diuji dengan berbagai kemampuan luar biasa. Ia tidak memilikinya. Jika
seseorang hanya akan percaya kalau Muhammad mampu mendemonstrasikan hal-hal
yang ganjil, maka Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa. Maka jangan tanyakan
kepadanya soal Hari Kiamat. Sekiranya Muhammad mengetahui hal-hal gaib, tentu
ia akan dengan mudah dapat mengumpulkan kekayaan yang banyak dan menghindar
dari berbagai bahaya.
Katakanlah: “Aku tidak memiliki kekuasaan atas manfaat dan mudarat terhadap diriku kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku
6Lihat al-Bukhārī, S{ah}īh} al-Bukhārī, (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1987 M./1407 H.), Vol. 1, 4: Hadis No. 3.
7Q.S. al-Qalam: 4.
44
mengetahui yang gaib, tentu aku telah memperbanyak kebaikan8 dan aku tidak pernah ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.”9
Perhatian yang cermat akan menampakkan bahwa ayat ini mengekspresikan
kemanusiawian Nabi Muhammad dengan cara menunjukkan bahwa dirinya adalah
orang yang bergerak dalam bingkai kemanusiaan yang normal. Nabi tidak
mengetahui persoalan gaib, dengan bukti bahwa sekiranya ia memiliki kemampuan
tersebut tentu ia akan dengan mudah mencapai segala keinginannya. Namun, di sini
terdapat persoalan: bukankah al-Qur’an yang dibacakan oleh Nabi itu, sebagaimana
ia yakini sendiri, datang dari Yang Maha Gaib? Penjelasan terhadap hal ini dapat
ditemukan dalam ayat itu sendiri. Pada ujung ayat tersebut di atas [“Aku tidak lain
hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang
beriman”] tampak dengan tegas kepada Nabi Muhammad diperintahkan untuk
mengukuhkan dirinya tidak lebih dari seorang Paraclete, pemberi peringatan dan
kabar gembira bagi mereka yang percaya. Keterangan pada ujung ayat ini
memberikan makna bahwa bukan soal apakah Nabi Muhammad mengetahui atau
tidak persoalan gaib yang menjadi inti pembicaraan, tetapi apa sebenarnya tujuan
dakwah yang beliau lakukan dan mengapa beliau melakukannya. Pernyataan
8Para mufassir berbeda pendapat dalam memaknai kata khayr dalam ayat ini. Ada yang mengatakan artinya “kebaikan” dan ada pula yang mengatakan “harta kekayaan.” Tetapi yang penting dan relevan dalam pembicaraan ini adalah indikasi dan arah pembicaraan ayat tersebut, bukan makna harfiahnya. Nabi bukan seorang peramal yang sering kali diasosiasikan dengan kemampuan melihat nasib dan menentukan arah keberuntungan. Nabi tidak bekerja untuk kepentingan pribadi. Mengenai tafsir ayat ini, lihat misalnya Ibn Katsīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm, (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H.), Vol. 2, 274.
9Q.S. al-A‘rāf: 188 (diturunkan berkaitan dengan adanya pertanyaan kapan terjadi Hari Kiamat). Lihat ayat 187. Nas}s} (teks dalam bahasa Arab) ayat di atas – dan ayat-ayat selanjutnya, yang dikutip terjemahnya – dapat dilihat dalam Lampiran. Terjemah ayat-ayat al-Qur’an dalam disertasi ini adalah hasil terjemahan penulis dengan berpedoman pada Al-Qur’an dan Terjemahnya (terbitan Departemen Agama), The Meaning of the Holy Qur’an (oleh ‘Abdullah Yūsuf ‘Alī) dan tafsir al-Jalālayn.
45
“sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentu aku akan memperbanyak kebaikan
(harta kekayaan) dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan” secara historis tidak lain
menunjukkan kepada telah mewabahnya fenomena pada waktu itu bahwa otoritas,
kekuasaan dan kemampuan seumpama meramal dan melihat hal-hal tidak terlihat
secara normal selalu diarahkan untuk mencapai keinginan duniawi dan menolak
segala kemalangan. Sudah jelas, Nabi Muhammad dituduh oleh para penentangnya
sebagai orang yang haus kekuasaan dan bahwa apa yang beliau lakukan tidak lain
dari rekayasa semata untuk memenuhi ambisinya. Walaupun ayat ini, sebagaimana
ditunjukkan oleh ayat sebelumnya, merupakan jawaban terhadap pertanyaan kapan
datangnya hari kiamat, pengembangan jawaban yang diberikan sudah tentu
diarahkan kepada upaya menentang makna yang terkandung dalam watak pertanyaan
itu, yang sengaja diajukan untuk memojokkan. Dengan kata lain, Nabi seolah-olah
diperintahkan untuk menjawab: “Aku bukanlah seorang tukang ramal atau kāhin.
Sekiranya benar demikian, tentu aku telah menjadi kaya dan terhindar dari segala
bahaya dan kesulitan, seperti yang kamu anggap itu. Nyatanya, aku adalah seorang
yang hidup sederhana dan menjalani kehidupan keseharian secara normal.”
Inilah yang membuat para penentang Nabi di Mekkah heran: Mengapa
seorang Nabi utusan Tuhan sama dengan manusia lainnya; mengapa seorang Nabi
harus makan dan minum serta pergi ke pasar. Keganjilan yang dirasakan orang-orang
kafir Mekkah itu, diekspresikan dengan jelas oleh al-Qur’an:10
Dan mereka berkata: “Mengapa rasul ini makan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar bersama-sama dengannya memberikan peringatan?, atau (mengapa tidak) diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau (mengapa) ia (tidak) memiliki sebuah kebun yang ia makan dari (hasil)nya?” Dan orang-orang yang zalim
10Q.S. al-Furqān: 7-8.
46
itu berkata: “Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir.”
Pada sisi lain, sebagaimana dapat diperhatikan dalam Q.S. Hūd: 12, Nabi
Muhammad benar-benar merasa gelisah dan merasa berat menerima serta
menyampaikan risalah Tuhan itu.
Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu menjadi sempit disebabkan olehnya (karena khawatir) mereka mengatakan: “Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan (kekayaan) atau datang bersama-sama dengannya seorang malaikat?” Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah Pemelihara segala sesuatu.
Dalam ayat ini terlihat kembali bagaimana aktivitas dakwah Nabi dipersepsikan oleh
para penentangnya sebagai upaya untuk mencari keuntungan material. Lebih jauh
mereka menganggap bahwa menjadi utusan Tuhan seolah-olah menjadi Tuhan atau
“anak Tuhan” karena mendapatkan kekuasaan atas segalanya: hidup menjadi mudah
dan semuanya bisa serba “sim salabim” karena dibantu oleh Tuhan. Namun, yang
dialami oleh Nabi Muhammad sendiri justeru sebaliknya, dan inilah yang membuat
Nabi susah: bagaimana menjelaskan hal ini kepada mereka yang tidak mau mengerti?
Dari sejak pertama sebenarnya Nabi ingin lari dan menjauhkan diri dari
pengalaman gaib tersebut, namun ia kemudian merasa dapat menerimanya karena
semangat yang diberikan oleh Khadījah, isterinya, dan karena keterangan-keterangan
yang diberikan oleh Waraqah ibn Nawfal, seorang Pendeta Nasrani yang baik hati
dan juga sepupu Khadījah. Ayat ini adalah di antara yang paling jelas
mengindikasikan posisi dan hubungan Nabi Muhammad dengan al-Qur’an atau
wahyu. Ia benar-benar dipilih oleh Tuhan untuk menjadi “Hermes” dalam mitologi
47
Yunani, seorang komunikator yang berbicara atas nama Tuhan namun dengan bahasa
komunitasnya yang fasih.
Banyak ayat al-Qur’an11 yang mengisyaratkan karakteristik Nabi sebagai
manusia biasa; ia hanya seorang utusan Tuhan yang bertugas menyampaikan risalah,
menyeru kepada kebaikan dan mengingatkan manusia akan azab Tuhan kalau
mereka ingkar. Nabi Muhammad tidak diperintahkan melakukan hal-hal aneh –
seperti tukang sulap – atau melampaui batas-batas kenormalan. Berkali-kali al-
Qur’an memerintahkan agar Nabi menjawab: Saya hanyalah seorang manusia biasa.
Keterangan-keterangan tersebut di atas merupakan dalil yang jelas bahwa al-
Qur’an tidak lahir dari sebuah ambisi atau cita-cita pribadi yang terprogram, tetapi
merupakan sebuah irādah Keilahian yang datang dari “luar” dan terinspirasi ke
dalam diri Nabi Muhammad. Namun al-Qur’an tidak perlu disebut sebagai sebuah
karya yang melampaui batas-batas kemanusiaan dan juga tidak dapat dipisahkan dari
kesadaran dan keinginan-keinginan luhur Nabi sendiri. Ayat-ayat al-Qur’an tidak
datang secara terpisah dari kehendak kreatif dan intuisi manusiawi Nabi Muhammad;
semuanya demikian menyatu dengan sikap, hasrat dan kepribadiannya. Meskipun al-
Qur’an disebut sebagai firman Tuhan, tidak berarti ia terlepas dari relativitas
kemanusiaan. Inilah yang dikatakan Fazlur Rahman “bahwa al-Qur’an adalah firman
Tuhan, dan dalam arti kata yang biasa, juga seluruhnya adalah perkataan
Muhammad.”12
11Misalnya Q.S. Āli ‘Imrān: 144; al-An‘ām: 50 dan al-Kahf: 110.
12Fazlur Rahman, Islam, (Chicago: The University of Chicago Press, 1979) p. 14; kutipan dari edisi bahasa Indonesia, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1984), 33.
48
Tidak mudah pernyataan seperti ini diterima oleh masyarakat tradisional.
Namun, bagaimana pun, hal tersebut harus dijelaskan. Pemahaman apa saja yang
dilontarkan kepada masyarakat yang telah menganggap dirinya mapan dan
“sempurna”, membenci kreativitas intelektual yang inovatif dan takut kepada
perubahan, akan mendapatkan kendala. Namun sesungguhnya melakukan penalaran
terhadap firman Tuhan adalah bagai menyelam ke dalam samudera yang luas tiada
tara. Tanpa kreativitas dan keberanian berarti kegagalan.
Kembali kepada pernyataan Rahman, apakah mungkin seorang manusia,
dengan lisannya yang serba terikat oleh “bumi”, mengucapkan kalam Ilahi – yang
teramat luhur, serba tak terjangkau – dari “langit”? Atau, adakah Tuhan hadir dalam
peradaban manusia? Bagaimana mungkin tutur kata Muhammad disamakan dengan
firman Allah Yang Maha Suci? Semua ini sebenarnya sangat ditentukan oleh
perspektif dan konsep seseorang tentang Tuhan dan manusia serta hubungan antara
keduanya. Fazlur Rahman, dalam kutipan di atas, tentu tidak bermaksud mengatakan
Muhammad adalah jelmaan Tuhan di bumi, dan juga tidak hendak merusak kesucian
kalam Tuhan dengan mencampuradukkannya dengan tutur bahasa manusia. Untuk
memahami pandangan Fazlur Rahman tersebut diperlukan penjelasan yang lebih
filosofis tentang wahyu. Menurut pemahaman penulis, al-Qur’an sebagai wahyu
bukanlah karya Nabi Muhammad; artinya Nabi tidak pernah memiliki intensi untuk
membuat dan mengarangnya. Nabi juga tidak pernah memikirkan untuk
menyusunnya sedemikian rupa sehingga lahirlah ayat-ayat yang dinisbatkan
kepadanya. (Ini penting dicatat di sini sebab orang-orang kafir Mekkah menuduh
Nabi sebagai “penyair” yang biasanya dikaitkan dengan kegiatan mereka yang
49
bertujuan untuk kepentingan material. Nabi sama sekali berbeda dari mereka dan
komposisi ayat-ayat al-Qur’an yang dibacakan Nabi bersih sama sekali dari ambisi
keduniaan).13 Tetapi al-Qur’an adalah tutur kata Nabi Muhammad dalam pengertian
beliaulah yang telah mengeluarkan bacaan-bacaan itu dari kesadaran batinnya yang
teramat dalam. Firman Tuhan itu secara organis menyatu dengan Nabi dan ia
membacanya sebagai jawaban atas kegelisahannya yang teramat dalam terhadap
kondisi masyarakat yang sudah sangat parah. Getaran jiwanya yang suci itu dan
hasratnya yang tiada henti-henti ingin mengubah keadaan, mempertemukannya
dengan “Ruh” atau spirit pembawa wahyu, dan al-Qur’an menjadi jalan penyelesaian
bagi segala persoalan yang dihadapinya. Sebagai konsekuensi dari pemahaman
seperti ini, Rahman menolak adanya agent (perantara personal) yang disebut-sebut
sebagai Jibril yang bertugas sebagai pengantar wahyu. Pandangan ortodoks tentang
eksternalitas malaikat Jibril dan wahyu dianggap Rahman sebagai tidak dewasa
secara intelektual dan bertentangan dengan al-Qur’an sendiri yang menyebutkan “…
al-Rūh} al-Amīn turun membawanya ke dalam hatimu agar engkau menjadi salah
seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan ...” (Q.S. al-Syu‘arā’: 193-
194).14
Meskipun penulis tidak sepenuhnya sepakat dengan pernyataan Rahman yang
disebutkan terakhir, ada poin yang patut dicermati di sini. Jibril mungkin tidak sama
dengan agen wahyu, tetapi malaikat yang disebut dengan “roh terpercaya” ini telah
menjadi medium yang mengaktualkan visi spiritual Nabi. Walaupun wahyu
disampaikan “langsung ke dalam hati” Nabi, tidak perlu dipungkiri bahwa Jibril telah
13Lihat misalnya Q.S. al-Anbiyā’: 5; Yāsīn: 69; dan al-H{āqqah: 41.
14Fazlur Rahman, Islam. p. 14.
50
memainkan perannya sebagai “perantara,” yang menjadikan wahyu itu lebih aktual
dan lebih “terbaca” oleh Nabi.
Akan tetapi, dalam literatur Islam klasik umumnya atau dalam doktrin teologi
Islam, wahyu dipahami sebagai firman Tuhan yang diturunkan kepada rasul-Nya
melalui malaikat Jibril kata per kata sebagaimana adanya sejak zaman azalī, karena
firman Tuhan bukanlah wujud yang diciptakan, tetapi sudah ada sebagaimana telah
adanya Diri atau Zat Tuhan yang Maha Qadīm. Kitab-kitab ‘ulūm al-Qur’ān, baik
yang klasik maupun yang modern tidak lebih dari mengulang-ulang dua karya
monumental abad pertengahan yaitu al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān karangan al-
Zarkasyī (w. 795 H.)15 dan al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān karangan al-Suyūt}ī (w. 911
H./1505 M.).16 Kedua kitab ini menjadi rujukan para pengkaji tafsir dari zaman
klasik hingga sekarang.
Dalam kedua kitab ini, wahyu digambarkan sebagai pesan “telah jadi” dari
Tuhan yang dibawa oleh Jibril ke dunia ini, dan Muhammad tidak lebih dari seorang
speaker, “corong” Tuhan, di bumi. Ini sebenarnya adalah gambaran tradisional
tentang wahyu yang terdapat dalam agama-agama di Arab pada waktu itu terutama
Yahudi dan Nasrani. Dalam Bibel, malaikat kerap kali digambarkan turun ke bumi
dan bertemu serta berbicara dengan para Rasul.17 Gambaran seperti ini juga tidak
sulit ditemukan dalam al-Qur’an dengan pembacaan yang sederhana, sebab –
memang tidak mengherankan – istilah-istilah yang digunakan al-Qur’an merujuk
15Al-Zarkasyī, al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, (Beirut: Dār al-Ma‘rifāt, 1391).
16Al-Suyūt}ī, al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, (Kairo: Mus}t}afā al-Bābī al-H{alabī, 1370 H.).
17Lihat misalnya kisah Ibrahim dalam Genesis, kisah Musa dalam Exodus dan kisah Joshua dalam Judges.
51
pada tradisi, peradaban dan bahasa yang telah dikenal luas oleh masyarakat zaman
tersebut. Namun perlu diingat bahwa istilah wahyu yang digunakan al-Qur’an tidak
hanya ditujukan kepada ayat-ayat yang dibacakan Muhammad semata; al-Qur’an
juga menggunakan istilah wahyu untuk hal-hal lain yang, secara komparatif,
mempunyai implikasi yang signifikan. Misalnya, Tuhan dikatakan telah
mewahyukan perintahnya kepada lebah,18 dan pada kesempatan lain juga disebutkan
wahyu disampaikan kepada Ibu Musa.19 Bahkan bisikan setan juga kadang-kadang
disebut wahyu.20
Al-Qur’an dengan tegas menyebut dirinya tidak lain dari wahyu yang
diwahyukan.21 Tetapi apakah wahyu al-Qur’an sama dengan wahyu yang
diwahyukan kepada lebah, atau kepada Ibu Musa? Kitab-kitab ‘ulūm al-Qur’an telah
menjawab persoalan ini dengan cara membagi wahyu kepada tiga macam: wahyu
dalam pengertian firman Allah yang diturunkan kepada para Nabi, wahyu dalam
pengertian ilhām (inspirasi) dan wahyu dalam pengertian instinct.22 Dengan
demikian, berdasarkan konsep ini, wahyu Tuhan kepada lebah atau kepada Ibu Musa,
misalnya, berbeda dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad. Kalau dilihat isinya
memang sangat berbeda, tetapi bagaimana dengan proses dan karakteristik dasarnya?
Tidak ada satu bukti yang meyakinkan bahwa mereka berbeda secara substansial.
18Q.S. al-Nah}l: 68.
19Q.S. al-Qas}as}: 7.
20Q.S. al-An‘ām: 112 dan 121.
21Q.S. al-Najm: 4.
22Sebagai contoh, lihat S{ubh}ī al-S{ālih}, Mabāh}its fī ‘Ulūm al-Qur’ān, (Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1977), 23-24.
52
Jawaban klasik yang diberikan mengenai masalah ini, dengan membagi wahyu
kepada tiga macam, lebih merupakan upaya mempertahankan prakonsepsi lama yang
telah menjadi ciri pandangan klasik bahwa wahyu adalah fenomena “luar biasa”
(tidak normal), dan kalau tidak demikian maka dianggap telah hilang
kemukjizatannya.
Wahyu adalah istilah alamiah dalam bahasa Arab dan telah digunakan sejak
sebelum Islam. Syair-syair pra-Islam mengindikasikan makna wahyu sebagai
komunikasi yang penuh isyarat, rahasia dan sangat terbatas. Komunikasi antara dua
entitas yang berbeda, seperti seekor unta dengan pendekapnya, sering disebut wahyu.
Hal tersebut ditunjukkan misalnya oleh sebuah puisi ‘Alqamah, sebagaimana dikutip
Daniel A. Madigan:
Dia berkomunikasi (yûhî) dengan mereka dalam bunyi yang berdecit-decitan dan suara-suara berkeletak-keletak, sebagaimana orang-orang Yunani dalam istana-istana mereka berbicara satu sama lain dalam bahasa yang tidak dapat dipahami.23
Fakta ini mengantarkan seseorang pada keyakinan bahwa wahyu, dalam
pengertian yang paling mendasar, memiliki makna yang sangat kompleks dan rumit.
Wahyu begitu menyatu dengan penerima wahyu. Wahyu Tuhan kepada lebah adalah
karakter alamiah lebah itu sendiri. Demikian juga wahyu yang disampaikan kepada
Ibu Musa, telah merupakan bagian dari naluri seorang Ibu ketika menghadapi
suasana sulit dalam rangka menyelamatkan anaknya. Wahyu yang diterima Nabi
Muhammad adalah puncak dari kegelisahan moralnya, yang tumbuh dari rasa
kemanusiaannya yang amat dalam dan kemudian terucap dan mengalir lewat
23Daniel A. Madigan, Membuka Rahasia Alquran, terj. Tim Redaksi Nalar, (Jakarta: Intimedia Ciptanusantara, 2001), 33. Lihat juga Nas}r H{āmid Abū Zayd, Mafhūm al-Nas}s}: Dirāsah fī ‘Ulūm al-Qur’ān, (al-Dār al-Bayd}ā’: al-Markaz al-Tsaqāfī al-‘Arabī, cet. V, 2000), 32.
53
lisannya dalam bahasa Arab yang fasih. Ketika itulah wahyu menjadi teks, yang
terekam (baik dalam tulisan maupun dalam memori orang-orang yang menghafalnya)
dan terbaca sebagai bagian dari peradaban manusia.
Penulis tidak menolak kemungkinan Nabi telah mendapatkan apa yang
disebut dengan spiritual vision (seperti melihat malaikat) atau Nabi telah melampaui
realitas fisiknya dan memasuki dunia lain (dunia Keilahian atau dunia spiritual) pada
saat menerima wahyu, tetapi yang ingin digarisbawahi adalah bahwa apa yang
didapatkan Nabi dari pengalaman batinnya itu, berupa wahyu, bukanlah Realitas
Mutlak dan bukan sebuah command atau otoritas yang absolut, sehingga terlepas
sama sekali dari relativitas kemanusiaan. Pencerapan Nabi terhadap segala
pengalaman spiritualnya tidak lebih dari sebuah visi manusiawi belaka. Nabi adalah
orang yang berkata benar, karena ia memang tidak berdusta; ajarannya adalah
petunjuk bagi umat manusia; segala perintah dan larangannya tidak lain dari upaya
menegakkan keadilan dan menyelamatkan manusia dari kehancuran moral. Namun
semuanya tidak bisa dipahami sebagai pengetahuan dan pengalaman yang asing dari
nilai-nilai kemanusiaan secara normal. Karena itu al-Qur’an jelas sekali
menampilkan dirinya sebagai sosok yang sangat familiar dengan lingkungan
masyarakatnya (sasaran pertamanya). Al-Qur’an tidak berbicara soal dunia luar yang
tidak terjangkau oleh mereka, yang asing dari peradaban mereka; tidak pernah
ditemukan dalam al-Qur’an disebutkan, misalnya, tentang negeri Cina dan Indonesia,
tentang Orpheus dan Hermes atau tentang Taoisme dan Hinduisme. Ini disebabkan
al-Qur’an itu historis, fit dengan setting peradaban tertentu; ia tidak menampakkan
dirinya sebagai yang Maha Absolut, rinci, magis, menyelesaikan segala persoalan di
54
dunia ini dengan tuntas. Dalam bahasa Kenneth Cragg, itu semua beyond its [the
Qur’an’s] purpose and foreign to its nature.
If he [a reader] asks how Athen, Rome or Alexandria, the philosophers and the imperialists of the classic world, or the disciples of Zoroaster, might have seem to them [the first Qur’ān-reciters], the text affords him little or no clue.24
Memang ada sebagian kaum Muslim yang berusaha menunjukkan sisi-sisi
kemukjizatan al-Qur’an dengan menampilkan sejumlah fakta yang dianggapnya
ganjil sehingga al-Qur’an kelihatan “luar biasa” dan dengan demikian berarti ia
bersifat Keilahian dan merupakan kalam Allah yang sempurna, sebuah kitab suci
yang lebih superior dari kitab-kitab suci lain yang ada di bumi ini.25 Lebih jauh
mereka juga menunjukkan kelemahan-kelemahan kitab suci lainnya, untuk
menegaskan bahwa selain al-Qur’an bukanlah kitab suci yang benar-benar datang
dari Tuhan, atau sekurang-kurangnya, firman Tuhan yang telah bercampur baur
dengan kata-kata manusia. Tindakan demikian sebenarnya lebih merupakan sikap
kurang dewasa secara intelektual dan bahkan dapat menjadi bumerang.26 Semua
pemilik kitab suci dapat menunjukkan keganjilan-keganjilan seperti itu dalam kitab
suci mereka. Orang-orang Kristen, misalnya, memiliki alasan yang serupa untuk
24Kenneth Cragg, The Event of the Qur’an: Islam in Its Scripture, (Oxford: Oneworld, 1994), 167.
25Contohnya dalam al-Qur’an disebutkan ramalan tentang kemenangan Romawi dalam waktu dekat setelah kekalahannya melawan Persia. Lihat misalnya penjelasan M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Quran, (Bandung: Mizan, Cet. IV, 1998), 212. Lihat juga uraian tentang berbagai kemukjizatan al-Qur’an oleh Badiuzzaman Said Nursi, Risalah Mukjizat Al-Quran, terj. Anuar Fakhri Omar, dkk., (Terengganu: Yayasan Islam Terengganu, 1999).
26Nursi (1877 – 1960), misalnya, mengatakan bahwa al-Qur’an adalah Kitab yang tidak pernah membosankan untuk dibaca dan dipelajari, dan ini merupakan salah satu kemukjizatan kitab suci ini. Ibid., 36. Ini jelas tidak lebih dari ekspresi pengalaman Muslim semata. Untuk kepentingan studi al-Qur’an, terlebih lagi bagi kalangan non-Muslim, pernyataan seperti itu sama sekali tidak mempunyai nilai yang signifikan.
55
membuktikan keunggulan kitab sucinya. Demikian juga orang-orang Hindu atau
Budha tidak kalah dalam memperlihatkan hal-hal luar biasa atau keajaiban yang
dilakukan tokoh-tokoh mereka, seperti kekebalan dan kemampuan berkomunikasi
dengan dunia spiritual pada saat-saat upacara ritual. Setiap peradaban menyimpan
misterinya tersendiri dan setiap peradaban memiliki kelebihan serta kekurangan.
Sementara itu, akibat tindakan-tindakan provokatif sebagian Muslim, telah bangkit
pula sebagian Kristen yang mencari dan menunjukkan kelemahan-kelemahan al-
Qur’an dengan pendekatan yang sama.27 Ini bukan pekerjaan yang dewasa secara
ilmiah, dan dari sudut pandang akademik, adu kehebatan seperti ini adalah hal yang
sia-sia. Setiap orang yang terlibat dalam polemik seperti ini selalu berpikir: “Alasan
apa lagi yang dapat kukemukakan untuk membenarkan pendapatku.” Ia tidak lagi
mencari kebenaran, tetapi pembenaran.
Sekilas tentang milieu masyarakat penerima pertama al-Qur’an barangkali
dapat memberikan penjelasan yang lebih jernih soal hubungan Nabi dan wahyu.
Seperti telah disinggung secara sepintas di atas, Nabi bukan tidak mendapatkan
tantangan dari masyarakatnya tatkala mencoba menyampaikan ayat-ayat al-Qur’an
yang diterima dari Tuhan. Mengapa mereka menentang? Bagaimana mereka
mempersepsikan wahyu yang disampaikan Muhammad? Namun sebagian mereka
27Sangat banyak tulisan dan artikel ditulis oleh kaum Muslim dalam bentuk serangan terhadap Bible dan Nasrani yang diekspos ke internet. Serangan tersebut terutama sekali diarahkan kepada “fakta” bahwa terdapat banyak kontradiksi dalam kitab suci orang Nasrani tersebut. Ini memang bukan hal baru, tetapi polemik ini telah menimbulkan fitnah yang lebih besar lagi. Orang-orang Nasrani telah memberi respon dengan sikap mental yang tidak berbeda. Pertentangan tidak sehat seperti ini tidak menghasilkan apa-apa bagi perkembangan pemahaman keagamaan pihak mana pun. Kedua belah pihak tidak saling berusaha memahami, tetapi sama-sama berangkat dari kebencian dan prejudice. Lihat daftar kontradiksi dan problem dalam al-Qur’an dalam <http://www.answering-islam.org/Quran/ Contra/>. Sebagai perbandingan, lihat juga situs Muslim yang memuat jawaban-jawaban terhadap tuduhan itu: <http://www.ummah.muslimsonline.com/~islamawe/Quran/Contrad/ External>.
56
menerima dengan tulus dan bahkan rela menyerahkan jiwa raganya untuk
kepentingan dakwah Nabi. Mengapa?
Seperti dikatakan Fazlur Rahman,28 secara kronologis, doktrin paling awal
ditanamkan al-Qur’an, setelah ajarannya tentang monoteisme dan keadilan sosial,
adalah kepercayaan akan Hari Akhirat: bahwa manusia akan mempertanggung-
jawabkan segala perbuatannya di hadapan pengadilan Tuhan setelah terjadinya Hari
Kiamat. Setiap jiwa akan dibangkitkan dan semua perbuatan, baik maupun buruk,
akan diberikan balasannya. Tentu saja ini mengacu pada fakta bahwa manusia adalah
pendurhaka; mereka zalim dan bodoh.29 Manusia harus diberikan peringatan dan
sebuah pembalasan moral harus ditegaskan dengan harapan agar manusia menjadi
sadar. Karena itulah dakwah Nabi harus berhadapan dengan oposisi yang sengit di
kota Mekkah. Ajaran Nabi Muhammad bukan hanya telah menggoyahkan agama
tradisional kaum musyrikin Mekkah, tetapi bahkan membuat struktur masyarakat
tersebut dengan segala kepentingan elitnya porak-poranda. Inilah yang membuat para
pemuka kota Mekkah panik dan permusuhan mereka terhadap Nabi semakin
menjadi-jadi.30
Fenomena ini menggambarkan kesenjangan sosial yang sudah amat
menyedihkan di tengah-tengah masyarakat Mekkah. Ini juga terlihat dari sikap Nabi
yang sangat prihatin dan menghendaki agar sebuah perubahan ke arah kehidupan
yang lebih baik dapat terjadi, dengan jalan mengajak manusia menjauhi segala
kejahatan dan perbuatan amoral serta kembali mengikuti petunjuk Tuhan.
28Fazlur Rahman, Islam., 15-16.
29Q.S. al-Ah}zāb: 72.
30Fazlur Rahman, Islam., 15-16.
57
Kepedulian sosial inilah yang amat ditekankan al-Qur’an sebagai bentuk ajaran yang
amat penting untuk membangun sebuah masyarakat yang adil dan makmur. Namun
kaum penentang, terutama kalangan elit masyarakat, justeru semakin melancarkan
serangannya terhadap Nabi dan para pengikutnya, bahkan sampai pada tingkat
perlakuan tidak wajar dan penganiayaan-penganiayaan. Mereka menuduh Nabi –
seperti terekam dalam ayat-ayat yang telah disebutkan di atas – sebagai orang yang
terkena sihir, tidak waras dan tidak pantas menjadi Nabi. Orang-orang yang
mengikuti Nabi diperolok-olok dan disakiti dengan cara-cara yang tidak manusiawi.
Kisah Bilāl Ibn Rābah, seorang budak asal Etiopia, adalah di antara yang paling
terkenal dalam sejarah perjuangan dakwah Islam. Ia dianiaya sampai setengah mati,
namun keteguhan hatinya untuk tetap setia kepada ajaran yang disampaikan Nabi
tidak pernah tergoyahkan. Bilāl kemudian menjadi sebuah legenda dan dijadikan
simbol perjuangan kaum lemah melawan tirani hingga hari ini, seperti di Amerika.
Apa yang paling jelas terlihat dalam sejarah perjuangan Nabi, terutama pada masa-
masa awal di Mekkah bukanlah penarikan sebuah garis pemisah antara Islam31 dan
agama-agama lain, tetapi penegasan terhadap moral dan keadilan sosial yang
berlandas pada Keesaan Tuhan dan pembalasan di Hari Akhirat – meskipun secara
teknis kaum penentang Mekkah itu disebut sebagai memiliki agama sendiri, yaitu
agama kafir.32
31Islam itu sendiri pada waktu itu belum dikenal sebagai sebuah agama formal atau resmi-institusional.
32Lihat Q.S. al-Kāfirūn. Ungkapan دين ولي دينكم lebih merupakan pemisahan لكمyang religious dari yang non-religious. Surat ini adalah ungkapan konfrontasi tanpa kompromi antara Nabi dan orang-orang kafir Mekkah, yakni mereka yang menolak seruan kepada kebenaran. Kāfir, dari kata kerja kafara-yakfuru, adalah orang yang fanatik, menutup diri dan tidak terbuka terhadap kebenaran. Lihat Toshihiko Izutsu, Ethico-Religious Concepts in the Qur’ān, (Montreal: McGill University Press, 1966), 119 ff.
58
Dari sudut pandang sosial budaya, fakta ini memperlihatkan bahwa orang-
orang yang menentang Nabi tidak secara sungguh-sungguh memberikan perhatian
pada konsep wahyu. Fenomena wahyu bukanlah hal yang menjadi masalah; yang
mereka tentang adalah muatan wahyu dan mungkin pribadi penyampai wahyu.
Sebagaimana dikatakan Nas}r H{āmid Abū Zayd,33 bahwa bangsa Arab, lama
sebelum Islam, telah mengenal fenomena komunikasi manusia dengan dunia gaib.
Praktik perdukunan dan komposisi syair-syair yang terinspirasi oleh jin adalah
aktivitas yang tidak lagi dianggap aneh oleh penghuni gurun pasir Arabia itu.
Pertalian antara dunia manusia dan dunia gaib, terutama alam jin, telah menjadi
bagian dari konsep budaya mereka dan merepresentasikan salah satu segmen dari
kreativitas dan nalar Arab pra-Islam. Dari itu, menurut Abū Zayd, dapat dikatakan
bahwa keyakinan mereka akan kemungkinan model komunikasi dua alam yang
berbeda menjadi “basis kultural bagi fenomena wahyu agama itu sendiri.”34
Penerimaan dan penolakan mereka terhadap wahyu yang disampaikan Nabi tidak
berangkat dari pemahaman mereka terhadap konsep wahyu, tetapi lebih berdasar
pada permusuhan dan sentimen sosial ekonomi. Mereka yang tidak memiliki
kebencian terhadap gugatan agama baru itu – karena mereka memang berasal dari
kalangan lemah dan bahkan dieksploitasi oleh mereka yang berkuasa – justeru
menjadi pembela Nabi yang gigih. Namun dalam rangka mempertahankan
posisinya, kelompok penentang kemudian mengembangkan argumentasi dengan
formulasi yang miring. Mereka tetap tidak menolak fenomena wahyu, tetapi
mengalihkannya kepada asumsi yang lain: bahwa inspirasi yang diterima
33Nas}r H{āmid Abū Zaiyd, Mafhūm al-Nas}s}, 33.
34Ibid., 34.
59
Muhammad bukan berasal dari Tuhan, tetapi dari jin. Mereka mengatakan
Muhammad itu pendusta, tukang sihir atau korban sihir.
Dari diskusi di atas, yang ingin digarisbawahi adalah keterikatan al-Qur’an
dengan watak peradaban Arab dan sifat pribadi Nabi Muhammad. Firman Tuhan
adalah pengejawantahan-Nya dalam hikmah yang terkucur melalui hati nurani dan
lisan manusia sebagaimana Ia memancarkan cahaya-Nya dalam keagungan alam
semesta. Kalam Tuhan adalah bagian dari ayat-ayat-Nya untuk direnungkan dan
untuk membuat manusia semakin tercerahkan. Ayat-ayat Tuhan tidak diturunkan
untuk mematikan kreativitas dan akal budi yang merupakan potensi dasar kesadaran
manusia.
Kajian terhadap al-Qur’an tidak terlepas dari kajian terhadap sejarah dan
peradaban Arab. Ungkapan-ungkapan al-Qur’an mesti dipahami dalam konteks yang
dikehendaki oleh peradaban pada masa itu. Peradaban Arab itu sendiri, demikian
menurut Abū Zayd, adalah “peradaban teks.” Tekslah yang merupakan jantung
peradaban masyarakat Arab dan teks pula yang telah menggerakkan mereka sehingga
mampu melintas jazirah tandus itu ke berbagai belahan dunia. Namun perlu
ditegaskan bahwa yang membangun peradaban bukanlah teks, tetapi manusia,
melalui interaksinya dengan realitas di satu pihak dan dialognya dengan teks di pihak
lain. Karena itu teks memiliki posisi sentral di tengah-tengah pergumulan masyarakat
mengembangkan dirinya, dan interpretasi (tafsir atau ta’wīl) merupakan salah satu
mekanisme peradaban yang paling penting dalam memproduksi ilmu pengetahuan.35
Tafsir telah mulai berkembang sejak masa turun wahyu. Nabi adalah penafsir wahyu
yang paling otoritatif. Sahabat-sahabat Nabi juga menafsirkan al-Qur’an; Ibn Abbās
35Ibid., 9.
60
adalah yang paling terkenal di antara mereka dan disebut dengan Abū al-Tafsīr.36
Pada masa awal hingga zaman al-T{abarī (w. 923 M.) kitab-kitab tafsir merupakan
nukilan-nukilan sabda Nabi dan pandangan para sahabat tentang makna ayat-ayat al-
Qur’an. Sesuai dengan perkembangan bahasa dan sastra, tafsir berkembang lebih
jauh; tafsir menjadi ilmu untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dari sudut pandang
bahasa dan realitas teks.37 Tafsir ternyata tidak berhenti berkembang, sampai hari ini,
dan telah melahirkan khazanah keilmuan Islam yang amat kaya. Ketika teks menjadi
inti peradaban, maka tafsir adalah alat yang paling tangguh dalam melahirkan ilmu
pengetahuan.
Hubungan wahyu dan teks kini sudah jelas. Wahyu adalah konsekuensi logis
dari sebuah proses interaksi kehendak, hasrat dan imajinasi manusia dengan realitas
kehidupan yang dijalaninya. Teks terlahirkan, karena wahyu itu – tidak bisa tidak –
harus diekspresikan. Wahyu disebut sebagai “inspirasi” yang datang dari Tuhan,
yakni dari “luar” diri manusia, karena ia memang sebelumnya tidak ada dalam dunia
manusia yang historis, lalu terlahirkan; ia adalah anugerah Tuhan melalui hamba
pilihan-Nya. Peradaban adalah kreasi manusia. Peradaban tidak akan pernah ada
tanpa manusia. Pertanyaannya, apakah wahyu juga tidak ada sekiranya manusia tidak
ada? Tentu saja: “Ya, tidak ada.” Akan tetapi itu adalah pertanyaan yang absurd,
karena bertentangan dengan kenyataan, dan tidak mungkin diandaikan. Yang paling
krusial di sini adalah fakta bahwa wahyu, manusia dan peradaban tidak dapat
36Mus}t}afā al-S{āwī al-Juwaynī, Manāhij fī al-Tafsīr, (al-Iskandariyyah: Mansya’ah al-Ma‘ārif, t.t.), 23.
37Ibn Khaldūn, Muqaddimah, (Mesir: al-Mat}ba‘ah al-Azhariyyah, 1930), 368-369.
61
dipisahkan. Wahyu tidak lahir dari kekosongan, tanpa cradle peradaban, dan
peradaban tidak pernah ada tanpa manusia yang melahirkannya.
Poin yang ingin ditegaskan di sini sebagai kesimpulan dari semua diskusi di
atas adalah mengenai watak atau karakteristik al-Qur’an tersebut sebagai wahyu dan
teks, sebagai kalam Ilahi dan juga sebagai sebuah warisan peradaban. Al-Qur’an
adalah cerminan dari kesatuan irādah Tuhan dan cita-cita ideal manusia. Ketika
seorang manusia suci (Nabi) mencapai titik kulminasi dari pencapaian idealitas
kemanusiaannya, maka ia akan memasuki titik terendah dari wilayah Keilahian. Jadi
kitab suci dapat dikatakan sebagai wujud pancaran cahaya Tuhan pada titik paling
rendah dalam peradaban manusia. Pada sisi lain ia merupakan ekspresi yang berada
pada titik pencapaian paling tinggi dari cita-cita ideal dan moral kemanusiaan.
B. Jalan Memahami al-Qur’an: Metodologi Tafsir
Ada pendekatan berbeda-beda yang ditempuh ulama dalam memahami al-
Qur’an. Secara umum pendekatan tersebut terbagi dua: skriptural dan rasional.
Pendekatan skriptural mengandalkan otoritas dan riwayat-riwayat dari Nabi, sahabat
dan tābi‘īn, sedangkan pendekatan rasional, meskipun sedikit banyaknya bergantung
pada riwayat-riwayat, lebih menekankan aspek penalaran dan pertimbangan-
pertimbangan akal.
Sebelum melangkah lebih jauh, ada sedikit catatan ingin dikemukakan di sini
mengenai istilah “metodologi tafsir.” Penulis memilih istilah yang simpel: “jalan
memahami al-Qur’an.” Maksudnya sama dengan “metodologi tafsir.” Metodologi
62
yang dimaksudkan di sini bukan berarti penjelasan terhadap metode-metode, seperti
yang dipahami oleh sebagian orang, tetapi lebih merupakan sebuah “metode” yang
terkait dengan aspek-aspek teoretis dan konseptual dari suatu bidang kajian
keilmuan. Memang ada yang menyebutkan metodologi sebagai ilmu tentang metode.
Ini tidak salah; sebagian kamus menyebutkan seperti itu. Nashruddin Baidan menulis
buku Metodologi Penafsiran al-Qur’an. Isinya adalah penjelasan tentang beberapa
metode tafsir. Pada bagian awal buku tersebut, penulisnya dengan tegas mengatakan
“… metodologi tafsir ialah ilmu tentang metode menafsirkan al-Qur’an.”38 Istilah
metodologi dalam kajian disertasi ini digunakan dalam pengertian agak berbeda.
Metodologi disamakan dengan paradigma dan proses kerja dalam melakukan suatu
pendekatan (approach). Metode lebih dipahami sebagai teknik dalam mendekati
suatu objek kajian sebagaimana sering digunakan dalam investigasi saintifik atau
eksperimental. Metode adalah “cara” atau langkah-langkah dalam pengertian yang
sederhana dan teknikal, sedangkan metodologi mempunyai concern yang lebih
konseptual, teoretis dan filosofis.39
Kembali pada permasalahan dasar, sub bab ini akan mendiskusikan model
pendekatan atau jalan yang dapat ditempuh dalam memahami al-Qur’an. Al-Qur’an,
sebagai teks, memiliki multi dimensi: keagamaan, sosial, kultural, linguistik, filosofis
dan historis. Al-Qur’an adalah wahyu atau, dalam bahasa yang agak sekuler,
inspirasi dari Tuhan. Wahyu ini dalam sejarah telah terekam menjadi bagian dari
budaya manusia. Ia diungkapkan dengan bahasa manusia, dipenuhi oleh berbagai
38Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 2.
39David Jary dan Julian Jary, The Harper Collins Dictionary of Sociology, (New York: HarperCollins, 1991), 305.
63
simbol yang berasal dari kreativitas manusia, dan pada tahap awal pewahyuan atau
era formatif, ia juga telah dipahami, dijelaskan dan diperankan pesan-pesannya oleh
manusia, yang kemudian oleh generasi berikutnya dianggap sebagai tafsiran paling
otoritatif terhadapnya. Keragaman peradaban, sosial budaya dan latar belakang
sejarah kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial, tak pelak lagi
membawa kepada keragaman cara memahami al-Qur’an. Bukan hanya itu,
munculnya berbagai aliran dan mazhab dalam Islam (bahkan dalam agama mana pun
di dunia) juga berangkat dari kenyataan tersebut. “Pemahaman” ternyata adalah
bentuk paling kompleks dari pencerapan manusia terhadap realitas.
Para ulama atau sarjana Muslim klasik telah menggunakan berbagai
pendekatan dalam memahami al-Qur’an. Namun pada intinya ada tiga poin mendasar
yang dapat disebut sebagai landasan bagi paradigma pemikiran mereka. Pertama, al-
Qur’an diyakini sebagai kebenaran mutlak dan telah final. Al-Qur’an merupakan
firman Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi, diturunkan kepada manusia, untuk
dijadikan pedoman dalam rangka beribadah kepada Allah. Sebagai kalam Tuhan, al-
Qur’an menempati kedudukan yang amat tinggi dan tidak dapat disamakan dengan
kata-kata atau ungkapan-ungkapan lain mana pun juga di dunia ini.40
Kedua, al-Qur’an diyakini sebagai firman Tuhan yang selalu up-to-date untuk
ditafsirkan sepanjang zaman dan di segala tempat. Pesan-pesan yang terkandung di
dalamnya menembusi seluruh rentangan sejarah dan melampaui seluruh imajinasi
dan cipta karsa manusia. Al-Qur’an adalah sebuah mukjizat. Diturunkan selama
40Sebenarnya amat sulit memahami pernyataan ini. Walaupun demikian, inilah ungkapan yang sangat disukai oleh umumnya umat Islam. Apa maksud “mutlak” dan “final” kalau kalimat-kalimat dalam al-Qur’an masih harus dijelaskan atau ditafsirkan dan bahkan masih menimbulkan banyak kontroversi?
64
kurun waktu lebih kurang dua puluh tiga tahun, ia dapat memenuhi semua tuntutan
zamannya dan semua tuntutan masa depan umat manusia sepanjang sejarah. Sekali
umat Islam memiliki al-Qur’an maka mereka telah memiliki segalanya; tidak ada
pedoman lain lagi yang diperlukan.
Ketiga, Nabi adalah figur penafsir al-Qur’an yang paling absah, dan generasi
pertama penerima al-Qur’an dianggap lebih mampu memahami al-Qur’an dari yang
lainnya atas landasan bahwa mereka menyaksikan dan menghayati secara langsung
ayat-ayat al-Qur’an bersama Nabi. Terlebih lagi, merekalah pemilik bahasa dan
peradaban di mana wahyu al-Qur’an diturunkan.
Dengan demikian tafsir klasik sangat terikat dengan teks secara literal dan
bahkan dalam kenyataannya cenderung mengabaikan sikap kritis-rasional, dan
bersifat apologetik. Secara umum pendekatan yang digunakan para mufassir klasik
tetap berada dalam bingkai pemikiran yang sama, yakni sebuah paradigma pemikiran
yang mengacu pada upaya pembenaran atas keyakinan yang telah ada, atau
pengukuhan terhadap presuposisi keyakinan keagamaan yang dianggap telah mapan
atau bahkan telah final. Lebih jauh, kitab-kitab tafsir juga telah ditulis dengan
menggunakan paradigma mazhab atau aliran tertentu, sehingga isinya penuh dengan
pembelaan-pembelaan bagi mazhab sendiri dan perlawanan terhadap mazhab dan
aliran lain. Namun perlu dicatat bahwa kenyataan ini sama sekali tidak harus
mengurangi rasa hormat dan kagum generasi sekarang terhadap khazanah intelektual
masa lalu yang maha kaya itu. Hanya saja, kerinduan akan pencerahan menuntut para
pengkaji ilmu hari ini untuk tetap bersikap fair dan dapat meletakkan segala sesuatu
pada posisinya secara proporsional. Para sarjana yang hidup di zaman ini juga harus
65
mengapresiasikan zaman klasik itu sebagai dunia yang sulit dan penuh pertentangan,
yakni saat-saat di mana masyarakat Muslim sedang mencari dan mengukuhkan
identitas diri di panggung sejarah dan peradaban dunia. Polemik bukan hanya terjadi
sesama Muslim, tetapi juga dengan non-Muslim, terutama Yahudi dan Nasrani; dan
yang lebih menarik adalah bahwa keterlibatan dalam polemik memiliki kebanggaan
tersendiri. Kekalahan dan kemenangan dalam berdebat merupakan standar prestise
seorang intelektual zaman itu dan sangat berpengaruh terhadap karirnya.41
Karya-karya tafsir modern yang muncul pada abad 20 lebih bercorak
pembelaan terhadap Islam dari serangan Barat. Ini bisa dipahami mengingat periode
awal abad ini merupakan zaman yang penuh dengan pergolakan politik yang pada
gilirannya juga adalah pertarungan pemikiran. Dua karya tafsir modern yang sangat
terkenal, al-Manār dan Fī Z{ilāl al-Qur’ān, masing-masing karya Muhammad
‘Abduh dan Sayyid Qut}b, walaupun mempunyai corak yang berbeda, keduanya
sama-sama merupakan respon terhadap Barat yang dianggap telah menjadi
pecundang terhadap Islam dan dunia Islam, sekaligus merupakan kritik-diri bagi
umat Islam yang dianggap secara mental telah lesu dan secara intelektual tidak
berdaya.
Ibn Khaldun, dalam karya monumentalnya Muqaddimah Ibn Khaldūn,
mengatakan bahwa tafsir terbagi kepada dua, yaitu: tafsir naqlī dan tafsir yang
berlandas pada bahasa, termasuk pemahaman ‘ibārāt dan analisis balāghah.42 Dari
dua jenis tafsir inilah kemudian muncul berbagai aliran dan corak tafsir yang
41Lihat Hasan Asari, “Yang Hilang dari Pendidikan Islam: Seni Munādharah,” Ulumul al-Qur’an, No. 1, Vol. V, 1994, 62-68.
42Ibn Khaldūn, Muqaddimah Ibn Khaldūn, (Beirut: Dār al-Qalam, 1984), 439.
66
berbeda-beda. Di kalangan ulama masa awal Islam, sampai sekitar awal abad kedua
Hijriah, memang ada kekhawatiran atau semacam rasa takut dalam menafsirkan al-
Qur’an, bahkan sebagian mereka ada yang sama sekali tidak mau menafsirkan al-
Qur’an.43 Bagi mereka, al-Qur’an adalah kalām Allah yang Maha Agung dan
kebenaran yang Maha Nyata; menafsirkan al-Qur’an akan menimbulkan kecacatan
dan kerusakan pada makna Kalam Tuhan yang Maha Mulia tersebut. Akan tetapi
setelah masyarakat Muslim mengenal berbagai macam disiplin ilmu yang dapat
diterapkan dalam menafsirkan al-Qur’an, seperti nah}w, balāghah, logika dan
filsafat, maka tafsir mengalami perkembangan yang pesat.
Perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer telah memberikan sumbangan
yang besar bagi kajian teks, terutama sekali teks-teks kitab suci, termasuk Kitab Suci
al-Qur’an. Studi antropologi, sosiologi, filsafat (terutama sekali hermeneutika) telah
memberikan cukup banyak informasi dan pertimbangan dalam pemahaman terhadap
wahyu dan agama secara umum, sebagai keyakinan manusia. Toshihiko Izutsu,
seorang guru besar studi Islam dari Jepang, misalnya, telah mengembangkan sebuah
formulasi kajian linguistik untuk diterapkan dalam kajian (tafsir) al-Qur’an. Menurut
Izutsu, setiap kata-kata dalam sebuah peradaban merepresentasikan pandangan dunia
tertentu yang terkait dalam sebuah jaringan struktur yang terpadu dan independen.
Kalimat-kalimat dalam al-Qur’an yang berbicara tentang moral, merefleksikan
struktur dasar budaya dan agama masyarakat yang terkejawantah dalam bahasa
secara kompak.44
43Muh}ammad Abū Syahbah, al-Isrā’īliyyāt wa al-Mawd}ū‘āt fī Kutub al-Tafsīr, (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1408 H.), 36-37.
44Toshihiko Izutsu, Ethico-Religious Concepts in the Qur’ān, (Montreal: McGill University Press, 1966), 9-12.
67
Apa yang dilakukan Izutsu dan kebanyakan sarjana lainnya dalam upaya
memahami al-Qur’an merupakan bentuk pola baru pengkajian kitab suci. Dalam hal
ini pendekatan yang dilakukan tidak dengan cara semata-mata melihat pada
ungkapan teks sebuah kitab suci tetapi langsung dikaitkan dengan berbagai persoalan
lain yang secara kompak mengikat sebuah peradaban manusia secara utuh. Dengan
berbasis pada pendekatan seperti yang diterapkan dalam bidang-bidang ilmu
humaniora itulah metodologi kajian disertasi ini dikembangkan.
Banyak cara untuk mendekati al-Qur’an. Artinya banyak metodologi yang
dapat diterapkan dalam upaya untuk memahami al-Qur’an. Beberapa pendekatan
terhadap al-Qur’an, yang barangkali juga sudah dikenal secara luas, akan
didiskusikan di sini sebagai perbandingan dan juga sebagai upaya menjelaskan
model pendekatan yang diterapkan dalam kajian disertasi ini.
1. Pendekatan Naqlī (tradisional-skriptural)
Dalam ‘Ulūm al-Qur’ān umumnya tafsir dibagi dua, yaitu tafsir bi al-ma’tsūr
dan tafsir bi al-ra’y.45 Yang pertama adalah penafsiran al-Qur’an dengan
menggunakan atsar, yakni hadis-hadis Nabi dan pendapat para sahabat serta ayat-
ayat al-Qur’an sendiri, sedangkan yang kedua, penafsiran al-Qur’an dengan
menggunakan akal atau rasio. Pendekatan naqlī di sini tidak lain dari tafsir bi al-
ma’tsūr tersebut.46 Istilah naqlī – sebagaimana digunakan Ibn Khaldūn – lebih
45S{ubh}ī al-S{ālih}, Mabāh}its, 291.
68
disukai dengan alasan bahwa penukilan memang merupakan karakteristik paling
mendasar dari pendekatan tafsir model ini.
Pendekatan naqlī adalah model paling klasik dalam menafsirkan ayat-ayat al-
Qur’an. Penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur’an dilakukan dengan mengutip atsar
atau hadis-hadis Nabi yang terkait dengannya atau yang dianggap relevan. Di antara
kitab tafsir yang menggunakan pendekatan ini yang paling monumental adalah tafsir
al-T{abarī (Abū Ja‘far Muh}ammad Ibn Jarīr al-T{abarī, w. 923 di Baghdad) dan
tafsir Ibn Katsīr (‘Imād al-Dīn Ismā‘īl Ibn ‘Umar Ibn Katsīr, w. 1373 di Damaskus).
Pendekatan ini, seperti telah disinggung di atas, dilakukan para mufassir atas
dasar keyakinan bahwa Nabi dan orang-orang yang dekat dengan Nabilah yang
paling otoritatif dalam memahami al-Qur’an. Pandangan seperti ini dapat dimaklumi,
karena secara historis ayat-ayat al-Qur’an sering kali turun dalam konteks tertentu
sehingga pernyataan-pernyataannya mengasumsikan para pendengar telah
memaklumi persoalan yang dibicarakan. Para pendengar pertamalah yang dapat
dianggap paling mengerti makna ayat-ayat tersebut. Namun demikian, konsep dasar
pendekatan ini adalah literal, dogmatik dan cenderung menekankan kepatuhan pada
otoritas. Karena itu ia tidak kritis. Pendekatan seperti ini tidak dapat melahirkan
tafsir baru dan tidak akan mampu menjawab tantangan kehidupan yang terus
berubah, karena sifatnya yang statis dan menolak pikiran baru yang inovatif.
Meskipun diakui bahwa generasi sahabat, dan mungkin juga tābi‘īn, adalah
kelompok paling potensial untuk memahami dan mencapai makna paling dekat
dengan maksud ayat-ayat al-Qur’an (pada saat ia diturunkan), mereka tetap tidak
memiliki akses ke dunia peradaban luar yang masih asing dan belum mereka kenal.
69
Jika al-Qur’an disepakati sebagai pembawa pesan-pesan universal, maka mestilah al-
Qur’an juga dapat dipahami dalam paradigma peradaban berbeda, selain peradaban
yang dimiliki oleh para penerima pertamanya.
Lebih jauh, problem pendekatan ini juga terletak pada sejauh mana sebuah
atsar itu dapat dipertanggungjawabkan kesahihan atau keasliannya. Tidak diragukan
bahwa para sahabat Nabi adalah orang-orang yang jujur dan setia terhadap keyakinan
keagamaan, tetapi hal ini tidak dapat merupakan jaminan bahwa mereka sama sekali
bersih dari kekeliruan atau kesilapan. Di samping itu, dalam perkembangannya, tafsir
dengan pendekatan seperti ini telah mencampuradukkan antara nukilan-nukilan yang
sahih dengan yang tidak sahih tanpa klarifikasi. Inilah di antara kelemahan tafsir
model ini.47
Dalam tafsir kontemporer, pendekatan ini tidak berarti diabaikan sama sekali.
Tafsir al-Manār, misalnya, mengklaim dirinya sebagai tafsir yang menggabungkan
antara bi al-ma’tsūr dan bi al-ra’y, yakni antara pendekatan naqlī dan ‘aqlī
(rasional).48 Abduh dan Rasyīd Rid}ā (pengarang al-Manār) tidak mengabaikan
pentingnya memahami al-Qur’an dengan merujuk pada hadis-hadis dan pendapat
para sahabat, namun penerapan akal dalam mengeksplorasi makna ayat-ayat al-
Qur’an secara lebih mendalam dianggap tidak mungkin ditinggalkan.
Bagaimanapun, penafsiran naqlī bertumpu pada otoritas dan tidak memiliki
perkembangan atau perluasan. Otoritas acap kali menjadi penghalang bagi
kreativitas. Namun demikian penafsiran naqlī tetap dibutuhkan. Kitab-kitab tafsir
47Ibid., 292.
48Muh}ammad Rasyīd Rid}ā, Tafsīr al-Manār, (Beirut: Dār al-Fikr, 1973), Halaman Judul.
70
yang telah ditulis dengan pendekatan ini sebenarnya lebih merupakan rekaman
sejarah dan bersifat ensiklopedik, karena itu kitab-kitab tafsir tersebut sangat
diperlukan sebagai sumber kajian, bukan sebagai pegangan atau sumber keyakinan.
Tafsir al-T{abarī, misalnya, diakui sebagai sumber paling bernilai untuk penelitian
historis-kritis modern.49
2. Pendekatan ‘Aqlī (Rasional)
Dalam menafsirkan al-Qur’an, rasionalitas – sekurang-kurangnya dalam
batasan minimal – sulit dielakkan. Menafsirkan al-Qur’an berarti memahaminya; dan
pemahaman adalah suatu kegiatan yang melibatkan kerja akal. Penafsiran al-Qur’an
dengan pendekatan rasional atau tafsir bi al-ra’y telah diperdebatkan oleh ulama
mengenai keabsahannya. Sebagian ulama tafsir dengan terang-terangan mencela
tafsir dengan pendekatan ini, sedangkan sebagian yang lain membolehkannya dan
bahkan memujinya.
Ulama yang menolak penafsiran al-Qur’an dengan pendekatan rasional
menganggap bahwa kalam Tuhan terlalu suci untuk dijelaskan dengan akal manusia.
Sebagian ayat-ayat al-Qur’an dapat menjelaskan sebagian yang lain. Demikian juga
Hadis-hadis Nabi sudah cukup untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an yang dianggap
masih kurang jelas. Penolakan terhadap tafsir rasional acap kali dicari legitimasinya
pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudhī, yang menyebutkan Nabi
bersabda bahwa barangsiapa berucap tentang al-Qur’an dengan ra’y (akal)-nya maka
49Helmut Gätje, The Qur’ān and Its Exegesis, (Oxford: Oneworld, 1997), 34.
71
ia akan menempati posisi di neraka.50 Akan tetapi, jika hadis ini dibandingkan
dengan hadis yang lain oleh perawi yang sama barangkali maksudnya akan lebih
jelas. Dalam hadis satu lagi ini, redaksinya agak berbeda: frase bi ra’yih (dengan
akalnya) disebut dengan bi ghayri ‘ilm, tanpa ilmu; jadi, barangsiapa berucap tentang
al-Qur’an tanpa ilmu maka ia akan menempati posisi di neraka.51 Dari itu sebagian
ulama tidak keberatan terhadap tafsir dengan pendekatan rasional, asal saja dilakukan
dengan penuh tanggung jawab dan berlandas pada ilmu dan dasar argumentasi yang
kuat.
Maksud pendekatan rasional dalam tafsir adalah upaya menjelaskan ayat-ayat
al-Qur’an dengan menggunakan akal dan ilmu pengetahuan. Jika dalam pendekatan
pertama di atas yang diandalkan adalah nukilan-nukilan atsar, maka di sini yang
diandalkan adalah akal, rasionalitas atau ijtihad. Para sahabat Nabi sebenarnya telah
melakukan ijtihad dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, meskipun, seperti telah
disebutkan di atas, sebagian mereka lebih suka diam dan tidak berkomentar terhadap
ayat-ayat al-Qur’an yang Nabi tidak memberikan komentar terhadapnya. Nabi
pernah berdoa untuk Ibn ‘Abbās agar Allah memberinya pengetahuan tentang
ta’wīl.52 Di samping itu para sahabat juga telah berbeda pendapat dalam banyak hal
yang terkait dengan makna ayat-ayat al-Qur’an.53 Ini menunjukkan bahwa mereka
telah berijtihad atau menggunakan akalnya dalam memahami al-Qur’an. Hal ini juga
50Al-Turmudhī, Sunan al-Turmudhī, (Beirut: Dār Ih}yā’ al-Turāts al-‘Arabī, t.t.), Vol. 5, 199: Hadis No. 2951.
51Ibid., Hadis No. 2950.
52Ah}mad, Musnad al-Imām Ah}mad, (Mesir: Mu’assasah Qurt}ubah, t.t.), Vol. 1, 266: Hadis No. 2397.
53Khālid ‘Abd al-Rah}mān Us}ūl al-Tafsīr, 170.
72
merupakan indikasi bahwa Nabi tidak menjelaskan semua tafsir al-Qur’an kepada
para sahabatnya. Jadi pada masa Nabi ternyata telah dikenal ruang rasionalitas dalam
tafsir al-Qur’an. Jika ulama yang berpegang teguh pada tafsir naqlī – sementara yang
dikutip dalam tafsir naqlī termasuk pendapat-pendapat sahabat juga, dengan alasan
bahwa mereka adalah generasi yang dapat dipercaya sebagai paling memahami al-
Qur’an – menolak pendekatan rasional dalam tafsir, maka itu hanya merupakan
persoalan mentalitas dan keberanian intelektual saja. Jika al-Qur’an diyakini sebagai
wahyu yang diturunkan untuk umat manusia, maka tentu saja bukan hanya sahabat
yang hidup di zaman Nabi yang berhak memahami dan menafsirkannya. Kualitas
pemahaman manusia mungkin saja berbeda-beda, dan Tuhan pasti sangat mengerti,
tetapi sesungguhnya semua manusia punya potensi untuk memahami, dan potensi ini
tumbuh serta berkembang seiring dengan perkembangan peradaban dan pengetahuan
manusia serta kesadaran mereka terhadap dunia dan sejarah. Karena itu kebutuhan
setiap generasi dalam menafsirkan al-Qur’an tentu saja akan berbeda-beda sesuai
dengan tuntutan kehidupan zamannya.
Pendekatan rasional bukan tidak memiliki kelemahan. Setiap orang yang
menggunakan akalnya untuk berijtihad akan terpengaruh oleh tujuan-tujuannya
berijtihad. Bias kepentingan tertentu, pengalaman, prakonsepsi, latar belakang
kehidupan dan pengetahuan tetap membawa pengaruh bagi suatu upaya pemahaman.
Karena itu ulama membuat syarat-syarat yang ketat bagi kebolehan menggunakan
akal dalam menafsirkan al-Qur’an. Namun tetap saja syarat-syarat tersebut tidak
sepenuhnya menjadi standar, dan pembuatan syarat-syarat itu sendiri tetap saja dapat
dikritisi. Menurut penulis, prinsip dasar dalam tafsir rasional adalah keikhlasan dan
73
kejujuran. Ini memang tidak dapat diukur, tetapi di sinilah letak keluwesan
pendekatan model ini. Kekuatannya terletak pada keterbukaannya menerima kritik
dan keberaniannya dalam memberikan ruang bagi kebebasan berpikir. Kesalahan
dalam berpikir – sejauh menggunakan prinsip-prinsip kejujuran dan tanggung jawab
– lebih baik daripada tidak berpikir sama sekali.
Konsep dasar tafsir dengan pendekatan rasional, jika dihadapkan dengan
tafsir naqlī, tampak lebih potensial bagi perkembangan ilmu dan peradaban manusia:
bahwa setiap orang, bukan hanya sahabat Nabi, bebas berijtihad dalam menafsirkan
al-Qur’an sejauh hal tersebut dilakukan atas dasar pengetahuan yang dapat
dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, dalam pendekatan rasional ini, ruang
gerak tafsir al-Qur’an diberikan secara lebih longgar, terbuka, dinamis dan selalu
dapat dikritisi.
Tafsir dengan pendekatan ini sudah banyak ditulis. Sayangnya tidak sedikit
dari tafsir-tafsir tersebut digunakan untuk kepentingan pembelaan apologetik
mazhab-mazhab atau aliran tertentu. Bias kepentingan-kepentingan pribadi dan
kelompok masih menonjol. Al-Rāzī (w. 1209), misalnya, menulis Mafātih} al-
Ghayb, sebuah karya tafsir bi al-ra’y yang dianggap paling otoritatif dan
monumental. Al-Rāzī terkenal sebagai seorang teolog Muslim, ilmuwan pengembara,
polemikus paling agresif dan tangkas dalam berdebat, sehingga banyak memiliki
“musuh” intelektual. Karakteristik pribadinya yang jenius, “nakal”, berpikiran kritis
dan “tajam” ikut mewarnai gaya penafsirannya terhadap al-Qur’an. Al-Rāzī
membahas berbagai masalah dalam kitab tafsirnya dengan menggunakan logika
Aristotelian. Ketika membahas masalah-masalah keyakinan, al-Rāzī “mati-matian”
74
membela mazhab yang disebut dengan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā‘ah. Mafātih} al-
Ghayb adalah sebuah contoh tafsir rasional, yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an
dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan akal dan logika filsafat. Tafsir ini
menghasilkan pengetahuan baru dan perdebatan yang senantiasa menuntut
kecerdasan akal dan pengetahuan yang mendalam. Al-Rāzī adalah seorang ulama
yang memiliki pengetahuan keagamaan yang luas dan mendalam, seorang mufassir
yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Namun keterikatannya dengan
mazhab dan aliran tertentu membuatnya kadang-kadang terlalu kelihatan dalam
berapologi.
Apa pun kekurangannya, pendekatan rasional ini telah melahirkan keberanian
intelektual, kritisisme dan menginspirasikan jalan bagi pencarian berbagai rahasia
dan hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an. Makna ayat-ayat al-Qur’an
tidak lagi dicari semata-mata dalam nukilan-nukilan pendapat “orang-orang
terdahulu”, tetapi dalam alam nyata, imajinasi, pikiran dan bahkan dalam seluruh
elemen kehidupan yang terjangkau oleh manusia.
3. Pendekatan Linguistik dan Sastra
Bahasa tidak lain adalah simbol-simbol yang digunakan manusia untuk
mengekspresikan ide-ide, gagasan-gagasan, perasaan, pengalaman dan segala yang
ada dalam dirinya. Bahasa adalah simbol untuk mengungkapkan diri dan
berkomunikasi. Karena itu dalam antropologi manusia disebut animal symbolicum,
yakni makhluk simbol, sebab dalam kehidupannya, manusia tidak terlepas dari
75
penggunaan simbol-simbol, termasuk bahasa. Dengan demikian bahasa adalah alat,
yakni alat untuk berkomunikasi. Ketika al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab,
maka Tuhan berarti “meminjam” alat bahasa masyarakat Arab untuk
mengkomunikasikan pesan-pesan-Nya kepada mereka atau kepada manusia. Dalam
hal ini, yang menjadi pertanyaan adalah: sejauh mana bahasa tersebut
merepresentasikan maksud yang sesungguhnya dari seorang komunikator. Ini
sebenarnya akan didiskusikan lebih jauh dalam bagian berikutnya, tentang
pendekatan hermeneutik. Di sini hanya akan dikemukakan gambaran ringkas aspek-
aspek kebahasaan sebagai pendekatan dalam memahami al-Qur’an dan bagaimana
sebagian ulama tafsir telah menempuh pendekatan ini.
Dalam satu aspek, pendekatan kebahasaan sama dengan pendekatan naqlī,
karena ia menuntut kepada kepatuhan akan hukum-hukum kebahasaan. Bahasa
bukan hanya bisa dikuasai, tetapi juga menguasai. Orang yang ingin “menguasai”
suatu bahasa harus bersedia “dikuasai” oleh peradaban bahasa tersebut. Karena
bahasa adalah peradaban, maka penguasaan terhadapnya terikat oleh peradaban.
Karena itu maksud atau pengertian dari suatu ungkapan dalam suatu bahasa mesti
dirujuk kepada pemilik bahasa dan peradaban tersebut, tidak bisa hanya diduga-duga.
Dalam kaitan dengan penafsiran al-Qur’an maka penguasaan bahasa Arab adalah
suatu keniscayaan, dan rules yang digunakan adalah rules yang ditetapkan oleh
peradaban Arab.
Tetapi dari sisi lain, pendekatan kebahasaan tidak terlepas juga dari logika
pemahaman, sehingga ia terkait dengan aspek-aspek pendekatan rasional. Bahasa
bukanlah rules yang kaku dan matematis, tetapi ia hidup dan dinamis. Ia harus
76
dicerna dan dianalisa; ia memiliki makna yang melampaui garis-garis yang mungkin
ditarik berdasarkan aturan-aturan gramatikal. Jadi bahasa juga memiliki aspek ra’y
(rasionalitas, akal).
Tafsir dengan pendekatan linguistik (kebahasaan) adalah tafsir yang mencoba
menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dari aspek kebahasaan. Bahasa yang digunakan
dalam al-Qur’an dianalisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan makna-makna
yang, dari sudut pandang linguistik, lebih jelas, terang dan terarah. Kata-kata dan
kalimat-kalimat yang digunakan dalam al-Qur’an kadang-kadang “membingungkan”
dan kabur, terutama sekali bagi non-Arab. Di sinilah letak tugas tafsir dengan
pendekatan linguistik: menjelaskan dan menghilang kekaburan tersebut.
Para sahabat Nabi, dalam memahami bahasa al-Qur’an, tidak jarang merujuk
kepada syair-syair zaman jahiliah. Tidak kurang dari Ibn ‘Abbās, tokoh tafsir
terkenal kalangan sahabat yang bergelar turjumān al-Qur’ān, dan ‘Umar Ibn al-
Khat}t}āb, tokoh sahabat besar, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap syair-
syair pra-Islam.54 Dalam al-Itqān, al-Suyūt}ī (w. 911 H.) mengutip riwayat yang
menyebutkan Ibn ‘Abbās mengatakan bahwa: “Syair adalah khazanah Arab; karena
itu jika ada satu huruf yang tidak jelas bagi kita dari al-Qur’an, di mana Allah telah
menurunkannya dalam bahasa Arab, maka kita merujuk pada khazanahnya.” Pada
riwayat lain disebutkan Ibn ‘Abbās berkata: “Jika kamu sekalian bertanya kepadaku
istilah-istilah yang asing dalam al-Qur’an, maka carilah dalam syair-syair;
sesungguhnya syair itu adalah khazanah Arab.”55
54Khālid ‘Abd al-Rah}mān Us}ūl al-Tafsīr, 140.
55Al-Suyūt}ī, al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, (Kairo: Mus}t}afā al-Bābī al-H{alabī, 1370 H.). Juz I, 119-120.
77
Kesadaran akan aspek bahasa dalam melakukan kajian terhadap al-Qur’an
ternyata sudah ada sejak awal sejarah tafsir al-Qur’an, walaupun pada masa tersebut
belum dilakukan studi dalam bentuk yang lebih sophisticated. Studi secara lebih
mendalam terhadap al-Qur’an dengan menggunakan berbagai aspek linguistik dalam
bahasa Arab, seperti s}arf, nah}w dan balāghah, dilakukan belakangan, setelah
muncul gerakan-gerakan yang secara spesifik memfokuskan diri pada studi bahasa
dan sastra. Berbagai kitab tafsir telah memberikan perhatian khusus pada aspek
bahasa, dan hal ini telah melahirkan khazanah tafsir yang kaya raya. Al-Kasysyāf
adalah sebuah contoh kitab tafsir yang memberikan ulasan kebahasaan sangat
mendalam terhadap ayat-ayat al-Qur’an. Meskipun penulisnya, al-Zamakhsyarī (w.
1144 M./538 H.), dikenal sebagai seorang Mu‘tazilah dan karyanya al-Kasysyāf
dipenuhi oleh pembelaan-pembelaan terhadap aliran tersebut, berbagai penjelasannya
terhadap ayat-ayat al-Qur’an dalam aspek kebahasaan diakui sebagai yang paling
berkualitas dan patut dijadikan rujukan penting, baik oleh pengikut aliran tersebut
maupun oleh “lawan-lawan”nya.
Bahasa adalah sisi peradaban manusia yang paling kaya, karena ia hidup,
berkembang dan dinamis. Seperti telah disebutkan di atas, bahasa tidak hanya
memiliki sisi naqlī, tetapi juga sisi aqlī. Bahasa memang harus mengikuti aturan
peradaban, namun ia juga berkembang sesuai dengan berkembangnya peradaban.
Walaupun telah banyak karya tafsir yang ditulis dengan menonjolkan aspek
kebahasaan, tidak menutup peluang bagi kemungkinan pengkajian kembali ayat-ayat
al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan tersebut.
78
4. Pendekatan Hermeneutika Multikultural: Tafsir Kritis
Hermeneutika (hermeneutics) berasal dari bahasa Yunani hermēneuein (kata
kerja), umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan to interpret
(menafsirkan) dan hermēneia (kata benda), diterjemahkan dengan interpretation
(tafsiran). Kata ini dapat ditemukan dalam sejumlah teks kuno Yunani dan digunakan
oleh banyak penulis kuno terkenal negeri itu, seperti Xenophon, Plutarch, Euripides
dan Epicurus; bahkan beberapa kali kata tersebut terdapat dalam karya Plato.56
Kata hermēneia dalam tradisi Yunani merujuk lebih jauh pada seorang dewa
bernama Hermes. Ia bertugas mentransformasikan segala hal di luar pemahaman
manusia ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh kecerdasan manusia. Ia juga
disebut-sebut sebagai penemu bahasa dan tulisan yang dijadikan alat oleh manusia
untuk menangkap pesan serta makna-makna dan menyampaikannya kepada orang
lain. Dari pengertiannya yang klasik dalam tradisi Yunani itulah berakar
hermeneutika modern, yang tidak lain menunjuk kepada the process of “bringing to
understanding”, terutama sekali proses yang melibatkan bahasa, karena bahasa itulah
medium par excellence dalam komunikasi manusia.57
Belakangan ini istilah hermeneutika telah sangat populer dalam berbagai
kajian keilmuan, bukan hanya untuk studi teks kitab suci. Ini disebabkan oleh
karakteristik manusiawi dan spirit yang dimiliki hermeneutika. Hermeneutika
mengacu pada pemahaman dan upaya menangkap spirit dari sebuah objek. Ia
56Richard E. Palmer, Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer, (Evanston: Northwestern University Press, 1969), 12.
57Ibid., 13.
79
membantu manusia yang selalu ingin mencari, bahkan meraba dalam kegelapan.
Hasrat manusia untuk menjangkau segalanya tidak pernah berhenti. Manusia bahkan
ingin menembus segala batas. Hermeneutika adalah salah satu alat yang memberikan
harapan bagi potensi tersebut. Hermeneutika membuka ruang bagi penelusuran dan
penjelajahan ke luar batas ruang dan waktu. Hermeneutika adalah konsep penafsiran
dengan mengkombinasikan berbagai sisi yang mungkin dipertemukan untuk
mencapai sebuah makna yang lebih utuh, relevan dan applicable. Bahasa dan
pemahaman adalah inti dari hermeneutika; inilah yang membedakan pendekatan
hermeneutik dari pendekatan linguistik yang didiskusikan dalam tulisan ini. Jika
linguistik mengungkapkan secara apa adanya sebuah bahasa sebagaimana
dikehendaki oleh aturan-aturan kebahasaan, maka hermeneutika berupaya mencapai
makna yang lebih jauh serta menjangkau ke luar batas-batas aturan kebahasaan.
Hermeneutika melampaui wilayah-wilayah ruang dan waktu, melintasi sejarah dan
peradaban.
Hermeneutika lahir di dunia Barat dengan latar belakang tradisi Yudeo-
Kristiani dan filsafat Yunani. Konsep ini dimunculkan sebagai upaya memahami
kembali kitab suci yang dirasa seperti telah kehilangan relevansinya di hadapan ilmu
pengetahuan modern atau sains. Dengan hermeneutika, kitab suci yang ditulis
berabad-abad silam dijembatani untuk dimaknai kembali dengan pengertian-
pengertian yang lebih segar, relevan dan dapat diterapkan dalam setting kehidupan
dan kerangka pikir kekinian. Kemunculan konsep ini di dunia Barat telah menjadi
alasan timbulnya kecurigaan di kalangan orang-orang Timur, terutama sekali
kalangan Muslim. Hermeneutika dianggap tidak relevan untuk kajian Islam, sebab ia
80
dilahirkan oleh dunia asing, oleh Yunani, dan kemudian dibesarkan oleh Barat yang
bertradisi Yahudi dan Kristen. Pandangan seperti ini sebenarnya lebih merupakan
ketakutan yang tidak beralasan. Kebenaran, kejujuran, intelektualitas dan juga
spiritualitas tidak mengenal wilayah geografis dan peradaban. “Ambillah hikmah
dari mana pun sumbernya” telah merupakan pegangan para sarjana Muslim sejak
zaman dahulu. Jika hermeneutika dapat menawarkan sebuah solusi keilmuan untuk
studi Islam, mengapa harus ditolak. Untuk itu diskusi tentang hermeneutika,
walaupun secara singkat, akan dimulai dari sejarah kemunculannya di Barat.
Perkembangan agama di Eropa abad 19 telah mengantarkan para pemikir di
sana pada suatu suasana yang disebut dengan “kesadaran sejarah baru.”58 Klaim-
klaim keagamaan dan kebenaran absolut oleh gereja Kristen mulai mendapat
kritikan-kritikan ilmiah dari tokoh-tokoh agama sendiri. Kesadaran pluralisme agama
memunculkan dirinya secara perlahan beriringan dengan lahirnya konsep-konsep
pemikiran liberal. Superioritas Kristen sebagai sebuah agama manusia dan klaim
kemutlakannya dipertanyakan dan orang mulai tertarik pada upaya-upaya pencarian
makna ajaran agama secara lebih mendalam dan hakiki. Tafsiran terhadap ajaran
agama, khususnya yang terdapat dalam kitab suci, dengan cara yang “tidak ortodoks”
dan perhatian pada ilmu pengetahuan modern serta sejarah, sebagai dasar
pertimbangan dalam memahami kitab suci, diangkat sedikit demi sedikit oleh kaum
Protestan liberal. Tema-tema yang mengandung spekulasi rasional dalam teologi
58Muhammad Legenhausen, Satu Agama atau Banyak Agama, terj. Arif Mulyadi dan Ana Farida (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), 33.
81
diperkenalkan.59 Semua ini berdampak pada gugatan terhadap agama dan membawa
konsekuensi bagi pemahaman dan tafsiran baru terhadap agama.
Sikap kritis terhadap ajaran agama di satu sisi dan keinginan batin untuk tetap
memeluk dan menghayati agama di sisi lain mendorong para pemikir dan filosof
Eropa abad 19 untuk memperbarui pandangan dan sikap keagamaan mereka. Benih
kesadaran ini telah dilontarkan oleh pendiri Protestanisme liberal sendiri, Friedrich
Schleiermacher (1768-1834), ketika ia masih membela superioritas Kristen namun
menganggap bahwa sesungguhnya inti ajaran agama terletak pada jiwa manusia dan
penghayatan nilai yang melebur dalam kehendak Tuhan yang Tak Terbatas, bukan
pada doktrin-doktrin formal dan sistem keagamaan institusional. Inti agama tidak
melekat pada penampakan-penampakan lahiriahnya, tetapi pada kesadaran batin
manusia yang amat dalam.60 Meskipun Schleiermacher masih membela keimanan
Kristen sebagai puncak dari kesempurnaan pengalaman keagamaan manusia,
sekurang-kurangnya, ia telah memperkenalkan kesadaran akan keterkandungan
kebenaran Ilahi dalam agama-agama lain.61
Seorang teolog Protestan asal Jerman, Ernst Troeltsch (1865-1923), yang
sangat berpengaruh terhadap para teolog muda zamannya, menegaskan pentingnya
gereja Kristen melakukan pengkajian ulang terhadap klaim-klaim kebenaran
absolutnya. Pembelaan terhadap Kristen, dengan berbagai argumentasi kemukjizatan,
tidak mungkin lagi dilakukan dengan adanya pendekatan historis modern. Jika
59Ibid., 27-28.
60Dikutip dari Glyn Richards, Toward a Theology of Religions, (London: Routledge, 1989), 37.
61Muhammad Legenhausen, Satu Agama, 28-29.
82
argumentasi-argumentasi kemukjizatan dalam agama Kristen diterima, maka, dengan
metode yang sama, seluruh kisah-kisah mukjizat dalam semua agama lain juga harus
diterima. Berbeda dari tokoh-tokoh sebelumnya, Troeltsch menolak pandangan
bahwa ajaran Kristen merupakan puncak evolusi pengalaman keagamaan yang
sempurna. Pandangan seperti itu, menurutnya, tidak lebih dari refleksi pengalaman
keagamaan pribadi para teolog liberal dan bukan hasil objektif sebuah studi historis.62
Walaupun pada awalnya Troeltsch berupaya melakukan pembelaan terhadap ajaran
Kristen, dalam tulisan-tulisannya yang terakhir terbukti ia menyerah dan menyatakan
bahwa kebenaran agama Kristen bersifat relatif dan terbatas pada kultur komunitas
Kristen saja, sebagaimana dalam semua agama juga terdapat kebenaran yang relatif
dan menjadi ajaran normatif bagi pemeluknya semata.63
Kesadaran liberal kaum Protestan inilah – yang kemudian mengarah pada
munculnya pluralisme agama – penabur benih hermeneutika modern. Schleiermacher
dikenal sebagai “Bapak Hermeneutika” karena dialah yang telah mengangkat
kembali hermeneutika menjadi sebuah metode interpretasi, baik untuk diterapkan
pada analisis teks kitab suci dan sastra maupun pada studi-studi lain. Dua tokoh
pendahulunya, Friedrich Ast (1778-1841) dan Friedrich August Wolf (1759-1824)
sangat berpengaruh terhadap pemikiran hermeneutika Schleiermacher. Seruannya
menuju konsep baru hermeneutika yang ia kemukakan dalam sebuah kuliah pada
1819 merujuk kepada kedua tokoh tersebut.64 Menurut Ast, tugas hermeneutika
adalah “mengklarifikasi sebuah karya melalui pengembangan maknanya secara
62Ibid., 31.
63Glyn Richards, Toward a Theology, 25-31.
64Richard E. Palmer, Hermeneutics, 75.
83
internal dan pengembangan hubungan antara bagian-bagian dalamnya serta
hubungan dengan semangat zamannya.”65 Tugas ini mempunyai tiga bagian: historis
(konteks sebuah karya), gramatikal (hubungannya dengan bahasa), dan spiritual
(hubungannya dengan pandangan yang menyeluruh tentang pengarang dan
pandangan yang menyeluruh tentang semangat zaman).66 Sementara itu Wolf
menyatakan bahwa tujuan hermeneutika adalah “untuk menangkap (memahami)
pemikiran-pemikiran tertulis maupun terucap dari seorang pengarang sebagaimana
diinginkan oleh pengarang itu untuk dipahami.”67
Dua tokoh inilah yang memberikan andil dalam pembentukan teori
hermeneutika Schleiermacher. Keduanya adalah tokoh klasik yang meletakkan dasar-
dasar filologi modern. “Grammatical” interpretation masih mendapat tempat yang
kuat dalam pemikiran mereka, namun kecenderungan historis telah memiliki nuansa
yang lebih dalam. Schleiermacher mengangkat konsep hermeneutika mereka ke level
yang lebih filosofis. Meskipun interpretasi gramatikal masih foundational,
penekanannya sudah mengarah pada interpretasi psikologis dan pembentukan
konsepsi dasar tentang bagaimana pemahaman manusia beroperasi dalam dialog.
Menurutnya, kunci hermeneutika adalah pemahaman. Pemahaman adalah sebuah
proses yang misterius dan mengagumkan. Ia hidup dan bergerak dengan sendirinya.
65Friedrich Ast, Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und Kritik, (Lanshut: Thomann, 1808), 174-175.
66Richard E. Palmer, Hermeneutics, 77.
67Friedrich August Wolf, Vorlesung u\ber die Enzyklopa\die der Altertumswissenschaft, ed. J.D. Gürtl, (Leipzig: Lehnhold, 1831), Vol. 1, 293.
84
Ia merupakan seni dan keahlian dalam mentransformasikan simbol-simbol, bahkan
dalam memberi makna terhadap seluruh tindakan, perasaan dan institusi manusia.68
Setelah Schleiermacher, hermeneutika diusung oleh filosof dan sejarawan
Wilhelm Dilthey (1833-1911), filosof Martin Heidegger (1889-1976), filosof Hans-
Georg Gadamer (1900-2002) dan para filosof kontemporer lainnya. Mereka
membawanya ke arah pemikiran filsafat yang lebih kompleks dan sebagai landasan
bagi ilmu-ilmu kemanusiaan. Ketika agama telah diposisikan sebagai bagian dari
ilmu-ilmu kemanusiaan maka konsekuensinya adalah bahwa agama dapat dikaji
secara kritis, termasuk kitab suci yang menjadi landasan bagi agama itu sendiri.
Ketika Dilthey69 menekankan pentingnya dimensi historis dalam hermeneutika maka
kajian terhadap kitab suci tidak terlepas dari kritik historis. Ketika hermeneutika
diterapkan sebagai the phenomenological method of investigation oleh Heidegger70
maka agama dan kitab suci ditelaah melalui berbagai manifestasi yang dapat dicerap
oleh manusia dan ditafsirkan melampaui batas-batas pencerapan tersebut. Segala
yang tampak dan yang tidak tampak dari struktur eksistensi manusia dan dunia harus
dipahami dan diinterpretasikan. Ketika mengaitkan pemahaman manusia dengan
peristiwa-peristiwa historis, dialektik dan linguistik, Gadamer71 telah menjadikan
hermeneutika sebagai ontologi dan sekaligus fenomenologi pemahaman.
Hermeneutika menjadi sesuatu yang dialektik. Dengan konsep dan metode ini,
tafsiran terhadap agama tidak lagi bertumpu pada otoritas maupun sebuah sisi
68Richard E. Palmer, Hermeneutics, 84-85.
69Lihat ibid., 98 ff.
70Lihat ibid., 124 ff.
71Lihat ibid., 194 ff.
85
pemahaman tertentu. Pemahaman terhadap agama dapat dikembangkan sesuai
dengan perkembangan dialektika manusia dalam sejarah dan peradaban.
Berangkat dari hermeneutika inilah, istilah “tafsir kritis” dikembangkan dan
diajukan sebagai sebuah alternatif bagi kajian al-Qur’an (tafsir) dalam disertasi ini.
Dengan kata lain, hermeneutika yang dimaksudkan di sini, dalam istilah yang lebih
sederhana, adalah “tafsir kritis.” Lalu mengapa “tafsir kritis”? Karena ia menjelaskan
makna-makna, menyadarkan dan membongkar kemapanan.72 Tafsir kritis melibatkan
bahasa, simbol, emosi dan intelektualitas dalam mengupayakan sebuah pemahaman.
Ia mempertimbangkan sejarah, peradaban, serta psikologi “kita” (the insiders) dan
“mereka” (the outsiders). Pemahaman terhadap ayat-ayat mengenai Yahudi yang
dijadikan topik kajian ini, ditafsirkan dengan cara mendialogkannya dengan berbagai
pengalaman dan pengetahuan kontemporer; ayat-ayat al-Qur’an yang diturunkan
pada masa lalu ditafsirkan dengan memberi makna yang lebih aplikatif dan
bermanfaat untuk hari ini.
Teori yang lebih menentukan lagi untuk dipertimbangkan adalah
“hermeneutika multikultural.” Hermeneutika inilah yang menjadi basis bagi proses
kerja “tafsir kritis” dalam kajian ini.
72Penulis, seperti telah disebutkan dalam bab satu, mengadopsi istilah ini dari Gregory Baum ketika ia berbicara mengenai critical theology. Ada paralel di antara keduanya. Istilah kritis di sini bermaksud menjangkau segala wilayah yang relevan, menghindari keberpihakan dan segala bentuk keterlibatan dalam kepentingan politik tertentu. Kritis juga dimaksudkan sebagai kejelian memisahkan tujuan agama dari apa yang telah dihasilkan oleh agama dalam kehidupan manusia; memisahkan antara the intention dan the consequences dari agama. Jadi, baik teologi kritis maupun tafsir kritis, sama-sama bertujuan untuk mengaktualkan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat; menjadikan pemahaman keagamaan sebagai sesuatu yang konkret dan efektif dalam kehidupan nyata – dalam istilah Baum, reflection on praxis. Lihat Gregory Baum, Religion and Alienation: A Theological Reading of Sociology, (New York: Paulist Press, 1975), 195.
86
Banyak Muslim, dan juga umat-umat lain, melakukan pembacaan terhadap
kitab sucinya atas dasar iman yang telah terlebih dahulu dibangun berdasarkan
otoritas. Mereka memahami pesan kitab suci dalam kerangka keyakinan yang telah
tumbuh terlebih dahulu dan mungkin tidak didasari pada pengetahuan serta
argumentasi yang kuat. Kemudian mereka hanya merasa berkewajiban untuk tetap
setia pada iman yang telah dimilikinya (benar ataupun salah) dan
mempertahankannya bahkan sampai tetes darah terakhir. Pembacaan tradisional atas
kitab suci seperti ini tentu saja menutup kemungkinan bagi dialog yang lebih terbuka.
Orang terlalu ditakut-takuti dengan istilah bid‘ah, sesat dan murtad, padahal
penerapan istilah-istilah itu sendiri cenderung dilakukan serampangan dan tidak pada
tempatnya. Pembacaan terhadap kitab suci semestinya dilakukan secara lebih sehat
dan dengan akal terbuka, sehingga pesan dari kitab suci itu sendiri dapat dipelajari
dengan cara yang lebih jernih, bukan pesan yang dipaksakan sesuai dengan kehendak
otoritas tradisional. Untuk itu dalam melakukan pembacaan terhadap kitab suci
diperlukan upaya untuk bergerak melampaui the “innocent” manner dan melangkah
ke model pembacaan baru: the “no innocent” manner. Pembacaan model yang kedua
inilah, seperti dikatakan González, yang akan menjadikan seseorang mampu melihat
kesalahan dan kegagalan dirinya.73 Banyak orang kadang-kadang terlalu takut ketika
menemukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah diketahui atau
diyakininya selama ini, sehingga membuang pengetahuan berharga dan lebih
memilih diam demi mempertahankan sebuah keyakinan yang rapuh.
73Justo L. González, Mañana: Christian Theology from a Hispanic Perspective (Nashville: TN: Abbingdon Press, 1990), 78-79.
87
Pembacaan yang innocent melihat segala sesuatu yang dibaca sebagai
kebenaran, dan menyingkirkan segala nalar kritis terutama sekali yang dapat
menyalahkan diri pembaca sendiri. Teks-teks yang dibaca tidak dipertentangkan
antara yang satu dengan yang lain, tetapi dilakukan dengan cara yang selektif,
sehingga bagian-bagian yang tidak “menguntungkan” ditinggalkan atau ditafsirkan
sesuai dengan yang diinginkan. Sebaliknya pembacaan yang noninnocent
meniscayakan kesediaan untuk menerima diri sebagai manusia yang tidak luput dari
kesalahan dan kegagalan sehingga merasa perlu selalu membuka diri untuk dikritik
dan dikoreksi. Pembacaan seperti ini akan membuka ruang dialog yang lebih sehat
dan luas serta memungkinkan si pembaca bersikap berani memasuki wilayah-
wilayah mana pun dari potensi kemanusiaannya.
Al-Qur’an adalah teks yang suci dan harus dihormati. Al-Qur’an lebih layak
dijadikan hakim untuk menilai pandangan, cara hidup dan sikap moral “kita,” bukan
malah dijadikan landasan dan pendukung bagi arogansi “kita” untuk menciptakan
konflik dan melawan “orang lain.”
Pembacaan al-Qur’an dengan cara noninnocent akan memudahkan proses
kerja hermeneutika multikultural, karena ia selalu menyisakan ruang untuk kritik dan
koreksi meskipun berasal dari wilayah yang asing. Noninnocent menjadikan
seseorang sadar, rendah hati, tidak arogan dan respek terhadap sesama. “Saya”
ataupun “kita” bukanlah satu-satunya pemilik kebenaran dan “kita” seharusnya
welcome meski terhadap mereka yang punya pandangan berbeda atau berseberangan.
Hal ini bisa terlihat dari prinsip-prinsip hermeneutika multikultural itu sendiri
sebagaimana dikemukakan oleh Douglas Jacobsen dalam artikelnya Multicultural
88
Evangelical Hermeneutics and Ecumenical Dialogue. Menurut Jacobsen74 ada empat
prinsip yang membantu seseorang bernegosiasi dengan diversitas hermeneutika di
sekitar dirinya. Pertama, seseorang menyadari bahwa ia tidak berangkat dari awal.
We all “start in the middle.” Banyak orang mengatakan bahwa menafsirkan kitab
suci haruslah dengan sikap yang netral. Dalam tradisi Islam sudah dikenal luas
bahwa di antara syarat seorang mufassir adalah tidak fanatik kepada suatu mazhab
atau aliran. Seorang mufassir harus dapat memposisikan dirinya sebagai seorang
peneliti yang independent, tidak memihak dan jujur secara akademik. Ini sepertinya
telah menjadi mitos yang menyenangkan untuk didengar dan mungkin orang mengira
amat mudah melakukannya. Namun, sesungguhnya manusia tidak terlepas dari dunia
dalam dirinya. Pada saat membaca sebuah teks, seseorang acap kali membacanya
dengan paradigma yang telah terbentuk dalam dirinya; seseorang adakala membuat
teks itu masuk akal atau menjadikannya sebagai nonsense, sesuai dengan
keyakinannya tentang kebenaran. Pada saat memahami sebuah teks, orang lalu
cenderung memahaminya sejalan dengan warisan tradisi dan budaya yang
dimilikinya: prasuposisi, pradisposisi dan prapemahaman selalu mempengaruhi cara
pikir dan kecenderungan nalar dirinya. Jadi dengan menyadari hal ini, orang dapat
lebih berhati-hati dalam memposisikan diri berhadapan dengan teks. Sikap seperti ini
tidak mesti mengubah pandangan seseorang mengenai otoritas teks, tetapi dapat
mengubah cara seseorang menemukan makna yang diungkapkan oleh teks.
Kedua, berdialog dengan orang-orang yang tidak sepaham. Adalah awal dari
kesalahan ketika orang menganggap dirinya tidak bersalah. Adalah pemilik pikiran
74Douglas Jacobsen, “Multicultural Evangelical Hermeneutics and Ecumenical Dialogue”, Journal of Ecumenical Studies, Vol. 37, No. 2, Spring 2000, 133-137.
89
yang sempit orang yang menganggap dirinya berpikiran sangat luas. Dunia dan
pengetahuan tidak ada batas. Manusia tidak akan mampu melihat segala sesuatu
sekaligus; manusia penuh dengan keterbatasan. Ketika orang melihat ke satu arah,
pandangannya tertutup untuk arah yang lain. Orientasi menghalangi seseorang untuk
menggapai segalanya. Inilah yang oleh Mikhail Bakhtin (w. 1975), seorang filosof
Bahasa dan teoritikus sastra Rusia, disebut dengan law of placement.75 Ruang dan
waktu menghalangi manusia mengusai segalanya. Karena itu setiap orang
membutuhkan orang lain yang bahkan berbeda orientasi dan pandangan darinya;
karena itu, juga sangat penting bagi seseorang untuk mengakui bahwa hanya karena
ia tidak dapat melihat sesuatu, yang orang lain dapat melihatnya, tidak berarti sesuatu
itu tidak eksis. Dengan berdialog dengan “orang lain,” seseorang akan mendapatkan
a new “surplus of seeing.”76 Dialog tidak mesti membawa seseorang kepada sebuah
kesimpulan yang harus diambil, tetapi dialog dapat memperkaya dunia setiap orang
yang terlibat di dalamnya.
Ketiga, melakukan pergantian hermeneutik, antara diam dan berjuang.
Hermeneutical struggle tentu saja tidak akan berujung ketika ia terus menerus
didialogkan. Poin kedua di atas membawa seseorang pada perputaran dialog yang
tidak berkesudahan. Ini akan membingungkan. It is thus writ in heaven that any critic
who has not given up will remain to some degree confused.77 Tidak akan ada manusia
yang dapat menyelesaikan dialog ini dengan tuntas. Lalu mengapa berdialog? Karena
75Michael Holquist, Dialogism: Bakhtin and His World, (London and New York: Routledge, 1990), 21.
76Ibid., 36.
77Wayne C. Booth, Critical Understanding: The Power and Limits of Pluralism, (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 340.
90
manusia telah memulainya; mereka sedang berada di tengah jalan. Jadi
pertanyaannya bukan mengapa berdialog, tetapi bagaimana seseorang harus
menyikapinya?78 Dalam hal memahami teks kitab suci, seseorang memang harus
berjuang untuk mendapatkan pemahaman yang benar, tetapi tidak berarti bahwa
ketika dialog tidak berhenti maka kebenaran juga tidak pernah diterapkan dalam
kehidupan. Orang perlu “beristirahat” sejenak untuk mengamalkan “kebenaran” yang
telah dicapainya, untuk kemudian bergumul kembali dengan pemahaman dan makna-
makna kehidupan yang tiada habisnya. Inilah barangkali makna taqarrub dalam
tradisi Islam: bahwa kebenaran hanya dapat didekati, tidak dapat ditangkap
hakikatnya.
Keempat, bersikap terbuka dengan hati-hati terhadap hermeneutika masa
depan. Manusia tidak perlu terlalu terikat dengan masa lalu, karena masa lalu tidak
semuanya dapat dijamin baik; juga tidak perlu takut kepada masa depan, karena tidak
semuanya buruk. Ada sebagian orang terlalu bernostalgia dan memuja masa lalu
berlebihan, sementara yang lainnya terlalu terobsesi dengan harapan-harapan masa
depan yang membawa kemajuan dan inovasi yang sophisticated. Sikap ini secara
hermeneutik perlu diseimbangkan dengan hati-hati. We need to respect the
interpretative islands on which we and others have come to rest for the time being,
but we must remember that those resting places are not permanent hermeneutical
homes.79
Diskusi di atas memperlihatkan jalan yang telah ditempuh dan jalan yang
mungkin untuk ditempuh dalam upaya memahami al-Qur’an. Hermeneutika
78Douglas Jacobsen, “Multicultural,” 135.
79Ibid., 137.
91
multikultural adalah sebuah model pendekatan dalam melakukan pembacaan
terhadap al-Qur’an yang diandalkan dapat memberi nuansa baru untuk menghasilkan
pemahaman lebih baik dalam konteks diversitasnya kehidupan manusia, khususnya
umat beragama, di zaman ini.
C. Tafsir/Ta’wīl : Penalaran atas Wahyu
Dalam sejarah dan perkembangan tafsir al-Qur’an, tafsir telah merupakan
sebuah kerja individual dalam memahami makna ayat-ayat al-Qur’an. Sebagaimana
telah didiskusikan sebelumnya, pemahaman merupakan kegiatan akal yang bersifat
sangat pribadi dan subjektif. Setiap mufassir menggunakan penalarannya sendiri
yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman hidupnya serta lingkungan
peradaban di mana dia berada untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an yang dianggap
perlu dijelaskan. Kitab-kitab tafsir umumnya ditulis oleh ulama Islam di berbagai
wilayah dunia Islam secara independen; masing-masing dengan nuansa, pola pikir,
metode dan tujuannya sendiri. Tafsir menjadi sebuah wilayah ilmu yang sangat luas
dan kaya, seluas imajinasi manusia – tanpa batas. Walaupun pada awalnya tafsir
mengalami ruang gerak yang agak sempit dengan the rules of interpretation-nya
yang ketat, dalam perkembangannya kemudian ia menjadi sangat terbuka dan liberal.
Masing-masing mazhab dan aliran dalam Islam hampir dapat dikatakan memiliki
tafsir tersendiri, yang menjelaskan dan membela mazhab atau alirannya, walaupun,
92
di samping itu, terdapat juga tafsir-tafsir yang mencoba melintas mazhab-mazhab
dan aliran.
Tafsir, dari kata bahasa Arab tafsīr, artinya penjelasan. Kata ini ke dalam
bahasa Inggris sering diterjemahkan dengan interpretation. Di samping itu ada kata
lain yang hampir sepadan dengan tafsir yaitu ta’wīl. Para ulama atau pakar ‘Ulūm al-
Qur’ān memperdebatkan pengertian kedua kata tersebut: apakah keduanya memiliki
pengertian yang sama atau tidak, atau yang satu lebih umum dari yang lain. Kata-
kata lain yang secara teknis mempunyai pengertian yang sama dengan tafsir, seperti
syarh}, ma‘ānī dan ta‘bīr, hampir dapat dipastikan tidak digunakan untuk komentar
atau penjelasan bagi al-Qur’an. Istilah syarh} dan ma‘ānī sering digunakan untuk
komentar hadis; sedangkan ta‘bīr, dalam literatur Arab, umumnya digunakan untuk
tafsir mimpi, seperti ta‘bīr al-manām atau ta‘bīr al-ru’yā.
Tafsir umumnya dipahami oleh para sarjana Muslim sebagai penjelasan
terhadap suatu ungkapan baik murni maupun simbolik, sedangkan ta’wīl adalah
pencarian terhadap hakikat yang dimaksudkan oleh ungkapan tersebut. Tafsir lebih
bersifat teknis, sementara ta’wīl mengungkapkan makna-makna yang lebih dalam
dan tersembunyi. Dalam ungkapan yang lebih populer disebutkan bahwa tafsir
menjelaskan makna-makna yang didapatkan berdasarkan wad}‘ al-‘ibārah,
sementara ta’wīl menemukan makna bi t}arīq al-isyārah. Ada juga yang
menyebutkan bahwa tafsir terkait dengan riwāyah, sedangkan ta’wīl dengan dirāyah.
Tafsir menyingkap dan menjelaskan maksud-maksud ayat sebagaimana dikehendaki
oleh Allah, karena itu ia mesti dirujuk kepada hadis-hadis Nabi atau pendapat
sahabat yang mengerti konteks turun ayat itu sendiri. Adapun ta’wīl, hanya terbatas
93
pada upaya memahami lafaz-lafaz yang ambigu, tidak terang dan memerlukan
kepada pengetahuan bahasa yang luas serta kemampuan berijtihad.80
Sepertinya perselisihan tentang pengertian ta’wīl muncul beriringan dengan
perselisihan mengenai prinsip-prinsip penerapan ta’wīl itu sendiri. Ketika filsafat
Yunani menembus jaringan pemikiran Islam sekitar abad 2 Hijrah, muncullah
oposisi-oposisi terhadap kaum pembela otoritas absolut wahyu dan sunnah Nabi
(mereka adalah kaum Mu‘tazilah atau kelompok rasionalis dan para filosof Muslim)
serta para penentang mereka di kalangan mutakallimūn Muslim yang berkembang
lebih pesat pada abad 3-4 Hijrah. Kelompok rasionalis dituduh oleh pihak penguasa
agama formal dan mapan sebagai telah memahami al-Qur’an sesuai dengan
kehendak hawa nafsu mereka, tidak mengikuti petunjuk-petunjuk sebagaimana telah
digunakan oleh para salaf atau ulama terdahulu. Maka mereka dikatakan telah
“menta’wīlkan” al-Qur’an dengan cara-cara yang jauh menyimpang dari maksud al-
Qur’an itu sendiri. Tuduhan “menggunakan ta’wīl sekehendak hati” tentu lebih
mudah dan kelihatan lebih tepat digunakan dibandingkan tuduhan “menafsirkan
sekehendak hati.” Lagi pula, ta’wīl dalam pengertian dasarnya bisa bermakna
memalingkan sebuah makna kepada makna lain. Dari situ muncullah perbedaan yang
signifikan antara tafsir dan ta’wīl. Kaum rasionalis sendiri lebih suka menggunakan
istilah ta’wīl daripada tafsir, bahkan ta’wīl telah menjadi salah satu asas pemikiran
mereka.81
80Khālid ‘Abd al-Rah}mān, Us}ūl al-Tafsīr wa Qawā‘iduh, (Beirut: Dār al-Nafā’is, 1986), 52-53.
81Ibid., 55.
94
Sebaliknya bagi kelompok pengukuh kemapanan, yang menyebut dirinya
pemegang sunnah dan pemilik mayoritas (ahl al-sunnah wa al-jamā‘ah), ta’wīl
mengisyaratkan hal negatif. Ta’wīl, menurut mereka, adalah pengotoran terhadap
kalam Tuhan dan mencerminkan kesemberonoan. Ta’wīl tidak dilakukan kecuali
oleh orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Meskipun ada pengakuan atas
keabsahan ta’wīl, ia tetap sulit diterima dan sering kali dianggap menyimpang atau,
sekurang-kurangnya, sebagai tafsir bi al-ra’y yang sangat gampang dituduh tercela.
Ta’wīl menjadi istilah yang tidak disukai dan tafsir mendapat legitimasi bagi
popularitasnya. Ta’wīl ditakuti karena ada kebimbangan bahwa penalaran dengan
menggunakan ta’wīl akan membawa kepada fitnah. Hal ini dirujuk kepada al-Qur’an
surat Āli ‘Imrān: 7, sebagaimana akan didiskusikan di bawah ini.
Nas}r Hāmid Abū Zayd mengkritik dengan keras kemapanan dalam tafsir. Ia
menyatakan bahwa pembungkaman terhadap ta’wīl tidak terlepas dari upaya
pelestarian tafsir formal yang dianggap bersih dari noda-noda bid‘ah dan kesalahan.
Tafsir formal ini tidak lain dari tafsir berupa nukilan-nukilan pendapat ulama
terdahulu, dari sahabat hingga tābi‘īn dan generasi sesudahnya yang tetap setia pada
otoritas pendahulunya. Para pendukung ta’wīl dianggap sebagai pembuat
penyimpangan dalam agama. Mereka ini umumnya adalah Mu‘tazilah dan penganut
tasawuf. Tafsir yang diinginkan bukanlah tafsir dalam bentuk ta’wīl tetapi tafsir yang
bersandar pada otoritas yang dianggap telah mapan. Ta’wīl hanya bisa dilakukan
dalam kaitannya dengan bahasa, dan itu pun sejauh tidak bertentangan dengan
pandangan otoritas.82 Terlepas dari berbagai kontroversi, kedua istilah tersebut telah
82Nas}r H{āmid Abū Zayd, Mafhūm al-Nas}s}: Dirāsah fī ‘Ulūm al-Qur’ān, (al-Dār al-Bayd}ā’: al-Markaz al-Tsaqāfī al-‘Arabī, cet. V, 2000), 220-222.
95
populer dipahami sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur’an atau
pengembangan terhadap makna-makna yang terkandung di dalamnya, walaupun
harus diakui bahwa dalam kenyataannya istilah tafsir memang lebih banyak
digunakan.
Sebelum pengkajian lebih jauh, pertanyaan paling awal yang mungkin dapat
diajukan mengenai hal ini adalah mengapa harus ada tafsir atau ta’wīl; mengapa al-
Qur’an harus ditafsirkan, sementara al-Qur’an sendiri tidak secara eksplisit
menyuruh menafsirkan ayat-ayatnya; dan bukankah al-Qur’an diturunkan dalam
“bahasa Arab yang jelas?”83 Dalam al-Qur’an sendiri hanya sekali disebutkan kata
tafsīr, yaitu dalam surat al-Furqān ayat 33, tetapi kata inilah yang paling populer
digunakan dalam literatur Arab, bukan hanya Islam, sebagai komentar terhadap
kitab-kitab suci, termasuk Taurat dan Injil. Orang-orang Yahudi dan Nasrani Arab
juga menggunakan kata tafsir untuk komentar kitab suci mereka. Andrew Rippin
mengutip Sa‘adyah Gaon (w. 942) seorang teolog Yahudi yang menulis terjemahan
Pentateuch dalam bahasa Arab dengan judul Tafsīr Basīt} Nas}s} al-Tūrah.
Demikian juga But}rus al-Sadamanti pada 1260 telah menulis al-Muqaddimah fī al-
Tafsīr sebagai bagian dari komentarnya terhadap kitab Perjanjian Baru.84
Dalam Islam, tafsir al-Qur’an sangat dibutuhkan karena al-Qur’an
menyisakan banyak ruang untuk berbagai pertanyaan dan penelitian. Al-Qur’an
banyak membuat statemen yang umum, sehingga membutuhkan kepada penjelasan
yang lebih mendetil. Terlebih lagi, sebagaimana telah dikemukakan di atas, ketika
83Q.S. al-Nah}l: 103 dan al-Syu‘arā’: 195.
84Andrew Rippin, “Tafsir”, dalam Mircea Eliade (ed.), The Encyclopaedia of Religion, (New York: Macmillan, 1987), Vol. XIV, 238.
96
Islam berkembang luas sampai ke luar jazirah Arab, tuntutan terhadap adanya
penjelasan mengenai ayat-ayat al-Qur’an yang dianggap asing terutama dari segi
budaya dan style atau gaya bahasanya, semakin dirasakan. Kebutuhan akan berbagai
penjelasan inilah yang menuntut lahirnya tafsir – upaya menjelaskan ayat-ayat al-
Qur’an yang tampak memerlukan penjelasan.
Al-Qur’an memang mengklaim dirinya sebagai kitab yang diturunkan dengan
bahasa Arab yang jelas, tetapi kalimat ini juga memerlukan penjelasan. Karena
“jelas” itu memiliki pengertian yang relatif – jelas dalam satu hal, mungkin tidak
jelas dalam hal lain. Pesan-pesan moral al-Qur’an, misalnya, tentang keadilan dan
kemanusiaan yang bersifat universal, adalah jelas. Namun mengenai berbagai teknis
penerapan hal tersebut tetap masih memerlukan penjelasan. Al-Qur’an menyuruh
Nabi Muhammad agar memerintahkan keluarganya mengerjakan salat (s}alāh). Ini
adalah perintah yang jelas, tetapi soal bagaimana salat itu dikerjakan, masih perlu
dipertanyakan. Pernyataan tersebut (bahwa al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab
yang jelas) juga dapat dipahami dalam pengerian lain: al-Qur’an diturunkan dalam
bahasan Arab, sehingga orang-orang Arab dapat mengerti semua isinya, karena
semua ayatnya diungkapkan dalam bahasa mereka. Al-Suyūt}ī mengutip banyak
riwayat mengenai hal ini. Sebagai contoh, Ibn ‘Abbās pernah ditanya oleh Nāfi‘ ibn
al-Azraq tentang beberapa pertanyaan mengenai pengertian kata-kata dalam al-
Qur’an, di antara lain kata ‘izīn dalam surat Q.S. al-Ma‘ārij: 37.85 Beliau menjawab,
al-‘izūn adalah al-h}ilaq, al-riqāq. “Apakah orang-orang Arab mengetahuinya,”
tanya Nāfi‘. Beliau menjawab, “Ya, apakah engkau tidak mendengar ‘Abīd ibn al-
Abras} [seorang penyair pra-Islam] berkata: fa jā’ū yuhra‘ūn ilayh h}attā yakūn
85 عزين الشمال وعن اليمين عن
97
h}awla minbarihī ‘izīnā.86 Dalam perspektif ini, pengertian “bahasa Arab yang jelas”
adalah bahasa yang dikenal dengan baik oleh orang-orang Arab. Dengan demikian,
“jelas” di sini bukan berarti tidak ada lagi ruang bagi elaborasi makna yang lebih
dalam. Tafsir dan ta’wīl adalah upaya mengisi ruang-ruang tersebut yang diyakini
tetap ada dan bahkan tiada habisnya.
Tafsir dan ta’wīl adalah human endeavor, upaya manusia menjelajah makna
dan nilai. Manusia berhadapan dengan banyak paradoks, kompleksitas dan
kepentingan sosial budaya. Manusia juga tidak sendirian dalam membangun semua
itu dan dalam menjabarkan berbagai kebutuhan umat manusia yang sangat beragam,
baik material atau spiritual. Orang atau sekelompok orang yang berbeda akan
melahirkan interpretasi yang berbeda. Dari sinilah dapat dipahami munculnya
keragaman dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. Seperti telah didiskusikan,
berbagai mazhab telah mengarang bervolume kitab tafsir untuk menjadi sumber
kajian agama dalam mazhabnya. Sebuah tafsir yang membela mazhabnya sering kali
tidak terlepas dari upaya mengkritik atau menyalahkan mazhab lain, karena
konsekuensi dari klaim kebenaran bagi sebuah interpretasi telah dipahami sebagai
klaim kekeliruan bagi interpretasi yang berbeda. Jika sesuatu adalah benar maka
yang bertentangan dengannya adalah salah. Cara pandang seperti inilah yang telah
mengubah konsep kerja tafsir dan ta’wīl – yang pada dasarnya elegan dan dinamis –
menjadi kaku dan penuh pertentangan. Tafsir dan ta’wīl telah menjadi alat ideologi
para penafsir dan penta’wīl itu sendiri. Inilah yang dikhawatirkan al-Qur’an:
Dialah yang telah menurunkan kitab (al-Qur’an) kepadamu, di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muh}kamāt; itulah pokok-pokok isi al-Qur’an dan yang
86Al-Suyūt}ī, al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān. Kairo: Mus}t}afā al-Bābī al-H{alabī, 1370 H., Vol. 1, 348.
98
lain (ayat-ayat) mutasyābihāt. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecondongan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyābihāt untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta’wīlnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah; dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyābihāt, semuanya itu dari sisi Tuhan kami;” dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.87
Pemahaman terhadap ayat inilah yang menjadi sumber kontroversi sekitar
tafsir dan ta’wīl. Dalam ayat ini tidak disebutkan tafsir, tetapi ta’wil. Jika ta’wīl,
berdasarkan ayat ini, dipandang sebagai konsep yang sakral dan hanya Tuhan yang
mengetahuinya – sementara orang-orang yang mendalam ilmunya hanya
mengimaninya saja – maka tidak demikian halnya dengan tafsir; ia tidak disebutkan
dalam ayat tersebut. Jika ta’wīl dianggap dilarang berdasarkan ayat ini, maka tafsir
tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian ayat ini menjadi legitimasi bagi
kelompok yang membela tafsir dan mendiskreditkan ta’wil. Seperti telah disebutkan,
bahwa tafsir dalam hal ini tidak lebih dari nukilan-nukilan atas dasar otoritas, bukan
pengkajian atau pendalaman makna secara inovatif dan inspiratif dengan melibatkan
berbagai pengetahuan dan sisi pengalaman hidup manusia.
Pokok persoalan yang diperdebatkan dalam ayat ini adalah huruf wāw pada
wa al-rāsikhūn fī al-‘ilm: apakah ia isti’nāf atau ‘at}f. Jika wāw itu isti’nāf maka
pengertiannya: “ ... tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah; sementara
orang-orang yang mendalam ilmunya berkata ....” Tetapi jika wāw itu dianggap ‘at}f
maka maknanya menjadi: “... tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah
dan orang-orang yang mendalam ilmunya; mereka berkata ....” Perbedaan ini
membawa konsekuensi pada pandangan tentang ayat-ayat mutasyābihāt, apakah
87Q.S. Āli ‘Imrān: 7.
99
hanya Allah yang mengetahuinya atau juga manusia. Perdebatan dalam masalah ini
telah dibicarakan secara panjang lebar dalam kitab-kitab tafsir dan ‘Ulūm al-
Qur’ān.88 Mereka yang membatasi pemahaman ayat-ayat mutasyābihāt pada ilmu
Allah semata berkata bahwa ayat di atas diturunkan untuk menguji kecenderungan
hati manusia, apakah ia tunduk kepada Allah atau mengikuti hawa nafsu dan
membuat fitnah. Orang-orang yang membela kemungkinan pemahaman ayat-ayat
mutasyābihāt oleh manusia yang berilmu mengatakan bahwa sangat janggal jika
Tuhan menurunkan ayat-ayat-Nya (khususnya yang mutasyābihāt) tidak untuk
dimengerti dan dipahami oleh manusia. Al-Suyūt}ī mengutip sebuah riwayat dari
Ibn ‘Abbās mengenai ayat tersebut, di mana ia berkata: “Aku adalah di antara orang
yang mengetahui ta’wīlnya,” tetapi kemudian al-Suyūt}ī mengutip riwayat lain
tentang bacaan ayat tersebut oleh Ibn ‘Abbās juga: “beliau membacanya dengan
berhenti (waqf) pada illa Allāh,” yang mengindikasikan wāw pada wa al-rāsikhūn fī
al-‘ilm adalah isti’nāf. (Jadi orang-orang yang mendalam ilmunya hanya beriman
kepada ayat-ayat mutasyābihāt; mereka tidak mengetahui ta’wīlnya – hanya Allah
yang tahu). Al-Suyūt}ī menjelaskan bahwa riwayat ini telah disampaikan dengan
sanad yang sahih dari Turjumān al-Qur’ān, yakni Ibn ‘Abbās. Ini didukung pula
oleh kenyataan bahwa ayat tersebut mencela orang-orang yang mengikuti ayat-ayat
mutasyābihāt dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang dalam hatinya ada
zaygh (kecenderungan untuk menyimpang).89
88Lihat misalnya al-Zarkasyī, al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1391 H.), Vol. 2, 72-73; al-Tabarī, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān, (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H.), Vol. 3, 182-183.
89Al-Suyūt}ī, al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, (Kairo: Mus}t}afā al-Bābī al-H{alabī, 1370 H.), Vol. 2, 7-8.
100
Perkara yang samar memang mudah untuk diselewengkan. Karena itu
kekhawatiran ulama terhadap munculnya penyelewengan-penyelewengan dalam
pemahaman al-Qur’an jika pintu ta’wil dibuka sepintas tampak cukup beralasan.
Ayat di atas itu sendiri sebenarnya telah dita’wīlkan untuk menutup pintu ta’wīl.
Persoalan ini tidak berbeda dari “kisah” penutupan pintu ijtihad dalam bidang fikih.
Para “pemimpin agama,” karena keyakinannya yang “mendalam,” sangat khawatir
jika paham-paham yang berseberangan dengan yang mereka miliki muncul dan
mendapat legitimasi yang luas. Mereka sangat takut terjadi “penyimpangan-
penyimpangan” dalam agama. Mengapa mereka takut? Karena mereka yakin bahwa
kebenaran tidak ada selain yang mereka klaim sebagai kebenaran, dan karena itu
yang lainnya dipandang tidak layak untuk dibiarkan tanpa diberangus. Ini mungkin
merupakan tuduhan yang tidak bijaksana, tetapi hal ini perlu diperjelas:
sesungguhnya agama juga perlu direspon dengan cara yang lebih bijaksana. Agama
bukan milik perseorangan atau kelompok, tetapi milik Tuhan, yakni milik umat
manusia. Agama juga bukan milik sejarah dan masa lalu yang telah beku, tetapi milik
segala zaman, dan karena itu perlu dibiarkan tetap hidup dalam seluruh rangkaian
dinamika kehidupan orang-orang yang peduli kepadanya.
Kesamaran yang terkandung dalam ayat tentang ta’wīl di atas mengandung
hikmah. Para mufassir telah melakukan pembacaan terhadapnya dengan cara yang
berbeda-beda. Namun, al-Qur’an sebenarnya sangat jelas dalam mengajarkan cara
bersikap orang-orang mukmin: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyābihāt,
semuanya itu dari sisi Tuhan kami.” Allah pasti tahu ta’wīl ayat-ayat mutasyābihāt.
Orang-orang yang mendalam ilmunya? Mungkin mereka tahu, mungkin juga tidak.
Kalaupun mereka tahu, kebenaran pengetahuan mereka tidak akan diklaim sebagai
mutlak, karena mereka yakin hanya Allah yang Maha Benar.
BAB IIIYAHUDI DALAM TRADISI ISLAM
ISLAM memiliki banyak kisah tentang Yahudi, karena Islam berkembang dalam
milieu masyarakat yang tidak terlepas dari, dan secara intens terus berinteraksi
dengan, umat Yahudi. Yahudi adalah saudara atau sepupu bagi Islam, karena itu,
demikian sering dikatakan, konflik antara keduanya adalah konflik keluarga.
Hubungan Yahudi-Muslim telah terbentuk sejak awal, sedemikian rupa, dengan
segala bentuk persahabatan dan pertikaian, sampai masa-masa kejayaan dan
keruntuhan kekuasaan Muslim, dan sampai hari ini. Berbagai peristiwa telah dicatat
dan berbagai pandangan serta persepsi telah terbentuk. Semuanya sangat heterogen,
kompleks dan kadang-kadang terselimuti oleh kabut ideologi, politik dan berbagai
kepentingan lainnya. Bab ini tidak untuk mengklarifikasi hal tersebut. Bab ini
berupaya menampilkan sebuah peta perjalanan pemikiran yang telah membentuk
sikap kaum Muslim terhadap apa dan siapa yang sekarang disebut dengan umat
Yahudi.
A. Yahudi Sebuah Nama yang Kompleks
Siapa Yahudi? Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat ditentukan oleh
pandangan dunia yang dianut seseorang. Seorang Muslim tradisional akan
memberikan jawaban yang berbeda dari Muslim liberal. Seorang penganut agama
Yahudi akan menjawab dengan cara yang berbeda dari penganut agama Islam. Perlu
ditegaskan juga bahwa, sesuai dengan istilah yang digunakan dalam bahasa
Indonesia, Yahudi yang dimaksudkan di sini adalah umat Yahudi dan tradisi
keagamaan yang mereka anut.1
Al-Qur’an menyebut orang Yahudi dengan kata-kata bervariasi. Kadang-
kadang al-Qur’an langsung menggunakan concrete noun (kata benda konkret), yaitu:
al-yahūd (orang-orang Yahudi; kata tunggalnya adalah al-yahūdī).2 Tetapi kadang-
kadang yang digunakan adalah penggabungan relative pronoun “alladhīna” dengan
verb (kata kerja) “hādū” (jadi, artinya: orang-orang yang menganut agama Yahudi).3
Di samping itu terdapat juga kata yahūdiyyan (a Jew, seorang Yahudi; bentuk
nakīrah atau common noun dari al-yahūdī),4 dan kata hūdan (jamak dari hā’id
1Dalam bahasa Indonesia, sudah sering disebut istilah agama Yahudi dan bangsa Yahudi. Lihat W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984,), 1153.
2Misalnya dalam surat al-Baqarah: 113, … اليهود . وقالت
3Misalnya dalam surat al-Baqarah: 62, … هادوا والذين ءامنوا الذين Sebagian .إنliteratur Muslim, terutama sekali kitab-kitab tafsir, menyebutkan bahwa Yahudi berasal dari kata hāda-yahūdu, artinya tobat atau kembali. Nabi Musa pernah berkata: إليك هدنا .Q.S) إناal-A‘rāf: 156). Lihat tafsir Ibn Katsīr; Lihat juga Mohd. Fauzi bin H. Awang, Ugama-ugama Dunia, (Malaysia: Pustaka Aman Press, 1971), 129. Penjelasan seperti ini sebenarnya agak naif karena istilah Yahudi (Judaism) itu sendiri tidak muncul dari bahasa Arab dan juga belum dikenal pada masa Nabi Musa, tetapi muncul jauh setelah itu, ketika terbentuk suku Judah atau ketika berdiri kerajaan Judah. Jadi Yahudi (dalam bahasa Ibrani, Yĕhūdhī) pada awalnya adalah a member of Judah. Lihat Encyclopaedia Britannica, s.v. “Jew,” Deluxe Edition 2004 CD-ROM. Ibn Katsīr sendiri, setelah mengutip pendapat tersebut, mengatakan bahwa Jābir Ibn Yazīd al-Ja‘fī, salah seorang sanad dalam riwayat yang dikutipnya, adalah lemah (d}a‘īf).
4Bentuk ini hanya disebutkan satu kali dalam al-Qur’an. Lihat Q.S. Āli ‘Imrān: 67, نصرانيا .… وال يهوديا إبراهيم كان ما
penganut agama Yahudi).5 Dalam bahasa Inggris, orang-orang Yahudi disebut Jews
dan agama mereka Judaism.
Istilah lain yang dipakai al-Qur’an untuk umat Yahudi adalah Ahl al-Kitāb.
Frase ini telah digunakan oleh orang-orang Arab sebelum Islam untuk merujuk
kepada mereka yang memiliki tradisi keagamaan yang bersumber dari al-Kitāb,
khususnya Yahudi dan Nasrani. Dalam kenyataannya, istilah Ahl al-Kitāb yang
digunakan al-Qur’an lebih banyak merujuk kepada kaum Yahudi. Tentu saja ini
karena wahyu lebih banyak berinteraksi dengan kaum Yahudi dibandingkan Nasrani.
Secara generik, Yahudi disebut Banī Isrā’īl (Bani Israil) atau sekarang dikenal
dengan bangsa Israel. Lebih empat puluh kali istilah ini disebutkan dalam al-Qur’an
dalam konteks yang berbeda-beda. Isrā’īl adalah gelar yang dianugerahkan Tuhan
kepada Nabi Yakub. Maka, karena bangsa Yahudi adalah anak keturunannya, mereka
disebut Bani Israil.
“Yahudi” merupakan sebuah istilah yang kompleks. Yahudi (Judaism,
Yudaisme) tidak dapat dijelaskan semata-mata dalam konteks sebuah keyakinan
keagamaan, tetapi juga terkait dengan sebuah bangsa yang bernama Israel. Lewis M.
Hopfe (w. 1992) mengakui betapa sulit mendefinisikan Yudaisme atau agama
Yahudi. Dapat saja dikatakan bahwa seorang Muslim berarti penganut agama Islam,
seorang Kristen berarti penganut agama Kristen, dan seorang Yahudi mungkin saja
berarti penganut agama Yahudi. Dalam banyak hal, cara pendefinisian seperti ini
memang efektif, tetapi dalam kasus Yahudi persoalannya lebih rumit. Dalam
5Misalnya Q.S. al-Baqarah: 135, … هودا كونوا .وقالوا
kehidupan kontemporer bangsa Israel sendiri, “Who is a Jew?” masih merupakan
persoalan yang belum selesai.6
Yahudi tidak dapat didefinisikan hanya dalam konteks keyakinan keagamaan
karena tidak sedikit orang yang disebut Yahudi namun menganggap dirinya ateis.
Mendefinisikan Yahudi dalam konteks ras juga menimbulkan masalah karena
ternyata Yahudi tampil dengan karakteristik ras yang berbeda-beda: ada Yahudi
Afrika, Yahudi Eropa dan bahkan Yahudi Oriental. Mereka juga menggunakan
bahasa dan bahkan budaya tempat atau negeri di mana mereka berada.7 Namun satu
hal barangkali agak jelas, bahwa setiap orang yang mengidentifikasikan dirinya
dengan tradisi keagamaan Yahudi (Judaism) dapat disebut seorang Yahudi (a Jew).
Walaupun demikian, ini juga menyisakan persoalan: Yudaisme sangat tipikal bagi
orang-orang Yahudi atau Bani Israil. Karena itu, bagaimana mungkin agama Yahudi
(Judaism) dapat dipisahkan dari bangsa Yahudi (Jews); bagaimana mungkin
seseorang dari luar keturunan Israel menjadi Yahudi?
Jacob Neusner, seorang Judaic scholar kontemporer, mendefinisikan Judaism
sebagai a religion that privileges Scripture’s account of Israel as holy people whose
life encompasses the experience of exile and return.8 Pandangan ini menekankan
kesadaran eksklusif-rasial dan historis dalam melihat Yahudi sebagai sebuah
keyakinan keagamaan yang terikat secara khusus dengan suatu suku bangsa, Israel,
suatu umat yang telah menjalani hidup dengan berbagai pengalaman pahit dan
6Lewis M. Hopfe, Religion of the World, ed. Mark R. Woodward, (New Jersey, Prentice Hall, 1998), 260.
7Ibid.
8Jacob Neusner, Signposts on the Way of Torah, (USA: Wadsworth, 1998), 1.
kejayaan, dan telah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Tradisi keagamaan tersebut
terbentuk dalam sebuah proses sejarah yang panjang, melalui lisan para nabi dan
rabbi mereka, dengan konsep-konsep Ketuhanan dan moral yang terus menerus
diwariskan dan dimatangkan.
Pada awalnya, seperti dikatakan George Robinson, Yahudi hanyalah
sekelompok orang, sebuah suku, a band of nomads, probably shepherds. Namun
kemudian mereka menjadi something more. Orang-orang Yahudi menjadi
“pengusung” sebuah konsep baru: monoteisme etikal. Konsep inilah yang menjadi
cikal bakal terbentuknya sebuah agama baru, Judaism (Yudaisme, agama Yahudi).9
Agama Yahudi umumnya “lebih dikenal dengan istilah Judaism.” Ada juga
yang menyebutnya dengan “The Wisdom of Israel atau Hebrew Religion.”10
Menurut perspektif Yahudi sendiri, orang-orang Yahudi (Hebrew atau Israel) pada
dasarnya adalah pemilik tunggal agama Yahudi, dan agama tersebut telah dipilih
Tuhan untuk menjadi agama mereka. Jadi tidak ada Judaism tanpa Jews (Bangsa
Yahudi atau Israel); dan bangsa Israel atau Jews yang menolak Judaism atau
bertindak melanggar perintah-perintah Taurat adalah sinning Jews (Yahudi-yahudi
berdosa), walaupun dalam kenyataannya semua Yahudi, to a greater or lesser extent,
adalah sinning Jews. Namun, mereka tetap Yahudi. Jadi secara ontologis, seorang
Yahudi adalah Yahudi karena ia keturunan Israel. Dalam konsep ini, Yudaisme
bukan lagi persoalan keyakinan, tetapi ketetapan, aturan dan perintah yang
9George Robinson, Essential Judaism: A Complete Guid to Beliefs, Customs and Rituals, (New York: Pocket Books, 2000), 7.
10Burhanuddin Daya, Agama Yahudi, (Yogyakarta: Bagus Arafah, 1982), 1.
ditetapkan secara khusus kepada bangsa Yahudi.11 Karena itu konversi ke agama
Yahudi adalah sesuatu yang kontroversial dan memerlukan penjelasan.
Ini mengundang tanda tanya. Mengapa sebuah agama besar memiliki
pandangan demikian “sempit” dan eksklusif? Jika Yahudi membawa sebuah
kebenaran, mengapa orang lain dihalangi untuk meraihnya? Bukankah tindakan
seperti itu menyiratkan arogansi dan merupakan monopoli kebenaran? Bukankah
kebenaran itu sendiri bersifat universal? Bahkan, yang lebih mendasar lagi, mengapa
Tuhan bersikap diskriminatif? Pertanyaan-pertanyaan ini kelihatan sederhana.
Namun di balik semua itu sesungguhnya ada persoalan yang lebih kompleks.
Kebenaran tidak selalu terkait dengan fakta, tetapi juga dengan nilai. Kebenaran yang
ada adalah “kebenaran” yang dipersepsikan – kebenaran yang ditafsirkan manusia,
sesuai dengan lingkup sejarah dan sosial budayanya. Kebenaran dalam agama juga
membawa implikasi pada keselamatan. Ketika Yahudi menganggap bahwa
keselamatan juga dapat diraih melalui “ketulusan” di luar Yahudi, maka tidak ada
alasan yang mendasar untuk mendakwahkan pemeluk agama monoteis lain agar
memeluk agama Yahudi; yang harus diajak adalah kaum ateis yang tidak mempunyai
agama atau penyembah berhala.12
Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Yahudi memang tampil sebagai
agama yang mungkin tidak dikenal terlibat dalam aktivitas misionaris. Akan tetapi
banyak bukti memperlihatkan bahwa orang-orang Yahudi ternyata menerima dengan
11Michael Wyschogrod, “Islām and Christianity in the Perspective of Judaism”, dalam I.R. Faruqi (ed.), Trialogue of the Abrahamic Faiths, (New Delhi: Genuine Publication, 1989), 14.
12Louis Jacobs, The Jewish Religion: A Companion, (Oxford: Oxford University Press, 1995), 97-98.
baik pemeluk baru yang masuk dengan suka rela ke dalam agama Yahudi dan bahkan
mengajak pemeluk agama lain untuk konversi atau melakukan proselitasi.13
Tema sentral agama Yahudi adalah hubungan manusia (khususnya bangsa
Israel) dengan Tuhan melalui perjanjian yang ditetapkan-Nya. Tuhan adalah Yang
Maha Kuasa, the Omnipotent, Pencipta segalanya, yang mendengar hamba-Nya dan
menyelamatkan. Tuhan mempunyai banyak nama dalam tradisi Yahudi.
Sebagaimana dalam Islam, nama-nama tersebut merupakan atribut Ketuhanan,
sebagai simbol untuk menjelaskan bagaimana Tuhan memanifestasikan diri-Nya.
Dalam Taurat (Hebrew Bible) dan Talmud, banyak nama Tuhan disebutkan: El (The
Strong One, Yang Maha Kuat), El Shaddai (God Almighty, Tuhan Yang Maha
Kuasa), El Olom (God Everlasting, Tuhan Yang Maha Kekal), El Khai (The Living
God, Tuhan Yang Maha Hidup), El Elyon (God Most High, Tuhan Yang Maha
Tinggi), Elohim (God, Tuhan), Adon (Lord, Penguasa), Adonai (Lord, Penguasa),
Adonay Tzivaot (Lord of Hosts, Penguasa Segala Pasukan), Abir (The Strong, Yang
Maha Kuat), Kedosh Yisroel (Holy One of Israel, Tuhan Yang Maha Suci orang
Israel), Melekh (The Ruler, Yang Maha Mengatur), Tzur Yisroel (Rock of Israel, Batu
[Kekuatan] orang Israel).14
Tuhan inilah yang telah berperan dalam penyelamatan Bani Israil dan telah
menjadikan mereka sebagai umat pilihan. Pada mulanya Tuhan telah memilih
Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai umat-Nya.
(1) Now the LORD said unto Abram: ‘Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father’s house, unto the land that I will show thee.
13Ibid., 98.
14Ibid., 9.
(2) And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great; and be thou a blessing. (3) And I will bless them that bless thee, and him that curseth thee will I curse; and in thee shall all the families of the earth be blessed’.15
Pemilihan Ibrahim, Ishak dan Yakub serta anak keturunannya oleh Tuhan
mempunyai implikasi yang cukup signifikan bagi keyakinan keagamaan bangsa
Israel. Tuhan telah memilih sebuah umat dan, karena itu, dalam perspektif orang-
orang Yahudi, sebuah sistem keagamaan juga telah ditetapkan Tuhan khusus untuk
umat tersebut. Pemilihan tersebut membawa konsekuensi bahwa orang-orang Israel
telah mendapatkan a special set of commands, di mana mereka, dan hanya mereka,
harus tunduk kepadanya.16 Atas dasar inilah, konversi dan proselitasi dalam tradisi
Yahudi menjadi kurang relevan, walaupun bukan tidak mungkin; dalam bahasa
Michael Wyschogrod, If conversion to Judaism is possible – as it is – it becomes a
possibility by means of a kind of miracle.17 Berpindah ke agama lain, berarti
melakukan kedurhakaan dan pengkhianatan. Berpindah ke agama Yahudi berarti
melakukan sebuah transformasi bukan hanya spiritual tetapi juga mungkin semacam
quasi-biologis-fisikal. Menjadi Yahudi berarti menjadi keturunan Ibrahim, Ishak dan
Yakub. Ia terlahirkan kembali sebagai orang baru dan dianggap terputus hubungan
dengan keluarganya, hatta dengan perempuan yang telah melahirkannya. Jadi –
sekali lagi – dengan demikian, Yahudi tetap Yahudi sebagai anak keturunan Yahudi.
Jika orang-orang Yahudi melihat dirinya eksklusif dan istimewa – tidak jauh
berbeda dari cara pandang setiap umat terhadap dirinya – maka bagi orang lain,
15Genesis 12: 1-3
16Michael Wyschogrod, “Islām and Christianity,” 14.
17Ibid.
khususnya kebanyakan umat Islam, mereka amat menjijikkan. Mereka terkutuk dan
hina; bahkan segala kekejian dapat ditumpahkan atas pundak mereka.
Yahudi telah menjadi sebuah simbol kebencian bagi kebanyakan Muslim.
Sudah sangat sering orang-orang Islam mengungkapkan kata “Yahudi” untuk
melemparkan suatu kutukan atau penghinaan terhadap seseorang atau suatu
kelompok. Yahudi berarti jahat, licik, menjijikkan, dan bahkan dianggap sebagai
sebuah istilah yang padanya melekat segala keburukan dan kejahatan.
Dari mana permusuhan itu datang dan bagaimana karakteristik permusuhan
Yahudi-Muslim tersebut? Apakah permusuhan Yahudi-Muslim bersifat religius,
politik ataukah memiliki akar dalam peradaban? Pertanyaan lain yang juga tidak
kurang penting untuk dipertimbangkan adalah, apakah kedua penganut agama
berbeda ini menganggap permusuhan seperti itu sebagai bagian tak terpisahkan dari
keyakinan mereka?
Mungkin hampir semua penganut agama sepakat bahwa tujuan yang
sesungguhnya dari agama adalah membahagiakan manusia lahir dan batin, material
dan spiritual, tetapi mengapa juga agama telah berperan sebagai pembawa bencana
bagi kemanusiaan dalam berbagai bentuk kebencian, perang dan permusuhan?
Jika secara lebih spesifik persoalan ini diarahkan pada hubungan Yahudi dan
Muslim, akan terlihat bahwa konflik-konflik tersebut lebih merupakan akibat dari
pertikaian politik semata. Ketika Nabi Muhammad pertama datang ke Medinah
kesepakatan politik yang pertama beliau lakukan adalah agar setiap kelompok etnik
dan agama di negara yang hendak beliau bina tersebut secara bersama-sama
memelihara dan melindungi masyarakat mereka dari berbagai serangan dari luar.
Hubungan umat Islam dengan pemeluk agama lain, khususnya umat Yahudi berjalan
dengan harmonis. Apa yang menyebabkan timbulnya pertikaian di antara mereka
adalah akibat dari persekongkolan pihak-pihak tertentu dari kalangan Yahudi
Medinah dengan kaum musyrikin Mekkah.
Pada zaman Islam berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah dan Abbasiyah,
kelompok Yahudi dan juga Nasrani menjadi warga negara kelas dua. Mereka tetap
diperlakukan dengan baik, namun dari segi politik dan ekonomi mereka tidak
mendapatkan status yang sejajar dengan umat Islam. Ini bisa dipahami dengan
melihat latar belakang hubungan mereka pada masa Nabi yang penuh dengan
ketegangan akibat dari pengaruh-pengaruh musyrikin Mekkah. Trauma psikologis
tersebut memang tidak dapat terhapus tuntas, apalagi kelompok Yahudi sendiri tidak
melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk memperbaiki citra mereka di mata
kaum Muslim. Namun pada masa kejayaan Islam di bawah kekhalifahan Bani
Abbasiyah, banyak orang-orang Yahudi memainkan peran mereka yang cukup
signifikan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, terutama sekali dalam
kegiatan penerjemahan kitab-kitab filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Musa ibn
al-Maymūn, misalnya, yang terkenal di Barat dengan nama Moses Maimonides,
adalah seorang Rabbi Yahudi yang sangat alim dan terkenal. Pada masa Salahuddin
al-Ayyubi, ia pernah menjadi dokter pribadi sang Khalifah. Ketika Richard the Lion-
Hearted mengajak Maimonides untuk datang ke England Maimonides menolak. Hal
ini dapat dipahami, seperti kata Fazlur Rahman, karena England abad ke 12 sedikit
sekali memiliki kehidupan intelektual yang dapat menarik orang seperti
Maimonides.18
Jika orang-orang Yahudi hari ini di dunia Arab hidup dalam kondisi paling
menjijikkan, itu bukan karena orang-orang Arab menolak mereka. Kondisi ini
diciptakan untuk orang-orang Yahudi dan juga untuk orang-orang Arab oleh para
penakluk berikutnya (setelah kejayaan Islam). … Konflik Arab-Israel tidak berakar
pada permusuhan rasial dan keagamaan, tetapi lebih disebabkan oleh berbagai
kebijakan politik kontemporer. … Sejarah menunjukkan bahwa Yahudi dan Arab
dapat hidup berdampingan tanpa pertikaian dan bahkan dalam suasana saling
menguntungkan.19
B. Yahudi di Tanah Arab: Tarik Menarik Peradaban
Orang-orang Yahudi (dan juga Nasrani) telah hidup di tengah-tengah bangsa
Arab demikian lama sehingga peradaban dan kehidupan sosial mereka sudah “ter-
Arabkan.” Namun agama mereka tidak terlalu banyak membawa pengaruh kepada
orang-orang Arab. Agama mereka dianggap asing, terutama sekali agama orang
Yahudi, karena sikap mereka yang eksklusif atau tertutup. Namun di sisi lain, orang-
orang Arab tetap merasa respek kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani sebab
mereka memiliki kitab dan ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh kaum Arab.
Kehidupan sosial di antara mereka dan orang-orang Arab berjalan dengan baik. 18Fazlur Rahman, “Islam’s Attitude Toward Judaism”, The Muslim World, No. 1,
Vol. LXXII, January 1982, 7.
19Max I. Dimont, Jews, God and History, (New York: Penguin Books, Edisi Revisi 1994), 210.
Beberapa orang di antara bangsa Arab pun ada yang memeluk agama mereka.
Karena itu mungkin saja sebagian dari dogma dan ajaran agama mereka telah dikenal
atau telah menyebar di kalangan orang Arab sejak sebelum Islam.20
Jauh sebelum Islam datang, orang-orang Yahudi dan Nasrani telah
menempati beberapa wilayah di jazirah Arab. Mereka diperkirakan sudah berada di
sana lebih seratus tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Tampaknya, setelah
Yerusalem dihancurkan oleh Titus, Kaisar Romawi, pada 70 M. dan pemberontakan
sengit namun gagal yang dipimpin oleh Bar Kochba pada 135 M., banyak orang
Yahudi yang bermigrasi ke wilayah Arab.21 Di samping itu, ada juga kemungkinan
bahwa kedatangan mereka ke Arab didorong oleh sebuah ramalan yang berkembang
di kalangan para rabbi Yahudi dan rahib-rahib Nasrani tentang kedatangan seorang
“Juru Selamat” atau nabi di daerah gurun yang kaya pohon kurma itu. Mereka ingin
berada di negeri tersebut ketika nabi yang diramal itu diutus Tuhan. Ibn Ishāq22
meriwayatkan bahwa pada zaman jahiliah pertengkaran sering terjadi antara orang-
orang musyrik dan kaum Yahudi. Dalam pertengkaran tersebut orang-orang Yahudi
sering berkata: “zaman diutusnya seorang nabi sekarang telah tiba. [Ketika dia
datang], kami akan memerangi kalian dengan bantuannya [dan menghancurkan
kalian] seperti kaum ‘Ād dan Iram dimusnahkan.” Ini menunjukkan bahwa
keberadaan mereka di sekitar tanah Hijaz bukanlah sebuah kebetulan, tetapi didasari
oleh sebuah harapan messianic (kedatangan Juru Selamat) seperti diramalkan para
20Khalil Abdul Karim, Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya dan Kekuasaan, (Yogyakarta: LKíS, 2002), 112-133.
21Helmut Gätje, The Qur’ān, 3.
22Guillaume, A., The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah, (London: Oxford University Press, Third Impression 1970), 93.
pemimpin mereka. Orang-orang Arab sendiri menyaksikan hal tersebut dan sedikit
banyaknya membawa pengaruh bagi sikap keberagamaan mereka. Sekurang-
kurangnya, setelah Islam datang, ada sebagian sahabat – mengenang saat-saat
mereka bertikai dengan orang-orang Yahudi – berkata: “kami menerimanya [Nabi
Muhammad] tetapi mereka [orang-orang Yahudi] menolaknya.”23 Keyakinan orang
Arab pada waktu itu akan Islam dan Nabi Muhammad ternyata juga memiliki
keterkaitan yang unik dengan orang-orang Yahudi dan agama yang mereka anut.
Umumnya sarjana Barat tidak yakin bahwa komunitas Yahudi di Medinah
secara orisinal berasal dari keturunan Yahudi. Mereka diperkirakan sebagai orang-
orang Arab yang memeluk agama Yahudi. Menurut Moshe Gil, suku-suku Yahudi
Medinah adalah proselytes24 yang berasal dari keturunan Badui. Mereka menjadi
Yahudi di tangan para misionaris Yahudi yang melarikan diri dari tentara Romawi
sekitar tahun 70 M. dan 135 M., seperti tersebut di atas, menuju Arabia. Sepertinya
para pengungsi inilah yang merupakan pembentuk utama populasi Yahudi di wilayah
utara Hijaz itu. Beberapa abad kemudian, jumlah mereka bertambah dengan adanya
suku-suku Arab yang bergabung ke dalam agama mereka. Para pemeluk baru
tersebut bukan hanya mengadopsi kehidupan agrikultural dan pandangan hidup umat
Yahudi, tetapi juga bahasa yang mereka gunakan, yaitu Aramai.25
23Ibid.
24Dalam bahasa Inggris, orang yang beralih agama ke agama Yahudi disebut a proselyte, sedangkan orang Yahudi yang memeluk agama lain disebut a convert. Dalam bahasa Hebrew juga digunakan istilah yang berbeda: ger untuk proselyte dan meshumad (yang akar katanya bermakna to destroy, menghancurkan) untuk convert ke agama lain. Lihat Louis Jacobs, The Jewish Religion: A Companion, (Oxford: Oxford University Press, 1995), 97.
25Moshe Gil, “The Origin of the Jews of Yathrib,” Jerussalem Studies in Arabic and Islam, No. 4, 1984, 218-219
Bagaimana pun, apakah mereka peoselytes atau bukan, orang-orang Yahudi
Medinah telah menjadi penduduk yang mapan. Mereka bahkan telah menghuni
wilayah itu sebelum al-Aws dan al-Khazraz, dua suku Arab dominan di Medinah.26
Berbeda dari suku-suku Arab, orang-orang Yahudi lebih terampil. Mereka adalah
saudagar-saudagar dan petani yang berbakat. Al-Wāqidī (w. 823 M.) mengutip
kesaksian orang-orang Arab Muslim masa awal: “Banū Qurayz}ah adalah orang-
orang dari keturunan kelas menengah dan kaya raya, sementara kami hanya suku
Arab, yang tidak memiliki pohon kurma dan kebun anggur, hanya penggembala
domba dan unta.”27 Tidak jarang orang-orang Arab Badui dan untanya disewa oleh
orang-orang Yahudi untuk membawa kurma mereka ke pasar terdekat. Kehidupan
mereka terkesan lebih prestisius dan sophisticated. Mereka melek huruf, bisa
membaca dan menulis serta memiliki kitab dan para rabbi.28
Ada tiga suku Yahudi terkenal – di samping beberapa suku yang lebih kecil –
di Medinah pada waktu itu, yaitu: Banū Nad}īr, Banū Qurayz}ah dan Banū
Qaynuqā‘. Ketika Nabi Muhammad berhijrah ke Medinah pada 622 M., orang-orang
Yahudi Medinah telah menjadi sekutu-sekutu bagi al-Aws dan al-Khazraj, dua suku
Arab yang telah mendominasi negeri itu. Kedua suku ini secara kolektif disebut Banū
Qaylah, dinisbatkan kepada Qaylah bint Kāhil, ibu mereka.29 Mereka sebenarnya
pendatang baru yang bermigrasi dari selatan. Tidak jelas bagaimana mereka
26F.E. Peters, Muhammad and the Origins of Islam, (New York: State University of New York Press, 1994), 192.
27Al-Wāqidī, Kitāb al-Maghāzī, Vol. 1, 480. Dikutip F.E. Peters, Muhammad, 193.
28A, Guillaume, The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah, (London: Oxford University Press, Third Impression 1970), 240-241.
29Ibn Manz}ūr, Lisān al-‘Arab, (Beirut: Dār S{ādir, t.t.), Vol. 11, 580.
kemudian menjadi “penguasa” di Medinah dan mengambil alih posisi hegemoni
orang-orang Yahudi. Al-Isfahānī (w. 967 M.), dalam Kitāb al-Aghānī, mengisahkan
bagaimana pada awalnya orang-orang Arab merasa lebih rendah dari orang-orang
Yahudi yang secara general menempati posisi sosial dan ekonomi kelas menengah.30
Tetapi lama-kelamaan orang-orang Yahudi menemukan diri mereka dalam posisi
yang tidak menyenangkan. Mereka bahkan ketakutan. Jika terjadi pertengkaran
dengan salah satu suku Arab, mereka akan mencari perlindungan dari suku Arab
lainnya, bukan pada kelompok Yahudi. Keluarga-keluarga Yahudi kemudian
mencari perlindungan pada kelompok Arab, al-Aws atau al-Khazraj.31 Ini tidak
mengherankan. Selama orang-orang Yahudi adalah kelompok yang mapan secara
ekonomi, mereka tentu saja tidak menginginkan kekacauan yang dapat menyebabkan
terganggunya stabilitas ekonomi mereka. Sebagai kelompok kelas menengah, mereka
lebih suka “tunduk” kepada kekuasaan dan cenderung tidak melawan atau, tegasnya,
oportunis. Sementara itu, suku-suku Arab yang telah terbiasa hidup dengan tantangan
alam yang keras dan suasana kasar, lebih suka bermusuhan dan menumpahkan darah.
Banū Qaylah saling berperang di antara sesamanya (antara al-Aws dan al-Khazraj)
dan membuat suasana tidak nyaman dan keadaan tidak stabil di Medinah. Ketika
mereka menarik orang-orang Yahudi untuk menjadi pendukungnya, kelompok
Yahudi pun kini ikut terpecah: Banū Qurayz}ah dan Banū Nad}īr mengikuti al-
Aws, Banū Qaynuqā‘ mengikuti al-Khazraj. Ketika kedua suku ini saling berperang,
maka orang-orang Yahudi juga ikut memerangi saudaranya yang bergabung di pihak
30Al-Isfahānī, Kitāb al-Aghānī, Vol. 19, 95-96. Dikutip F.E. Peters, Muhammad, 193
31Ibid., 194.
lawan, walaupun kemudian mereka berusaha menebusnya jika ada yang tertawan.
Mereka mengamalkan sebagian ajaran kitab suci (yakni menebus saudaranya) dan
meninggalkan sebahagiannya (yaitu memerangi sesamanya). Inilah sikap Yahudi
yang kemudian dikritik oleh al-Qur’an.
Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya; kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) dilarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab (Taurat) dan ingkar kepada sebagian yang lain? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.32
Orang-orang Yahudi memang berusaha mempertahankan tradisi
keagamaannya. Mereka menganggap peradabannya lebih superior dari lainnya,
apalagi berhadapan dengan orang-orang Arab Badui yang kehidupannya jauh lebih
sederhana. Di sini muncul pertanyaan, sejauh mana sebuah peradaban mampu
mempertahankan dirinya untuk tidak berasimilasi dengan, dan tidak terpengaruh
oleh, peradaban lain? Yahudi memiliki daya resistensi yang kuat terhadap peradaban
lain karena sejak awal mereka telah membangun self-image yang tinggi. Konsep
“umat pilihan” adalah basis kekuatan mereka melawan segala pengaruh dari luar.
Empat abad sebelum Masehi, ketika Ezra memimpin Bani Israil, mereka telah
mendapatkan peringatan yang keras karena berani melakukan perkawinan dengan
orang-orang asing.
(1) Now when these things were done, the princes drew near unto me, saying: ‘The people of Israel, and the priests and the Levites, have not separated
32Q.S. al-Baqarah: 85. Lihat Syihāb al-Dīn Abū al-Fad}l, al-‘Ujjāb fī Bayān al-Asbāb, (al-Dimām: Dār Ibn al-Jawzī, 1997), Vol. 1, 278.
themselves from the peoples of the lands, doing according to their abominations, even of the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, the Jebusites, the Ammonites, the Moabites, the Egyptians, and the Amorites. (2) For they have taken of their daughters for themselves and for their sons; so that the holy seed have mingled themselves with the peoples of the lands; yea, the hand of the princes and rulers hath been first in this faithlessness’ 33
Ezra menyatakan sangat malu kepada Tuhan karena perbuatan kaumnya yang
dianggap menjijikkan itu. Ia memohon ampun kepada Tuhan, tidak makan dan tidak
minum karena terus menerus bermunajat. Akhirnya ia memerintahkan mereka untuk
bertobat dan memisahkan diri dari istri dan orang-orang yang berasal dari bumi asing
itu, sebab “asing” dalam pandangannya adalah “kafir” dan “kotor.”
(10) And Ezra the priest stood up, and said unto them: ‘Ye have broken faith, and have married foreign women, to increase the guilt of Israel. (11) Now therefore make confession unto the LORD, the God of your fathers, and do His pleasure; and separate yourselves from the peoples of the land, and from the foreign women’.34
Ini tentu saja bukan sebuah pertobatan politik dalam perspektif seorang
pemimpin spiritual dan kaum awam. Pada zaman itu, bercampur baur dengan orang
asing adalah dosa. Orang asing selalu dipahami sebagai penyembah berhala dan tidak
mengenal Tuhan, karena itu selalu harus dijauhi. Itu adalah kenyataan bagi zaman
tersebut, yang tentu saja tidak dapat disamakan dengan segala zaman. Hanya saja
ketika kitab suci telah merekam fenomena seperti itu, persoalannya jadi lain atau,
paling tidak, penafsiran tentangnya akan menjadi sebuah perdebatan.
Setelah Islam datang, kaum Muslim Arab mengenal orang-orang Yahudi dan
Nasrani sebagai masyarakat Ahli Kitab (Ahl al-Kitāb), sebagaimana tersebut dalam
banyak ayat al-Qur’an. Sebagian dari Ahli Kitab memeluk Islam karena menemukan
33Ezra 9: 1-2.
34Ezra 10: 10-11
bukti-bukti lalu percaya akan kerasulan Nabi Muhammad, tetapi kebanyakan mereka
tetap bertahan dalam agamanya.
C. Kebencian terhadap Yahudi
Pikiran kaum Muslim dipenuhi oleh bayangan kejahatan eternal Yahudi yang
dimulai sejak bangsa tersebut mengenal Nabi Muhammad dan Islam sampai hari ini
dan bahkan dari zaman Nabi Musa sampai hari kiamat. Yahudi tidak henti-hentinya
memusuhi Islam. Mereka membuat berbagai rencana kejahatan, konspirasi, intrik
dan kebohongan untuk menghancurkan Islam dan menyesatkan kaum Muslim. Lebih
dari itu, segala petaka moral dan politik di dunia sekarang tidak jarang dianggap oleh
kaum Muslim sebagai rekayasa Yahudi belaka yang ingin menguasai seluruh jagat
ini untuk kepentingan bangsa mereka dan untuk memperbudak seluruh bangsa lain di
permukaan bumi ini. Segala kebijakan politik internasional dan segala pikiran
modern, mulai dari liberalisme, humanisme, demokrasi, kapitalisme, mode, iklan,
sampai kepada perang dan terorisme, tidak terlepas dari lobi internasional Yahudi
dan kepentingan politik mereka. “Yahudi memang terkutuk.” Mereka harus
dimusnahkan dari bumi ini.
Permusuhan dan kebencian tersebut belum berakhir, dan tidak pernah
berakhir tanpa ada kesadaran sejarah dan budaya di kedua belah pihak. Konflik
politik di Timur Tengah telah menyeret umat Islam dan Yahudi dalam perangkap
kepentingan kelompok-kelompok tertentu: Amerika, Inggris, pengusaha minyak,
pemilik pabrik senjata, dan berbagai persekongkolan kelas dunia yang meraup
keuntungan dari berbagai jenis konflik. Kedua belah pihak saling ingin menghabisi
dan saling menciptakan citra seburuk-buruknya terhadap lawan. Tidak ada diskusi
dan dialog; semuanya telah final. Tuhan telah berfirman dengan sejelas-jelasnya
kepada masing-masing pihak bahwa mereka adalah yang terbaik dan musuhnya
adalah yang terjelek di dunia ini, walaupun, anehnya, Tuhan mereka adalah satu
juga: Tuhan yang Maha Esa. Di sini terlihat kekuatan fanatisme dan indoktrinasi
ideologi demikian dalam mencengkeram ke akar keyakinan manusia ketika akal dan
kebebasan telah dilenyapkan dari kesadaran.
Jika diusut jauh ke belakang, semua ini ternyata berawal dari sebuah
perselisihan di sebuah kota kecil yang bernama Yatsrib. Kota ini disebut oleh orang-
orang Yahudi dengan nama medinta, dari bahasa Aramai, artinya “kota.” Nabi
Muhammad kemudian mengadopsi nama ini dan menyebutnya Madīnah.35
Hubungan Nabi dengan orang-orang Yahudi pada awalnya amat baik, bahkan
mereka, bagi Nabi, adalah kelompok potensial untuk mendukung dakwahnya.
Mereka adalah orang-orang yang memiliki Kitab dan tradisi keagamaan yang
diwarisi dari nabi-nabi sebelumnya. Beberapa ayat al-Qur’an menunjukkan harapan
tersebut, misalnya:
Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (al-Qur’an) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.36
35Karen Armstrong, Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam, (London: Victor Gollancz, 1991), 149.
36Q.S. al-Baqarah: 41.
Beberapa tradisi Yahudi bahkan diadopsi oleh Nabi ke dalam Islam, seperti puasa
hari ‘Āsyūrā’ (tanggal 10 Muharram)37 dan sembahyang menghadap Bayt al-Maqdis
(Yerusalem), dalam rangka menarik mereka kepada Islam atau, mungkin, karena
Nabi menganggapnya sebagai bagian dari tradisi yang patut dilestarikan. Orang-
orang Yahudi juga sangat baik menerima Nabi dengan harapan dapat menarik beliau
menjadi partner atau berpihak pada mereka. Nabi mendatangi pimpinan-pimpinan
mereka dan mendapatkan kehormatan serta persahabatan yang hangat dan akrab.
Semuanya seakan-akan merupakan sebuah harapan terbentuknya persaudaraan dan
kerja sama Yahudi-Muslim yang kokoh serta masa depan yang cemerlang bagi kedua
pihak. Kerendahan hati Nabi, kesederhanaan, kejujuran, kesetiaan, kebaikan dan
kepeduliannya terhadap kaum miskin dan lemah membuat penduduk Yatsrib
37Al-Bukhārī dan Muslim (juga perawi lainnya) meriwayatkan bahwa ketika hijrah ke Medinah, Nabi menemukan orang-orang Yahudi melaksanakan puasa pada hari ‘Āsyūrā. Nabi bertanya mengapa mereka puasa, di mana mereka menjawab, bahwa hari tersebut adalah hari baik dan Allah telah melepaskan Bani Israil dari musuh mereka pada hari tersebut. Maka Nabi menganggap dirinya lebih berhak melaksanakannya dan menyuruh para sahabat untuk ikut berpusa pada hari tersebut. Lihat al-Bukhārī, S{ah}īh} al-Bukhārī, (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1987 M./1407 H.), Vol. 2, 704: Hadis No. 1900; Muslim, S{ah}īh} Muslim, (Beirut: Dār Ih}yā’ al-Turāts al-‘Arabī, t.t.), Vol. 2, p 795: Hadis No. 1130. Hadis ini memberikan kesan pengadopsian Nabi terhadap tradisi Yahudi. Bagi Muslim ortodoks ini mungkin sangat tidak menyenangkan. Bagaimana mungkin Nabi mengikuti tradisi Yahudi sementara beliau sendiri menyuruh kaum Muslim menyalahi mereka. Yusuf al-Qarad}āwī telah menjelaskan masalah ini agak rinci. Sebagaimana dikemukakan al-Qarad}āwī, memang ada hadis lain yang mengatakan bahwa Nabi telah melaksanakan puasa hari ‘Āsyūrā’ sejak sebelum hijrah. Orang-orang jahiliah juga telah melaksanakannya sebelum itu. Lihat <http://www.qaradawi.net>. Untuk hadis puasa ‘Āsyūrā’ jahiliah, lihat di antara lain al-Bukhārī, Vol. 2, 704: Hadis No. 1898 dan Muslim, Vol. 2, 792: Hadis No. 1125. Jadi, menurut al-Qarad}āwī, meskipun Nabi telah mengatakan apa yang beliau katakan, Nabi tidak melakukan puasa hari ‘Āsyūrā karena mengikuti Yahudi. Lebih-lebih lagi, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi bercita-cita untuk mengiringi puasa hari ‘Āsyūrā dengan puasa sehari sebelumnya, yakni tanggal 9 Muharram, untuk menyalahi tradisi Yahudi dalam berpuasa. Lihat Muslim, Vol. 2, 797: Hadis No. 1134. Jika pun dipahami bahwa Nabi telah mengadopsi tradisi Yahudi, sebenarnya maklum saja, karena pada masa awal hijrah, Nabi sedang menarik hati mereka kepada Islam. Hal ini juga tidak bertentangan dengan al-Qur’an yang diturunkan termasuk untuk membenarkan ajaran Kitab sebelumnya (Q.S. al-Baqarah: 41). Sangat mungkin, bahkan, bahwa tradisi puasa ‘Āsyūrā’ yang dilakukan orang-orang Arab sebelum Islam adalah juga berasal dari tradisi orang-orang Yahudi.
terpesona. Nabi adalah sebuah harapan bagi penduduk kota itu yang selama ini saling
bertikai dan terpecah belah. Nabi menyambut baik harapan tersebut dan membuat
sebuah pakta yang terkenal dengan Piagam Madīnah. Semua penduduk kota itu, dari
kelompok mana pun, termasuk Yahudi, ditetapkan untuk bertanggung jawab atas
keamanan dan keutuhan wilayah tersebut. Semua mereka mendapatkan hak dan
kewajiban, bertanggung jawab menegakkan keadilan dan tidak boleh ada yang
disakiti atau dizalimi. Kaum Muslim dan orang-orang Yahudi mendapatkan hak dan
kewajiban yang seimbang serta kebebasan menjalankan agama masing-masing. Pakta
tersebut terutama sekali menjadi instrumen kesepakatan dan kerja sama antara orang-
orang Muhājirīn dan Ans}ār di satu pihak dan orang-orang Yahudi di pihak lain.38
Suasana awal amat menyenangkan. Lalu apa yang membuat timbulnya
pertikaian sengit dan permusuhan amat dalam antara Muslim dan Yahudi, sampai
mereka diperangi dan diusir dari Medinah, dan hari ini dianggap sebagai bangsa
terkutuk dan menjijikkan? Pertikaian, di mana pun dan dalam peradaban mana pun,
tidak langsung dimulai begitu saja tanpa preseden-preseden. Ketika seseorang
membenci orang lain, ia akan mencari alasan untuk menjatuhkannya. Dalam
hubungan Yahudi-Muslim, siapa sebenarnya yang telah memulai pertikaian itu? Di
hadapan mahkamah sejarah, orang patut mengajukan pertanyaan ini. Namun ada
persoalan: sejauh manakah sejarah mampu memberikan jawaban yang setepat-
tepatnya dalam hal yang satu ini? Ini adalah pertikaian keluarga: pertikaian sepupu,
antara anak-anak Ishak dan anak-anak Ismail. Amat jarang peradilan dapat
memberikan jalan keluar bagi pertikaian seperti ini; amat sulit ditelusuri dari mana
38H{usein Haykal, The Life of Muh}ammad, trans. Isma‘īl Rājī al-Fārūqī (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1993), 179-183.
ujung pangkalnya. Mungkin, saling berusaha untuk memahami dan mencari solusi
secara internal adalah jalan terbaik mengakhiri konflik semacam itu.
Tidak ada keraguan bahwa permusuhan antara Yahudi dan Nasrani telah lama
terjadi. Kedua kelompok ini, menurut al-Qur’an, saling menuduh lawannya sebagai
penganut agama yang batil, tidak mempunyai landasan.39 Al-T{abarī (w. 923/310)
meriwayatkan bahwa ketika orang-orang Nasrani Najrān menghadap Nabi
Muhammad, datang pula tokoh-tokoh Yahudi ke sana. Mereka bertengkar di hadapan
Nabi soal agama. Orang-orang Nasrani berkata: agama Yahudi batil; mereka
mengingkari Taurat dan menolak kenabian Musa. Orang-orang Yahudi juga
melakukan hal yang sama. Mereka mengatakan batil terhadap agama Nasrani dan
menyatakan ingkar terhadap Injil dan Isa.40 Maka turunlah Q.S. al-Baqarah: 113:
Dan orang-orang Yahudi berkata: “Orang-orang Nasrani tidak mempunyai suatu pegangan,” dan orang-orang Nasrani berkata: “Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan,” padahal mereka (sama-sama) membaca Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka perselisihkan.
Lebih jauh al-T{abarī mengemukakan bahwa pertengkaran kedua kelompok ini telah
dimulai sejak awal kemunculannya. Pengingkaran mereka satu sama lainnya juga
mengindikasikan penolakan mereka atas kenabian Muhammad, sebab dalam kitab
masing-masing mereka terdapat keterangan mengenai kedatangan Nabi terakhir itu.41
My enemy’s enemy is my friend. Pepatah ini bisa saja berlaku bagi sikap
Yahudi di Medinah yang melihat Nabi sebagai pembawa agama baru. Penerimaan 39Q.S. al-Baqarah: 113.
40Al-T{abarī, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān, (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H.), Vol. 1, 495.
41Ibid., 496.
mereka terhadap Nabi mungkin saja dipahami sebagai upaya memperkuat posisi
mereka melawan kaum Nasrani. Kehadiran Nabi Muhammad sebagai seorang
pemimpin yang penuh karisma di Medinah tentu saja membuat orang-orang Yahudi
pada awalnya terpesona, dan tak pelak lagi mengharapkan Nabi menjadi sekutu yang
potensial untuk dijadikan pendukung mereka melawan musuh Nasraninya. Perjanjian
mereka dengan Nabi dapat dipandang sebagai sebuah harapan ambisius untuk
kepentingan politik dan ideologi mereka sendiri. Namun, sayang sekali, dalam
kenyataannya Nabi Muhammad telah menempati posisi politik yang lebih tinggi
daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sendiri, dan ajaran-ajarannya semakin
mendapat pengaruh yang lebih besar.42
Pada tahap inilah orang-orang Yahudi mulai berpikir kembali soal perjanjian
mereka dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Mereka telah membuat
sebuah kesepakatan dengan sebuah harapan yang mulai terpupus. Mereka mulai
mempertanyakan apakah Muhammad dengan segala seruan, ajaran dan
kekuasaannya dapat dibiarkan, sementara mereka sendiri puas dengan perlindungan
yang diberikan. Bagaimana dengan orang-orang mereka yang mulai tertarik dan
memeluk ajaran Muhammad? Bukankah ini sebuah ancaman keagamaan yang tidak
diharapkan?
Pertemuan Nabi dengan delegasi Nasrani dari Najrān telah dimanfaatkan
Yahudi untuk melibatkan semuanya dalam sebuah perdebatan publik. Dengan
pengetahuannya yang dianggap lebih superior, mereka ingin mengalahkan orang-
orang Nasrani dan Nabi Muhammad. Mereka ingin mengacaukan suasana dan
42H{usein Haykal, The Life of Muh}ammad, 190.
melemparkan keraguan-keraguan kepada publik agar ajaran Muhammad ditinggalkan
orang. Sebelumnya pun mereka telah melakukan hal yang sama. Mereka menabur
benih-benih pertikaian dan membangkitkan permusuhan lama, terutama sekali di
antara suku al-Aws dan al-Khazraj. Sekiranya Nabi tidak cepat menanggulangi hal
tersebut, mungkin pertumpahan darah akan terjadi kembali.43
Pertikaian Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi semakin hari
semakin intens. Orang-orang Yahudi bahkan menyerang dengan pertanyaan-
pertanyaan teologis dan melemparkan penghinaan-penghinaan. Hal ini telah
menyebabkan ayat-ayat al-Qur’an turun memberikan jawaban-jawaban yang
mengandung perlawanan dan kritikan.
Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Rūh{ al-Qudus (Roh Suci). Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh, sehingga beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?
Dan mereka berkata: “Hati kami tertutup.” Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka; maka sedikit sekali mereka yang beriman.
Dan setelah datang kepada mereka al-Qur’an dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka – dan sebelumnya mereka memang biasa memohon untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir – maka (sekali lagi) setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka ingkar kepadanya. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir.44
Ayat-ayat ini, dan semua ayat yang menyeru dan mengkritik orang-orang Yahudi
pada bagian awal surat al-Baqarah, diturunkan di Medinah pada masa awal kehadiran
43Ibid., 192.
44Q.S. al-Baqarah: 87-89.
Nabi di kota itu, tatkala dialog-dialog antara mereka dan Nabi terus terjadi sampai
berujung pada konflik dan pertikaian-pertikaian. Beberapa ayat yang dikutip di atas
adalah di antara ayat-ayat yang merupakan puncak peringatan al-Qur’an kepada
orang-orang Yahudi.45 Dalam ayat-ayat sebelumnya, sejak ayat 40 surat al-Baqarah,
al-Qur’an mengajak orang-orang Yahudi melakukan perenungan atas segala karunia
Tuhan kepada mereka dan juga hukuman-hukuman yang diberikan karena
perlanggaran yang mereka lakukan. Tampak bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan
pada awalnya dengan nada yang agak lembut dan penuh ajakan, namun kemudian
terus berlanjut dengan nada yang semakin keras. Hal ini menunjukkan perkembangan
atmosfer hubungan Nabi dan orang-orang Yahudi yang semakin hari semakin
mengarah pada konflik.
Sementara itu, ayat-ayat di atas mengisyaratkan mulai “gerah”nya al-Qur’an
melihat sikap orang-orang Yahudi yang semakin menunjukkan perilaku yang tidak
sopan dan tidak bersahabat. Menurut al-Qur’an, orang-orang Yahudi mempunyai
pengetahuan yang memadai dari kitab suci untuk dapat melihat kebenaran yang
disampaikan Nabi Muhammad. Keingkaran mereka semata-mata karena
kesombongan. Mereka sendiri padahal “menunggu-nunggu” kehadiran Nabi, namun
ketika Rasul yang ditunggu-tunggu itu hadir di tengah-tengah mereka, mereka
mengingkarinya.
Kritik yang dilancarkan al-Qur’an di sini amat keras, namun sebenarnya
mempunyai sasaran yang jelas, yaitu orang-orang yang ingkar, sombong dan
memusuhi utusan Tuhan. Mereka disebut kafir, dan Tuhan mengutuk mereka.
45Lihat Muhammad al-Ghazālī, A Thematic Commentary on the Qur’an, trans. Ashur A. Shamis, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2001), 6 ff.
Meskipun berbicara dalam konteks Yahudi Medinah, bahkan berhadapan dengan
mereka, al-Qur’an sepertinya memperlihatkan sentimen yang lebih luas terhadap
kaum Yahudi secara umum. Dalam ayat-ayat lain, orang-orang Yahudi secara lebih
jelas digambarkan sebagai kelompok yang suka membuat makar, pendosa dan
bahkan mereka tega membunuh para nabi. Ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani
mengklaim diri mereka sebagai “anak-anak” dan kekasih Tuhan, al-Qur’an
mengingatkan bagaimana mereka dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa yang
mereka perbuat. Al-Qur’an ingin membantah klaim tersebut, dan menegaskan bahwa
mereka adalah manusia seperti yang lainnya juga. Tuhan bisa saja menghukum dan
mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya. Bantahan al-Qur’an kelihatan sekali
sangat proporsional, humanis dan universal. Apa yang ditunjukkan al-Qur’an di sini
jelas merujuk pada kitab dan tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani sendiri. Mereka
justeru diajak untuk merefleksikan kembali pengalaman sejarah mereka sebagaimana
terdapat dalam sumber agama mereka sendiri.
Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Berimanlah kepada al-Qur’an yang diturunkan Allah,” mereka berkata: “Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami.” Dan mereka ingkar kepada al-Qur’an yang diturunkan sesudahnya, sedang al-Qur’an itu adalah (Kitab) yang kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah: “Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?”46
Dalam ayat yang lain disebutkan:
Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: “Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.” Katakanlah: “Lalu mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?” Kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Kepunyaan
46Q.S. al-Baqarah: 91.
Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).47
Ayat-ayat ini, dan sederetan ayat-ayat lain dengan semangat seperti ini, sering
kali dijadikan alasan oleh kaum Muslim untuk mengklaim Yahudi sebagai bangsa
atau etnis yang berwatak jahat. Mereka sejak dari dulu, sebelum kedatangan Islam,
menentang para nabi, berbuat jahat, menabur permusuhan dan terkenal sangat licik.
Mereka sejak dari dulu dimurkai oleh Tuhan, dikutuk dan diturunkan kepadanya
azab. Dengan image (kesan) seperti itu, bagaimana mungkin kaum Muslim diajak
berdamai dengan mereka?
Pada awalnya adalah sebuah pertikaian kecil dan bahkan mungkin “kekanak-
kanakan.” Ibn Hisyām, sebagaimana dikutip oleh al-Būt}ī,48 meriwayatkan bahwa
seorang perempuan Arab (Muslimah) pernah pergi ke pasar Banī Qaynuqā‘
membawa barang-barangnya untuk dijual. Ia duduk pada tempat tukang perhiasan.
Orang-orang Yahudi di situ menginginkan dia membuka wajahnya, tetapi ia tidak
mau. Tukang perhiasan itu lalu sengaja mengikat ujung kain perempuan tersebut ke
belakangnya. Ketika ia bangun, tersingkaplah kainnya dan terlihat auratnya. Maka
mereka menertawakannya. Perempuan itu berteriak, dan seorang Muslim segera
melompat dan membunuh Yahudi tukang perhiasan tersebut. Orang-orang Yahudi itu
pun tidak tinggal diam; mereka membunuh Muslim tadi. Akibat kejadian itu,
keluarganya mengadu kepada orang-orang Muslim lainnya. Terjadilah pertikaian
yang hebat antara mereka dan Banī Qaynuqā‘, sehingga Nabi Muhammad kemudian
47Q.S. al-Mā’idah: 18.
48Muhammad Sa‘īd Ramad}ān al-Būt}ī, Fiqh al-Sīrah, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 228.
melancarkan serangan terhadap kelompok Yahudi tersebut, dan mereka diusir dari
Medinah. Inilah awal dari pengkhianatan kaum Yahudi terhadap kaum Muslim, dan
ini menjadi rujukan betapa Islam membenci Yahudi dan melarang kaum Muslim
berteman ataupun berdamai dengan mereka. Adalah ‘Ubādah ibn al-S{āmit –
sahabat yang pernah mengadakan konfederasi (perwalian, persekutuan) dengan Banū
Qaynuqā‘ – yang datang kepada Nabi dan menyatakan melepaskan diri dari
persekongkolan dengan kaum Yahudi. Peristiwa ini direspon dan dipertegas oleh al-
Qur’an:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin-(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.49
Hal ini dinyatakan al-Qur’an dalam rangka membenarkan sikap ‘Ubādah dan
mencela ‘Abdullāh ibn Ubay ibn Salūl yang tetap bersekongkol dan mengukuhkan
persekutuannya dengan Yahudi.50
Menurut riwayat Ibn Ish}āq, Nabi juga pernah mengumpulkan Banū
Qaynuqā‘ di pasar mereka, mengajaknya kepada Islam dan memberikan peringatan
serta mengingatkan mereka akan azab yang mungkin saja diturunkan Tuhan jika
mereka ingkar. Jawaban yang diterima oleh Nabi adalah:
Wahai Muhammad, apakah engkau menganggap kami sama dengan kaummu? Janganlah mengira engkau sedang berhadapan dengan sebuah kaum tidak mengerti cara berperang sehingga dengan mudah engkau
49Q.S. al-Mā’idah: 51. Lihat Abū al-H{asan ‘Alī al-Wāh}idī, Asbāb al-Nuzūl, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994/1414), 110.
50Muhammad Sa‘īd Ramad}ān al-Būt}ī, Fiqh, 229.
memanahnya. Sesungguhnya, demi Allah, jika engkau memerangi kami, engkau akan tahu bahwa kami adalah juga manusia.”51
Banū Qaynuqā‘ terkenal memiliki semangat perang yang tinggi dan mereka
adalah kelompok yang kaya.52 Merekalah yang mengawali permusuhan ini, secara
terang-terangan dan terbuka. Kenyataan ini barangkali dapat dijadikan isyarat bahwa
permusuhan yang dilancarkan Yahudi, khususnya Banū Qaynuqā‘, terhadap Islam
tidak mengakar pada problem keagamaan tetapi lebih pada persoalan politik, sosial-
budaya dan ekonomi. Kedengkian telah lebih dahulu menghalangi mereka menerima
seruan risalah Nabi Muhammad. Mereka secara kultural dan juga ekonomi merasa
lebih superior dan memandang rendah kaum Muslim. Persoalan ini menjadi lebih
parah ketika orang-orang Arab sendiri telah menerima image (kesan) seperti itu
sebagai “fakta.” Ini bukan hal yang ganjil; dalam peradaban bangsa mana pun
fenomena serupa dapat ditemukan. Dalam kondisi seperti itu tentu saja amat susah
mengajak mereka tunduk kepada Islam yang dianggap muncul dari, dan berakar
pada, peradaban Arab. Amat sedikit orang yang dapat melepaskan diri dari belenggu
fanatisme seperti ini; hanya dengan kesadaran universal yang mendalam baru dapat
seseorang menemukan core (jati diri) ajaran agama yang disampaikan para nabi.
Barangkali di antara mereka adalah ‘Abdullāh ibn Salām, seorang tokoh Yahudi
Medinah, yang dengan jernih dapat melihat kebenaran dari ajaran-ajaran yang
disampaikan Muhammad.
Patut juga diperhatikan bahwa ketika Nabi Muhammad mengadakan seruan
kepada orang-orang Yahudi agar menjadi Muslim, tidak ada bukti yang jelas
51Ibid., 228.
52K. Ali, A Study of Islamic History, (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1980), 59.
bagaimana mereka harus menjadi Muslim. Nabi mengingatkan Banū Qaynuqā‘:
Ih}dhirū min Allāh …wa aslimū ..! (Waspadalah terhadap [hukuman] Allah … dan
pasrah dirilah!).53 Pusat perhatian Nabi paling mendasar adalah sikap moral Yahudi
yang dinilai harus diluruskan sejalan dengan ajaran yang mereka yakini dan tuntutan
agar mereka mengakui keberadaan beliau sebagai seorang utusan Tuhan, yang
mengajak kepada inti ajaran yang sama.
Seruan-seruan Nabi kepada orang-orang Yahudi tidak berlangsung sukses;
bahkan sebaliknya, ajakan tersebut dipandang sebagai gugatan atas status mereka
sebagai umat pilihan Tuhan dan pemilik kitab suci dari langit. “Cengkeraman
identitas diri” orang Yahudi ini pada gilirannya mengkristal dan membentuk watak
permusuhan terhadap Nabi dan Islam, barangkali sebagai jalan pelarian mental atau
apa yang disebut dengan defense mechanisms dalam psikologi. Mereka memberontak
terhadap Islam, tetapi sebenarnya mereka memberontak terhadap diri sendiri.
Peristiwa yang menimpa Banū Qaynuqā‘ tidak menjadi pelajaran bagi suku
Yahudi lainnya. Setelah mereka diusir pada akhir tahun kedua Hijrah, peristiwa
serupa terulang kembali, pada tahun keempat Hijrah, menimpa Banū al-Nad}īr.
Mereka berkomplot dengan orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi. Usaha
mereka gagal. Nabi menyerang mereka dan bahkan memotong serta membakar
sebagian dari pohon-pohon kurma mereka. Kemudian Nabi mengusir semua mereka
dari Medinah.
53Syihāb al-Dīn Ah}mad ibn ‘Alī, al-‘Ujāb, Vol. 2, 665.
Setelah memaparkan riwayat sekitar pengusiran dan evakuasi Banū al-Nad}īr
dari Medinah, al-Būt}ī membuat komentar mengenai tabiat jahat yang melekat pada
diri orang Yahudi:
Inilah gambaran kedua dari watak khianat yang inheren dalam diri orang Yahudi. Kita telah melihat sebelumnya bentuk lain kejahatan mereka yang dilakukan Yahudi Banū Qaynuqā‘. Itulah kebenaran historis yang dibuktikan oleh fakta-fakta cukup banyak. Itu pula rahasia kutukan Ilahi (al-la‘nah al-ilāhiyyah) atas mereka yang direkam sendiri oleh Tuhan dalam firman-Nya: “Telah dilaknat orang-orang kafir di antara Bani Israil melalui lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas” (al-Mā’idah: 78).54
Apa yang dikatakan al-Būt}ī merepresentasikan pandangan Muslim yang
memenuhi berbagai literatur dalam tradisi Islam. Siapa pun di kalangan Muslim tahu
persis apa artinya ketika seseorang mengatakan: “Yahudi!” Dalam Kamus Bahasa
Indonesia pun, “memperyahudikan” diartikan dengan “mengejikan; memandang
jahat (hina, rendah dsb.).”55 Ini tentu saja bukan sebuah kesalahan yang dilakukan
kamus, karena tugas kamus adalah mengungkapkan sebagaimana adanya bahasa
yang digunakan. Sekurang-kurangnya, hal ini mencerminkan betapa luas dan
mengakarnya image buruk Yahudi dalam peradaban Muslim. “Yahudi” itu sendiri
telah menjadi sebuah simbol, bukan lagi berarti agama ataupun etnis.
Nabi Muhammad, berdasarkan sejarah yang dapat diketahui, sepertinya
memang tidak dapat menghindari pertikaian dengan kaum Yahudi. Beliau selalu
gagal dan menemui jalan buntu ketika mengajak mereka kepada Islam atau jalan
kedamaian. Dua suku Yahudi yang didiskusikan di atas sudah cukup memperlihatkan
54Muhammad Sa‘īd Ramad}ān al-Būt}ī, Fiqh, 261.
55W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984,) p. 1153.
pahitnya penderitaan mereka dan mendalamnya kesedihan Nabi. Namun
disayangkan, masing-masing tetap bersikukuh dengan pendiriannya dan membiarkan
permusuhan itu berlangsung sebagaimana adanya, seakan-akan demikianlah atmosfer
alami kehidupan Yahudi bersama kaum Muslim.
Banū Qurayz}ah juga tidak memperlihatkan isyarat perdamaian yang
sungguh-sungguh, walaupun mereka tidak dikeluarkan oleh Nabi dari Medinah
sebagaimana beliau lakukan terhadap dua suku Yahudi sebelumnya. Mereka
melakukan pelanggaran serius dalam perang Uhud. Namun mereka mengajukan
pertobatan dan berjanji memperbaiki sikapnya. Apakah ini merupakan sebuah
harapan bagi Nabi dan orang-orang Yahudi untuk secara berdampingan bersama-
sama membangun sebuah masyarakat yang damai? Ternyata akhirnya mereka juga
berkomplot dengan orang-orang kafir Quraisy yang melakukan perlawanan terhadap
Muslimin. Mereka membuat kekacauan untuk memudahkan orang-orang kafir
melakukan pengepungan terhadap kaum Muslim di Medinah. Demikian juga dalam
perang Khandaq, mereka memainkan peran yang signifikan. Setelah perang, mereka
diperintahkan untuk meninggalkan kota. Karena menolak, mereka lalu diserang dan
akhirnya menyerah. Persoalan mereka kemudian diselesaikan melalui sebuah
arbitrase. Sejumlah mereka dibunuh dan yang lainnya diusir ke Syria.56
Kehidupan Yahudi seakan-akan sebuah kisah penderitaan, sebuah
perlambang kejahatan dan bahkan sumber petaka bagi manusia. Inilah sisi paling
terang di mata kebanyakan orang tentang perjalanan hidup mereka. Literatur Islam
56K. Ali, A Study, 60-61.
mana pun yang berbicara mengenai Yahudi akan menyusun sebuah daftar berisi
kejahatan dan sifat buruk bangsa Yahudi.57
Dalam sebuah konferensi di Mesir, ketika berbicara tentang Yahudi dalam
konteks permusuhan dengan Nabi di Medinah, Muhammad Azzah Darwaza
mengatakan:
The Jews were also stubborn in telling lies and contradicting the truth. They preferred the pleasures of the world. They enjoined the good although they were not good people. They deceived the people. They did not cooperate with others. They put their heads together and secretly agreed among themselves to deceive the people and to be hypocrites. The Jews did not help others or teach them. They told lies about Allah and let people suspect their religion… They were not ashamed of embracing Polytheism or performing the rites of paganism… They displaced the words of Allah and disfigured the laws of Heaven and God’s advice. They were hard-hearted and sinful, they committed unlawful and forbidden crimes… Thus the Jews rightfully deserved the wrath and the curse of Allah, recorded throughout many verses.58
Deskripsi Darwaza ini memang dalam konteks kehidupan Yahudi Medinah
pada masa Nabi, dan mengenai hal ini, sejumlah ayat al-Qur’an dapat dijadikan
rujukan. Akan tetapi kemudian ia melanjutkan:
It is extremely astonishing to see that the Jews of today are exactly a typical picture of those mentioned in the Holy Quran and they have the same bad manners and qualities of their forefathers although their environment, surroundings and positions are different from those of their ancestor… Consequently, the Jews are avoided by all people who scorn and hate them.
People are always cautious when they get in touch with them so as to avoid their wickedness and deceit.
57Lihat misalnya sebuah buku yang disadur oleh Anas ‘Abd al-Rahmān dari tafsir Sayyid Qut}b dengan judul S{irā‘unā ma‘a al-Yahūd fī Z{ilāl al-Qur’ān, (Kuwait: Maktabah Dār al-Bayān, 1989). Di dalamnya terdapat sederetan topik mengenai sifat-sifat orang Yahudi, seumpama: Sifat Permusuhan, Jauh dari Iman, Umat Terkutuk, Umat yang Sesat dan Menyesatkan, Umat yang Terpecah Belah, Umat Fasik, Umat Hipokrit dan sebagainya.
58Muhammad Azzah Darwaza, “The Attitude of the Jews Towards Islam, Muslims and the Prophet of Islam-P.B.U.H. at the Time of His Honourable Prophethood,” dalam D.F. Green (ed.), Arab Theologians on Jews and Israel, ed (Genève, 1974), 27.
… All races of mankind, throughout the world, always reject the Jewish actions and behavior unanimously and thus it is an evidence and a strong proof that their wickedness and bad manners are a result of the evil nature which is inherent in them.59
Bukti-bukti kejahatan umat Yahudi bukan hanya ditemukan dalam kitab suci
kaum Muslim, tetapi juga dalam kitab suci mereka sendiri. Walaupun kebanyakan
Muslim enggan membaca, dan bahkan menyentuh, kitab suci umat lain,60 tetapi
untuk satu hal ini (yakni mencari cela orang lain) mereka mengkajinya dengan
mendetil. Kamal Ahmad Own mengungkapkan pengalamannya:
In reviewing the Old Testament especially its historical chapters, I was shocked at the scenes of bloodshed, sex perversion and the violation of the prophets, sanctity included therein. I felt that what took place in Palestine before and after the May War 1948 did not differ from what I had read in the Old Testament.61
Pada akhirnya ia menyimpulkan:
59Ibid., 27-28.
60Pandangan ini sering diperkuat dengan sebuah hadis yang menceritakan Nabi Muhammad menegur para sahabat yang suka bertanya kepada orang-orang Yahudi dan beliau mengatakan bahwa sekiranya Musa hidup kembali, beliau akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Al-Zarqānī – dalam bukunya Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’an, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), Vol. 2, 22 – mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ah}mad dan al-Bazzār tersebut sebagai berikut:
لن ف//إنهم ش/يء عن الكت//اب أه//ل تس//ألوا ال بلف/ظ ج//ابر حديث من والبزار أحمد ورواه بين موس//ى ك//ان ل//و والله بباطل تصدقوا أو بحق تكذبوا أن إما وإنكم ضلوا وقد يهدوكم
من ش//يئا كتب عم//ر أن علم الن//بي أن الح//ديث هذا وسبب اتباعي إال له حل ما أظهركموقاله فغضب اليهود عن التوراة
Menurut Nurcholish Madjid, banyak ulama Islam terkenal seperti al-Syahristānī, al-‘Āmilī dan Ibn Taymiyyah, yang menguasai Taurat dan Injil secara mendalam, walaupun “ironisnya,” kata Nurcholish, “umat Islam sekarang ini memegangnya saja enggan.” Lihat Nurcholish Madjid, “Metodologi dan Orientasi Studi Islam Masa Depan,” Jauhar, Vol. I, No. 1, Desember 2000, 19-20.
61Kamal Ahmad Own, “The Jews are the Enemies of Human Life as is Evident from Their Holy Book,” dalam D.F. Green (ed.), Arab Theologians on Jews and Israel, (Genève, 1974), 13.
So both in their Holy Book and the Talmud are full to the brim with such horrible deeds, evil and crimes that make us feel that they deserved all the disasters and the afflictions that befall them.62
Mudah disadari bahwa ungkapan-ungkapan yang dikutip di atas tidak terlepas
dari sentimen politik akibat dari pertikaian Arab-Israel di Timur Tengah. Walaupun
demikian, orang mungkin akan bertanya-tanya, mengapa begitu mudah seseorang,
dalam sebuah konferensi ilmiah seperti itu, mengekspresikan pandangan-pandangan
yang begitu sempit, eksklusif, dan menghina keyakinan orang lain. Sungguhkah kitab
suci umat Yahudi itu penuh dengan pandangan-pandangan yang keji tentang diri
mereka sendiri? Apakah dapat diterima berdasarkan perasaan sehat dan akal waras,
bahwa sebuah kitab suci menghina umatnya sendiri? Bukankah semua ini
menunjukkan naifnya pandangan umat Islam terhadap keyakinan umat lain? Lalu
bagaimana “kita” dapat mengharapkan “orang lain” memahami “kita” jika “kita”
sendiri tidak pernah berusaha memahami “orang lain?”
Sampai hari ini permusuhan tersebut belum berakhir. Berbagai media massa
Muslim masih mengisi lembaran-lembarannya dengan berbagai bentuk provokasi
dan berita-berita yang bernada permusuhan. Pada 10 Maret 2002, misalnya, sebuah
koran Arab Saudi, al-Riyād}, menurunkan sebuah artikel yang ditulis oleh Dr.
Umayma Ahmad al-Jalahma, dari Universitas King Fays}al, al-Dammām, tentang
festival Yahudi yang dikenal dengan hari raya Purim. Hariraya Purim, demikian
menurut al-Jalahma, dirayakan oleh orang-orang Yahudi dengan sebuah upacara
ritual yang amat mengerikan: darah manusia, khususnya anak remaja dari kalangan
non-Yahudi (Muslim dan Kristen), harus digunakan sebagai bumbu tambahan
62Ibid., 18.
pembuatan kue-kue perayaan tersebut. Al-Jalahma bahkan mendeskripsikan secara
grafis dan rinci tentang ritual aneh dan menyeramkan itu. Lebih lanjut ia mengatakan
bahwa peristiwa tersebut telah merupakan fakta sejarah yang tidak dapat
dipungkiri.63
Apa yang dilakukan al-Jalahma tentu saja menimbulkan reaksi keras dari
berbagai kalangan terutama di Barat. Ketika Turki al-Sudairi, Editor-in-Chief koran
al-Riyād} tersebut, yang tidak berada di tempat pada waktu itu, ditanyakan oleh
Hani Wafa, salah seorang koleganya, perihal artikel itu, ia terkejut. Setelah
mempelajarinya, ia mengatakan bahwa artikel tersebut:
… not fit for publication because it was not based on scientific or historical facts, and it even contradicted the rituals of all the known religions in the world, including Hinduism and Buddhism. The information included in the article was no different from the nonsense always coming out in the ‘yellow literature,’ whose reliability is questionable.64
Menurut al-Sudairi, al-Jalahma keliru dengan pandangannya itu sebagaimana
ia telah keliru memahami bahwa Yahudi di seluruh dunia adalah sama; padahal
Yahudi dan Zionisme adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Di Israel sendiri
terdapat orang-orang Yahudi moderat seperti Yisrael Shahak, yang menentang
rasisme Zionis dan mengekspos hal tersebut dalam berbagai studi yang ia lakukan.
There are others like Shahak, and our dispute with phenomena such as Sharon must
in no way cause us to generalize the emotions of hatred to all Jews. Mengenai isi
artikel al-Jalahma, al-Sudairi menegaskan: … in principle, an idiotic and false news
63Al-Riyād}, 10 Maret 2001. Lihat juga MEMRI (The Middle East Media Research Institute), Special Dispatch Series, No. 354, March 13, 2002. Lihat juga Internet Version, <www.memri.org>.
64MEMRI (The Middle East Media Research Institute), Special Dispatch Series, No. 357, March 21, 2002.
item regarding the use of human blood in the food of other human beings, whoever
they may be, should not be published, since this does not exist in the world at all.65
Satu hal yang menarik diperhatikan adalah bahwa sentimen permusuhan
bukan hanya menggema di Timur Tengah, tempat terjadi permusuhan politik
Muslim-Yahudi atau Palestina-Israel, tetapi juga di seluruh dunia Islam atau di mana
saja kaum Muslim berada. Abdullah al-Faisal seorang Muslim asal Jamaika
melebarkan dakwahnya sampai ke Inggris. Ia mengajak pengikutnya untuk
melakukan “Jihad” dan membunuh orang-orang Yahudi. Menurutnya, kaum Muslim
tidak boleh berdamai dengan Yahudi sebab mereka adalah najis dan memiliki watak
alamiah yang keji.66 Belum lama ini, seorang tokoh pemimpin Asia Tenggara,
Mahathir Mohamad, juga menyampaikan sebuah pidato yang berisi kalimat-kalimat
dengan nada yang membangkitkan sentimen rasial terhadap Yahudi. Mahathir
mengatakan bahwa “kaum muslim dengan jumlah 1,3 miliar tidak boleh dikalahkan
oleh hanya jutaan Yahudi,” dan ia meminta agar “negara-negara muslim memperkuat
alat-alat pertahanan negara serta menepis perasaan tidak berdaya dalam menghadapi
kekuatan Yahudi, yang dikatakannya saat ini tengah menguasai dunia.”67 Pidato yang
disampaikan pada pembukaan KTT OKI di Putrajaya, Malaysia, itu juga mendapat
reaksi dari berbagai kalangan; sebagian membela dan sebagian lagi mengecam
dengan keras. Keberatan yang disampaikan tentu saja menyangkut pernyataan yang
secara eksplisit menunjukkan kepada permusuhan Yahudi-Muslim. Menurut
65Ibid.
66Response, Vol. 23, No. 1, Spring 2002, 5.
67Republika Online, 16 Oktober 2003: <www.republika.co.id/berita/online/2003/ 10/16/143265.shtm>. Lihat juga Reme Ahmad, “Mahathir tells Muslims to use brains to fight Jews,” The Straits Times, Oct. 19, 2003.
European Union, statemen Mahathir justeru melukai semua pihak, baik Yahudi
maupun Muslim. His unacceptable comments hinder all our efforts to further inter-
ethnic and religious harmony, and have no place in a decent world. Such false and
anti-Semitic remarks are as offensive to Muslims as they are to others.68
Apakah semua ini menghapus seluruh harapan damai dan persaudaraan antar
umat berbeda agama, terutama antara Yahudi dan Muslim? Tidak adakah tanda-tanda
menuju perdamaian? Jika kebencian modern yang menyelimuti pandangan Muslim
terhadap Yahudi dan juga pandangan Yahudi terhadap Muslim muncul dan
menyebar dari Timur Tengah, maka harapan damai tersebut juga dapat diharapkan
datang dari sana. Beberapa fenomena berikut barangkali dapat dijadikan indikasi ke
arah pencapaian harapan tersebut. Pertama, sebagaimana telah didiskusikan di atas,
bahwa tulisan al-Jalahma yang bernada antisemitisme telah dikecam dengan keras
oleh Editor koran tersebut sendiri, Turki al-Sudairi. Ia mengkritik penulis tersebut
sebagai telah melakukan kekeliruan besar dan tindakan yang tidak pantas.
Kedua, penolakan para intelektual Arab terhadap konferensi internasional
yang direncanakan oleh the holocaust deniers. Sejumlah kalangan mengatakan
bahwa peristiwa the holocaust tidak pernah terjadi dalam sejarah; itu hanya rekayasa
Yahudi untuk menarik simpati dunia. Pandangan yang dikembangkan oleh para
antisemitis ini juga telah tersebar luas di kalangan Muslim dan sekaligus dijadikan
dasar bagi kebencian terhadap umat Yahudi. Ketika the holocaust deniers ini
merencanakan mengadakan sebuah konferensi internasional di Beirut akhir Maret
2002, banyak tokoh dari kalangan intelektual Arab menyadari bahwa bahaya
68“What they say about Mahathir’s remarks on Jews,” The Straits Times, Oct. 19, 2003.
konferensi tersebut lebih besar dari manfaatnya dan mereka melakukan kritik tajam
terhadap perencanaan pelaksanaannya. Seorang kolumnis al-H{ayāt, sebuah koran
berbahasa Arab di London, menulis sebagai berikut: “Mengadakan konferensi
tersebut di Beirut tidak membawa kehormatan apa pun bagi ibukota Libanon.
Barangkali kerusakannya secara konseptual, politik dan ekonomi jauh lebih besar
dari manfaatnya, yang jika dilihat dari luar hampir tidak ada sama sekali.” Lebih jauh
ia mengatakan bahwa konferensi tersebut tidak lebih dari pembelaan terhadap para
kriminal Nazi yang membunuh orang-orang Yahudi dan lainnya, atas nama para
korban Palestina dan Arab.69 Abd al-Wahhāb Badrikhān juga telah memberi
komentar yang sama, dan mengatakan bahwa sejumlah intelektual Arab telah
mencela dengan keras perencanaan konferensi tersebut.70
Ketiga, sebuah rekomendasi baru telah dikeluarkan oleh Universitas al-Azhār
yang melarang kaum Muslim menyebut “kera” dan “babi” kepada orang-orang
Yahudi. Sebagaimana banyak terjadi di kalangan Muslim, Yahudi sering dikutuk
dengan menggunakan istilah-istilah keji. Ini sering dilakukan dalam khutbah-khutbah
dan pertemuan-pertemuan khusus kalangan Muslim. Rekomendasi ini tentu saja
merupakan sebuah kemajuan penting, karena ia menyentuh lapisan bawah dan
populer yang sangat potensial. Osama al-Baz, penasehat politik Presiden Mubarak,
lebih jauh dalam sebuah seri artikel di al-Ah}rām, menentang serta mengkritik
dengan tajam berbagai mitos antisemitik yang kerap kali digembar-gemborkan
kalangan Muslim, terutama sekali the Protocols of Zion, pelabelan Yahudi sebagai
69Al-H{ayāt, 13 Maret 2001.
70Ibid., 19 Maret 2001.
peminum darah manusia dan penolakan terhadap the holocaust. Lebih lanjut, al-Baz
mengatakan bahwa antisemitisme adalah konsep Eropa yang diimpor ke dunia Islam,
bukan berasal dari Arab dan Muslim.71
Fenomena positif di atas hanya sebuah gerak maju kecil yang dilakukan umat
Islam menuju kesadaran pluralisme keagamaan yang jauh lebih besar dan kompleks.
Apalagi, jika dibandingkan dengan gerakan kelompok ekstremis yang lebih banyak
mendahulukan pemenuhan klaim-klaim absolut kelompoknya, apa yang dilakukan
segelintir kalangan intelektual Muslim moderat hanya sebuah seruan sayup-sayup di
tengah hiruk pikuk emosi dan rasa dendam yang telah lebih dahulu menggema ke
seluruh relung kesadaran masyarakat Muslim dunia secara luas.
Pelabelan Yahudi dengan berbagai istilah yang menjijikkan sepertinya telah
menjadi simbol yang abstrak dan bercampur baur dengan emosi, ideologi, kebencian
dan bahkan kebodohan. Umumnya orang tidak peduli lagi dari mana asal usulnya
dan bagaimana duduk persoalannya. Hal yang paling nyata bagi kaum Muslim
kontemporer adalah bahwa mereka tidak dapat menerima pendudukan Israel atau
kaum Zionis di Palestina dan tindakan-tindakan mereka yang melanggar berbagai
asas kemanusiaan terhadap penduduk Muslim setempat. Namun, sesungguhnya
Zionisme harus dipisahkan dari Yudaisme sebagai sebuah tradisi keagamaan, yang
sangat kaya dan telah mengilhami berbagai kesadaran moral, hukum dan falsafah
hidup dalam kehidupan manusia. Kaum Muslim tidak akan menyadari hal ini jika
mereka memang mulai dengan rasa benci dan self-image yang berlebihan, serta
71Al-Ah}rām, 23, 24, and 25, Desember 2002.
pandangan superioritas yang menimbulkan klaim-klaim absolut terhadap diri sendiri
tetap dipertahankan.
Umat Islam mungkin tidak menyadari bahwa dengan menghina orang lain
berarti menciptakan permusuhan dan juga menghina diri sendiri. Dalam hal ini al-
Qur’an sebenarnya telah memberikan peringatan yang jelas bahwa mencaci maki
keyakinan orang kafir sekalipun akan membawa akibat yang buruk bagi Islam dan
kaum Muslim. Karenanya hal tersebut dilarang.
Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhanlah mereka akan kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.72
Al-Qur’an dan Nabi Muhammad tidak pernah menghina atau mencaci maki
agama dan kitab suci orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Meskipun mengkritik
dengan tajam sikap moral dan pandangan keagamaan yang mereka kembangkan, al-
Qur’an tetap memberi respek terhadap sumber ajaran mereka. Beberapa ayat al-
Qur’an memerintahkan baik orang Yahudi maupun Nasrani untuk menerapkan ajaran
yang terdapat dalam kitab suci mereka. Dalam Taurat dan Injil terdapat hukum
Tuhan, cahaya dan petunjuk, dan karena itu hendaklah mereka konsisten berpegang
teguh padanya. Al-Qur’an mengkritik mereka karena telah mengabaikan hal
tersebut.73
72Q.S. al-An‘ām: 108.
73Lihat Q.S. al-Mā’idah: 43-47.
Seperti dikatakan Sayyid Muhammad Syeed,74 dalam sebuah diskusi di kantor
ISNA, hatred will produce much more hatred, kebencian akan menciptakan lebih
banyak kebencian. Kebencian tidak menyelesaikan masalah, tetapi menciptakan
lebih banyak masalah. Doktor Syeed termasuk salah seorang penggalang solidaritas
umat Islam Amerika Serikat dan penyeru Islam perdamaian. Menurut Syeed, umat
Islam harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang
mengajak kepada sikap terbuka dan toleran. Peristiwa 11 September 2001, yang
menghancurkan gedung WTC di kota New York, tidak ada kaitannya dengan Islam,
dan orang-orang Amerika harus mengerti hal tersebut. Ia, bersama sejumlah pakar
Islam di Amerika, berjuang untuk menjelaskan kepada dunia bahwa Islam bukan
agama yang menabur kebencian dan bahwa Islam termasuk agama yang sering kali
disalahpahami oleh umat non-Islam.
Syeed barangkali merupakan representasi dari “pengusung” model Islam
dalam tafsiran Muslim yang hidup di dunia Barat yang tentu saja sulit diterima oleh
kebanyakan kalangan tradisional yang berorientasi Timur. Orang-orang Muslim yang
hidup di Barat, apalagi dilahirkan dan dibesarkan di sana serta terdidik secara Barat,
berhadapan dengan realitas kehidupan yang, dalam beberapa hal, secara substansial
berbeda dari Timur. Banyaknya para imigran dari berbagai negara yang datang ke
Amerika Serikat, dengan membawa tradisi keagamaan dan budaya berbeda-beda,
menjadikan penduduk negara itu harus belajar menghadapi kenyataan pluralitas
kehidupan yang sangat beragam. Hal ini membawa dampak yang mendalam bagi
pemeluk dan pengkaji agama mana pun di sana. Tokoh-tokoh Muslim yang hidup
74Sayyid Muhammad Syeed adalah sekretaris umum ISNA (Islamic Society of North America), Indiana, Amerika Serikat.
dan memperjuangkan Islam di Barat seperti Fazlur Rahman, Hasan Turabi dan
Mahmoud Ayoub, tidak segan-segan memperlihatkan keakrabannya dengan, dan
apresiasinya kepada, pemeluk agama lain serta bersikap kritis meski terhadap tradisi
keagamaannya sendiri. Rahman tidak hanya mengkritik dengan tajam para
Orientalis, tetapi juga kebanyakan sarjana Muslim sendiri yang dinilai telah membuat
Islam meleset terlalu jauh dari semangat dasar al-Qur’an.75
Pada akhirnya disadari bahwa pengalaman hidup memberikan dampak
psikologis pada setiap individu yang mempengaruhi pandangan dan keyakinan
keagamaannya. Agama itu sendiri ternyata tidak terlepas dari sikap dan penghayatan
terhadap kehidupan yang dijalani seseorang. Jadi tafsiran atas agama adalah tafsiran
manusia dan pengalaman keagamaan yang dihayati seseorang serta konsepsinya
tentang agama adalah pencerapan kemanusian belaka. Tidak ada yang mutlak dan
sakral sehingga tabu untuk dikritisi. Kesadaran manusiawi seperti inilah mungkin
yang akan membuat seseorang selalu bersedia membuka dirinya kepada perubahan
dan proses pembenahan diri dalam memberi makna yang lebih sempurna bagi
kehidupan dan penghayatan keagamaan. Jadi kebencian kaum Muslim terhadap
Yahudi, walaupun tampak telah demikian mengakar, tidak berasal dari semangat
ajaran al-Qur’an, tetapi lebih disebabkan oleh provokasi politik dan didukung oleh
pemahaman yang tidak proporsional terhadap ayat-ayat al-Qur’an.
D. Bias dalam Tafsir
75Lihat Kate Zebiri, “Relation Between Muslims and Non-Muslims in the Thought of Western-Educated Muslim Intellectuals,” Islam and Christian-Muslim Relations, Vol. 6, No. 2, 1995, 255-271.
“Bias dalam tafsir,” maksudnya di sini adalah bias dalam memahami ayat-
ayat al-Qur’an. Tafsir adalah karya manusia, yang tidak terlepas dari subjektivitas
dan prakonsepsi yang selalu ia bawa bersamanya dalam setiap gerak pikir dan nalar
tentang apa pun. Adalah absurd, kata Bultmann, mengharapkan seorang interpreter
(pelaku interpretasi atau tafsir) untuk sama sekali menyingkirkan seluruh
subjektivitasnya, lalu memahami teks tanpa ada pemahaman awal dan pertanyaan-
pertanyaan yang ditimbulkan olehnya.76 Pencerapan, penafsiran dan kemudian
makna-makna yang dilahirkan, selalu bersifat parsial. “Tidak ada interpretasi yang
innocent,” kata Tracy, “tidak ada pembuat interpretasi yang innocent, tidak ada teks
yang innocent.”77 Setiap tafsir, bersamanya akan menyertai mazhab dan ideologi
mufassir. Di dalamnya ada gema yang memperlihatkan kecenderungan pembuat
tafsir. Namun ini bukan berarti tidak ada yang dapat diharapkan dari mufassir. Ini
justeru memperlihatkan kekayaan khazanah pemikiran umat manusia; menyadarkan
setiap orang yang mempelajarinya akan bahwa ia tidak sendirian di dunia ini dan
bahwa ia perlu saling belajar dengan orang lain. Tafsir adalah ekspresi yang akan
memperkenalkan seorang mufassir kepada orang lain, watak, karakteristik pemikiran
dan latar belakang kehidupannya. Ekspresi tersebut merupakan pembongkaran
berbagai ide dan gagasan dalam dirinya. Semua ini akan memperkaya dan
memperluas jaringan pengenalan manusia akan berbagai makna yang tersembunyi
dari teks. 76Rudolf Bultmann, Essays, Philosophical and Theological, (London: SCM Press,
1955), 251.
77David Tracy, Plurality and Ambiguity: Hermeneutics, Religion, Hope, (San Francisco: Harper and Row, 1987), 79.
Namun demikian, penafsir bukan tanpa daya untuk mencapai objektivitas.
Hanya saja objektivitas dalam memberi makna tidaklah sempurna. Sejauh sebuah
tafsiran dapat diverifikasi dan dibuktikan fakta-faktanya, maka ia dapat disebut
objektif. Maka dalam hal ini, sebagaimana telah dibicarakan, yang dituntut dari
seorang mufassir adalah ketulusan dan kerendahan hati, tanpa arogansi dan pretensi
bahwa ia telah mencapai kesempurnaan.
Objektivitas yang berangkat dari ketulusan inilah yang dituntut dalam
memahami teks al-Qur’an, bukan yang berpijak pada keyakinan absolut akan
kepastian kebenaran yang telah dibingkai sebelumnya. Seorang penafsir harus
membuka diri – inilah arti objektivitas dalam memahami makna dan nilai. Teks al-
Qur’an bukan matematika, sejarah, biologi maupun antropologi. Al-Qur’an berulang
kali menyebut dirinya sebagai petunjuk bagi manusia. Karena itu pengukuran
terhadap tafsir tidak mungkin eksak, tidak mungkin tanpa pertimbangan elastisitas
makna. Karena pemahaman manusia bukan hanya berbeda-beda, tetapi juga
bertingkat-tingkat, maka setiap langkah naik menuju kesempurnaan akan bertemu
dengan langkah selanjutnya, tanpa habis. Jadi tafsir tidak pernah final.
Gambaran di atas dimaksudkan untuk menegaskan lagi bahwa tafsir adalah
human institution. Betapa pun sebuah tafsiran dianggap keliru, ia tetap pantas
mendapat respek. Sebaliknya, sehebat apa pun sebuah tafsiran, tidak tertutup
kemungkinan untuk ditinjau kembali dan dikonstruksi ulang. Sekarang tafsir al-
Qur’an telah merupakan fakta dan realitas, telah ditulis dan menjadi bagian dari
warisan sejarah dan peradaban Islam. Kitab-kitab tafsir telah ditulis dalam berbagai
mazhab dan aliran, dan untuk berbagai kepentingan, baik ilmiah maupun
propaganda. Terkait dengan studi ini, lalu bagaimana menempatkan mereka semua?
Sebagian kaum Muslim telah menjadikannya sebagai pegangan dalam memahami
dan mengamalkan ajaran al-Qur’an, sementara sebagian yang lain menjadikannya
sebagai objek kajian atau mempelajarinya dengan kritis.
Prakonsepsi bahwa Yahudi adalah bangsa terkutuk, sebagaimana telah
dibicarakan di atas, membuat para sarjana Muslim pengkaji al-Qur’an seolah tidak
mungkin membangun sebuah konstruksi pemikiran yang positif dalam memahami
ayat-ayat tentang Yahudi. Agama Yahudi diyakini sebagai agama yang telah
mansūkh dan spirit bangsa Yahudi dianggap spirit yang telah terkontaminasi dengan
berbagai dosa yang mereka lakukan. Mereka disebut sebagai pembunuh para Nabi,
pembangkang terhadap Tuhan dan senantiasa melanggar kitab yang telah diturunkan.
Bagaimana mungkin mereka dapat diselamatkan dari kekejian moral yang telah
mengkristal dalam watak mereka sejak lebih seribu tahun yang lalu. Dalam anggapan
kebanyakan Muslim, mereka memang harus diperangi dan pantas mendapatkan
berbagai perlakuan buruk dari bangsa-bangsa di dunia, seperti yang dilakukan Nazi
Jerman tahun 1938 yang terkenal dengan peristiwa the Holocaust.78 Semua ini
tampak dengan jelas sebagai bias kebencian dalam memahami al-Qur’an.
Pandangan seperti di atas, sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya, bukan
hanya beredar di kalangan awam. Kaum terpelajar pun ikut mengukuhkan dan
menyebarkan paham mengerikan itu. Lebih-lebih lagi, perseteruan politik “Arab-
78Peristiwa ini dianggap yang paling fenomenal dalam sejarah kesengsaraan bangsa Yahudi. Ia telah memberikan perubahan yang besar dalam struktur pemikiran dan ideologi masyarakat Yahudi. … until the Holocaust every massacre, expulsion, pogrom, or atrocity was interpreted at least partially as divine punishment for sin. The solution, then, consisted of more observance, not less. Lihat Samuel G. Freedman, Jew v.s. Jew: The Struggle for the Soul of American Jewry, (New York: Touchstone, 2000), 277.
Israel” di Timur Tengah telah menjadikan suasana semakin sulit mencari posisi pijak
intelektual yang aman dari kecenderungan emosional dan keberpihakan. Lalu apakah
mungkin sebuah tafsir kontemporer tentang ayat-ayat Yahudi lahir tanpa bias?
Komitmen keilmuan seorang terpelajar seharusnya memungkinkan hal itu terjadi,
meski dalam batasan-batasan yang masih bersifat relatif. Tafsir-tafsir klasik telah
ditulis dalam suasana politik dan intelektual relatif terkendali, namun tetap dalam
bingkai self-image kaum Muslim. Polemik Yahudi-Muslim sering terjadi di abad
tengah, namun mereka mendiskusikan topik-topik keagamaan secara mendalam dan
relatif sehat, walaupun masing-masing berupaya dengan gencar membela kebenaran
agamanya dan menunjukkan sisi-sisi kelemahan pihak lawan. Al-T{abarī (w. 310
H./923 M.), Ibn H{azm (w. 456 H./1064 M.), al-Syahrastānī (w. 548 H./1153 M.)
dan al-Samaw’al (Muslim asal Yahudi, w. 1175 M.)79 adalah di antara nama-nama
yang telah menjadi rujukan standar setiap Muslim yang ingin berpolemik dengan
orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menyerang keyakinan Yahudi dan Nasrani
dengan argumentasi-argumentasi ilmiah dan diskusi yang mendalam. Sementara
kebanyakan penulis Muslim kontemporer, sebagaimana telah didiskusikan di atas,
sering lebih cenderung mengutip ayat-ayat tentang Yahudi untuk dipahami sebagai
penghinaan dan cercaan terhadap mereka.
79Mengenai diskusi tentang karya-karya Muslim mengenai Yahudi, lihat Camilla Adang, Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible from Ibn Rabban to Ibn Hazm, (Leiden: E. J. Brill, 1996).
BAB IVPRESENTASI AL-QUR’AN TENTANG YAHUDI:
TEKS DAN KONTEKS
TUJUAN paling utama bab ini adalah memberikan sebuah gambaran umum yang
menyeluruh tentang apa dan bagaimana Yahudi dalam persepsi al-Qur’an, dengan
menganalisa sejumlah ayat yang dianggap representatif mengenai topik-topik yang
relevan. Ayat-ayat yang didiskusikan di sini mencakup sejarah kemunculan
kehidupan orang-orang Israel (Bani Israil), perjuangan, sikap dan perilaku mereka
dalam berinteraksi dengan para Nabi atau pemimpin keagamaan, sampai kepada
“sepak terjang” mereka berhadapan dengan Nabi Muhammad serta berbagai kritik
yang diarahkan al-Qur’an kepada mereka.
Seperti telah dibicarakan sebelumnya, al-Qur’an bukan buku sejarah yang
bertujuan memuat fakta-fakta kehidupan masa lalu, tetapi kitab petunjuk (hudā) yang
bertujuan untuk membimbing manusia kepada kesadaran spiritual dan cara hidup
yang benar. Apa yang dikisahkan al-Qur’an tentang umat-umat terdahulu adalah
untuk dijadikan peringatan bagi manusia yang hidup hari ini. Karena itu kisah-kisah
dalam al-Qur’an bertebaran di mana-mana dalam berbagai surat, sesuai dengan poin
pembicaraan yang ingin diketengahkan atau ditegaskan. Kisah-kisah tentang umat
Yahudi di masa lalu dan respon-respon langsung al-Qur’an terhadap orang-orang
Yahudi yang dihadapinya di Medinah kadang-kadang terdapat secara bersamaan atau
beriringan dalam bagian-bagian atau surat tertentu. Ini tidak mengherankan karena
yang ingin diungkapkan al-Qur’an adalah realitas kehidupan manusia yang abstrak,
prevalent dan permanen, bukan realitas sejarah yang dipilah-pilah oleh waktu dan
tempat.
Demikian juga kritik-kritik al-Qur’an terhadap umat Yahudi, semuanya
bersifat universal, humanis dan memiliki semangat edukasi yang tinggi dan luas;
bahkan jika ayat-ayat itu dibaca dengan cermat dan reflektif, akan terasa bahwa yang
dikritik al-Qur’an adalah perilaku keseharian manusia. Argumentasi yang akan
dibangun dari analisis di bawah ini adalah bahwa al-Qur’an, ketika berbicara tentang
umat Yahudi, ia sedang mengekspresikan tujuan dan harapannya dari umat yang
sedang dihadapinya itu. Al-Qur’an mengajak mereka bergabung dalam sebuah
komunitas baru dan mengoreksi berbagai pandangan mereka yang dianggap keliru.
Al-Qur’an berbicara “apa adanya” dan merujuk pada pandangan-pandangan umum
yang telah dikenal luas. Namun al-Qur’an juga bersikap keras dan tegas ketika
ternyata kebenaran itu dianggap remeh dan direndahkan. Berikut adalah topik-topik
yang didiskusikan dengan ayat-ayat yang relevan.
A. Narasi Kehidupan Bangsa Yahudi
Secara keseluruhan al-Qur’an memberikan gambaran tentang bangsa Yahudi
sebagai sebuah potret perjalanan sejarah suatu umat beragama yang unik. Tidak jauh
berbeda dari narasi Bible, kisah al-Qur’an tentang Yahudi memperlihatkan
penyelamatan Tuhan kepada sebuah umat yang dipilih-Nya, karena kepercayaan
mereka kepada-Nya. Kepada mereka diutus para Nabi yang terus menerus
memberikan peringatan serta membimbing mereka kepada keselamatan moral dan
menuju kehidupan yang sejalan dengan tuntunan Tuhan. Namun sikap mereka yang
kasar, primitif dan tidak jarang membuat para utusan Tuhan kesal serta terpaksa
mengadu pada Yang Maha Kuasa, telah menyebabkan turunnya bencana-bencana
sebagai hukuman atas kedurhakaan mereka. Di sisi lain, keluarga-keluarga yang
saleh di antara mereka juga disebutkan al-Qur’an, meskipun jumlah mereka terkesan
amat sedikit.
Secara hermeneutik, kisah bangsa Yahudi dalam al-Qur’an dapat dilihat
sebagai potret kehidupan yang mengandung pesan moral dan spiritual yang
mendalam. Pertarungan antara yang benar dan salah, keadilan dan kezaliman, yang
tertindas dan yang menindas, komitmen moral dan kedurhakaan, terlihat sangat jelas.
Sejak Yusuf anak Yakub dimusuhi oleh saudara-saudaranya karena kedengkian,
pertarungan Firaun dan Musa, sampai pada kelahiran Isa Almasih, kisah-kisah itu
memperlihatkan ekspresi pertarungan tersebut yang tidak henti-hentinya dan menjadi
filter untuk menyeleksi mereka yang setia kepada iman dari mereka yang durhaka.
Kebaikan, kejujuran, ketulusan hati, komitmen moral dan keadilan pada akhirnya
adalah yang menang, meskipun harus melalui ujian-ujian yang berat.
1. Dari Keturunan Khalīl Allāh
Kisah Bani Israil, jika dirujuk pada konsep dasar dan tujuannya, dimulai dari
Ibrahim (Hebrew Avraham [אברהם], Inggris Abraham) ketika ia meninggalkan ‘Ur
di Babilonia untuk mengembara mencari kebenaran dan kedamaian. Namun al-
Qur’an tidak mengulas masalah ini secara panjang lebar sebagaimana dalam
Perjanjian Lama. Nabi Ibrahim disebutkan dalam al-Qur’an sebagai “Bapak” orang-
orang Yahudi dan juga Muslim, sumber utama yang menginspirasikan agama yang
berpusat di Yerusalem dan negeri Hijaz. Dalam perspektif kitab suci Muslim,
Ibrahim adalah seorang yang tulus dan setia pada ajaran Tauhid yang lurus,1 seorang
nabi dan hamba pilihan.2 Ibrahim pernah berpikir tentang Tuhan melalui jalan
refleksi terhadap alam semesta.3 Ibrahim juga pernah mempertanyakan persoalan
kebangkitan kepada Tuhan,4 berdebat dengan kaumnya hingga membuat mereka
marah dan berusaha membakarnya. Tuhan menyelamatkan Ibrahim dari angkara
murka tersebut.5 Kebencian kaumnya itulah yang membuat Ibrahim terpaksa
meninggalkan negerinya. Inilah awal dari pengembaraan sang Patriark, yang dalam
versi Bible sampai ke Kanaan, Palestina sekarang; menurut al-Qur’an sampai ke
Hijaz dan di sana ia membangun Ka‘bah, rumah Tuhan, bersama anaknya Ismail.
Dalam al-Qur’an, sejarah Yahudi atau Bani Israil dalam bentuk agak lebih
rinci, dimulai dari Nabi Yakub dan anak-anaknya yang kemudian dari Kanaan
bermigrasi ke Mesir. Ini dikisahkan secara “lengkap” dalam satu surat al-Qur’an –
surat Yusuf. Yusuf (anak Yakub anak Ishak anak Ibrahim) meninggalkan negeri
asalnya karena diusir oleh saudara-saudaranya. Mereka membuangnya dengan
melemparnya ke dalam sebuah sumur di pinggir perlintasan para musafir. Sebuah
kafilah menemukan Yusuf, membawanya ke Mesir dan kemudian menjualnya
1Q.S. al-Nah}l: 120
2Q.S. Āli ‘Imrān: 33; Maryam: 41.
3Q.S. al-An‘ām: 75-79.
4Q.S. al-Baqarah: 260.
5Q.S. al-Baqarah: 258; al-Anbiyā’: 52-69.
kepada seorang pembesar negeri itu. Yusuf mengalami liku-liku kehidupan yang
panjang di Mesir sampai ia benar-benar dewasa secara fisik, mental dan spiritual.
Yusuf harus menghadapi sebuah intrik dari seorang perempuan yang tidak lain
adalah istri majikannya, dan seterusnya ia juga harus mendekam sekian lama dalam
penjara. Ketabahan terhadap semua rintangan itulah yang membuat Yusuf semakin
kuat dan dewasa, sehingga kebijaksanaan benar-benar tertancap dalam jiwanya dan
tercermin dalam seluruh sikap hidup, ilmu dan budi bahasanya. Yusuf memiliki
sebuah kelebihan yang unik, yaitu mampu memberikan ta‘bir mimpi. Dari sinilah
karir Yusuf dimulai, yakni ketika sang Raja bermimpi tentang sebuah peristiwa aneh
yang tidak ada seorang ahli nujum pun mampu menjelaskan maksudnya. Yusuf
menawarkan jasanya dan diterima sang Raja. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi
seorang petinggi negeri yang bertugas mengurus kekayaan negara.6
Peristiwa yang diramalkan Yusuf (yakni kemarau panjang) benar-benar
terjadi. Musim paceklik datang dan rakyat Mesir telah siap menghadapinya.
Penduduk negeri sekitar, termasuk Kanaan berdatangan ke Mesir untuk mencari
bantuan pangan. Di situlah, demikian al-Qur’an mengisahkan, Yusuf bertamu
saudara-saudaranya kembali dalam suasana yang berbeda. Saudara-saudara Yusuf
bertobat dan mengakui kesalahan mereka yang iri hati kepada Yusuf. Mereka
bersama orangtuanya, Yakub, kemudian berpindah dan akhirnya menetap di Mesir.
Dari sinilah berawal kehidupan Bani Israil di Mesir hingga zaman perbudakan oleh
6Dalam al-Qur’an (Yusuf: 43-49) dikisahkan bahwa Raja bermimpi melihat tujuh ekor lembu kurus memakan tujuh ekor lembu gemuk, dan tujuh kayu kering (melilit tujuh kayu segar). Yusuf menta‘birkan mimpi itu sebagai pertanda akan terjadinya tujuh tahun masa kekeringan, dan karena itu masyarakat harus mempersiapkan diri menghadapinya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia menikmati hujan dan kesuburan sehingga mereka dapat bercocok tanam dan memeras anggur seperti sedia kala.
Firaun yang berakhir dengan kedatangan Nabi Musa sebagai penyelamat yang
membimbing mereka menuju tanah yang dijanjikan.
Narasi al-Qur’an memperlihatkan kepedulian moral yang tinggi. Keluarga
Ibrahim dijadikan Tuhan sebagai orang-orang pilihan karena komitmen mereka
kepada kesalehan dan ajaran agama yang lurus. Al-Qur’an tidak menyebutkan agama
formal yang dianut Ibrahim dan keluarganya (anak keturunannya, seperti Ishak,
Yakub, Yusuf dan lain-lain), namun al-Qur’an berulang kali mengatakan bahwa
mereka adalah orang-orang yang muslim, menyerah diri kepada Tuhan. Ketika
Ibrahim dinyatakan Tuhan sebagai hamba-Nya yang terpilih, ia pernah berharap agar
anak keturunannya (secara otomatis) juga menjadi orang-orang pilihan. Lalu Tuhan
menegaskan bahwa janji-Nya tidak akan mencapai orang zalim.
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.” Ibrahim berkata: “(Dan aku mohon juga) dari keturunanku.” Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim.”7
Al-Qur’an sangat tegas mengilustrasikan Ibrahim sebagai sosok yang tulus
dan penyantun, dan keterpilihannya sebagai khalīl Allāh dan imam orang-orang
bertakwa adalah semata-mata karena hatinya yang suci dan perilakunya yang santun.
Al-Qur’an dalam hal ini dapat dipahami sebagai ingin menegaskan bahwa tidak ada
yang spesial dari perlakuan Tuhan terhadap Ibrahim. Tuhan tidak bersikap
diskriminatif terhadap hamba-Nya. Peringkat tinggi yang dicapai Ibrahim adalah
karena kemenangan spiritualitasnya atas segala godaan dan tantangan; Ibrahim dapat
melewati semua ujian Tuhan.
7Q.S. al-Baqarah: 124.
Rujukan-rujukan al-Qur’an kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub tentu ada
kaitannya dengan klaim-klaim orang Yahudi dan Nasrani sebagai kelompok yang
mewarisi ajaran sang Patriark. Lebih-lebih lagi, kelompok Yahudi mengatakan
mereka menjadi umat pilihan hanya karena mereka adalah keturunan Ibrahim.
Menurut al-Qur’an, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa hanya
dengan mengikuti agama mereka manusia akan terpetunjuk.
Dan mereka berkata: “Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani niscaya kamu mendapat petunjuk.” Katakanlah: “Tidak, bahkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Ia bukanlah dari golongan orang musyrik.” 8
Al-Qur’an membantah klaim tersebut dan merekonstruksi kisah Ibrahim dan
Israel dalam format yang lebih universal dan humanis. Sebagaimana terlihat dalam
ayat di atas dan berbagai ayat al-Qur’an lainnya, pengungkapan kisah Bani Israil,
termasuk akar moyang mereka, tidak terlepas dari upaya al-Qur’an memenangkan
polemik dengan kelompok Yahudi dan Nasrani di Medinah.
Keberadaan kisah-kisah al-Qur’an dalam bentuk yang berserakan dalam
berbagai surat juga menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan dalam konteks
tertentu yang terkait dengan peristiwa-peristiwa, terutama sekali interaksi Nabi
dengan kelompok Yahudi dan Nasrani. Berbeda dari narasi dalam kitab Bible, kisah
yang diungkapkan al-Qur’an tidak menunjukkan minat kitab suci ini kepada
kronologi sejarah. Karena itu para ulama mengatakan bahwa kisah-kisah al-Qur’an
tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan data-data sejarah, tetapi sebagai satu
bentuk penyampaian pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Kisah-kisah tersebut harus
dipahami sebagai refleksi dari tingkah laku manusia dalam kehidupan, tidak terbatas
8Q.S. al-Baqarah: 135.
pada wilayah geografis dan zaman tertentu. Lebih jauh, menurut Muhammad Iqbal,
sebagian dari kisah-kisah al-Qur’an, seperti tentang Adam, hanya fiksi belaka;
artinya bukan fakta yang benar-benar ada dalam sejarah.9 Ibrahim disebutkan dalam
dua puluh dua surat al-Qur’an dengan porsi yang berbeda. Dalam surat al-Baqarah ia
disebutkan agak lebih banyak.10 Di sini Ibrahim dipotret sebagai pribadi yang tulus
mengabdi pada Tuhan dan disebut sebagai muslim. Anak cucunya yang saleh juga
digambarkan sebagai pengikut jejak Ibrahim. Mereka adalah orang-orang yang hanya
menyerah diri dengan pasrah pada Tuhan.
Adakah kamu hadir ketika kepada Yakub datang (tanda-tanda) maut, pada saat ia berkata kepada anak-anaknya: “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” Mereka menjawab: “Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa; kami menyerah diri (tunduk dan patuh) kepada-Nya.”11
Al-Qur’an berkali-kali menyebutkan bahwa Ibrahim, Ishak dan Yakub adalah
orang muslim. Al-Qur’an mengawali berbagai statemennya tentang Ibrahim di sini
dengan sebuah prelude dalam bentuk seruan kepada Bani Israil agar menyadari
betapa besar nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada mereka, dan dengan
demikian tidak seharusnya mereka membangkang ajaran Tuhan, terlebih lagi
memusuhi Muhammad dan ajaran yang dibawanya, sebab apa yang disampaikan
Muhammad adalah kelanjutan dari ajaran yang telah disampaikan oleh para nabi dari
nenek moyang Bani Israil juga. Al-Qur’an menegaskan bahwa tidak ada perbedaan
di antara rasul Tuhan. Semua mereka membawa ajaran yang sama: mengesakan
9?Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), 83.
10Lihat Q.S. al-Baqarah: 124-140 dan 258-260.
11Q.S. al-Baqarah: 133.
Tuhan dan mengingatkan manusia akan tanggung jawab moral mereka di dunia
sebab tanggung jawab tersebut akan diperhitungkan di akhirat kelak. Karena itu,
seperti dikatakan Fazlur Rahman, al-Qur’an dengan jelas memberikan otonomi yang
luas kepada orang-orang Yahudi untuk mengamalkan ajaran agamanya, meskipun
tidak henti-hentinya mengajak mereka kepada Islam.12
Yusuf, yang kenabiannya diperdebatkan oleh para sarjana Muslim,13 juga
termasuk tokoh kunci dalam kisah kemunculan Bani Israil sebagai sebuah komunitas
keagamaan yang khas. Seperti telah disebutkan, Yusuflah yang mengawali peristiwa
kehadiran Bani Israil di Mesir. Penyebutan Yusuf dalam al-Qur’an sangat penting,
bukan hanya sebagai contoh sosok pribadi dengan spiritualitas yang mendalam,
tetapi juga dalam rangka memperlihatkan kepada pembaca bagaimana kedengkian,
yang berasal dari mentalitas yang rendah, telah menyeret manusia kepada kehinaan.
Hanya orang-orang yang memiliki kejujuran dalam dirinya dan setia mengikuti
petunjuk agama yang benar pada akhirnya yang akan selamat dan menang. Yusuf
dalam berbagai kesempatan dirujuk oleh al-Qur’an sebagai orang yang berpegang
teguh pada prinsip-prinsip moral dan mengikuti agama Ibrahim. Ketika Yusuf berada
dalam penjara, pada saat dua orang temannya bertanya kepadanya tentang tafsir
mimpi mereka, sebelum menjawab dan menjelaskan makna mimpi itu, Yusuf
terlebih dahulu menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada temannya itu. Yusuf
bangga menyatakan dirinya meninggalkan agama yang batil – agama yang tidak
12Fazlur Rahman, “Islam’s Attitude Toward Judaism,” The Muslim World, Vol LXXII, No. 1, January 1982, 5.
13Lihat Mazheruddin Siddiqi, The Qur’ānic Concept of History, (Delhi: Adam Publishers, 1994), 98.
percaya pada Tuhan dan hari akhirat. Ia mengikuti agama Ibrahim, Ishak dan Yakub
– agama yang lurus, agama yang merupakan karunia Tuhan kepada manusia.
Yusuf berkata: “Tidak sampai kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku telah mengungkapkan takwilnya, sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian.
Dan aku mengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia; tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur.
Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?
Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.14
Yusuf disebutkan al-Qur’an sebagai orang yang mendapatkan hikmah dan
ilmu dari Tuhan. Ini tidak lain karena kebaikan Yusuf sendiri.
Dan manakala dia telah cukup dewasa, Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.15
Penekanan al-Qur’an pada aspek moral dan agama tawh}īd (mengesakan
Tuhan) terlihat dalam segala kesempatan al-Qur’an berbicara tentang Bani Israil. Ini
adalah isyarat yang sangat jelas betapa al-Qur’an selalu berusaha memposisikan
dirinya di antara agama Yahudi dan Nasrani sebagai pemilik warisan agama Ibrahim
yang lurus, tanpa korup dan penyimpangan. Al-Qur’an merespon orang-orang
14Q.S. Yūsuf: 37-40.
15Q.S. Yūsuf: 22.
Yahudi dan Nasrani dengan merujuk pada pandangan dan tradisi mereka sendiri.
Namun al-Qur’an dengan sengaja memperlihatkan sisi-sisi moral dan ajaran agama
yang lurus, yang selama ini dianggap telah diabaikan mereka. Orang-orang Bani
Israil atau orang-orang Yahudi memang berasal dari keturunan orang-orang saleh
dan mulia, dan ajaran yang mereka anut pada dasarnya adalah ajaran Tuhan yang
lurus. Namun, asal keturunan tidak cukup untuk meraih kemuliaan di sisi Tuhan
tanpa kebaikan dan ketulusan hati. Demikian juga ajaran Tuhan, tidak cukup dengan
hanya diamalkan sesuai selera nafsu saja, tanpa keteguhan dalam berprinsip bahwa
jalan Tuhan adalah jalan keselamatan yang harus ditempuh dengan sejujur-jujurnya.
2. Perbudakan di Mesir
Al-Qur’an tidak memberikan gambaran yang rinci mengenai proses
perubahan status Bani Israil di Mesir menjadi para budak dan bahkan diperlakukan
dengan kejam. Dalam beberapa ayat, al-Qur’an mengingatkan Bani Israil agar
melakukan refleksi, bagaimana ketika Firaun dan para pengikutnya menzalimi
mereka, membunuh anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan yang
perempuannya hidup, dan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan mereka dari
kesengsaraan tersebut.
Dan (ingatlah) ketika Kami selamatkan kamu dari (Firaun) dan pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu siksaan yang amat keji: mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.16
16Q.S. al-Baqarah: 49.
Perbudakan tidak hanya telah menghancurkan tradisi dan peradaban Bani
Israil tetapi juga telah merusak mentalitas mereka. Orang-orang Israel telah
kehilangan jati dirinya. Keturunan Yakub adalah orang asing di Mesir. Meskipun
pada awalnya mereka mendapat tempat yang terhormat dalam kerajaan, pada
akhirnya orang-orang Mesir mungkin menyadari bahwa orang-orang “pribumi”lah
yang lebih berhak berkuasa dan mendapat kedudukan terhormat dibanding orang-
orang “asing,” dan bahwa orang-orang asing tidak pantas menggeser kedudukan
orang-orang pribumi. Ini adalah model ketakutan yang selalu menghantui umat
manusia dalam sejarah kedaulatan suku bangsa – suku bangsa manapun di dunia ini,
sampai hari ini. Bible mengisahkan bagaimana ketakutan orang-orang Mesir melihat
orang-orang Bani Israil semakin banyak mendiami wilayah bumi mereka:
(7) And the children of Israel were fruitful, and increased abundantly, and multiplied, and waxed exceeding mighty; and the land was filled with them. (8) Now there rose a new king over Egypt, who knew not Joseph. (9) And he said unto his people: ‘Behold, the people of the children of Israel are too many and too mighty for us; (10) come, let us deal wisely with them, lest they multiply, and it come to pass, that, when there befalleth us any war, they also join themselves unto our enemies, and fight against us, and get them up out of the land’. (11) Therefore they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens. And they built for Pharaoh store-cities, Pithom and Raamses. (12) But the more they afflicted them, the more they multiplied and the more they spread abroad. And they were adread because of the children of Israel. (13) And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigour. (14) And they made their lives bitter with hard service, in mortar and in brick, and in all manner of service in the field; in all their service, wherein they made them serve with rigour.17
Al-Qur’an hanya mengungkap pelajaran yang perlu dipetik dari peristiwa
tersebut. Ketika al-Qur’an berbicara tentang kisah Bani Israil, sasaran utamanya
adalah orang-orang Israel itu sendiri yang ada di Medinah dan sekitarnya pada waktu
17Exodus 1: 7-14.
itu, meski pelajaran yang dikandungnya bersifat universal. Karena itu al-Qur’an tidak
merasa perlu mengungkapkan kembali detail peristiwa tersebut, di mana orang-orang
Israel telah memiliki pengetahuan tentangnya. Jadi sasaran pembicara diasumsikan
telah mengetahui persoalan. Tugas al-Qur’an hanya mengingatkan dan menggiring
sasarannya kepada sebuah pemahaman yang reflektif terhadap sejarah.
Tuhan yang diungkapkan al-Qur’an dalam kisah ini, dan juga dalam ayat-ayat
lain,18 adalah Tuhan yang selalu berpihak pada kaum lemah. Dalam ayat di bawah ini
lagi-lagi al-Qur’an menunjukkan bagaimana Tuhan begitu care terhadap Bani Israil.
Namun perlu diberikan catatan, bahwa kepedulian Tuhan kepada Bani Israil bukan
semata-mata karena mereka lemah. Tuhan menyayangi dan memberikan pertolongan
kepada mereka karena mereka sabar.
Dan Kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah Kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun.19
Demikian juga sebaliknya, Tuhan menghancurkan Firaun dan para
pengikutnya karena mereka zalim dan sombong, bukan semata-mata karena mereka
musuh Bani Israil.
… Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka Kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya dan Kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya; semua mereka adalah orang zalim.20
18Lihat misalnya Q.S. al-Anfāl: 26 tentang bantuan Tuhan kepada orang-orang Muslim Mekkah.
19Q.S. al-A‘rāf: 137.
20Q.S. al-Anfāl: 54.
Perbudakan terhadap Bani Israil di Mesir tidak hanya dilihat oleh al-Qur’an
sebagai sebuah hukuman dalam pengertian negatif, tetapi juga mengandung nilai
positif, yakni sebagai ujian. Paling tidak, ayat 137 surat al-A‘rāf sebagaimana dikutip
di atas memandang positif sikap Bani Israil yang sabar menghadapi cobaan, dan
karena itu Tuhan membalasnya dengan memberikan bantuan dan kemenangan bagi
mereka terhadap musuhnya.
Musa adalah figur yang mendominasi seluruh drama penyelamatan Bani
Israil dari perbudakan di Mesir. Ia lahir di tengah-tengah ancaman pembunuhan
terhadap bayi-bayi yang dilahirkan etnis Israel. Menurut al-Qur’an, Tuhan telah
menyelamatkan seorang bayi yang kelak dikenal dengan nama Musa dan menjadi
pemimpin Bani Israil, melalui inspirasi yang disampaikan kepada Ibu sang bayi.21
Kisah Musa dikenal dalam ketiga agama besar dunia: Yahudi, Kristen dan
Islam. Bagi kaum Yahudi kisah tersebut adalah gambaran tentang sebuah
kemenangan besar, sebuah kelepasan dari penderitaan, sebuah penyelamatan yang
agung. Tuhan telah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dengan karunia-Nya yang
hebat dan membimbing mereka ke sebuah tanah yang makmur.22 Dalam Perjanjian
Lama, kisah Musa dimulai dari kitab Exodus sampai kitab Deutoronomy. Kisah
tersebut secara detil menceritakan liku-liku perjalanan Bani Israil mulai dari
kehadiran mereka di Mesir, perbudakan oleh penguasa Mesir (Firaun), kelepasan dari
Mesir, sampai Musa wafat.
21Q.S. al-Qas}as}: 7.
22Leviticus, 26: 9-10.
Pada awalnya Musa adalah seorang keturunan Israel yang dibesarkan dalam
istana kerajaan Mesir. Ia dididik untuk menjadi pendeta ajaran Akhenaton. Dalam
tradisi kaum Rabbani disebutkan bahwa setelah Musa menjadi seorang pemuda
dewasa, ia berjalan-jalan ke luar istana dan berbincang-bincang bersama kaum Bani
Israil yang hidup sebagai buruh dan budak penguasa Mesir. Di sinilah ia mulai
belajar mengenai legenda agama nenek moyangnya, dan tentang Ibrahim sebagai
pembawa agama monoteis. Musa juga mulai mendengar tentang Kanaan yang subur
dan makmur, sebuah wilayah yang kaya dengan susu dan madu. Maka pada suatu
hari, setelah terjadi sebuah insiden di mana Musa membela seorang bangsa Israel dan
membunuh seorang Kubti Mesir hingga tewas, ia lari ke Madyan dan hidup di sana
sebagai penggembala. Pada saat Musa pulang dari Madyan itulah Tuhan
memanggilnya dan mengangkatnya sebagai seorang rasul untuk membimbing Bani
Israil dan melepaskan mereka dari perbudakan Firaun.23
Inti dari narasi kisah Musa dalam tradisi Yahudi mirip dengan narasi yang
terdapat dalam al-Qur’an, walaupun semangat, tekanan dan pesannya mungkin
berbeda. Musa, dalam pandangan Yahudi, adalah sebuah figur sejarah yang unik dan
agung, seorang pemimpin yang memperkenalkan kembali agama yang hanya tunduk
kepada Yahweh semata dan membawa Hukum untuk mengadili manusia. Pengikut
Musa secara umum adalah kaum tidak beradab dan menjalani hidup yang kasar.
Karena itu Musa memerlukan ketegasan dan aturan (yakni Hukum) yang simpel.24
23Moinuddin Ahmed, Religions of All Mankind, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1994), 107.
24Ibid., 104.
Bagi orang-orang Kristen, Musa adalah pembuka jalan bagi kehadiran Yesus.
Dalam Injil secara general Yesus digambarkan sebagai Musa kedua yang juga hadir
untuk menyelamatkan kaumnya. Namun dalam membandingkan kedua tokoh ini
mereka kadang-kadang lebih cenderung menempatkan Yesus pada posisi lebih
superior. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus
Christ.25 Lebih jelas lagi dalam Surat kepada orang Ibrani, setelah disebutkan
tentang Musa dan Tauratnya dikatakan bahwa Yesus telah menemukan kedudukan
yang lebih utama. But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much
also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better
promises.26 Konsep Kristus sebagai anak Tuhan dalam tradisi Kristen tentu saja
menyebabkan mereka melihat Musa lebih rendah dari Yesus, meskipun mengakuinya
sebagai seorang tokoh yang hebat dalam sejarah.
Di sisi lain keteladanan Musa dapat dilihat dari segi kepemimpinan. Seorang
penulis Kristen mengatakan bahwa Musa telah mengorbankan hidupnya untuk
umatnya dan membimbing mereka menuju keselamatan. Ketika Tuhan menyerahkan
tugas ini kepadanya, ia merasa dirinya tidak berarti dan sangat kecil, lalu berkata:
“Siapa gerangan hamba-Mu ini sehingga hamba akan menghadapi Firaun dan
membawa Bani Israil keluar dari negeri Mesir?” Namun Tuhan menjawab: “Aku
akan bersamamu!”27 Seorang pemimpin besar atau yang ingin berhasil, demikian
25John 1: 17.
26Hebrew 8: 1-6.
27Exodus 3: 11-12.
menurut sang penulis, memang harus berangkat dari rasa bersalah dan kekecilan diri,
serta menghadirkan Tuhan dalam segenap tindakannya.28
Ringkasnya, dalam tradisi Yahudi dan Kristen kisah Musa tetap menjadi
dorongan bagi pengembangan kehidupan ke arah yang lebih baik bagi individu dan
masyarakat. Kisah Musa adalah kisah tentang kekuasaan Tuhan dan bimbingan-Nya
yang tiada henti kepada segenap hamban-Nya.
Kisah Nabi Musa berserakan di berbagai surat dalam al-Qur’an. Namanya
disebutkan sebanyak 129 kali dalam 32 surat dengan porsi yang berbeda-beda.
Dalam beberapa surat, kisahnya disebutkan secara agak panjang. Surat-surat tersebut
yaitu: al-Baqarah: 51-61, al-A‘rāf: 103-126, Yūnus: 75-92, T{āhā: 9-36, al-Syu‘arā’:
10-65, dan al-Qas}as}: 3-34.
Kisah Nabi Musa, sebagaimana juga kisah beberapa nabi yang lain,
disebutkan secara berulang-ulang dalam al-Qur’an. Bagian-bagian yang telah
disebutkan dalam suatu surat sering kali diulang kembali dalam surat/surat-surat
yang lain. Ini disebabkan al-Qur’an memiliki pesan-pesan tertentu yang ingin
disampaikan. Sering kali kisah atau ungkapan yang sama memiliki tekanan dan
pesan yang berbeda. Peristiwa berhadapannya Musa dengan Firaun dan tukang sihir,
misalnya, disebutkan dalam beberapa surat bahkan dengan ungkapan yang sama.
Demikian juga urutan kisah-kisah, sering kali tidak diatur menurut kronologisnya.
Dalam surat al-Syu‘arā’, sebagai contoh, setelah disebutkan kisah Musa, dilanjutkan
dengan kisah Ibrahim dan setelah itu kisah Nuh}, Hūd dan seterusnya. Hal ini,
menurut Qut}b, dikarenakan yang menjadi tujuan utamanya adalah penyampaian
28James Fitz, S.M., “Moses As A Leadership Model” Human Development, Vol. 4 Winter 1983, 34.
pelajaran tertentu yang sama sekali terlepas kaitannya dengan kronologis sejarah.
Berbeda halnya dengan kisah-kisah yang disebutkan dalam surat al-A‘rāf, di mana
rentetan sejarahnya dijadikan perhatian karena pesan yang akan disampaikan
berkenaan dengan pewarisan bumi ini bagi orang-orang yang beriman dan kepada
rasul sejak Adam dan seterusnya.29
Kisah Nabi Musa dalam al-Qur’an, mirip sebagaimana diutarakan dalam
Bible, dimulai dari inspirasi yang diilhami oleh Tuhan ke dalam hati ibunda Musa.
Ibunya kemudian menghanyutkannya ke dalam sungai Nil, diketemukan oleh Firaun
dan diadopsikan sebagai anaknya. Ketika Musa telah dewasa terjadilah sebuah
insiden. Musa membunuh seorang Mesir dan kemudian melarikan diri. Musa lalu
sampai ke Madyan dan kawin dengan salah seorang putri Nabi Syu‘ayb dan hidup
sebagai seorang penggembala domba. Karena kerinduan, maka Musa pulang ke
Mesir. Di tengah jalan, Musa melihat api dan mencarinya. Musa berjumpa dengan
Tuhan dan menerima perintah untuk menghadapi Firaun dan membebaskan Bani
Israil. Musa menentang Firaun dan tukang sihir, dan akhirnya dapat menyelamatkan
kaumnya keluar dari negeri Mesir. Firaun mengejarnya, namun ia dan para
pengikutnya tenggelam dalam laut. Musa, pada episode terakhir kisahnya, ternyata
juga harus menghadapi kaumnya yang “cengeng” dan keras kepala. Semua
komponen ini, seperti telah disebutkan, terdapat dalam berbagai surat dengan
tekanan yang berbeda-beda.
Figur sentral dalam kisah Musa adalah Firaun dan Musa sendiri. Al-Qur’an
mengkonfrontasikan keduanya dalam bentuk pertentangan antara yang benar dengan
29Sayyid Qut}b, Fī Z{ilāl al-Qur’ān, (Beirut: Dār Ih}ya’ al-Turāth al-‘Arabī, 1971), Vol. 6, 215.
yang batil. Keduanya merepresentasikan dua sisi kehidupan (yang gelap dan yang
terang) dan dua golongan manusia (yang zalim dan yang tertindas). Firaun mewakili
kelompok yang ingkar dan berbuat sewenang-wenang, dan Musa adalah cerminan
dari mereka yang berjuang melepaskan diri dari kezaliman. Yang pertama selalu
merujuk konsepnya kepada dunia dan kekuasaan manusiawi, sedangkan yang kedua
merujuk kepada Tuhan: bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan dan semua akan
kembali kepada Tuhan. Dua fondasi nalar inilah yang menjadikan Firaun dan Musa
berada pada kutub yang bertentangan. Firaun mengatakan bahwa kekuasaan negeri
Mesir adalah milik orang-orang Mesir, sedangkan menurut Musa, bumi ini adalah
milik Tuhan, dan Ia menganugerahkannya kepada siapa yang Ia kehendaki. Logika
Firaun tersebut tidak dapat diterima oleh Musa, terlebih ketika logika semacam itu
dijadikan alasan untuk memperbudak manusia, yakni (dalam hal ini) Bani Israil.
Maka Musa menjadi “pemberontak” bagi Firaun dan harus diusir dari negeri Mesir.
Kesombongan Firaun diungkapkan al-Qur’an antara lain pada awal surat al-
Qas}as} sebagai prelude bagi kisah Musa.
Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Firaun dengan benar untuk orang-orang yang beriman.
Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.
Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi),
dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Firaun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu.30
30Al-Qas}as}: 3-6
Lebih lanjut dalam ayat lain disebutkan bahwa para pengikut Firaun pun
memandang Musa tidak lebih dari seorang pemimpin gerakan kekacauan dan
perusak tradisi atau peradaban negeri Mesir.
Pembesar-pembesar kaum Firaun berkata: “Apakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di bumi (Mesir) dan meninggalkan kamu serta tuhan-tuhanmu?” Firaun menjawab: Akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka.”31
Akar psikologis dari sebuah kebencian dan motivasi dari berbagai kejahatan
selalu dibuat tersembunyi. Permusuhan selalu menampilkan alasan-alasan yang tidak
jelas. Dalam setiap kejahatan sosial, pelakunya selalu kaya dengan berbagai
argumentasi, atau, kalau tidak, maka kekuatan yang akan menjadi alat justifikasi.
Kekuatan fisik selalu menjadi pemenang dalam pertarungan yang instan. Tapi tidak
demikian halnya dalam sebuah proses sejarah; mungkin saja yang terjadi adalah
sebaliknya. Al-Qur’an telah menjadikan kisah Musa dan Firaun sebagai contoh
bagaimana sejarah memihak kepada kebenaran dan tidak bersikap netral. Tuhan akan
memenangkan kebenaran dan menjadikan kebatilan pada akhirnya sebagai yang
lenyap. Namun semua ini memerlukan proses, kerja keras, keteguhan hati dan
kesabaran.
Kesulitan yang dihadapi Musa berhadapan dengan Firaun dan para
pengikutnya adalah bahwa mereka menganggap Musa sebagai pemberontak dan
datang untuk merebut kekuasaan. Karena itu mereka tidak akan percaya kepadanya.32
Sikap seperti ini muncul sebagai akibat dari pandangan keduniawian dan keterikatan
31Al-A‘rāf: 127.
32Q.S. Yūnus: 78.
mereka secara fanatik pada masa lalu dan tradisi leluhur mereka – sebuah sikap yang
selalu dikecam al-Qur’an. Hal inilah yang menjadi penghalang besar bagi
perkembangan moral suatu bangsa.33
Seperti Nabi Muhammad juga, Musa pada awalnya digerakkan oleh
kegelisahan ingin melepaskan masyarakatnya dari kezaliman. Namun inspirasi-
inspirasi yang menjadi basis gerakan moral dan ajaran yang dibawanya bersifat
universal. Musa tidak semata-mata datang untuk menyelamatkan Bani Israil dari
kezaliman Firaun, tetapi juga menyelamatkan Firaun dan kaumnya dari kesesatan.
Musa datang membawa alasan moral yang kuat mengapa ia melakukan hal tersebut
dan mengajak Firaun untuk kembali ke jalan yang benar.
Pergilah kamu berdua (Musa dan Harun) kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.34
Al-Qur’an tidak menolak kemungkinan Firaun menerima seruan yang
disampaikan Musa. Namun dalam kenyataannya ia bersikap sombong, membalas
ajakan yang lembut dengan kebencian serta melawan segala argumentasi dengan
kekuatan, pendustaan dan penghinaan.
Konfrontasi antara Musa dan Firaun mencapai klimaks pada pertarungan fisik
atau adu kehebatan. Firaun menganggap Musa sebagai seorang tukang sihir, karena
itu ia mengumpulkan semua tukang sihir di seluruh negeri untuk melawan Musa.
Namun, ternyata Musa memenangkan pertarungan tersebut dan tukang-tukang sihir
33Mazheruddin Siddiqi, The Qur’anic Concept of History, (Delhi: S. Sajid Ali for Adam Publishers and Distributors, 1994), 112.
34T{āhā: 43-44.
sewaan Firaun tunduk dan menyerah serta beriman kepada Tuhan Musa.35 Ini
merupakan kekecewaan besar bagi Firaun dan membuatnya tambah murka. Memang,
demikianlah seseorang penguasa tiran, amat sulit melihat kekurangan dirinya
ataupun mengakui kesalahan yang dilakukannya. Ia menganggap dirinya amat benar
dan bersih dan tidak akan pernah mau dikalahkan. Seruan Musa akhirnya “sia-sia”
bagi Firaun dan sang Nabi benar-benar menjadi “pemberontak.” Sebab, kebenaran
tidak pernah bisa berkompromi dengan kebatilan.
Mengenai kehidupan Musa dan pengikutnya di Mesir pada masa-masa penuh
tekanan itu, al-Qur’an mengisahkan:
Musa berkata: “Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri.”
Maka mereka menjawab: “Kepada Allah-lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim,
dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang yang kafir.”
Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: “Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir sebagai tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah rumah-rumahmu itu kiblat, dan dirikanlah sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman.”
Musa berkata: “Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia; ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih.”
Allah berfirman: “Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui.”36
35Lihat Q.S. T{āhā: 57-76.
36Q.S. Yūnus: 84-89.
Ayat-ayat ini memperlihatkan betapa mencekamnya kehidupan mereka di
bawah tekanan politik Firaun, dan Musa menyatakan sikap dengan jelas bahwa
perlawanan harus dilakukan. Musa mengingatkan kaumnya untuk tetap bertawakal
dan menyerah diri pada Tuhan. Musa telah yakin bahwa Firaun tidak mungkin diajak
lagi untuk mengikuti kebenaran; Firaun telah banyak melakukan kerusakan dan
Musa memohon kepada Tuhan agar Firaun dihancurkan bersama peradaban dan
kaumnya yang arogan. Tuhan menerima doa Musa dan ia bersama Bani Israil
diselamatkan.
Kami mungkinkan Bani Israil melintasi laut; lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya, dengan sikap penuh kedengkian dan permusuhan; sehingga pada saat hampir tenggelam, Firaun berkata: “Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya termasuk orang yang berserah diri (kepada Tuhan).”37
Tuhan, dalam ayat di atas, menolak pertobatan yang diajukan Firaun karena
tentu saja bukan pertobatan yang tulus; lagi pula ia adalah seorang pembuat petaka
bagi manusia.38 Ayat ini memperlihatkan bagaimana sebuah peradaban yang
dibangun kini telah sia-sia, karena ia ditegakkan tanpa merujuk pada spiritualitas dan
moral serta dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Sebuah bangsa yang
tertindas kini diselamatkan, karena mereka sabar dan berpegang teguh pada ajaran
Tuhan. Gambaran yang dibuat al-Qur’an ini merupakan potret dua masyarakat yang
masing-masing memilih jalan hidup berbeda: yang satu memilih dunia dengan segala
kenikmatan yang menggiurkan serta mengabaikan segala nilai moral dan menolak
ajaran Tuhan, sedangkan yang lain memilih jalan Tuhan, yang mengedepankan
37Q.S. Yūnus: 90.
38Q.S. Yūnus: 91.
kualitas spiritual dan moral serta ketundukan pada nilai-nilai kemanusiaan, apa pun
konsekuensi yang akan mereka terima. Namun, ini bukanlah gambaran utuh tentang
Bani Israil. Ini hanya salah satu episode dari sejarah mereka yang panjang dan
kompleks. Namun, ada kecenderungan dalam tradisi Islam untuk melihat ayat-ayat
seperti ini secara terpisah dari kisah Bani Israil yang panjang. Ayat ini dianggap
tidak cukup mengimbangi penggambaran negatif al-Qur’an tentang Bani Israil,
bahkan ini terasa lebih mudah untuk ditafsirkan sebagai dasar untuk memperlihatkan
bagaimana karunia Allah kepada mereka yang begitu besar kemudian mereka
abaikan.
3. Exodus dan Pengembaraan di Sinai
Tuhan telah menjanjikan Ibrahim bahwa anak keturunannya akan menjadi
sebuah bangsa yang besar, dan Kanaan adalah dataran yang akan menjadi tempat
hunian mereka; seluruh dunia, dengan rahmat Tuhan, akan tercerahkan oleh bangsa
tersebut. Sekarang anak keturunan Ibrahim itu (Bani Israil) sedang berada di Mesir,
dalam sebuah perjuangan mempertahankan eksistensi dan harga dirinya di bawah
cengkeraman seorang penguasa zalim. Maka Eksodus, pelarian dan pelepasan diri
dari perbudakan di Mesir menuju kembali ke Kanaan, merupakan satu bentuk upaya
realisasi janji Tuhan tersebut. Eksodus menjadi inti dan spirit ajaran Yudaisme.
Melalui peristiwa yang penuh mukjizat itu Tuhan telah menyelamatkan sebuah
bangsa dari perbudakan dan mengangkatnya menjadi bangsa yang berkuasa dan
besar. Tuhan menghadirkan diri-Nya dan melakukan campur tangan langsung dalam
perjalanan sejarah bangsa tersebut serta menurunkan hukum-hukum dan aturan moral
melalui pemimpin mereka. Peristiwa itu benar-benar menjadi pengalaman sejarah
penuh makna dan apa yang disebut dengan Sinai experience menjadi the most
important material in the Hebrew Bible.39
Kisah Eksodus dalam Bible merujuk pada perjanjian Ibrahim dengan Tuhan,
sebagaimana tersebut di atas. Hal ini menunjukkan bahwa di situlah letak semangat
dan kekuatan revolusioner vokasi Musa dalam menyeru dan menyelamatkan
kaumnya. Bagian akhir kitab Genesis menceritakan tentang sebuah bangsa yang
unggul, keturunan dari Ibrahim, Ishak dan Yakub. Mereka bukan di Kanaan, tetapi di
Mesir. Namun Kanaan tetap merupakan tanah tujuan akhir mereka, tanah yang
dijanjikan.
And Joseph said unto his brethren: ‘I die; but God will surely remember you, and bring you up out of this land unto the land which He swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob.’40
Karena itu perbudakan Bani Israil di Mesir, kehadiran Musa sebagai Sang
Penyelamat, pelarian Musa ke Median dan pertemuannya dengan Tuhan dalam
sebuah perjalanan pulang, mempunyai makna tersendiri, sebagai bagian dari proses
yang telah diatur Tuhan untuk membimbing hamba pilihan-Nya ke tanah yang subur
dan penuh berkah, yakni Kanaan. Itulah sebabnya, semua event dan tokoh-tokoh
dalam Eksodus dianggap sebagai the heart and soul of the Jewish Religion.41
39Lewis M Hopfe dan Mark R. Woodward, Religions of the World, (New Jersy: Prentice Hall, 1998), 264.
40Genesis 50: 24.
41Lewis M Hopfe dan Mark R. Woodward, Religions, 264.
Dalam al-Qur’an, kisah ini juga diungkapkan dengan nada yang sama, namun
memiliki semangat dan tekanan yang berbeda. Kisah Nabi-nabi dalam al-Qur’an
selalu memiliki relevansi dengan semangat dan pergerakan dakwah Nabi Muhammad
dan diturunkan dalam rangka mengingatkan Sang Nabi akan bahwa watak alamiah
perjuangan itu memang penuh tantangan, dan bahwa Tuhan kemudian dengan
kekuasaan-Nya akan memenangkan kebenaran atas kebatilan.
Setelah terlepas dari perbudakan di Mesir dan telah mencapai daratan
seberang laut, Bani Israil dipresentasikan oleh al-Qur’an dengan fokus yang berbeda.
Mereka kini diungkapkan sebagai kelompok masyarakat yang tidak disiplin,
pembangkang dan tidak berterimakasih.
Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: “Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Ia mengangkat nabi-nabi di antara kamu, menjadikan kamu raja-raja, dan memberimu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain.”
Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditetapkan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh), sehingga kamu menjadi orang-orang yang merugi.
Mereka berkata: “Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa; sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka ke luar darinya. Jika mereka keluar darinya, pasti kami akan memasukinya.”
Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah karena) nikmat yang telah diberikan-Nya atas keduanya: “Serbulah mereka melalui pintu gerbang (kota) itu; maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman.”
Mereka berkata: “Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja.”
Musa berkata: “Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku, karena itu pisahkanlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu.”
Allah berfirman: “(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun; (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi itu. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang fasik itu.”42
Ayat-ayat di atas merupakan poin-poin kisah pembangkangan sebuah kaum
terhadap pemimpin mereka. Namun dari catatan al-Qur’an yang ringkas itu terlihat
dinamika kehidupan dan mentalitas sebuah bangsa yang baru saja memulai
kehidupan baru mereka setelah sekian lama dijajah dan diperbudak oleh seorang
penguasa zalim. Kalau dilihat dalam mus}haf al-Qur’an, ayat-ayat di atas adalah
kelanjutan dari peringatan-peringatan Tuhan kepada umat Nabi Muhammad, yang
dimulai dari ayat 7 surat al-Māidah sampai ayat-ayat tersebut di atas; mereka
diingatkan untuk tidak lupa berterimakasih kepada Tuhan atas segala nikmat dan
karunia-Nya; agar tetap menjadi orang yang jujur, adil dan menyerahkan hasil segala
urusan kepada Allah. Lalu al-Qur’an mengutip kisah-kisah Bani Israil sebagai bukti
kebenaran “historis” bahwa perjalanan hidup sebuah umat sangat ditentukan oleh
sikap moral dan komitmennya kepada ajaran Tuhan. Orang-orang yang patuh kepada
Tuhan diselamatkan dan para pembangkang akan dimurkai dan diberikan hukuman.
Dalam mendiskusikan ayat-ayat di atas, perhatian kebanyakan para mufassir
di antaranya tertuju pada pernyataan al-Qur’an yang memberikan pujian kepada Bani
Israil. Al-T{abarī (w. 923/310) mengutip sejumlah riwayat mengenai pandangan
kaum Muslim masa awal, termasuk para sahabat besar seperti Qatādah dan Ibn
‘Abbās, yang menggambarkan pandangan umum kaum Muslim terhadap Bani Israil.
Mereka memperbincangkan apa yang dimaksudkan al-Qur’an ketika menyebut Bani
Israil sebagai mulūk (raja-raja) dan apa pula maksud pernyataan: “dan memberimu
42Q.S. al-Mā’idah: 20-26.
apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang
lain.” Menurut para mufassir kalangan sahabat, orang-orang Bani Israil itu disebut
sebagai raja-raja karena mereka memiliki rumah, isteri dan pelayan-pelayan.
Pandangan seperti itu dirujuk pada tradisi mereka sendiri di Medinah di mana ketika
seseorang telah hidup “mapan” sampai memiliki al-khādim (pelayan) maka ia
disebut malik (raja). Sebuah riwayat yang berasal dari Zayd ibn Aslam bahkan
mengatakan Nabi pernah bersabda bahwa barangsiapa memiliki rumah dan pelayan
maka ia adalah seorang raja.43
Mengenai anugerah Tuhan “yang belum pernah diberikan-Nya kepada
seorang pun di antara umat-umat yang lain,” al-T{abarī juga mengemukakan
beberapa riwayat berbeda. Sebagian mufassir mengatakan bahwa yang dimaksudkan
adalah umat Nabi Muhammad, sementara sebagian yang lain mengatakan, yang
dimaksudkan adalah umat Nabi Musa. Riwayat yang berasal dari Ibn ‘Abbās dan
Mujāhid mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah umat Nabi Musa, namun
kelebihan mereka terbatas pada zamannya semata.44 Suatu umat mungkin saja
memiliki kelebihan dari umat lain, tetapi hal ini tentu saja tidak bersifat mutlak.
Sebagaimana dikatakan Mazheruddin Siddiqi, dalam beberapa hal Bani Israil
memang memiliki kelebihan di atas umat lain. Misalnya, mereka mendapat karunia
dengan kehadiran sejumlah pemimpin spiritual dan sebagiannya adalah Nabi yang
membawa kitab. Tidak ada umat lain di zaman tersebut yang memeliki keistimewaan
seperti itu. Akan tetapi, terdapat bangsa-bangsa lain pada waktu itu yang memiliki
43Al-T{abarī, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Ay al-Qur’ān, (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H.), 169-171.
44Ibid., 170.
kekuatan militer yang hebat dan tanah jajahan yang luas. Jadi dapat dikatakan bahwa
kelebihan yang diberikan kepada Bani Israil bersifat relatif.45
Makna lain yang mungkin dapat dipahami dari ayat di atas adalah indikasi
bahwa al-Qur’an, dalam mendeskripsikan Bani Israil, “menyerap” pandangan Bani
Israil sendiri terhadap diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Al-Qur’an hanya
mengklarifikasi bahwa keterpilihan mereka, sebagaimana telah didiskusikan di atas,
terkait dengan sikap moral dan komitmen keagamaan mereka. Di samping itu al-
Qur’an juga menunjukkan bahwa sebagian mereka, dalam sebagian perjalanan
hidupnya, telah gagal memenuhi persyaratan-persyaratan menjadi umat pilihan itu.
Karenanya di sisi lain, ayat-ayat al-Qur’an justeru mengecam kaum Bani
Israil dengan keras. Mereka disebutkan sebagai kaum yang bodoh serta tidak setia
pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Mereka mudah terpengaruh oleh tingkah laku
kaum lain yang mereka saksikan, meski menyimpang dari komitmen perjanjian
mereka dengan Tuhan.
Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan itu; maka sampailah mereka kepada suatu kaum yang menyembah berhala yang mereka miliki. Bani Israil berkata: “Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai tuhan-tuhan.” Musa menjawab: “Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang bodoh.”46
Mereka kini menjadi kaum yang tidak berterimakasih. Al-Qur’an
memperlihatkan bagaimana suatu kaum yang telah diselamatkan dari berbagai
bencana dan diberikan karunia yang banyak tetapi mereka tetap menunjukkan sikap
yang tidak pantas terhadap Tuhan. Musa diingatkan agar tidak terlalu bersedih hati
45Mazheruddin Siddiqi, The Qur’ānic Concept of History, (Delhi: Adam Publisher, 1994), 119.
46Q.S. al-A‘rāf: 138.
menyaksikan sikap mereka seperti itu. Tuhan akan membalas perbuatan mereka
dengan hukuman yang nyata.
Kisah ini tentu saja memberikan perbandingan kepada Nabi Muhammad
mengenai tugas kenabian yang diembannya, memperlihatkan bagaimana misi
seorang Nabi tidak selalu dapat dijalani dengan mudah dan bahwa umat yang
dihadapinya juga tidak selalu memberikan sikap dan respon yang menggembirakan.
Sebuah masyarakat bahkan kadang-kadang begitu mudah melupakan sejarahnya dan
membangkang pemimpin yang telah menyelamatkannya dari kesengsaraan. Ayat-
ayat mengenai kisah ini diturunkan dalam rangka menenteramkan jiwa Nabi karena
begitu gelisah menyaksikan umatnya yang abai terhadap peringatan-peringatan
Tuhan. Al-Qur’an turun untuk menegaskan bahwa hal serupa juga dialami nabi-nabi
terdahulu dan bahwasanya Tuhan tidak akan mengabaikan utusan-Nya. Seperti
disebutkan pada tempat lain, al-Qur’an tidak diturunkan untuk menyulitkan Nabi; ia
hanyalah peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan
Kami tidak menurunkan al-Qur’an ini kepadamu supaya kamu susah; Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah).47
Jika hal ini dicermati dengan sense historis yang tajam, tidak diragukan akan
terlihat bahwa al-Qur’an sedang berbicara mengenai watak manusia dalam sejarah.
Al-Qur’an memperingatkan Nabi Muhammad dan juga umatnya agar berhati-hati
dan tidak mengulangi kekeliruan yang sama seperti telah pernah dikerjakan Bani
Israil. Ini tidak berari al-Qur’an mendiskredit Bani Israil. Setiap bangsa dan individu
dapat mengulangi kesalahan yang sama sebagaimana setiap bangsa dan individu juga
dapat mengambil pelajaran dari bangsa dan individu yang lain. Al-Qur’an adalah
47Q.S. T}āhā: 2-3.
kitab yang memberikan pelajaran; kisah-kisah yang dikemukakannya juga mesti
dilihat dalam konteks pemberian pelajaran tersebut. Demikian juga harus dicatat
bahwa setiap bangsa dan peradaban memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri.
Jadi sungguh amat naif jika sebuah umat mengklaim superioritas dirinya atas umat
lain.
Musa telah melakukan tugasnya, membebaskan Bani Israil dari kekejaman
Raja Firaun dan membawa mereka menuju cita-cita leluhurnya, menempati negeri
Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan. Mereka telah diselamatkan ke sebuah dataran
menuju ranah yang penuh harapan itu. Sekarang mereka berada di Sinai, sebuah
gurun yang menawarkan kehidupan yang sulit. Namun, Tuhan tetap memberikan
mereka kemudahan dan makanan yang melimpah. Air keluar dari batu dan makanan
turun dari langit – sebuah gambaran “imajinatif” tentang karunia luar biasa.
Kami naungi kamu dengan awan dan Kami turunkan kepadamu manna48 dan salwā.49 Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan
48Menurut Qatādah, sebagaimana diriwayatkan Ibn Katsīr, manna adalah semacam cairan kental, warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu. Ibn Kasir juga mengutip sejumlah pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian manna, namun semuanya menunjuk pada makanan atau minuman yang manis dan lezat. Lihat Ibn Kasir, Tafsir, Vol. 1, 96. Manna mungkin berasal dari man hu (Hebrew: “apa itu?”). Lihat Encyclopaedia Britannica, s.v. “Manna,” Deluxe Edition 2004 CD-ROM. Dalam Bible, menurut terjemahan King James Version, disebutkan: And when the children of Israel saw it, they said one to another, It is manna: for they wist not what it was. And Moses said unto them, This is the bread which the LORD hath given you to eat (Exodus 16:15). Namun ini lebih jelas dalam terjemahan Jewish Publication Society 1917: And when the children of Israel saw it, they said one to another: ‘What is it?’ – for they knew not what it was. And Moses said unto them: ‘It is the bread which the LORD hath given you to eat.’ Kemudian dalam ayat 16:31: And the house of Israel called the name thereof Manna; and it was like coriander seed, white; and the taste of it was like wafers made with honey.
49Salwā adalah sebangsa burung puyuh. Al-Jalālayn menyebutnya dengan al-t}ayr al-sumānā. Lihat al-Jalālayn, Tafsīr al-Jalālayn, (Kairo: Dār al-H{adīts, t.t.), 12. Menurut The Encyclopaedia of Islam, salwa inilah yang dalam Bible (misalnya, Exodus 16: 11-13) disebut dengan quail (Latin: quaquilla), yakni burung puyuh. Lihat The Encyclopaedia of Islam, s.v. “Salwā,”CD-ROM Edition, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 1999).
kepadamu. Mereka tidak menganiaya Kami; mereka hanyalah menganiaya dirinya sendiri.50
Dalam ayat yang lain, mengenai mata air yang memancar dari batu, dikatakan:
Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: “Pukullah batu itu dengan tongkatmu.” Maka memancarlah darinya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.51
Ayat-ayat ini menerangkan karunia dan nikmat Tuhan yang banyak yang
diberikan kepada Bani Israil. Al-Qur’an menyeru orang-orang Yahudi untuk
memperhatikan dan merenungi kembali hal tersebut; bahkan tidak sekedar itu,
kepada mereka juga diperlihatkan bagaimana sikap “keras kepala” mereka dan sikap
tidak tahu berterimakasih atas nikmat-nikmat Tuhan itu telah menyebabkan mereka
dimurkai oleh Tuhan dan diturunkan hukuman atau siksaan yang berat. Menurut al-
Qur’an, sejak zaman Nabi Musa mereka sudah diingatkan untuk tidak melakukan
kerusakan di bumi dan agar tunduk patuh kepada pemimpin mereka, yaitu nabi yang
diutus Allah, tetapi dalam kenyataannya, mereka tetap saja tidak mengambil
pelajaran dari masa lalu itu dan tidak menghiraukan janji-janjinya dengan Tuhan.
Kisah lain yang diungkapkan al-Qur’an tentang fenomena kaum Musa di
Sinai adalah cerita Karun (Qārūn).
Sesungguhnya Karun termasuk di antara kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: “Janganlah kamu terlalu
50Q.S. al-Baqarah: 57. lihat juga Q.S. al-A‘rāf: 160 dan T}āhā: 80.
51Q.S. al-Baqarah: 60.
bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.”52
Kisah Karun adalah bagian dari kisah Musa, namun ia disebutkan agak
terpisah. Surat al-Qas}as} dimulai dengan kisah Musa yang diungkapkan secara
panjang, sampai empat puluh ayat. Lalu dari kisah itu al-Qur’an menarik beberapa
pelajaran yang dikemas menjadi hujah dalam merespon sikap kaum kafir Arab dan
menentang alasan mereka menolak risalah yang disampaikan Nabi Muhammad.
Ayat-ayat dalam surat ini kemudian berlanjut dalam bentuk upaya menenteramkan
hati Nabi bahwa risalahnya ditolak hanya karena kedengkian dan kebodohan spiritual
mereka semata, bukan karena kurangnya reliabilitas risalah itu sendiri.
Mereka berkata: “Jika kami mengikuti petunjuk bersamamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami.” Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezeki (bagimu) dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.53
Ayat ini mengekspresikan ucapan kaum kafir Mekkah54 yang menunjukkan
rendahnya kesadaran mereka terhadap nilai kebenaran yang lebih tinggi dibanding
posisi sosial dan barang-barang keduniaan yang sebenarnya amat mudah untuk
datang dan lenyap – Tuhan Maha Kuasa untuk mendatangkan dan memusnahkannya.
Terkait dengan ini, kisah Karun diceritakan pada akhir surat untuk memperlihatkan
paralel yang lebih jelas antara mereka (kaum Mekkah yang ingkar) dengan umat
dahulu yang telah dimusnahkan Tuhan karena memperlakukan utusan Allah dan
52 Q.S. al-Qas}as}: 76.
53Q.S. al-Qas}as}: 57.
54Al-Wāh}idī, al-Wajīz, Vol. 2, 812.
risalah-Nya dengan cara yang sama. Karun, seperti tersebut dalam ayat di atas,
adalah orang yang sangat kaya, namun kekayaan tersebut telah mengantarnya pada
kesombongan dan kekufuran. Semua nasehat kaumnya ia tepis dan menganggap
bahwa ia pantas berbangga diri. Ia menganggap telah mendapatkan kelebihan
tersebut karena ilmu pengetahuan yang ia miliki. Sebagian orang tercengang dan
berangan-angan dapat meraih “sukses” seperti Karun. Namun “orang-orang yang
dianugerahi ilmu,” kata al-Qur’an, tidak akan pernah terpedaya dengan
kegemilangan duniawi tersebut; “pahala (yang diberikan) Allah lebih baik, bagi
orang-orang yang beriman dan beramal saleh; dan pahala tersebut tidak akan
diperoleh kecuali oleh orang-orang yang sabar.”55
Karun dibenamkan Tuhan ke dalam bumi, serta seluruh kekayaan yang ia
miliki. Kejadian ini telah menyadarkan orang-orang yang sebelumnya sangat kagum,
terpesona dan cemburu terhadap kekayaan Karun; untunglah mereka belum sempat
terjerumus bersamanya. Mereka lalu berkata: “Sekiranya bukan karena Allah telah
melimpahkan karunia-Nya atas kita, Dia pasti telah membenamkan kita juga. Duhai
sungguh benar, tidak akan beruntung orang-orang yang ingkar.”56
Dalam Bible,57 Karun (Korah) dikisahkan sebagai pemberontak terhadap
Musa dan Harun. Tidak begitu jelas mengenai alur cerita tentang asal mula
pemberontakan itu. Kelihatannya, Karun ingin menjadi seorang “Imam” bagi
kaumnya dan mendapatkan posisi sebagai pemimpin. Mungkin ia cemburu terhadap
kesuksesan Musa atau karena Tuhan telah memilihnya menjadi pemimpin Bani 55Q.S. al-Qas}as}: 80.
56Ibid., 82.
57Number 16.
Israil. Namun kemudian, cerita tentang hukuman yang diberikan Tuhan kepada
Karun dan para pengikutnya diekspresikan secara jelas dan grafis.
(32) And the earth opened her mouth and swallowed them up, and their households, and all the men that appertained unto Korah, and all their goods. (33) So they, and all that appertained to them, went down alive into the pit; and the earth closed upon them, and they perished from among the assembly. (34) And all Israel that were round about them fled at the cry of them; for they said: ‘Lest the earth swallow us up’. (35) And fire came forth from the LORD, and devoured the two hundred and fifty men that offered the incense.58
Versi al-Qur’an tampak berbeda. Sisi moral yang diketengahkan al-Qur’an
terkait dengan atmosfer kehidupan kota Mekkah dengan para pembesarnya yang
arogan dan sangat takut kehilangan harta benda. Kecocokan versi dua kitab suci
barangkali tidak terlalu penting bagi sebuah pelajaran moral. Bagi al-Qur’an, ini
adalah kisah yang benar, dan kebenaran tersebut tentu saja terletak pada muatan
pesan Ilahi yang terkandung di dalamnya – tidak mesti kebenaran faktual yang dapat
diverifikasi secara historis.
Beginilah kenyataannya cara al-Qur’an mengungkapkan kisah perjalanan
Bani Israil di gurun Sinai. Kronologis dan detil kisah tidak pernah ditemukan dalam
al-Qur’an. Fokus perhatian al-Qur’an adalah semata-mata pada sisi moral dan
pendidikan dari kisah itu. Al-Qur’an hanya mencatat kembali beberapa peristiwa
penting dengan menonjolkan karakteristik manusianya. Sejarah tidak pernah
berulang, tetapi watak manusia dalam sejarah selalu menjadi cermin bagi generasi-
generasi berikutnya. Inilah yang diangkat al-Qur’an. Akhir perjalanan Musa
membimbing umatnya pun tidak disebutkan. Namun dari narasi Bible dapat
diketahui bahwa sang Nabi telah wafat sebelum berhasil membawa kaum Bani Israil
58Numbers 16: 32-35.
ke tanah yang dijanjikan itu. Tuhan hanya memperlihatkan kepadanya negeri
tersebut, ketika ia berdiri di puncak gunung Nebo di atas dataran Moab, sebelah
timur lembah Yordan.59
4. Kehidupan di Kanaan
Kanaan adalah tanah yang dijanjikan itu. Tuhan telah mengatakannya kepada
Ibrahim, Ishak dan Yakub bahwa tanah itu adalah milik mereka dan anak cucunya,
kaum Bani Israil. Dalam literatur sejarah dan dalam Bible negeri ini dirujuk secara
bervariasi, namun semuanya berpusat pada wilayah yang dikenal sekarang dengan
Palestina.60 Dalam ayat-ayat bagian akhir Deuteronomy dikatakan:
(1) And Moses went up from the plains of Moab unto mount Nebo, to the top of Pisgah, that is over against Jericho. And the LORD showed him all the land, even Gilead as far as Dan; (2) and all Naphtali, and the land of Ephraim and Manasseh, and all the land of Judah as far as the hinder sea; (3) and the South, and the Plain, even the valley of Jericho the city of palm-trees, as far as Zoar. (4) And the LORD said unto him: ‘This is the land which I swore unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, saying: I will give it unto thy seed; I have caused thee to see it with thine eyes, but thou shalt not go over thither’.61
Menurut Bible, Yosua (Joshua; Yūsya‘ dalam tradisi Islam) kemudian
meneruskan perjuangan Musa hingga tanah tersebut dapat mereka duduki. Kisah
panjang, sebagaimana dalam Bible, tentang proses penaklukan itu tidak menjadi
perhatian al-Qur’an. Peristiwa penting yang disebutkan al-Qur’an mengenai
kehidupan Bani Israil di Kanaan pertama sekali adalah kisah perjuangan T{ālūt
59Deuteronomy 34: 1-4.
60Encyclopaedia Britannica, s.v. “Canaan,” Deluxe Edition 2004 CD-ROM.
61Deuteronomy 34: 1-4.
melawan Jālūt. Ini diungkapkan al-Qur’an berkaitan dengan sikap kaum Muslim
dalam menghadapi perang. Perang memang menelan korban jiwa dan harta, tetapi
hal ini tidak perlu dikhawatirkan oleh mereka yang beriman dan yakin akan anugerah
Tuhan. Perang bukan semata-mata soal kalah dan menang, tetapi juga melibatkan
pengorbanan dan kesetiaan. Dalam pandangan al-Qur’an, yang terakhir inilah yang
paling penting. Perang adalah sebuah ujian mental dan kesetiaan. Orang yang
menang dalam ujian inilah – tidak mesti menang dalam peperangan – yang mendapat
kedudukan tinggi di sisi Tuhan; semua pengorbanan mereka tidak akan pernah disia-
siakan dan kepada mereka diberikan balasan yang berlipat ganda.62 Di samping itu,
keyakinan, kedisiplinan dan keteguhan hati juga menjadi kekuatan dan sumber
pertolongan Tuhan. Pelajaran mengenai sikap mental dalam menghadapi perang
inilah yang paling menggema dalam kisah T{ālūt.
Menurut Bible,63 Tālūt (Saul) adalah anak Kish bin Abiel, seorang
terpandang dan disegani dari sebuah suku kecil Bani Israil, suku Benyamin. Tālūt
merupakan seorang pemuda yang gagah dan tampan ketika diangkat oleh Nabi
Samuel mejadi raja Bani Israil. Ia menjadi seorang tokoh yang menonjol dan
disenangi rakyat. Pengangkatannya sebagai raja mendapatkan dukungan penuh,
walaupun perlawanan tetap ada dari sekelompok kecil orang-orang yang tidak
senang kepadanya sebab ia berasal dari suku yang dianggap rendah. Tālūt, seperti
diungkapkan al-Qur’an, bukan hanya hebat secara fisik, tetapi juga sangat baik budi,
berilmu dan bijaksana.
62Q.S. al-Baqarah: 244-245; al-Nisā’: 74.
63Samuel 9: 1-2; Kisah T{ālūt (Saul) diceritakan panjang lebar dalam Samuel 8-15.
Kisah sekitar kehidupan Tālūt dalam Bible hanya merupakan bagian kecil
dari episode zaman perubahan besar yang amat menentukan bagi Bani Israil. Mereka
berada di tengah kurun yang penuh kekacauan. Kekuatan bangsa Filistin merupakan
ancaman amat menakutkan bagi Bani Israil. Sudah sekitar satu abad terjadi konflik di
antara dua bangsa ini dan Bani Israil hampir saja kehilangan kepercayaan dirinya.
Tokoh paling menonjol pada zaman ini sebenarnya adalah Samuel, seorang Imam
yang kemudian dipanggil Tuhan menjadi Nabi. Seruan profetik inilah yang telah
membuka jalan baru bagi kemenangan mereka. Samuel pada waktu itu telah berusia
lanjut dan tidak sanggup memberikan pelayanan maksimal bagi perjuangan
rakyatnya. Maka para pemuka masyarakat meminta kepadanya agar mengangkat
seorang raja untuk memimpin Bani Israil melawan musuh-musuhnya.64 Cuplikan
kisah inilah yang dicatat kembali oleh al-Qur’an.
Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: “Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah.” Nabi mereka menjawab: “Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang.” Mereka menjawab: “Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?” Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim.65
Ayat ini memperlihatkan semangat Bani Israil pada tahap awal, yang sangat
eager, seakan tidak sabar lagi menunggu perintah berjuang di medan perang; dalam
64W. S. LaSor, D. A. Hubbard dan F. W. Bush, Pengantar Perjanjian Lama 1: Taurat dan Sejarah, terj. Werner Tan dkk., (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 325-337.
65Q.S. al-Baqarah: 246.
istilah Qut}b, mutah}assūn naz}riyya li al-jihād.66 Tetapi Nabi mereka menguji
terlebih dahulu semangat mereka, jangan-jangan setelah raja diangkat mereka tidak
mau berperang. Namun mereka tetap menunjukkan kesungguhannya. Setelah
kewajiban perang ditetapkan, barulah terlihat siapa yang setia dan siapa yang tidak.
Semua orang mengatakan “ya” sebelum mendapatkan ujian, tetapi ketika telah
berhadapan dengannya, kebanyakan manusia akan mundur. Dalam kisah T{ālūt, itu
baru ujian pertama dan itu belumlah cukup. Untuk membentuk sebuah pasukan juang
yang handal, ujian semangat pada tataran permukaan saja tidak memadai. Untuk itu
T{ālūt menempuh beberapa tahapan ujian kedisiplinan yang akhirnya membentuk
sebuah pasukan inti dengan keteguhan iman yang tidak tergoyahkan.67
Al-Qur’an melanjutkan, ketika Tālūt diangkat menjadi raja, mereka protes.
Keberatannya tidak lain karena Tālūt bukan seorang yang terpandang dalam hal
harta kekayaan. Di sini kembali terlihat bagaimana al-Qur’an menampakkan pesan
moral paling penting dari kisah tersebut. Seorang raja atau pemimpin tidak diukur
berdasarkan kekayaan yang ia miliki, tetapi pengetahuan dan kesehatan jasmaninya
yang harus dipertimbangkan.
Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya Allah telah mengangkat T{ālūt menjadi rajamu.” Mereka menjawab: “Bagaimana T{ālūt memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak?” (Nabi mereka) berkata: “Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.” Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.68
66Sayyid Qut}b, Fī Z{ilāl al-Qur’an, Edisi CD-ROM, (Jordan: Arabic Textware), 266.
67Sayyid Qut}b, Fī Z{ilāl, Edisi CD-ROM, 262-263.
Sementara itu, tanda bahwa Tālūt menjadi raja adalah kembalinya tabut
Tuhan69 kepada mereka (kaum Bani Israil), yang “di dalamnya terdapat ketenangan
dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu
dibawa oleh Malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu,
jika kamu orang yang beriman.”70 Menurut Heribert Busse,71 ternyata benar, sejalan
dengan narasi Bible, bahwa tabut tersebut dikembalikan lagi oleh orang-orang
Palestina yang merampasnya, sebelum T{alūt menjadi raja.
Kini T{ālūt dan tentaranya keluar menuju medan pertempuran. Ujian
kedisiplinan diterapkan.
Maka tatkala T{ālūt keluar membawa tentaranya, ia berkata: “Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku; barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku.” Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala T{ālūt dan orang-orang yang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: “Tak ada kesanggupan bagi kami pada hari ini untuk melawan Jālūt dan tentaranya.” Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata: “Berapa banyak dari golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.”72
68Q.S. al-Baqarah: 247.
69Dalam al-Qur’an disebut tābūt, yakni the Ark of the Covenant, kotak tempat Taurat. Tabut tersebut telah merupakan lambang kehadiran Tuhan bagi orang-orang Israel. Mereka sangat menghormatinya. Dalam sebuah peperangan, tabut itu pernah dirampas oleh bangsa Filistin. Namun mereka tidak menduga bahwa tindakannya itu telah mendatangkan bencana dan kutukan. Akhirnya mereka mengembalikannya kembali kepada kaum Bani Israil (1 Samuel 5-6).
70Q.S. al-Baqarah: 248.
71Heribert Busse, Islam, Judaism, and Christianity: Theological and Historical Affiliations, terj. Allison Brown dari Bahasa Jerman, (Princeton: Markus Wiener Publishers, 1998, 105.
72Q.S. al-Baqarah: 249.
Kelompok inti tersebut kemudian berhadapan dengan Jālūt, musuh mereka.
Maka inilah yang terjadi:
Tatkala mereka tampak oleh Jālūt dan tentaranya, mereka pun (T{ālūt dan tentaranya) berdo‘a: “Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas kami, dan kokohkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.”
Maka mereka mengalahkan tentara Jālūt dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud (Dāwūd) membunuh Jālūt, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah, (setelah meninggal T{ālūt) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (kejahatan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, sungguh rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.73
Cuplikan kisah tersebut sampai di situ. Ini tentu saja amat singkat jika
dibanding narasi Bible yang sangat panjang dan mendetil. Daud, dalam Bible, adalah
seorang anak muda dengan peralatan perang yang sederhana, mengalahkan Jālūt
(Goliath) yang dilengkapi persenjataan berat. Di sini ada poin penting yang memiliki
persamaan: Sekelompok pasukan yang berjuang di jalan Tuhan, dengan berpegang
teguh pada iman kepada-Nya serta yakin akan pertolongan-Nya, meskipun sedikit
dan hanya dengan persenjataan sederhana, dapat mengalahkan pasukan kafir yang
jumlahnya lebih besar dan lebih hebat secara fisik; yang satu berperang atas nama
Tuhan, yang satu atas nama berhala. Ayat di atas mengacu pada penegasan bahwa
kekuatan spiritual dapat mengalahkan kesombongan material yang berada di atas
jalan setan atau kesesatan. Kisah yang diungkapkan ayat tersebut barangkali juga
menjadi justifikasi bagi gagasan-gagasan perang lainnya dalam al-Qur’an. Perang,
sejauh dilakukan secara benar dan jujur di jalan Tuhan untuk melawan musuh yang
agresif, dapat dibenarkan. Perang yang dijalankan Bani Israil melawan kaum agresor
73Ibid., 250-251.
Filistin yang telah mengusir mereka dari kampung halamannya mempunyai paralel
dengan gerakan Nabi Muhammad dan kaum Muslim melawan kekejaman kaum
Musyrik Mekkah. Kisah ini bukan hanya memberikan semangat perang kepada kaum
Muslim, tetapi juga landasan teologis bagi kebenaran dan bahkan kewajiban perang
itu sendiri. Tentu saja pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa al-
Qur’an mencari legitimasi dari Bible; yang ingin ditegaskan adalah bahwa al-Qur’an
tidak mustahil diasumsikan sebagai telah mencari dukungan bagi gerakan dan ajaran-
ajarannya dari berbagai peristiwa yang terjadi pada umat-umat terdahulu yang juga
berjuang di bawah bimbingan Tuhan. Fenomena ini merupakan bagian dari respek
yang diberikan al-Qur’an kepada setiap umat yang menunjukkan kesetiaannya
kepada risalah Tuhan serta mendahulukan spiritualitas atas keduniaan, kebenaran
atas kebatilan, jalan Tuhan atas jalan setan, ketundukan atas keangkuhan.
Dalam tradisi Yahudi, Kanaan adalah negeri yang dijanjikan Tuhan. Namun –
“entah mengapa” – orang-orang Yahudi harus memasuki dan mendudukinya dengan
jalan yang penuh pertumpahan darah. Wilayah tersebut, seperti kata Max I. Dimont,74
telah menjadi koridor para serdadu kekaisaran yang suka berperang. Tiada hentinya
Bangsa Israel terlibat dalam adu kekuatan di medan tempur. Mereka ditangkap,
diperbudak dan dideportasi ke negeri asing. Namun, mereka – bahkan sampai hari ini
– tetap kembali ke Kanaan, dengan harga apa pun yang harus dibayar. Mereka, kata
Dimont, dalam hal ini telah mengambil keputusan yang sangat keliru.75 Namun itulah
keputusan Tuhan; atau, Tuhan telah membuat keputusan yang menyesatkan?
74Max I. Dimont, Jews, God and History, (New York: Penguin Books, Edisi Revisi 1994), 48-49.
75Ibid., 48.
Ketika memasuki Kanaan, Bani Israil, di bawah pimpinan Yosua yang gagah
berani, telah mengalahkan musuh-musuhnya dengan telak. Deskripsi Bible tentang
penaklukan tersebut bahkan mungkin terlihat menyeramkan, biadab dan sangat
barbarik.
(8) And the LORD delivered them into the hand of Israel, and they smote them, and chased them unto great Zidon, and unto Misrephoth-maim, and unto the valley of Mizpeh eastward; and they smote them, until they left them none remaining. (9) And Joshua did unto them as the LORD bade him; he houghed their horses, and burnt their chariots with fire. (10) And Joshua turned back at that time, and took Hazor, and smote the king thereof with the sword: for Hazor beforetime was the head of all those kingdoms. (11) And they smote all the souls that were therein with the edge of the sword, utterly destroying them; there was none left that breathed; and he burnt Hazor with fire. (12) And all the cities of those kings, and all the kings of them, did Joshua take, and he smote them with the edge of the sword, and utterly destroyed them; as Moses the servant of the LORD commanded.76
Orang yang tidak familiar dengan kisah kehidupan zaman kuno akan merasa
aneh, bagaimana Tuhan telah memerintahkan umat pilihan-Nya melakukan
kekejaman luar biasa seperti itu. Namun sesungguhnya ini tidaklah sekejam
penghancuran peradaban yang dilakukan bangsa Yunani terhadap Kreta, atau orang-
orang Romawi terhadap Etruscan sekitar tujuh abad sebelum Masehi. Terlebih lagi,
peradaban Kanaan memang harus dihancurkan karena Tuhan yang Maha Esa
menghendakinya. Agama yang menjadi basis peradaban mereka telah diselewengkan
untuk memuja dewa-dewa selain Tuhan yang Esa; korban-korban manusia
dipersembahkan kepada dewa Moloch, ritus-ritus cabul dan pesta-pora dihidupkan
dan bahkan “prostitusi suci” dilakukan atas nama dewa perempuan yang disebut
76Joshua 11: 8-12.
Asherah atau Baala. Semua perbuatan ini telah menimbulkan amarah Tuhan, dan Ia
mengutus Bani Israil untuk menghancurkannya.77
Al-Qur’an tentu saja tidak ingin berspekulasi dengan semua kisah ini dan
bukan tujuan al-Qur’an mencatat peristiwa-peristiwa sejarah seperti yang dilakukan
Bible. Sebagai sebuah kitab hidāyah, al-Qur’an menganggap telah cukup mengambil
sebuah cuplikan tertentu dari suatu kisah, yang memiliki muatan moral dan
pendidikan yang mendalam. Fakta-fakta sejarah merupakan bagian dari ilmu
pengetahuan yang bisa digali sendiri oleh manusia; al-Qur’an memberikan kebebasan
yang luas dalam hal ini.
Kanaan di bawah kekuasaan Bani Israil kini memasuki babak baru, yakni
setelah T{ālūt menjadi raja. Sebelumnya, Kanaan adalah negeri yang terdiri atas dua
belas suku Bani Israil dengan pemerintahan sendiri-sendiri, tanpa raja atau
pemerintahan pusat yang kuat. Para sesepuh (the Elders) setiap suku memegang
kendali pemerintahan dan memutuskan perkara atas dasar hukum Tuhan. Di atas
mereka semua, yang menjadi rujukan seluruh kaum, terdapat Hakim (the Judge).
Pemerintahan para Hakim ini berjalan dengan baik sekitar dua abad, sampai sebuah
kelemahan fatal mulai terasa: It did not provide the basis for a strong centralized
leadership.78 T{ālūt adalah raja mereka yang pertama dan memerintah secara sentral.
Namun raja tidak memiliki kekuasaan mutlak. Semua manusia, tidak terkecuali raja
atau pun para Hakim, tunduk pada hukum – yakni hukum Tuhan, the commands of
77Max I. Dimont, Jews, 49.
78Ibid., 51.
God. Dalam hal ini, Nabi, tokoh yang mampu berkomunikasi dengan Tuhan, adalah
rujukannya.
Nabi Samuel telah mengangkat seorang raja; terbentuklah sebuah model
pemerintahan baru yang belum pernah mereka buat sebelumnya. Sang Nabi
mempunyai firasat bahwa raja bukanlah pemerintah yang baik. Raja cenderung untuk
korup dan arogan, karena itu sebelumnya mereka tidak pernah berpikir untuk
mengangkat seorang raja. Apa yang dibayangkan Samuel akhirnya terjadi. Raja
T{ālūt, sedikit demi sedikit, mengalami kegagalan dalam mengendalikan dirinya. Ia
telah menjadi abai terhadap titah-titah Tuhan dan mengambil berbagai keputusan
secara sewenang-wenang. Akhirnya ia jatuh, setelah Tuhan menolaknya dan Samuel
memberikan keputusan yang tegas untuk menggantikannya dengan seorang raja baru.
Kisah kejatuhan T{ālūt amat menyedihkan. Ia mengalami depresi yang berat
karena Tuhan telah menolaknya. Permohonan ampunnya tidak mengubah keputusan
sang Nabi. Walaupun demikian, Samuel tidak berpikir untuk kembali ke sistem
“federal” dua belas suku seperti sebelumnya; yang perlu dilakukan adalah mencari
seorang raja pengganti yang lebih baik. “Atas perintah Tuhan, Samuel pergi ke
Betlehem untuk menemui calon raja baru itu,”79 yakni Daud. Kisah Daud dan
anaknya Sulaiman (Sulaymān) inilah yang menjadi cuplikan selanjutnya dalam al-
Qur’an tentang dinasti Yahudi di negeri Palestina itu. Di bawah kerajaan Daud dan
Sulaiman, Bani Israil menjadi bangsa yang bersatu dan kuat, damai dan makmur.
Kerajaan ini menjadi model selama empat abad, dan masa tersebut benar-benar
79W. S. LaSor, D. A. Hubbard dan F. W. Bush, Pengantar Perjanjian Lama, 345.
merupakan “zaman keemasan Israel.”80 Keindahan zaman itu terlukis dalam ayat-
ayat Zabūr (Psalms) Daud. Al-Qur’an menggambarkannya sebagai berikut:
Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu. Telah Kami tundukkan pula gunung-gunung dan burung-burung; semua bertasbih bersama Daud. Dan Kamilah yang melakukannya.
Sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami. (Kami berfirman): “Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud,” dan Kami telah melunakkan besi untuknya.81
Dalam tradisi Islam Daud dikenal sebagai seorang nabi dengan sense of art
yang luar biasa. Keindahan bait-bait pujiannya dalam kitab Zabūr mampu membuat
alam semesta terpana ketika didendangkannya. Burung-burung akan berhenti terbang
dan gunung-gunung gemetar jika mendengarkan suara Daud membaca Zabūr.82
Keindahan dalam membaca kitab suci, lantas, menjadi seni tersendiri dalam Islam,
sebagaimana juga dalam tradisi Yahudi. Tilāwah al-Qur’ān dan cantillation of the
Torah memiliki kedudukan istimewa dalam tradisi kedua umat Yahudi dan Muslim.
Dalam Talmud83 terdapat indikasi bahwa membaca kitab suci tanpa melodi atau
berirama adalah lifeless.84 Kaum Muslim hari ini bahkan memperlombakan keahlian
dalam seni tilāwah al-Qur’ān, dari tingkat desa sampai internasional, dari Afrika
sampai Indonesia. Tak pelak lagi, ini disebabkan Nabi Muhammad sendiri dikenal
dalam tradisi Islam sebagai telah mengapresiasi keindahan seni baca al-Qur’an, dan
80Ibid., 348.
81Q.S. al-Anbiyā’: 79; Saba’: 10.
82Ibn Katsīr, Tafsīr, Vol. 3, 188.
83Lihat Megillah 32a.
84Louis Jacobs, The Jewish Religion, 65.
ini tidak terlepas dari kekagumannya terhadap kemerduan nyanyian sajak-sajak
pujian Daud – Nabi yang dikenal sebagai seorang musisi dalam tradisi Bible itu.
Diriwayatkan, suatu malam Nabi berhenti karena mendengarkan Abū Mūsā al-
Asy‘arī melantunkan ayat-ayat al-Qur’an dengan suara yang sangat merdu. Beliau
berkata: Orang ini telah dianugerahi suatu alat musik (mizmār) di antara alat-alat
musik keluarga Daud.85
Ayat-ayat di atas, jika boleh dipahami secara alegoris, mengisyarat
kedamaian yang menyeluruh dalam kerajaan Daud. Keharmonisan bukan hanya
terjadi dalam masyarakat manusia, tetapi semesta pun tertegun dalam menatap
keagungan yang terpancar pada keadilan, kebijaksanaan dan ketulusan sang Raja.
Titahnya tidak lain adalah titah Yang Maha Kuasa, sebab ia sendiri telah dinobatkan
sebagai wakil-Nya di bumi.86 Karena itu gunung-gunung dan burung-burung pun
tunduk kepadanya.87
Kisah tentang Daud dalam al-Qur’an secara general berbentuk komentar-
komentar ringkas seperti dalam ayat-ayat yang dikutip dan dirujuk di atas. Daud
adalah salah satu di antara nabi-nabi yang menerima wahyu dari Tuhan,
mendapatkan petunjuk-Nya dan diberikan Zabūr. Ia adalah seorang hamba Tuhan
yang memiliki keteguhan hati, saleh, taat dan bersyukur.88 Ayat-ayat ini umumnya
diturunkan dalam konteks meyakinkan Nabi Muhammad akan kebenaran dan
keaslian risalah yang diterimanya dari Tuhan, serta mengingatkan beliau mengenai 85Ibn Katsīr, Tafsīr, Vol. 3, 188.
86Q.S. S{ād: 26.
87Ibid., 18-19.
88Q.S. al-Nisā’: 163; al-An‘ām: 84; al-Naml: 15; S{ād: 17.
karakteristik kerasulan yang diembannya itu. Tantangan hendaklah diterima sebagai
konsekuensi logis dari misi risalahnya, sebagaimana yang dihadapi nabi-nabi
terdahulu. Nabi-nabi selalu mendapatkan cobaan, dan mereka bersabar; nabi-nabi
juga menerima karunia yang banyak dari Tuhan, dan mereka bersyukur.
Kisah yang diceritakan al-Qur’an agak panjang adalah tentang pertobatan
Daud karena suatu kekeliruan yang dilakukannya. Tuhan memberi teguran melalui
sebuah perkara yang diajukan kepadanya oleh dua orang yang bersengketa.
Adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara, ketika mereka memanjat pagar?
Ketika mereka masuk (menemui) Daud, lalu ia terkejut karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata: “Janganlah engkau merasa takut; (kami) adalah dua orang yang berperkara, salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah engkau menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus.
Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: “Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkanku dalam perdebatan.”
Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim terhadap sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikit mereka ini.” Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu tersungkur bersujud dan bertaubat.
Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik.89
Inilah sisi kemanusiaan Daud yang diperjelas al-Qur’an: seorang Raja yang
agung dan bijaksana, tetapi bukan tanpa kelemahan; seorang hamba yang saleh,
selalu taat dan waspada, namun bisa saja keliru. Apa yang membuat Daud tetap dekat
89Q.S. S{ād: 21-25.
dengan Tuhan adalah sikapnya yang segera menyadari kekeliruan tersebut, lalu
bertobat dan kembali kepada-Nya.
Kesalahan apa yang telah dilakukan Daud, tidak diterangkan al-Qur’an. Ayat-
ayat di atas, dari sudut pandang pengungkapan sebuah cerita, masih menyimpan
tanda tanya. Namun sebagai sebuah medium penyampaian pesan moral, al-Qur’an
telah mencapai tujuannya. Apakah al-Qur’an tidak mengungkapkan berbagai detil
cerita karena menganggap bahwa para pendengarnya telah mengetahuinya, hanyalah
sebuah spekulasi. Sepertinya, dalam kasus ini, lebih tepat dikatakan bahwa al-Qur’an
enggan untuk menyelami ke dalam perasaan tidak menyenangkan dari seseorang
yang sebenarnya lebih patut dihormati daripada dilecehkan. Seperti telah
didiskusikan di atas, al-Qur’an sama sekali mengabaikan kisah akhir kehidupan
T{ālūt yang menurut narasi Bible bukan hanya menyedihkan tetapi juga tragis.
Barangkali ini adalah bagian dari moralitas al-Qur’an yang ingin ditunjukkan kepada
pembacanya. Aspek-aspek yang ditonjolkan oleh kitab-kitab suci tentu saja berbeda-
beda, sebab mereka bertarung dengan peradaban yang berbeda-beda pula. Al-Qur’an
tidak dapat disamakan dengan Bible, karena zaman dan corak umat yang
dihadapinya juga tidak sama.
Kisah Sulaiman anak Daud lebih mencengangkan lagi. Al-Qur’an
menggambarkan keduanya sebagai raja dan hakim yang adil dan bijaksana. Namun
Sulaiman memiliki intuisi yudisial yang lebih tajam.
Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu;
Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu. Kami juga telah menundukkan gunung-gunung dan burung-burung; semua bertasbih bersama Daud. Kamilah yang melakukannya.90
Diriwayatkan bahwa ketika perkara itu diajukan kepada Daud, ia memutuskan bahwa
kambing-kambing itu diserahkan kepada pemilik tanaman. Ketika mereka keluar dari
“ruang persidangan,” Sulaiman, yang pada waktu itu dikatakan masih berusia sebelas
tahun,91 bertanya perihal keputusan yang diberikan kepada mereka, dan mereka
menceritakan sebagaimana adanya. Sulaiman mendekati ayahnya dan mengajukan
sebuah solusi yang menurutnya lebih tepat. Kambing-kambing itu, kata Sulaiman,
hendaklah diserahkan kepada pemilik kebun untuk diambil susu, bulu dan anak-
anaknya, sementara kebun itu diserahkan kepada pemilik kambing agar ia
merawatnya. Setelah kebun itu kembali seperti sedia kala, masing-masing mereka
saling mengembalikan kambing-kambing dan kebun tersebut kepada pemiliknya.
Daud sangat setuju dan memutuskan kembali perkara itu sesuai saran anaknya
Sulaiman. Karena itulah Allah berfirman: fa fahhamnāhā sulaymān ...92
Dalam al-Qur’an Sulaiman digambarkan sebagai seorang penguasa universal,
kerajaannya meliputi masyarakat manusia, binatang dan juga makhluk spirit atau jin.
Binatang-binatang pun berbicara dengannya; mereka tunduk dan taat. Kisah
kehidupan Sulaiman sebagai seorang raja penguasa semesta berkelindan dengan
berbagai legenda menakjubkan – pembicaraannya dengan semut dan burung hud-
90Q.S. al-Anbiyā’: 78-79.
91Al-Bayd}āwī, Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996 M./1416 H.), Vol. 4, 102.
92Lihat Ibid. dan Ibn Katsīr, Tafsīr, Vol. 3, 187.
hud,93 kemampuannya mengerahkan angin untuk membawanya terbang,94 sampai
kepada kehebatannya menundukkan jin untuk bekerja membangun gedung-gedung,
istana dan Kuil tempat ibadah.95
Narasi ihwal hubungan Sulaiman dengan ratu Saba’ dikisahkan agak
panjang.96 Berawal dari cerita yang disampaikan burung hud-hud tentang negeri
seberang yang disaksikannya, Sulaiman tertarik untuk menyampaikan pesan risalah
kepada ratu dan penduduk negeri itu. Ratu dan kaum penyembah matahari itu
disurati oleh Sulaiman, diperintahkan agar tunduk dan menyerah kepadanya. Sang
Ratu, demi ketenteraman negerinya, memandang bahwa tidak bijaksana melawan
seorang Raja yang perkasa. Ia mencoba mengirimkan sebuah hadiah. Namun hadiah
seperti itu tidaklah bermakna apa-apa bagi seorang Sulaiman. Ia mengancam akan
menyerang. Maka bagi Ratu Saba’ tidak ada pilihan yang dianggap lebih tepat selain
tunduk dan menyerah. Sulaiman berencana membuat sebuah kejutan. Sebelum
datangnya Ratu Saba’ menyerahkan diri, Sulaiman bertanya siapa di antara bala
tentaranya yang sanggup memindahkan istana Ratu tersebut ke hadapannya. ‘Ifrīt,
seorang jin, menyatakan sanggup melakukannya sebelum Sulaiman berdiri dari
tempat duduknya. Namun seseorang yang memperoleh ilmu dari al-kitāb sanggup
melakukannya lebih cepat, sekejap mata. Tiba-tiba saja, Sulaiman melihat istana
tersebut telah berada di depan matanya. Lalu:
93Q.S. al-Naml: 16-28
94Q.S. al-Anbiyā’: 81.
95Q.S. Saba’: 12-13.
96Q.S. al-Naml: 20-44.
Ketika ia (Ratu tersebut) datang, ditanyakanlah kepadanya: “Apakah seperti ini singgasanamu?” Dia menjawab: “Seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri (muslimīn).”97
Narasi ini agak berbeda dari kisah dalam Bible98 yang sangat panjang dan
mendetil, di mana disebutkan bahwa kepada Sulaiman diajukan sejumlah pertanyaan
oleh Ratu Saba’ untuk membuktikan segala berita yang telah ia dengar tentangnya.
Sulaiman menjawab semuanya, dan Ratu itu menyatakan kesaksiannya atas
keagungan dan kebijaksanaan Sulaiman. Mereka lalu saling menukarkan hadiah,
layaknya yang dilakukan raja-raja. Namun elemen moral dan ketauhidan tampak
menonjol dari pesan al-Qur’an. Kisah ini, dalam al-Qur’an, merupakan bagian dari
serial kisah-kisah tentang para nabi dan misi risalah yang diembannya. Ayat-ayat
sebelum dan sesudahnya memperlihatkan berbagai konfrontasi antara nabi-nabi dan
kaum yang dihadapinya – Musa dan Firaun (7-14), Saleh dan kaum Tsamūd (45-53),
Lūt} dan kehancuran kaum Sodom (54-58). Kisah Sulaiman dan Ratu Saba’ adalah
di antara seri kisah-kisah itu. Jika kaum-kaum yang lain mengalami kehancuran
karena menentang risalah para nabi, Ratu Saba’ terselamatkan karena ia tunduk dan
percaya pada seruan Tuhan.
Sulaiman mencapai kejayaan yang luar biasa dan unik. Puncak kejayaannya
tergambar dari bangunan-bangunan dan istana yang megah, hasil karya jin yang
tunduk di bawah kekuasaannya.
Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya: gedung-gedung yang tinggi, patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga
97Ibid., 42.
98Lihat 1 Kings 10: 1-13.
Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih.99
Sebagai seorang raja dengan karunia yang melimpah, kehidupan Sulaiman bukan
tanpa godaan yang melalaikan. Sebagaimana ayahnya, Sulaiman juga pernah terjebak
dalam ujian, yakni “pada saat dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang
ketika berhenti dan cepat ketika berlari pada waktu sore.” Sulaiman sangat
menyukainya sampai ia lalai dari “mengingat Tuhan.” Ketika sadar akan
kekeliruannya, Sulaiman meminta kuda itu dibawakan kembali kepadanya lalu ia
memotong kaki dan lehernya.100 Kekuasaan dan kekayaan tidak terlepas dari godaan
yang menggoyahkan. Seorang raja yang bijaksana atau nabi yang taat pun terkadang
juga luluh dalam menghadapinya. Namun jalan keluar selalu diberikan Tuhan.
Sepertinya inilah yang ingin diingatkan al-Qur’an dalam kisah tersebut.
Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah karena sakit), kemudian ia bertaubat.101
Berakhirnya kerajaan Sulaiman menandai berakhirnya ketenteraman dalam
dinasti Bani Israil. Perpecahan demi perpecahan terjadi sampai sebuah petaka besar
menimpa mereka. Israel, yang telah pecah menjadi Israel sebelah utara dan Yehuda
sebelah selatan, kini sudah menjadi amat lemah dan mudah dihancurkan musuh.
Nebukadnezar, penguasa Babilonia, mengalahkan Jerussalem pada 597 SM. dan
kemudian menghancurkannya secara total pada 586 SM. Penduduknya dibunuh dan
99Q.S. Saba’: 13.
100Q.S. S{ād: 30-34.
101Ibid., 34.
kotanya dihancurkan. Semua tawanan diangkut sebagai budak ke Babilonia.102
Kehancuran inilah mungkin yang disebutkan al-Qur’an sebagai hukuman bagi Bani
Israil karena kesombongan dan pengabaian mereka atas perintah Allah.
Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam kitab itu: “Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.”
Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.103
Inilah destruksi pertama, yang dilakukan Nebukadnezar yang menghancurkan
seluruh negeri Bani Israil. Namun pada 358 SM., Cirus II dari Persia mengalahkan
Babilonia dan membiarkan orang-orang Israel pulang ke Yerusalem, membangun
negerinya dan membina kembali Kuil (Temple) yang telah dihancurkan. Yerusalem
kembali mengalami kejayaan hingga zaman penjajahan Romawi, di mana Kuil
tersebut dihancurkan lagi untuk kedua kalinya pada 70 M.104 Al-Qur’an mengatakan
(lanjutan ayat di atas):
Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
Jika kamu berbuat baik (itu berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri juga, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid (Temple), sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.105
102Mengenai kejatuhan Yerusalem, lihat 2Kings 23: 31 – 25: 30.
103Q.S. al-Isrā’: 4-5.
104Encyclopaedia Britannica, s.v. “Yerusalem, Temple of,” Deluxe Edition 2004 CD-ROM.
Kanaan adalah negeri kuno yang diduduki bangsa Yahudi selama berabad-
abad, dan sampai hari ini mereka tetap enggan meninggalkannya. Di sana mereka
hidup berperang dan berdamai, mengalahkan musuh dan dikalahkan, diusir dan
kembali lagi. Al-Qur’an menggambarkan kehidupan Bani Israil di negeri itu penuh
dinamika dan menjadi pelajaran bagi umat yang percaya kepadanya. Kejayaan,
kemenangan dan ketenteraman hidup adalah anugerah Tuhan; karena itu harus
disyukuri. Siapa yang berlaku sombong dan durhaka terhadap titah Tuhan, mudah
saja bagi Tuhan untuk menghancurkannya. Namun Tuhan selalu menawarkan jalan
keselamatan, meski kepada mereka yang telah berulang kali melakukan kesalahan.
Tampak, ayat-ayat di atas terutama ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang
dianggap kembali melakukan kesombongan dengan melawan risalah yang dibawa
Nabi Muhammad. Maka kepada mereka diberikan alternatif (lanjutan ayat di atas):
Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat (Nya) kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan), niscaya Kami kembali (mengazabmu) dan Kami jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.106
Berdasarkan uraian-uraian di atas dalam sub bab ini, dapat disimpulkan
bahwa kisah-kisah tentang umat Yahudi dalam al-Qur’an penuh dengan pujian-
pujian; mereka berasal dari keturunan orang-orang yang dimuliakan Tuhan, dan
dalam sejarah perjalanan hidup mereka Tuhan telah menunjukkan berbagai karunia
yang luar biasa. Poin yang menarik dari pembahasan di atas adalah bahwa ternyata
ayat-ayat yang mengedepankan aspek-aspek positif dari kisah umat Yahudi
umumnya diturunkan pada periode Makkiyyah. Ayat-ayat tersebut terdapat,
105Q.S. al-Isrā’: 6-7.
106Ibid., 8.
misalnya, dalam surat al-An‘ām, Yūsuf, al-Isrā’, al-Anbiyā’, al-Naml dan Saba’.
Sementara itu beberapa ayat yang lain diturunkan di Medinah pada masa awal hijrah,
yaitu ayat-ayat pada bagian awal surat al-Baqarah. Hal ini menggambarkan
karakteristik seruan al-Qur’an pada periode tersebut yang bersifat universal dan lebih
menekankan aspek moral dan ketauhidan. Ayat-ayat tersebut diturunkan lebih
sebagai pelajaran dan peringatan kepada Nabi dan kaum Muslim agar menghadapi
perjuangan dengan tabah dan supaya yakin bahwa kebenaran pada akhirnya akan
menang. Di samping itu, Al-Qur’an telah memberikan penjelasan yang berimbang,
yaitu bahwa umat Yahudi juga telah melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat
pada murka Tuhan. Di sinilah al-Qur’an mengajukan tawaran kepada kebenaran serta
mengingatkan akan beratnya penderitaan yang akan diterima oleh mereka yang
berbuat durhaka.
B. Pandangan Keagamaan Umat Yahudi
Sejak awal, Nabi Muhammad telah menunjukkan sikap positif dan apresiatif
terhadap kaum Yahudi di Medinah. Sebagaimana telah didiskusikan, Nabi sangat
mengharapkan mereka menjadi pendukungnya dalam dakwah menyampaikan
risalah Tuhan, sebab mereka adalah juga umat yang memiliki kitab dari Tuhan. Al-
Qur’an, melanjutkan tradisi Arab sebelumnya, memanggil mereka ahl al-kitāb. Jadi
al-Qur’an telah mengenal kaum Yahudi sebagai umat dengan ajaran dan
keyakinannya sendiri. Namun interaksi Nabi Muhammad dengan umat Yahudi di
Medinah telah melahirkan berbagai perdebatan keagamaan dan telah menginspirasi
sejumlah ayat-ayat al-Qur’an yang bahkan dengan keras mengkritik mereka. Berikut,
pandangan-pandangan keagamaan Yahudi sebagaimana dipresentasikan al-Qur’an
didiskusikan dengan menggunakan pendekatan historis, analisis komparatif dan
kritik teks.
Sikap dan pandangan al-Qur’an terhadap keyakinan keagamaan umat Yahudi
merefleksikan pergumulan historis Nabi Islam dengan sebuah umat yang telah
memiliki keyakinan mapan namun ditantang untuk bersikap jujur, hormat dan
terbuka berhadapan dengan sebuah risalah baru yang juga menampilkan watak dasar
yang sama. Pada bagian ini kritik-kritik al-Qur’an tampak semakin mendasar, namun
perlu dicermati dengan seksama konteks dan realitas historisnya, serta sejauh mana
jangkauan kritik tersebut telah mengkristal secara dogmatik dan kultural dalam
tradisi Islam.
1. Monoteisme
Monoteisme adalah keyakinan akan satu Tuhan, Pencipta dan Pemelihara
semesta ini, yang telah memberi segala anugerah kepada makhluk-Nya dan
berkomunikasi dengan hamba-hamba-Nya melalui doa-doa dan penyembahan;
Penguasa yang tiada batas namun penuh kasih sayang, Penentu segalanya namun
telah menetapkan hukum-hukum keteraturan pada alam; Maha Awal dan Maha
Akhir; tidak seorang pun bersekutu dengan-Nya; Ia Maha Sendiri.
Yahudi dan Islam termasuk agama monoteis yang ketat. Kedua agama ini
sangat sensitif mengenai penggambaran tentang Tuhan dan pengasosiasian Tuhan
dengan sesuatu yang lain. Patung-patung dilarang dengan keras dan syirik
(menyekutukan Tuhan) adalah dosa besar. Di antara prinsip-prinsip keyakinan
Yahudi, sebagaimana diformulasikan oleh Moses Maimonides (1135-1204), seorang
tokoh terkemuka Yahudi abad tengah, adalah bahwa Tuhan itu Esa, Pencipta alam
semesta dan tidak ada satu pun yang menyerupai-Nya; Ia Maha Kekal, tidak berawal
dan tidak berakhir; dan hanya kepada-Nya tempat berdoa.107
Shema (“Hear”, artinya: “Dengarlah”), yang telah menjadi syahadat atau
semacam kesaksian umat Yahudi, yang dibaca pagi dan petang, berasal dari salah
satu ayat Taurat: HEAR, O ISRAEL: THE LORD OUR GOD, THE LORD IS ONE.108
Dalam Shema, ayat ini (Deuteronomy 6: 4) kemudian diikuti dengan ayat 5-9, 11: 13-
21 dan Number 15: 37-41. Shema dibacakan bersama dengan doa-doa malam dan
siang, sebelum tidur dan waktu bangun. Orang-orang saleh bahkan berharap
meninggal dalam keadaan bibirnya sedang mengucapkan kalimat tersebut. Seperti
syahadat dalam Islam, kesaksian ini mempunyai makna yang cukup dalam; bukan
hanya sebuah ucapan di mulut semata, tetapi sebuah deklarasi dan pengakuan yang
sungguh-sungguh akan kebesaran Tuhan dan ketundukan yang tulus kepada-Nya.
Kesaksian itu berimplikasi pada sikap dan kehidupan sehari-hari. Dalam Mishnah,
pembacaan Shema disebutkan sebagai the taking-on of the yoke of the Kingdom of
107Louis Jacob, The Book of Jewish Belief, (Behrman House, t.t.), 5.
108Deuteronomy 6: 4.
Heaven,109 yakni sebagai the acceptance of God as Creator and Lord of the universe
with the implications of this belief for the conduct of human life.110
Dalam Shema tersebut terlihat dengan jelas prinsip paling mendasar dari
keyakinan umat Yahudi terhadap keesaan Tuhan dan bahwa keyakinan tersebut harus
diterapkan dalam kehidupan keseharian. Al-Qur’an, seperti telah dikutip sebelumnya,
menggambarkan saat-saat Bani Israil di Mesir bersama Nabi Musa masih dalam
tekanan politik Firaun, ketika Musa menyeru mereka untuk tetap bertawakkal, dan
mereka menyambutnya dengan baik:
Musa berkata: “Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakkallah hanya kepada-Nya, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri.”
Lalu mereka menjawab: “Kepada Allah jua kami bertawakkal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim.”
“Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari (tipu daya) orang-orang yang kafir.”111
Ayat-ayat ini memperlihatkan sikap keberagamaan mereka dan ketulusan
mereka dalam mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah prinsip dasar dari
ajaran Musa (nabi Yahudi), yang juga tidak berbeda dari fondasi dasar ajaran Islam.
Pertanyaannya, mengapa kemudian bangsa Yahudi melakukan penyimpangan-
penyimpangan? Mengapa mereka menyembah anak lembu emas, membangkang
kepada Tuhan dan Nabi serta melakukan kesalahan-kesalahan lain? Ini sebenarnya
hanya menyangkut perilaku individunya dan tidak dapat dikaitkan dengan dasar-
109Jacob Neusner, The Mishnah: A New Translation, (New Haven: Yale University Press, 1988), Berakhot, 2. 2.
110Louis Jacobs, The Jewish Religion: A Companion, (Oxford: Oxford University Press, 1995), 462.
111Q.S. Yūnus: 84-86.
dasar ajaran yang mereka terima. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sikap
positif yang dikemukakan al-Qur’an di atas terlihat pada saat mereka dalam tekanan
Firaun dan mereka sedang memiliki harapan besar untuk keluar darinya. Karena itu
tidak mengherankan ketika ditemukan adanya perubahan besar dalam watak
keagamaan mereka setelah melewati semua penderitaan tersebut. Seperti telah
dibicarakan sebelumnya, al-Qur’an mengutip sejumlah perilaku Bani Israil yang
sangat tidak respek dan tidak berterima kasih, dalam pengembaraan mereka di Sinai
menuju Kanaan. Memang bukan otoritas siapa pun untuk menilai ketulusan dan
keimanan seseorang. Namun sesungguhnya agama itu sendiri sebagai sebuah
perilaku, seperti kata James B. Pratt, memiliki aspek “subjektif” dan “objektif.”112
Orang kadang-kadang menjadi tekun dan “khusyu‘” pada saat-saat ingin melakukan
“petisi” atau sangat berharap kepada Tuhan, tetapi kemudian dapat bahkan sama
sekali melupakan Tuhan. Ini adalah model agama subjektif; ia sangat terkonsentrasi
pada suasana psikologis dan reaksi seseorang terhadap kondisi diri dan dunia
sekitarnya. Sementara itu, agama objektif terfokus pada kesadaran dan responnya
terhadap Tuhan. Ia merupakan kesadaran batin yang dalam dan terlahir sebagai hasil
pandangan dan sikap objektif dalam memahami makna agama dan konsep-konsep
tentang Tuhan.
Pandangan psikologis ini barangkali dapat menjelaskan mengapa terjadi
perubahan paradigma dalam sikap moral dan keagamaan Bani Israil setelah
mengalami kelepasan dari kezaliman Firaun, dan dalam hal ini al-Qur’an sangat
tajam menyorot tingkah laku mereka tersebut, sehingga dalam tradisi Muslim seolah-
112James B. Pratt, The Religious Consciousness: A Psychological Study, (New York: The Macmillan Co., 1920), Lihat penjelasan dalam bab 14 dan 15.
olah itulah watak sesungguhnya umat Yahudi sepanjang sejarah – sebuah kekejian
yang dianggap tidak mungkin terobati. Umat mana pun pada dasarnya akan
mengalami berbagai dinamika dan perubahan dalam sikap beragama, dan sejarah
Islam telah menunjukkan fluktuasi yang luar biasa dalam hal ini. Lahirnya berbagai
firqah, perdebatan soal kalām, munculnya mazhab-mazhab, penutupan pintu ijtihad
dan gagasan-gagasan kebangkitan kembali Islam adalah realitas yang begitu jelas
memperlihatkan dinamika tersebut; dan masa-masa pencerahan serta kebodohan
adalah bagian tidak terpisahkan darinya.
Monoteisme adalah prinsip yang paling mendasar dari ajaran agama Yahudi,
dari sejak awal pertumbuhannya sampai hari ini. Monoteisme bahkan telah diklaim
sebagai kontribusi paling mendasar dari Yudaisme bagi pemikiran keagamaan Timur
Tengah.113 Namun dalam tradisi Islam, hal ini umumnya jarang diapresiasi. Ayat al-
Qur’an yang paling populer dikutip dalam mengkritik pandangan teologi Yahudi
adalah al-Tawbah: 30:
Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair adalah putera Allah” dan orang Nasrani berkata: “Almasih adalah putera Allah.” Demikian itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka; mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Tuhan melaknat mereka; mengapa mereka sampai berpaling?
Pembacaan sekilas terhadap ayat ini tidak diragukan akan menimbulkan
kesan yang jelas bahwa orang-orang Yahudi telah syirik; mereka mengatakan Tuhan
mempunyai anak, yaitu Uzair. Ini berarti sangat bertentangan dengan monoteisme.
Seorang penulis Muslim yang mencoba “mengungkap kelicikan Yahudi,” mengutip
ayat ini sebagai salah satu bukti “kelicikan Yahudi pada Allah SWT,” tanpa
113 Huston Smith, The World’s Religions: Our Great Wisdom Traditions, (New York: HarperCollins, 1991), 274.
memberikan komentar apa pun.114 Dalam tafsir Fath} al-Qadīr, komentar terhadap
ayat ini dimulai dengan pernyataan bahwa “kalimat tersebut dinyatakan sebagai
mengawali penjelasan mengenai kesyirikan orang-orang Ahli Kitab.” Komentar
dilanjutkan dengan mendiskusikan perbedaan pendapat di kalangan para mufassir
soal apakah ayat itu bersifat umum atau khusus: apakah semua orang Yahudi
mengatakan demikian atau hanya sebagian dari mereka saja? Al-Syawkānī (w. 1250
H.), pengarang kitab tafsir tersebut, pada akhirnya menyimpulkan sebagai berikut:
Ayat di atas diturunkan karena ucapan mereka kepada Nabi Muhammad bahwa Uzair
adalah anak Tuhan. Memang yang mengucapkan itu adalah sebagian mereka, namun
berlaku untuk semuanya.115 Dalam tafsir Ibn Katsīr, sebuah kitab tafsir yang anggap
telah menjadi pegangan kalangan Sunni, komentar yang diberikan juga tidak
berbeda. Menurut Ibn Katsīr (w. 1373 M./774 H.), ayat tersebut merupakan seruan
Allah kepada orang-orang Mukmin untuk memerangi orang-orang kafir Yahudi dan
Nasrani karena ucapan-ucapan keji mereka terhadap Allah. Orang-orang Yahudi
berkata bahwa Uzair putera Allah dan orang Nasrani berkata Almasih putera Allah.
“Maha Suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan itu.”116
Pandangan kaum Muslim terhadap keyakinan umat Yahudi seperti di atas
mencerminkan kurangnya akses mereka ke literatur Yahudi. Karena al-Qur’an
berbicara tentang Yahudi, maka dianggap bahwa apa yang dikatakan al-Qur’an sudah
cukup memadai untuk memahami apa Yahudi itu sesungguhnya, tanpa merasa perlu
114M. Didik Hariyanto, Mengungkap Kelicikan Yahudi dalam al-Qur’an, Hadis, dan Sejarah, (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002), 57.
115Al-Syawkānī, Fath} al-Qadīr, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Vol. 2, 352.
116Ibn Katsīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Az}īm, (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H.), Vol 2, 349.
membuka mata terhadap realitas dan mempelajari konteks historis ayat-ayat al-
Qur’an tersebut diturunkan. Berbeda dari kebanyakan peminat hadis, kaum dogmatik
dan skripturalis, ulama yang sejarawan umumnya memiliki pandangan yang lebih
luas dan mereka menyadari problem tafsir itu harus dipecahkan dengan tanpa
mengabaikan realitas sejarah dan sosial budaya. Persoalannya adalah apakah
pernyataan al-Qur’an tersebut dapat digeneralisasikan kepada semua orang Yahudi di
seluruh dunia, sehingga mereka berhak dikutuk sebagaimana dikatakan al-Qur’an?
Komunikasi global dan sistem informasi yang tidak lagi mengenal batas waktu dan
jarak serta interaksi peradaban yang semakin intens menuntut setiap orang atau
kelompok mempertimbangkan berbagai sikap dan hubungannya dengan “orang lain.”
Siapa pun yang peduli dengan kehidupan umat beragama di Amerika, misalnya, atau
di negara-negara yang memiliki penduduk umat Yahudi dan Nasrani, atau siapa pun
yang pernah memiliki kontak sosial atau personal dengan orang Yahudi, atau sedikit
banyak mengenal literatur Yahudi dan Nasrani, akan mempertanyakan: benarkan
orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan?, dan menemukan pernyataan al-
Qur’an tersebut “bermasalah.” Bahkan bagi sebagian pemikir Barat, seperti William
Montgomery Watt dan John Van Seters – sebagaimana dikutip Hamim Ilyas –
pernyataan al-Qur’an tersebut merupakan kesalahan pokok atau sesuatu yang ganjil
dan tidak memiliki dasar yang jelas dari sumber Yahudi mana pun.117 Tentu saja
sebaliknya seorang Muslim fanatik mungkin akan berkata bahwa Yahudi telah
berdusta kalau mengatakan tidak menyembah Ezra dan mereka tentu saja
menyembunyikan kesalahannya itu. Ketika seorang “Imam” di Amerika Serikat
117Hamim Ilyas, Pandangan Al-Qur’an Terhadap Ahli Kitab: Studi Tafsir Al-Manar, Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001, 158.
ditanyakan mengenai isu Ezra dalam al-Qur’an, ia menjawab: “We don't know” what
they really believe and say and do in their synagogues, so they may very well
worship Ezra!118
Namun sebenarnya persoalan ini tidaklah baru dan telah disadari oleh
sebagian sarjana Muslim sejak masa awal. Persoalan ayat yang didiskusikan di atas
bukan tidak menimbulkan problem di kalangan para pemikir Muslim yang serius
sejak zaman klasik. Mereka hidup bersama dan berinteraksi dengan orang-orang
Yahudi, namun tidak menemukan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak
Tuhan. Sementara itu orang-orang Yahudi sendiri menolak konsep ketuhanan Yesus
sebagaimana didakwakan oleh orang-orang Nasrani. Tuhan tidak beranak dan tidak
bersekutu dengan siapa pun jua. Lalu bagaimana menjelaskan statemen al-Qur’an
tersebut di atas?
Menyadari hal ini, para mufassir zaman awal menemukan sedikit petunjuk
dari riwayat-riwayat mengenai konteks historis turunnya ayat tersebut. Al-T{abarī
(w. 923 M./310 H.), seorang mufassir yang juga sejarawan, misalnya,
mengemukakan sebuah riwayat dari al-Qāsim, yang berasal dari ‘Adullah ibn ‘Ubayd
ibn ‘Umayr, bahwa “Uzair anak Allah” telah diucapkan oleh hanya seorang yang
dikenal bernama Finh}ās}. Disebutkan pula bahwa dialah orang yang mengatakan
bahwa “Allah itu fakir dan kami kaya.”119 Riwayat lain, yang berasal dari Ibn ‘Abbās,
menyebutkan bahwa empat orang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad dan
berkata: “Bagaimana kami mengikuti engkau, sementara engkau telah meninggalkan
118<http://www.secularislam.net/Secular Islam_NET Jews in the Qur’an.htm>.
119Al-T{abarī, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta'wīl Āy al-Qur’an (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H.), Vol. 10, 110.
kiblat kami dan engkau tidak mengakui Uzair anak Tuhan,” maka turunlah ayat
tersebut.
Dengan demikian, sebagaimana disimpulkan al-Qurt}ubī (w. 671),120
pernyataan al-Qur’an itu hanya merujuk kepada seorang atau sekelompok Yahudi di
Medinah pada zaman turunnya wahyu tersebut, tidak kepada semua umat Yahudi.
Gagasan Uzair anak Tuhan tidak pernah terdapat secara eksplisit dalam mainstream
Yudaisme, namun beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa sejumlah orang
Yahudi telah mengasosiasikan Uzair dengan sifat-sifat Ketuhanan dapat ditemukan.
Menurut Reuven Firestone:
While it is clear that Judaism as a religious civilization does not accept the view that God has partners or children, it is probable that some fringe groups pushed the limits of acceptable belief with the important figure of Ezra. Two ancient and originally Jewish books, for example, associate a near-divine or angelic status to the biblical personages of Ezra and Enoch. These are 4 Ezra, also known as 2 Esdras 14:9, 50 and 2 Enoch 22:11. Although composed by Jews, both of these books were rejected by Judaism.121
Sangat mungkin bahwa sejumlah orang Yahudi dari sekte tersebut yang hidup
di Medinah zaman Nabi Muhammad telah mengekspresikan keyakinan demikian,
sehingga turunlah ayat yang menolak pandangan mereka. Keterangan ini, sekurang-
kurangnya, telah memberikan penjelasan yang lebih baik bagaimana “tuduhan” al-
Qur’an tersebut dapat diletakkan dalam konteks historisnya secara lebih realistik.
Penjelasan ini sekaligus merupakan hujah untuk menegaskan bahwa pembicaraan al-
Qur’an tentang sebuah realitas mesti dipahami dalam konteks sosial dan historis
120Al-Qurt}ubī, al-Jāmi‘ li Ah}kām al-Qur’ān, (Kairo: Dār al-Sya‘b, Cet. II, 1372 H.), Vol. 8, 116.
121Diskusi melalui e-mail dengan Prof. Reuven Firestone, Direktur Institute for the Study of Jewish-Muslim Interrelations, Hebrew Union College, 18 Nopember 2003. Lihat bukunya, Children of Abraham: An Introduction to Judaism for Muslims, (Hoboken: Ktav Publishing House, 2001), 35-36.
secara tepat. Kritik Watt dan Seters di atas menjadi tidak proporsional, karena
mereka telah memahami pernyataan al-Qur’an dalam surat al-Tawbah: 30 itu terlepas
dari konteksnya.
2. Perjanjian dengan Tuhan
Istilah covenant dalam bahasa Inggris, yang bermakna perjanjian atau kontrak
yang menimbulkan hak dan kewajiban secara mutual, dalam pengertian khusus
dikenal sebagai perjanjian antara Tuhan dan Bani Israil; dalam bahasa Hebrew
disebut berit. Covenant termasuk konsep teologi yang memiliki makna unik bagi
kaum Bani Israil. Ibrahim adalah orang pertama yang mengadakan perjanjian
tersebut dengan Tuhan secara lebih khusus, setelah sebuah covenant universal terjadi
antara Tuhan dan Nabi Nuh beserta anak cucunya dan seluruh makhluk hidup di
permukaan bumi, di mana Tuhan berjanji tidak akan pernah lagi mengirim banjir
untuk menghancurkan dunia ini.122 Dengan Ibrahim Tuhan membuat perjanjian lebih
personal:
(7) And He said unto him: ‘I am the LORD that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it.’ (8) And he said: ‘O Lord GOD, whereby shall I know that I shall inherit it?’ (9) And He said unto him: ‘Take Me a heifer of three years old, and a she-goat of three years old, and a ram of three years old, and a turtle-dove, and a young pigeon.’ (10) And he took him all these, and divided them in the midst, and laid each half over against the other; but the birds divided he not. (11) And the birds of prey came down upon the carcasses, and Abram drove them away. (12) And it came to pass, that, when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, a dread, even a great darkness, fell upon him. (13) And He said unto Abram: ‘Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years; (14)
122Genesis 9: 8-17.
and also that nation, whom they shall serve, will I judge; and afterward shall they come out with great substance. (15) But thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age. (16) And in the fourth generation they shall come back hither; for the iniquity of the Amorite is not yet full.’ (17) And it came to pass, that, when the sun went down, and there was thick darkness, behold a smoking furnace, and a flaming torch that passed between these pieces. (18) In that day the LORD made a covenant with Abram, saying: ‘Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates; (19) the Kenite, and the Kenizzite, and the Kadmonite, (20) and the Hittite, and the Perizzite, and the Rephaim, (21) and the Amorite, and the Canaanite, and the Girgashite, and the Jebusite.’123
Bagi Bani Israil atau orang-orang Yahudi, perjanjian inilah di antara lain
yang dianggap telah menempatkan mereka pada posisi khusus di antara umat-umat
lain di dunia, seperti akan didiskusikan nanti. Lebih jauh, Ibrahim juga diperintahkan
untuk menyatakan perjanjiannya dengan melakukan khitan,124 sebuah tanda
perjanjian yang dimanifestasikan dalam bentuk jasmaniah – the ‘sign in the flesh’.125
Dalam masyarakat kuno, perjanjian sering diekspresikan dalam bentuk sumpah atau
pengutukan terhadap diri sendiri jika seseorang itu tidak jujur atau tidak menepati
janjinya. Kutukan tersebut kadang-kadang disimbolkan dalam bentuk yang lebih
nyata dan tertera, seperti memotong binatang. Ekspresi simbolik inilah yang
dinyatakan oleh ritual khitan yang dilakukan Nabi Ibrahim bersama keluarga dan
pengikutnya. Itulah tanda yang tertera secara jasmaniah, sebagai pernyataan simbolik
akan komitmen dan ketundukannya kepada Tuhan.
Bagi orang-orang Yahudi, tradisi khitan telah dianggap sebagai bagian dari
ritual yang harus dilaksanakan, sebagai pertanda bahwa seseorang telah menyatakan 123Genesis 15: 7-21.
124Genesis 17: 10-11.
125Louis Jacobs, The Jewish Religion: A Companion, (Oxford: Oxford University Press, 1995), 81.
janjinya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tertera secara fisikal pada
jasmaninya. Dalam tradisi Islam, khitan juga umumnya dianggap sebagai amal yang
dianjurkan dan bahkan sebagian ulama mengatakannya wajib.126 Dalam al-Qur’an
perintah khitan tidak disebutkan; hanya ada beberapa hadis yang mengindikasikan
bahwa khitan adalah bagian dari upaya mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan dianggap
sebagai salah satu dari fit}rah manusia.127 Di samping karena alasan kesehatan dan
kebersihan, dalam tradisi Islam, khitan juga dianggap sebagai simbol pemisahan diri
dari orang-orang kafir.
Lebih lanjut, covenant juga merupakan sebuah hubungan spesial Bani Israil
dengan Tuhan, di mana Tuhan memberi mereka anugerah dan karunia yang banyak,
sebagai imbalan atas ketundukan, komitmen dan loyalitas mereka kepada-Nya. Di
Sinai Tuhan telah membuat perjanjian dengan Bani Israil, melalui Musa, bahwa
mereka akan diangkat menjadi umat pilihan jika mereka tetap memelihara perintah-
perintah-Nya.
(19: 5) Now therefore, if ye will hearken unto My voice indeed, and keep My covenant, then ye shall be Mine own treasure from among all peoples; for all the earth is Mine.
(24:1) And unto Moses He said: ‘Come up unto the LORD, thou, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel; and worship ye afar off; (2) and Moses alone shall come near unto the LORD; but they shall not come near; neither shall the people go up with him’. (3) And Moses came
126Menurut mazhab Mālik dan mazhab Abū H{anīfah, khitan hukumnya sunnah mu’akkadah bagi laki-laki, dan hanya sebagai penghormatan bagi perempuan; sedangkan menurut mazhab al-Syāfi‘ī, wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sementara itu Imam Ah}mad mengatakan, wajib bagi laki-laki dan dianjurkan bagi perempuan. Lihat Wahbah al-Zuh}aylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), Vol. 4, 2752.
127Lihat misalnya al-Bukhārī, S{ah}īh} al-Bukhārī, (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1987 M./1407 H.), Vol. 3, 1224: Hadis No. 3178; Mālik, al-Muwat}t}a’, (Mesir: Dār Ih}yā’ al-Turāts al-‘Arabī, t.t.), Vol. 2, 922: Hadis No. 1642; Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, (Dār al-Fikr, t.t.), Vol. 1, 14: Hadis No. 53.
and told the people all the words of the LORD, and all the ordinances; and all the people answered with one voice, and said: ‘All the words which the Lord hath spoken will we do’. (4) And Moses wrote all the words of the LORD, and rose up early in the morning, and builded an altar under the mount, and twelve pillars, according to the twelve tribes of Israel. (5) And he sent the young men of the children of Israel, who offered burnt-offerings, and sacrificed peace-offerings of oxen unto the LORD. (6) And Moses took half of the blood, and put it in basins; and half of the blood he dashed against the altar. (7) And he took the book of the covenant, and read in the hearing of the people; and they said: 'All that the LORD hath spoken will we do, and obey’. (8) And Moses took the blood, and sprinkled it on the people, and said: 'Behold the blood of the covenant, which the LORD hath made with you in agreement with all these words’.128
Covenant begitu bermakna dalam tradisi keagamaan orang Yahudi, sehingga
kritik-kritik al-Qur’an juga dinyatakan dalam bentuk mengingatkan mereka terhadap
janji-janji dengan Tuhan tersebut.
Wahai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut.129
Kata covenant atau perjanjian, pada prinsipnya, ekuivalen dengan kata ‘ahd
dan mītsāq (dari kata kerja watsaqa) dalam al-Qur’an. Kata ‘ahd, dengan berbagai
variasi, disebutkan sebanyak 46 kali dalam 17 surat; dan mītsāq 34 kali dalam 13
surat. Ini mencerminkan “kesadaran” al-Qur’an akan pentingnya konsep covenant
tersebut. Covenant memiliki akar yang sudah sangat tua dalam sejarah umat manusia.
Kaum Bani Israil tentu bukan yang pertama membuat konsep tersebut. Sangat
mungkin bahwa covenant telah dipraktikkan sejak zaman prasejarah, ditandai oleh
adanya kenyataan bahwa tiga milenium sebelum Masehi ia telah dikembangkan
sebagai salah satu instrumen politik. Dari berbagai observasi modern yang dilakukan
128Exodus 19: 5; 24: 1-8.
129Q.S. al-Baqarah: 40.
para antropolog, diketahui bahwa covenant, sejak zaman dahulu, telah dikembangkan
terutama sekali sebagai perjanjian kontrak perkawinan di antara para suku-suku yang
menganut eksogami, yakni perkawinan dilakukan di luar suku sendiri.130 Dari
pengalaman kontrak sosial dan politik inilah barangkali terinspirasi konsep covenant
bagi Bani Israil. Al-Qur’an bahkan memandang covenant ini telah ada sejak
keberadaan manusia itu sendiri. Adam yang disimbolkan sebagai moyang manusia
telah membuat perjanjian dengan Tuhan, meski kemudian ia tidak sanggup
memenuhinya dengan baik.
Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan (‘ahidnā) kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan Kami tidak mendapatinya memiliki kemauan yang kuat.131
Dalam perspektif al-Qur’an, perjanjian manusia dengan Tuhan merupakan
sebuah covenant primordial, yang abadi, dan telah ada sejak zaman immemorial serta
berlaku sepanjang sejarah manusia.
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: Benar (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi.” (Yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini.132
Setiap manusia dilahirkan bersama janji Tuhan, yakni fit}rah yang
dibawanya ke dunia ini. Janji itulah yang harus dipenuhinya selama ia hidup.
Manusia, dengan segala kelemahannya, berjuang menepati janjinya dengan Tuhan,
walau kadang-kadang ia terbentur dengan berbagai kesulitan dan masalah. Tuhan 130Encyclopaedia Britannica, s.v. “Origin and Function of Covenants,” Deluxe
Edition 2004 CD-ROM.
131Q.S. T{āhā: 115.
132Q.S. al-A‘rāf: 172.
memberi manusia pertolongan melalui berbagai fasilitas, seperti akal dan wahyu,
agar manusia dapat menyelamatkan dirinya dari berbagai godaan dan pelanggaran-
pelanggaran.
Jadi covenant yang dibuat Bani Israil dengan Tuhan tidaklah terlalu unik,
namun, dalam konteks zamannya, ia dapat dikatakan istimewa. Sementara bangsa-
bangsa lain yang ada pada waktu itu telah mengembangkan kontrak perjanjian sosial
dan politik antara sesama manusia, bangsa Israel telah menunjukkan kesadaran
spiritual yang lebih jauh: mereka menyatakan sumpah setia kepada Tuhan Yang
Gaib, yang diimani sebagai Pencipta dan Penguasa alam semesta ini.
Al-Qur’an mengenal perjanjian Bani Israil dengan Tuhan ini sebagai
perjanjian yang absah dan memiliki kekuatan dan makna religius yang mendalam.
Al-Qur’an hanya mengkritik orang-orang Yahudi yang dianggap justeru telah
mengabaikan perjanjian tersebut. Al-Qur’an, dalam hal ini, mengarahkan kritiknya
terhadap orang-orang Yahudi ihwal sikap mereka terhadap Nabi Muhammad dan
risalah yang beliau bawa. Penolakan mereka terhadap risalah Tuhan yang dibawa
Nabi Muhammad dianggap al-Qur’an sebagai bagian dari pelanggaran akan janji
tersebut, sebab keingkaran mereka tidak terlepas dari sikap arogansi dan
pembangkangan terhadap kebenaran dan keadilan, yang sama sekali tidak berbeda
dari apa yang telah mereka kenal dalam kitab mereka.
Pada sisi lain, al-Qur’an mengembangkan konsep covenant yang lebih
universal. Al-Qur’an mempertegas bahwa janji Tuhan tidak terkait dengan bangsa
atau etnis tertentu, tidak ditentukan oleh keturunan siapa, dan tidak pada institusi
atau kelompok mana seseorang mengasosiasikan diri. Janji Tuhan terkait dengan
komitmen moral dan ketundukan kepada-Nya semata. Tuhan juga tidak pernah
membuat janji-janji “murahan” untuk hal-hal yang “remeh”, atau janji-janji yang
bersifat diskriminatif. Watak universal inilah yang melandasi kritik-kritik al-Qur’an
terhadap covenant Bani Israil, yang dinilainya sudah terlalu dilebih-lebihkan.
Beberapa ayat berikut, sebagai contoh, memperlihatkan karakteristik dan gaya kritik
al-Qur’an tersebut.
Dan mereka berkata: “Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja.” Katakanlah: “Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?”133
Beberapa riwayat tentang sebab turun ayat ini memperlihatkan adanya
“pertengkaran” atau “perang mulut” antara Nabi dan orang-orang Yahudi.
Sepertinya, orang-orang Yahudi Medinah pada waktu, dengan pengetahuannya
tentang agama dan kitab wahyu, merasa sangat “percaya diri” dan menganggap
dirinya lebih superior dari orang-orang Arab dan bahkan Nabi Muhammad, sehingga
dengan mudah meremehkan orang lain dan dengan arogan mengucapkan kata-kata
sinis dan merendahkan. Mungkin dengan tujuan menciptakan kekesalan di pihak
Nabi, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan masuk neraka; kalau pun Tuhan
akan memasukkan mereka ke neraka, itu hanya beberapa hari saja. Maka turunlah
ayat tersebut di atas.134
Ayat tersebut jelas mencoba menjawab kesombongan orang-orang Yahudi
dengan nada sinis, dalam rangka mematahkan sikap mereka yang congkak. Al-
Qur’an menyangkal ucapan mereka dengan merujuk pada prinsip-prinsip kebenaran 133Q.S. al-Baqarah: 80.
134Syihāb al-Dīn Ah}mad ibn ‘Alī, al-‘Ujāb fī Bayān al-Asbāb, (al-Dammām: Dār Ibn al-Jawzī, 1997), Vol. 1, 276.
dan keadilan paling mendasar dan bahwa Tuhan tidak mungkin telah membuat janji-
janji yang tidak masuk akal dan berakibat pada kezaliman.
Ayat berikut lebih tajam lagi mengecam orang-orang Yahudi yang berpura-
pura beralasan dengan kitab suci untuk menolak risalah nabi Muhammad. Lalu al-
Qur’an merujuk pada sejarah mereka sendiri yang dicatat oleh kitab, bahwa mereka
telah membunuh nabi-nabi yang sebenarnya telah menunjukkan bukti-bukti nyata
kepada mereka. Al-Qur’an sepertinya ingin mengindikasikan bahwa mereka sama
sekali tidak memiliki niat baik terhadap Nabi dan perjuangan dakwahnya. Janji
Tuhan telah mereka permainkan untuk kepentingan nafsu semata; janji Tuhan hanya
dijadikan alasan dan tempat merujuk keinginan mereka, dan menyangka bahwa Nabi
Muhammad tidak akan pernah tahu apa yang mereka rahasiakan. Maka turunlah ayat
berikut.135
(Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan: “Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan beriman kepada seorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api.” Katakanlah: “Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku, membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar?”136
Menurut penuturan al-Tsa‘labī dari Ibn al-Kalabī, ayat ini diturunkan
berkenaan dengan beberapa orang Yahudi, yakni Ka‘b ibn al-Asyraf, Mālik ibn al-
S{ayf, Wahb ibn Yahūdhā, Zayd ibn al-Tābūt, Finh}ās} ibn ‘Āzūrā dan H{uyay ibn
al-Akht}ab. Mereka mendebat Nabi Muhammad soal kerasulan beliau. Menurut
mereka, Taurat telah menetapkan bahwa seorang nabi tidak boleh diterima sampai ia
135Mengenai sebab turun ayat ini, lihat misalnya ibid., Vol. 2, 807; al-T{abarī, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Tafsīr ‘Āy al-Qur’ān, (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H.), Vol.4, 197.
136Q.S. Āli ‘Imrān: 183.
mampu mempersembahkan kurban yang kemudian dimakan api (sebagai bukti
kurbannya telah diterima Tuhan). Maka mereka berkata kepada Nabi: “Jika engkau
melakukan hal itu untuk kami, maka kami akan beriman kepadamu.” Maka ayat
tersebut diturunkan untuk menjawab tantangan mereka itu.137
Ayat ini tidak menyatakan penolakannya secara tegas terhadap tuduhan
mereka bahwa Tuhan telah menjanjikan (yakni menetapkan) bagi mereka kriteria
seorang nabi untuk diimani. Al-Qur’an hanya membalas dengan argumentasi lain,
yakni merujuk pada kenyataan sejarah mereka sendiri: tuntutan mereka tidak lebih
dari sebuah upaya mengelak dari kebenaran dan berpura-pura berpegang teguh pada
janji Tuhan yang telah ditetapkan kepada mereka. Al-Qur’an tidak secara tegas
menyatakan mereka bohong dan menolak kebenaran janji Tuhan yang mereka
dakwakan itu; mereka hanya dituntut untuk melakukan refleksi historis serta bersikap
lebih dewasa dan jujur. Menurut al-T{abarī, Nabi diperintah Tuhan untuk menjawab
tantangan orang-orang Yahudi itu dengan mempertanyakan sikap mereka (yakni para
pendahulu mereka yang ternyata juga mempunyai sikap mental yang sama) yang
mengingkari dan bahkan membunuh para utusan Tuhan, padahal mereka telah
menunjukkan bukti kenabian tersebut.138 Memang, secara logis, ada perbedaan antara
perintah untuk beriman kepada seorang nabi yang telah mendatangkan bukti berupa
kurban yang dimakan api, dengan larangan untuk beriman kepada seorang nabi yang
tidak mendatangkan bukti tersebut. Jika orang-orang Yahudi diperintahkan untuk
beriman kepada nabi yang telah mendatangkan bukti tersebut, tidak berarti mereka
137Syihāb al-Dīn Ah}mad ibn ‘Alī, al-‘Ujāb, Vol. 2, 809.
138Al-T{abarī, Jāmi‘ al-Bayān, Vol. 4, 197-198.
dilarang beriman kepada nabi yang tidak mendatangkannya. Jadi mungkin saja
mereka telah memutarbalikkan argumentasi tersebut.
Sebagian mufassir mencoba menjelaskan ayat tersebut dalam kerangka
teologis dogmatis. Mereka mengatakan bahwa dalam Taurat, orang-orang Yahudi
memang diperintahkan untuk menguji orang-orang yang mendakwakan dirinya nabi
dengan mukjizat, yaitu persembahan kurban yang kemudian dimakan oleh api yang
turun dari langit. Jika hal itu tidak terjadi, yang berarti kurbannya tidak diterima,
maka orang tersebut bukanlah seorang nabi utusan Tuhan. Ini dipahami sebagai jalan
menghalangi munculnya nabi-nabi palsu yang berbohong atas nama Tuhan.
Kemukjizatan itu, kata mufassir, tidak berlaku bagi Nabi Isa dan Muhammad.
Perjanjian Tuhan tersebut tidak dapat diterapkan kepada dua nabi terakhir ini; orang-
orang Yahudi diperintahkan untuk menerima risalah keduanya dengan pasrah, karena
keduanya adalah nabi yang telah dijanjikan.139
Tampaknya al-Qur’an memandang covenant, yakni perjanjian manusia
dengan Tuhan, sebagai sesuatu yang telah tertanam dalam kesadaran batin diri
manusia. Tuhan telah membuat perjanjian ini sejak zaman azali. Karena itu covenant
yang diakui al-Qur’an adalah covenant primordial dan universal. Ia merupakan
perintah Tuhan kepada manusia untuk tunduk kepada-Nya, di mana sebagai
imbalannya Tuhan menjanjikan kemenangan dan keselamatan akhir. Kata ‘ahd dan
mītsāq dalam al-Qur’an, dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, ekuivalen
dengan makna perintah. Janji-janji Tuhan dengan Bani Israil yang dikemukakan al-
Qur’an adalah juga dalam konteks yang sama.
139Syihāb al-Dīn Ah}mad ibn ‘Alī, al-‘Ujāb, Vol. 2, 809.
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling.
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudara sebangsamu) dari negerinya, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.140
Shema atau syahadat itulah janji di pihak manusia, sebuah ikrar bahwa ia
tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan sebab Tuhan itu Pengasih dan Berkuasa.
Tuhan amat baik kepada manusia, meski Tuhan juga marah dan menghukum
manusia dengan hukuman yang berat jika mereka melanggar janji dengan-Nya.
Ayat-ayat di atas juga merupakan contoh lain dari style kritik al-Qur’an
terhadap orang-orang Yahudi. Mereka diingatkan akan kesalahan-kesalahan yang
telah mereka lakukan, tentu saja, dalam rangka menantang atau “mematahkan”
arogansi mereka terhadap Nabi Muhammad, Islam dan masyarakat Arab Muslim
pada waktu itu. Dengan kesan-diri sebagai kelompok agama superior, orang-orang
Yahudi Medinah telah cenderung bersikap sewenang dan mengeluarkan hujah-hujah
menyesatkan dan penuh kebohongan.
Satu hal yang patut diberikan perhatian di sini adalah mengenai kemungkinan
generalisasi atas sikap tidak terpuji orang-orang Yahudi yang dikemukakan al-
Qur’an tersebut. Pada sub bab sebelumnya, tentang monoteisme, telah disinggung
mengenai problem penerapan interpretasi kritik ayat-ayat al-Qur’an terhadap orang
Yahudi. Problem tersebut muncul ketika tafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an
dikaitkan dengan realitas sejarah dan kehidupan yang lebih realistik. Mengapa al-
140Q.S. al-Baqarah: 83-84.
Qur’an mengingatkan “dosa-dosa” orang Yahudi masa lalu? Apakah kesalahan
nenek moyang mereka ikut diwariskan kepada orang-orang yang datang kemudian?
Di mana letak proporsionalitas kritik al-Qur’an?
Jawaban terhadap persoalan ini dapat diberikan pertama sekali dengan
melihat konteks ayat-ayat itu diturunkan. Kedua, dengan mempertimbangkan
psikologi sosial hubungan orang Yahudi dengan orang-orang Arab pada waktu itu.
Pertimbangan pertama, ayat-ayat tentang Yahudi jelas diturunkan di Medinah.
Sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya, Nabi pada awalnya telah melihat
adanya potensi dukungan keagamaan dari orang-orang Yahudi terhadap dakwahnya
dan karena itu, tidak mengherankan, Nabi menjalin hubungan yang baik dengan
mereka. Orang-orang Yahudi juga secara politik berharap Nabi akan berpihak
kepadanya dalam pertikaian ideologis mereka dengan orang-orang Nasrani dari
Najran. Ketika terjadi perdebatan yang melibatkan ketiga pihak, yakni Yahudi,
Nasrani dan Nabi Muhammad, ternyata bagi mereka Nabi Muhammad tidak dapat
diharapkan untuk memenangkan pihak mereka. Nabi ternyata justeru memiliki
prinsip-prinsip tersendiri dan tidak pernah mau berkompromi dengan siapa pun
dalam hal-hal yang mendasar; Nabi juga tidak takut melawan mereka demi
mempertahankan apa yang beliau yakini sebagai kebenaran. Jadi secara politis, Nabi
menjadi ancaman bagi mereka. Setelah itulah terjadi perdebatan keagamaan yang
lebih sering antara Nabi Muhammad dan orang-orang Yahudi. Maka turunlah ayat-
ayat al-Qur’an yang menjawab berbagai persoalan yang dihadapi Nabi bersama
orang-orang Yahudi. Dalam konteks ketegangan politik dan ideologis seperti itulah
al-Qur’an berbicara mengenai orang-orang Yahudi dan menentang mereka dengan
merujuk pada tradisi dan pandangan keagamaan mereka sendiri. Selain ayat-ayat
yang “menegangkan” turun pula ayat-ayat yang bersikap lebih lunak – sebagaimana
akan terlihat nanti – yang membentuk konsep-konsep dasar pandangan al-Qur’an
tentang agama dan manusia secara lebih universal dan lebih humanis. Sikap keras al-
Qur’an dapat dimengerti sebagai respon yang pantas atas arogansi orang-orang
Yahudi serta sikap-sikap mereka yang licik dan penuh fitnah.
Kedua, hubungan orang-orang Yahudi dan Arab Muslim serta Nabi tidak
hanya dapat dilihat sebagai hubungan bilateral sosial-keagamaan. Nabi telah
mencoba membangun hubungan yang baik dengan mereka, namun kemudian
terbukti orang-orang Yahudi melakukan berbagai pengkhianatan yang sangat
berbahaya. Akhir hubungan ini sangat tragis. Namun perlu diingat bahwa Yahudi di
tanah Arab adalah orang-orang asing yang melarikan diri dari negerinya, atau
mencoba mencari jejak kebangkitan seorang Messiah di padang pasir yang banyak
pohon kurma. Orang-orang Arab bagi mereka adalah sama dengan orang-orang
gentile lainnya: dianggap pagan dan barbar – penyembah berhala dan tidak memiliki
aturan agama. Apakah mungkin dengan prakonsepsi seperti itu mereka tiba-tiba akan
tunduk dan taat mengikuti seorang Nabi bangsa Arab? Lalu di mana letak harga
agama dan tradisi mereka yang telah beratus tahun mereka pertahankan? Pada saat
Kristus mendakwahkan misi yang sama, mereka menolaknya; apakah kini mereka
akan menerima seruan Muhammad? Begitulah, ketika agama telah menjadi sebuah
institusi, maka sesungguhnya ia telah berada pada ujung terakhir proses
perkembangannya. Apa yang lahir sesudahnya adalah agama lain; dianggap asing
dan batil. Kristalisasi inilah yang terjadi dalam agama-agama di dunia, dan kesadaran
seperti inilah yang membentuk sikap penolakan pemeluknya terhadap agama lain.
Tanpa historical consciousness (kesadaran historis), sebenarnya setiap kelompok
akan didesak oleh keyakinannya ke sisi ekstrem dari institusi agama tersebut dan
cenderung bersikap abai terhadap kelompok lain dan pada akhirnya menganggap
mereka sebagai musuh. Lalu setiap orang yang telah menganut sebuah agama
institusional akan terikat secara sosiologis dan psikologis dengan semua penganut
yang lain; dan secara umum sikap mereka juga akan sama.
3. Siapa Umat Pilihan?
Semua pemeluk agama akan mengklaim agamanya sebagai yang terbaik dan
kelompoknya sebagai umat pilihan. Ini logis, sebab jika tidak demikian maka dapat
dipastikan bahwa landasan bagi pemilihan agama yang dipeluk seseorang itu sangat
rapuh. Apakah seseorang akan memilih agama yang tidak sempurna untuk
dianutnya? Memilih agama terbaik berarti menjadi umat terbaik. Tapi adakah semua
orang memilih agama yang dipeluknya? Bukankah hampir semua orang memeluk
agama yang “dibaptiskan” kepadanya pada waktu ia masih kecil, ketika ia sendiri
belum mengerti secara mendalam ajaran agama yang akan harus ia pegang teguh itu?
Jadi benarkah setiap orang telah memilih agama yang terbaik untuk dirinya? Atau itu
hanya sebuah pembenaran psikologis, agar setiap orang puas dengan agama yang
dipeluknya? Atau, tidakkah mungkin, itu hanya politik penguasa agama agar dapat
mempertahankan atau memperbanyak komunitas agamanya? Siapa tahu, dan siapa
yang akan dapat menjawabnya secara objektif?
Sebelum isu ini didiskusikan lebih jauh, yakni pada bab selanjutnya, di sini
beberapa analisa akan difokuskan pada sejumlah ekspresi al-Qur’an mengenai umat
pilihan atau umat terbaik. Dalam al-Qur’an, umat Nabi Muhammad disebut sebagai
khayr ummah (umat terbaik) yang diutus untuk manusia, karena mereka menyuruh
perbuatan makruf dan mencegah perbuatan mungkar.
Kamu adalah umat terbaik (khayr ummah) yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.141
Di samping itu, umat pengikut Musa, yakni Bani Israil, juga dikatakan
sebagai umat pilihan, di mana Tuhan telah memilih mereka atau melebihkan mereka
dari umat-umat lain di dunia.
Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: “Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Ia mengangkat nabi-nabi di antara kamu, menjadikan kamu raja-raja, dan memberimu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun (wa ātākum mālam yu’ti ah}adan) di antara umat-umat yang lain.”142
Dalam ayat lain, al-Qur’an mengekspresikannya dengan lebih jelas:
Wahai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya Aku telah melebihkan kamu (fad}d}altukum) atas segala umat.143
Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka (ikhtarnā hum) dengan pengetahuan (Kami) atas segala umat.144
141Q.S. Āli ‘Imrān: 110.
142Q.S. al-Mā’idah: 20.
143Q.S. al-Baqarah: 47 dan 122.
144Q.S. al-Dukhān: 32.
Lalu siapa, menurut al-Qur’an, umat pilihan? Umat Islam atau umat Yahudi?
Pertanyaan ini tentu amat mudah dijawab oleh kedua belah pihak. Tanpa diragukan,
keduanya pasti memiliki cukup banyak argumentasi untuk membela pihaknya
masing-masing. Memang perdebatan linguistik mungkin terjadi, sebab al-Qur’an
menyebutkan apresiasi tersebut dengan ekspresi kata berbeda: khayr ummah,
ikhtarnā hum, fad}d}altukum, wa’ātākum mā lam yu’ti ah}adan dan lain-lain. Tapi
hal ini tidak akan diperbincangkan lebih jauh dalam kajian disertasi ini, karena sudah
berada di luar fokus; yang jelas, al-Qur’an telah mengungkapkan pernyataan-
pernyataan yang menunjukkan ada umat yang diberikan penilaian lebih tinggi dari
yang lain. Jika persoalannya demikian, menurut kebanyakan mufassir, maka dapat
saja dipahami bahwa penilaian tersebut bersifat relatif. Sebuah penilaian akan
terbatas pada aspek-aspek tertentu. Jika seseorang mendapatkan prestasi yang tinggi
dalam satu hal maka tidak mustahil dalam hal lain ia berkurang.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, menurut Ibn Katsīr, orang-orang
Israel adalah umat yang terbaik pada zamannya jika dibandingkan dengan bangsa-
bangsa lain seperti Mesir dan Yunani.145 Mengenai pernyataan al-Qur’an bahwa
Allah telah memilih bangsa Israel, para mufassir secara general menganggap bahwa
keunggulan mereka tersebut bersifat relatif, tidak mutlak. Dalam beberapa hal
mereka memang memiliki kelebihan, namun ada juga bangsa-bangsa lain yang
memiliki kelebihan berbeda. Namun dalam hal agama, kepemimpinan, kedatangan
145Ibn Katsīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Az}īm, (Kairo, 1956), Vol. 3, 36-7.
nabi-nabi dan kitab suci, bangsa Yahudi memang termasuk spesial pada zaman
tersebut, seperti kata Ibn Katsīr di atas. Demikian juga pendapat al-Rāzī.146
Namun al-Qurt}ubī memiliki pendapat agak berbeda. Ketika menafsirkan
ayat 47 surat al-Baqarah, al-Qurt}ubī berkata, bahwa Bani Israil telah dilebihkan
oleh Tuhan atas segala umat, baik umat di zamannya atau pun umat di zaman-zaman
yang lain. Tuhan telah mengangkat nabi-nabi yang banyak di kalangan mereka; ini
merupakan kelebihan Bani Israil secara khusus.147 Tetapi ketika menjelaskan ayat 32
surat al-Dukhān, al-Qurt}ubī tampak ragu untuk bersikap tegas dengan
pandangannya sebelum itu. Ia mengatakan bahwa kelebihan Bani Israil adalah jika
dibandingkan dengan umat-umat lain di zamannya; ini berdasarkan ayat 110 surat
Āli ‘Imrān yang menegaskan keterpilihan umat Muhammad. Namun, setelah itu ia
berkata: ini pendapat Qatādah, sementara pendapat yang lain mengatakan, kelebihan
mereka adalah atas segala umat pada setiap zaman, karena mereka memiliki nabi-
nabi yang banyak.148 Al-Qurt}ubī tidak memberikan komentar yang banyak setelah
itu. Tampaknya ia sendiri menyadari bahwa kebanyakan mufassir pendahulunya juga
memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ia sendiri tentu saja tidak mungkin menolak
bahwa umat Muhammad adalah umat pilihan, berdasarkan al-Qur’an sediri.
Menyambung al-Qurt}ubī, lalu apa salahnya jika diterima bahwa kedua komunitas
ini adalah umat pilihan?
146Al-Rāzī, Mafātih} al-Ghayb, (Kairo, 1308 H.), Vol. 1, 336-7.
147Al-Qurt}ubī, al-Jāmi‘ li Ah}kām al-Qur’ān, (Kairo: Dār al-Sya‘b, Cet. II, 1372 H.), Vol. 1, 376. Pendapat ini didukung pula oleh Q.S. al-Jātsiyah: 16: “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Bani Israil kitab (Taurat), kekuasaan (al-h}ukm) dan kenabian (al-nubuwwah) dan Kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa yang lain.”
148Ibid., Vol. 16, 142-143.
Apa sesungguhnya arti “umat pilihan” itu? Ketika Tuhan telah memilih suatu
umat, apakah berarti Ia telah menyia-nyiakan umat yang lain? “Kita” sepertinya
cenderung menafikan setiap kelebihan pada “orang lain” dan amat takut jika ternyata
harus mengakui bahwa orang lain mengungguli kita. Al-Qur’an sebenarnya telah
memberikan isyarat bahwa Tuhan telah memilih siapa saja yang Dia kehendaki di
antara hamba-hamba-Nya. Tuhan telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan
keluarga Imran atas sekalian manusia; Tuhan juga telah menjadikan Maryam sebagai
perempuan pilihan di atas sekalian perempuan di dunia.149 Tuhan telah memilih
banyak manusia dan melebihkan mereka dari manusia-manusia yang lain. Namun
Tuhan tidak memilih mereka begitu saja tanpa alasan. Ketundukan mereka yang
tulus kepada-Nya dan komitmen moral mereka yang berada pada level standar
tertinggi adalah alasan utama mengapa mereka menempati posisi lebih terhormat di
mata Tuhan. Dalam berbagai ayat dan surat, al-Qur’an menegaskan hal tersebut.
Ketika dipilih oleh Tuhan menjadi imam bagi sekalian manusia, Ibrahim bermohon:
“(Ya Tuhan! Demikian juga) dari anak keturunanku!” Tuhan menjawab: “Janji-Ku
tidak akan mengenai orang-orang yang zalim.”150
Al-Qur’an selalu mengacu pada prinsip-prinsip yang universal. Al-Qur’an
tidak mungkin dipahami dalam konteks yang sempit. Menalar al-Qur’an dengan
cara-cara yang tendensius akan berhadapan dengan berbagai paradoks, dan
membingungkan. Sejauh ini, kasus ayat-ayat yang telah dibicarakan di atas adalah
contoh-contoh yang jelas. Sekali lagi, ayat-ayat ini menunjukkan historisitas al-
149Q.S. Āli ‘Imrān: 33 dan 42.
150Q.S. al-Baqarah: 124.
Qur’an dan keterikatannya dengan sosial-budaya masyarakat yang menjadi
sasarannya. Ayat-ayat al-Qur’an pertama sekali ditujukan kepada masyarakat Arab
dan pembicaraan al-Qur’an mengenai orang-orang Yahudi dan Nasrani pada intinya
juga tidak terlepas dari persoalan hubungan mereka dengan Nabi Muhammad dan
orang-orang Arab. Orang-orang Bani Israil yang dibicarakan al-Qur’an haruslah
dilihat sebagai contoh-contoh untuk dijadikan pelajaran. Mereka dipilih oleh Tuhan
karena ketulusan hati dan kebaikan amalnya; mereka dicela karena sikap-sikapnya
yang menyimpang dari kebenaran dan melanggar sumpah setia yang telah mereka
ikrarkan.
Gagasan al-Qur’an mengenai keterpilihan Bani Israil barangkali juga tidak
terlepas dari klaim Bani Israil sendiri bahwa mereka telah dipilih oleh Tuhan.
Beberapa ayat al-Qur’an mengindikasikan bahwa orang-orang Yahudi Medinah telah
mengekspresikan hal tersebut, namun mungkin dengan nada sinis dan merendahkan.
Dan mereka berkata: “Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk.” Katakanlah: “Tidak, bahkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan dia (Ibrahim) bukanlah di antara orang-orang musyrik.”
Katakanlah (hai orang-orang Mukmin): “Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.”151
Pada ayat lain ekspresi ini tampak lebih tegas:
Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: “Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.” Katakanlah: “Lalu mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?” (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya
151Q.S. al-Baqarah: 135-136.
dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).152
Ayat-ayat ini turun mengoreksi sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang
memandang diri mereka terlalu eksklusif. Kedua komunitas ini dianggap al-Qur’an
telah terjebak dalam kesesatan mental yang sama. Tuhan telah memilih mereka
dengan menurunkan agama yang benar, namun mereka telah mengalihkan makna
keterpilihan itu kepada bentuk-bentuk yang lebih sempit: rasialisme dan formalitas.
Al-Qur’an membantah klaim-klaim yang telah merusak kebenaran universal dan
merendahkan persaudaraan kemanusiaan itu.
Dalam konteks seperti ini, barangkali, ayat-ayat di atas dapat dilihat secara
lebih terang. Pernyataan-pernyataan al-Qur’an tidak boleh dilihat dengan perspektif
yang sempit, sehingga seseorang terjebak kembali dalam kekeliruan yang sama. Al-
Qur’an adalah petunjuk dan peringatan, bukan buku manual; ia harus dipahami
melalui perspektif kehidupan yang lebih luas, lebih real dan lebih bijaksana.
Kesadaran sebagai umat pilihan, melalui cara-cara tertentu, telah terbentuk
dalam berbagai komunitas agama yang percaya agamanya sebagai agama yang
diturunkan oleh Tuhan yang Esa; dan ini telah mencirikhaskan ketiga agama besar
dunia: Yahudi, Nasrani dan Islam. Masing-masing memiliki alasan, yakni dari kitab
suci, untuk mengklaim dirinya sebagai umat pilihan Tuhan; dan bahwa Tuhan sendiri
telah berkata demikian. Namun, sesungguhnya yang lebih penting adalah upaya
mengeksplorasi makna yang lebih dalam dari pernyataan bahwa Tuhan telah memilih
seseorang atau suatu umat. Jika Yahudi adalah umat pilihan, mengapa Tuhan
152Q.S. al-Mā’idah: 18.
menghukum mereka dengan berbagai siksaan? Demikian al-Qur’an mengajukan
kritikan. Namun kritik ini sering kali tidak diterapkan oleh umat Islam (pemilik al-
Qur’an) untuk diri mereka sendiri. Artinya, meskipun umat Islam melihat dirinya
sebagai umat pilihan, kebanyakan mereka tidak berupaya dengan sungguh-sungguh
untuk merealisasikan hal tersebut dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana
ditetapkan al-Qur’an.
Para sarjana Muslim sejak awal telah mengemukakan pendapat berbeda
dalam memahami ungkapan al-Qur’an: kuntum khayr ummah (kamu adalah umat
terbaik).153 Berdasarkan riwayat al-T{abarī, Ibn ‘Abbās berpendapat bahwa yang
dimaksud oleh ayat tersebut adalah para sahabat Nabi yang berhijrah bersama beliau
dari Mekkah ke Medinah. ‘Umar ibn al-Khat}t}āb juga mengatakan demikian.
Menurutnya, mereka yang terpilih itu adalah khusus para sahabat Rasulullah dan
orang-orang yang berbuat seperti para sahabat Rasul berbuat. Namun sejumlah
riwayat lain yang barangkali lebih mencerminkan kepedulian akan makna sejati ayat
tersebut juga dikutip oleh al-T{abarī. Menurut Mujāhid, demikian al-T{abarī
meriwayatkan, umat di zaman mana saja dapat menjadi umat terbaik sejauh mereka
memenuhi persyaratan yang telah dibuat al-Qur’an, yaitu: menyuruh yang makruf
dan mencegah yang mungkar; buktinya al-Qur’an mengatakan: “Sekiranya Ahli
Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka.” Sayangnya, “di antara mereka
ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”154
153Q.S. Āli ‘Imrān: 110.
154Al-T{abārī, Jāmi‘ al-Bayān, Vol. 4, 43-45.
Umumnya kaum Muslim, sebagaimana terungkap dalam berbagai literatur
Islam sepanjang sejarah, menyadari bahwa menjadi pilihan Tuhan tidaklah dengan
serta-merta, tetapi harus dengan amal dan ketulusan hati. Akan tetapi jika ditelusuri
lebih jauh, dalam keyakinan yang lebih populer, pada akhirnya umat Nabi
Muhammadlah yang diyakini sebagai umat yang terbaik; sebaik apa pun umat lain
(umat terdahulu), tidak akan menyamai, apa lagi melebihi, umat Nabi terakhir.
Padahal, ini jelas amat sulit disejalankan dengan semangat dasar al-Qur’an. Beberapa
riwayat telah dijadikan sandaran untuk pandangan ini. Al-T{barī, misalnya, telah
menukilkan riwayat-riwayat yang mengatakan – mengenai takwil ayat 110 di atas –
“kita adalah umat terakhir dan kita yang terbaik.” Bahkan Nabi diriwayatkan
bersabda: “Kamu sekalian telah menyempurnakan sembilan puluh umat, dan kamu
adalah yang terbaik dan termulia di sisi Allah.”155
Sementara itu al-Qur’an sendiri mengatakan bahwa para rasul memang telah
dilebihkan oleh Tuhan, sebagian mereka di atas sebagian yang lain, namun masing-
masing mereka mempunyai kelebihan tersendiri; dan manusia sebagai umatnya serta
sebagai hamba Tuhan tidaklah berhak membanding-bandingkan mereka.
Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung kepadanya) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat dia dengan Rūh} al-Qudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka di antara mereka ada yang beriman dan ada (pula) yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.
Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya; demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah,
155Ibid., 45
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata): “Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul-rasul-Nya,” dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami taat.” (Mereka berdo‘a): “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.”156
Kedua ayat ini memperlihatkan pandangan al-Qur’an yang cukup jelas soal
bagaimana umat Muhammad seharusnya bersikap terhadap umat dan nabi-nabi yang
lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan secara sahih oleh al-Bukhārī, Nabi
Muhammad sendiri telah mengekspresikan sikap yang cukup tegas. Pada suatu hari
seorang Muslim bertengkar dengan seorang Yahudi; mereka saling mencaci maki.
Maka terucap oleh si Muslim: “Demi Tuhan yang telah memilih Muhammad atas
sekalian manusia.” Lalu Yahudi tersebut membalas: “Demi Tuhan yang telah
memilih Musa atas sekalian manusia.” Maka orang Muslim tadi marah dan
menampar si Yahudi. Yahudi itu mengadu kepada Rasulullah. Rasul memanggil
orang tersebut dan bertanya apakah benar pengaduan tersebut. Ia mengaku. Lalu
Rasul bersabda: “Janganlah engkau melebih-lebihkan aku atas Musa ...”157
Pertengkaran demi pertengkaran, baik politik maupun ideologi, telah
mewarnai sejarah hubungan Yahudi-Muslim dari awal sampai hari ini. “Siapa yang
telah memulainya?” Ini adalah pertanyaan yang keliru kalau pertengkaran tersebut
tidak ingin dilanjutkan lagi. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak akan pernah
relevan bagi dialog antar umat. Jawaban yang diberikan, baik itu “benar” atau keliru,
justeru akan memperkeruh suasana. Keinginan mencari jawaban tersebut telah
mendorong masing-masing untuk saling merendahkan dan mengindoktrinasi setiap 156Q.S. al-Baqarah: 253 dan 285.
157Al-Bukhārī, S{ah}īh} al-Bukhārī, (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1987 M./1407 H.), Vol. 2, 849: Hadis No. 2280. Dalam teks lain disebutkan, mendengar itu “maka Nabi s.a.w. marah ...” Lihat Ibid., Vol. 3, 1254: Hadis No. 3233.
pemeluk masing-masing untuk meyakini diri merekalah yang lebih superior, dengan
mencari berbagai legitimasi dari kitab suci dan mengabaikan realitas kehidupan yang
lebih nyata. Kadang-kadang kebodohan atau kejahatan segelintir orang – atau bahkan
satu orang – dalam sebuah komunitas, harus ditanggung konsekuensinya oleh seluruh
individu dalam komunitas tersebut. Dalam setiap komunitas pasti ada orang, atau
orang-orang, yang berbuat bodoh, namun tidak adil kalau hal tersebut digeneralisir
kepada semua individu. Fakta bahwa al-Qur’an telah mengkritik orang-orang Yahudi
dan bahkan melemparkan beberapa tuduhan tercela, tidak dapat dijadikan alasan
untuk menghapus fakta bahwa al-Qur’an juga telah mengekspresikan sejumlah
apresiasi positif kepada mereka; bahwa Tuhan telah memilih Bani Israil telah
diekspresikan al-Qur’an secara nyata.
Klaim umat Islam sebagai khayr ummah jelas merupakan tantangan bagi
kaum Yahudi. Pertengkaran seorang Yahudi dengan seorang Muslim di Medinah,
sebagaimana tersebut dalam riwayat di atas, memperlihatkan suasana tersebut.
Masing-masing mengatakan Nabinya yang terhebat dan, logikanya, masing-masing
menganggap dirinya, sebagai pengikut Nabi tersebut, adalah yang terhebat pula.
Dalam situasi pergolakan pemikiran keagamaan yang hebat, pada abad tengah, ketika
kaum Muslim mengalami kejayaan dan berkesempatan melancarkan misi Islam
dengan gencar, Moses Maimonides (1135-1204), untuk yang pertama kalinya dalam
sejarah perkembangan agama Yahudi, memformulasikan tiga belas prinsip dasar
keyakinan Yahudi, di mana salah satunya menyebutkan: Moses is the greatest of the
prophets.158 Apa yang dilakukan Maimonides, hampir dapat dipastikan, adalah 158Tiga belas prinsip dasar keyakinan tersebut, sebagaimana dikutip Tracey Rich,
ialah: 1. G-d is one and unique; 2.G-d is incorporeal; 3. G-d is eternal; 4. Prayer is to be directed to G-d alone and to no other; 5. The words of the prophets are true; 6. Moses’s
sebagai upaya melawan klaim umat Islam atas “kebesaran” Nabi Muhammad.159
Maimonides jelas bukan yang pertama menciptakan gagasan tersebut, tetapi, dalam
kondisi pertentangan ideologi seperti di abad tengah itu, ia merasa perlu
menegaskannya kembali dalam rangka “memperteguh keimanan” kaumnya dan
“menyelamatkan” mereka dari “kemurtadan.” Kedua belah pihak sebenarnya sama
saja. Keinginan untuk menjadi yang terhebat, atau mendapat pengakuan sebagai yang
terhebat, barangkali, merupakan naluri dasar manusia. Lagi-lagi al-Qur’an
menegaskan bahwa seseorang menjadi hebat bukan karena keturunan atau
komunitasnya, tetapi karena hati dan amalnya. Maka Nabi Muhammad pun menolak
untuk disebut sebagai lebih hebat dari Nabi Musa. Hanya Tuhan yang berhak menilai
hati dan amal manusia.
Di kalangan Yahudi telah muncul pula kesadaran untuk mengkritisi makna
keberadaan mereka sebagai the chosen people. Dalam tradisi Yahudi, gagasan bahwa
Tuhan telah memilih orang-orang Yahudi sebagai umat istimewa yang akan
melaksanakan kehendak-Nya dapat ditemukan secara jelas dalam Bible – di
antaranya sebagaimana telah dikutip di atas – dan menjadi ajaran yang diyakini
secara luas oleh masyarakat Yahudi. Namun, apakah ketika Tuhan telah memilih
orang-orang Yahudi berarti Ia telah mengabaikan umat-umat yang lain? Para sarjana
Yahudi telah mengembangkan tafsiran berbeda-beda dalam menjelaskan makna
prophecies are true, and Moses was the greatest of the prophets; 7. The Written Torah (first 5 books of the Bible) and Oral Torah (teachings now contained in the Talmud and other writings) were given to Moses; 8. There will be no other Torah; 9. G-d knows the thoughts and deeds of men; 10. G-d will reward the good and punish the wicked 11. The Messiah will come; 12. The dead will be resurrected. Lihat <http://www.jewfaq.org/frames/beliefs.htm>. Lihat juga Louis Jacobs, The Book of Jewish Belief, (Behrman House, t.t.), 5.
159Louis Jacobs, The Book of Jewish Belief, (Behrman House, t.t.), 6.
“umat pilihan Tuhan.” Sebagian mereka menunjukkan bahwa persoalannya tidaklah
sederhana. Bible memang mengatakan bahwa Tuhan telah memilih bangsa Yahudi,
tetapi nowhere is it suggested that other peoples have no role to play in God’s plan
for humanity.160 Lebih jauh, doktrin tersebut tampak dengan jelas bertentangan
dengan keyakinan akan betapa luasnya rahmat Tuhan, whose care and providence
extends equally ... to all human beings He has created in His image.161
Sebagian mereka bahkan merasa “risih” dengan sebutan tersebut. Mengapa
Tuhan harus memilih satu umat khusus untuk suatu tugas tertentu? Mengapa orang-
orang Yahudi sebagai pilihan terbaik? Why not make the whole human race the
instrument for the fulfillment of His purpose? Kita tidak tahu, itu adalah urusan
Tuhan, jawab Maimonides dan sejumlah pemikir Yahudi lainnya.162
Namun sebagian mereka sangat yakin bahwa Tuhan memang telah memilih
ras Yahudi sebagai yang terbaik di antara umat manusia. Jiwa orang-orang Yahudi
lebih superior dari yang lainnya. Walaupun demikian, ini tidak berarti orang-orang
Yahudi dapat bertindak sekehendaknya terhadap bangsa lain yang dianggap berjiwa
inferior. Yang dituntut justeru sebaliknya: Karena Tuhan telah memilih mereka,
berarti Tuhan telah memundakkan tugas yang lebih besar, yaitu memberikan servis
kepada umat lain, bukan memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri; mengajak
mereka ke jalan Tuhan dan membantu mereka menjalankan kehendak Tuhan.
Pandangan ini, walaupun mencoba menunjukkan diri bersikap dan berniat baik, jelas
160Ibid., 38.
161Louis Jacobs, The Jewish, 77.
162Louis Jacobs, The Book, 40.
sangat imperialistik. Kebanyakan sarjana Yahudi menolak pandangan tersebut, atau
dianggap sebagai pandangan yang kurang meyakinkan.163
Mengenai hal ini George Robinson mengutip dua kisah ilustratif. Yang
pertama, Tuhan menawarkan Taurat kepada bangsa-bangsa lain. Satu kelompok
bertanya: “Apa di dalam nya?” di mana Tuhan menjawab: “Kamu tidak boleh
mencuri.” Mereka lalu berkata: “Ya, bagaimana, itulah penghidupan kami. Kami
tidak tertarik.” Kelompok lain lagi juga bertanya apa isi Taurat itu, dan Tuhan
menjawab: “Kamu tidak boleh membunuh.” Mereka merespon: “Kami adalah bangsa
pahlawan, maaf, kami tidak dapat mengikutinya.” Akhirnya Tuhan menawarkan
Taurat itu kepada orang-orang Hebrew dan mereka setuju untuk menerimanya.
Dalam kisah kedua, Tuhan mengangkat gunung Sinai ke atas kepala orang-
orang Israel, lalu menahannya dan berkata bahwa jika mereka tidak mau menerima
Taurat, Ia akan menjatuhkan gunung tersebut.
Jadi, kata Robinson, orang-orang Yahudi tidak dipilih karena superioritasnya,
tetapi karena kemauannya mengikuti hukum Tuhan. Mereka dipilih karena mereka
tidak berani menolak. Either way, the worldview these two stories propound is one in
which being chosen is a responsibility and a burden. In Deuteronomy 7: 7, God tells
the Israelites that they were not chosen because they were greater among the nations
but because they were small, the least of the nations.164
Apa yang dikemukakan al-Qur’an tentang keterpilihan Bani Israil adalah
konsep yang telah dikembangkan oleh Bani Israil itu sendiri. Dalam kenyataannya
163Ibid.
164George Robinson, Essential Judaism: A Complete Guide to Beliefs, Customs, and Rituals, (New York: Pocket Boks, 2000), 73-74.
sekarang, orang-orang Yahudi berselisih tentangnya. Al-Qur’an dalam hal ini
sebenarnya telah menawarkan konsep yang lebih tercerahkan bagi orang-orang
Yahudi dalam memaknai arti gagasan “keterpilihan” tersebut. Sekiranya saja para
pemeluk suatu agama tidak merasa segan mengambil kitab suci umat lain untuk
memperkaya pemahaman mereka tentang isi kitab suci mereka sendiri mungkin
mereka akan bisa melihat dunia ini agak lebih luas. Tapi bagi kebanyakan orang, ini
pasti amat menjijikkan dan dianggap sebagai cara beragama paling keliru. Namun
para sarjana Muslim ternyata telah mengambil inisiatif seperti ini sejak awal dalam
sejarah tafsir al-Qur’an, walaupun pada akhirnya dikalahkan oleh pendapat lain, yang
mampu menciptakan kesan negatif bagi isrā’īliyyāt.
4. Tentang Kehidupan di Akhirat
Menurut al-Qur’an, orang-orang Yahudi mengklaim bahwa melalui agama
merekalah manusia akan terselamatkan di akhirat. Siapa pun tidak akan masuk sorga
melainkan dia adalah seorang Yahudi atau Nasrani.
Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: “Tidak akan pernah masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani.” Yang demikian itu hanyalah angan-angan kosong mereka. Katakanlah: “Tunjukkanlah buktimu jika kamu adalah orang-orang yang benar.”
Ayat ini menunjukkan respon al-Qur’an terhadap sikap orang-orang Yahudi dan
Nasrani yang tampak seperti kekanak-kanakan dan bahkan menggelikan. Kedua
mereka, menurut al-Qur’an bukan hanya telah terjebak dalam eksklusivisme, tetapi
telah berbohong dan menipu diri sendiri dengan menciptakan angan-angan kosong.
Lagi-lagi, ayat ini juga memperlihatkan gaya kritik al-Qur’an yang selalu merujuk
kepada penggunaan nalar dan argumentasi yang jelas dan penekanan pada sikap yang
tulus dan jujur. Ayat berikutnya merupakan formulasi lebih jelas dari gagasan
universal al-Qur’an:
Tetapi sesungguhnya, barangsiapa menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.165
Al-Qur’an sepertinya ingin menunjukkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani
bagaimana seharusnya seseorang bersikap dalam beragama. Jika agama mereka
sama-sama berasal dari Tuhan yang Esa mengapa mereka (Yahudi dan Nasrani)
berselisih dan mengapa menentang Muhammad? Jika agama-agama mereka
mengajarkan kebaikan, mengapa saling merendahkan dan menyombongkan diri?
Mungkin setiap agama memiliki pandangan-pandangan teologi dan cara-cara
beribadat yang berbeda. Pertanyaannya, apakah itu esensi dari ajaran agama
tersebut? al-Qur’an menawarkan pandangan yang menegaskan bahwa sesungguhnya
yang paling penting adalah penyerahan diri kepada Tuhan dan beramal kebaikan.
Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang S{ābi’īn, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat serta beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhannya; tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.166
Pernyataan al-Qur’an ini merupakan sikap paling “berani” dalam mengapresiasi umat
lain secara positif. Al-Qur’an memperlihatkan sikap tidak pernah takut kehilangan
“harga diri” hanya karena mengakui kebenaran yang inklusif. Ini jelas merupakan
165Q.S. al-Baqarah: 111-112.
166Q.S. al-Baqarah: 62.
bagian dari kritik al-Qur’an kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani atas pandangan
mereka yang eksklusif.
Ayat-ayat di atas berbicara mengenai hari akhirat, suatu hari di mana manusia
dibangkitkan atau di hidupkan kembali, dikumpulkan, diadili dan diberikan ganjaran
sesuai dengan amalnya. Orang-orang mukmin akan dimasukkan ke sorga, sedangkan
orang-orang kafir ke neraka. Iman kepada Tuhan dan hari akhirat merupakan basis
amat penting bagi keselamatan di hari itu dan bukti terhadap iman tersebut
ditunjukkan oleh amal kebajikan yang dilakukan seseorang. Karena itu setiap kali al-
Qur’an berbicara soal iman selalu dikaitkan dengan amal saleh atau kebajikan.
Konsep tentang hari akhirat sangat jelas dalam al-Qur’an. Pernyataan bahwa
manusia akan dihidupkan kembali dan diberikan balasan terhadap amalnya dapat
ditemukan di berbagai ayat dalam puluhan surat.167 Istilah yang digunakan untuk itu
juga bervariasi, sesuai dengan ciri dan fungsi hari tersebut, misalnya: yawm al-
h}isāb (hari pembalasan), yawm al-qiyāmah, yawm al-ba‘ts (hari bangkit), yawm
yub‘atsūn (hari mereka dibangkitkan), yawm al-ākhir (hari akhir), al-ākhirah, dan
al-sā‘ah (waktu).168
Kenyataan ini sangat berbeda dengan kenyataan yang ditemukan dalam Bible
Yahudi atau Taurat. Walaupun kepercayaan akan adanya hari akhirat dikenal secara
luas dalam keyakinan dan pemikiran keagamaan Yahudi, Bible amat sedikit
memberikan indikasi ke arah tersebut. Seorang penulis Muslim kontemporer,
167Lihat misalnya Q.S. al-Baqarah: 4, 28, 56; Āli ‘Imrān: 9-10, 14; al-Nisā’: 13, 87; al-A‘rāf: 51; dan al-Qiyāmah: 3.
168Mengenai Yawm al-h}isāb (hari pembalasan), lihat misalnya, Q.S. S{ād: 16; yawm al-qiyāmah, Q.S. al-Nisā’: 87; yawm al-ba‘ts (hari bangkit), Q.S. al-Rūm: 56; yawm yub‘atsūn (hari mereka dibangkitkan), Q.S. al-A‘rāf: 14; yawm al-ākhir (hari akhir), Q.S. al-Nisā’: 38; al-ākhirah, Q.S. al-Baqarah: 4; dan al-sā‘ah (waktu), al-An‘ām: 31.
Ah}mad Syalabī, bahkan berkomentar, bahwa agama Yahudi lebih mementingkan
amal, tidak terlalu melihat pada iman; ia adalah agama yang, pada intinya, mengatur
jalan kehidupan, bukan akidah. Ini, demikian menurut Syalabī, sangat berbeda dari
agama Nasrani yang lebih mementingkan iman dari amal saleh. Karena itu,
kebangkitan, hari akhirat dan pembalasan tidak dibicarakan dalam agama Yahudi;
isyarat kepada adanya kehidupan sesudah mati sangat sedikit ditemukan. Tidak ada
dalam agama tersebut konsep tentang kehidupan yang kekal; pahala dan dosa hanya
disempurnakan di dunia ini.169
Apakah orang-orang Yahudi tidak percaya pada hari akhirat? Jika agama
mereka berasal dari ajaran Musa dan bersumber dari tradisi Ibrahim, maka,
berdasarkan al-Qur’an, kepercayaan akan hari akhirat mestilah merupakan fondasi
iman yang utama. Ibrahim, demi untuk menenangkan hatinya, pernah bertanya
kepada Tuhan ihwal bagaimana Ia menghidupkan orang mati. Tuhan lalu
menunjukkan bukti yang kemudian menjadikan Ibrahim puas dengan keyakinannya.
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati.” Allah berfirman: Apakah engkau belum percaya?” Ibrahim menjawab: “Memang, aku telah percaya, tetapi (ini) untuk menenteramkan hatiku (memantapkan imanku).” Allah berfirman: “(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Setelah itu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera.” Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.170
Tentang keimanan Musa akan hari akhirat juga terdapat isyarat dalam al-Qur’an.
Musa menentang Firaun yang sombong dan tidak percaya akan hari pembalasan:
169Ah}mad Syalabī, Muqāranah al-Adyān 1: al-Yahūdiyyah, (Kairo: Maktabah al-Nahd}ah al-Mis}riyyah, Cet. V, 1978), 202.
170Q.S. al-Baqarah: 260.
Dan Musa berkata: “Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari pembalasan.”171
Beberapa pernyataan al-Qur’an, misalnya al-Baqarah: 111-112 yang dikutip di atas,
menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi pada masa Nabi Muhammad pernah
mengemukakan pandangan mereka tentang adanya hari akhirat, sorga dan neraka,
walaupun konsep mereka tentang situasi kehidupan akhirat itu, yang hanya berpihak
pada kepentingan mereka secara eksklusif, ditentang oleh al-Qur’an.
Kepercayaan akan hari akhirat umumnya dipahami sebagai gagasan yang
mengacu pada sebuah janji tegaknya keadilan yang sungguh-sungguh dan
menyeluruh – a final, cosmic justice. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan.
Penderitaan, kezaliman, kesewenangan dan berbagai kejahatan tidak pernah dapat
diimbangi oleh upaya manusia menegakkan keadilan. Banyak orang telah mati tanpa
memiliki kesempatan menuntut hak-haknya yang telah dirampas; banyak orang telah
kehilangan nyawanya sebelum keadilan ditegakkan baginya. Apakah keadilan hanya
merupakan harapan ilusif belaka? Hari akhirat merupakan gagasan yang menampung
harapan tersebut. Di hari akhiratlah semua amal manusia akan dikalkulasikan dengan
sedetil-detilnya dan keadilan ditegakkan dengan sesungguhnya di hadapan
mahkamah Tuhan yang Maha Kuasa. Hak-hak orang yang telah terampas akan
dikembalikan dan orang-orang zalim akan diberikan hukuman yang setimpal. Karena
itu tidak mengherankan, dalam sejarah keagamaan umat Yahudi, konsep tentang hari
akhirat mulai berkembang sekitar dua abad sebelum Masehi, pada zaman
171Q.S. al-Mu’min: 27.
Maccabees,172 ketika kehidupan mereka dihancurkan dan mereka mengalami suatu
penderitan yang berat. In the face of such trauma, the old ideas of reward of good
and punishment of evil seemed untenable, but the notion of another life after death
promised a final, cosmic justice.173
Dalam Bible terdapat dua ayat yang menunjuk pada kehidupan sesudah mati
dan pembalasan bagi setiap amal manusia, baik maupun buruk. Akan tetapi kedua
ayat tersebut, menurut perkiraan para sarjana Bible, dikomposisikan pada masa-masa
terakhir, sehingga diduga doktrin tentang akhirat itu berasal dari pengaruh Persia.
Kedua ayat tersebut berbunyi:
Thy dead shall live, my dead bodies shall arise--awake and sing, ye that dwell in the dust--for Thy dew is as the dew of light, and the earth shall bring to life the shades.
And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to reproaches and everlasting abhorrence.174
Terlepas dari pandangan para sarjana Bible dan terlepas dari pengaruh mana pun
yang telah melahirkan ayat-ayat ini, konsep tentang hidup sesudah mati tentu saja
mempunyai akar yang kuat dalam tradisi Yahudi. Walaupun hanya dua ayat yang
menyatakannya secara eksplisit dalam Bible, para rabbi telah sering berbicara
tentang the World to Come. Sebagaimana dalam Islam, penafsiran terhadap hari
akhirat dan kebangkitan manusia juga berbeda-beda dalam tradisi Yahudi –
172Maccabees adalah sebuah keluarga Pendeta Yahudi yang memimpin pemberontakan terhadap penguasa Seleucid, Antiochus IV, yang berkuasa pada 175-164/163 SM. Tindakan Antiochus IV yang mengedepankan kebudayaan dan institusi Yunani serta merendahkan dan menekan habis-habisan tradisi Yudaisme berakhir pada pemberontakan Maccabees tersebut yang terjadi pada 168-164 SM. Lihat Encyclopaedia Britannica, s.v. “Maccabees,” Deluxe Edition 2004 CD-ROM.
173George Robinson, Essential, 192.
174Isaiah 26: 19 dan Daniel 12: 2.
tergantung jalur pemikiran yang diambil: simbolik atau literal! Apakah jiwa (soul) itu
kekal, dan kematian berarti terlepasnya jiwa dari tubuh untuk hidup dalam
keabadian, atau Tuhan memang mengembalikan jiwa itu ke dalam tubuh yang telah
mati sehingga ia hidup kembali? Ini hanya pertengkaran para filosof dengan kaum
literalis, sebagaimana dalam Islam.
Mengapa Bible hampir saja tidak memberikan perhatian pada persoalan
kehidupan akhirat? Menurut Louis Jacobs,175 para penulis Bible tidak mungkin tidak
mengetahui sama sekali tentang doktrin ini sementara mereka mengetahui tentang
piramida dan bukti-bukti lain yang mengisahkan keyakinan orang-orang Mesir serta
masyarakat kuno lainnya tentang kehidupan sesudah mati. Sikap Bible yang relatif
“diam” soal eksistensi akhirat barangkali sebagai protes terhadap keterikatan doktrin
tersebut dengan agama-agama pagan pada masa itu. Mungkin itu pula sebabnya
sehingga, dalam Leviticus, melakukan kontak dengan orang meninggal sekalipun
dilarang.
(1) And the LORD said unto Moses: Speak unto the priests the sons of Aaron, and say unto them: There shall none defile himself for the dead among his people; (2) except for his kin, that is near unto him, for his mother, and for his father, and for his son, and for his daughter, and for his brother; (3) and for his sister a virgin, that is near unto him, that hath had no husband, for her may he defile himself.
Namun sejak masa pasca-Biblikal sampai sekarang, kepercayaan akan hari akhirat
menjadi dominan dalam pandangan dan pemikiran keagamaan Yahudi. Keyakinan
akan keadilan Ilahi bagi setiap individu menjadikan keyakinan akan adanya hari
pembalasan tidak dapat dielakkan, terlepas dari bagaimana bentuk dan konsep
tentang hari akhir tersebut. Jika kehidupan di dunia tidak mampu mewujudkan
175Louis Jacobs, The Book, 231.
keadilan yang sesungguhnya, maka hanya tinggal satu harapan: Tuhan akan
membangkitkan kembali manusia dan memberi mereka keadilan. Menurut Emil L.
Fackenheim, jika ditanya mengapa Bible tidak memberikan perhatian pada masalah
tersebut, maka respon para rabbi adalah bahwa itu hanya karena kita tidak mengerti.
“There is not a single chapter in the Torah” … “which does not contain the doctrine
of the resurrection of the dead; only we cannot understand it.”176 Karena itu, dalam
puji-pujian yang telah menjadi bacaan resmi, orang-orang Yahudi membaca: Thou
sustainest the living with kindness, and revivest the dead with great mercy … Thou
canst be trusted to revive the dead. Praised be Thou, O God, who revivest the
dead.177
Doktrin kebangkitan dalam tradisi Yahudi memang diperselisihkan.
Persoalannya adalah, seperti telah disebutkan, tidak tersurat secara jelas dalam Bible
bahwa kematian bukan akhir dari kehidupan manusia. Perselisihan ini sudah muncul
sejak kelompok Sadducees dan Pharisees (abad kedua SM.) berbeda paham, bukan
hanya soal agama tetapi juga politik. Lebih tiga abad sebelum Masehi, orang-orang
Yahudi berada dalam kekuasaan Yunani, dan Hellenisme mulai menyusupkan
pengaruhnya kepada mereka, bahkan tidak lama kemudian Bible pun diterjemahkan
ke dalam bahasa Yunani. Pengaruh sebuah peradaban tentu membawa dampak yang
besar bagi kehidupan, pandangan dan perilaku suatu masyarakat. Tradisi dan adat
istiadat lama mengalami perubahan dan tantangan. Ada yang sepakat dan ada yang
tidak. Dari sinilah berawal munculnya kelompok pro-Hellenizer yang diwakili oleh
176Emil L. Fackenheim, What is Judaism: An Interpretation for the Present Age, (New York: Collier Books, 1987), 270.
177Ibid.
Sadducees dan anti-Hellenizer yang diwakili oleh Pharisees. Saddusees adalah
kelompok aristokrat, karena itu sangat segan merusak tatanan politik yang ada;
namun dalam soal agama mereka sangat konservatif. Sebaliknya Pharisees, mereka
berbasis pada grass root, rakyat jelata. Mereka konservatif dari sudut pandang
politik, namun terbuka dan bersikap liberal dalam pemahaman keagamaan. Mereka
membuka ruang yang lebih longgar dalam menalar kitab suci, dan memperkenalkan
penafsiran yang lebih elastis. Paham merekalah yang menjadikan tradisi Yahudi terus
hidup dan bertahan sampai hari ini dan mampu menjawab berbagai tantangan yang
sulit berhadapan dengan perubahan-perubahan.178
Tidak dapat dipastikan, apakah Yahudi yang berbasis pada aliran pemikiran
Saddusees atau Pharisees, ataupun lainnya, yang bermigrasi dan menetap di Arabia
sampai zaman Islam. Jika teori yang mengatakan bahwa gelombang migrasi Yahudi
ke gurun Arabia terjadi setelah Romawi menguasai Yerusalem dan melakukan
tindakan kekerasan dan supresi terhadap orang-orang Israel179 dapat dijadikan
pegangan, maka ada kemungkinan bahwa kebanyakan di antara mereka adalah
orang-orang yang konservatif secara politik dan liberal dalam pemikiran keagamaan.
Aliran yang berakar pada Pharisees barangkali lebih dominan.
Dari mana pun asal mereka, orang-orang Yahudi Medinah/Arab ternyata
memiliki ajaran yang mengenal hari akhirat; sorga dan neraka adalah gagasan yang
telah familiar bagi mereka. Namun, dari catatan-catatan al-Qur’an, mereka terlihat
lebih cenderung mempermainkan doktrin tersebut untuk merendahkan Nabi 178Max I. Dimont, Jews, God and History, (New York: Penguin Books, Edisi Revisi
1994), 93.
179Lihat Gordon Newby, A History of the Jews of Arabia (South Carolina: University of South Carolina Press, 1988), 14-23
Muhammad dan ajaran Islam. Menurut al-Qur’an, mereka telah mengalami krisis
moral, dan keyakinan mereka akan hari akhirat telah kehilangan signifikansinya.
Hari akhirat bagi mereka tidak lagi merupakan hal penting; kalaupun itu ada, mereka
menganggap dapat memenangkannya. Artinya, sekiranya saja hari akhirat terjadi,
dan mereka akan dihukum karena dosa-dosanya, itu hanya akan berlangsung sebentar
saja. Karenanya, tidak begitu mengkhawatirkan. Berikut, ayat-ayat tersebut dikutip
kembali:
Dan mereka berkata: “Kami tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja.” Katakanlah: “Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya, atau kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?”
Katakanlah: “Jika negeri akhirat (yakni surga) itu khusus untukmu di sisi Allah, tidak untuk orang lain, maka bercita-citalah untuk (segera) mati, jika kamu memang benar.”
Mereka tidak akan pernah mencita-citai kematian itu (segera) selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka (sendiri). Dan Allah Maha Mengetahui tentang orang-orang yang aniaya.180
Menurut apa yang dituturkan al-Qur’an, doktrin hari akhirat, sorga dan
neraka, dalam tradisi Yahudi, tetap mengakar dengan kuat. Persoalan yang menjadi
sorotan al-Qur’an adalah bagaimana orang-orang Yahudi menyikapi hari akhirat itu.
Al-Qur’an berulang kali mengingatkan mereka akan kerugian besar yang akan
menimpa mereka jika mengabaikan pesan-pesan Tuhan dan bertingkah laku semata-
mata atas pertimbangan kepentingan hawanafsu. Mereka telah berkata bohong.
Ucapan-ucapan mereka tentang akhirat tidak lebih dari upaya mengelak seruan Nabi
Muhammad kepada kebenaran atau ajaran Tuhan yang lurus. Buktinya – demikian
al-Qur’an mencoba menyelami ke dalam perasaan batin mereka yang penuh
180Q.S. al-Baqarah: 80 dan 94-95.
keguncangan – mereka sangat takut menghadapi kematian. Sekiranya mereka yakin
dengan sungguh-sungguh bahwa mereka akan selamat dari azab Tuhan di akhirat,
atau akan menjalani kehidupan penuh bahagia di sorga, tentu mereka tidak perlu
takut mati dan bahkan berharap dapat mengalaminya dalam waktu dekat.
Sebagaimana diriwayatkan al-T{abarī, dari Abū al-‘Āliyah, ayat 94 di atas
diturunkan sebagai respon terhadap pernyataan orang-orang Yahudi dan Nasrani
bahwa tidak akan masuk sorga kecuali golongan mereka saja dan mereka adalah
anak-anak dan kekasih Tuhan. Maka al-Qur’an turun menantang mereka dengan cita-
cita segera mengalami kematian untuk meraih kebahagiaan akhirat itu, jika mereka
jujur dengan ucapannya itu.181 Tetapi ternyata mereka menolaknya. Ibn ‘Abbās
mengatakan, sekiranya pada waktu itu mereka berani bercita-cita segera mati, maka
mereka benar-benar akan mati semuanya.182
Sejauh ini, apa yang dapat dicerapi dari berbagai ekspresi al-Qur’an tentang
sejumlah pandangan keagamaan Yahudi adalah bahwa al-Qur’an terutama sekali
sangat concern soal prinsip-prinsip moral dan universalitas nilai-nilai kemanusiaan.
Al-Qur’an menolak dengan keras segala bentuk diskriminasi yang muncul dari
pandangan kemanusiaan yang sempit, dan mengkritik dengan tajam paham-paham
keagamaan yang telah terdistorsi oleh angan-angan kosong, arogansi rasial dan
kesombongan religius serta penyelewengan-penyelewengan atas dasar mengikuti
hawanafsu. Orang-orang Yahudi “dituduh” oleh al-Qur’an sebagai telah melakukan
kecurangan-kecurangan tersebut. Mereka telah mempersempit agama Tuhan yang
181Al-T{abarī, Jāmi‘ al-Bayān, Vol. 1, 425.
182Ibid.
sesungguhnya amat luas, terbuka dan dinamis. Bagi al-Qur’an, ini adalah fakta –
yakni fakta yang disaksikan sendiri secara langsung oleh Nabi Muhammad. Al-
Qur’an jelas berbicara tentang orang-orang Yahudi Medinah, sebab dalam
kenyataannya al-Qur’an memang tidak berbicara mengenai sesuatu beyond the scope
of its natural environment.
Notasi al-Qur’an tentang Yahudi tidak dapat dikatakan meliputi seluruh aspek
dari tradisi umat tersebut dengan beragam aliran pemikiran dan interpretasi
keagamaan yang sangat variatif. Tidak dapat juga diklaim bahwa pandangan-
pandangan Yahudi Medinah/Arab yang dikecam al-Qur’an telah mewakili seluruh
pandangan Yahudi di seluruh dunia. Hal yang paling jelas adalah, bahwa al-Qur’an
mengkritik segala bentuk arogansi: rasial, intelektual, religius ataupun lainnya.
Arogansi tidak lebih dari sikap pengecut yang justeru menumbuhkan keberanian
dalam bentuk lain: berani berdusta, berani melakukan penyelewengan-
penyelewengan dan sebagainya. Al-Qur’an telah menjadikan Yahudi sebagai
prototipe sejarah sebuah umat yang dapat dijadikan pelajaran bagi semua umat lain,
mungkin karena al-Qur’an menemukan banyak hal “menarik” pada mereka.
Terakhir, sebagai kesimpulan dari sub bab ini adalah bahwa ayat-ayat yang
mengkritik kaum Yahudi kebanyakan diturunkan di Medinah sebagai respon
terhadap perilaku mereka yang tercela. Beberapa sikap mereka yang arogan telah
menyebabkan kerasnya bantahan al-Qur’an, sampai pada pernyataan bahwa mereka
adalah kafir dan terkutuk. Pandangan-pandangan Yahudi tentang diri mereka dan
beberapa keyakinan yang mereka nyatakan kepada Nabi dikritik keras oleh al-
Qur’an, karena dianggap bertentangan dengan semangat dasar ajaran Tuhan. Jika
dicermati dengan seksama, pandangan-pandangan mereka tersebut tidak mewakili
ajaran yang dikenal luas dalam tradisi keagamaan umat Yahudi sampai hari ini.
Mungkin itu hanya pandangan “segelintir” orang di kalangan Yahudi Medinah pada
waktu itu atau hanya olok-olokan mereka kepada Nabi (seperti pernyataan bahwa
mereka tidak akan masuk neraka sebab mereka adalah kekasih Tuhan; kalau pun
masuk neraka hanya beberapa hari saja); olok-olokan tersebut juga bisa jadi dalam
bentuk penyelewengan penafsiran terhadap ajaran agama mereka sendiri, seperti
penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad atas dasar larangan Taurat menerima
seseorang yang mengaku sebagai rasul Tuhan sebelum ia memperlihatkan bukti
mukjizat tertentu. Menurut al-Qur’an, dalam beberapa hal ini orang-orang Yahudi
telah bertindak melampaui batas dan tidak dapat ditolerir, maka mereka dikecam
dengan keras serta ditunjukkan bagaimana dalam sejarah perjalanan hidup bangsa
mereka Tuhan telah menurunkan berbagai azab karena perilaku mereka di zaman
dahulu juga tidak jauh berbeda dari mereka yang dihadapi al-Qur’an.
Jadi, jika konteks ini diperhatikan, maka akan terlihat bahwa Yahudi yang
menjadi sasaran al-Qur’an tersebut adalah jelas, yakni mereka yang sedang
berinteraksi dengan Nabi di Medinah. Siapa pun yang mempelajari sejarah dan
ajaran agama Yahudi dengan baik, tidak akan dapat menerima “tuduhan-tuduhan” al-
Qur’an itu sebagai kebenaran yang bersifat general dan berlaku untuk seluruh
kehidupan dan ajaran dalam tradisi umat Yahudi di dunia ini.
C. Mentalitas dan Intelektualitas Umat Yahudi
Deskripsi al-Qur’an tentang berbagai karakteristik Yahudi dapat dipahami
sebagai gambaran bagaimana sebuah masyarakat merespon kebenaran yang dibawa
oleh para nabi. Sebuah komunitas umumnya memiliki mentalitas dan cara berpikir
yang khas, namun tidak mesti mencerminkan mentalitas dan cara berpikir setiap
individu di dalamnya. Kebenaran dan keadilan tidak setiap saat memenangkan
pertarungan. Kegelapan kadang-kadang, pada masa-masa tertentu, lebih lantang dan
lebih didengarkan, sebab manusia sering kali lebih ingin agar hasrat lahirnya
terpenuhi dan lupa akan hasrat jiwanya. Karena itu setiap Nabi berhadapan dengan
beragam tingkah laku kaumnya: di antara mereka ada yang mendukung risalahnya
dan ada pula yang membangkang; bahkan tidak jarang di antara mereka yang lebih
suka menjadi oportunis. Siapa di antara mereka yang lebih dominan? Ini sangat
beragam, tergantung sejarah dan peradaban yang telah melahirkan umat tersebut.
Apa yang diperlihatkan oleh al-Qur’an mengenai mentalitas bangsa Yahudi adalah
contoh bagi umat Nabi Muhammad. Tuhan telah memilih bangsa Yahudi karena
ketundukannya dan juga telah menghukum mereka karena pembangkangannya.
1. Membangkang dan Membunuh para Nabi
Ini adalah di antara kejahatan berat yang “dituduhkan” al-Qur’an kepada
orang-orang Yahudi. Mereka menentang ajaran yang disampaikan nabi-nabi mereka
dan bahkan sebagian dari nabi-nabi itu mereka bunuh. Sebagaimana telah disinggung
sebelumnya, setelah meninggalkan Mesir bersama Nabi Musa, orang-orang Yahudi
sudah mulai menampakkan sikap kasarnya dan berani melawan aturan-aturan yang
telah ditetapkan. Di Sinai mereka membuat Nabi Musa murka. Sepeninggal beliau
menjemput firman Tuhan di gunung Sinai, mereka membuat patung anak lembu
emas dan menyembahnya. Musa pulang dengan amarah, sebab Tuhan sangat murka.
Namun Musa tetap bermohon kepada Tuhan agar murka-Nya tidak menurunkan
bencana kepada mereka; dan Tuhan ternyata bersedia memaafkan.183
Bukan hanya itu, mereka juga mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas
terhadap Nabi mereka.
(2) And the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and against Aaron in the wilderness; (3) and the children of Israel said unto them: ‘Would that we had died by the hand of the LORD in the land of Egypt, when we sat by the flesh-pots, when we did eat bread to the full; for ye have brought us forth into this wilderness, to kill this whole assembly with hunger.184
Maka al-Qur’an mengatakan:
Dan tiada seorang nabi pun datang kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.185
Al-Qur’an bahkan mengutip ucapan mereka yang lebih menyakitkan lagi, yaitu
ketika Nabi Musa mengajak mereka berperang melawan musuh pada saat hendak
memasuki kota Yerusalem:
Mereka berkata: “Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja.”186
Tentang hal ini, al-Qur’an telah mengemukakan sederetan kritik yang
panjang. Dalam surat al-Baqarah, mulai ayat 40 sampai 123, seperti telah disinggung 183Exodus 32: 11-14.
184Exodus 16: 2-3.
185Q.S. al-Zukhrūf :7.186Q.S. al-Mā’idah: 24.
sebelumnya,187 al-Qur’an terus menerus mengingatkan Bani Israil dan mengajak
mereka kepada agama yang benar, yaitu sebagaimana diajarkan oleh para nabi
mereka. Sungguh menarik, al-Qur’an tidak terlihat sama sekali berkeinginan untuk
mengkonversi mereka kepada agama “Islam.” Al-Qur’an hanya mengajak mereka
untuk mematuhi aturan moral dan hukum sebagaimana mereka sendiri telah
mengenalnya dengan baik. Dengan nada sangat akrab, al-Qur’an bahkan mengajak
mereka bersembahyang bersama-sama.188 Al-Qur’an tidak memiliki keberatan sama
sekali soal ini, berbeda dari sikap al-Qur’an terhadap orang-orang musyrik atau kafir
penyembah berhala yang dipisahkan secara tegas: “bagimu agamamu dan bagiku
agamaku.”189 Kalau pun al-Qur’an menyeru kepada “Islam,” maka yang
dimaksudkan tidak lebih dari sikap pasrah dan ketundukan sepenuhnya kepada
Tuhan. Dalam ayat 40 sampai 123 surat al-Baqarah tersebut, al-Qur’an mereview
kisah perjalanan panjang Bani Israil mulai dari kelepasan dari Firaun di Mesir
sampai kehadiran mereka di Kanaan; mulai dari liku-liku kehidupan mereka bersama
Musa, kemarahan dan kasih sayang, pembangkangan dan hukuman, tuduhan-tuduhan
terhadap nabi, seperti Sulaiman, tentang Ibrahim yang menjadi panutan dan sumber
tradisi mereka, sampai kepada sikap mereka terhadap Nabi Muhammad. Tidakkah
mereka sadar, demikian al-Qur’an menasehati, akan konsekuensi setiap amal yang
mereka kerjakan di dunia ini di hadapan mahkamah Tuhan di akhirat nanti?
Tidakkah mereka takut akan suatu hari di mana tidak seorang pun dapat
187Lihat halaman 125.
188Q.S. al-Baqarah: 43.
189Q.S. al-Kāfirūn: 6.
menyelamatkan manusia kecuali dirinya sendiri, dan tidak seorang pun dapat
menebus dosa/kesalahannya dengan suatu apa pun?190
Intinya adalah, sebagaimana telah di sebutkan, bahwa orang-orang Bani Israil
telah diberi karunia yang banyak oleh Tuhan, namun mereka selalu saja
membangkang terhadap ajaran Tuhan dan tidak mau berterima kasih. Jika ternyata
mereka menolak kenabian Muhammad, itu tidak lebih dari sebuah “lagu lama” yang
telah pernah “dinyanyikan” oleh para pendahulu mereka. Mereka tidak perlu banyak
membuat alasan; al-Qur’an tidak akan mau mendengarnya. Kisah-kisah dalam tradisi
mereka sendiri menunjukkan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran-
pelanggaran yang nyata di hadapan nabi mereka sendiri; mereka membangkang dan
bahkan membunuhnya. Mereka menolak kebenaran bukan karena kebenaran itu tidak
nyata, tetapi karena kedengkian mereka semata. Maka al-Qur’an dengan mantap
menegaskan:
Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Berimanlah kepada al-Qur’an yang diturunkan Allah,” mereka berkata: “Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami,” dan mereka kafir kepada al-Qur’an yang diturunkan sesudahnya, padahal al-Qur’an itu adalah al-h}aqq (kebenaran); yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah: “Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?”191
Sepertinya ini adalah alasan orang-orang Yahudi yang mereka anggap paling
moderat dan mungkin paling mereka harapkan dapat diterima al-Qur’an/Muhammad
soal mengapa mereka menolak beriman kepada kitab tersebut. Mereka mengatakan
bahwa mereka telah memiliki Taurat dan beriman kepadanya; mereka tidak perlu
190Misalnya, Q.S. al-Baqarah: 48.
191Q.S. al-Baqarah: 91.
beriman lagi kepada al-Qur’an. Bantahan al-Qur’an terhadap alasan ini mengacu
pada kenyataan sejarah mereka sendiri: “Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-
nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?” Kalau diparafrase, al-
Qur’an seolah-olah mengatakan: “Kamu tidak beriman! Bukan hanya kepada al-
Qur’an kamu tidak beriman, tetapi juga kepada kitab yang pernah diturunkan kepada
kamu, sebab jika benar kamu beriman, kamu tidak akan melakukan perbuatan jahat
seperti yang telah kamu lakukan. Lagi pula, al-Qur’an membenarkan kitab Taurat
yang diturunkan kepada kamu. Jika kamu membantahnya, berarti sama dengan
membantah Taurat itu sendiri.”
Para mufassir umumnya memberikan komentar yang sama mengenai rujukan
al-Qur’an kepada mereka yang disebut telah membunuh para nabi. Dalam ayat di
atas, yang menjadi lawan bicara al-Qur’an tentu saja orang-orang Yahudi Medinah.
Lalu mengapa tuduhan pembunuhan terhadap nabi-nabi Bani Israil di zaman dahulu
ditujukan kepada mereka? Mengapa mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan
nenek moyang mereka? Ketika menjelaskan ayat tersebut, yakni ungkapan “mengapa
kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang
beriman?,” al-T{abarī pertama sekali mengemukakan perbedaan pandangan para
pakar bahasa Arab soal struktur gramatika yang digunakan. Al-Qur’an
mengekspresikan pernyataan itu dengan kata kerja mud}āri‘ (masa sekarang atau
akan datang), yaitu taqtulūn, tetapi tiba-tiba muncul frase min qabl yang
menunjukkan kepada masa lalu (mād}ī). Ini menimbulkan problem dari segi ilmu
nah}w. Menurut para pakar nah}w Bas}rah (al-Bas}ariyyūn), makna frase tersebut
setelah ditakwilkan mejadi fa lima qataltum ... Hal ini, kata mereka, karena dalam
ekspresi bahasa Arab mād}ī dan mud}āri‘ kadang-kadang sama saja, seperti
ungkapan: famā ad}h}ā wa la amsaytu... Sementara itu, menurut pakar Kūfah (al-
Kūfiyyūn)192 meskipun diungkapkan dengan kata kerja mud}āri‘, maksudnya adalah
mād}ī; orang kadang-kadang mengungkapkan apa yang telah terjadi pada masa lalu
dengan menggunakan kata kerja mud}āri‘, seperti: wayh}aka lima takdhib (celaka
kamu, mengapa berdusta). Takdhib adalah kata kerja mud}āri‘, tetapi jelas yang
dimaksudkan adalah peristiwa yang telah terjadi. Lalu bagaimana memahami
tuduhan “kamu telah membunuh para nabi” yang ditujukan al-Qur’an kepada lawan
bicaranya, yakni orang-orang Yahudi Medinah? Itu karena para pendahulu mereka
telah melakukannya dan mereka mendiamkan serta merelakannya, maka kejahatan
tersebut juga dinisbatkan kepada mereka.193 Al-T{abarī kemudian menyimpulkan
bahwa meskipun al-Qur’an mempertanyakan kepada orang-orang Yahudi Medinah,
mengapa mereka (telah) membunuh para nabi, yang dimaksudkan adalah semacam
khabar atau berita yang mempertanyakan “mengapa para pendahulu kamu telah
membunuh para nabi?” Al-Qur’an mengajukan pertanyaan itu kepada orang-orang
Yahudi Medinah karena mereka mengatakan beriman kepada Taurat, hal mana tidak
berbeda dari sikap pendahulu mereka yang juga mengatakan beriman kepada Taurat,
tetapi tetap melakukan kejahatan.194
192Kesimpulannya sebenarnya sama juga dengan al-Bas}ariyyūn, mereka hanya beda dalam teori.
193Al-T{abarī, Jāmi‘ al-Bayān,Vol. 1, 419-420. Lihat juga tafsir lain, misalnya al-Qurt}ubī, al-Jāmi‘ li Ah}kām al-Qur’ān, (Kairo: Dār al-Sya‘b, Cet II, 1372 H.), Vol. 2, 30.
194Ibid., 421.
Sikap al-Qur’an seperti itu dapat dipahami, mengingat orang-orang Yahudi
sendiri mendakwa diri mereka sebagai sebuah umat, a nation, yang istimewa dan
eksklusif. Mereka adalah satu, sebuah komunitas yang tidak dapat dipisah-pisahkan;
mereka adalah umat dan kekasih Tuhan. Keyahudian, menurut mereka, menjadi
alasan bagi segala kebaikan dan keselamatan. Maka tatkala al-Qur’an mengatakan
“mengapa kamu membunuh para nabi,” sesungguhnya al-Qur’an sedang memberikan
sebuah sindiran yang amat tajam. “Kamu” adalah kamu semua orang Yahudi, jika
merujuk kepada klaim mereka sendiri sebagai sebuah identitas eksklusif. Namun
generalisasi yang dibuat al-Qur’an bukan tanpa batas. Al-Qur’an, setelah mengkritik
orang-orang Yahudi, tentu saja tidak mungkin dirinya juga terlibat dalam
eksklusivisme. Al-Qur’an menyadari bahwa tidak semua orang Yahudi ingkar
kepada ajaran agama Tuhan. Sebagian mereka memang beriman, walaupun amat
disayangkan bahwa kelompok ini amat sedikit.
Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa (alasan) yang benar serta ucapan mereka: “Hati kami tertutup.” Namun sebenarnya, Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil di antara mereka.195
Pada kesempatan lain al-Qur’an menunjukkan bukti yang lebih konkret
bahwa mereka sebenarnya hanya berpura-pura saja menampakkan diri sebagai orang
religius dan seolah-olah berpegang teguh pada kitab suci dalam menentukan berbagai
sikap dan kegiatannya, yaitu tindakan mereka berkolaborasi dengan orang-orang
kafir:
195Q.S. al-Nisā’: 155.
Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan.
Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong. Tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.196
Para mufassir berbeda pendapat mengenai siapa “mereka” yang dimaksudkan
dalam kedua ayat di atas. Menurut al-Wāh}idī (w. 468 H.), mereka tersebut adalah
orang-orang Yahudi, dan orang-orang kafir yang menjadi teman kolaborasi mereka
adalah kaum musyrik Mekkah.197 Sementara itu al-Baghawī (w. 516 H.) mengutip
dua pendapat yang berlainan. Pendapat yang pertama mengatakan, “mereka” itu
adalah orang-orang Yahudi, khususnya Ka‘b ibn al-Asyraf dan teman-temannya,
sedangkan kolaborator mereka adalah orang-orang musyrik Mekkah. Mereka bekerja
sama dengan orang-orang kafir pada saat melakukan penyerangan terhadap Nabi
Muhammad. Sedangkan menurut pendapat yang lain, yaitu yang bersumber dari Ibn
‘Abbās dan Mujāhid, mereka yang dimaksudkan itu adalah orang-orang munafik dan
kolaborator mereka adalah kaum Yahudi.198 Namun jika dilihat konteks susunan ayat,
maka lebih tepat jika “mereka” yang dimaksudkan dalam ayat tersebut dipahami
sebagai orang-orang Yahudi atau Bani Israil. Demikian pula “nabi” yang disebutkan
dalam ayat berikutnya, akan lebih sesuai kalau dipahami sebagai Nabi Musa,
walaupun kebanyakan mufassir klasik memahaminya sebagai Nabi Muhammad.
196Q.S. al-Mā’idah: 80-81.
197Al-Wāh}idī, al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz, (Beirut: Dār al-Qalam, 1415 H.), Vol. 1, 331.
198Al-Baghawī, Ma‘ālim al-Tanzīl, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1987), Vol. 2, 56.
Dengan demikian, makna ayat tersebut menjadi: “Sekiranya orang-orang Yahudi
atau Bani Israil itu beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa dan kepada Taurat
yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang
musyrikin Mekkah itu menjadi kolaboratornya pada saat mereka ingin menyerang
Nabi Muhammad. Sayangnya, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik,
sehingga kecenderungan mereka kepada orang-orang kafir lebih besar.”
Pengertian seperti ini sebenarnya lebih memperlihatkan kesejarahan
hubungan Nabi Muhammad dan al-Qur’an dengan orang-orang Yahudi Medinah.
Semangat dari ayat-ayat seperti ini adalah menegaskan bahwa orang-orang Yahudi
yang menentang Nabi tidaklah beriman kepada Taurat. Penolakan mereka terhadap
Nabi dan al-Qur’an adalah penolakan mereka (dan juga para pendahulu mereka)
terhadap Musa dan Tauratnya. Semua itu tidak lain melainkan karena keangkuhan
dan kecenderungan mereka mengikuti hawanafsu belaka.
Dan sesungguh telah Kami datangkan kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami ikutkan (berturut-turut) setelah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Rūh} al-Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh; sehingga beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?
Sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israil, dan telah Kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, (maka) sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh.199
Semua ini adalah ekspresi paling nyata dari pandangan al-Qur’an mengenai
sikap orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad. Mereka bukan tidak
menemukan ciri-ciri kebenaran pada ajaran yang disampaikan Nabi; mereka hanya
199Q.S. al-Baqarah: 87 dan al-Mā’idah: 70.
menyombongkan diri dan mengikuti keinginan hati yang cenderung tidak sejalan
dengan agama Tuhan.
Upaya orang-orang Yahudi membunuh para Nabi disebutkan al-Qur’an
berulang-ulang sampai sepuluh kali200 dengan konteks dan tekanan yang agak
berbeda. Namun pada dasarnya ayat-ayat tersebut mengacu pada dua argumentasi,
yaitu: Pertama, orang-orang Yahudi menolak ajaran yang disampaikan para rasul
Tuhan karena tidak sejalan dengan keinginan nafsu mereka. Ajaran para nabi bersifat
tegas dan menggugat segala ketidakadilan dan kejahatan, baik individual maupun
sosial. Karena itu, mengikuti kebenaran yang diajarkan para nabi menjadi amat berat
bagi mereka yang tidak bermoral dan tidak memiliki kedisiplinan. Kedua, akibat dari
tindakannya itu, orang-orang Yahudi telah menuai kemurkaan Tuhan dan mendapat
berbagai bencana dan kehinaan.
Ayat-ayat di atas memperlihatkan dengan jelas adanya perselisihan yang
tajam antara Nabi Muhammad dan orang-orang Yahudi di Medinah. Mereka
menolak kenabian Muhammad dengan menggunakan alasan keagamaan. Muhammad
bukan seorang nabi, kata mereka, karena Muhammad tidak dapat menunjukkan bukti
mukjizat sebagaimana mereka mintakan, yaitu kurban yang dimakan oleh api yang
turun dari langit.201 Al-Qur’an lalu memberikan respon dengan mengatakan bahwa
itu hanyalah dalih mereka saja. Kalau benar, mengapa nabi-nabi yang menunjukkan
mukjizat tersebut mereka ingkari juga dan bahkan mereka bunuh? Al-Qur’an
mengakui, bahwa sebagian mereka kadang-kadang lebih suka bersikap tidak jelas,
200Q.S. al-Baqarah: 61, 87 dan 91; Āli ‘Imrān: 21, 112, 181 dan 183; al-Nisā’: 155 dan 157; al-Mā’idah: 70.
201Q.S. Āli ‘Imrān: 183.
skeptis dan menghindar. Kelompok ini menunjukkan sikap pengakuan
tersembunyinya akan kebenaran ajaran Nabi Muhammad, akan tetapi mereka sendiri
lebih cenderung untuk tidak terlibat.202 Al-Qur’an mengajukan kritik terhadap mereka
dari sisi bahwa mereka lebih mementingkan kedudukan duniawi daripada kebenaran;
al-Qur’an menyebutnya sebagai telah membeli kehidupan dunia dengan akhirat atau
menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah.203
Telah didiskusikan bagaimana mereka menolak beriman kepada Nabi
Muhammad dengan menggunakan alasan agama, bahwa sebuah mukjizat harus
ditunjukkan sebagaimana mereka kehendaki. Mereka menolak beriman kepada al-
Qur’an dengan alasan bahwa Taurat sudah cukup bagi mereka. Lalu al-Qur’an
menegaskan bahwa mereka hanya berdalih semata. Ayat-ayat berikut memperjelas
permusuhan mereka dengan Nabi Muhammad dan memperlihat bagaimana mereka
memutarbalikkan perkataan untuk mencela Nabi dan memperolok-olokkan agama:
Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagian berupa kitab (Taurat)? Mereka membeli (memilih) kesesatan (dengan petunjuk) dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat (menyimpang) dari jalan (yang benar).
Dan Allah lebih mengetahui (daripada kamu) tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi Penolong (bagimu).
Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata: “Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya,” “dengarlah, bukan diperdengarkan,” dan “rā‘inā,”204 dengan
202Q.S. al-Baqarah: 44.
203Q.S. al-Baqarah: 86 dan 41.
204Dalam surat al-Baqarah: 104, al-Qur’an melarang orang-orang mukmin mengatakan rā‘inā, tetapi unz}urnā. Kedua kata ini mempunyai arti yang hampir bersamaan, yaitu: “dengarkanlah kami baik-baik” atau “perhatikanlah kami.” Tetapi rā‘inā termasuk kata-kata kasar dalam percakapan dan kata ini sering digunakan orang-orang Ans}ār pada masa jahiliah. Lalu orang Yahudi menggunakan kata tersebut ketika berbicara
memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan: “Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami,” tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit saja.205
Al-Qur’an berulang kali mengingatkan Nabi bahwa orang-orang Yahudi itu
menentangnya bukanlah karena keyakinan mereka akan agama Musa dan Taurat,
tetapi justeru karena mereka kufur atau ingkar. Ayat-ayat seperti ini tentu saja
diturunkan dalam rangka menenteramkan hati Nabi dan meneguhkan jiwanya.
Penolakan orang-orang Yahudi terhadap risalah yang dibawanya tentu saja
merupakan pukulan berat yang ia hadapi. Mereka adalah orang-orang yang dianggap
potensial oleh Nabi, tetapi justeru mereka yang menghadang langkah dakwahnya.
Maka ayat-ayat seperti ini merupakan spirit yang dapat memberikan kekuatan dan
keteguhan hati bagi Nabi.
2. Berdalih dan Berhilah
Di antara kisah Bani Israil yang paling menyakitkan untuk didengar adalah
ihwal mereka diperintahkan menyembelih seekor lembu betina. Kisah ini tidak hanya
seolah-olah jenaka, tetapi memang tentang sebuah “lelucon” yang disengajakan oleh
Bani Israil terhadap nabi mereka – sebuah jenaka sekaligus sebuah kisah yang tragis.
dengan Nabi, sebagai celaan tersembunyi terhadapnya. Lihat al-Qurt}ubī, al-Jāmi‘, Vol. 2, 57; al-T{abarī, Jāmi‘ al-Bayān, Vol. 1, 468. Ada riwayat yang bahkan mengatakan bahwa rā’inā adalah kata yang mengandung cercaan dalam bahasa orang Yahudi, namun riwayat ini dianggap lemah. Lihat Abū Syahbah, al-Isrā’īliyyāt wa al-Mawd}ū‘āt fī Kutub al-Tafsīr (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1408 H.), 313. Maka al-Qur’an melarang orang-orang mukmin menggunakannya dan menggantikannya dengan kata lain yang lebih baik, unz}urnā.
205Q.S. al-Nisā’: 44-46.
Ia jenaka karena mengandung “permainan,” tragis karena yang dipermainkan adalah
seorang nabi utusan Tuhan. Bible Yahudi tidak menyebutkan kisah seperti ini,
walaupun isyarat ke arah kisah yang hampir sama memang ada. Namun al-Qur’an
menceritakan kisah itu secara mendetil. Sayyid Qut}b menafsirkan kisah itu, di
antara lain, sebagai gambaran bagaimana kaum Bani Israil mencari hilah untuk
melepaskan diri dari perintah Tuhan.206
Pada suatu waktu terjadi sebuah pembunuhan di kalangan Bani Israil. Mereka
berselisih tentang siapa pembunuhnya. Maka Tuhan menyuruh menyembelih seekor
lembu betina dan dagingnya dipukulkan ke tubuh mayat orang terbunuh itu, agar ia
hidup kembali dan berbicara untuk mengungkapkan pelaku pembunuhan terhadap
dirinya. Perintah penyembelihan inilah, serta sikap mereka dalam meresponinya,
yang diungkapkan al-Qur’an sebagai contoh tingkah laku Bani Israil
mempermainkan perintah Tuhan atau perintah nabi mereka.
Dan (ingatlah), tatkala Musa berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina.” Mereka bertanya: “Apakah kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan?” Musa menjawab: “Aku berlindung kepada Allah daripada termasuk di antara orang-orang yang jahil.”
Mereka berkata: “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu.” Musa menjawab: “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.”
Mereka berkata: “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya.” Musa menjawab: “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya.”
206Sayyid Qut}b, Fī Z{ilāl al-Qur’ān, (Beirut: Dār Ih}ya’ al-Turāth al-‘Arabī, 1971), Vol. 1, 102-103; Fī Z{ilāl al-Qur’ān, Edisi CD-ROM, (Jordan: Arabic Textware), 77.
Mereka berkata: “Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk (untuk memperoleh sapi itu).”
Musa berkata: “Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya.” Mereka berkata: “Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya.” Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak (dapat) melaksanakan perintah itu.207
Ketika diperintahkan menyembelih seekor lembu mereka tidak langsung
melaksanakan perintah tersebut. Mereka enggan melakukannya dan menghindar
dengan berbagai alasan dan pertanyaan, walaupun pada akhirnya mereka terpaksa
melaksanakannya juga, dengan susah payah. Dalam literatur Islam kisah ini
umumnya dikenal sebagai cercaan terhadap Bani Israil karena sikap mereka
memperolok-olok rasul Tuhan. Disebutkan juga bahwa sekiranya mereka langsung
saja mencari seekor lembu dan menyembelihnya, tanpa memperbanyak pertanyaan,
sungguh persoalannya telah selesai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah
memperberat diri mereka sendiri.208
Dalam literatur tafsir klasik, kisah tersebut telah diperlebar ke beberapa
masalah lain yang terkait, secara lebih rinci lagi. Mereka menambahkan beberapa
kisah moral ke dalamnya: bagaimana latar belakang terjadi pembunuhan, siapa yang
menemukan mayat tersebut, di mana mereka akhirnya mendapatkan lembu itu,
berapa harganya dan siapa pemiliknya. Semuanya terkait secara integral dan
mempunyai makna moral tersendiri. Merujuk kepada al-T{abarī, al-Qurt}ubī dan al-
207Q.S. al-Baqarah: 67-71.
208Al-T{abarī, Jāmi‘ al-Bayān, Vol. 1, 339; Ibn Kasir, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Az}īm, (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H.), Vol. 1, 111.
Rāzī, Mahmoud Ayoub mengatakan: Since the cow was finally specified, it was
necessary to obtain it at any cost. Therefore, either a widow and her orphaned
children, or pious but poor man, were paid large sums of gold for the cow.209
Al-T{abāt}abā’ī210 mungkin sedikit di antara mufassir – kalau bukan satu-
satunya – yang menyadari bahwa kisah semacam itu tidak terdapat di dalam Bible
Yahudi. Karena itu, menurutnya, akan lebih tepat kalau kepada orang-orang Yahudi
Medinah tidak dibacakan kisah ini, atau paling tidak, hanya dibacakan setelah
menunjukkan penghapusan yang mereka lakukan terhadap Taurat mengenai kisah
ini. Namun dalam salah satu hukum Taurat terdapat bukti bahwa peristiwa
penyembelihan tersebut pernah terjadi. Al-T{abāt}abā’ī mengutip ayat-ayat Bible
mengenai peristiwa itu. Dalam versi Bahasa Inggris ayat-ayat tersebut berbunyi:
(1) If one be found slain in the land which the LORD thy God giveth thee to possess it, lying in the field, and it be not known who hath smitten him; (2) then thy elders and thy judges shall come forth, and they shall measure unto the cities which are round about him that is slain. (3) And it shall be, that the city which is nearest unto the slain man, even the elders of that city shall take a heifer of the herd, which hath not been wrought with, and which hath not drawn in the yoke. (4) And the elders of that city shall bring down the heifer unto a rough valley, which may neither be plowed nor sown, and shall break the heifer’s neck there in the valley. (5) And the priests the sons of Levi shall come near--for them the LORD thy God hath chosen to minister unto Him, and to bless in the name of the LORD; and according to their word shall every controversy and every stroke be. (6) And all the elders of that city, who are nearest unto the slain man, shall wash their hands over the heifer whose neck was broken in the valley. (7) And they shall speak and say: ‘Our hands have not shed this blood, neither have our eyes seen it. (8) Forgive, O LORD, Thy people Israel, whom Thou hast redeemed, and suffer not innocent blood to remain in the midst of Thy people Israel.’ And the blood shall be forgiven
209Mahmoud Ayoub, The Qur’an and Its Interpreters, (Albany: State University of New York Press, 1988), 117.
210Al-T{abāt}abā’ī, al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān,(Beirut: Mu’assasah al-A‘lāmī li al-Mat}bū‘ah, 1393 H./1973 H.), Vol. 1, 200.
them. (9) So shalt thou put away the innocent blood from the midst of thee, when thou shalt do that which is right in the eyes of the LORD.211
Pengutaraan Bible Yahudi tentang kisah ini sangat berbeda dari pengutaraan
al-Qur’an. Bagi kebanyakan Muslim, ini jelas karena orang-orang Yahudi telah
menghapus atau melakukan distorsi terhadap kisah yang sebenarnya dalam kitab suci
mereka. Namun bagi seorang Yahudi Orientalis seperti Abraham Geger, ini adalah
salah satu bukti distorsi, atau penjiplakan keliru, yang dilakukan al-Qur’an terhadap
Bible.212 Dengan pendekatan keagamaan masing-masing yang berbasis pada
prasangka, jelas pemahaman kedua belah pihak tidak akan pernah ketemu. Namun,
barangkali, dengan menggunakan literary analysis dalam memahami kitab suci,
seseorang dapat lebih tercerahkan dan tidak akan merasa “tertekan batin” ketika tidak
menyalahkan kitab suci mana pun. Latar belakang sosial budaya lahirnya Bible dan
al-Qur’an sangat berbeda dan masyarakat yang mereka hadapi juga berbeda. Karena
itu nuansa, style, kecenderungan ekspresi bahasa dan berbagai ibarat di dalamnya
juga akan sangat berbeda. Isi al-Qur’an, baik perintah, larangan, tamsilan maupun
kisah-kisah tidak diadopsi dari teks Bible, walaupun dalam perkembangannya
merefleksikan kecenderungan kitab ini kepada isu-isu dalam Bible, karena ia harus
berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Namun demikian, tampak dengan jelas,
bahwa concern al-Qur’an tetap mengacu pada akar budaya dan paradigmanya
sendiri: masyarakat dan peradaban Arab, dengan pesan-pesan yang universal. Karena
itu, mengingat perkembangan kisah-kisah Bani Israil dalam tafsir-tafsir al-Qur’an,
meskipun tidak terdapat dalam Bible, tidak mustahil bahwa kisah-kisah tersebut telah 211Deuteronomy 21: 1-9.
212Abraham Geiger, Judaism and Islam, trans. F.M. Young, 1896, 136 (Downloaded from Internet: <http://www.answering-islam.org/geiger.zip>).
menjadi tradisi lisan dan sumber pendidikan moral, serta dikenal secara luas dalam
masyarakat Arab dan juga orang-orang Yahudi yang hidup di sana pada waktu itu.213
Kembali kepada penuturan al-Qur’an mengenai “kelicikan” Yahudi dalam
mengelak perintah Tuhan, terdapat beberapa ayat lain yang relevan dikutip di sini.
Penulis kutip kembali Q.S. al-Mā’idah: 24 dan 25 yang pernah dikutip sebelumnya:
Mereka berkata: “Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja.”
Ini merupakan dalih yang amat kasar dan sinis. Kalau diparafrase pernyataan Bani
Israil di atas menjadi: “Hai Musa, kami tidak akan masuk ke kota itu, karena ada
musuh di dalamnya; kami tidak sanggup melawan mereka. Bukankah engkau punya
Tuhan. Jika Tuhanmu itu Maha Hebat dan Maha Kuasa, mengapa tidak engkau pergi
saja dengan Tuhanmu berperang melawan mereka, dan kami dapat beristirahat di
sini.” Tentu saja ucapan mereka amat menyakitkan hati Nabi Musa. Beliau berdoa,
mengadu pada Tuhan:
“Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku, karena itu pisahkanlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu.”
Para nabi selalu mengalami kekecewaan terhadap umatnya. Kisah-kisah
mereka yang disebutkan al-Qur’an tidak terlepas dari ungkapan perasaan yang
menyedihkan itu. Nabi Nuh}, Hūd, S{ālih}, Yūnus214 dan lainnya hampir saja
merupakan simbol kepiluan dalam melangkah lurus di atas jalan risalah dan gerakan
213Bandingkan Reuven Firestone, Journeys in Holy Lands: The Evolution of the Abraham-Ishmael Legenda in Islamic Exegesis, (New York: State University of New York Press, 1990), 157.
214Tentang Nūh} (Misalnya Q.S. Nūh}: 1 ff., dan Hūd: 25-49) ); Hūd (Q.S. Hūd: 50-60); S{ālih} (Q.S. Hūd: 61-68); Yūnus (Q.S. al-Anbiyā’: 87-88 dan al-S{affāt: 139-148).
pemanggilan manusia kepadanya. Nabi Muhammad tidak hanya berhadapan dengan
kafir musyrik Mekkah, tetapi juga dengan orang-orang Yahudi Medinah yang tidak
pernah diperkirakan Nabi menjadi oposannya yang paling keras.
Terkait dengan sikap mereka dalam cara berdalih untuk tidak mengikuti
kebenaran, al-Qur’an telah mencatat bagaimana mereka sampai menyatakan
bermusuhan dengan malaikat Jibril sebagai jalan melepaskan diri dari tuntutan
mengikuti Nabi Muhammad.
Katakanlah: Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu telah menurunkannya (al-Qur’an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.215
Para ulama sepakat bahwa ayat ini diturunkan sebagai jawaban bagi orang-
orang Yahudi yang mengatakan bahwa Jibril adalah musuh mereka dan bahwa yang
menjadi walī mereka adalah Mikail.216 Al-Wāh}idī (468 H.) mengatakan bahwa
orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad, siapa nama malaikat yang
mendatanginya. Nabi menjawab: “Jibril.” Maka mereka berkata: “Jibril adalah
musuh kami; sekiranya yang datang itu adalah Mikail maka kami akan beriman
kepadamu ... sesungguhnya Jibril telah membawa perang dan kekerasan.” Maka
turunlah ayat di atas,217 menegaskan bahwa malaikat-malaikat Tuhan adalah
pelaksana titah Tuhan semata. Jibril dan Mikail adalah sama-sama pelaksana tugas
215Q.S. al-Baqarah: 97-98.
216Al-T{abarī, Jāmi al-Bayān, Vol. 1, 431.
217Al-Wāh}idī, al-Wajīz, Vol. 1, 120.
yang ditetapkan Allah. “Meskipun Jibril telah menurunkan pesan yang mengandung
kekerasan dan perang, ia juga telah menurunkan petunjuk dan kegembiraan bagi
orang-orang mukmin.”218
Mengenai ayat ini, Ibn Katsīr menyebutkan beberapa riwayat yang panjang
tentang perdebatan Nabi dan orang-orang Yahudi, hingga sampai kepada ucapan
mereka: “Sekarang katakan siapa malaikat yang menjadi walī-mu, dan ini akan
menentukan kami mengikutimu atau berpisah denganmu.” Nabi menjawab: “walī
saya Jibril, dan tidak seorang Nabi pun diutus Allah melainkan dia (Jibril) adalah
walinya.” “Kalau demikian,” kata mereka, “kami berpisah denganmu.” “Lalu apa
yang menghalangimu membenarkannya?,” tanya Nabi. Mereka menjawab: “Dia
adalah musuh kami.” Maka turunlah ayat di atas.219
Menurut al-Qur’an, itu hanya alasan yang dibuat-buat. Memusuhi malaikat
Allah sama dengan memusuhi Allah dan “sesungguhnya Allah adalah musuh orang-
orang kafir.” Secara tidak langsung al-Qur’an menilai mereka sebagai orang yang
ingkar. Mereka telah membuat alasan palsu untuk menolak kenabian Muhammad,
sekaligus telah menjerumuskan diri mereka dalam kekeliruan yang besar. Ayat-ayat
ini, sebagaimana telah disebutkan, adalah di antara sederetan ayat-ayat dalam surat
al-Baqarah yang berbicara soal tingkah laku Bani Israil untuk direnungkan kembali
oleh orang-orang Yahudi Medinah dan bahkan sebagian dari ayat-ayat tersebut
merupakan respon langsung terhadap perlakuan dan ucapan mereka terhadap Nabi
Muhammad, seperti kedua ayat yang dikutip di atas. Dalam konteks pembicaraan ini,
218Ibid.
219Ibn Katsīr, Tafsīr, Vol. 1, 130.
kedua ayat tersebut di atas secara khusus memperlihatkan bagaimana mereka
mencuri peluang untuk berdusta atas dasar yang dibuat seolah-olah logis.
Berdasarkan riwayat-riwayat yang dikutip di atas, orang-orang Yahudi menolak
bergabung dalam barisan Islam bersama Nabi Muhammad karena wahyu yang
diterimanya disampaikan oleh Jibril. Mereka lalu “berandai-andai.” Sekiranya pada
posisi Jibril itu adalah Mikail – kata mereka – mereka akan beriman, dan mereka
mengira bahwa alasan tersebut sangat masuk akal dan Nabi tidak akan pernah tahu
bagaimana membantah argumen tersebut. Jibril adalah malaikat pembawa pesan-
pesan perang dan penuh kekerasan. Karena itu mereka memusuhinya.
Pandangan bahwa Jibril dan Mikail berada pada dua posisi yang
berseberangan – yang satu keras dan yang satu lagi penuh kasih sayang – mesti telah
dikenal secara luas di kalangan orang-orang Yahudi Medinah dan juga orang-orang
Arab sejak sebelum Islam. Dalam Bible Yahudi terdapat cukup banyak rujukan
kepada malaikat (Hebrew: malakh), namun hanya Jibril (Gabriel) dan Mikail
(Michael)220 yang disebutkan dengan namanya, sementara malaikat-malaikat lain
tidak diberikan nama. Dalam tradisi Yahudi yang berkembang kemudian, Mikail
dikenal sebagai malaikat rahmat dan Jibril malaikat keadilan. Dalam doa sebelum
tidur, orang-orang Yahudi membacakan kalimat-kalimat sebagai berikut:
In the name of Lord, the God of Israel, may Michael be at my right hand; Gabriel at my left; Uriel before me; Raphael behind me; and the Shekhinah of God be above my head.221
220Gabriel dalam Daniel 8: 16 dan 9: 21; Michael dalam Daniel 10: 13 dan 12: 1.
221Louis Jacobs, The Jewish, 25.
Orang-orang Yahudi Medinah pada masa Nabi tentu mengenal tradisi ini,
yakni bahwa Jibril dan Mikail adalah dua malaikat Tuhan dengan posisi dan tugas
yang berbeda. Kalaupun mungkin ada di antara mereka yang menganggap Mikail
sebagai malaikat favorit, tetapi menganggap Jibril sebagai musuh adalah interpretasi
yang terlalu jauh. Al-Qur’an mengoreksi hal tersebut dan, lebih jauh lagi, mencela
orang-orang yang telah bersikap tidak pantas terhadap malaikat Tuhan. Mereka
sebenarnya – demikian menurut apa yang dapat dipahami dari pernyataan al-Qur’an
– adalah orang-orang yang ingkar dan ucapan mereka itu hanyalah “akal-akalan”
untuk menghindar dari kebenaran.
Dalam ayat lain al-Qur’an menunjukkan sikap mereka yang lebih kasar dan
arogan. Mereka bersikap tidak sopan dan penuh aniaya terhadap orang-orang yang
bukan golongan mereka. Alasan mereka adalah bahwa perbuatan seperti itu terhadap
orang-orang ummī tidaklah berdosa.
Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu Dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummī.” Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.
(Padahal, sebenarnya) siapa yang menepati janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.222
Pernyataan al-Qur’an ini merujuk pada adanya sebagian orang Yahudi yang
tidak mau membayar utangnya kepada orang Arab dengan alasan bahwa mereka sah
secara agama melakukan hal tersebut terhadap selain Ahli Kitab seperti mereka. Al-
Wāh}idī menunjuk ‘Abdullāh ibn Salām dan Finh}ās} ibn ‘Āzūrā’ sebagai dua
222Q.S. Āli ‘Imrān: 75-76.
orang dengan karakter berlawanan yang dimaksudkan al-Qur’an itu. ‘Abdullāh ibn
Salām menunaikan amanahnya, yakni membayar utangnya walaupun banyak,
sementara Finh}ās} lebih suka berkhianat. Ia tidak membayar utangnya walaupun
utang itu cuma sedikit. Menurutnya, mengambil harta orang-orang Arab (al-
ummiyyūn) adalah sah, dibenarkan berdasarkan kitab agama. Al-ummiyyūn (orang-
orang ummī) yang dimaksudkan oleh orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang
Arab semuanya.223 Dua karakter yang disebutkan al-Wāh}idī tentu merupakan
representatif dari dua golongan Yahudi Medinah yang mempunyai sikap berbeda
terhadap Islam, kaum Muslim dan Nabi Muhammad. Yang perlu diperhatikan di sini
adalah bantahan al-Qur’an terhadap alasan mereka yang membolehkan berkhianat
terhadap orang-orang ummī. Mereka telah berbohong, kata al-Qur’an, dan
kebohongan tersebut amat besar risikonya, sebab mereka mengucapkannya atas
nama Tuhan dan mereka melakukannya dengan sengaja.
Sementara pemikir Yahudi, sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya,
memang ada yang berpandangan bahwa orang-orang Yahudi memiliki jiwa (soul)
yang lebih superior dari manusia lainnya. Namun, ini pun tidak berarti mereka
beranggapan bahwa orang-orang Yahudi dapat bertindak sekehendak hati dan
mengeksploitasi umat lain untuk kepentingan dirinya. Yang mereka maksudkan
justeru sebaliknya, since the Jews has a superior soul the demands made on him are
the greater and more severe.224 Benih-benih superioritas diri mungkin telah ada
dalam pemikiran setiap bangsa dan pemeluk agama mana pun, dan telah menjadi
223Al-Wāh}idī, al-Wajīz, Vol. 1, 218.
224Louis Jacobs, The Book, 40.
semacam mekanisme mempertahankan diri dalam kehidupan berbudaya dan
bermasyarakat, sebab seseorang perlu memberi nilai yang lebih bermakna bagi apa
yang dianutnya. Seseorang mencintai keluarganya karena merasa keluarga itu
bermakna bagi hidupnya. Demikian juga, orang berpegang teguh pada agama yang
dianutnya, sebab ia merasa agama tersebut bermakna bagi kehidupan yang
dijalaninya. Maka ketika sebuah keluarga atau agama mendapat tantangan, pemilik
atau penganutnya secara otomatis merasa perlu membelanya. Ini secara umum telah
menjadi mekanisme mental untuk membela diri dalam kepribadian kebanyakan
manusia. Benih mekanisme mental seperti itu dalam sebuah masyarakat akan mekar
dengan baik pada saat-saat masyarakat tersebut merasa harus bergelut dengan
tantangan asing dalam rangka mempertahankan dan mengukuhkan identitas dirinya.
Dalam kasus umat Yahudi, hal ini telah terjadi ratusan tahun sebelum Masehi, ketika
serbuan Hellenisme, peradaban Babilonia dan Persia mengepung mereka. Dalam
Ezra, misalnya, dapat dibaca sebagai berikut:
(1) Now when these things were done, the princes drew near unto me, saying: ‘The people of Israel, and the priests and the Levites, have not separated themselves from the peoples of the lands, doing according to their abominations, even of the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, the Jebusites, the Ammonites, the Moabites, the Egyptians, and the Amorites. (2) For they have taken of their daughters for themselves and for their sons; so that the holy seed have mingled themselves with the peoples of the lands; yea, the hand of the princes and rulers hath been first in this faithlessness.’ (3) And when I heard this thing, I rent my garment and my mantle, and plucked off the hair of my head and of my beard, and sat down appalled.225
Uzair, dalam tradisi Yahudi dikenal dengan Ezra the Scribe, adalah tokoh
yang hampir saja disejajarkan dengan Musa sebagai maha guru Taurat. Ia adalah
seorang pemimpin dan pendeta Yahudi yang mahir. Dialah yang menghidupkan
225Ezra 9: 1-3.
kembali hukum Taurat dan melakukan reformasi kehidupan beragama masyarakat
Yahudi yang baru saja pulang dari pembuangan di Babilonia ke Yerusalem pada 458
SM. Ketika Uzair tiba di tengah-tengah komunitasnya, apa yang disaksikan adalah
destruksi moral yang sudah sangat parah serta pengabaian terhadap hukum agama
yang merajalela. Banyak orang-orang Israel telah bercampur baur dengan kaum
pagan melalui perkawinan. Ini membuat Uzair, sebagai seorang pemimpin agama,
sangat sedih dan marah.226 Apa yang ditakutkan Uzair adalah kemurkaan kembali
dari Tuhan setelah kini Ia memberikan berkah dan karunia, yakni seorang Raja yang
baik hati yang membebaskan mereka dari perbudakan dari penguasa zalim di
Babilonia.
(8) And now for a little moment grace hath been shown from the LORD our God, to leave us a remnant to escape, and to give us a nail in His holy place, that our God may lighten our eyes, and give us a little reviving in our bondage. (9) For we are bondmen; yet our God hath not forsaken us in our bondage, but hath extended mercy unto us in the sight of the kings of Persia, to give us a reviving, to set up the house of our God, and to repair the ruins thereof, and to give us a fence in Judah and in Jerusalem. (10) And now, O our God, what shall we say after this? for we have forsaken Thy commandments, (11) which Thou hast commanded by Thy servants the prophets, saying: The land, unto which ye go to possess it, is an unclean land through the uncleanness of the peoples of the lands, through their abominations, wherewith they have filled it from one end to another with their filthiness.227
Dalam suasana seperti itulah dia menyuruh kaumnya mengusir isteri-isteri
mereka yang berasal dari orang asing dan anak-anak yang telah mereka lahirkan.
Dalam konteks kehidupan tradisional, Uzair adalah seorang otoritas yang sangat
menyayangi masyarakatnya dan menginginkan mereka tetap berada dalam tuntutan
226Encyclopædia Britannica, Deluxe Edition 2004 CD-ROM, s.v. “Ezra.” Lihat juga Louis Jacobs, The Jewish, 159.
227Ezra 9: 8-11.
agama yang benar; dan orang asing yang dilihat Uzair adalah tidak lain dari kaum
pagan yang tidak mengenal agama yang benar.
Presentasi Bible tentang sikap Uzair itu mungkin merupakan kisah yang
sebenarnya dan mungkin juga telah bercampur dengan ide-ide dan interpretasi
pengarang. Tidak seorang pun tahu persis apa yang sebenarnya telah terjadi, dan
tidak seorang pun akan mengetahuinya dengan pasti. Namun secara historis, para ahli
percaya bahwa Uzair telah melakukan sebuah reformasi hukum yang luar biasa
setelah umat Yahudi pulang dari pembuangan di Babilonia. Yang jelas, apa yang
dikisahkan oleh Bible mengenai sikap Uzair yang tidak menginginkan bercampurnya
benih yang kudus dengan benih-benih lainnya dapat diinterpretasikan bermacam-
macam. Tidak mengherankan bahwa sebagian orang-orang Yahudi telah
memahaminya sebagai memberi makna bagi superioritas bangsa mereka sebagai
orang-orang yang berasal dari benih yang diistimewakan Tuhan.
Sikap dan interpretasi seperti itu dapat saja terjadi dalam komunitas manusia
di mana saja dan pada zaman mana pun. Ketika Islam datang, di antara orang-orang
Yahudi Medinah mungkin terdapat orang-orang yang berpaham demikian, atau,
sekurang-kurangnya, dalam usahanya menolak kenabian Muhammad, meremehkan
Islam dan kaum Muslim, ia mencoba merujuk pada tradisi yang telah dikenalnya itu,
yang tersurat dalam kitab suci. Memang sering, kitab suci dijadikan sebagai alat
legitimasi bagi sikap dan tindakan-tindakan moral yang sebenarnya tidak terpuji. Al-
Qur’an menangkap gejala tersebut di kalangan orang-orang Yahudi yang
dihadapinya dan, sebagai wahyu Tuhan, ia dengan berani membeberkan kebohongan
yang telah mereka lakukan. Lebih lanjut al-Qur’an mengatakan:
Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari kitab, padahal ia bukan dari kitab; mereka mengatakan: “Itu dari sisi Allah,” padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui.228
Al-Qur’an, sebagaimana telah berulang kali ditegaskan, selalu membantah
orang-orang Yahudi dengan merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan yang lebih
universal. Al-Qur’an tidak membantah kitab suci yang, menurut orang-orang Yahudi,
adalah dasar rujukan pandangan keagamaan mereka. Al-Qur’an mengkritik sikap dan
ucapan-ucapan tidak benar yang mereka keluarkan terhadap Nabi, wahyu dan kaum
Muslimin. Al-Qur’an boleh disebut bersikap “skeptis” terhadap isi kitab suci umat
lain. Ini mungkin karena dalam kenyataannya apa pun yang disebutkan dalam kitab
suci dapat dipahami dan diinterpretasikan bermacam-macam. Dalam hal ini sikap al-
Qur’an lebih realistis dan kebenaran yang ditawarkan al-Qur’an lebih manusiawi dan
rasional. Maka pada saat ada orang Yahudi yang enggan membayar hutang dengan
dalih legitimasi dari kitab suci, al-Qur’an langsung merespon: Itu adalah bohong; ia
menolak membayar hutang hanya karena kedengkian hati dan khianat; siapa yang
menepati janjinya, itulah sebenarnya orang yang disukai Allah.
3. Tidak Konsisten dalam Beragama
Termasuk ayat yang paling sering dikutip oleh kaum Muslim, bukan hanya
untuk menunjukkan kejelekan kaum Yahudi tetapi juga – disadari – untuk menjadi
peringatan bagi umat Islam sediri, adalah mengenai kritik terhadap orang-orang
228Q.S. Āli ‘Imrān: 78.
(Yahudi) yang tidak komit secara tulus terhadap kebenaran dan tidak serius dalam
usaha menegakkannya. Mereka mengenal kebenaran dengan baik namun tidak
merasa berkewajiban untuk berpegang teguh padanya. Jika ada orang bertanya
tentangnya, ia menjawab dengan jujur, tetapi ketika dituntut melaksanakannya, ia
menghindar. Al-Qur’an bertanya kepada mereka: “Apakah kamu tidak berpikir?”
Apakah kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakannya terhadap dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab (Taurat)? Apakah kamu tidak berpikir?229
Para mufassir umumnya mengaitkan ayat ini dengan sikap orang-orang
Yahudi Medinah yang menyuruh orang-orang lain mengikuti ajaran Nabi
Muhammad, sementara mereka sendiri tidak mengikutinya. Jika dilihat dalam
konteks urutan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, ayat ini masih berbicara soal
sikap Bani Israil dan berbagai kritik serta koreksi terhadap pandangan-pandangan
dan tingkah laku mereka. Mengutip Ibn ‘Abbās, al-Qurt}ubī mengatakan bahwa
orang Yahudi Medinah berkata kepada ipar dan para kerabatnya yang Muslim:
“Tetaplah kalian atas jalan Islam dan ikutilah perintah-perintah Muhammad.
Sesungguhnya ia benar.” Diriwayatkan juga dari Ibn ‘Abbās bahwa ada di antara
pendeta-pendeta Yahudi yang menyuruh para pengikutnya untuk melaksanakan
perintah Taurat, padahal mereka sendiri tidak mengerjakannya. Banyak komentar
lain dikutip oleh al-Qurt}ubī mengenai ayat ini, semuanya merujuk pada sikap atau
perilaku ulama Yahudi yang hanya menganjurkan kebaikan kepada orang lain dan
229Q.S. al-Baqarah: 44.
dia sendiri mengabaikannya. Maka ayat tersebut turun mencela mereka dan, tentu
saja, orang-orang yang mengikuti jejak mereka.230
Sekali lagi, kalau diperhatikan ayat ini dalam konteks ayat-ayat sebelumnya,
ia tampak sebagai kelanjutan dari argumentasi al-Qur’an dalam mengajak orang-
orang Yahudi untuk beriman kepada al-Qur’an. Beberapa ayat sebelumnya mengajak
orang-orang Yahudi melakukan refleksi atas karunia Tuhan yang telah mereka terima
dan karena itu diperintahkan untuk bersikap teguh dalam melaksanakan janji Allah.
Lalu mereka diajak mengimani al-Qur’an, yang tidak lain adalah kitab dari Tuhan
juga dan membenarkan kitab yang ada pada mereka. Mereka, menurut al-Qur’an,
memang seharusnya mendukungnya, jangan malah menjadi penentang di garis
depan. Al-Qur’an berulang kali mengatakan bahwa sebenarnya mereka mengerti
kebenaran yang disampaikannya, namun, amat mengherankan, mengapa mereka
selalu berpaling? Maka kali ini, karena terbukti mereka telah memberikan pengakuan
secara “diam-diam” namun masih bertahan dalam sikap memisahkan diri, al-Qur’an
mendesak: “Apakah kamu menyuruh orang lain semata untuk berbuat kebaikan dan
mengikuti kebenaran, sementara kamu sendiri meninggalkannya? Bukankah kamu
telah membacanya dalam kitab soal larangan berbuat seperti itu? Apakah kamu tidak
menggunakan akal?”
Argumentasi al-Qur’an di sini – dan juga pada bagian-bagian sebelumnya –
terlihat lebih bersifat reflektif. Al-Qur’an mengajak orang-orang Yahudi untuk
berpikir kembali ihwal pandangan dan sikap yang telah mereka ambil terhadap Nabi
Muhammad dan wahyu al-Qur’an. Mereka terus menerus diajak dan bahkan, seperti
230Al-Qurt}ubī, al-Jāmi‘, Vol. 1, 365. Lihat juga al-Wāh}idī, al-Wajīz, Vol. 1, 102-103.
terlihat dalam ayat di atas, didesak dengan keras, dengan berlandas pada konsep
universalitas wahyu Tuhan dan kesamaan prinsipil semua ajaran yang disampaikan
oleh para rasul-Nya. Al-Qur’an “heran” melihat sikap orang-orang Yahudi seperti
itu, sebab, jika menggunakan akal sehat, mereka pasti tidak akan melakukannya.
Maka al-Qur’an dengan nada keras bertanya: afalā ta‘qilūn?, apakah kamu sekalian
tidak menggunakan akal?
Apa yang diperlihatkan al-Qur’an di sini adalah lemahnya komitmen orang-
orang Yahudi dalam beragama secara jujur; mereka melihat kebenaran dengan jelas,
tetapi enggan menerimanya; mereka menyuruh orang lain mengikutinya, tetapi tidak
untuk dirinya sendiri. Rujukan al-Qur’an kepada pembacaan kitab oleh orang-orang
Yahudi (wa antum tatlūn al-kitāb) menunjukkan telah dikenalnya madrasah-
madrasah Yahudi di Medinah pada waktu itu. Tradisi membaca kitab Taurat masih
mereka pegang dengan baik, tetapi mengapa, tanya al-Qur’an, mereka tetap saja
menolak kebenaran? Mereka hanya mengakui kebenaran secara parsial.
Dalam ayat lain, pernyataan al-Qur’an mengenai hal ini disebutkan dengan
lebih jelas:
Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.231
231Q.S. al-Baqarah: 85.
Ayat ini sebenarnya masih merupakan lanjutan dari argumentasi al-Qur’an
mengenai pengingkaran orang-orang Yahudi Medinah terhadap kenabian
Muhammad yang seharusnya tidak terjadi karena mereka memiliki pengetahuan
tentang kebenaran tersebut. Selang sepuluh ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 75 surat
al-Baqarah, al-Qur’an telah menunjukkan harapan yang semakin memudar terhadap
dukungan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Ayat-ayat berikutnya
adalah kritik terhadap kecurangan-kecurangan keagamaan yang mereka lakukan,
hingga sampai pada pernyataan al-Qur’an bahwa mereka sesungguhnya telah
berpaling dari agama, kecuali beberapa orang saja.232 Maka ayat di atas merupakan
pengukuhan terhadap hujah-hujah sebelumnya, dalam bentuk bukti historis perlakuan
mereka terhadap sesamanya pada masa terjadinya perselisihan dan peperangan antara
suku-suku Arab Medinah di mana mereka terlibat di dalamnya.
Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, orang-orang Yahudi Medinah
telah lama bersekutu dengan suku-suku Arab sejak sebelum Islam. Dua suku Arab
Medinah, al-Aws dan al-Khazraj, selalu dalam pertikaian dan peperangan pada
zaman sebelum Islam. Orang-orang Yahudi adalah sekutu-sekutu mereka yang
terdapat dalam kedua belah pihak. Banū Qaynuqā‘ dan Banū al-Nad}īr adalah sekutu
suku al-Khazraj, sedangkan Banū Quryz}ah sekutu al-Aws. Dalam peperangan-
peperangan antara dua suku ini, orang-orang Yahudi juga ikut berperang bersama
sekutunya masing-masing. Maka orang-orang Yahudi pun saling membunuh satu
sama lain, padahal, menurut al-Qur’an – dan memang benar demikian – hal tersebut
232Q.S. al-Baqarah: 83.
terlarang dalam agama mereka.233 Setelah perang usai, orang-orang Yahudi yang
tertawan mereka tebus kembali, karena dalam agama mereka diperintahkan
demikian.234 Fenomena inilah yang dirujuk al-Qur’an untuk memperlihatkan bukti
bagaimana orang-orang Yahudi menjalankan sebagian perintah agama dan
mengabaikan sebagian yang lain; mereka tidak berpegang teguh pada ajaran agama
secara jujur, dalam pengertian bahwa mereka akan mengabaikan perintah-perintah
yang merugikan mereka secara keduniaan. Dalam kasus yang dirujuk oleh al-Qur’an
ini, orang-orang Yahudi tetap ikut berperang bersama sekutunya (suku Arab pagan
pada waktu itu) walaupun di pihak lawannya juga terdapat orang-orang Yahudi –
sebuah sikap yang seharusnya tidak diambil jika mereka benar-benar setia pada
janjinya dengan Tuhan.
Pandangan al-Qur’an terhadap sikap orang-orang Yahudi seperti tersebut di
atas semakin hari semakin kokoh, disebabkan oleh konflik dan perdebatan yang terus
233Dalam Talmud terdapat banyak isu kontroversial, terutama mengenai hubungan Yahudi dan non-Yahudi (gentile). Disebutkan bahwa orang-orang Yahudi boleh membunuh orang-orang non-Yahudi, namun dilarang membunuh antara sesamanya. Ayat-ayat Talmud yang dapat dipahami dengan pengertian seperti ini sering dikutip di luar konteks dan dipahami secara literal semata, kebanyakan oleh orang-orang Nasrani dan Muslim, untuk mendiskreditkan umat Yahudi. Lihat misalnya kutipan-kutipan dalam Didik Hariyanto, Mengungkap Kelicikan Yahudi dalam al-Qur’an, Hadis, dan Sejarah, (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002); <http://abbc.com/quotes>; dan respon pada <http://www.geocities.com/ Athens/Cyprus/8815/Response to 1000 Quotes by and about Jews.htm>. Bagi orang Yahudi sendiri, kaum gentile yang dimusuhi dan direndahkan tersebut adalah kaum pagan yang menolak etika monoteisme, sama dengan orang kafir dalam perspektif Muslim. Lihat <http:// talmud.faithweb.com/gentiles.htm>. Mereka dianggap rendah dalam konteks kehidupan spiritual dan bila perlu dapat diperangi. Akan tetapi dalam ayat al-Qur’an yang dikutip di atas, orang-orang Yahudi Medinah justeru telah bersikap sebaliknya. Terlepas dari konsep, interpretasi dan dari sudut bagaimana pun mereka memandang ajaran agama mereka, tindakan yang telah mereka lakukan itu jelas merupakan sebuah penyimpangan berdasarkan klaim mereka sendiri. Ayat ini memperlihatkan metode kritik al-Qur’an yang merujuk pada pandangan dan konsep keagamaan orang-orang yang dijadikan sasaran kritikan.
234Lihat Ibn Katsīr, Tafsīr, Vol. 1, 121-122; al-T{abarī, Jāmi‘ al-Bayān, Vol. 1, 397-398.
menerus antara mereka dan Nabi namun mereka tidak “bergeming” dari pijakan
keyakinan yang telah mereka tancapkan. Seruan al-Qur’an dan ajakan Nabi kepada
Islam bukan saja mereka tolak tetapi bahkan mereka rendahkan. Akan tetapi bagi al-
Qur’an, semakin lama “sepak terjang” mereka semakin membuktikan kebohongan
dan kekerasan hati mereka. Pergumulan sosial dan keagamaan Nabi dan kaum
Muslim dengan kaum Yahudi pada akhirnya terakumulasi pada sebuah keputusan
tanpa kompromi. Al-Qur’an menyimpulkan bahwa mereka benar-benar telah kafir
kepada Tuhan.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memisahkan antara (keimanan kepada) Allah dan (keimanan kepada) rasul-rasul-Nya dengan mengatakan: “Kami beriman kepada sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian (yang lain),” serta bermaksud mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir),
Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.235
4. Materialistik
Materialistik adalah sikap mementingkan keduniaan. Artinya, kepentingan-
kepentingan duniawi lebih didahulukan terutama sekali ketika berhadapan dengan
berbagai tuntutan agama dan moral yang dianggap memberatkan. Sebagai contoh
adalah sikap kaum Yahudi yang dikritik al-Qur’an sebagaimana didiskusikan di atas.
Mereka mengorbankan janjinya dengan Tuhan (agar tidak saling membunuh sesama
235Q.S. al-Nisā’: 150-151. Berdasarkan riwayat dari Ibn ‘Abbās, surat al-Nisā’ diturunkan di Medinah setelah surat al-Baqarah, al-Anfāl, Āli ‘Imrān, al-Ah}zāb dan al-Mumtah}anah. Lihat al-Suyūt}ī, al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, (Kairo: Mus}t}afā al-Bābī al-H{alabī), 1370 H., Vol. 1, 39. Isi surat al-Nisā’ mencakup berbagai persoalan keluarga, seperti perkawinan dan warisan, serta perintah-perintah untuk menegakkan keadilan. Ini mengindikasikan telah tegaknya sebuah institusi sosial yang kuat pada saat tersebut. Jadi pada waktu dan kondisi seperti itulah al-Qur’an mendeklarasikan sikapnya yang tegas terhadap orang-orang yang dihadapinya: mereka adalah orang kafir.
umat Yahudi) demi mempertahankan kesetiaan kepada sekutu Arabnya yang pagan,
sebab hal tersebut akan berdampak terhadap berbagai kepentingan sosial dan
ekonomi mereka. Jadi moral dan agama dikorbankan untuk kepentingan materi.
Istilah lain yang dipakai al-Qur’an untuk sikap seperti itu adalah “membeli kesesatan
dengan petunjuk” atau “menukarkan (mengambil) dunia dengan (melepaskan)
akhirat.”
Dalam al-Qur’an, dunia dan akhirat diekspresikan sebagai dua hal yang
bertentangan. Namun perlu dijelaskan bahwa “dunia” (al-dunyā) yang dimaksudkan
al-Qur’an, seperti kata Rahman,236 bukanlah dunia yang dihuni manusia ini, tetapi the
lower values, nilai-nilai rendah yang tampak secara langsung menggoda dan
membawa pada konsekuensi moral yang negatif. Maka dunia selalu diposisikan
sebagai lawan akhirat, the end: the moment of truth, karena akhirat adalah ujung atau
akhir dari seluruh rangkaian proses pencapaian manusia di dunia ini menuju
kebenaran. Jadi makna dunia dan akhirat dalam al-Qur’an lebih mengacu pada nilai-
nilai, seperti iman, takwa, kesalehan, kufur, fasik dan zalim. Orang yang memilih
dunia berarti memilih kufur atas iman, memilih fasik atas kesalehan dan sebagainya.
Ketika al-Qur’an menuduh orang-orang Yahudi loba terhadap dunia, itu berarti
merupakan sebuah kecaman terhadap pengabaian mereka akan ajaran agama dan
tuntutan moral sebagaimana telah mereka kenal dan pahami dari kitab yang ada pada
mereka.
Materialistik yang dikecam al-Qur’an adalah sikap yang tidak mengindahkan
nilai-nilai moral dan spiritual, membiarkan diri terpedaya oleh angan-angan dan
236Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), 108.
kenikmatan atau keuntungan sesaat namun meruntuhkan nilai yang lebih abadi dan
mulia. Orang yang tunduk kepada angan-angan kosong, yang oleh al-Qur’an
diistilahkan dengan ghurūr,237 dan tipuan-tipuan hawanafsu pada akhirnya akan
kehilangan jalan kembali. Mereka disebut sebagai orang sesat, buta atau telah
tertutup hatinya; mereka sangat susah atau sedikit sekali memiliki kemungkinan
untuk dapat diajak kembali kepada kebenaran.238 Maka tidak mengherankan, pada
saat menemukan tidak ada lagi harapan untuk dapat menyadarkan orang-orang
Yahudi yang dihadapinya, al-Qur’an membuat sebuah ultimatum: tidak ada gunanya
lagi mengajak mereka kepada kebenaran; dunia lebih mereka pentingkan dari akhirat.
Dan sungguh kamu akan mendapati mereka sebagai manusia paling loba kepada kehidupan (dunia), bahkan (lebih loba lagi) dari orang-orang musyrik. Setiap mereka berkeinginan agar kiranya diberi umur seribu tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.239
Orang-orang Yahudi disebutkan di sini lebih loba kepada dunia – bahkan –
dibandingkan orang-orang musyrik. Telah dimaklumi bahwa orang-orang musyrik
Mekkah adalah musuh Islam paling utama. Permusuhan dan penolakan mereka
terhadap Islam di antara lain terkait dengan persoalan kebangkitan dan konsep hari
pembalasan. Kehidupan, kata mereka, hanyalah kehidupan di dunia ini, dan waktu
(al-dahr) akan mengakhiri segalanya.240 Penolakan mereka terhadap hari pembalasan
sekaligus menyebabkan mereka tidak menghiraukan segala aturan dan kedisiplinan
moral. Tidak ada yang ditakuti di dunia selain bencana-bencana yang bersifat 237Misalnya Q.S. Āli ‘Imrān: 185.
238Misalnya Q.S. al-Nisā’: 136; al-Baqarah: 6-7.
239Q.S. al-Baqarah: 96.
240Q.S. al-Jātsiyah: 24.
material, dan kematian akan mengakhiri segalanya. Karena itu kematian amat
ditakutkan, sebab kematian berarti kehilangan yang tidak akan pernah terobati.
Mengapa orang-orang Yahudi dikatakan lebih tamak terhadap dunia daripada
orang-orang musyrik? Ibn ‘Abbās, menurut riwayat al-Tabarī, mengatakan bahwa
orang-orang musyrik tidak pernah mengharapkan hari akhirat (mereka tidak takut
kepadanya, meskipun telah melakukan kejahatan-kejahatan), sementara orang-orang
Yahudi mengetahui apa yang akan terjadi terhadap diri mereka akibat dari
melalaikan kewajiban mengikuti kebenaran yang telah mereka ketahui.241 Karena itu
mereka lebih takut kepada kematian; mereka berangan-angan andaikan saja dapat
hidup seribu tahun. Padahal, demikian menurut al-Qur’an, hidup seribu tahun itu
tidak akan menyelamatkan mereka dari azab Tuhan di akhirat. “Seribu tahun” di sini
tidak perlu diartikan secara literal, dan tidak berarti persis seribu tahun. Itu hanyalah
sebuah metafora untuk mengungkapkan masa yang cukup lama untuk sebuah
kehidupan dunia ini.
Ayat di atas merupakan penegasan kembali terhadap berbagai hujah al-
Qur’an dalam memberi respon terhadap penolakan orang-orang Yahudi akan
kenabian Muhammad. Mereka, sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya,
sebenarnya telah menyaksikan cukup bukti kebenaran risalah yang disampaikan
Muhammad. Mereka menolaknya tidak lain karena keingkarannya semata. Argumen
kemudian bergulir lebih lanjut: mereka menganggap dirinya kekasih Tuhan dan tidak
akan dihukum di hari akhirat (kalaupun masuk neraka pasti hanya sebentar saja),
padahal mereka sangat takut karena kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat.
Sekarang, al-Qur’an membongkar perilaku mereka lebih jauh: ternyata mereka
241Al-Tabarī, Jāmi‘ al-Bayān, Vol. 1, 429.
bahkan sangat tamak terhadap dunia, melebihi ketamakan orang-orang musyrik, yang
mereka sendiri – sesuai dengan ajaran agama yang mereka klaim kebenarannya –
bahkan memusuhinya.
Pada akhirnya, sebagaimana telah disimpulkan dalam sub bab sebelumnya,
apa yang didiskusikan dalam sub bab ini juga menunjukkan pada kesimpulan yang
sama, yakni mengenai sasaran kritik al-Qur’an terhadap umat Yahudi yang secara
khusus ditujukan kepada orang-orang Yahudi Medinah. Al-Qur’an sebenarnya telah
bersikap fair, dengan merujuk pada keyakinan dan tradisi mereka sendiri untuk
menunjukkan bahwa mereka telah melakukan penyimpangan-penyimpangan; sejarah
masa lalu mereka juga disebut-sebut, untuk mengingatkan bahwa, sebagai manusia,
di samping kelebihan, mereka juga memiliki kekurangan. Hal ini dinyatakan al-
Qur’an untuk “memperbaiki” sikap mereka yang terlalu membanggakan diri dan
bahkan merendahkan Islam dan Nabi Muhammad.
BAB VHUBUNGAN YAHUDI-MUSLIM
DALAM KONTEKS PLURALISME AGAMA
BAB yang lalu berupaya menganalisa berbagai kritik dan respon al-Qur’an terhadap
orang-orang Yahudi, dengan mengambil sejumlah ayat yang dianggap representatif.
Tampak bahwa baik narasi maupun respon-respon al-Qur’an tidak pernah keluar dari
paradigmanya sebagai penyampai risalah Tuhan, pemberi kabar gembira dan
peringatan; ia mengingatkan manusia kepada Tuhan dan memperbaiki perilaku
mereka sesuai yang diinginkan Tuhan. Al-Qur’an tidak pernah membuat prediksi-
prediksi seperti tukang ramal, dan tidak pula mencoba menerobos ke masa silam
yang tidak pernah dikenal umat manusia – tidak tampak berminat membongkar the
unknown history. Kisah-kisah al-Qur’an tentang Bani Israil dan respon-responnya
terhadap orang-orang Yahudi Medinah berada pada tataran yang wajar, rasional,
humanis dan really did make sense. Tidak ada bukti bahwa orang-orang Yahudi telah
membantah dengan mengatakan, misalnya, al-Qur’an telah membuat kutipan sejarah
yang keliru. Fakta justeru menunjukkan sebaliknya, bahwa orang-orang Yahudi tidak
dapat membantah al-Qur’an, meskipun mereka tetap menolaknya dengan berbagai
dalih yang lain. Apakah ini berarti bahwa narasi-narasi Bible Yahudi yang dicatat
kembali oleh al-Qur’an – walaupun dalam versi yang agak berbeda dari yang dikenal
oleh mainstream Yahudi – diakuinya sebagai cerita yang bersifat faktual dan
historis? Tidak mesti demikian. Kisah-kisah al-Qur’an tidak mesti merupakan fakta
sejarah, tetapi, tidak diragukan lagi, merupakan fakta tentang watak dan perilaku
moral manusia sepanjang sejarah.1
Bab ini akan memuat analisa dan refleksi lebih jauh terhadap pandangan-
pandangan yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya serta pandangan dan
interpretasi penulis sendiri yang didasarkan pada berbagai argumentasi baik
bersumber pada berbagai fakta yang telah dikemukakan maupun merujuk pada
hujah-hujah lain. Tema-tema yang akan dihadirkan di sini adalah berkaitan dengan
problem-problem hubungan antar agama, khususnya lagi hubungan Yahudi-Muslim,
dengan mengemukakan aspek-aspek interpretasi atau penalaran keagamaan yang
berasal dari sumber utamanya, yakni kitab suci. Analisis ini akan dilakukan dengan
berbagai pendekatan secara dinamis, tidak hanya bertumpu pada aturan-aturan
otoritas dogmatis yang sarat dengan “pembenaran-pembenaran.”2
Patut dicatat bahwa mungkin ada yang khawatir bila sebuah disiplin ilmu
dicampur-tangani oleh pihak di luar disiplin tersebut. Kekhawatiran seperti ini bisa
saja dimaklumi atas dasar bahwa sebuah disiplin memiliki metodologi dan ciri
khasnya tersendiri yang mungkin saja tidak akrab dengan para ahli di luarnya.
Namun kekhawatiran tersebut dapat dikatakan berlebihan jika ditujukan pada upaya
1Persoalan mengenai kisah-kisah al-Qur’an sebagai pelajaran moral, bukan fakta sejarah, telah didiskusikan secara panjang oleh Muhammad Ahmad Khalāf Allāh, al-Fann al-Qas}as}ī fi al-Qur’ān al-Karīm, (Kairo: Sīnā li al-Nasyr wa al-Intisyār al-‘Arabī, 1999); Edisi Indonesia, Muhammad A. Khalafullah, Al-Qur’an Bukan “Kitab Sejarah”: Seni Sastra, dan Moralitas Kisah-kisah al-Qur’an, terj. Zuhairi Misrawi dan Anis Maftukhin, (Jakarta: Paramadina, 2002).
2Djam’annuri pernah mengajukan metode alternatif untuk studi agama-agama yang disebutnya “metode sintesa.” Metode ini dianggap yang paling baik, agar “agama jangan terlalu melangit, tetapi juga tidak terlalu membumi.” Lihat Djam’annuri, “Metode Sintesa: Metode Alternatif Studi Agama,” Jurnal Penelitian Agama, No. 2, September – Desember 1992, 9. Penulis mengikuti metode yang hampir sama, tetapi untuk tujuan yang (penulis ingin menyebutnya) agak berbeda, yakni agar agama dapat dipahami relatif lebih menyeluruh dan pemahaman keagamaan menjadi lebih tercerahkan.
untuk meletakkan sebuah disiplin ilmu pada perspektif yang lebih luas dan dinamik,
sehingga ia menjadi lebih terbuka, bersentuhan dan berinteraksi secara langsung
dengan berbagai disiplin ilmu lain. Tidak jarang orang beranggapan bahwa sebuah
bidang ilmu memiliki metodologi tersendiri yang tidak atau kurang tepat untuk
diterapkan pada bidang ilmu lain. Barangkali ini ada benarnya. Akan tetapi sangat
keliru bila yang dimaksudkan adalah bahwa pada sebuah bidang ilmu hanya dapat
diterapkan satu metodologi atau model pendekatan. Studi al-Qur’an, misalnya,
seperti yang menjadi kajian penulis ini, secara umum dianggap telah memiliki
metodologi yang mantap dan mapan seperti yang diterapkan para ulama Islam (klasik
khususnya), sehingga, meletakkan studi al-Qur’an pada sebuah perspektif baru, atau
mengkajinya dengan pendekatan dan metodologi selain yang dipakai para ulama
Islam akan sangat menggelisahkan. Karena itu tulisan-tulisan Fazlur Rahman, Abū
Zayd dan Khalafullah, misalnya, mendapat kritik yang tidak sehat atau bahkan
kecaman. Apalagi karya-karya Orientalis atau para pakar non-Muslim.
Seperti telah disebutkan sebelumnya, penulis menyadari konsekuensi
tersebut. Akan tetapi tidak berarti seseorang harus berhenti di hadapan sebuah
tantangan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Merambah jalan ke
arah kajian ilmu-ilmu Keislaman yang lebih terbuka dan dinamis sepertinya masih
terus harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Karena itu penulis berkeyakinan
bahwa terus menerus mendialogkan studi Islam dengan studi-studi humaniora
lainnya dan membuka ruang kritik yang lebih luas dan tajam serta secara intelektual
lebih berani adalah di antara upaya yang masih harus dilakukan.
A. Islam dan Pluralisme Agama
Agama telah dipahami berbeda-beda secara konseptual; dalam wacana
filsafat, agama, dalam pengertiannya yang populer, bahkan diperdebatkan
validitasnya. Tidak diragukan bahwa agama telah merupakan wilayah paling
berpengaruh dan memiliki gerakan mengesankan dalam sejarah umat manusia.
Agama telah menggerakkan jutaan umat untuk mengubah dunia dan membangun
peradaban yang mempesona. Karena itu tidak mungkin fenomena ini diremehkan.
Perkembangan agama dan peradaban tidak ada batas; ia akan mencapai
segala jarak dan waktu, sejauh rentangan imajinasi manusia itu sendiri. Agama dan
peradaban tidak terlepas dari visi dan institusi kemanusiaan. Keduanya adalah bagian
dari dimensi kehidupan manusia, cerminan dari ekspresi diri dan wujud dari proses
pencarian dan pembentukan watak sejati manusia yang tidak akan pernah berakhir.
Namun, dari sudut pandang yang lain, bagi hampir semua pemeluk agama, agama
terlalu suci untuk ditarik ke bumi, ke wilayah kehidupan nyata manusia. Agama bagi
mereka adalah sesuatu yang datang ke dunia ini out of the blue, yakni secara tiba-
tiba, terlepas dari semua mata rantai yang menghubungkannya dengan berbagai
proses sejarah dan perjalanan sosial-budaya manusia. Agama tidak bisa dilihat
sebagai hasil kulminasi pergelutan manusia dengan dirinya, lingkungan sosialnya
dan alam semesta; agama turun dari langit, diwahyukan Tuhan dan sama sekali
terpisah dari nalar dan kesadaran kemanusiaan.
Dalam pandangan terakhir di atas, agama dianggap terpisah dari peradaban
manusia: agama adalah ciptaan Tuhan dan peradaban adalah ciptaan manusia.
Pandangan seperti ini pada awalnya ingin memisahkan antara kehendak Tuhan yang
absolut dari kehendak manusia yang relatif dan lemah. Mungkinkah Tuhan
disamakan dengan manusia? Jelas, suatu hal yang mustahil! Tapi pandangan ini
dapat menimbulkan efek negatif bagi kesadaran mental manusia dalam memahami
agama: jika agama dipisahkan dari manusia dan “logika Tuhan” dipisahkan dari
kesadaran akal manusia, maka agama itu sendiri akan menjadi pemenggal yang
memisahkan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas dari iman yang sejati. Kebenaran
akan menjadi kebenaran yang berada di luar nalar kemanusiaan dan keadilan akan
menjadi keadilan yang tak terpahamkan oleh akal sehat. Dalam kondisi seperti ini,
“pemeluk agama yang baik” tidak lebih dari seorang fanatik, dan justifikasi terhadap
segala sesuatu menjadi hitam-putih.
Dari mana agama mulai muncul? Dari seorang manusia sucikah, tanpa ada
kaitannya dengan orang lain sama sekali? Tanpa ada kaitan dengan lingkungan sosial
dan kehidupan manusia sekitarnya? Jelas, dari sudut pandang sejarah, tidak
demikian. Agama dan peradaban berjalan beriringan. Seorang Nabi muncul atas
dasar keresahan yang ia rasakan setelah melakukan refleksi yang mendalam tentang
moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Berbagai teori tentang asal usul agama telah
dibuat oleh para ahli studi agama, namun karena mereka menggunakan pendekatan
yang berbeda maka kesimpulan yang mereka buat juga tidak sama, sesuai dengan
bidang mereka masing-masing. Sebagian mereka lebih menekankan fungsi sosial
agama, sementara sebagian yang lain lebih menekankan aspek psikologi atau
antropologi. Semua ini tidak memberikan hasil yang memuaskan.3
3Hopfe, Lewis M dan Mark R. Woodward. Religions of the World, (New Jersy: Prentice Hall, 1998), 9-10.
Jika sejarah agama-agama dikaji dengan cermat maka akan terlihat bahwa
inspirasi moral dan keadilan mengawali segala kepedulian para pembawa agama.
Sedangkan persoalan teologi dan hukum formal lebih merupakan jalan pemberi
justifikasi bagi moral dan keadilan tersebut. Ini tidak berarti bahwa elemen-elemen
keagamaan yang terkait dengan metafisika, seperti Tuhan, kehidupan akhirat dan
kesadaran spiritual bersifat sekunder bagi sebuah agama, tetapi yang dimaksudkan
di sini adalah bahwa persoalan tersebut bukan hal yang sulit untuk dicapai atau
dibentuk dalam sebuah seruan agama. Kepercayaan adalah hal yang tidak terlalu sulit
untuk dicapai dalam konteks sebuah kehidupan sosial, tetapi apa artinya sebuah
kepercayaan tanpa ada realisasi dalam bentuk moral dan aturan-aturan yang jelas
untuk keselamatan manusia dalam pengertian yang lebih kompleks dan dinamis. Di
sinilah arti pentingnya moralitas dan hukum dalam ajaran setiap agama. Sedangkan
persoalan-persoalan yang terkait dengan keyakinan pada dasarnya memang batang
tubuh dari agama itu sendiri, atau sebagai basis bagi moralitas dan hukum yang ingin
ditegakkan. Jadi apa yang disebut “agama” tidak lain dari gerakan keagamaan, atau
gerakan moral dan keadilan. Adalah para pengikut gerakan tersebut yang kemudian
menerjemahkan seluruh muatan gerakan yang diperjuangkannya ke dalam institusi
yang bernama “agama.” Maka lahirlah agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam
dan lain-lain; penggeraknya adalah Musa, Isa, Muhammad dan lain-lain. Bagi para
pemimpin gerakan keagamaan tersebut, teologi dan perkara-perkara metafisika
bukanlah hal yang dicari lagi, tetapi fenomena yang sangat nyata dalam visi
imajinatif mereka. Visi-visi tersebut datang memberikan landasan bagi moral dan
aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Itulah yang disebut prophetic
phenomenon. Ia tidak perlu dan tidak mungkin dapat dibuktikan, kecuali kita sendiri
yang menjadi nabi dan mengalaminya.
Dalam paradigma seperti di atas, “Islam” adalah sebuah gerakan keagamaan
yang muncul di Mekkah yang merespon situasi meresahkan yang dialami penduduk
kota itu, dan al-Qur’an adalah rekaman seluruh visi gaib yang diperoleh Muhammad,
pemimpin gerakan tersebut. Mungkin akan dikatakan, seperti telah disinggung pada
bagian awal studi ini, bahwa Muhammad tidak pernah bercita-cita mendirikan
sebuah gerakan atau berpikir untuk menjadi nabi. Memang benar. Namun tidaklah
benar kalau dikatakan bahwa ia sama sekali tidak memberikan perhatian pada
keadaan masyarakatnya yang menggelisahkan itu. Muhammad adalah seorang yang
gelisah, dan kegelisahan itulah yang telah memanggilnya untuk mencari jawaban –
jawaban apa pun yang mungkin akan diterimanya untuk dapat mengubah keadaan.
Panggilan itulah yang lambat laun menjadi visi imajinatifnya yang semakin terang.
Akhirnya ia yakin, Tuhan telah memanggilnya untuk menyampaikan risalah.
Siapa yang dapat membuktikan – dalam pengertian verifikasi ilmiah atau
saintifik – kebenaran klaim Muhammad tentang pengalaman spiritualnya selain
dirinya sendiri? Tetapi di sisi lain, apakah dapat dengan mudah ia dituduh sebagai
pembohong, yang telah berpura-pura menerima wahyu dari Tuhan? Kedua hal ini
“tidak mungkin” dilakukan dengan tingkat verifikasi yang pasti. Namun, manusia
mungkin untuk, atau bahkan harus, percaya, bukan hanya sebagai sebuah alternatif,
tetapi juga karena telah merupakan watak batinnya yang penuh misteri. Manusia
sangat cepat secara intuitif menalar segala fenomena yang terkait dengan sebuah
peristiwa lalu inferensi langsung muncul dari benak batinnya yang sangat dalam,
atau di bawah sadar, sebagai sebuah kesimpulan yang meyakinkan – ia percaya.
Orang tidak serta-merta percaya kepada sesuatu. Seluruh rangkaian pengalaman
hidup, pengetahuan dan lingkungan yang membentuk sistem nalar seseorang akan
sangat berpengaruh terhadap keyakinannya atau cara ia meyakini sesuatu. Maka
ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakatnya,
sebagian mereka menerima dan sebagiannya menolak. Demikian juga ketika seruan
itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi, ada di antara mereka yang beriman dan
ada pula yang tidak; sebagian mereka tampak ragu-ragu, sebagian yang lain mungkin
percaya tetapi tetap memberontak.
Kepercayaan akan wahyu yang diterima Muhammad itulah yang merupakan
elan vital keyakinan Islam, dan komitmen terhadap ajaran yang terkandung dalam
wahyu itu yang merupakan sikap seorang Muslim sejati. Sementara itu, konstruk
pemikiran keagamaan dalam peradaban Muslim kemudian menjadikan Islam itu
sebagai sebuah institusi formal di mana seseorang bisa masuk dan keluar darinya,
meskipun keluar dari Islam dianggap sangat berbahaya dan diberikan hukuman yang
sangat berat.
Dalam keyakinan umumnya kaum Muslim, Islam adalah satu-satunya agama
Tuhan yang diturunkan melalui para utusan-Nya sepanjang sejarah Manusia, mulai
dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tuhan adalah satu dan umat manusia satu.
Karena itu agama yang sebenarnya juga satu, yaitu Islam. Para nabi yang diutus
Tuhan pada dasarnya membawa ajaran yang sama. Mereka hanya berbeda dalam
persoalan-persoalan furū‘ (cabang-cabang), seperti aturan-aturan hukum dan tata cara
ritual tertentu, hal mana disesuaikan dengan zaman dan kondisi kehidupan manusia.
Namun ajaran terakhir yang disampaikan Nabi Muhammad adalah yang paling
sempurna dan tidak dibutuhkan lagi penyempurnaan setelahnya.
Pandangan seperti di atas meniscayakan adanya penjelasan bagi posisi agama
lain dalam konteks realitas kehidupan beragama. Jika Islam adalah satu-satunya
agama yang benar maka agama lain yang berbeda dari Islam mesti dianggap salah.
Jika agama-agama tersebut ternyata mesti diakui berasal dari wahyu Tuhan juga
maka jalan untuk membenarkan Islam adalah dengan “memansūkhkan” mereka.
Yahudi dianggap telah mansūkh dengan kehadiran Yesus dan Nasrani juga telah
mansūkh dengan kedatangan Muhammad. Konsep naskh (hapus; agama yang datang
kemudian menghapus agama sebelumnya) ini memainkan peran penting dalam
pembentukan pandangan dan sikap Muslim terhadap agama selain Islam. Masalah ini
akan didiskusikan lebih jauh pada bagian selanjutnya.
Lebih jauh, karena Islam dalam keyakinan Muslim bukan hanya ajaran yang
diseru oleh Nabi Muhammad, tetapi merupakan agama Tuhan sejak Adam, Nuh,
Ibrahim dan sederetan nabi lain sampai Muhammad, maka akan dikatakan bahwa
agama Yahudi dan Nasrani pada dasarnya adalah Islam juga, tetapi para penganut
agama-agama tersebut telah melakukan distorsi terhadap agama mereka sehingga
ajarannya tidak asli lagi. Maka Tuhan menurunkan wahyu kepada Muhammad untuk
memperbarui kembali ajaran yang telah diselewengkan itu. Pandangan seperti ini
tentu saja akan dibantah oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang masing-masing
melihat agamanyalah yang benar dan orisinal, sementara yang lain adalah agama
yang mula-mulanya benar tetapi kemudian menyimpang. Orang-orang Yahudi
menganggap Nasrani sebagai sekte dari agama Yahudi yang sesat, dan Islam tidak
lebih dari sebuah penjiplakan. Begitu pula orang-orang Nasrani, mereka melihat
Yahudi sebagai agama yang telah mansūkh dengan kedatangan Kristus dan Islam
adalah sakte Nasrani yang sesat. Pandangan general seperti ini berada pada level
yang agak toleran, namun pada tataran yang ekstrem, masing-masing melihat pihak
lain sebagai musuhnya yang harus di perangi.
Pandangan suatu agama terhadap agama lain juga telah dipahami secara
berbeda-beda oleh para pemeluknya. Umat Islam, misalnya, tidak memiliki paham
yang seragam terhadap posisi Yahudi dan Nasrani dalam konteks persoalan-
persoalan teologis dan berbagai aspek kehidupan – sama dengan pandangan mereka
mengenai berbagai persoalan keagamaan dalam Islam itu sendiri. Ikhtilāf ternyata
adalah persoalan yang sangat luas. Lalu di mana seseorang harus memposisikan diri?
Apakah semuanya dibiarkan begitu saja, sebagai fragmen kehidupan yang tidak
mungkin lagi dikonstruk menjadi bangunan yang utuh, atau sekurang-kurangnya,
menjadi sesuatu yang mempunyai bentuk dan bermakna?
Seperti telah disinggung pada beberapa tempat sebelumnya, penulis
berpendapat bahwa agama adalah bangunan-bangunan sejarah yang harus selalu
direhab dan disempurnakan. Adanya kepingan-kepingan sejarah yang berserakan
adalah hal yang alamiah; mereka dapat dikumpulkan untuk dijadikan sebuah bentuk
karya baru yang dapat tampil lebih indah dan lebih bernilai. Adanya pendapat yang
beragam dalam satu agama dan adanya agama yang bermacam-macam adalah
produk sejarah, sebagai hasil pergumulan manusia dengan lingkungan sosio-
kulturalnya. Jika kesadaran historis ini dilibatkan dalam konsiderasi-konsiderasi
ketika seseorang menganalisa keragaman agama dan pandangan-pandangan yang
berbeda-beda secara internal dalam suatu agama, maka ketegangan-ketegangan dapat
dikurangi atau bahkan diarahkan kepada kompetisi yang positif. Lebih jauh, tidak
mustahil ketegangan itu sendiri relatif dapat dilenyapkan.
Di atas telah didiskusikan bagaimana pandangan umumnya umat Islam
tentang bangsa Yahudi yang telah menjadi simbol kemurkaan yang seolah-olah tak
terobati. Tidak ada lagi alternatif yang dianggap perlu ditawarkan. Padahal,
sebenarnya kejujuran, keterbukaan dan kesadaran yang kritis dapat menciptakan
kelonggaran dalam memposisikan “diri” berhadapan dengan “orang lain.” Al-
Qarad}āwī, misalnya, meskipun dikenal sangat keras menentang Zionisme, dengan
berani memposisikan Yahudi sebagai lebih dekat kepada Islam dibandingkan
Nasrani. Ini berbeda dari kecenderungan populer yang berdalil dengan ayat 82 surat
al-Mā’idah. Dalam terjemahan buku al-Qarad}āwī, al-Quds: Qad}iyyah Kull
Muslim, tertulis:
… Yahudi lebih dekat dengan orang Islam daripada orang Nasrani, hal ini semua karena agama Yahudi lebih dekat ke agama Ibrahim, baik dalam hal akidah maupun syariah…
Agama Yahudi telah mengikuti sunnah Ibrahim, yaitu menyunati anak-anak mereka sebagaimana kaum Muslimin sedangkan Nasrani tidak melaksanakan hal tersebut. Yahudi telah mensyaratkan penyembelihan sebagai tanda halal bagi hewan-hewan dan burung-burung seperti yang dilakukan oleh orang Muslim, sedangkan orang Masehi tidak mensyaratkan hal tersebut, karena Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu itu suci bagi orang-orang yang suci.
Yahudi mengharamkan babi sebagaimana kaum Muslimin mengharam-kannya, sedangkan Nasrani menghalalkannya. Yahudi mengharamkan patung-patung … sedangkan Nasrani tidak …4
Klarifikasi yang diberikan al-Qarad}āwī memperlihatkan kejujuran seorang
ulama Islam menempatkan pemeluk agama lain dalam konteks teologi Islam yang
4Yusuf al-Qaradhawi [al-Qarad}āwī – pen], Palestina: Masalah Kita Bersama, terj. Tim SAMAHTA ’99, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), 58-59.
“benar.” Walaupun apa yang dilakukan al-Qarad}āwī belum dapat disebut sebagai
konsiderasi berdasarkan sebuah kesadaran sejarah, sikapnya itu telah merupakan
sebuah kesadaran kritis. Ia lebih lanjut mengatakan:
… Jadi apabila kita memerangi Yahudi karena akidah maka [konsekuensinya] kita pun akan memerangi Nasrani masehi juga.5
Dengan demikian tampak jelas, kekeliruan sebagian besar orang awam yang mengira bahwa peperangan yang terjadi antara kita dan Yahudi adalah perang akidah, dan ini berarti bahwa kita memerangi Yahudi karena mereka telah mengingkari Risalah Muhammad, mengubah Kalamullah, menjelekkan hakikat ketuhanan dalam kitabnya, menyamakan Al-Khaliq dengan makhluk ciptaannya sebagaimana Nasrani setelahnya, serta mencemari gambaran Rasul dan para Nabi dan lain sebagainya…
Pandangan seperti ini yang telah menyentuh perasaan orang adalah merupakan kesalahan yang sangat besar…6
Al-Qarad}āwī memang seorang skripturalis, tetapi, sebagai seorang ulama, ia
telah melakukan tugasnya dengan baik. Pernyataan-pernyataan al-Qarad}āwī
tersebut dikutip di sini untuk memperlihatkan bahwa keterbukaan akan menemukan
jalannya sendiri ke arah penempatan diri yang lebih proporsional di tengah-tengah
pluralitas tradisi, budaya dan agama, yang hari ini semakin dirasakan eksistensi oleh
umat mana pun. Di sisi lain al-Qarad}āwī dapat disebutkan di sini sebagai contoh
mewakili salah satu pandangan Islam (baca: kaum Muslim) terhadap agama non-
Islam. Ini sering tidak disadari kebanyakan Muslim karena terpengaruh oleh bias
politik dan propaganda yang dilancarkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu
tanpa memiliki basis keagamaan yang jelas dan kuat.
Sikap seperti di atas membuka jalan bagi toleransi antar umat beragama.
Toleran berarti membiarkan orang menjalankan keyakinannya sejauh tidak
mengganggu keyakinan orang lain. Toleransi biasanya dimanfaatkan untuk
5Al-Qarad}āwī mengatakan hal ini dalam konteks peperangan Arab-Israel.
6Yusuf al-Qaradhawi [al-Qarad}āwī – pen], Palestina, 59-60.
kepentingan politik suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat masyarakat yang
majemuk. Bagi pemerintah ini sangat penting untuk menjaga stabilitas negara dan
membuatnya tetap aman dari konflik dan kerusuhan. Pada tataran intelektual, konsep
toleransi seperti ini tidaklah cukup memadai untuk mendalami makna agama dan
fenomena keagamaan. Toleran hanyalah cerminan dari ketakutan atau pun
ketidakmampuan menjangkau nalar yang berada di luar kesadaran yang telah
terpusat pada diri sendiri. Toleransi mungkin mampu meredam konflik dari luar,
tetapi ia ibarat api dalam sekam: tetap aman selagi masih ada jarak, namun akan
menghanguskan kalau bersentuhan. Toleransi bukan jalan menyelesaikan konflik
antar agama, tetapi hanya sebuah alat politik yang efektif untuk membungkam
keyakinan. Ini tidak berarti toleransi tidak penting, tetapi sesungguhnya ia akan amat
berbahaya ketika dimanfaatkan sebagai alat legitimasi politik sebuah kekuasaan;
toleransi akan membuat jarak di antara pemeluk agama berbeda dan setiap pemeluk
agama yang satu akan melihat agama lain sebagai elemen asing dan berbahaya bagi
kehidupan keagamaannya. Toleransi sebagai sebuah sikap kasual tidak ada masalah.
Dalam studi agama-agama, toleran hanyalah sikap awal dari seorang yang masih
awam terhadap agama lain. Seorang “toleran sejati” akan berhenti di situ selamanya.
Toleransi biasanya diartikan sebagai sikap simpati terhadap keyakinan dan
praktek agama lain meskipun bertentangan dengan keyakinan sendiri. Ini tentu saja
menimbulkan masalah dan secara psikologis berbahaya. Pengertian dasar toleransi
itu sendiri adalah: capacity to endure pain or hardship,7 kemampuan menanggung
sakit atau beban yang berat. Jadi sikap toleran tidak mustahil akan membawa kepada
7“Dictionary & Tesaurus,” s.v. “Tolerance,” dalam Encyclopaedia Britannica, Delux Edition 2004 CD-ROM.
tekanan perasaan yang tidak menyenangkan dan lama kelamaan akan menimbulkan
dampak negatif. Karena itu jalan yang harus ditempuh adalah membangun sikap
keterbukaan dan kesediaan memahami “orang lain.” Dalam konteks kehidupan yang
semakin plural, kesadaran akan kemajemukan tidak dapat dihindari dan bahwa
seseorang terus menerus “dikepung” oleh beragam pandangan dan keyakinan akan
semakin terasa. Ini, seperti telah didiskusikan sebelumnya, adalah konsekuensi logis
dari semakin majunya peradaban dan semakin kayanya imajinasi manusia.
Kesadaran kemanusiaan umat manusia pun dituntut semakin dalam. Kondisi ini tidak
mungkin dan tidak perlu dilawan, tetapi disikapi dengan cermat dan kritis.
Beranjak dari pemikiran di atas, konsep pluralisme merupakan tawaran yang
patut ditelaah secara cermat. Pluralisme atau kesadaran akan keragaman bukanlah hal
baru, tetapi telah ada sejak manusia menyadari bahwa ia tidak “sendirian” di bumi ini
dan bahwa peradaban serta tradisi yang dimiliki manusia tidaklah seragam dan tidak
mungkin diseragamkan. Sulit ditelusuri mengapa fenomena seperti itu eksis dalam
kehidupan manusia. Mungkin telah merupakan hukum dalam alam semesta. Namun
yang jelas, fenomena pluralisme atau keberagaman umat manusia adalah cerminan
dari kekayaan dan keluasan imajinasi manusia serta kemampuannya berkarya tanpa
batas. Oleh karena itu pluralisme mesti disikapi dengan dada lapang serta dijadikan
wacana untuk memperkaya wawasan dan peradaban masing-masing umat, bukan
dijadikan dasar bagi permusuhan. Let hundreds of flowers bloom. Biarkan manusia
dan dunia ini berkembang penuh dinamika.
B. Problem Teologi Islam
Teologi sesungguhnya tidak muncul dari kesadaran ketuhanan, tetapi lebih
merupakan kesadaran ideologis dan identitas diri. Teologi bukan penghayatan, tetapi
permainan logika dan penyusunan argumentasi untuk suatu interest tertentu. Karena
itu tidak mengherankan, seperti kata M. Amin Abdullah, bahwa para teolog tidak
menyukai filsafat sebagai sebuah metodologi,8 walaupun, mungkin, mereka
menyukai filsafat sebagai sebuah paham atau aliran pemikiran. Filsafat sebagai
sebuah metodologi atau pendekatan keilmuan berbeda dari filsafat sebagai sebuah
ideologi atau aliran pemikiran. Filsafat dengan corak pertama ditandai oleh sikapnya
yang kritis, terbuka (open-minded) dan apresiatif terhadap perbedaan dan pluralitas.9
Sedangkan yang kedua mungkin lebih menampilkan sisi keahlian dalam memainkan
argumentasi untuk membela sebuah paham atau aliran.
Teologi telah memainkan peran penting dalam pembentukan sikap suatu
agama terhadap agama lain. Karena itu berhadapan dengan pluralisme agama,
gagasan-gagasan dalam teologi menghadapi masalah. Terkait dengan studi ini ada
dua konsep yang dianggap mendasar dalam pemikiran Islam dan perlu didiskusikan,
yaitu tah}rīf dan naskh. Kedua konsep ini telah menjadi landasan utama bagi teologi
eksklusif umat Islam dan sangat penting untuk dicermati kembali dan dipahami
secara lebih proporsional.
8M. Amin Abdullah, “Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius”, dalam M. Amin Abdullah, dkk., Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 8-10.
9Ibid., 8.
1. Konsep Tah}rīf
Tah}rīf – mas}dar dari h}arrafa-yuh}arrifu – adalah kata yang berasal dari
al-Qur’an sendiri, artinya tindakan mengubah, menyelewengkan, menghapus atau
pun merusak. Orang-orang Yahudi dikatakan al-Qur’an telah melakukan tah}rīf
terhadap firman Allah, sehingga – demikian dipahami oleh para komentator Muslim
– dengan demikian kebenaran yang terkandung di dalam kitab suci mereka,
khususnya mengenai keterangan tentang kenabian Muhammad, telah terdistorsi.
Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya (yuh}arrifūnahū) setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?10
Tetapi apakah tah}rīf tersebut berarti perubahan pada teks kitab suci atau
perubahan/penyelewengan makna dari yang sebenarnya, adalah hal yang
diperdebatkan. Al-Qur’an tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang telah
melakukan hal tersebut, bagaimana prosesnya dan kapan ia melakukannya.
Ayat di atas mengindikasikan kuatnya harapan Nabi Muhammad, dan juga
orang-orang mukmin, agar orang-orang Yahudi beriman kepadanya dan mengikuti
risalah yang beliau sampaikan. Namun al-Qur’an mengingatkan bahwa harapan
tersebut sangatlah sulit diwujudkan, dengan menunjukkan bahwa di antara mereka
bahkan ada yang telah melakukan hal yang lebih buruk, yakni memahami firman
Allah dengan baik tetapi kemudian melakukan tah}rīf terhadapnya. Menurut
Mujāhid, yang melakukan tah}rīf itu adalah ulama Yahudi dan, selanjutnya,
menurut al-Suddī, yang mereka tah}rifkan adalah kitab Taurat. Ada juga pendapat
lain yang mengatakan bahwa mereka telah melakukan tah}rīf dengan mengubah
10Q.S. al-Baqarah: 75.
yang halal menjadi haram atau sebaliknya dan benar (haqq) menjadi batil atau
sebaliknya.11 Menurut al-T{abarī, arti yuh}arrifūnahū itu sendiri adalah yubaddilūna
ma‘nāhu wa ta’wīlahū wa yughayyirūnahū, mereka menggantikan makna dan
ta’wīlnya serta mengubahnya.12 Jadi istilah tah}rīf juga dikenal dengan tabdīl, yakni
menggantikan (dengan yang lain).
Dalam teologi Islam, konsep tah}rīf menjadi “penting” untuk menjelaskan
kontradiksi antara al-Qur’an dan kitab suci yang diyakini oleh orang-orang Ahli
Kitab, terutama sekali mengenai ramalan kedatangan Nabi Muhammad di akhir
zaman yang disebutkan dalam Taurat. Jika orang-orang Yahudi membantah bahwa
ramalan tersebut benar terdapat dalam kitab suci mereka, maka tah}rīf adalah jalan
untuk menjelaskan dan menolak bantahan mereka itu. Sesungguhnya, berdasarkan
argumen ini, dalam kitab Taurat yang asli terdapat ramalan tersebut, namun orang-
orang Yahudi telah menghapusnya untuk menyesatkan manusia dan memenangkan
kepentingan dirinya sendiri. Konsep tah}rīf memang ampuh digunakan sebagai
upaya mematahkan argumentasi lawan. Dengan menunjukkan bahwa sumber “orang
lain” adalah keliru maka dengan sendirinya “kita” telah memenangkan perdebatan.
Tuduhan penyelewengan, pemalsuan atau distorsi dalam kitab suci sejak sebelum
Islam telah dikenal luas sebagai alat perdebatan dengan motif polemik di antara
kaum pagan, orang-orang Samaria (Samaritan) dan para penulis Nasrani. Tuduhan
11Al-T{abarī, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān, (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H.), Vol. 1, 366-367.
12Ibid., 368.
306
seperti itu tentu saja dilakukan masing-masing dalam rangka mendiskreditkan
lawannya.13
Tuduhan pemalsuan kitab suci oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak
menjadi isu sentral pada masa awal Islam, meskipun telah dikenal secara luas. Baru
kemudian, mungkin karena intensitas hubungan kaum Ahli Kitab dengan Muslim
semakin meningkat pada masa-masa kejayaan Islam, isu tersebut menjadi polemik
yang luas dan tajam; studi terhadap Yudaisme menjadi menarik. Banyak penulis
Muslim yang membahas tentang keyakinan dan praktek agama Yahudi, dan mereka
menjadikan tah}rīf salah satu isu penting yang tidak dapat ditinggalkan. Mereka,
seperti telah disebutkan, tidak semuanya sepakat tentang pengertian tah}rīf yang
dituduhkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, apakah hanya berupa
penyelewengan penafsiran atau pun pemalsuan teks kitab suci itu sendiri. Ibn H{azm
(w. 456 H./1064 M.) adalah salah seorang penulis Muslim yang paling gencar
menyerang orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan dengan tegas menyebutkan, dengan
menunjuk sejumlah “fakta” berdasarkan sumber-sumber mereka sendiri, bahwa
mereka telah melakukan tah}rīf dalam pengertian mengubah atau memalsukan teks
kitab suci. Menurut Ibn H{azm, teks-teks kitab suci yang ada di tangan orang-orang
Yahudi itu, yang mereka namakan Taurat, penuh dengan berbagai pemalsuan.
Buktinya, teks-teks yang menjadi pegangan satu aliran di antara mereka berbeda
dengan yang lain: orang-orang Samaria mengatakan bahwa teks Taurat yang berada
di tangan mereka adalah yang benar dan asli sementara teks-teks yang menjadi
13Lihat Hava Lazarus-Yafeh, “Tah}rīf,” dalam The Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 1999); Camilla Adang, Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible from Ibn Rabban to Ibn Hazm, (Leiden: E. J. Brill, 1996), 223.
307
pegangan kelompok Yahudi lainnya telah dirusak dan dipalsukan (muh}arrafah
mubaddalah).14
Sisi lain yang menjadi sasaran kritik Ibn H{azm terhadap Bible adalah
kekeliruan-kekeliruan yang terdapat di dalamnya. Ibn H{azm menganalisa setiap
detil paragraf dari kelima kitab yang dikenal dengan the Five Books of Moses dalam
Bible Yahudi, lalu menyimpulkan bahwa kitab-kitab tersebut penuh dengan berbagai
kalimat keji, kekeliruan historis dan geografis serta kontradiksi di antara sesamanya.
Lebih dari itu, yang lebih penting lagi, menurut Ibn H{azm, pernyataan-pernyataan
di dalamnya bertentangan dengan al-Qur’an. Perubahan paling besar terhadap Taurat
terjadi pada zaman Ezra, setelah penghancuran Yerusalem oleh Nebukadnezar, di
mana Kuil dan kitab-kitabnya dibakar hangus; Taurat lenyap dan hilang dari ingatan
manusia. Setelah Yerusalem dibangun kembali, adalah Ezra yang melakukan
restorasi terhadap kitab suci Bani Israil itu. Walaupun dalam tradisi Islam umumnya
dikenal bahwa Ezra telah mendatangkan kembali Taurat dengan cara yang penuh
mukjizat, tidak demikian menurut Ibn H{azm. Ezra, menurutnya, telah menciptakan
sebuah Taurat baru, tentu saja tidak persis sama dengan transkrip wahyu yang
sebenarnya, dan orang-orang Yahudi mengakuinya demikian.15
Prinsip dasar dari konsep tah}rīf, seperti telah ditunjukkan di atas, merujuk
pada upaya menyalahkan sumber lawan. Jika sumber argumentasi dan otoritas telah
tertolak maka dengan sendirinya seluruh argumentasi akan runtuh dan tidak dapat
diterima. Ajaran Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang, dengan demikian, adalah
14Ibn H{azm, al-Fis}al fi al-Milal wa al-Ahwā’ wa al-Nih}al, (Kairo: Maktabah al-Khānijī, t.t.), Vol. 1, 94.
15Ibid., 95-166; Tentang Ezra, lihat 135-148.
308
batil, tidak sah dan merupakan kebohongan belaka. Mengikut analisis Ibn H{azm,
dapat dikatakan bahwa sepanjang sejarah Yahudi dan Nasrani berada dalam
kegelapan. Jalan keselamatan bagi mereka tidak lain kecuali dengan memeluk agama
Islam. Ini bukan kesimpulan yang mudah. Ibn H{azm melakukannya dengan
mengarang beberapa jilid kitab. Namun perlu disadari bahwa agenda utama sang
pengarang, sebagaimana tercermin dalam hampir setiap kalimat yang
dikeluarkannya, adalah bersifat polemik dan bertujuan untuk membela teologi Islam
dari serangan-serangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sumber-sumber yang
digunakannya juga masih dapat diperdebatkan, walaupun – tidak diragukan – bahwa
dibanding para penulis Muslim lain di zamannya dan sebelumnya, akses Ibn H{azm
ke literatur Yahudi dan Nasrani tampak lebih superior. Ia adalah seorang polemikus
kawakan, memiliki bahasa yang retorik, tegas dan bahkan tajam dalam
menyampaikan kritik. Tidak jarang dalam tulisannya ia mengatakan la‘anahu al-Lāh
(semoga Tuhan mengutuknya) ketika menyebutkan tentang orang Yahudi. Tidak
hanya dengan non-Muslim, kritik-kritik Ibn H{azm terhadap berbagai aliran dan
mazhab dalam Islam juga terkenal keras dan tajam.16
Analisis dan kesimpulan Ibn H{azm bukan tanpa menyisakan ruang yang
menimbulkan tanda tanya. Bagaimana, misalnya, nasib mereka yang tidak memiliki
kesempatan untuk hidup di zaman Islam namun juga tidak dapat menemukan kitab
Taurat atau Injil yang asli? Mengapa al-Qur’an sendiri dan juga Nabi Muhammad
menyuruh orang-orang Yahudi merujuk pada Taurat mereka? Bagaimana memahami
perkembangan sikap al-Qur’an yang tidak sekaligus dan menyeluruh menyalahkan
16Diskusi lebih jauh tentang pandangan Ibn H{azm tentang tah}rīf, lihat Camilla Adang, Muslim Writers, 237-248; tentang kehidupan dan karya-karyanya, lihat misalnya R. Alnardez, “Ibn H{azm,” dalam The Encyclopaedia of Islam.
309
dan mencela orang-orang Yahudi dan Nasrani? Satu pertanyaan yang mungkin tidak
disadari Ibn H{azm dan juga para pencela agama lain adalah: Apakah dengan
menggunakan metode yang sama, al-Qur’an dapat dipastikan sama sekali bersih dari
celah yang dapat digunakan untuk melemparkan tuduhan distorsi atau invalid?
Tidak semua ulama Islam sepakat dengan Ibn H{azm. Menurut Lazrus-
Yafeh, Ibn Khaldūn menolak tah}rīf dalam pengertian penghapusan teks kitab suci,
karena tradisi agama menghalangi penganutnya melakukan hal tersebut.17 Kitab suci
dalam agama mana pun selalu dijunjung tinggi oleh penganutnya, maka bagaimana
mungkin suatu umat dituduh telah merusak kitab suci mereka sendiri. Untuk apa
mereka melakukannya? Mungkinkah mereka merusak agamanya sendiri?
Pernyataan al-Qur’an tentang tah}rīf, seperti telah disebutkan, mengacu pada
pemberian peringatan atau larangan untuk terlalu berharap semua orang Yahudi akan
bergabung dalam risalah Islam yang didakwahkan Nabi Muhammad. Artinya, jika
kitab yang telah ada di tangan mereka sendiri, yang diturunkan dalam tradisi mereka
dan telah merupakan keyakinan bangsa mereka dari zaman dahulu, mereka
selewengkan pengertiannya untuk memenuhi selera nafsu, bagaimana mungkin dapat
diharap mereka akan beriman kepada al-Qur’an yang mungkin tampak asing dan
baru bagi mereka. Sebenarnya mereka tidak berani melawan kitab suci, tetapi mereka
melakukannya dengan cara menyelewengkan pengertiannya.18 Jadi berdasarkan teori
17Lazarus-Yafeh mengutip pandangan Ibn Khaldūn tersebut dari Muqaddimah-nya, tetapi kemudian ia mengatakan bahwa most printed editions omit this remark. Lihat Lazarus-Yafeh, “Tah}rīf,” The Encyclopaedia of Islam.
18Bagi umat mana pun, ketika agama telah menjadi bagian dari tradisi kehidupan mereka, melawan kitab suci bukanlah hal mudah untuk dilakukan. Tindakan tersebut akan sangat berbahaya serta menimbulkan tekanan sosial dan psikologis yang berat. Namun demikian, dengan memberikan penafsiran terhadap kitab suci untuk membenarkan tindakan-tindakan tertentu, beban psikologis tersebut dapat ditekan dan secara sosial cenderung dapat
310
ini,19 tah}rīf yang disebutkan al-Qur’an lebih cenderung untuk dipahami sebagai
penyelewengan dalam memberi makna, bukan mengubah teks. Al-Qur’an juga
tampak berhati-hati dalam mengeluarkan tuduhan ini. Tidak semua orang Yahudi
melakukannya, kata al-Qur’an, tetapi hanya sebagian dari mereka.20 Berikut ini
beberapa ayat tentang tah}rīf akan dianalisa kembali.
Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagian dari kitab (Taurat)? Mereka membeli (memilih) kesesatan (dengan petunjuk) dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat dari jalan (yang benar).
Dan Allah lebih mengetahui (daripada kamu) tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi Penolong.
Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya (yuh}arrifūn al-kalim ‘an mawād}i‘ih). Mereka berkata: “Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya,” “dengarlah, bukan diperdengarkan,” dan “rā‘inā,” dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan: “Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami,” tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit.21
Ayat-ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang Yahudi yang bersikap tidak
pantas terhadap Nabi Muhammad. Menurut penuturan Ibn ‘Abbās,22 adalah Rufā‘ah
ibn Zayd, seorang tokoh Yahudi, yang melakukan hal tersebut. Ketika berbicara
dengan Nabi, ia melakukannya dengan cara yang kasar dan mengatakan: “dengarkan
diterima. Al-Qur’an mengkritik sikap seperti ini, karena yang dicari bukan kebenaran tetapi pembenaran. Karena itu, seperti telah dijelaskan pada bagian tentang tafsir dan ta’wīl, al-Qur’an menekankan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam memahami kitab suci, jangan dita’wīlkan untuk memenuhi kepentingan hawanafsu.
19Diekstrak dari teori Ibn Khaldūn di atas.
20Lihat Q.S. al-Baqarah: 75.
21Q.S. al-Nisā’: 44-46.
22Al-T{abarī, Jāmi‘ al-Bayān, Vol. 5, 116.
311
aku, bukan aku mendengarkanmu.” Ia juga mengatakan “rā‘inā” dengan memutar-
mutar lidahnya23 untuk mencela Nabi. Al-Qur’an memberi respon dengan
mengatakan bahwa hal tersebut telah merupakan watak mereka. Nabi tidak perlu
merasa terbebani dengan sikap mereka seperti itu. Tuhan memang telah mengutuk
mereka, sebab mereka sendiri telah kufur. Tah}rīf telah merupakan bagian dari
“kecerdasan” orang-orang Yahudi dalam mempermainkan kata-kata untuk
mengalahkan lawan bicaranya. Kalau dalam Q.S. al-Baqarah: 75, sebagaimana telah
dikutip sebelumnya, dengan tegas dikatakan mereka telah mentah}rīfkan kalam
Allah, dalam ayat di atas hanya disebutkan secara umum: yuh}arrifūn al-kalima ‘an
mawād}i‘ihī, mereka menyelewengkan kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya
(yang sebenarnya). Dapat saja dipahami bahwa mereka telah menggunakan
pernyataan-pernyataan tidak pada tempatnya, dengan tujuan untuk mencela Nabi
Muhammad dan Islam, ataupun mereka telah menukar-nukarkan pengertian kalimat-
kalimat dalam kitab suci mereka. Menurut Mujāhid, tah}rīf yang disebutkan dalam
ayat di atas bahkan bermakna: orang-orang Yahudi telah menggantikan isi Taurat.24
Adalah sangat mungkin bahwa orang-orang Yahudi Medinah telah dengan
sengaja mengucapkan atau membacakan ayat-ayat Taurat secara keliru kepada Nabi
Muhammad dan kaum Muslim untuk tujuan-tujuan tertentu.25 Mereka melakukan hal
23Tentang rā‘inā, lihat halaman 263, footnote 204.
24Al-T{abarī, Jāmi‘ al-Bayān, Vol. 5, 118.
25Diriwayatkan bahwa ketika Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang hukuman zina, mereka membacakan Taurat kepada beliau namun menyembunyikan kalimat yang menyebutkan tentang rajam, sampai ‘Abd al-Lāh ibn Salām menyuruhnya menampakkan yang disembunyikan itu. Lihat al-Bukhārī, S{ah}īh} al-Bukhārī, (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1987 M./1407 H.), Vol. 3, 1330, Hadis No. 3436; Muslim, S{ah}īh}, Muslim, (Beirut: Dār Ih}yā’ al-Turāts al-‘Arabī, t.t.), Vol. 3, 1326, Hadis No. 1699. Karena itu pula al-Qur’an menyebut orang-orang Yahudi sebagai telah menyembunyikan kebenaran
312
tersebut atas dasar perasaan superioritas mereka atas orang-orang Arab dan Nabi
Islam. Egoisme telah mengalahkan kejujuran mereka dalam mengungkapkan pesan-
pesan kitab suci. Namun, ini tidak berarti mereka telah berani mengubah teks-teks
tertulis dari kitab suci mereka, jika memang mereka memilikinya. Tindakan mereka
itu tentu saja amat menyakitkan perasaan Nabi, dan al-Qur’an mengungkapkan hal
tersebut:
Wahai Rasul, hendaklah engkau jangan disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: “Kami telah beriman,” padahal hati mereka belum beriman, dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka mengubah (yuh}arrifūn) kalimat-kalimat (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: “Jika diberikan ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah.” Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk mensucikan hatinya. Mereka mendapatkan kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.26
Al-T{abarī menukil sangat banyak riwayat sekitar turunnya ayat di atas, di
antara lain tentang kisah perzinaan dua orang Yahudi, yang kemudian diperselisihkan
hukuman yang harus diterapkan kepadanya, lalu mereka mengajukannya kepada
Nabi Muhammad agar beliau memberikan keputusan.27 Al-Qurt}ubī menegaskan
bahwa inilah pendapat yang paling sahih mengenai turunnya ayat di atas.28 Al-
yang sebenarnya sangat jelas dan terang. Lihat Q.S. al-Baqarah: 146.
26Q.S. al-Mā’idah: 41.
27Al-T{abarī, Jāmi‘ al-Bayān, Vol. 6, 231 ff.
28Al-Qurt}ubī, al-Jāmi‘ li Ah}kām al-Qur’ān, (Kairo: Dār al-Sya‘b, Cet. II, 1372 H.), Vol. 6, 176.
313
Qurt}ubī kemudian mengutip hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī,
Muslim, Mālik dan Abū Daud tentang kisah tersebut. Dalam sebagian riwayat
dikatakan bahwa orang-orang Yahudi mengajukan kasus itu kepada Nabi karena
mengharapkan beliau akan memberikan keputusan yang ringan, mungkin karena
Nabi terkenal pemaaf dan suka mencari jalan tengah yang terbaik; mereka menyebut
beliau sebagai nabiyy bu‘itsa bi al-takhfīfāt. Selama ini mereka tidak lagi
menerapkan hukum Taurat secara benar dalam kasus perzinaan, karena kebanyakan
pelakunya dari kalangan “terhormat.” Namun ketika kejahatan tersebut dilakukan
orang “kecil,” mereka terapkan hukumnya. Lalu muncullah perselisihan dan mereka
mencari jalan keluarnya dan memberikan hukuman lain bagi pelaku zina, yaitu
tah}mīm (penghitaman muka) dan cambuk. Riwayat tersebut juga menambahkan
bahwa di antara sesama mereka, mereka mengatakan: “Jika Nabi ini memberikan
keputusan hukuman selain rajam, kita akan menerimanya dan menjadi hujah bagi
kita di hadapan Allah; kita akan mengatakan: ‘Nabi-Mu telah memberi fatwa
demikian.’” Tetapi Nabi Muhammad tidak mau memberikan keputusan sebelum
menanyakan langsung pada ulama mereka bagaimana sebenarnya keputusan yang
telah ditetapkan Tuhan dalam Taurat. Mereka mengatakan bahwa dalam Taurat
hukumannya adalah rajam, maka, berdasarkan sebagian riwayat, Nabi menyuruh
pelaku zina itu dirajam, dan keduanya dirajam.29
Kisah di atas telah diriwayatkan secara sahih dan terkenal di kalangan para
mufassir dan ahli hukum Islam. Meskipun telah diriwayatkan dengan redaksi yang
agak berbeda, kisah itu pada intinya memperlihatkan sebuah dinamika hubungan
orang-orang Yahudi, Nabi dan kaum Muslim. Dari keterangan di atas juga terlihat
29Ibid., 178.
314
bahwa orang-orang Yahudi memang telah menyelewengkan hukum Taurat, tetapi
mereka tidak pernah menghapus teks kitab suci atau menggantikannya dengan yang
lain. Apa yang mereka tah}rīfkan – berdasarkan ayat di atas dan konteks historisnya
– adalah makna, pemahaman atau pun penerapan dari aturan dalam kitab suci itu.
Ketika Nabi tidak memutuskan perkara sesuai keinginan mereka, orang-orang
Yahudi tentu kecewa, dan ini menjadi pemicu bagi sentimen dan konflik selanjutnya
antara mereka dan Nabi serta Islam secara general. Karena itu semangat ayat di atas
terlihat lebih menekankan peringatan kepada Nabi agar tidak perlu merasa kecewa
karena berpalingnya orang-orang Yahudi dari seruan beliau. Namun demikian, al-
Qur’an tidak tampak berkeinginan menuduh agama dan kitab suci orang Yahudi
tidak valid dan penuh pemalsuan. Jika ayat di atas di perhatikan dalam konteks ayat-
ayat lain yang mengiringinya, yang akan terlihat justeru sebaliknya: al-Qur’an
menekankan agar orang-orang Yahudi dan juga Nasrani merujuk kepada kitab suci
mereka secara jujur. Kemarahan al-Qur’an sebenarnya diarahkan kepada sikap
orang-orang Yahudi yang penuh dengan kepura-puraan. Mereka tidak datang kepada
Nabi untuk mencari hukum yang benar, tetapi mencari pembenaran bagi hawanafsu
mereka. Karena itu al-Qur’an pun membuat ultimatum: Jika mereka datang kepada
Nabi meminta diberikan keputusan dalam suatu perkara, Nabi diperintahkan untuk
memutuskannya dengan adil, atau Nabi berpaling saja jika tidak mau, dan mereka
tidak akan dapat melakukan bahaya apa pun terhadapnya.30 Mengapa demikian? Al-
Qur’an memberikan jawaban:
Bagaimana mungkin mereka bertahkim kepadamu (mengangkatmu menjadi hakim mereka), padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya
30Q.S. al-Mā’idah: 42.
315
(terdapat) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman.31
Jadi dalam suasana dan konteks historis seperti itulah al-Qur’an
memunculkan tuduhan tah}rīf terhadap orang-orang Yahudi. Tidak terlihat sama
sekali bahwa al-Qur’an telah mengajarkan doktrin mengenai pemalsuan kitab-kitab
suci sebelumnya, meskipun benar bahwa al-Qur’an, sebagaimana terlihat dengan
jelas, telah mencela orang-orang Yahudi yang mempermainkan ayat-ayat dalam kitab
Taurat untuk tujuan-tujuan tertentu dan dengan cara-cara yang merendahkan serta
menghina Islam dan Nabi Muhammad.32
2. Konsep al-Nāsikh wa al- Mansūkh
Konsep lain yang juga diterapkan sebagai basis bagi penolakan terhadap
validitas agama Yahudi dan Nasrani (bahkan agama-agama wahyu mana pun di
dunia) oleh kalangan Muslim adalah al-nāsikh wa al-mansūkh, atau disebut dengan
naskh saja. Naskh artinya penghapusan, al-nāsikh penghapus dan al-mansūkh yang
dihapuskan.33 Istilah naskh itu sendiri diangkat dari al-Qur’an, di mana dikatakan
Tuhan telah menghapus sebagian ayat dan menggantikannya dengan yang lain.34
31Ibid., 43.
32Bandingkan komentar Watt terhadap Q.S. al-Baqarah: 75 dalam W. Montgomery Watt, Companion to the Qur'an, (Oxford: Oneworld Publications, 1994), 22.
33Naskh telah menjadi salah satu cabang ilmu dianggap paling penting dalam studi al-Qur’an, terlebih lagi untuk memahami hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Mengenai hal ini diskusi lebih jauh tentang pengertian naskh, lihat al-Zarqānī, Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), Vol. 2, 125-130.
34Q.S. al-Baqarah: 106.
316
Namun ulama Islam berbeda pandangan dalam memahami atau menafsirkan ayat ini,
dan berbagai teori telah dikembangkan berkenaan dengan naskh tersebut,
sebagaimana akan didiskusikan nanti, walaupun hanya secara ringkas. Dalam
konteks teologi, dan juga fikih Islam, naskh dapat berarti penghapusan terhadap
semua agama dan hukum yang pernah diturunkan Tuhan sebelum kedatangan Islam.
Setelah Islam tiba Tuhan memberikan kesempurnaan pada agama terakhir ini untuk
menjadi pedoman hidup semua manusia sepanjang zaman, sehingga tidak ada agama
dan hukum lain selain dari Islam yang dibutuhkan lagi, dan bahkan semuanya
dianggap telah mansūkh – telah “expired.” Orang yang menganut agama selain
Islam adalah kafir; bahkan, barangsiapa tidak mau mengakui hal ini, atau ragu-ragu
untuk mengakuinya, maka ia juga dianggap telah menjadi kafir.35
Konsep naskh pada awalnya dibicarakan dalam konteks penghapusan
sebagian ayat-ayat al-Qur’an oleh sebagian yang lain, khususnya dalam studi ulūm
al-Qur’ān. Namun dalam perkembangannya ia menjadi konsep penghapusan agama-
agama dan kitab-kitab suci sebelumnya oleh Islam dan al-Qur’an. Dalam kitab-kitab
tafsir klasik dan kumpulan ayat-ayat al-nāsikh wa al-mansūkh oleh Qatādah (w. 117
H.),36 misalnya, konsep naskh yang dibicarakan adalah sekitar penghapusan ayat-ayat
al-Qur’an oleh sebagian terhadap sebagian yang lain. Namun ketika Ibn H{azm (w.
456 H.) menulis kitab al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur’ān al-Karīm37 dan Ibn al-
35Lihat misalnya al-Nawāwī, Rawd}ah al-T{ālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1405), Vol. 10, 66; al-Bahūtī, Kasysyāf al-Qinā‘ ‘an Matn al-Iqnā‘, (Beirut: Dār al-Fikr, 1402/1982), Vol. 6, 170.
36Qatādah ibn Di‘āmah, al-Nāsikh wa al-Mansūkh, (Beirut; Mu’assasah al-Risālah, 1404 H.).
37Ibn H{azm, al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur’ān al-Karīm, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H.), 8.
317
Jawzī (w. 597 H.) menulis Nawāsikh al-Qur’an,38 mereka mulai memperkenalkan
dan mendiskusikan istilah naskh dalam konteks yang lebih luas, termasuk konsep
naskh dalam tradisi Yahudi serta berbagai bantahan terhadapnya. Kemudian al-
Samaw’al (Muslim asal Yahudi, w. 570 H.) menulis Ifh}am al-Yahūd di mana ia
mendebat orang-orang Yahudi yang menolak adanya naskh dalam hal agama dan
syarī‘ah dan mengulasnya secara rinci.39 Namun ini tidak berarti bahwa penghapusan
agama-agama lain setelah kedatangan Islam tidak dikenal pada masa awal. Persoalan
ini dianggap telah jelas disebutkan dalam al-Qur’an, bahwa agama yang benar di sisi
Allah hanya Islam, dan agama-agama lain tidak akan diterima lagi oleh Allah setelah
datangnya agama Islam.40 Akan tetapi pada abad pertengahan, persoalan tersebut,
sebagaimana terindikasi dalam karya-karya tersebut di atas, telah menjadi polemik
terbuka antara orang-orang Yahudi dan Muslim.
Naskh yang dibicarakan para pakar al-Qur’an terbagi kepada tiga pola:
Pertama, naskh al-tilāwah wa al-h}ukm ma‘an, yakni penghapusan ayat al-Qur’an
sama sekali dari ingatan manusia, sehingga baik teks maupun hukumnya terangkat
dan tidak dikenal lagi; kedua, naskh al-tilāwah dūna al-h}ukm, penghapusan teks al-
Qur’an saja, sementara hukumnya tetap berlaku, seperti ayat tentang rajam; dan
ketiga, naskh al-h}ukm dūna al-tilāwah, penghapusan hukumnya saja, sementara
teksnya tetap ada.41 Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai yang terakhir ini:
38Ibn al-Jawzī, Nawāsikh al-Qur’ān, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1405 H.), 14 ff.
39Al-Samaw’al ibn Yah}yā, Ifh}ām al-Yahūd wa Qis}s}ah Islām al-Samaw’al wa Ru’yāh al-Nabiyy S{alla al-Lāh ‘alayh wa Sallam, (Beirut: Dār al-Jayl, 1990), 86 ff.
40Q.S. Āli ‘Imrān: 19 dan 85.
41Al-Zarqānī, Manāhil al-‘Irfān, Vol. 2, 154.
318
ayat-ayat mana saja yang telah dihapus dan ayat-ayat mana yang telah
menghapusnya; berapa jumlah ayat yang dihapus (mansūkh); dan apakah hadis sahih
juga dapat menghapus hukum dalam al-Qur’an?42
Terlepas dari perbedaan pendapat seperti di atas, tantangan lain muncul:
apakah naskh yang disebutkan al-Qur’an harus dipahami secara literal, bahwa sebuah
ketentuan Tuhan telah dihapuskan oleh ketentuan-Nya yang lain? Apakah Tuhan
pernah berubah pikiran? Para penulis klasik sediri telah menyadari tantangan ini dan
mereka berupaya mengantisipasinya;43 dan bagi Ibn al-Jawzī, itu hanyalah pendapat
segelintir orang yang tidak perlu digubris, sebab, menurutnya, persoalan naskh telah
disebutkan secara tegas dalam al-Qur’an (Q.S. al-Baqarah: 106).44
Tidak diragukan bahwa naskh adalah persoalan yang kompleks, dan mungkin
karena kompleksitasnya itu ia diberikan kredit yang tinggi. Suatu hari, demikian
diriwayatkan, ‘Alī ibn Abī T{ālib bertemu dengan seorang qād}ī (hakim), lalu
bertanya kepadanya: “Apakah engkau mengetahui al-nāsikh wa al-mansūkh?”
Qād}ī itu menjawab: “Tidak.” “Engkau telah celaka dan mencelakakan,” kata ‘Alī.
Jika memang hukum-hukum dalam sebagian ayat al-Qur’an telah dihapus oleh
sebagian ayat yang lain, maka jelas bahwa mengetahui ayat-ayat yang berkaitan
dengan masalah tersebut sangat penting. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang
ahli hukum, misalnya, dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram,
mana perintah dan mana larangan, karena mungkin saja sebagian dari yang halal
42Al-Nuh}h}ās, al-Nāsikh wa al-Mansūkh, (Kuwait: Maktabah al- Falāh}, 1408 H.), 53.
43Ibid., 40-42.
44Ibn al-Jawzī, Nawāsikh al-Qur’ān, 17.
319
telah diharamkan atau sebagian perintah telah dilarang. Bagaimana cara
mengetahuinya? Inilah problem selanjutnya. Karena Kitab al-Qur’an tidak disusun
berdasarkan kronologis turunnya, maka untuk mengetahui al-nāsikh wa al-mansūkh
meniscayakan seseorang menguasai sejarah turunnya ayat-ayat al-Qur’an. Hal ini
dikarenakan al-nāsikh dan al-masūkh mesti dibedakan dengan jalan mengetahui ayat-
ayat mana diturunkan lebih awal dan ayat-ayat mana diturunkan kemudian; hanya
ayat-ayat yang turun lebih akhir dapat menasakhkan ayat-ayat yang turun lebih awal.
Apa yang dikemukakan di atas bukan merupakan persoalan yang gampang.
Terlebih, seperti telah dikemukakan di atas, tidak ada kata sepakat mengenai ayat-
ayat yang dihapus atau pun yang menjadi penghapus. Ibn al-Jawzī sendiri telah
mengatakan bahwa di antara tujuannya mengarang kitab al-Nāsīkh wa al-Mansūkh
adalah untuk meluruskan berbagai pandangan yang dianggap telah keliru, yakni
mengenai ayat-ayat mana telah menghapuskan ayat-ayat mana. Sebagian orang, kata
Ibn al-Jawzī, telah menganggap mansūkh sebagian dari ayat-ayat al-Qur’an, padahal
ayat-ayat tersebut tidaklah mansūkh.45 Lalu apa yang menjadi kriteria bahwa suatu
ayat telah dihapuskan dan suatu ayat yang lain telah menjadi penghapusnya? Ibn al-
Jawzī menjelaskan, ada lima syarat untuk sebuah proses naskh, dan yang paling
penting di antaranya, tentu saja, ialah bahwa di antara kedua ayat tersebut tidak dapat
dipertemukan atau dikompromikan.46 Akan tetapi, ini juga bukan tanpa masalah,
sebab ayat-ayat yang tidak dapat dikompromikan oleh seorang pakar bisa jadi dapat
dikompromikan oleh pakar yang lain. Al-Dihlawī (w. 1176 H./1762 M.) mencatat
sampai lima ratus ayat telah dinyatakan mansūkh oleh kebanyakan ulama al-Qur’an,
45Ibid., “Muqaddimah.”
46Ibid., 23.
320
namun al-Suyūt}ī mampu mengompromikan sebagian besarnya, sehingga yang
mansūkh tinggal dua puluh satu; al-Dihlawī sendiri kemudian menguranginya lagi
menjadi lima.47 Fenomena ini, oleh sebagian sarjana kontemporer, dianggap telah
menimbulkan persoalan besar. “When almost every passage or practice which is held
as abrogated by one scholar is questioned by another, then there is little doubt that
the question of scriptural authority itself is involved.”48
Sebagian kaum reformis dan para sarjana modern dengan tegas menolak
konsep naskh dalam pengertian (literal) bahwa sebagian ayat al-Qur’an yang turun
lebih awal telah dihapuskan oleh sebagian ayat yang turun kemudian. Ayat-ayat yang
turun dalam kondisi tertentu, yang kemudian dimodifikasi atau dikembangkan oleh
ayat-ayat yang turun selanjutnya, tidak dapat disebut sebagai telah mansūkh dalam
pengertian dihapuskan dan tidak berlaku lagi. Alih-alih demikian, lebih tepat kalau
dikatakan bahwa ayat-ayat tersebut tetap berlaku dan dapat diterapkan dalam kondisi
sebagaimana pada saat ia diturunkan.49 Lebih jauh, menurut ‘Abd al-Muta‘āl,50
berdasarkan konteks ayat, yang dimaksudkan dengan naskh oleh al-Qur’an (al-
Baqarah: 106) adalah naskh al-syarā’i‘, penghapusan agama-agama terdahulu
dengan agama terakhir yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan manusia,
bukan penghapusan ayat-ayat al-Qur’an – sebuah pandangan yang berlawanan
47Al-Dihlawī, al-Fawz al-Kabīr fī Us}ūl al-Tafsīr, (Karachi: Qadīmī Kutub Khāna, 1966), 40-46.
48Farid Esack, Qur’an, Liberation and Pluralism, (Oxford: Oneworld Publication, 1998), 58.
49Ibid.
50‘Abd al-Muta‘āl, La..Naskh fī al-Qur’ān: Limādhā..? (Kairo: Maktabah Wabah, 1400 H./1980 M.), 16.
321
dengan apa yang dianut oleh kebanyakan sarjana Muslim kontemporer.51 Ayat
tersebut turun untuk memberikan jawaban terhadap fitnah yang dibuat orang-orang
Yahudi untuk mendiskreditkan Nabi. Mereka mengatakan, Muhammad telah
membawa ajaran yang sesat, karena berbeda dari ajaran yang mereka anut; ini berarti
sebuah penyimpangan dari ajaran Tuhan yang sebenarnya. Maka ayat tersebut
diturunkan untuk menegaskan bahwa Tuhan dapat melakukan apa yang Ia kehendaki,
dan penghapusan atau penggantian suatu ayat dengan ayat yang lain hanyalah untuk
kebaikan; ayat yang “baru” mestilah lebih baik dari yang “lama.”
Ayat mana saja yang Kami hapuskan (nansakh), atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?52
Memang benar bahwa ayat tentang naskh turun dalam rangka merespon
tuduhan orang-orang kafir bahwa ajaran-ajaran Muhammad telah menimbulkan
kebingungan dan tidak konsisten. Akan tetapi sulit sekali dibuktikan bahwa
inkonsistensi yang mereka maksudkan itu terletak antara ajaran Muhammad dan
ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Orang-orang Yahudi tidak menunjukkan keinginan
membandingkan ajaran Taurat dengan al-Qur’an; yang mereka tunjukkan sebagai
inkonsistensi adalah ajaran Nabi Muhammad sendiri, terutama sekali ketika turun
perintah memalingkan kiblat dari Yerusalem ke Mekkah. Menurut mereka,
Muhammad telah mengubah-ubah ajarannya; mana mungkin ajaran seperti itu datang
51Menurut Abdulaziz Sachedina, al-Qur’an tidak pernah menganggap dirinya sebagai penghapus wahyu-wahyu Yudeo-Kristiani. Lihat Abdulaziz Sachedina, “Is Islamic Revelation an Abrogation of Judaeo-Christian Revelation,” Concilium, March 1994, 101; Karl-Josef Kuschel, Abraham: Sign of Hope for Jews, Christians and Muslims, terj. John Bowden dari Bahasa Jerman, (New York: Continuum, 1995), 190-191.
52Q.S. al-Baqarah: 106.
322
dari Tuhan.53 Sebagian mufassir, seperti al-T{abarī dan Ibn Kastīr, mengaitkan ayat
di atas dengan pandangan orang-orang Yahudi tentang naskh. Menurut mereka,
orang-orang Yahudi telah menolak adanya naskh pada hukum Tuhan, karena mereka
kufur dan keras kepala. Penolakan orang-orang Yahudi terhadap naskh adalah
sebagai dalih bagi penolakan mereka terhadap Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Maka
ayat di atas diturunkan termasuk sebagai bantahan terhadap pandangan orang-orang
Yahudi tersebut.54 Akan tetapi pandangan ini sulit dipertahankan. Tidak ada bukti
yang menunjukkan bahwa perdebatan Nabi dengan orang-orang Yahudi telah
mengarah kepada argumentasi yang merujuk pada konsep mereka tentang naskh. Al-
Qur’an sendiri, sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya, mencatat bagaimana
orang-orang Yahudi meminta kepada Nabi bukti-bukti supaya mereka beriman,
meskipun kemudian al-Qur’an mencela mereka karena sikapnya yang tidak serius;
mereka bukan tidak beriman karena tidak ada bukti, tetapi karena kesombongan dan
kekufuran yang telah melekat dalam hatinya.55 Ibn Hisyām (w. 213 H.)
meriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi pernah berkata kepada Nabi: “Bawakanlah
kepada kami sebuah kitab yang turun dari langit untuk kami baca, dan pancarkanlah
untuk kami sungai-sungai, niscaya kami akan mengikutimu dan membenarkanmu.”
Maka, berkenaan dengan ucapan mereka itu, Allah menurunkan ayat: “Apakah kamu
menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada
Musa pada zaman dahulu? Dan barangsiapa menukarkan iman dengan kekafiran,
53Al-Qurt}ubī, al-Jāmi‘ li Ah}kām al-Qur’ān, (Kairo: Dār al-Sya‘b, Cet. II, 1372 H.), Vol. 2, 61; Syihāb al-Dīn Ah}mad ibn ‘Alī, al-‘Ujāb fī Bayān al-Asbāb, (al-Dammām: Dār Ibn al-Jawzī, 1997), Vol. 1, 348.
54Ibn Katsīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Az}īm, (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H.), Vol. 1, 152.
55Q.S. al-Baqarah: 91; Āli ‘Imrām: 181.
323
maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus” (al-Baqarah: 108).56 Jadi
tidak ada bukti historis bahwa orang-orang Yahudi Medinah telah menolak kenabian
Muhammad dan al-Qur’an atas dasar penolakan mereka terhadap konsep naskh. Jika
memang ini yang menjadi hujah mereka, tentu saja berbagai argumentasi lain tidak
mereka perlukan dalam menentang Nabi. Karena itu, seperti telah disebutkan,
pandangan yang dikemukakan al-T{abarī dan Ibn Katsīr di atas sulit dipertahankan.
Sepertinya mereka dalam hal ini lebih dipengaruhi oleh polemik Yahudi-Muslim
yang muncul belakangan.
Sebelum orang-orang Yahudi Medinah, orang-orang kafir Mekkah juga telah
pernah melemparkan tuduhan yang serupa terhadap al-Qur’an dan Nabi Muhammad.
Perubahan-perubahan hukum yang diajarkan Nabi Muhammad dijadikan landasan
hujah oleh orang-orang kafir untuk menuduh Nabi sebagai muftar, orang yang
mengada-ada.
Dan apabila Kami gantikan (baddalnā) suatu ayat dengan ayat yang lain – padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya – mereka berkata: “Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja (muftar).” Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.
Katakanlah: “Ruh al-Qudus telah menurunkan al-Qur’an itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.57
Baik ayat-ayat ini maupun ayat yang dikutip sebelumnya menunjuk kepada
adanya dinamika perkembangan ajaran al-Qur’an, dan ini telah direspon oleh para
penentang al-Qur’an, baik kalangan kafir Mekkah maupun Yahudi Medinah, dengan
nada negatif. Ayat-ayat di atas merupakan jawaban serta penjelasan terhadap makna
56Ibn Hisyām, al-Sīrah al-Nabawiyyah, (Beirut: Dār al-Jayl, 1411 H.), Vol. 3, 84.
57Q.S. al-Nah}l: 101-102.
324
dan hikmah Tuhan yang terkandung dalam fenomena naskh atau tabdīl tersebut.
Ayat-ayat Tuhan bukanlah Tuhan; ia relatif, tidak mutlak. Tuhan kuasa untuk
mengubah ayat-ayat-Nya, dan ini dilakukan Tuhan untuk kebaikan hamba-hamba-
Nya. Peristiwa naskh dan tabdīl adalah sebuah keniscayaan dalam realitas
kehidupan manusia yang selalu berubah dan dinamis. Ayat-ayat Tuhan, baik pada
alam semesta atau dalam kitab suci, adalah manifestasi dari iradah Yang Mutlak atas
realitas yang nisbi dan relatif, yang selalu bergerak menuju kesempurnaan yang tiada
habisnya. Ayat-ayat “yang baru” datang untuk menggantikan “yang lama” meskipun
keduanya tetap eksis. “Baru” dan “lama,” al-nāsikh dan al-mansūkh, tidak dapat
diukur dengan waktu dan kronologis sejarah, karena keduanya adalah fragmen dari
kehendak Yang Maha Tunggal; keduanya bisa berubah dan terbalik. Realitas dunia
ini yang terbatas tidak mampu menyerap segala kesempurnaan Tuhan dan kehendak-
Nya yang tidak terbatas. Karena itu al-nāsikh dan al-mansūkh tampak seperti
tersusun rapi dalam waktu dan seolah-olah konstan. Orang yang ingin memahami
ayat-ayat Tuhan dengan baik mesti menyadari bahwa perubahan itulah yang konstan
dan senantiasa mengiringi realitas. Selama teks merupakan teks yang diarahkan pada
realitas, maka kondisi realitas harus dipertimbangkan.58
Sebagian ulama telah memahami al-nāsikh wa al-mansūkh dalam konteks
ayat-ayat al-Qur’an semata, sementara ulama yang lain menolak adanya hal tersebut
dalam al-Qur’an dan mengalihkannya kepada yang lain, yaitu bahwa al-Qur’an
sendiri yang menjadi al-nāsikh dan kitab-kitab suci atau hukum-hukum yang
diturunkan Tuhan sebelumnya menjadi al-mansūkh. Akan tetapi kedua pemahaman
58Nas}r H{āmid Abū Zayd, Mafhūm al-Nas}s}: Dirāsah fī ‘Ulūm al-Qur’ān, (al-Dār al-Bayd}ā’: al-Markaz al-Tsaqāfī al-‘Arabī, cet. V, 2000), 120.
325
ini hanya menjelaskan fenomena naskh pada tataran yang bersifat teknis semata.
Bagaimana mungkin sebuah ayat Tuhan dianggap valid untuk suatu masa dan tidak
valid pada masa yang lain? Validitas tersebut bukan ditentukan oleh ruang dan
waktu, tetapi oleh kondisi dan realitas kehidupan manusia yang bergerak dalam
ruang dan waktu itu. Karenanya, seperti telah disinggung di atas, al-nāsikh wa al-
mansūkh adalah bagian dari jembatan dialektis dan dinamis yang berperan
menghubungkan iradah Tuhan yang Maha Sempurna dengan realitas kehidupan
manusia yang serba relatif. Dengan adanya naskh, ayat-ayat al-Qur’an maupun kitab-
kitab suci berbeda dapat mengisi dinamika peradaban manusia yang beragam secara
dialektik dan elegan, dan tidak mesti dilihat sebagai telah saling menghapuskan.
Semuanya merupakan bagian dari kehendak Tuhan untuk memenuhi berbagai
kebutuhan spiritual manusia dalam gerak kehidupan, kecenderungan psikologis,
tatanan sosial dan bentuk peradaban yang sangat bervariasi.
C. Kebenaran dan Salvation
Klaim kebenaran eksklusif menggiring penganut agama mana pun kepada
klaim siapa yang selamat dan siapa yang tidak. Jika Islam adalah agama kebenaran
maka, secara teologis, konsekuensinya, semua agama yang lain adalah batil, tidak
sah. Dengan demikian hanya orang-orang yang mengikuti keyakinan Islam yang
selamat di hari akhirat. Menurut keyakinan kaum Muslim, bahkan, mengikuti ajaran
Islam akan membahagiakan seseorang di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri dari
326
Islam berarti membuka jalan bagi petaka di kehidupan ini dan kehidupan di hari
kelak.
Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberikan Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.
Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. 59
Jika ini dijadikan alasan bahwa agama selain Islam akan membawa sengsara
dunia dan akhirat, maka bagaimana dengan ayat-ayat berikut?:
Sesungguhnya orang-orang yang beriman (kepada al-Qur’an), orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang S{ābi’īn, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka; tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman (kepada al-Qur’an), orang-orang Yahudi, S{ābi’īn dan orang-orang Nasrani, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman (kepada al-Qur’an), orang-orang Yahudi, orang-orang S{ābi’īn, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.60
Persoalan ini telah menjadi polemik hangat di kalangan para sarjana Muslim.
Ulama yang berpegang pada konsep naskh secara literal menganggap bahwa ayat-
ayat yang terakhir ini telah dihapus ketentuannya oleh dua ayat pertama di atas.
Setelah Allah mengukuhkan Islam sebagai agama yang sempurna, maka agama-
agama lain menjadi mansūkh. Orang-orang yang masih menganut agama selain Islam
tidak akan selamat di akhirat. Mereka termasuk “orang-orang yang rugi.” Akan tetapi
59Q.S. Āli ‘Imrān: 19 dan 85.
60Masing-masing, Q.S. al-Baqarah: 62; al-Mā’idah: 69; al-H{ajj: 17.
327
pemahaman seperti ini bertentangan dengan sebagian rules tentang naskh itu sendiri.
Naskh hanya dapat diterapkan pada hukum, seperti halal dan haram, tidak pada
khabar atau berita. Sebuah berita tidak dapat dihapuskan oleh berita lain yang datang
kemudian, kecuali berita yang pertama dianggap bohong, dan ini tidak mungkin
terjadi pada ayat al-Qur’an sebagai firman Tuhan.61 Dengan demikian, aturan naskh
tidak dapat diterapkan pada ayat-ayat di atas, karena muatannya berupa khabar,
bukan hukum. Ibn al-Jawzī menggunakan argumentasi ini untuk menolak penerapan
naskh pada ayat-ayat di atas. Namun ia merasa perlu memberikan penjelasan lebih
jauh untuk memelihara teologi eksklusifnya. Ayat-ayat tentang keselamatan orang-
orang Yahudi dan Nasrani, kata Ibn al-Jawzī, tidak mansūkh, karena yang dimaksud
dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam ayat tersebut (Q.S. al-Baqarah: 62;
al-Mā’idah: 69) adalah mereka yang hidup pada zaman sebelum diutusnya Nabi
Muhammad; kalau pun yang ditujukan al-Qur’an adalah orang-orang Yahudi dan
Nasrani yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, pastilah yang dimaksudkan
adalah mereka yang tidak merusak agamanya dan tidak melakukan tah}rīf serta
beriman kepada Nabi Muhammad.62
Baik pandangan yang menerapkan konsep naskh atau pun yang menolak
penerapan konsep naskh pada ayat-ayat di atas, keduanya tetap berbicara dalam
bingkai teologi Islam eksklusif. Hanya Islam yang benar dan hanya penganut agama
Islam yang selamat di akhirat. Pandangan seperti ini tentu saja tidak tipikal Muslim.
Dalam agama-agama lain, terutama Yahudi dan Nasrani, superioritas diri tetap
merupakan pandangan yang sangat dominan. Ini adalah sebuah kegagalan global
61Ibn al-Jawzī, Nawāsikh al-Qur’ān, 21-22.
62Ibid., 43.
328
masyarakat beragama – kegagalan dalam mengapresiasi “orang lain,” apalagi
menempatkannya pada posisi yang sama dengan “kita.” Tapi patut dicatat, bahwa
kegagalan kaum Muslim mengapresiasi umat Yahudi di kemudian hari tidak terlepas
dari kegagalan kebanyakan orang Yahudi dalam mengapresiasi seruan spiritual Nabi
Muhammad secara jujur dan tulus pada saat-saat sang Nabi sedang menaruh harapan
yang sangat besar pada mereka.
Konsep keselamatan yang dianut umat Islam, baik eksklusif, inklusif maupun
pluralis, berlandas pada ayat-ayat yang telah dikutip di atas, namun dengan
pendekatan dan penafsiran yang berbeda. Kelompok eksklusif, seperti telah
disebutkan, menggunakan pendekatan naskh atau menakwilkan “orang-orang Yahudi
dan Nasrani” sebagai mereka yang hidup zaman sebelum Nabi Muhammad atau pun
di zaman Nabi Muhammad namun telah memeluk Islam. Bagi kelompok inklusif
ataupun pluralis, ayat-ayat di atas sudah jelas dan tidak ada pertentangan di
dalamnya; tidak ada nāsikh, tidak ada mansūkh dan tidak perlu ditakwilkan. Semua
orang akan diselamatkan oleh Tuhan, dengan syarat: ia beriman kepada Tuhan dan
hari akhirat serta berbuat kebaikan, terlepas dari institusi agama formal mana ia
berasal.
Mengenai klaim al-Qur’an tentang Islam sebagai satu-satunya agama di sisi
Tuhan, bagi kelompok inklusif atau pluralis, tidaklah sulit untuk dijelaskan. Islam
pada dasarnya adalah sebuah istilah generik yang bermakna “tunduk dan patuh”
(kepada Tuhan), yang kemudian oleh para teolog Muslim diartikan sebagai sebuah
nama agama historis yang dibawa oleh Nabi Muhammad.63
63Abdulaziz Sachedina, “Is Islamic Revelation an Abrogation,” 101.
329
Jika dilacak ke dalam al-Qur’an, tampak Islam mengasumsikan makna yang
universal. Pada awalnya Tuhan memerintahkan Ibrahim untuk tunduk dan patuh
(aslim), lalu Ibrahim menjawab: “Aku tunduk dan patuh (aslamtu) kepada Tuhan
semesta alam.”64 Karena itu Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya – demikian juga
Yakub, mengikuti jejak Ibrahim – agar mereka tidak meninggalkan dunia ini (mati)
melainkan dalam keadaan tunduk kepada Tuhan (muslimūn); itulah agama yang
benar, agama yang telah dipilih oleh Allah untuk mereka.65 Karena itu kepada umat
yang mengikuti al-Qur’an diperintahkan untuk membuat kesaksian atas kesetiaan
mereka bagi agama tersebut:
Katakanlah: “Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya (lahū muslimūn).66
Ayat-ayat di atas dengan jelas mengindikasikan pengasosiasian Islam oleh al-
Qur’an dengan agama yang diajarkan para nabi sebelumnya. Islam adalah satu-
satunya agama dari Tuhan, tetapi Muhammad bukan satu-satunya nabi yang
mengajarkan Islam. Jika demikian halnya maka orang-orang Yahudi dan Nasrani
(atau siapa pun yang menganut agama yang berasal dari Tuhan) yang menjalankan
agama dengan jujur dan tulus, mereka juga berarti tunduk dan patuh kepada Tuhan,
dan secara generik diistilahkan dengan Muslim.
Dalam ayat berikut ini al-Qur’an berkata:
64Q.S. al-Baqarah: 131.
65Ibid., 132-133.
66Ibid., 136.
330
Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran risalah yang engkau sampaikan), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah (aslamtu wajhiy li al-Lāh) dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku.” Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberikan kitab dan kepada orang-orang yang ummi: “Apakah kamu masuk Islam (a aslamtum)? Jika mereka masuk Islam (aslamū), sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.67
Apakah ayat ini menunjukkan kepada Islam eksklusif? Apakah kaum Ahli Kitab
diajak masuk Islam dengan cara meninggalkan agama mereka sebelumnya? Bahkan,
apakah Islam di sini berarti sebuah agama formal-institusional? Tidak ada indikasi
kepada hal tersebut. Seruan al-Qur’an kepada kaum Ahli Kitab untuk menjadi
Muslim tidak lain kecuali dalam pengertian tunduk secara jujur dan tulus kepada
Tuhan dengan mengikuti agama yang benar. Apakah agama yang benar itu Yahudi,
Nasrani atau Islam? Al-Qur’an menyebutnya “Islam,” agama yang diwariskan oleh
Ibrahim, Ishak dan Yakub. Lebih jauh, “Islam” itu bahkan telah merupakan
karakteristik seluruh alam semesta.68 Karena itu, yakni karena karakteristiknya yang
universal, “Islam” disebut oleh al-Qur’an sebagai cara beragama yang paling baik.69
Seruan al-Qur’an pada dasarnya adalah seruan moral, bukan seruan untuk
mengikuti suatu agama formal, walaupun pada akhirnya ini diperlukan sebagai jalan
pemisahan diri dari mereka yang ingkar dan menolak kebenaran. Sejak di Mekkah
hal ini telah ditegaskan, yaitu ketika turun ayat lakum dīnukum wa liya dīn.70 Tetapi
67Q.S. Āli ‘Imrān: 20.
68Ibid., 83.
69Q.S. al-Nisā’: 125.
70Q.S. al-Kāfirūn: 6.
331
ketika berhadapan dengan kaum Ahli Kitab, al-Qur’an menyampaikan seruan
sebagai berikut:
Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat yang sama (kalimah sawā’) antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan tidak mempersekutukan Dia dengan suatu pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (muslimūn).”71
Kalimah sawā’72 mengindikasikan perspektif al-Qur’an mengenai Ahli Kitab
seperti telah disebutkan di atas. Al-Qur’an menganggap bahwa di antara dirinya dan
mereka terdapat dasar ajaran yang sama. Al-Qur’an hanya menginginkan pengakuan
tersebut dari mereka, yang ternyata justeru “mengecewakan” al-Qur’an. Karena itu
al-Qur’an melancarkan kritik yang bertubi-tubi atas sikap mereka yang dianggap
arogan, eksklusif dan telah menyimpang dari agama yang benar. Di sinilah tampak
bahwa rujukan al-Qur’an kepada “Islam” sebagai agama yang benar dan lurus yang
diwariskan oleh Ibrahim dan anak-anaknya menjadi sangat signifikan. Ibrahim
bukanlah Yahudi dan bukan pula Nasrani, tetapi ia seorang yang lurus dan tunduk
(h}anīfan musliman).73 Atas dasar ini, kritik-kritik al-Qur’an terhadap kaum Ahli
Kitab semakin jelas. Mereka dianggap telah menyimpang dari jalan lurus, dari agama
yang sebenarnya, sebagaimana telah diwasiatkan oleh Ibrahim, Ishak dan Yakub. Al-
Qur’an merujuk “Islam” kepada Ibrahim, sesosok figur yang diakui sendiri oleh
orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai sumber dasar ajaran mereka, dan al-Qur’an
71Q.S. Āli ‘Imrān: 64.
72Burhanuddin Daya mengartikan kalimah sawā’ dengan “konsep yang sama, dasar yang sama, dalil yang sama, ungkapan yang sama, dan bahkan obsesi yang sama.” Lihat Burhanuddin Daya, “Bingkai Teologi Kerukunan Bersama,” al-Jāmi’ah, No. 59, 1996, 193.
73Ibid., 67.
332
menunjukkan fakta yang tidak dapat dibantah bahwa Ibrahim bukanlah Yahudi atau
pun Nasrani. Maka mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani kembali kepada
ajaran yang lurus merupakan agenda paling penting dari seruan al-Qur’an.
Jika al-Qur’an mengkritik orang-orang Yahudi dan Nasrani karena sikap
mereka yang eksklusif, maka merupakan hal yang sangat ironis kalau al-Qur’an
sendiri dianggap telah mengajarkan eksklusivisme. Sebagaimana dikatakan
Mahmoud Ayoub, di tangan para teologlah, beserta fuqahā’ dan para mufassir, visi
keagamaan al-Qur’an yang semula harmonis telah ditransformasikan menjadi
pandangan yang eksklusif. Gagasan-gagasan mereka telah menyeret Islam menjadi
agama yang tertutup. Sementara al-Qur’an sendiri, kata Ayoub, dengan merujuk pada
Q.S. al-Mā’idah: 48, telah memberikan penegasan yang positif terhadap berbagai
tradisi keagamaan yang berbeda.74 Karena itu Ayoub percaya bahwa semua agama
merupakan jalan kepada keselamatan.75 Akan tetapi Fazlur Rahman, dalam hal ini,
mengambil sikap yang lebih hati-hati. Meskipun mengakui validitas agama kaum
Ahli Kitab (dan juga agama-agama wahyu yang lain) dan menganggapnya sudah
memadai untuk mencapai keselamatan, al-Qur’an, kata Rahman, tetap mengajak
mereka kepada Islam, yakni beriman kepada al-Qur’an dan mengikuti Nabi
Muhammad. Karena hanya dengan jalan seperti itu seruan Tuhan kepada umat
manusia melalui al-Qur’an dapat terpenuhi.76
74Mahmoud Ayoub, “Islam and Christianity between Tolerance and Acceptance,” Islam and Christian-Muslim Relation, Vol. 2, 1991, 177.
75Mahmoud Ayoub, “Christian-Muslim Relations Into the Twenty-first Century: A Round Table Discussion,” Islam and Christian-Muslim Relation, Vol. 3, 1992, 25.
76Fazlur Rahman, “Islam,” dalam Mircea Eliade (ed.), Encyclopaedia of Religion, (New York, 1987), Vol. 7, 321.
333
Berangkat dari diskusi di atas, Islam ternyata telah dipahami secara kompleks
oleh umat pemeluknya sendiri. Kaum Muslim percaya akan kebenaran Islam, namun
mereka tidak sepakat mengenai bagaimana Islam itu sendiri memandang umat lain.
Bagi sebagian umat Islam, kebenaran Islam meniscayakan kebatilan selain Islam.
Namun tidak demikian bagi sebagian mereka yang lain, yang melihat bahwa Islam
adalah bagian dari rahmat Tuhan kepada alam semesta yang tidak menafikan rahmat
Tuhan yang juga datang melalui jalan keselamatan berbeda. Cara pandang berbeda
seperti ini sekilas terlihat sangat fatal, sebab menyangkut soal keselamatan umat
manusia – “soal masuk sorga atau neraka.” Tetapi dalam konteks kesadaran plural,
perbedaan tersebut tidaklah begitu menakutkan. Ia hanyalah bagian dari kekayaan
visi umat manusia dalam memandang dunia, agama dan dirinya sendiri. Jika dirujuk
kepada al-Qur’an, hanya Tuhan yang dapat memutuskan perkara ini di hari akhirat
nanti.77 Keputusan manusia tidak lain hanyalah nisbi dan kebenarannya hanya pada
tataran kemanusiaan belaka. Kesadaran ini akan datang ketika manusia sudah melihat
kebenaran yang diyakininya sebagai bagian dari kebenaran yang lebih universal,
yang tidak mungkin sepenuhnya tercerapkan. Semakin kaya pengetahuan seseorang
terhadap “yang lain,” semakin mampu ia menghargai perbedaan. Sebaliknya, mereka
yang hanya mengenal “diri sendiri” akan cenderung lebih eksklusif dan bahkan
arogan. Namun, patut dicatat, bahwa persoalannya tidaklah sesederhana itu. Karena
eksklusivisme dan arogansi pada dasarnya sangat terkait dengan mentalitas.
Kesadaran plural tidak dimulai dari pengetahuan tentang kemajemukan, tetapi pada
kesadaran diri yang tidak pernah sempurna. Pengetahuan tentang kemajemukan
hanya merupakan penunjang.
77Q.S. al-H{ajj: 17; al-Sajdah: 25.
334
Setiap persepsi akan mempengaruhi tingkah laku. Persepsi seseorang tentang
orang lain akan membentuk perilaku dan cara ia bersikap terhadap orang lain itu.
Jika hal ini dikaitkan dengan sikap keberagamaan, maka akan tampak betapa besar
pengaruh persepsi tersebut terhadap image dan stereotip yang terbentuk terhadap
pemeluk agama lain. Semua ini tentu ada kaitannya dengan konsep keselamatan atau
salvation. Bagaimana seorang Muslim, misalnya, harus bergaul dengan baik, ramah
dan santun dengan orang non-Muslim, sementara dalam hatinya gelora kebencian
selalu mengatakan hal-hal menjijikkan terhadap orang tersebut. Mengucapkan salam
saja tidak dibolehkan – belum lagi jika dikaitkan dengan konsep sebagian Muslim
yang menganggap non-Muslim itu najis. Bagaimana seorang Muslim dapat bergaul
dengan non-Muslim dengan wajah ceria, sementara orang yang ada bersamanya itu
dia yakini tidak lebih dari calon penghuni neraka di akhirat kelak. Bagaimana
seorang Muslim dapat mengapresiasi non-Muslim sementara lembaran-lembaran
kitab suci mereka saja, sebagaimana tersebut dalam karya Nūr al-Dīn al-Rānīrī,
diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat beristinjā’ (membersihkan qubul/dubur
sehabis buang air).78
Sikap tidak sopan terhadap “orang lain,” mesti memiliki akar teologis dalam
agama. Karena itu membangun hubungan antar umat beragama yang harmonis
meniscayakan sebuah rekonstruksi pandangan keagamaan itu sendiri. Jadi kebenaran
teologi, tidak terhindarkan, akan tergugat. Ini sebenarnya tidak perlu
mengkhawatirkan siapa pun, kecuali mereka yang menganggap teologi itu sebagai
agama, dan agama sebagai Tuhan.
78Nūr al-Dīn al-Rānīrī, S{irāt} al-Mustaqīm, tepi kitab karangan Muh}ammad Arsyad ibn ‘Abdullāh al-Banjārī, Sabīl al-Muhtadīn li al-Tafaqquh fī Amr al-Dīn, (Indonesia: Maktabah Dār Ih}yā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), 39.
335
D. Cita-cita Perdamaian
Agama tidak mungkin pernah ada tanpa sejarah dan tanpa pergumulan
manusia dengan kehidupan. Agama lahir pada ujung sebuah kelelahan dari daya
upaya manusia yang sungguh-sungguh untuk mencapai makna yang lebih dalam dari
apa yang mereka alami dan saksikan dengan segenap perangkat dan fakultas yang
ada pada dirinya, baik inteligensia, indera, rasa maupun perasaan. Pada saat
pencapaian telah tiba pada batas akhir kemanusiaan, “Tuhan” merespon dan
menurunkan “wahyu.” Wahyu itulah, sebagaimana telah didiskusikan dalam bab-bab
sebelumnya, yang menjadi core ajaran agama. Karena ia bersumber dari “luar”
manusia, maka ia sebenarnya “asing” dari realitas kemanusiaan. Ia harus didekati,
dipahami dan ditafsirkan, tidak lain karena ia harus meleburkan watak hakikinya
yang non-insani untuk menjadi bagian dari pengalaman manusia yang insani dan
membumi. Proses inilah yang jarang disadari, sehingga orang mencampur adukkan
agama dan tafsiran manusia terhadap agama. “Agama memang harus ditafsirkan dan
dibentuk, namun jelas, bukan tafsir dan bentuk itu sendiri yang merupakan agama.”79
Agama adalah sesuatu yang terilhami, bukan sesuatu yang dibuat atau diciptakan.
Walaupun ia terungkap dalam kesadaran dan terekspresikan dalam berbagai
fenomena kehidupan nyata, agama tetap merupakan bagian paling misterius dari
peradaban manusia.
79“Pengantar Redaksi”, dalam Ziaul Haque, Wahyu dan Revolusi, terj. E. Setiawati Al Khattab, (Yogyakarta: LKiS, 2000), vi.
336
Namun, agama tidak mesti dikaitkan dengan mistik. Ia tidak diturunkan untuk
mengubah manusia menjadi Tuhan; tetapi justru untuk menjadikan manusia benar-
benar manusia. Agama, memang, adalah wahyu: sebuah hasil komunikasi antara
manusia dengan Yang Maha Gaib, sebuah “uluran tangan” dari Yang Maha
Penyayang untuk menyelamatkan manusia dari kebingungan dan kehancuran. Dari
sinilah terlihat watak wahyu itu sebagai pembimbing yang dengan tegas disebutkan
oleh al-Qur’an dengan istilah hudā. Hudā atau petunjuk bukanlah sebuah campur
tangan, tetapi sebuah pengajaran yang merdeka dan menuntut kecerdasan serta
independensi. Hudā adalah seperti kompas dan peta yang niscaya memerlukan
kepada berbagai pengetahuan lain dan pengalaman hidup yang lebih banyak.
Semakin kaya pengalaman dan pengetahuan manusia, semakin tajam ia menafsirkan
petunjuk itu.
Wahyu sebagai sumber ajaran agama adalah petunjuk kepada jalan lurus,
kepada pencapaian keinginan Tuhan (rid}ā-Nya). Karena itu wahyu mensyaratkan
manusia tunduk kepada supremasi kebenaran dan keadilan, tidak boleh tunduk
kepada hawanafsu dan keinginan-keinginan yang rendah. Di sini pula tafsiran dan
takwilan (ta’wīl) manusia terhadap agama diuji, apakah ia jujur pada dirinya sendiri
atau mengikuti kehendak-kehendak duniawi dan keuntungan sesaat;80 apakah agama
dapat menjadikannya lebih tercerahkan atau sebaliknya, yakni lebih sesat.
Wahyu adalah kriteria (al-furqān), pemberi nilai dan standar norma-norma.
Manusia boleh saja membangun peradaban setinggi-tingginya. Menerobos seluruh
80Q.S. Āli ‘Imrān: 7.
337
penjuru langit dan bumi pun mereka dipersilakan, asal saja tidak lupa akan
bahwasanya seluruh karunia itu adalah nikmat Tuhan.81
Dari sisi lain, agama adalah sebuah cita-cita pembebasan. Para nabi diutus
tidak hanya untuk mengingatkan manusia “menyembah Tuhan,” tetapi juga untuk
menegakkan kebenaran, keadilan dan solidaritas.82 Ibrahim dan Musa, misalnya,
dengan jelas digambarkan al-Qur’an sebagai figur dengan watak subversive bagi
penguasa negerinya. Mereka, dan juga nabi-nabi yang lain, adalah para
“pemberontak” terhadap arogansi kekuasaan dan para elit yang korup. Jadi agama
juga meniscayakan keberanian dan perlawanan terhadap kezaliman dan
pengungkungan atas kebebasan manusia, baik kebebasan fisik maupun intelektual –
karena kekuasaan sering kali tidak sendirian, tetapi berkolaborasi dengan tradisi dan
peradaban untuk membodohkan dan memenjarakan akal manusia. Bukan hanya
kekuasaan, tradisi juga dapat memperbudak manusia. Tugas nabi tidak hanya
membebaskan kaumnya dari kejahatan tirani, tetapi juga dari jeratan kebodohan
tradisi yang sering kali diperalat oleh sang tiran.
Inilah yang sering tidak disadari oleh kebanyakan pemeluk agama. Mereka
lebih suka melihat agama sebagai barang yang semata-mata turun dari langit, bukan
tumbuh di bumi; Tuhan selalu dilihat sebagai penguasa yang berdiri sendiri, yang
berkehendak secara terpisah dari nilai-nilai yang dikenal manusia, yang tak
terjangkau, dan menetapkan hukum tanpa kompromi.
Para Nabi pembawa agama adalah manusia biasa. Mereka adalah penyampai
kebenaran dan penyeru kepada keselamatan. Akan tetapi sejarah kemudian
81Q.S. al-Rah}mān: 33-34.
82Bandingkan Ziaul Haque, Wahyu, 33.
338
mengubah seruan mereka menjadi sistem-sistem yang mapan dan didominasi
sekelompok manusia. Agama menjadi peradaban tertentu dan dianut oleh kelompok
manusia tertentu pula. Agama-agama tampil dengan wajah berbeda-beda dan
mengajarkan ritus-ritus serta hukum-hukum yang beragam. Maka, meskipun
mengajak kepada inti ajaran yang sama, antara satu agama dengan yang lainnya
saling menyalahkan. Pada titik ini muncullah pertanyaan: Bagaimana mendefinisikan
kebenaran itu dan bagaimana membuktikan bahwa sebuah sistem keagamaan adalah
jalan keselamatan yang sesungguhnya. Adakah jaminan terhadap persoalan ini,
sementara jalan yang berbeda-beda menawarkan tujuan yang sama? Orang yang
melihatnya dengan keputusasaan akan berkata: Tidak ada agama yang benar dan
perlu dipercaya.
Tidak diragukan lagi bahwa sepanjang sejarah, sampai hari ini, agama telah
memainkan peran amat penting dalam menggerakkan miliaran umat manusia untuk
hidup dengan moral dan spiritualitas yang positif dan membangun. Agama mampu
memberikan kekuatan melawan arogansi kehidupan, kekuasaan dan kesewenangan,
walaupun, sangat ironis, “acap kali” agama sendiri dapat menimbulkan arogansi.
Saat-saat seseorang menghadapi kesulitan secara mental pun agama selalu
menawarkan solusi yang menenteramkan. Agama memberikan kepercayaan diri yang
luar biasa, bahkan tanpa batas, sampai kematian pun menjadi legitimate demi agama.
Pada abad kesembilan, di tengah-tengah kejayaan Islam, orang-orang Nasrani
telah merelakan dirinya terbunuh dengan jalan menghina Nabi Muhammad dan
Islam. Seorang rahib bernama Perfectus telah memulai kisah tragis ini. Suatu hari ia
pergi berbelanja di pasar Cordova, ibu kota negara Islam Andalusia, lalu ia terlibat
339
dalam sebuah perdebatan dengan sekelompok Muslim soal ketuhanan Yesus.
Menyadari keberadaannya di tengah-tengah mayoritas Muslim, pada awalnya ia
sangat hati-hati. Tapi tiba-tiba ia menyerang secara sangat kasar dan menuduh Nabi
Muhammad sebagai seorang dukun palsu, cabul dan sekaligus anti Kristus. Maka
dapat dibayangkan, ia langsung diadili. Qād}ī Islam hanya mengingatkan Perfectus
dan tidak menjatuhkan hukuman kepadanya, karena kekeliruannya muncul atas dasar
hasutan yang dilakukan umat Islam. Namun Perfectus tidak berhenti di situ. Ia
kembali melancarkan serangannya dengan cercaan yang lebih keji kepada Islam,
sehingga Hakim tidak punya pilihan lain kecuali memberikannya hukuman yang
keras. Sang rahib pun dieksekusi. Perfectus ternyata tidak sendirian. “Pahlawan-
pahlawan” lain bermunculan. Mereka rela mati demi “kepuasan batin” dalam
“membela” agamanya dengan cara menghina agama lain. Pendeta Eulogio dan Paul
Alvaro membela para martir sebagai “tentara Tuhan” yang dengan gagah berjuang
membela keyakinannya.83
Perang Salib, di kemudian hari, juga digerakkan dengan mentalitas yang
sama. Pada tahun 1095, di Council of Clermont, Paus Urbanus II berseru kepada
umatnya – para pendeta, pahlawan, rakyat biasa – untuk menggerakkan sebuah
perang suci melawan umat Islam. Kaum barbarian Muslim dikatakan telah merampas
tanah dan kekuasaan Nasrani, dan sekaranglah saatnya, kata Paus, “kita bersatu
untuk melawan musuh Tuhan dan berhenti saling bertikai di antara sesama.” Orang-
orang Turki, lanjut sang Paus, “adalah ras terkutuk, ras yang tidak mengenal
83Karen Armstrong, Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam, (London: Victor Gallancz, 1991), 22-23.
340
Tuhan ...” Membunuh para monster tersebut dan mengusirnya dari negeri kita adalah
sebuah tugas suci, a holy act.84
Walaupun hari ini orang-orang Kristen mungkin menyadari betapa buruknya
kisah itu,85 mereka tidak dapat menghapus kesan betapa kejinya perlakuan yang telah
mereka buat terhadap kaum Muslim dan juga umat Yahudi. Sejarah kekejian sering
lebih sulit dilupakan daripada sebaliknya. Yesus mengajarkan cinta kasih, meski
terhadap musuh, tetapi sang Paus menyerukan peperangan juga atas nama Kristus.
Inilah contoh paradoks yang sering kali di temukan dalam agama.
Dalam Islam, kisah yang hampir serupa tidak sulit ditemukan; bersedia
menjadi martir (syahīd) berarti memilih jalan hidup yang amat mulia. Mati dalam
membela kebenaran dipuji oleh al-Qur’an. Orang yang terbunuh di jalan Allah
bahkan tidak disebut mati; ia tetap hidup dan mendapat rezeki di sisi Allah,
walaupun kebanyakan orang tidak menyadarinya.86 Perang dalam Islam bukan
peristiwa yang aneh, dan kesyahidan telah menjadi alat legitimasi yang ampuh bagi
setiap kegiatan kekerasan. Kaum Muslimin juga tidak takut mati demi agama dan
kebenaran. Kesyahidan bahkan merupakan fenomena yang dirindukan.
Siapa pun yang menengok ke Palestina hari ini, misalnya, dengan mudah
dapat menangkap fenomena tersebut. Kekerasan demi kekerasan terus berlanjut dan
telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian. Seorang ibu kadang kala merasa
bangga dan bahagia justeru ketika mendengar anaknya tewas dalam sebuah operasi
84Karen Armstrong, Holy War: The Crusades and Their Impact on Today’s World, (New York: Anchor Books, 2001), 3.
85Ibid., 4.
86Q.S. al-Baqarah: 154 dan Āli ‘Imrān: 169
341
bom bunuh diri. “Aku berdoa dari lubuk hati yang dalam semoga Allah memberikan
kepada anakku suksses dalam operasi yang ia lakukan,” kata seorang ibu dalam
sebuah wawancara dengan sebuah koran berbahasa Arab di London. “Aku mohon
kepada Allah agar Ia memberikan aku sepuluh orang Israel untuk Muhammad
(anakku) ... dan sekarang mimpinya menjadi kenyataan. Ia membunuh sepuluh orang
penduduk dan tentara Israel. Tuhan bahkan memberinya kehormatan lebih dari itu, di
mana sangat banyak orang Israel yang terluka.”87
Ini tentu saja bukan hanya merupakan fenomena konflik kontemporer. Seperti
telah disebutkan, tradisi Islam menyimpan literatur yang sangat kaya mengenai hal
ini. Namun di sini yang menjadi fokus perhatian adalah cita-cita perdamaian dari
agama itu sendiri, bukan mengungkit kembali permusuhan dan pertikaian.
Perlu disadari bahwa agama sering kali menjadi referensi kuat untuk berbagai
tindakan kekerasan dan permusuhan. Ini, kata François Houtart,88 dikarenakan agama
merupakan sumber ideologi sekaligus sumber kebudayaan. Sebagai sumber ideologi,
agama menekankan identitas yang melekat pada pemeluknya dan tidak dapat tidak
pada akhirnya akan mengarah pada pembentukan simbol-simbol khusus bagi
kelompok sendiri. Di sinilah berawal semangat eksklusivisme sebagai jalan
pengukuhan diri sendiri di tengah-tengah sebuah komunitas, yang merupakan rival
dari komunitas lain. Manusia dipecah-pecahkan oleh simbol yang menjadi lambang
sebuah ideologi. Sebagai sumber kebudayaan, agama juga telah memisah-misahkan
manusia dalam tradisi dan tipe budaya yang beragam. Pemisahan masyarakat Muslim
87Al-Syarq al-Awsāt}, 5 Juni 2002.
88François Houtart, “Kultus Kekerasan atas Nama Agama: Sebuah Panorama,” dalam Wim Beuken dan Karl-Josef Kuschel (ed.), Agama Sebagai Sumber Kekerasan? terj. Imam Baehaqie, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2003), xv-xxv.
342
dan masyarakat Barat, misalnya, merupakan contoh konkret dalam hal ini. Masing-
masing merasa memiliki peradaban sendiri dan saling merasa sebagai yang terbaik.
Bagaimana pun, persoalan yang paling krusial adalah ketika agama menjadi
landasan bagi kekerasan dan pembunuhan terhadap orang lain. Agama-agama besar
seperti Yahudi, Kristen dan Islam memiliki referensi tersendiri dalam kitab suci bagi
legitimasi untuk berperang melawan agama lain, meskipun sebenarnya landasan
tersebut amat kabur dan harus diperjelas melalui berbagai interpretasi. Perintah
perang memang jelas dalam kitab suci, tetapi siapa sebenarnya yang harus diperangi,
telah dikaburkan oleh ideologi dan tafsiran-tafsiran yang penuh dengan bias
kepentingan.
Ayat-ayat mengenai perang sangat jelas dalam al-Qur’an. Demikian pula
ayat-ayat yang menyuruh menahan diri dan melarang peperangan, amat terang
disebutkan dalam al-Qur’an. Sebagian ulama telah menerapkan konsep naskh di sini,
sehingga ayat-ayat yang dianggap masih berlaku hukumnya adalah ayat-ayat yang
menyuruh melancarkan perang terhadap orang-orang kafir.
Persoalan sesungguhnya di sini bukan hanya sekedar mengenai konsep naskh,
tetapi juga soal interpretasi terhadap objek perang yang disebutkan al-Qur’an. Siapa
yang sebenarnya yang harus diperangi dan dalam kondisi bagaimana? Ini dapat
merupakan objek kajian tersendiri. Cukup dikatakan di sini bahwa ayat-ayat al-
Qur’an juga tidak terlepas dari pengeksploitasian kelompok-kelompok tertentu untuk
kepentingan pengukuhan ideologi atau konsep teologi tersendiri.
E. Adakah Genuine Pluralism?
343
Pluralitas atau keberagaman barangkali telah ada sejak awal terbentuknya
kehidupan komunitas manusia, sebab pluralitas merupakan konsekuensi logis dari
keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia pada dasarnya adalah
individu-individu, yakni pribadi yang berdiri sendiri, namun juga tidak terlepas dari
keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat. Dalam rangka memenuhi
keutuhannya sebagai individu dan masyarakat, manusia perlu berkomunikasi dan
bahkan sering kali harus melawan sebagian dari kehendaknya untuk memenuhi
kehendaknya yang lain. Lebih lanjut, oleh para antropolog, manusia disebut animal
symbolicum, karena kemampuannya mengkategorikan sesuatu dengan menggunakan
simbol-simbol – sebuah kualitas yang membedakan manusia dari hewan. Inilah
barangkali yang diisyaratkan al-Qur’an bahwa kepada manusia telah diajarkan nama-
nama (al-asmā’) segala sesuatu.89 Artinya, manusia adalah makhluk yang cerdas dan
kreatif. Sisi lain dari kemampuan menggunakan simbol-simbol adalah kemampuan
memberi makna dan melakukan interpretasi. Di sinilah manusia mulai berbeda dalam
bentuk yang lebih signifikan, khususnya lagi ketika mereka berbicara mengenai nilai
dan agama.
Agama tentu saja agama manusia, bukan agama Tuhan, meskipun benar
bahwa agama adalah jalan manusia menuju Tuhan. Dengan demikian tidak ada
absolutisme dan klaim-klaim kemutlakan. Bagi mereka yang tidak menyadari bahwa
sumber perbedaan manusia adalah dalam kreativitasnya memberi makna-makna pada
kehidupan, agama adalah ajaran yang absolut dan karena itu tidak ada tawar
menawar dalam memahami agama. Karena itu, pluralitas didasarkan pada sebuah
89Q.S. al-Baqarah: 31.
344
kesadaran universal, di mana semua manusia merupakan makhluk Tuhan yang
diberikan kapasitas untuk mencerap kebenaran, namun juga memiliki kelemahan dan
keterbatasan sehingga pencerapannya tidak pernah dapat sempurna.
“Kesadaran” adalah kata kunci di sini. Bagaimana setiap komunitas budaya
dan agama seharusnya berusaha menyadari posisi masing-masing di tengah-tengah
kehidupan global adalah pertanyaan yang harus dicari jawabannya secara serius dan
sungguh-sungguh. Kesadaran ideologis-dogmatis kadang-kadang, ketika tidak
diimbangi dengan kesadaran sosial-budaya dan historis, dapat membawa kepada
kepincangan dan pemahaman yang parsial terhadap makna agama dan kehidupan.
Manusia tidak hidup sendirian di planet bumi. Pengetahuan dan pengalaman setiap
individu sebagai manusia tentang kebenaran juga tidak akan pernah sempurna.
Kebenaran adalah proses yang terus menerus dan abadi. Karena itu setiap “kita”
perlu membangun “jembatan” untuk melintas ke dalam kesadaran komunitas “lain.”
Kesadaran “lintas budaya dan agama” inilah yang akan dapat “memperbaiki
pemahaman tentang hubungan interpersonal” di antara sesama manusia.90
Pluralitas telah merupakan kenyataan dalam hidup, terutama dalam
beragama.91 Sikap eksklusif kaum beragama telah menjadi catatan sejarah yang tidak
terlupakan. Permusuhan antar agama adalah cerita menyedihkan dan kebanyakan
umat beragama mulai menyadari bahwa jalan damai jauh lebih baik dan lebih
diharapkan oleh agama itu sendiri. Dunia hari ini dapat menunjukkan bahwa
permusuhan antar agama tidak akan pernah menyelesaikan persoalan kemanusiaan
90Alef Theria Wasim, “Minoritas dan Mayoritas” dalam M. Amin Abdullah, dkk., Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 110.
91Alef Theria Wasim, “India Abad -16 dan -17: Tinjauan tentang Ke-beragamaan dalam Beragama,” al-Jāmi’ah, No. 49, 1992, 31-32.
345
universal yang sebenarnya jauh lebih besar dan lebih kompleks serta memerlukan
energi yang lebih banyak untuk menyelesaikannya. Persoalan kemiskinan dan
keadilan sosial seharusnya memiliki agenda yang lebih utama ketimbang perang dan
saling memusnahkan.
Karena itu yang lebih penting adalah mencari alternatif pemahaman
keagamaan yang secara intrinsik lebih menyentuh spirit dasar yang diserukan para
pembawa agama itu sendiri. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan kajian yang
mendasar, baik secara historis maupun hermeneutik, terhadap sumber ajaran agama
yang secara serentak dapat dipertanggung jawabkan oleh dan terhadap kelompok
mana pun.
Sampai pada poin ini, kajian dalam studi ini telah mencoba menelusuri
hubungan Yahudi-Muslim dengan berpijak pada ayat-ayat al-Qur’an dan fakta-fakta
sejarah yang relevan. Permusuhan memang bermula dari rasa bangga terhadap diri
sendiri serta sikap eksklusif dan fanatik. Melenyapkannya tidak mudah, apa lagi jika
telah menjadi bagian dari simbol komunitas dan ideologi yang diyakini memiliki
muatan keagamaan. Al-Qur’an senantiasa mengajak orang-orang Yahudi untuk
meninggalkan sikap tersebut dan mengatakan bahwa agama mereka sebenarnya,
kalau mereka mau jujur mengakuinya, tidak seperti yang mereka pertahankan. Al-
Qur’an melihat bahwa jalan rekonsiliasi terdapat dalam rujukan yang sangat
fundamental, yang merupakan akar ajaran agama Tuhan. Antara Yahudi, Nasrani dan
Islam, al-Qur’an menemukan figur Ibrahim, sebagai penyeru agama yang lurus,
tunduk dan patuh hanya kepada Tuhan semesta alam. Dasar inilah yang ditegaskan
al-Qur’an berulang kali kepada semua pemeluk agama monoteis, agar mereka tidak
346
terjebak dalam kesempitan berpikir yang berujung pada saling menyalahkan dan
saling bermusuhan.
Mengakui kebenaran orang lain memerlukan kebesaran jiwa yang luar biasa
dan tidak semua orang mudah melakukannya, tetapi inilah yang merupakan tuntutan
paling mendasar dari asas persaudaraan dan perdamaian.
Jika diulang kembali pertanyaan “adakah genuine pluralism?” – atau lebih
tegas, adakah genuine religious pluralism? – maka sejauh ini ada beberapa jawaban
berbeda yang dapat diberikan. Bagi sebagian kecil sarjana Muslim, genuine
pluralism adalah hal yang mungkin dan merupakan tantangan bagi umat beragama.
Namun bagi kebanyakan umat Islam, dan mungkin bagi kebanyakan umat beragama,
genuine pluralism adalah sesuatu yang mustahil.
Rita M. Gross92 menawarkan genuine pluralism sebagai sebuah sikap
alternatif bagi kehidupan beragama di zaman ini dan masa akan datang. Filosofi dari
pluralisme agama, menurut Gross, mesti melampaui upaya to include “them” in our
categories, dan juga tidak sekedar bersikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan.93
Genuine pluralism meniscayakan kesadaran yang sungguh-sungguh terhadap
perbedaan itu sendiri, namun tidak perlu yang satu dianggap melampaui yang lain
sebagai lebih superior, atau sebaliknya, semuanya dianggap sama. Apa yang paling
dibutuhkan adalah sikap apresiatif yang mendalam terhadap sistem-sistem yang
berbeda; perbedaan-perbedaan yang sebenarnya tiada batas itu hendaklah dilihat
sebagai sumber pengayaan nilai dan pengembangan diri yang sangat berharga, bukan
92Rita M. Gross, “Religious Pluralism: Some Implications for Judaism,” Journal of Ecumenical Studies, No. 26, Winter 1989, 29 ff.
93Ibid., 36.
347
sebagai problem atau sumber malapetaka. Hal seperti ini jelas tidak mungkin dalam
sistem beragama tradisional, yang melihat kebenaran sebagai sesuatu yang tunggal
dan absolut.
Keberatan terhadap pluralisme agama umumnya dinyatakan sebagai
keinginan untuk membela kebenaran agama, sebab pluralisme dianggap telah
terjebak dalam relativisme. Sebenarnya pluralisme tidak berangkat dari anggapan
bahwa segala sesuatu itu – termasuk agama – bersifat relatif, tetapi dari kenyataan
bahwa keberagaman merupakan sesuatu yang niscaya dalam kehidupan manusia.
Agama-agama yang berbeda hendaknya tidak dilihat pada sisi benar atau salahnya,
tetapi pada nilai dan kekhasannya masing-masing.94 Menurut penulis, bahkan ada
yang lebih penting, yaitu setiap pemeluk agama hendaknya berusaha mengenal – dan
kemudian, bila perlu, mengakui – kebenaran sebagaimana diungkapkan oleh
pemeluk agama lain, meski dengan perspektif yang berbeda. Hal ini didasarkan pada
kenyataan bahwa kebenaran yang dicapai manusia adalah kebenaran yang selalu
dapat diperkaya. Jika Tuhan adalah Yang Absolut, maka agama sebagai pencerapan
manusia yang serba terbatas terhadap Yang Absolut, tidak mungkin absolut. Dengan
demikian, pluralisme agama lebih merupakan kesadaran akan kelemahan diri
manusia atau sifat kerendahan hati di hadapan keagungan Tuhan yang tidak terbatas.
94Lihat Haryatmoko, “Paradigma Hubungan Antar Agama: Pluralisme De Jure Dan Kritik Ideologi,” dalam M. Amin Abdullah, dkk. (ed.), Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 37.
BAB VIP E N U T U P
A. Kesimpulan
Dari berbagai analisis dan diskusi yang dikemukakan dalam bab-bab
sebelumnya, beberapa kesimpulan penting dapat diambil di sini: Pertama, ayat-ayat
al-Qur’an tentang Yahudi atau Bani Israil pada dasarnya tidak semuanya berupa
kritik dan kecaman; sangat banyak ayat-ayat al-Qur’an yang justeru memberikan
apresiasi kepada mereka atau, sekurang-kurangnya, bersifat netral. Bani Israil
disebutkan al-Qur’an sebagai umat pilihan dan dalam banyak ayat dirujuk sebagai
Ahli Kitab, yakni umat yang memiliki kitab suci yang diturunkan Tuhan. Sementara
itu, kritik-kritik terhadap mereka ditujukan pada sikap dan perilaku mereka yang
menurut al-Qur’an telah menyimpang dari ajaran kitab suci mereka sendiri. Karena
itu al-Qur’an menyeru mereka mengamalkan ajaran kitab sucinya dengan benar.
Berkaitan dengan hal ini, konsep tah}rīf atau tabdīl, seperti yang kembangkan ulama
tradisional, yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi telah melakukan distorsi
terhadap teks kitab suci mereka, menurut penulis, sulit dipertahankan.
Kedua, kecaman-kecaman al-Qur’an terhadap Yahudi, sesuai tesis di atas,
sebenarnya merupakan respon kepada mereka yang secara nyata menentang al-
Qur’an. Artinya, al-Qur’an sama sekali tidak bermaksud menyerang agama Yahudi
atau menghina umat Yahudi; yang dikritik adalah perilaku mereka, dan yang dikutuk
adalah mereka yang melakukan pengkhianatan. Mereka ini adalah orang-orang
349
Yahudi Medinah yang hidup dan bergumul dengan peradaban Arab serta secara
intens berinteraksi dengan Nabi dan al-Qur’an. Dengan demikian, tidak semua
Yahudi di seluruh dunia dan sepanjang sejarah persis seperti diungkapkan al-Qur’an,
baik dari segi positif maupun negatifnya, bahkan jika kaum Muslim ingin
mengetahui segala sesuatu tentang Yahudi (sejarah, peradaban dan tradisi keagamaan
mereka), maka al-Qur’an bukanlah sumber satu-satunya dan bukan pula sumber yang
memadai. Dengan demikian, al-Qur’an akan dapat dipahami lebih baik jika
dipertemukan atau dibandingkan dengan ilmu pengetahuan dan teks-teks keagamaan
lainnya.
Ketiga, sesuai penjelasan di atas, pandangan-pandangan dan kritik al-Qur’an
terhadap kaum Yahudi dapat dikatakan bersifat khusus dan kondisional. Karena itu
konteks dan tujuan dari ayat-ayat tentang mereka itu harus diperhatikan. Ketika al-
Qur’an, misalnya, mengatakan Tuhan mengutuk mereka (orang-orang Yahudi), tidak
berarti yang dimaksudkan adalah semua mereka di seluruh permukaan bumi dan
sepanjang sejarah dunia. Demikian juga ketika al-Qur’an menuduh mereka
mengatakan Uzair anak Tuhan, yang dimaksudkan hanya beberapa orang di antara
mereka yang disaksikan langsung olah al-Qur’an sendiri. Kalau konteks pembicaraan
al-Qur’an seperti ini tidak diperhatikan maka akan menimbulkan kekeliruan dalam
menangkap pesan-pesan dasar dari al-Qur’an itu sendiri.
Keempat, dengan demikian, kebencian kaum Muslim terhadap Yahudi
sebenarnya tidak berasal dari ajaran al-Qur’an, dan pelabelan Yahudi dengan segala
macam kejahatan dan keburukan tidak sejalan dengan semangat al-Qur’an.
Fenomena ini memang telah mewarnai sejarah dan literatur Muslim dari sejak awal
350
sampai hari ini. Akan tetapi tidak berarti itulah kebenaran yang harus diterima dan
tidak boleh dikritisi. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan modern tampak
membuka peluang yang lebih positif untuk membangun kesadaran “kita” yang lebih
kritis terhadap “diri sendiri” dan “orang lain.” Demikian juga, kesadaran sejarah
(historical awareness) akan menjadikan seseorang lebih mampu bersikap positif dan
apresiatif terhadap keragaman pandangan dan tradisi dalam kehidupan manusia.
Kelima, ajaran dasar al-Qur’an sebenarnya sangat kompatibel dengan
semangat pluralisme agama. Al-Qur’an mengajak kepada keterbukaan dan
mengkritik sikap eksklusif dan klaim-klaim benar sendiri seperti yang diperlihatkan
oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di lingkungan masyarakat Arab
zaman turun wahyu. Oleh karena itu, alangkah ironisnya – dan memang tidak
mungkin – jika al-Qur’an sendiri lantas dianggap telah mengambil sikap dan
tindakan yang sama.
Akhirnya, jika semua umat beragama mau merujuk pada inti ajaran kitab
sucinya secara jujur dan bersedia untuk bersikap terbuka terhadap umat lain serta
mampu mengapresiasi kitab suci umat lain secara positif, maka akan ada harapan
yang lebih cerah bagi kehidupan yang lebih damai di antara umat manusia (yang
memiliki budaya dan tradisi keagamaan berbeda-beda) di masa akan datang.
B. Saran
Studi ini sangat terbatas, hanya mengeksplorasi ayat-ayat tentang Yahudi dan
melakukan reinterpretasi atas ayat-ayat tersebut dengan melihat konteks hubungan
351
Yahudi-Muslim dan wacana pluralisme agama yang sedang berkembang akhir-akhir
ini. Sasaran utama kajian ini adalah pembenahan pemahaman terhadap kitab suci dan
perbaikan hubungan Yahudi-Muslim yang telah dikotori oleh berbagai fitnah politik
dan dendam sejarah yang tidak rasional.
Ayat-ayat tentang Yahudi dapat dikaji dalam konteks dan dengan pendekatan
berbeda-beda. Dari sudut pandang bahasa, misalnya, masih diperlukan telaah lebih
mendalam mengenai istilah-istilah yang digunakan al-Qur’an, baik istilah Yahudi
dan Bani Israil itu sendiri (apa perbedaan di antara keduanya; apakah perbedaan
tersebut berdampak secara konseptual pada pemaknaan pandangan al-Qur’an?)
maupun istilah-istilah lain yang digunakan al-Qur’an ketika memberi respon dan
mengkritik mereka. Secara historis, telaah terhadap kronologis ayat-ayat tentang
Yahudi secara lebih rinci dan mendalam juga masih diperlukan: bagaimana,
misalnya, ayat-ayat tersebut berkembang secara radikal dari bentuk-bentuk seruan
yang lunak sampai pada sikap permusuhan dan kutukan? Sejauh mana
perkembangan tersebut dapat menjelaskan perkembangan hubungan orang-orang
Yahudi dan Nabi Muhammad serta bagaimana menyikapi keputusan akhir Nabi yang
mengambil tindakan keras terhadap mereka?
Terkait dengan kajian penulis dalam disertasi ini, ada baiknya dilakukan
penelitian mengenai buku-buku tentang Yahudi – baik asli maupun terjemahan –
yang beredar di Indonesia. Buku-buku tersebut mungkin, sejauh pantauan penulis,
hampir semuanya bernada negatif dan mengecam umat Yahudi, dan secara umum
argumentasi-argumentasi di dalamnya lebih banyak didasarkan pada ayat-ayat al-
Qur’an. Lalu, persoalannya, sejauh mana pemahaman ayat-ayat al-Qur’an tersebut
352
telah dilakukan secara tepat dan proporsional? Lebih jauh, bagaimana dampak isi
buku tersebut terhadap sikap masyarakat dalam merespon isu pluralisme agama,
konflik Timur Tengah, terorisme dan bahkan perkembangan pemikiran keagamaan di
Tanah Air yang dinilai sebagian kalangan juga karena pengaruh kejahatan Yahudi?
Penelitian tentang Yahudi dalam fikih penulis anggap juga patut
direkomendasikan. Fikih, yang ditulis ulama Islam berabad-abad silam dan masih
dipakai hingga saat ini, telah mendiskusikan secara ekstensif berbagai persoalan
terkait dengan Yahudi dan Nasrani serta Taurat dan Injil, mulai dari soal perkawinan,
pakaian, makanan, sampai masalah bersuci dan istinjā’. Secara garis besar, fikih
telah mendiskreditkan umat Yahudi dan juga Nasrani, bahkan dengan cara-cara yang
tidak pantas. Jika hal ini dapat dikaji kembali dengan pendekatan yang lebih terbuka,
positif dan semangat ilmiah yang sungguh-sungguh, maka akan sangat besar
kontribusinya bagi pemahaman keagamaan yang lebih sehat dan apresiatif, terutama
dalam konteks pluralisme agama. Kajian ini, menurut penulis, benar-benar penting
dalam rangka melacak serta memetakan kembali persoalan hubungan Yahudi-
Muslim yang hari ini semakin berada pada titik kritis yang mengkhawatirkan.
- أعلم الله - و
BIBLIOGRAFI
‘Abd al-Muta‘āl. La..Naskh fī al-Qur’ān: Limādhā..? Kairo: Maktabah Wabah, 1400 H./1980 M.
‘Abd al-Rah}mān, Khālid. Us}ūl al-Tafsīr wa Qawā‘iduh. Beirut: Dār al-Nafā’is, 1986.
‘Abd al-Rahmān, Anas. S{irā‘unā ma‘a al-Yahūd fī Z{ilāl al-Qur’ān, Saduran tafsir Sayyid Qut}b. Kuwait: Maktabah Dār al-Bayān, 1989.
‘Alī, ‘Abdullah Yūsuf. The Meaning of the Holy Qur’ān. Maryland: Amana Corporation, New ed. 1992.
Abdul Karim, Khalil. Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya dan Kekuasaan, Yogyakarta: LKíS, 2002.
Abū Daud, Sulaymān ibn al-Asy‘āts. Sunan Abī Dāwud. Dār al-Fikr, t.t.
Abū Syahbah, Muh}ammad ibn Muh}ammad. Al-Isrā’īliyyāt wa al-Mawd}ū‘āt fī Kutub al-Tafsīr. Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1408 H.
Abū Zayd, Nas}r H{āmid. Isykāliyyāt al-Qirā’ah wa Āliyyāt al-Ta’wīl. al-Dār al-Baid}ā’: al-Markaz al-Tsaqāfī al-‘Arabī, cet. III, 1994.
-------. Mafhūm al-Nas}s}: Dirāsah fī ‘Ulūm al-Qur’ān. Al-Dār al-Bayd}ā’: al-Markaz al-Tsaqāfī al-‘Arabī, cet. V, 2000.
Adang, Camilla. Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible from Ibn Rabban to Ibn Hazm. Leiden: E. J. Brill, 1996.
Ahmad, Barakat. Muhammad and the Jews: A Re-Examination. New Delhi: Vikas Publishing House, 1979.
Ahmad, Reme. “Mahathir tells Muslims to use brains to fight Jews,” The Straits Times. Oct. 19, 2003.
Ahmed, Moinuddin. Religions of All Mankind. New Delhi: Kitab Bhavan, 1994.
Alef Theria Wasim. “India Abad -16 dan -17: Tinjauan tentang Ke-beragamaan dalam Beragama,” al-Jāmi’ah. No. 49, 1992.
354
-------. “Minoritas dan Mayoritas” dalam M. Amin Abdullah, dkk. Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
Ali, K. A Study of Islamic History. Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1980.
Amin Abdullah, M. “Al-Qur’an dan Pluralisme dalam Wacana Posmodernisme,” Profetika. Vol.1, 1 Januari 1999.
-------. “Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius,” dalam M. Amin Abdullah, dkk. Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
-------, dkk. Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga - Kurnia Kalam Semesta, 2002.
-------. Studi Agama: Normativitas atau Historisitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Arkoun, Mohammed. “Explorations and Responses: New Perspectives for a Jewish-Christian-Muslim Dialogue,” Journal of Ecumenical Studies. No. 26, Summer 1989.
Armstrong, Karen. Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam. London: Victor Gollancz, 1991.
Ast, Friedrich. Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und Kritik. Lanshut: Thomann, 1808.
Aviezer, Ravitzky. Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, trans. Michael Swirsky and Jonathan Chipman. Chicago: Chicago University Press, 1996.
Ayoub, Mahmoud. “Islam and Christianity between Tolerance and Acceptance,” Islam and Christian-Muslim Relation. Vol. 2, 1991.
-------. “Christian-Muslim Relations Into the Twenty-first Century: A Round Table Discussion,” Islam and Christian-Muslim Relation. Vol. 3, 1992.
-------. The Qur’an and Its Interpreters. Albany: State University of New York Press, 1988.
Baghawī, al-H{usayn ibn Mas‘ūd al-. Ma‘ālim al-Tanzīl. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1987.
Bannā, H{asan al-. Risālatān fī al-Tafsīr wa sūrah al-Fātih}ah. Beirut: Mansyūrāt al-‘Ashr al-H}adīth, 1972.
355
Barāniq, Muh}ammad Ah}mad dan Muh}ammad Yūsuf al-Mah}jūb. Muh}ammad wa al-Yahūd. Kairo: Mu’assasah al-Mat{bū‘āt al-H}adītsah, t.t.
Baum, Gregory. Religion and Alienation: A Theological Reading of Sociology. New York: Paulist Press, 1975.
Bayd}āwī, ‘Abdullāh ibn ‘Umar al-. Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl. Beirut: Dār al-Fikr, 1996 M./1416 H.
Bickerton, Ian J. dan M.N. Person. The Arab-Israeli Conflict. Melbourn: Longman Cheshire, 2nd edition 1990.
Bighā, Mus}t}afā Dīb al- dan Muh}yi al-Dīn Dīb Mastū. al-Wād{ih{ fī ‘Ulūm al-Qur’ān, Damsyiq: Dār al-Kalim al-T{ayyib, 1996.
Booth, Wayne C. Critical Understanding: The Power and Limits of Pluralism. Chicago: University of Chicago Press, 1979.
Bahūtī, Mans}ūr ibn Yūnus, al-. Kasysyāf al-Qinā‘ ‘an Matn al-Iqnā‘. Beirut: Dār al-Fikr, 1402 H./1982 M.
Bukhārī, Muh}ammad ibn Ismā‘īl al-. S{ah}īh} al-Bukhārī. Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1987 M./1407 H.
Bultmann, Rudolf. Essays, Philosophical and Theological. London: SCM Press, 1955.
Burhanuddin Daya. Agama Yahudi. Yogyakarta: Bagus Arafah, 1982.
-------. “Bingkai Teologi Kerukunan Bersama,” al-Jāmi’ah. No. 59, 1996.
Busse, Heribert. Islam, Judaism, and Christianity: Theological and Historical Affiliations, terj. Allison Brown dari Bahasa Jerman. Princeton: Markus Wiener Publishers, 1998.
Būt}ī, Muhammad Sa‘īd Ramad}ān al-. Fiqh al-Sīrah. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
Carrier, James G. (ed.). Occidentalism: Images of the West. Oxford: Clarendon Press, 1995.
Cragg, Kenneth. The Event of the Qur’an: Islam in Its Scripture. Oxford: Oneworld, 1994.
Darwaza, Muhammad Azzah. “The Attitude of the Jews Towards Islam, Muslims and the Prophet of Islam-P.B.U.H. at the Time of His Honourable
356
Prophethood,” dalam D.F. Green (ed.). Arab Theologians on Jews and Israel. Genève, 1974.
Deedat, Ahmad. Dialog Islam dan Yahudi: Damai atau Terus Konflik, terj. Djamaluddin Albunny. Surabaya: Pustaka Progressif, 1991.
Didik Hariyanto, M. Mengungkap Kelicikan Yahudi dalam al-Qur’an, Hadis, dan Sejarah. Jogjakarta: Menara Kudus, 2002.
Dihlawī, Syah Walī al-Lāh, al-. Al-Fawz al-Kabīr fī Us}ūl al-Tafsīr. Karachi: Qadīmī Kutub Khāna, 1966.
Dimont, Max I. Jews, God and History. New York: Penguin Books, Edisi Revisi 1994.
Encyclopaedia Britannica. Deluxe Edition 2004 CD-ROM.
Esack, Farid. Qur’an, Liberation and Pluralism. Oxford: Oneworld Publication, 1998.
Fackenheim, Emil L. What is Judaism: An Interpretation for the Present Age. New York: Collier Books, 1987.
Faruqi, Ismail R. al-. “Islam and Zionism,” dalam John L. Esposito (ed.). Voices of Resurgent Islam. Oxford: Oxford University Press, 1983.
Ferguson, Duncan S. Biblical Hermeneutics: An Introduction, London: SCM Press, 1986.
Firestone, Reuven. Children of Abraham: An Introduction to Judaism for Muslims, Hoboken: Ktav Publishing House, 2001.
-------. Diskusi melalui e-mail. 18 Nopember 2003.
-------. Journeys in Holy Lands: The Evolution of the Abraham-Ishmael Legenda in Islamic Exegesis. New York: State University of New York Press, 1990.
Fitz, James, S.M. “Moses As A Leadership Model,” Human Development. Vol. 4 Winter 1983.
Freedman, Samuel G. Jew v.s. Jew: The Struggle for the Soul of American Jewry. New York: Touchstone, 2000.
Gätje, Helmut. The Qur’ān and Its Exegesis. Oxford: Oneworld, 1997.
357
Ghazālī, Muhammad al-. A Thematic Commentary on the Qur’an, trans. Ashur A. Shamis. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2001.
Gil, Moshe. “The Origin of the Jews of Yathrib,” Jerussalem Studies in Arabic and Islam. No. 4, 1984.
González, Justo L. Mañana: Christian Theology from a Hispanic Perspective. Nashville: TN: Abbingdon Press, 1990.
Green, D. F. (ed.). Arab Theologians on Jews and Israel. Genève, 1974.
Gross, Rita M. “Religious Pluralism: Some Implications for Judaism,” Journal of Ecumenical Studies. No. 26, Winter 1989.
Guillaume, A. The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah. London: Oxford University Press, Third Impression, 1970.
Hamid Basyaib. “Perspektif Sejarah Hubungan Islam dan Yahudi,” dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. (ed.). Passing Over: Melintas Batas Agama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
Hamim Ilyas. “Pandangan al-Qur’an terhadap Bigetisme Yahudi dan Kristen,” al-Jāmi’ah. No. 62/XII/1998.
-------. Pandangan Al-Qur’an Terhadap Ahli Kitab: Studi Tafsir Al-Manar, Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001, 158.
Haque, Ziaul. Wahyu dan Revolusi, terj. E. Setiawati Al Khattab. Yogyakarta: LKiS, 2000.
Haryatmoko. “Paradigma Hubungan Antar Agama: Pluralisme De Jure Dan Kritik Ideologi,” dalam M. Amin Abdullah, dkk. Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
Hasan Asari. “Yang Hilang dari Pendidikan Islam: Seni Munādharah,” Ulumul al-Qur’an. No. 1, Vol. V, 1994.
Hasjmy, A. Jahudi Bangsa Terkutuk: Lukisan Kedjahatan Mereka dalam Sejarah, (Banda Atjeh: Pustaka Faraby, 1970).
Haykal, H{usein. The Life of Muh}ammad, trans. Ismā‘īl Rājī al-Fārūqī. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1993.
Heschel, Abraham Joshua. God in Search of Man: A Philosophy of Judaism. New York: The Noonday Press, 1998.
358
Holquist, Michael. Dialogism: Bakhtin and His World. London and New York: Routledge, 1990.
Hopfe, Lewis M dan Mark R. Woodward. Religions of the World, New Jersy: Prentice Hall, 1998.
Houtart, François. “Kultus Kekerasan atas Nama Agama: Sebuah Panorama,” dalam Wim Beuken dan Karl-Josef Kuschel (ed.), Agama Sebagai Sumber Kekerasan? terj. Imam Baehaqie. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2003.
Ibn ‘Alī, Syihāb al-Dīn Ah}mad. Al-‘Ujāb fī Bayān al-Asbāb. Al-Dammām: Dār Ibn al-Jawzī, 1997.
Ibn ‘Arabī, Muh}y al-Dīn. Tafsīr Ibn ‘Arabī. 2 Volume, Beirut: Dār al-S}ādir, t.t.
Ibn H{anbal, Ah}mad. Musnad al-Imām Ah}mad. Mesir: Mu’assasah Qurt}ubah, t.t.
Ibn H{azm, ‘Alī ibn Ah}mad. al-Fis}al fi al-Milal wa al-Ahwā’ wa al-Nih}al, (Kairo: Maktabah al-Khānijī, t.t.
-------. Al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur’ān al-Karīm. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H.
Ibn Hisyām, ‘Abd al-Malik. Al-Sīrah al-Nabawiyyah. Beirut: Dār al-Jayl, 1411 H.
Ibn al-Jawzī, ‘Abd al-Rah}mān ibn ‘Alī. Nawāsikh al-Qur’ān. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1405 H.
Ibn Katsīr. Tafsīr al-Qur’ān al-‘Az}īm. Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H.
Ibn Khaldūn, ‘Abd al-Rah}mān ibn Muh}ammad. Muqaddimah. Beirut: Dār al-Qalam, 1984.
Ibn Manz}ūr. Lisān al-‘Arab. Beirut: Dār S{ādir, t.t.
Iqbal, Muhammad. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. New Delhi: Kitab Bhavan, 1981.
Ismatu Ropi. “Wacana Inklusif Ahl al-Kitāb,” Paramadina. Vol. 1 No. 2, 1999.
Izutsu, Toshihiko. Ethico-Religious Concepts in the Qur’ān. Montreal: McGill University Press, 1966.
Jacobs, Louis. The Book of Jewish Belief. Behrman House, t.t.
359
-------. The Jewish Religion: A Companion. Oxford: Oxford University Press, 1995.
Jacobsen, Douglas. “Multicultural Evangelical Hermeneutics and Ecumenical Dialogue”, Journal of Ecumenical Studies. Vol. 37, No. 2, Spring 2000.
Jalālayn (Jalāl al-Dīn al-Mah}allī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūt}ī) al-. Tafsīr al-Jalālayn. Kairo: Dār al-H{adīts, t.t.
Jary, David dan Julian Jary. The Harper Collins Dictionary of Sociology. New York: HarperCollins, 1991.
Jacobsen, Douglas. “Multicultural Evangelical Hermeneutics and Ecumenical Dialogue,” Journal of Ecumenical Studies. Vol. 37, No. 2, Spring 2000.
Juwaynī, Mus}t}afā al-S{āwī al-. Manāhij fī al-Tafsīr. Al-Iskandariyyah: Mansya’ah al-Ma‘ārif, t.t.
Khalāf Allāh, Muhammad Ahmad. al-Fann al-Qas}as}ī fi al-Qur’ān al-Karīm. Kairo: Sīnā li al-Nasyr wa al-Intisyār al-‘Arabī, 1999; Edisi Indonesia, Muhammad A. Khalafullah. Al-Qur’an Bukan “Kitab Sejarah”: Seni Sastra, dan Moralitas Kisah-kisah al-Qur’an, terj. Zuhairi Misrawi dan Anis Maftukhin. Jakarta: Paramadina, 2002.
Kuschel, Karl-Josef. Abraham: Sign of Hope for Jews, Christians and Muslims, terj. John Bowden dari Bahasa Jerman. New York: Continuum, 1995.
Lakhsassi, Abderrahmane. “The Qur’an dan the “Other”,” dalam Leonard Swilder (ed.). Theoria → Praxis: How Jews, Christians, and Muslims Can Together Move from Theory to Practice. Leaven: Peeters, 1998.
LaSor, W. S., D. A. Hubbard dan F. W. Bush. Pengantar Perjanjian Lama 1: Taurat dan Sejarah, terj. Werner Tan dkk. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
Legenhausen, Muhammad. Satu Agama atau Banyak Agama, terj. Arif Mulyadi dan Ana Farida. Jakarta: Lentera Basritama, 2002.
Lewis, Bernard. Islam in History: Ideas, People, and Events in the Middle East. Chicago: Open Court Publishing Company, 2nd Edition, 1993.
Machasin. “Sumbangan Hermeneutika terhadap Ilmu Tafsir.” Makalah Diskusi, Forum Cendekia Muda, Lembaga Studi Agama dan Demokrasi (èLSAD), Surabaya, 2002.
Madigan, Daniel A. Membuka Rahasia Alquran, terj. Tim Redaksi Nalar. Jakarta: Intimedia Ciptanusantara, 2001.
360
Mālik ibn Anas. Al-Muwat}t}a’. Mesir: Dār Ih}yā’ al-Turāts al-‘Arabī, t.t.
MEMRI (The Middle East Media Research Institute). Special Dispatch Series, No. 354, March 13, 2002; No. 357, March 21, 2002.
Mohd. Fauzi bin H. Awang. Ugama-ugama Dunia. Malaysia: Pustaka Aman Press, 1971.
Muhammad Galib M. Ahl al-Kitāb: Makna dan Cakupannya. Jakarta: Paramadina, 1998.
Muslim ibn al-H{ajjāj. S{ah}īh} Muslim. Beirut: Dār Ih}yā’ al-Turāts al-‘Arabī, t.t.
Nah}h}ās, Ah}mad ibn Muh}ammad, al-. Al-Nāsikh wa al-Mansūkh. Kuwait: Maktabah al- Falāh}, 1408 H.
Nashruddin Baidan. Metodologi Penafsiran al-Qur’an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
Nawāwī, Yah}yā ibn Syaraf, al-. Rawd}ah al-T{ālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1405.
Neusner, Jacob. Signposts on the Way of Torah. USA: Wadsworth, 1998.
-------. The Mishnah: A New Translation. New Haven: Yale University Press, 1988.
Nurcholish Madjid. “Metodologi dan Orientasi Studi Islam Masa Depan,” Jauhar. Vol. I, No. 1, Desember 2000.
Nursi, Badiuzzaman Said. Risalah Mukjizat Al-Quran, terj. Anuar Fakhri Omar, dkk. Terengganu: Yayasan Islam Terengganu, 1999.
Own, Kamal Ahmad. “The Jews are the Enemies of Human Life as is Evident from Their Holy Book,” dalam D.F. Green (ed.). Arab Theologians on Jews and Israel. Genève, 1974.
Palmer, Richard E. Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer. Evanston: Northwestern University Press, 1969.
Peters, F.E. Muhammad and the Origins of Islam. New York: State University of New York Press, 1994.
Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
361
Pratt, James B. The Religious Consciousness: A Psychological Study. New York: The Macmillan Co., 1920.
Qaradhawi [Qarad}āwī – pen], Yusuf al-. Palestina: Masalah Kita Bersama, terj. Tim SAMAHTA ’99. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
Qatādah ibn Di‘āmah. al-Nāsikh wa al-Mansūkh. Beirut; Mu’assasah al-Risālah, 1404 H.
Quraish Shihab, M. Mukjizat Al-Quran. Bandung: Mizan, Cet. ke-4 1998.
Qurt}ubī, Muh}ammad ibn Ah}mad al-. Al-Jāmi‘ li Ah}kām al-Qur’ān. Kairo: Dār al-Sya‘b, Cet. II, 1372 H.
Qut}b, Sayyid. Fī Z{ilāl al-Qur’ān. Beirut: Dār Ih}ya’ al-Turāth al-‘Arabī, 1971; Fī Z{ilāl al-Qur’ān, Edisi CD-ROM. Jordan: Arabic Textware.
Rahman, Fazlur. “Islam,” dalam Mircea Eliade (ed.), Encyclopaedia of Religion. New York, 1987.
-------. “Islam’s Attitude Toward Judaism,” The Muslim World. No. 1, Vol. LXXII, Januari 1982.
-------. Islam. Chicago: The University of Chicago Press, 1979.
-------. Major Themes of the Qur’an. Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980.
Rānīrī, Nūr al-Dīn al-. S{irāt} al-Mustaqīm, tepi kitab karangan Muh}ammad Arsyad ibn ‘Abdullāh al-Banjārī. Sabīl al-Muhtadīn li al-Tafaqquh fī Amr al-Dīn. Indonesia: Maktabah Dār Ih}yā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.
Rāzī, Fakhr al-Dīn al-. Mafātih} al-Ghayb, Mekkah: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1990.
Republika Online (16 Oktober 2003): www.republika.co.id/berita/online/2003/ 10/16/143265.shtm.
Richards, Glyn. Toward a Theology of Religions. London: Routledge, 1989.
Rid}ā, Muh}ammad Rasyīd. Tafsīr al-Manār. Beirut: Dār al-Fikr, 1973.
Rippin, Andrew. “Tafsir”, dalam Mircea Eliade (ed.). The Encyclopaedia of Religion. New York: Macmillan, 1987.
Riyād}, al-. (Saudi Arabia, 10 Maret 2001).
362
Robinson, George. Essential Judaism: A Complete Guid to Beliefs, Customs and Ritual. New York: Pocket Books, 2000.
Sachedina, Abdulaziz. “Is Islamic Revelation an Abrogation of Judaeo-Christian Revelation,” Concilium, March 1994.
S{ālih}, S{ubh}ī al-. Mabāh}its fī ‘Ulūm al-Qur’ān. Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1977.
Samaw’al ibn Yah}yā, al-. Ifh}ām al-Yahūd wa Qis}s}ah Islām al-Samaw’al wa Ru’yāh al-Nabiyy S{alla al-Lāh ‘alayh wa Sallam. Beirut: Dār al-Jayl, 1990.
Siddiqi, Mazheruddin. The Qur’ānic Concept of History. Delhi: Adam Publishers, 1994.
Smith, Huston. The World’s Religions: Our Great Wisdom Traditions. New York: HarperCollins, 1991.
Smith, Wilfred Cantwell . “Comparative Religion: Whither—and Why?”, dalam Mircea Eliade and Joseph M. Kitagawa (ed.). The History of Religions: Essays in Methodology. Chicago: The University of Chicago Press, 1959.
Suyūt}i, al-. Al-Durr al-Mantsūr fī Tafsīr bi al-Ma’tsūr. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
-------. Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān. Kairo: Mus}t}afā al-Bābī al-H{alabī, 1370 H.
Syalabī, Ah}mad. Muqāranah al-Adyān 1: al-Yahūdiyyah. Kairo: Maktabah al-Nahd}ah al-Mis}riyyah, Cet. V, 1978.
Syawkānī, al-. Fath} al-Qadīr. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
Syeed, Sayyid Muhammad. Diskusi di ISNA (Islamic Society of North America), Indiana, Amerika Serikat.
T{abarī, Muh}ammad ibn Jarīr al-. Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān. Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H.
T{abāt}abā’ī, Sayyid Muh}ammad H{usayn al-. al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān. Beirut: Mu’assasah al-A‘lāmī li al-Mat}bū‘ah, 1393 H./1973 H.
T{abbārah, ‘Afīf ‘Abd al-Fattāh}. Al-Yahūd fī al-Qur’ān. Beirut: Dar al-‘Ilm lil-Malāyīn, 1986.
Thalib, M. 76 Karakter Yahudi dalam al-Qur’an. Solo: Pustaka Mantiq, t.t.
The Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition. Leiden: Koninklijke Brill NV, 1999.
363
Tracy, David. Plurality and Ambiguity: Hermeneutics, Religion, Hope. San Francisco: Harper and Row, 1987.
Turmudhī, Muh}ammad ibn ‘Īsā al-. Sunan al-Turmudhī. Beirut: Dār Ih}yā’ al-Turāts al-‘Arabī, t.t.
Wāh}idī, Abū al-H{asan ‘Alī al-. al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz. Beirut: Dār al-Qalam, 1415 H.
-------. Asbāb al-Nuzūl. Beirut: Dār al-Fikr, 1414/1994.
Watt, William Montgomery. Companion to the Qur’an. Oxford: Oneworld Publications, 1994.
-------. Muhammad’s Mecca. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1988.
“What they say about Mahathir’s remarks on Jews”, The Straits Times. Oct. 19, 2003.
Wolf, Friedrich August. Vorlesung u\ber die Enzyklopa\die der Altertumswissenschaft. ed. J.D. Gürtl. Leipzig: Lehnhold, 1831, Vol. I.
Wyschogrod, Michael. “Islām and Christianity in the Perspective of Judaism,” dalam I.R. Faruqi (ed.). Trialogue of the Abrahamic Faiths. New Delhi: Genuine Publication, 1989.
Zarkasyī, Muh}ammad ibn Bahādir al-. Al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān. Beirut: Dār al-Ma‘rifāt, 1391 H.
Zarqānī, Muh}ammad ‘Abd al-‘Az}īm al-. Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’an. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
Zebiri, Kate. “Relation Between Muslims and Non-Muslims in the Thought of Western-Educated Muslim Intellectuals,” Islam and Christian-Muslim Relations. Vol. 6, No. 2, 1995.
Zuh}aylī, Wahbah al-. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
<http://abbc.com/quotes>.
<http://talmud.faithweb.com/gentiles.htm>.
<http://www.answering-islam.org/Quran/Contra/>.
<http://www.jewfaq.org/frames/beliefs.htm>.
364
<http://www.memri.org>.
<http://www.secularislam.net/Secular Islam_NET Jews in the Qur’an.htm>.
<http://www.qaradawi.net>.
<http://www.ummah.muslimsonline.com/~islamawe/Quran/Contrad/External>.
<http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/8815/Response to 1000 Quotes by and about Jews.htm>.