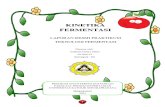Majapahit dan Pajajaran - Satria, Wina, Eka - SMAK Mgr. Soegijapranata Pasuruan
Chitin Chitosan_Elizabeth Caroline Setiawan_12.70.0006_A3_UNIKA SOEGIJAPRANATA
-
Upload
reed-jones -
Category
Documents
-
view
16 -
download
0
description
Transcript of Chitin Chitosan_Elizabeth Caroline Setiawan_12.70.0006_A3_UNIKA SOEGIJAPRANATA
12CHITIN & CHITOSAN
LAPORAN RESMI PRAKTIKUMTEKNOLOGI HASIL LAUT
Disusun oleh :Nama: Elizabeth Caroline SetiawanNIM: 12.70.0006Kelompok: A3
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGANFAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIANUNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATASEMARANG2014
Acara I
1. HASIL PENGAMATAN
Hasil pengamatan persentase rendemen chitin I, rendemen chitin II dan rendemen chitosan yang diperoleh dari limbah padat kulit udang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Hasil Pengamatan Rendemen Chitin & Chitosan Limbah Padat Kulit UdangKelPerlakuanRendemen Chitin I (%)Rendemen Chitin II (%)Rendemen Chitosan (%)
A1Kulit udang + HCl 0,75 N + NaOH 3,5% + NaOH 40%301021,765
A2Kulit udang + HCl 0,75 N + NaOH 3,5% + NaOH 40%3428,57124,875
A3Kulit udang + HCl 1 N + NaOH 3,5% + NaOH 50%203016,462
A4Kulit udang + HCl 1 N + NaOH 3,5% + NaOH 50%49045,455
A5Kulit udang + HCl 1,25 N + NaOH 3,5% + NaOH 60%304010,355
A6Kulit udang + HCl 1,25 N + NaOH 3,5% + NaOH 60%302010,4
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa konsentrasi larutan asam serta larutan basa yang digunakan dalam pengesktrakan chitin dan chitosan yang berbeda akan menghasilkan persentase rendemen yang berbeda pula. Rendemen chitin I tertinggi diperoleh dengan penggunaan HCl 0,75 N (34%), sedangkan yang terendah pada HCl 1 N (4%). Rendemen chitin II tertinggi diperoleh oleh kelompok A4 (90%), sedangkan yang terendah diperoleh oleh kelompok A1 (10%). Sedangkan untuk rendemen chitosan tertinggi diperoleh dengan penggunaan NaOH 50% (45,455%), sedangkan yang terendah pada NaOH 60% (10,355%).
12. PEMBAHASAN
Chitin adalah substansi keras yang menyusun rangka luar serangga dan krustasea. Selain itu, chitin dapat diperoleh dari fungi, mushroom, cacing dan diatom. Chitin merupakan polimer alami terbanyak kedua setelah selulosa dan juga tergolong sebagai polisakarida struktural (Isa et al., 2012). Chitin merupakan homopolimer dari residu N-asetil-D-glukosamin yang diikat oleh ikatan -1-4. Sumber utama chitin ialah limbah krustasea dan dinding sel dari fungi. Chitin dan turunannya memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Limam et al., 2011). Chitin dapat diekstrak dari kulit udang-udangan yang dicuci, dikeringkan dan kemudian dihaluskan hingga dapat melewati ayakan 250 m (Isa et al., 2012).
Chitosan ialah kopolimer dari N-asetil glukosamin dan unit glukosamin dalam bentuk homopolimer. Chitosan merupakan polisakarida dengan berat molekul tinggi. Chitosan terdapat di alam sebagai dinding sel beberapa jamur serta serangga. Chitosan diperoleh dengan deasetilasi dari kitin dengan penambahan larutan alkali 40-50% pada suhu 120-160C (Radhakumary et al., 2005).
Udang merupakan salah satu produk hasil perikanan utama di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Udang biasa diekspor dalam keadaan beku setelah mengalami proses pemisahan kepala dan kulit. Proses pemisahan ini menimbulkan banyak limbah padat yang berdampak pada polusi lingkungan. Meskipun begitu, limbah ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi jika mengalami pengolahan menjadi chitin dan chitosan (Patria, 2013). Chitin dan chitosan dapat diekstrak dari produk sampingan Parapenaeus longirostris dan Squilla mantis, kemudian dilakukan pengujian dengan parameter aktivitas biologi, contohnya aktivitas antibakteri, antijamur dan antioksidan (Limam et al., 2011). Deasetilasi yang dikontrol untuk menghasilkan turunan yang kurang lebih 50% bebas amina dapat digunakan untuk memproduksi chitosan (water soluble chitin). Chitin dan chitosan telah diketahui tidak beracun dan tidak menyebabkan alergi (Naznin, 2005).
2Chitin dan chitosan dapat diperoleh dari kulit udang yang telah mengalami tahapan demineralisasi, deproteinasi dan deasetilasi (Naznin, 2005). Pada praktikum ini dibuat chitin dan chitosan dari limbah padatan kulit udang. Pertama-tama, kulit udang dicuci dengan air mengalir. Kulit yang sudah bersih kemudian dikeringkan dan dicuci lagi dengan air panas sebanyak dua kali. Setelah itu kulit udang kembali dikeringkan dan dihancurkan dengan blender hingga menjadi serbuk. Penghancuran ini bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel sehingga luas permukaan partikel yang didapatkan lebih besar sehingga mudah berkontak dengan senyawa lain (Anief, 2004). Untuk mendapatkan serbuk yang benar-benar halus, dilakukan pengayakan dengan ayakan berukuran 40-60 mesh. Hasil yang diperoleh ialah serbuk sampel kulit udang.
Preparasi sampel diawali dengan pengumpulan kulit udang. Kulit ini kemudian dicuci dan dikeringkan. Sampel yang sudah kering kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender dan diayak dengan ayakan ukuran 80 mesh (Patria, 2013).
Selanjutnya dilakukan tahap demineralisasi, pertama-tama ditimbang serbuk kulit udang sebanyak 5 gram, dilanjutkan dengan penambahan HCl dengan perbandingan serbuk dan larutan sebesar 1:10. Konsentrasi dari HCl yang digunakan beragam, 0,75 N untuk kelompok A1-A2, 1 N untuk kelompok A3-A4 dan 1,25 N untuk kelompok A5-A6. Larutan HCl pada proses demineralisasi memiliki tujuan untuk menghilangkan komponen garam yang bersifat anorganik serta komponen mineral yang terdapat pada chitin. Mineral yang paling banyak ditemukan dalam chitin yang dibuat dari kulit udang ialah kalsium karbonat (CaCO3) serta mineral-mineral lain yang terdapat dalam jumlah kecil, misalnya magnesium dan silika (Martati, 2002). Kemudian dilakukan pengadukan selama 1 jam pada suhu 90C. Hasil yang diperoleh kemudian dicuci dengan air mengalir hingga didapatkan pH yang netral. Tahap pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan sisa HCl pada residu (Yuliusman, 2010). Setelah mencapai pH netral, residu ini dikeringkan dalam oven bersuhu 80C selama 24 jam. Hasil dari tahap ini disebut rendemen chitin I.
3Demineralisasi dilakukan pada suhu ruang dengan menggunakan HCl 1 M. Residu yang diperoleh dicuci dengan aquades hingga pHnya netral, kemudian dilanjutkan dengan
pengeringan dengan oven 60C hingga diperoleh berat yang konstan (Isa et al., 2012). HCl 30% (Naznin, 2005) dan HCl 1,25 N (Limam et al., 2011) juga dapat digunakan sebagai larutan pereaksi pada tahap demineralisasi. Pada tahapan demineralisasi, hasil pengeringan pada tahap deproteinasi ditambah dengan HCl 2 N dengan perbandingan sampel dan HCl sebesar 1:5. Campuran ini kemudian didiamkan selama 1 jam agar diperoleh hasil berupa filtrat dan residu. Residu lalu dipisahkan dari filter dan dicuci hingga memiliki pH yang netral. Selanjutnya dilakukan lagi pengeringan selama 4 jam dengan suhu sebesar 60C (Patria, 2013). Pada penelitian tersebut dilakukan tahap deproteinasi terlebih dahulu dan diikuti dengan tahap demineralisasi. Besarnya konsentrasi larutan NaOH disesuaikan dengan karakteristik bahan baku yang digunakan. Hal tersebut disebabkan karena bahan baku yang berbeda akan menghasilkan persentase chitin yang berbeda (Isa et al., 2012).
Selanjutnya, tahap demineralisasi ini dilanjutkan dengan tahap deproteinasi. Mula-mula hasil pengeringan demineralisasi ditimbang beratnya. Selanjutnya ditambahkan larutan NaOH 3,5% dengan perbandingan berat sampel dan volume NaOH sebesar 1:6. Protein di dalam chitin memiliki ikatan kovalen, sehingga diperlukan larutan NaOH dengan temperatur tinggi untuk memutuskan ikatan kovalen yang ada. Pada tahapan ini, ujung poliamida yang memiliki muatan negatif akan mulai mengalami reaksi dengan NaOH sehingga terbentuk garam amino (Yuliusman, 2010). Setelah penambahan ini, campuran dipanaskan dengan hotplate sambil diaduk hingga didapatkan sampel yang agak kering. Sampel yang telah mengering ini kemudian dicuci dengan air mengalir hingga didapatkan pH residu yang netral. Sama seperti pencucian pada tahap demineralisasi, pencucian ini juga bertujuan untuk menghilangkan sisa NaOH yang ada pada residu (Yuliusman, 2010). Residu kemudian ditimbang dan dilanjutkan dengan pengeringan dengan oven bersuhu 80C selama 24 jam. Hasil yang diperoleh dari tahap ini disebut rendemen chitin II.
4Pada tahap deproteinasi, sampel tepung kulit udang ditambah dengan larutan NaOH 3,5% dengan perbandingan sampel dan NaOH sebesar 1:5. Campuran ini kemudian diaduk sambil dipanaskan dengan suhu 90C kurang lebih selama 1 jam. Hasil pemanasan selanjutnya disaring, residu yang didapatkan dicuci dengan aquades hingga
memiliki pH yang netral. Selanjutnya residu ini dikeringkan di dlaam tanur bersuhu 60C selama 4 jam (Patria, 2013). Deproteinisasi dilakukan dengan pemanasan sampel yang dicampur dengan NaCl 1 M dalam beaker glass bersuhu 100C (Isa et al., 2012). Pada tahap ini, dapat digunakan larutan 3% NaOH (Limam et al., 2011) atau NaOH 1,5 N (Naznin, 2005).
Setelah diperoleh rendemen chitin II, hasil tersebut dapat diproses untuk menghasilkan rendemen chitosan. Rendemen chitosan diperoleh dari hasil deproteinasi yang telah melalui tahap deasetilasi. Pada tahap deasetilasi ini, mula-mula chitin hasil pengeringan kedua ditimbang. Selanjutnya ditambahkan larutan NaOH dengan perbandingan sampel dan volume NaOH sebanyak 1:20. Konsentrasi NaOH yang ditambahkan bervariasi, yakni: 40% untuk kelompok A1-A2, 50% untuk kelompok A3-A4 dan 60% untuk kelompok A5-A6. Pada larutan NaOH 50% diperoleh reaksi hidrolisis amida serta pemecahan ikatan gugus asetil yang berhubungan dengan atom nitrogen yang paling efektif (Yuliusman, 2010). Selanjutnya dilakukan pula pemanasan dengan suhu 90C hingga didapatkan campuran yang cukup kering. Selanjutnya juga dilakukan pencucian dengan air mengalir sampai residu yang didapatkan memiliki pH yang netral. Kemudian residu dikeringkan dengan oven bersuhu 70C selama 24 jam. Hasil pengeringan kemudian ditimbang dan dihitung dengan rumus sehingga diperoleh rendemen chitosan. Pada tahapan ini, kitin yang memiliki gugus asetil akan mengalami reaksi dengan atom nitrogen sehingga terbentuk gugus amina (chitosan) (Yuliusman, 2010).
5Pada tahap deasetilasi chitin, dihasilkan chitosan. Chitin direaksikan dengan NaOH 50% dan dipanaskan dengan menggunakan hot plate. Seletah itu dilakukan penyaringan untuk memisahkan residu dari filtratnya. Residu kemudian dicuci lagi dengan menggunakan aquades hingga pHnya netral. Setelah itu residu kembali dikeringan dengan tanur bersuhu 60C selama 4 jam. Derajat deasetilasi merupakan parameter paling krusial yang digunakan untuk menentukan kualitas chitosan. Derajat deasetilasi ini menunjukkan persentase gugus asetil yang dapat dihilangkan dari chitin untuk memproduksi chitosan. Derajat deasetilasi yang besar menunjukkan sedikit gugus asetil yang terdapat pada chitosan. Hal tersebut mengindikasikan kuatnya ikatan ionik dan ikatan hidrogen pada chitosan. Derajat deasetilasi ini tergantung pada bahan baku
pembuatan dan kondisi pada proses pembuatan. Sebagai contohnya ialah konsentrasi larutan basa, suhu dan waktu (Patria, 2013).
Rumus yang digunakan:
Dari percobaan yang dilakukan saat praktikum, ditemukan hasil yang bervariasi. Untuk rendemen chitin I, yield terbesar didapatkan dengan konsentrasi HCl sebesar 0,75 N, lalu diikuti 1,25 N. Pada penggunakan larutan HCl dengan konsentrasi 1 N diperoleh yield paling sedikit. Hal tersebut dikarenakan setiap bahan memiliki konsentrasi yang akan lebih efektif jika dibandingkan dengan konsentrasi yang lain (Isa et al., 2012). Untuk rendemen chitin II, yield terbesar didapatkan oleh kelompok A4 (90%). Hal ini dapat disebabkan karena pencucian yang salah. Jika air yang digunakan mengalir dengan terlalu deras dan kain saring yang digunakan tidak digenggam dengan benar, maka akan terdapat banyak massa residu yang tumpah keluar dari kain saring bersama dengan air. Untuk rendemen chitosan, diperlukan konsentrasi NaOH 50% untuk hasil paling efektif (Yuliusman, 2010). Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya yield yang diperoleh oleh kelompok A4 (45,455%) yang menggunakan larutan NaOH dengan konsentrasi 50%.
6Total chitin dalam kulit krustasea berkisar antara 0,44-8,15%. Udang memiliki kandungan kitin tertinggi jika dibandingkan dengan sampel krustasea yang lain. Hal tersebut dipengaruhi oleh sumber bahan yang digunakan serta metode ekstraksi yang digunakan (Isa et al., 2012). Rendemen chitosan yang diperoleh berkurang seiring dengan meningkatnya termperatur pemanasan. Hal tersebut disebabkan karena rantai molekul chitosan mengalami depolimerisasi yang mengakibatkan penurunan berat molekul. Kualitas chitosan diukur pula dengan kelarutannya. Chitosan yang semakin mudah larut akan memiliki kualitas yang semakin baik. Berat molekul merupakan salah
satu parameter yang dapat digunakan untuk pengukuran standar kualitas chitosan. Chitosan dengan berat molekul yang rendah biasa digunakan sebagai senyawa anti-bakteri, antioksidan dan anti-tumor, sedangkan chitosan dengan berat molekul yang lebih besar digunakan sebagai senyawa anti-kolesterol (Patria, 2013).
Chitin dan turunannya memiliki banyak aplikasi, contohnya: di bidang medis, pangan, pertanian, industri tekstil dan industri kertas. Pada bidang pangan, chitin dapat digunakan sebagai emulsifying agent, biokatalis dan juga dalam proses pengelolaan limbah cair (Isa et al., 2012). Chitosan memiliki karakteristik yang baik sebagai biomaterial karena sifatnya yang dapat didegradasi serta tidak beracun (Radhakumary et al., 2005). Penggunaan chitin dan chitosan dalam berbagai bidang membutuhkan karakteristik mutu. Karakteristik tersebut meliputi derajat deasetilasi, kelarutan, viskositas dan berat molekul (Patria, 2013).
Dalam industri pangan, chitosan dapat digunakan sebagai emulsifier, koagulan, chelating agent dan thickening agent. Selain itu, chitosan juga dapat digunakan sebagai pengawet yang aman untuk dikonsumsi (Patria, 2013). Aktivitas chitin dapat digunakan untuk menghambat peroksidasi lemak pada sistem emulsi asam linoleat. Nitrogen pada rantai karbon C kedua chitosan dapat digunakan untuk menghilangkan radikal bebas (Limam et al., 2011). Dalam larutan asam, kelompok amina bebas cocok digunakan sebagai chelating agent yang mengikat logam maupun dispersi. Karena struktur polimernya yang lurus, chitosan memiliki peran yang besar dalam proses flokulasi, pembentukan lapisan tipis atau imobilisasi enzim. Gugus amina bebas yang dimiliki oleh chitosan dapat terprotonasi dalam keadaan asam dan membentuk gugus amino kation (NH3+) yang dapat bereaksi dengan polimer anion yang lain untuk membentuk elektrolit kompleks (Patria, 2013).
7Karakteristik antibakteri dan/atau antijamur alami yang dimiliki oleh chitosan dan turunannya dapat digunakan sebagai senyawa disinfektan. Baik chitin maupun chitosan berperan dalam pengaktifan pertahanan sel dan mencegah terjadinya invasi oleh mikroba patogen. Secara umum, chitosan memiliki aktivitas antijamur yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan chitin. Namun di samping itu, chitosan tidak efektif jika
digunakan untuk melawan jamur yang berdinding sel chitin. Karakteristik antibakteri dan/atau antijamur pada chitosan dan turunannya dapat dimanfaatkan sebagai senyawa disinfektan komersial. Chitosan memiliki aktivitas mikrobiologis terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Chitin yang diekstrak dari P.longirostris merupakan antibakteri Escherichia coli. Aktivitas antibakeri chitosan dipengaruhi oleh berat molekul, derajat deasetilasi, konsentrasi larutan serta pH media yang digunakan. Interaksi molekul chitosan yang bermuatan positif dan membran sel mikroba yang bermuatan negatif memicu terjadinya leakage dari protein dan komponen intrasel lainnya. Chitosan berperan pada permukaan luar bakteri. Pada konsentrasi yang lebih rendah (< 0,2 mg/ml), chitosan polikation dapat mengikat permukaan bakteri yang bermuatan negatif dan mengakibatkan aglutinasi. Pada konsentrasi yang lebih tinggi, muatan positif yang lebih besar memciptakan jaring yang menahan bakteri tetap dalam bentuk suspensi. Chitin dan chitosan yang diekstrak dari krustasea menunjukkan aktivitas antijamur terhadap jamur yang bersifat patogen. Chitin memiliki efek yang siknifikan terhadap spesies Candida dengan menginterverensi proses germinasinya (Limam et al., 2011).8
3. KESIMPULAN
Chitin dan chitosan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Chitin dan chitosan dapat diekstrak dari kulit krustasea. Limbah padat kulit udang mengandung chitin dan chitosan. Tahap pembuatan chitin dan chitosan meliputi demineralisasi, deproteinasi dan deasetilasi. Pada tahap demineralisasi, dilakukan penghilangan mineral dengan penambahan HCl 0,75 N sebagai konsentrasi paling optimal untuk menperoleh rendemen chitin I terbesar. Pada tahap deproteinasi, dilakukan pemecahan ikatan protein dengan penambahan NaOH 3,5% sebagai konsentrasi paling optimal untuk menperoleh rendemen chitin II terbesar. Pada tahap deasetilasi, terjadi pembentukan gugus amina dengan penambahan NaOH 50% sebagai konsentrasi paling optimal untuk menperoleh rendemen chitosan terbesar.
Semarang, 25 September 2014Asisten Dosen:- Stella GunawanElizabeth Caroline Setiawan12.70.0006
94. DAFTAR PUSTAKA
Anief, Moh. (2004).Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktek. UGM Press. Yogyakarta.
Isa et al. (2012). Extraction and Characterization of Chitin from Nigerian Sources. Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies, 21 (1): 73-81.
Limam et al. (2011). Extraction and Characherization of Chitin and Chitosan from Crustacean By-products: Biological and Physicochemical Properties. African Journal of Biotechnology, 10 (4): 640-647.
Martati et al. (2002). Optimasi Proses Demineralisasi Cangkang Rajungan (Portunus pelagicus) Kajian Suhu dan Waktu Demineralisasi. J. Tek. Pert., 3 (2): 128-136.
Naznin, Rokshana. (2005). Extraction of Chitin and Chitosan from Shrimp (Metapenaeus monoceros) Shell by Chemical Method. Pakistan Journal of Biological Sciences, 8 (7): 1051-1054.
Patria, Anshar. (2013). Production and Characterization of Chitosan From Shrimp Shells Waste. Aquaculture, Aquarium, Conservation and Legislation: International Journal of the Bioflux Society, 6 (4): 339-344.
Radhakumary et al. (2005). Biopolymer Composite of Chitosan and Methyl Methacrylate for Medical Applications. Trends Biomater. Artif. Organs, 18 (2): 117-124.
Yuliusman. (2010). Pemanfaatan Kitosan dari Cangkang Rajungan pada Proses Adsorpsi Logam Nikel dari Larutan NiSO4. Seminar Rekayasa Kimia dan Proses, C-27: 1-7.
105. LAMPIRAN
5.1. PerhitunganRumus:
Kelompok A1
Kelompok A2
Kelompok A3
11Kelompok A4
Kelompok A5
Kelompok A6
5.2. Diagram Alir
5.3. Laporan Sementara