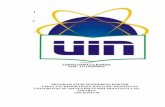PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK DAUN BINAHONG (Anredera...
Transcript of PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK DAUN BINAHONG (Anredera...

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK DAUN
BINAHONG (Anredera cordifolia (Tenore) Steenis)
TERHADAP REEPITALISASI KULIT PASCA LUKA
BAKAR DERAJAT II TIKUS Sprague dawley
Laporan Penelitian ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar SARJANA KEDOKTERAN
OLEH :
RAISSA PRAMUDYA WARDHANI
NIM : 1113103000067
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1438 H/ 2016 M

i
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Laporan penelitian ini merupakan hasil karya asli yang saya ajukan untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana kedokteran di UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya, maka
saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Ciputat, Oktober 2016
Raissa Pramudya Wardhani

ii
PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK DAUN
BINAHONG (Anredera cordifolia (Tenore) Steenis)
TERHADAP REEPITALISASI KULIT PASCA LUKA
BAKAR DERAJAT II TIKUS Sprague dawley
LEMBAR PERSETUJUAN
Laporan Penelitian
Diajukan kepada Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter, Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Kedokteran (S.Ked)
Oleh
Raissa Pramudya Wardhani
NIM: 1113103000067
Pembimbing I Pembimbing II
Rr. Ayu Fitri Hapsari, M. Biomed. dr. Dyah Ayu Woro, M. Biomed
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1438 H / 2016 M

iii
LEMBAR PENGESAHAN Laporan penelitian berjudul Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steenis) terhadap Reepitalisasi Kulit Pasca Luka Bakar Derajat II Tikus Sprague dawley yang diajukan oleh Raissa Pramudya Wardhani (NIM: 1113103000067), telah diujikan dalam sidang di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada Rabu, 12 Oktober 2016. Laporan penelitian ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) pada Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter.
Ciputat, 12 Oktober 2016
DEWAN PENGUJI
Ketua Sidang
Rr. Ayu Fitri Hapsari, M. Biomed
Pembimbing 1
Rr. Ayu Fitri Hapsari, M. Biomed
Pembimbing 2
dr. Dyah Ayu Woro, M. Biomed
Penguji 1
dr. Lucky Brilliantina, M.Biomed
Penguji 2
dr. Rahmatina, Sp.KK
PIMPINAN FAKULTAS
Dekan FKIK UIN SH Jakarta
Prof. Dr. H. Arief Sumantri, M.Kes
Kaprodi PSKPD FKIK UIN SH Jakarta
dr. Achmad Zaki, M.Epid, Sp. OT

iv
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warohmatullah Wabarokatuh,
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wata’ala. Sholawat
beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad
sholallahu’alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya dan orang-orang
yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari yang telah dijanjikan kelak, yaitu
hari kiamat.
Penulis bersyukur kepada Allah subhanahu wata’ala yang dengan
RahmatNya lah penelitian dan tulisan ini dapat diselesaikan sesuai dengan
harapan penulis. Rasa terimakasih tak lupa penulis sampaikan kepada seluruh
pihak yang telah membantu dan memberi dukungan materi maupun dukungan
moril sehingga penulisan Laporan Penelitian yang berjudul “Pengaruh
Pemberian Ekstrak Daun Binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steenis)
terhadap Reepitalisasi Kulit Pasca Luka Bakar Derajat II Tikus Sprague
dawley” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat
terselesaikan.
Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1) Prof. Dr. H. Arief Sumantri, M.Kes, selaku dekan FKIK UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2) dr. Achmad Zaki, Sp. OT, M.Epid, selaku ketua program studi
kedokteran dan profesi dokter
3) Rr. Ayu Fitri Hapsari, M.Biomed dan dr. Dyah Ayu Woro, M.Biomed
selaku dosen pembimbing, yang telah rela meluangkan banyak waktunya
untuk keberhasilan penulis, yang tak bosan-bosannya memotivasi penulis.
Terimakasih atas kebaikan pembimbing kami, sehingga penulis bisa
menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik. Semoga Allah
Membalas kebaikan guru-guru kami dengan kebaikan yang berlipat ganda.
Aamiin.

v
4) dr. Lucky Brilliantina, M.Biomed dan dr. Rahmatina, Sp.KK selaku
penguji laporan penelitian yang telah meluangkan waktunya untuk
menguji laporan penelitian penulis dan memberikan arahan yang baik
dalam pengujian kelayakan laporan penelitian yang penulis buat.
5) Kepada dr. Flori Ratna Sari, PhD sebagai Pembimbing Akademik terbaik,
yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mendengar keluh kesah
penulis. Semoga Allah Membalas kebaikannya dengan kebaikan yang
lebih baik.
6) Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orangtua
penulis, Ayahanda Ir. Wisnu Wardhana dan Ibunda Yulie Hartiningtyas,
S.Ip. yang telah memberikan dukungan yang tak terhingga jumlahnya,
hingga penulis dapat menjadi insan yang bermanfaat bagi bangsa dan
negara. Semoga Allah subhanahu wata’ala Membalas seluruh kebaikan
ayah dan ibu dengan surga tertinggiNya. Aamiin.
7) Kepada suami tercinta Muhammad Rizki Forest, ST. yang telah
memberikan banyak pelajaran hidup yang memotivasi penulis untuk terus
berusaha, sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini.
8) Kepada Pemerintah Propinsi Riau yang telah memberikan beasiswa
pendidikan selama penulis menempuh pendidikan sarjana hingga penulis
dapat mencapai gelar Sarjana Kedokteran.
9) Teman-teman seperjuangan Riski Bastanta, Wildana Aqila, Fadli
Fajriansyah, Alfi Alfina, Zahrotu Romadhon, Muhammad Riski Dwi
Saputra dan tak lupa kepada saudara penulis, Tanjung Bismantara.
Terima kasih atas bantuan, kerjasama dan pengorbanan yang telah kalian
lakukan. Banyak cerita suka dan duka yang kita lalui bersama selama
proses ini. Pada akhirnya atas izin Allah, penulis dapat menyelesaikan
penulisan laporan penelitian ini. Semoga Allah subhanahu wata’ala
Membalas Kebaikan kalian.
10) Staf LIPI, BALITRO, iRATco, Laboratorium Patologi Anatomi Cito
Depok, Laboratorium Parasitologi FKIK UIN Jakarta, serta Laboratorium
Histologi FKIK UIN, yang telah membantu dalam proses penelitian.
11) Teman-teman PSKPD UIN angkatan 2013.

vi
Harapan penulis, semoga penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik,
dan dapat menjadi amal jariyah bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa banyak
kekurangan dan kekhilafan yang penulis lakukan. Oleh karena itu penulis
berharap atas kritik dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat menjadi
lebih baik lagi untuk kedepannya.
Wassalamu’alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.
Ciputat, Oktober 2016
Penulis

vii
ABSTRAK
Raissa Pramudya Wardhani. Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steenis) terhadap Reepitalisasi Kulit Pasca Luka Bakar Derajat II Tikus Sprague dawley. 2016
Pendahuluan: Kejadian luka bakar merupakan permasalahan yang tidak dapat diabaikan. Luka bakar menempati urutan ke-10 yang menjadi penyebab luka tersering di Indonesia. Sepuluh persen penyebab kematian disebabkan oleh luka bakar. Binahong dikenal memiliki khasiat dalam menyembuhkan penyakit ringan dan berat, termasuk penyembuhan luka. Adanya zat aktif yang terkandung dalam Binahong, seperti saponin, flavonoid, asam oleanolic, berperan dalam berbagai proses tersebut. Sehingga pada penelitian ini akan dilakukan pengkajian mengenai pengaruh pemberian ekstrak daun binahong terhadap pertumbuhan lapisan re-epitelisasi pasca luka bakar derajat II. Metode: Pengkajian dilakukan secara eksperimental, tikus dibagi menjadi 5 grup berdasarkan perlakuan yang akan diterapkan, yaitu perlakuan salep, oral, kombinasi perlakuan oral dan perlakuan salep, kontrol positif serta kontrol negatif. Setelah diberikan perlakuan selama 5 hari, kulit tikus diambil dan diolah menjadi preparat dengan pewarnaan HE dan dilihati hasilnya di bawah mikroskop dengan perbesaran 40x10. Hasil: Didapatkan hasil pengukuran rerata re-epitelisasi pada tiap perlakuan adalah P1 43.44 μm, P2 28.46 μm, P3 31.07 μm, K+ 34.51 μm, K- 41.13 μm, dengan p>0.05 pada tiap grup. Kesimpulan: Pemberian salep ekstrak daun binahong pada luka bakar derajat II tikus Sprague dawley menunjukkan hasil rerata re-epitelisasi lebih baik dibanding kelompok perlakuan lainnya, namun perbedaan antar kelompok tidak signifikan.
Kata kunci : Ekstrak daun binahong, salep daun binahong, suspensi daun
binahong, luka bakar derajat II, tikus Sprague dawley, Anredera cordifolia
(Tenore) Steenis, reepitelisasi

viii
ABSTRACT
Raissa Pramudya Wardhani. Medical Education Departement, Faculty of
Medicine and Health Sciences, Syarif Hidayatullah State Islamic University of
Jakarta. The effect of giving the Binahong (Anredera cordifolia (Tenore)
Steenis) leaf Extract Against Re-epitelization in Skin with Second Degrees Burn
Wound on Sprague dawley Rats. 2016
Introduction: Burn wounds is a problem that cannot be ignored. Burn wounds occupies the tenth of the most common cause injuries in Indonesia. Ten percent causes of death caused by burns. Binahong known to have efficacy in healing mild and severe disease, including wound healing. The existence of the active substances contained in Binahong, like saponin, flavonoid, oleanolic acid, role in those process. So this research will analyze the effect of giving the binahong leaf extract, against re-epitelization in Sprague dawley’s skin with second degrees burn wound. Methods: Study done experimentally, rats were divided into 5 groups based on the treatments that will be applied, those are topical treatment, oral treatment and combantion of topical and oral treatment, also there are positive control and negative control. After five days treatment, the rat’s skin is taken to make preparations with HE staining, than the preparation will be analyzed under the microscope with 40x10 zoom. The result: We obtain the average of re-epithelization on each treatments are P1 43.44 μm, P2 28.46 μm, P3 31.07 μm, K+ 34.51 μm, K- 41.13 μm, with p>0.05 on each group. Conclusion: Apply binahong leaf extract on Sprague dawley with second degree burn wounds, shows better results in the average of re-epithelization than the other treatment groups, but the difference between groups is not significant.
Key Words : Binahong leaf extract,binahong ointment, binahong suspension,
second degrees burn wound, Sprague dawley rat, Anredera cordifolia (Tenore)
Steenis, re-epithelization

ix
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN ..................................................................................... i
LEMBAR PERSETUJUAN.................................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................... iii
KATA PENGANTAR ........................................................................................... iv
ABSTRAK ............................................................................................................ vii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiii
DAFTAR BAGAN .............................................................................................. xiv
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xv
BAB 1 ..................................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1
1.2 Rumusan masalah ..................................................................................... 3
1.3 Hipotesis ................................................................................................... 3
1.4 Tujuan Penelitian ...................................................................................... 3
1.4.1 Tujuan Umum : ................................................................................. 3
1.4.2 Tujuan Khusus : ................................................................................ 3
1.5 Manfaat Penelitian .................................................................................... 4
1.5.1 Bagi peneliti ...................................................................................... 4
1.5.2 Bagi Institusi ..................................................................................... 4
1.5.3 Bagi Keilmuan .................................................................................. 4
1.5.4 Bagi Masyarakat................................................................................ 4
BAB 2 ..................................................................................................................... 5
2.1 Landasan Teori ......................................................................................... 5
2.1.1 Binahong ........................................................................................... 5
2.1.2 Kulit .................................................................................................. 9
2.1.3 Lapisan dan komponen penyusun kulit ........................................... 10
2.1.4 Pertahanan kulit ............................................................................... 14
2.1.5 Luka Bakar ...................................................................................... 15
2.1.6 Epidemiologi Luka Bakar ............................................................... 15
2.1.7 Patofisiologi luka bakar................................................................... 16
2.1.8 Derajat Luka Bakar ......................................................................... 18
2.1.9 Penanganan Luka Bakar .................................................................. 22
2.1.10 Perawatan pada Luka Bakar ............................................................ 22
2.1.11 Penyembuhan Luka Bakar .............................................................. 23

x
2.1.12 Krim Silver Sulfadiazin (AgSD) ..................................................... 27
2.1.13 Sediaan Topikal Salep Ekstrak Daun Binahong ............................. 28
2.1.14 Rute Penyerapan Obat Topikal ....................................................... 30
2.1.15 Sediaan Oral Larutan atau Solutions Daun Binahong..................... 31
2.1.16 Tikus Sprague Dawley .................................................................... 32
2.2 Kerangka Teori ....................................................................................... 33
2.3 Kerangka Konsep ................................................................................... 34
2.4 Identifikasi Variabel ............................................................................... 34
2.5 Definisi Operasional ............................................................................... 34
BAB 3 ................................................................................................................... 37
3.1 Desain Penelitian .................................................................................... 37
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian ................................................................ 37
3.3 Bahan Uji ................................................................................................ 37
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian ............................................................. 38
3.5 Besar Sampel .......................................................................................... 38
3.6 Kriteria Inklusi ....................................................................................... 39
3.7 Kriteria Eksklusi ..................................................................................... 39
3.8 Alat dan Bahan Penelitian ...................................................................... 39
3.9 Alur Kerja Penelitian .............................................................................. 41
3.10 Adaptasi dan Pemeliharaan Hewan Sampel ........................................... 42
3.11 Cara Kerja Penelitian .............................................................................. 42
3.11.1 Pembuatan Ekstrak Daun Binahong untuk Bahan Salep ................ 42
3.11.2 Pembuatan Suspensi Ekstrak Daun Binahong ................................ 44
3.11.3 Pembuatan Luka Bakar pada Tikus ............................................... 46
3.11.4 Cara Pemberian Salep dan Suspensi Ekstrak Daun Binahong ........ 47
3.11.5 Pengambilan Jaringan dan Pembuatan Sediaan Histopatologi ....... 47
3.11.6 Pengamatan Histopatologi .............................................................. 49
3.12 Manajemen Analisis Data Pembentukan Jaringan Epitel ....................... 50
3.13 Etika Penelitian ....................................................................................... 50
BAB 4 ................................................................................................................... 52
4.1 Hasil ........................................................................................................ 52
4.2 Pembahasan ............................................................................................ 55
Keterbatasan Penelitian ..................................................................................... 58

xi
BAB 5 ................................................................................................................... 59
5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 59
5.2 Saran ....................................................................................................... 59
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 60
LAMPIRAN .......................................................................................................... 66

xii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Definisi Operasional .............................................................................. 34
Tabel 4.1 Data Rerata Ketebalan Re-epitelisasi ..................................................... 54
Tabel 4.2 Hasil Analisis Data dengan metode One Way Anova ............................ 55

xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Daun Binahong ..................................................................................... 6
Gambar 2.2 Daun Binahong ..................................................................................... 7
Gambar 2.3 Lima Lapisan Epidermis pada Kulit Tebal ........................................ 11
Gambar 2.4 Tiga Zona Respon Lokal Tubuh terhadap Luka Bakar ...................... 17
Gambar 2.5 Persentase tiap Bagian Tubuh pada Anak dan Dewasa Rule of Nine. 19
Gambar 2.6 Diagram Lund dan Browder untuk mengukur luas permukaan tubuh
atau TBSA ........................................................................................... 20
Gambar 2.7 Derajat Luka Bakar Berdasarkan Kedalamannya .............................. 21
Gambar 2.8 Tahap Penyembuhan Luka ................................................................. 24
Gambar 2.9 Tahap yang Dilalui Sediaan Topikal (Transdermal Patch) ............... 30
Gambar 3.1 Hasil Tes Homogenitas Salep Ekstrak Daun Binahong ..................... 44
Gambar 3.2 Keadaan Kulit Tikus Menjadi Kemerahan sesaat Setelah Dilakukan
Intervensi Plat Besi.............................................................................. 46
Gambar 4.1 Sediaan Luka Bakar Deajat II Perbesaran 10x ................................... 52
Gambar 4.2 Gambar mikroskopik P1, P2, P3, K+, K- perbesaran 40x ................ 53
Gambar 4.3 Grafik Rerata Ketebalan Re-epitelisasi P1, P2, P3, K+, K-
perbesaran 40x..................................................................................... 54

xiv
DAFTAR BAGAN
Bagan 2.1 Kerangka Teori ..................................................................................... 33
Bagan 2.2 Kerangka Konsep .................................................................................. 34
Bagan 3.1 Alur Penelitian ...................................................................................... 41

xv
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Surat Keterangan Hasil Determinasi/Identifikasi Bahan Uji ........ 66
LAMPIRAN 2 Suat Keterangan Ekstraksi Bahan Uji ........................................... 67
LAMPIRAN 3 Surat Profile Bahan Uji ................................................................. 68
LAMPIRAN 4 Dokumentasi Penelitian ................................................................ 69
LAMPIRAN 5 Riwayat Penulis ............................................................................. 72

1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Luka bakar menempati urutan ke-10 dari beberapa jenis luka tersering
yang ditemukan di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa luka bakar bukan
merupakan kejadian langka yang terjadi di negeri ini. Luka bakar yang sering
terjadi berdasarkan data dari Unit Luka Bakar RSCM pada bulan Januari
2011-Desember 2012 adalah disebabkan oleh kecelakaan kerja seperti
tersiram air panas dan juga disebabkan oleh suatu zat kimia yang bersifat
korosif .1
Secara detail, berdasarkan data yang dihimpun oleh Riskesdas 2013, 78%
peristiwa yang menyebabkan terjadinya kebanyakan luka bakar di Indonesia
adalah disebabkan oleh terpapar api secara langsung dan hal ini menjadi
penyumbang utama tingginya angka mortalitas pada korban luka bakar.
Urutan kedua terbanyak kejadian luka bakar adalah disebabkan oleh listrik
(14%) dan selanjutnya disebabkan oleh air panas (4%), bahan kimia (3%) dan
metal (1%). Kebanyakan luka bakar terjadi pada kelompok usia 1-4 tahun, dan
insidensi tertinggi terjadi di Papua (2%) dan terendah berada di Kalimantan
Timur.2
Kepercayaan turun temurun akan khasiat daun binahong dalam mengobati
luka merupakan contoh paradigma pengobatan herbal yang masih melekat
dalam kepercayaan masyarakat di Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam
penelitian Yuzda, 2014 mengenai perilaku masyarakat di Gorontalo dalam
mengobati luka menggunakan daun binahong.3 Dalam mengobati luka,
biasanya daun binahong ditumbuk lalu ditempelkan pada tempat yang terluka
atau dapat juga dilakukan dengan membasuh luka tersebut dengan air rebusan
daun binahong.4
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Muhlisah, memang obat-obatan
tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan memiliki efek samping yang
lebih minim dibanding dengan obat-obatan kimia yang kita kenal sekarang.5
Selain itu, obat-obatan herbal juga dikenal relatif lebih murah, akan tetapi

2
risiko dari pengolahan obat-obatan yang masih bersifat tradisionil dan tidak
menerapkan prinsip higienitas, dapat menimbulkan permasalahan baru berupa
infeksi.
Daun binahong diketahui bukan merupakan tanaman endemis Indonesia.
Penyebarannya meliputi Afrika, Eropa, Asutralia, Asia dan sebagian daerah di
Amerika. Binahong telah dipercaya akan manfaatnya sejak dahulu, terbukti
pada zaman perang Vietnam melawan Amerika, para tentara Vietnam
diwajibkan untuk mengonsumsi Binahong, karena mereka mempercayai
adanya manfaat di dalamnya6 dan penelitian di era modern telah
membenarkan adanya manfaat tersebut.
Binahong atau dalam bahasa latin disebut Anredera cordifolia (Tenore)
Steenis diketahui mempunyai khasiat dalam penyembuhan penyakit ringan
dan berat, termasuk khasiatnya dalam menyembuhkan luka. Kandungan zat
aktif berupa flavonoid, asam oleanolik, protein, saponin, dan asam askorbat
membantu proses hidroksilasi untuk pembetukan kolagen, sehingga dapat
mempercepat proses penyembuhan luka.7,8
Adanya zat-zat aktif yang terkandung dalam Binahong terutama berfungsi
dalam proses penyembuhan luka, membuat peneliti tertarik untuk meneliti
lebih lanjut mengenai khasiat tumbuhan ini. Oleh karena belum banyaknya
penelitian mengenai efek pemberian ekstrak daun binahong secara topikal
maupun oral dalam mengobati luka bakar,9 maka penelitian ini akan
difokuskan pada hal tersebut.
Luka bakar derajat II pada tikus Sprague dawley, akan diteliti ketebalan
reepiteliasasi kulitnya pasca pemberian perlakuan yang telah disebutkan
sebelumnya. Binahong yang dibuat dalam bentuk ekstrak, kemudian akan
diberikan dalam bentuk salep dan sediaan oral. Adanya kandungan minyak
dalam sediaan salep, serta sifatnya yang tidak mudah menguap, membuat
sediaan cenderung akan sukar untuk dieliminasi oleh air dan udara, dan akan
lebih tahan lama berada di atas kulit.10 Dengan demikan, diharapkan efek
terapetik yang terdapat dalam binahong dapat tercapai dengan lebih efektif.
Selain salep, peneliti akan mencoba untuk mengetahui efek daun binahong
terhadap penyembuhan luka bakar apabila ekstrak diberikan secara sistemik

3
melalui oral. Pada dua penelitian yang dilakukan terpisah oleh Elin (2011) dan
Sukandar (2011) mengenai efek daun binahong yang diberikan secara oral
terhadap tikus yang diinduksi diabetes mellitus dan gagal ginjal, menunjukkan
adanya efek penyembuhan yang signifikan pada kelompok tikus yang
diintervensi dengan ekstrak binahong oral dibanding dengan kelompok
kontrol.11,12 Oleh karena itu peneliti berharap, pemberian binahong secara oral
juga dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka bakar.
1.2 Rumusan masalah
Apakah pemberian ekstrak daun binahong berpengaruh terhadap
reepitalisasi kulit pasca luka bakar derajat II tikus Sprague dawley?
1.3 Hipotesis
Ekstrak daun binahong berpengaruh terhadap reepitelisasi kulit pasca luka
bakar bakar derajat II tikus Sprague dawley
1.4 Tujuan Penelitian
1.4.1 Tujuan Umum :
Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun binahong
terhadap reepitalisasi kulit pasca luka bakar derajat II tikus Sprague
dawley.
1.4.2 Tujuan Khusus :
1. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun binahong
melalui oral-salep dalam proses reepitalisasi kulit pasca luka
bakar derajat II tikus Sprague dawley
2. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun binahong
melalui oral dalam proses reepitalisasi kulit pasca luka bakar
derajat II tikus Sprague dawley
3. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun binahong
melalui salep dalam proses reepitalisasi kulit pasca luka bakar
derajat II tikus Sprague dawley

4
4. Untuk mengetahui cara pemberian binahong yang paling
efektif dalam proses reepitalisasi kulit pasca luka bakar derajat
II tikus Sprague dawley
1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Bagi peneliti
Menambah pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan luka bakar dan proses penyembuhannya
Peneliti dapat mengamati secara langsung proses penyembuhan
luka bakar baik secara mikroskopik maupun makroskopik
Menambah pengalaman penulis dalam bidang riset dan pembuatan
karya ilmiah
1.5.2 Bagi Institusi
Memperbanyak penelitian dan publikasi dalam bidang kedokteran
di bawah institusi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Meningkatkan rating universitas dalam bidang publikasi dan riset.
1.5.3 Bagi Keilmuan
Sebagai referensi atau data awal bagi peneliti selanjutnya yang
akan mengembangakan penelitian dalam bidang yang sama atau
bidang lainnya.
Menambah pengetahuan mengenai efek ekstrak daun binahong
terhadap penyembuhan luka bakar derajat II
1.5.4 Bagi Masyarakat
Menambah pengetahuan masyarakat mengenai efek dari
penggunaan binahong dalam bentuk salep dan sediaan minum
terhadap proses penyembuhan luka bakar derajat II
Memberikan alternatif pengobatan untuk luka bakar

5
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Binahong
Morfologi dan Klasifikasi Tanaman
Tanaman binahong menurut Suseno, 2013 merupakan tumbuhan yang
berasal dari daratan Tiongkok, dikenal dengan nama asli dheng san chi.13 Ada
pula pendapat lain yang menyatakan bahwa binahong berasal dari daerah Brazil
dan dikenal dengan sebutan Madeira vine atau Mignonette vine.14
Tumbuhan ini
termasuk jenis tumbuhan menjalar yang dapat mencapai panjang 6 meter bahkan
bila keadaan tanah lembab dan subur, binahong dapat tumbuh hingga mencapai 40
meter.6,15 Rata-rata tanaman binahong memiliki umur panjang. Daun binahong
termasuk dalam jenis daun tunggal, memiliki bentuk yang khas seperti gambaran
jantung dengan panjang sekitar 5-10 cm dan lebar 3-7 cm, serta permukaan daun
yang licin. Daun binahong tidak beracun, dan dapat dimakan.15 Tanaman
binahong dapat tumbuh baik di daerah dengan kadar cahaya yang banyak,
sehingga tanaman binahong tumbuh subur di daerah tropis yang dikenal memiliki
intensitas penyinaran cahaya matahari yang cukup.6
Di daerah tropis, tanaman ini umumnya dimanfaatkan sebagai tanaman
rambat hias, dan sudah menjadi bahan yang dikonsumsi selama ribuan tahun oleh
masyarakat di Negara Cina, Korea dan Taiwan. Namun tanaman ini masih kurang
familiar penggunaannya di Indonesia, sedangkan di Vietnam, tanaman binahong
sudah menjadi tanaman yang dibutuhkan untuk bahan sayur-sayuran mereka.14

6
Gambar 2.1 Daun Binahong
Sumber Badan POM RI. Taksonomi Koleksi Tanaman Obat Kebun Tanaman Obat Citeureup Jakarta Pusat: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;
2008
Klasifikasi tanaman binahong16 adalah sebagai berikut :
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Super divisi : Spermatophyta
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Sub Kelas : Hamamelidae
Ordo : Caryophyllales
Famili : Basellaceae
Genus : Anredera
Spesies : Anredera cordifolia

7
Manfaat dan Kandungan Daun Binahong
Daun binahong yang paling sering dimanfaatkan sebagai bahan obat
herbal, memiliki berbagai macam komponen aktif, seperti asam askorbat yang
berguna sebagai properti antioksidan dengan perannya dalam melindungi sel-sel
tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas serta membantu pembentukan kolagen.
Bagian daun juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit menular seksual
karena tingginya kandungan fenol yang dapat melawan bakteri Gram positif dan
Gram negatif. Adapula kandungan asam oleanolik yang berfungsi sebagai properti
antiinflamasi, sehingga dapat mengurangi rasa nyeri pada luka, contohnya pada
luka bakar. Selain itu, terdapat juga Saponin, yang menjadi senyawa aktif yang
paling tinggi kadarnya pada tanaman binahong. Senyawa ini didapatkan sebanyak
28.14±0.22 mg/gr di bagian daun, 3.65±011 mg/gr di bagian batang, 43.15±0.10
mg/gr di bagian umbi dan akar. Hal ini menyatakan bahwa bagian daun binahong,
mengandung banyak senyawa saponin dibanding senyawa lain.14
Gambar 2.2 Daun Binahong
Sumber : Badan POM RI. Taksonomi Koleksi Tanaman Obat Kebun Tanaman Obat Citeureup Jakarta Pusat: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia; 2008
Saponin, diketahui memiliki aktivitas sebagai antitumor, penurun
kolesterol, properti imun yang poten, antikanker, antioksidan, senyawa penurun
risiko penyakit jantung koroner dan juga dapat menstimulasi pembentukan
kolagen tertutama kolagen I, yaitu suatu protein yang berperan dalam proses awal

8
penyembuhan luka. Selain fungsi-fungsi tersebut, saponin juga diketahui memiliki
aktivitas antimikroba (antibakteri dan antivirus). Masih banyak senyawa aktif
lainnya yang terdapat pada daun binahong, sehingga menjadikannya suatu pilihan
tepat yang berperan sebagai bahan pengobatan herbal terutama dalam pengobatan
luka.14
Manfaat dan kandungan dari bagian lain tumbuhan binahong tak hanya
dapat dirasakan pada bagian daunnya saja, namun dapat ditemukan pula pada
bunga, batang, maupun akar, yang masing-masingnya memiliki kandungan
senyawa fitokimia, yaitu senyawa aktif kimia yang terkandung di dalam tanaman.8
Senyawa fitokimia tersebut termasuk fenol, flavonoid, saponin, terpenoid, steroid,
alkaloid dengan saponin adalah senyawa yang paling banyak ditemukan
dibanding senyawa lainnya.14 Flavonoid bertanggung jawab dalam meningkatkan
kecepatan epitelisasi, sebagai zat antiinflamasi, yang menurunkan aktivitas sel
radang pada jejas atau luka sehingga nyeri berkurang, antioksidan yang
menangkal radikal bebas.17 Flavonoid teridentifikasi memiliki 8000 kandungan.
Flavonoid berjenis trimethoxyisoflavone (TMF) terbukti dapat menginduksi
migrasi keratinosit melalui jalur NOX2. Turunan TMF yaitu Dichloro-7-
methoxyisoflavone (DCMF) juga dapat merangsang migrasi keratinosit melalui
aktivasi kaskade sinyal Src/FAK, ERK, AKT dan p38 MAPK. Src berinteraksi
dengan focal adhesion kinase (FAK) untuk membentuk kompleks Src/FAK yang
mengaktivasi jalur sinyal yang dapat meregulasi migrasi dan perlekatan sel.
Dengan kemampuan DCMF yang dapat mengaktivasi berbagai jalur sinyal sel
kertibosit, DCMF mampu memacu penutupan luka dan re-epitelisasi pada tikus
secara in vivo, sehingga penyembuhan luka dapat terjadi lebih cepat.18
Saponin, fenol dan flavonoid masing-masing memiliki fungsinya sebagai
antibiotik. Aktivitasnya dapat setara dengan antibiotik tetrasiklin dan penisilin.19
Senyawa fenol dan flavonoid bekerja dengan menghancurkan sel dinding bakteri,
sedangkan saponin melakukan aktivitasnya di bagian permukaan. Beberapa
senyawa fitokimia yang telah disebutkan sebelumnya secara umum juga memiliki
aktivitas antioksidan.14 Dari senyawa-senyawa inilah binahong dapat menjalankan
fungsinya sebagai tanaman herbal.

9
Diketahui juga bahwa bagian umbi binahong turut dapat dimanfaatkan
sebagai bagian dari pengobatan herbal, dikarenakan adanya kandungan protein
Ancordin. Protein ini berfungsi untuk menstimulasi pembentukan sistem imun dan
nitrit oksida yang dapat membantu melancarkan peredaran darah dan merangsang
produksi hormon pertumuhan. Adanya komponen-komponen tersebut, binahong
terbukti dapat mempercepat proses penyembuhan luka, diantaranya melalui proses
pembentukan kolagen dan aktivitasnya dalam mencegah terjadinya infeksi dengan
menghambat pertumbuhan bakteri.17
Kemampuan binahong yang tidak biasa, maka tidak heran tumbuhan ini
dikenal sebagai tanaman herbal yang berkhasiat untuk membantu mengobati
berbagai penyakit seperti, diabetes, hipertensi, kanker, infeksi, penyakit jantung
koroner, stroke, penyakit ginjal, hepatitis.14
2.1.2 Kulit
Kulit merupakan sawar terluar tubuh yang melindungi tubuh dari berbagai macam
gangguan eksternal yang berasal dari faktor fisika, kimia dan biologi.20 Selain
sebagai sawar, kulit juga menjalani fungsi-fungsi sebagai berikut :
1. Sensorik. Kulit memiliki ujung-ujung saraf yang berperan dalam
melakukan fungsi sensorik. Ujung-ujung saraf tersebut melakukan tugas
sesuai dengan bentuk rangsangan yang diterimanya, seperti Krause dan
Ruffini bertanggung jawab sebagai penghantar sinyal terhadap adanya
tekanan pada daerah dermis, korpuskel Meissner mendeteksi sentuhan
ringan yang berada di telapak kaki, telapak tangan dan ujung jari.
Korpuskel Pacini mendeteksi rangsang tekanan, sentuhan kasar, dan getar,
sedangkan ujung saraf bebas bertanggung jawab menghantarkan sinyal
nyeri, suhu tinggi dan rendah, rasa gatal. Dengan adanya fungsi ini, maka
tubuh dapat mendeteksi kondisi lingkungan sekitarnya dan melakukan
proses homeostasis atau penyesuaian diri.21
2. Termoregulatorik. Kulit menjalankan fungsinya sebagai pengatur suhu
melalui bantuan lapisan adipose yang termasuk dalam komponen insulator
yaitu komponen yang tidak menghantarkan panas, berfungsi menahan
pengeluaran panas dari tubuh, sehingga apabila lingkungan mengalami

10
peristiwa penurunan suhu, tubuh tidak mudah menjadi hipotermi. Adanya
kelenjar keringat serta struktur kulit yang kaya akan mikrovaskular
memudahkannya untuk melakukan pengeluaran panas yang berlebihan,
sehingga tubuh tidak mengalami kerusakan.21
3. Metabolik. Kulit melakukan sintesis Vitamin D3 melalui bantuan sinar
UV yang diperlukan untuk membantu proses metabolisme kalsium. Fungsi
kulit lainnya dalam metabolik yaitu meregulasi kelebihan kadar elektrolit
di dalam tubuh dengan mengeluarkannya melalui keringat. Kadar lemak
yang tersimpan di dalam subkutan juga berperan dalam metabolisme
energi tubuh. 21
4. Kosmetis. Gambaran kulit seperti rambut, kadar pigmen sering menjadi
patokan visual kondisi kesehatan seseorang yang juga menjadi daya tarik
bagi lawan jenis pada semua jenis vertebrae termasuk manusia. 21
Berdasarkan berbagai fungsi ini, membuat kulit menjadi stuktur yang tidak
boleh luput dari perhatian disamping karena strukturnya yang paling terlihat
bila terjadi perubahan.
2.1.3 Lapisan dan komponen penyusun kulit
Secara umum, kulit terbagi menjadi tiga lapisan besar, lapisan dari luar ke dalam
yaitu Epidermis, Dermis dan Hipodermis atau subkutan.
Epidermis adalah lapisan terluar dari kulit yang memiliki fungsi khusus
yaitu sebagai sawar permeabilitas yang menjaga agar tidak terjadi pelepasan
cairan interstitial ke lingkungan dan proteksi terhadap sinar UV. Epidermis
manusia diperbarui tiap 15-30 hari dengan berbagai faktor yang dapat
mempengaruhi cepat atau lambatnya proses tersebut, diantaranya adalah faktor
usia, bagian tubuh, dan lainnya. Lapisan ini merupakan derivat pembentuk kuku,
kelenjar keringat serta kelenjar minyak dapat memiliki ketebalan dari 1.5 mm
hingga 4.0 mm bergantung di bagian tubuh mana lapisan ini berada. Secara
umum epitel tersusun oleh sel epitel pipih berkeratin yang disebut keratinosit
dengan porsi sebesar 80% dari seluruh jumlah sel yang ada di epidermis.
Keratinosit secara progresif berdiferensiasi dari bentuk sel basal yang proliferative,
yang kemudian melekat pada bagian membran basal epidermis dan pada akhirnya

11
mencapai fase akhir diferensiasi dengan menjadikan stratum korneum
terkeratinisisasi.22 Sel lain yang dapat ditemukan di bagian epidermis adalah sel
melanosit, berfungsi sebagai produsen melanin, zat pigmen kulit yang menjadikan
kulit menjadi lebih gelap namun bermanfaat sebagai pelindung dari komponen
berbahaya sinar UV. Selain itu, terdapat juga sel Merkel atau sel taktil epithelial
yang terletak di lapisan basal epitel, berperan sebagai mekanoreseptor yang
memiliki sensitivitas taktil yang tinggi dalam menghantarkan sensasi sentuhan.21
Gambar 2.3 Lima Lapisan Epidermis pada kulit tebal
Sumber : Mescher AL. Histologi Dasar Junqueira Teks & Atlas Jakarta: EGC; 2011
Epidermis terdiri dari 5 lapisan yang diberi nama sesuai dengan posisi dan
komponen struktural dari sel penyusunnya. Lapisan tersebut dari dalam ke luar
adalah :
1. Stratum Basalis
Lapisan ini terletak di atas membran basal, terdiri dari selapis sel yang
berbentuk kubus (kuboid). Stratum basalis ditandai dengan tingginya aktivitas
mitosis, sehingga lapisan ini bertanggung jawab untuk mensuplai sel ke
lapisan-lapisan epidermis berikutnya, karena diketahui sel-sel yang diproduksi
oleh stratum basal ini akan bermigrasi disertai dengan penambahan kandungan
keratin pada sel tersebut. 21
2. Stratum Spinosum

12
Lapisan paling tebal yang terdiri dari sel kuboid yang agak gepeng. Yang
menjadi keistimewaan lapisan ini adalah adanya struktur permukaan sel yang
menyerupai spina (duri). Struktur tersebut terbentuk akibat aktivitas sitoplasma
yang ditarik kedalam juluran sel pendek di sekitar tonofibril. Pada daerah yang
sering mengalami gesekan dan tekanan, seperti pada telapak kaki, lapisan ini
akan menjadi semakin tebal dan tersusun dengan banyak kumpulan berkas
filament (tonofibril) dan desmosom atau taut antar sel di dalamnya. 21
3. Stratum Granulosum
Lapisan yang tersusun atas 3-5 lapis sel yang berbentuk poligonal dan gepeng.
Disebut sebagai lapisan granulosum karena selnya yang mengandung granul
lamela yang diselubungi membran, berisi banyak lamel yang berasal dari
berbagai bahan lipid. Granula lamella akan melakukan eksositosis sehingga isi
sel tersebut keluar memenuhi ruang antar sel pada lapisan granulosum, hal
inilah yang berperan dalam fungsi epidermis sebagai sawar yang mencegah
hilangnya air dari kulit. Dengan adanya proses keratinisasi yang semakin
meningkat disertai dengan terbentuknya lapisan lipid ini, memungkinkan
lapisan granulosum untuk menjalankan fungsinya sebagai sawar terpenting
yang mencegah penetrasi sebagian besar benda asing.21
4. Stratum Lusidum
Lapisan ini hanya dijumpai pada kulit tebal, terdiri dari sel eosinofilik yang
sangat pipih yang tergambar translusen pada mikroskop cahaya. Pada bagian
ini, organel dan inti sel telah hilang. Hampir seluruh bagian dari sitoplasma
terdiri atas filamen keratin padat.21
5. Stratum Korneum
Disusun oleh 15-20 lapis sel gepeng berkeratin tanpa inti dengan sitoplasma
yang dipenuhi oleh filamen keratin. Sel-sel ini secara bertahap akan lepas dari
stratum korneum.21
Dermis merupakan batas antara lapisan epidermis dan dermis adalah taut
dermo-epidermal.22 Dermis sebagian besarnya terdiri dari jaringan ikat yang
berfungsi mengikat jaringan di atasnya yaitu epidermis dengan hipodermis serta
berperan sebagai jaringan penunjang epidermis. Gambaran dermis berupa

13
permukaan yang irregular dan memiliki banyak tonjolan (papilla dermis)
difungsikan sebagai pengikat jaringan yang kuat bersama dengan rete ridge yaitu
penonjolan epidermis yang mengarah ke dermis, sehingga terbentuk taut dermis-
epidermis yang kuat. Pada daerah yang sering mengalami tekanan, papilla dermis
menjadi lebih banyak.21
Dermis tersusun atas dua lapisan yang tidak memiliki batas yang jelas.
Lapisan tersebut dibedakan berdasarkan komponen penyusunnya. Lapisan papilar,
merupakan lapisan tipis yang terdiri atas jaringan ikat longgar dan sel-sel jaringan
ikat seperti fibroblas, sel Mast dan makrofag. Adapula dijumpai leukosit yang
telah mengalami ekstravasasi. Lapisan kedua yang menjadi penyusun dermis
adalah lapisan retikular yang lebih tebal dan tersusun atas jaringan ikat yang padat
dan ireguler. Lapisan ini lebih banyak mengandung serat terutama kolagen tipe I
dibanding sel jaringan ikat. Ditemukan pula serat elastin yang berperan dalam
membentuk elastisitas kulit. 21
Pada lapisan dermis inilah dapat ditemukan derivat epidermis berupa
folikel rambut dan kelenjar. Kelenjar tersebut dibagi menjadi dua kelompok
berdasarkan produk yang dihasilkannya. Kelenjar sebasea atau penghasil minyak,
dapat ditemukan hampir pada seluruh permukaan tubuh, kecuali pada kulit tebal
yang tidak berambut (glabrosa) seperti pada telapak tangan dan telapak kaki.
Kelenjar ini memiliki muara akhir di folikel rambut. Produk yang dihasilkannya
berupa sebum yang merupakan campuran lipid berupa ester malam (wax), skualen,
kolesterol dan trigliserida. Sebum berfungsi untuk mempertahankan stratum
korneum dan rambut, serta memiliki aktivitas antibakteri dan antijamur yang
lemah. Sedangkan kelenjar sudorifera atau penghasil keringat memiliki dua
kelompok lagi yaitu kelenjar keringat ekrin dan apokrin. Kelenjar keringat ekrin
memiliki lumen seketorik yang lebih kecil dibanging kelenjar keringat apokrin.
Adapun fungsinya lebih condong sebagai termoregulator dengan memproduksi
cairan yang menguap pada permukaan tubuh dengan produksi sekret diatur
berdasarkan suhu lingkungan eksternal dan internal tubuh serta peran dari
persarafan kolinergik. Lain halnya dengan kelenjar keringat apokrin yang lebih
banyak mengeluarkan sekret yang kaya akan protein yang memiliki sifat-sifat

14
feromon. Kelenjar ini diatur pengeluarannya oleh hormon-hormon sex dan
dipersarafi oleh serabut adrenergik. 21
Terdapat pula banyak serabut saraf. Saraf efektor berasal dari
pascaganglionik ganglia simpatis dan tidak terdapat persarafan parasimpatis
padanya. 21
Subkutan/ Hipodermis adalah lapisan yang terdiri dari jaringan ikat
longgar yang mengikat kulit secara longgar pada berbagai organ di bawah
hipodermis, sehingga memungkinkan kulit untuk bergeser. Pada lapisan subkutan,
sering ditemukan sel-sel lemak yang bervariasi jumlahnya bergantung pada
daerah tubuh dan status gizi seseorang. Lapisan ini kaya dengan suplai vaskular,
sehingga apabila melakukan penyuntikan obat pada bagian ini, maka obat-obatan
tersebut akan cepat beredar di dalam darah. 21
2.1.4 Pertahanan kulit
Kulit sebagai lapisan pelindung yang letaknya secara langsung terpapar
dengan lingkungan eksternal tubuh, harus memiliki sistem pertahanan yang kuat,
agar komponen berbahaya dan zat-zat patogen tidak berhasil untuk menginvasi
lebih dalam lagi.
Komponen melanosit yang terdapat di bagian basal epidermis berperan
melindungi kulit dari bahaya radiasi ultraviolet yang dapat memicu sel kanker
serta menurunkan jumlah sel Langerhans yang rentan terhadap pajanan sinar
UV.23 Melanosit bekerja dengan memproduksi melanin, akan menggelapkan
warna kulit. Ketika kulit terpajan oleh radiasi UV, keratinosit akan terangsang
untuk menyekresikan berbagai faktor parakrin yang menyebabkan melanosit aktif
menghasilkan melanin. Melanin yang terbentuk akan berformasi bagaikan tudung
supranuklear yang menyerap dan menyebar sinar matahari yang masuk ke dalam
kulit, sehingga DNA inti tidak terpapar langsung oleh UV. Apabila sinar UV
dapat secara langsung mengenai inti DNA, maka hal itu dapat mengubah struktur
nukleotida DNA, sehingga timbul sel yang bermutasi. 21
Kulit memiliki peran sebagai pelindung dari patogen dan zat asing dengan
adanya stuktur kelenjar dan sel imun yang menetap di jaringan seperti sel

15
dendritik. Kelenjar keringat pada umumnya dan kelenjar minyak, menghasilkan
suatu produk yang mengandung bahan sangat toksik bagi bakteri. Sedangkan sel
dendritik bekerja sebagai antigen presenting cell, yang memberikan sinyal awal
kepada sel limfosit bahwa telah terjadi invasi zat berbahaya. Sel dendritik
membantu sel Thelper untuk mengenali antigen asing tersebut, sehingga dapat
segera dieradikasi bila terjadi penyerangan kembali. 23
2.1.5 Luka Bakar
Luka adalah hilangnya kontinuitas jaringan akibat rudapaksa atau dapat
juga merupakan sesuatu yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu.24 Sedangkan
luka bakar merupakan respons kulit dan jaringan subkutan terhadap trauma
suhu/thermal.25
2.1.6 Epidemiologi Luka Bakar
Menurut WHO, jumlah kematian akibat luka bakar yang dimuat dalam
katalog The Global Burden of Disease tahun 2012, sebanyak 267.000 orang
meninggal akibat luka bakar thermal, 30% merupakan pasien yang berumur di
bawah 20 tahun, terutama pada masa-masa balita dengan penyebab terbanyak
adalah akibat siraman dari air mendidih dan uap panas. Permasalahan luka bakar
ini tidak dapat diabaikan, karena merupakan urutan ke-11 dari penyebab kematian
terbanyak pada rentang usia 1-9 tahun dan 10% dari penyebab kematian akibat
kecelakaan disebabkan oleh luka bakar.26
Angka kematian akibat luka bakar pada daerah dengan income per kapita
rendah serta negara dan menengah memiliki tingkat kematian sebelas kali lebih
besar dibanding pada negara dengan income per kapita yang tinggi. Jumlah
kematian terbesar terjadi di negara miskin seperti Afrika dan Asia Tenggara,
jumlah menengah pada negara-negara Mediteranian timur sedangkan Amerika,
Eropa dan negara-negara di daerah Pasifik Barat yang tergolong negara dengan
pendapatan besar, memiliki tingkat kematian yang paling rendah.27
Kejadian Luka Bakar di Indonesia memiliki prevalensi sebesar 0.7% 2
dengan angka kejadian tertinggi terdapat di Papua. Data epidemiologi dari unit
luka bakar RSCM yang diperoleh dari tahun 2011-2012, terdapat 257 pasien luka
bakar, dengan etiologi tersering adalah api (54.9%), kemudian yang disebabkan

16
air panas (29.2%), luka bakar listrik (12.8%) dan luka bakar akibat bahan kimia
(3.1%). Rata-rata lama rawat pasien luka bakar adalah 13.2 hari. Data mortalitas
pasien luka bakar masih tergolong tinggi. Didapatkan sebanyak 27.6% (2012)
pasien luka bakar yang meninggal di RSCM dan 26.41% (2012) pasien meinggal
di RS DR. Soetomo1 Dari data-data tersebut dapat kita ketahui bahwa luka bakar
menyebabkan peningkatan masa rawat pasien, kecacatan dan kematian.
2.1.7 Patofisiologi luka bakar
Pada saat terjadi luka bakar, maka selanjutnya akan timbul respon inflamasi tubuh
berupa respon lokal dan sistemik.
RESPON LOKAL
Respon lokal tubuh digambarkan dengan terbentuknya tiga zona yang
dideskripsikan oleh Jackson pada 1947 sebagai berikut :28
1. Zona Koagulasi
Terjadi pada bagian tubuh yang mengalami cedera thermal paling berat.
Kerusakan jaringan bersifat irreversible disebabkan karena adanya sumbatan
oleh protein konstituen, yang menghilangkan perfusi ke jaringan tersebut,
sehingga suplai berupa nutrisi dan oksigen tidak tersalurkan. Pada akhirnya,
terjadilah kematian jaringan atau nekrosis.
2. Zona Stasis
Secara klinis, akan tampak sebagai daerah yang terlihat pucat. Jaringan yang
terlibat masih mungkin untuk dilakukan upaya penyelamatan dengan
melakukan reperfusi jaringan melalui pemberian terapi cairan yang adekuat
sebelum terjadinya perburukan yang pada akhirnya membuat jaringan tersebut
tidak dapat diperbaiki kembali. Hal yang dapat memperburuk progresifitas
cedera jaringan pada zona ini adalah adanya hipotensi yang berkepanjangan,
infeksi dan edema.
3. Zona Hiperemia
Pada daerah ini, yaitu daerah yang terletak paling luar dari zona sebelumnya,
memiliki perfusi yang meningkat. Pada gambaran klinisnya terlihat sebagai
daerah yang paling merah. Jaringan yang ada pada zona ini, hampir selalu
dapat selamat kecuali pada keadaan sepsis berat dan hipoperfusi yang lama. 28

17
Ketiga zona tersebut dipresentasikan dalam Gambar 2.4
Gambar 2.4 Tiga zona respon lokal tubuh. Terdapat zona nekrosis
sentral yang dikelilingi oleh zona stasis dan hiperemis.
Sumber : Shehan H PD. Pathophysiology and types of burns. BMJ. 2004;: p. 1427-
1429.
Respon Sistemik
Efek sistemik dari kejadian luka bakar, terjadi akibat pelepasan berbagai macam
sitokin dan mediator inflamasi lainnya. Sehingga mempengaruhi keadaan sistemik
tubuh pada luka bakar seluas 30% atau lebih. 28
Beberapa hal yang terjadi adalah
1. Nyeri
Cedera thermal yang terjadi pada jaringan, akan merangsang aktivitas sel Mast
dengan mengeluarkan produk-produk granul sel Mast, diantaranya berupa
histamin. Histamin nantinya akan merangsang badan saraf akhir perifer, yang
diteruskan melalui serabut C ke kornu dorsalis medulla spinalis, menuju otak yang
mengakibatkan seseorang akan merasakan nyeri.29,30
2. Edema jaringan
Adanya faktor XIIa, plasmin, tripsin dan toksin akan menyebabkan teraktivasinya
jalur kinin yang produk akhirnya berupa bradikinin. Bradikinin akan
menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular, sehingga terjadi ekstravasasi

18
cairan plasma menuju interstitial, yang menyebabkan pasien luka bakar
mengalami edema di bagian tubuh yang cedera.29,30
3. Bronkokonstriksi
Bronkokonstriksi dapat disebabkan oleh edema yang terjadi di saluran napas. Hal
tersebut dapat menyebabkan penyempitan saluran napas yang dapat berakhir pada
distress pernapasan. 29
4. Hipotensi dan hipoperfusi
Peningkatan ekstravasasi cairan yang terjadi pada luka bakar seluas 30% atau
lebih, dapat menurunkan volume intravaskular yang merangsang vasokontriksi
perifer dan mekanisme splaknik, pada akhirnya menyebabkan penurunan perfusi
pada jaringan-jaringan perifer sehingga akan tampak sebagai gambaran pucat pada
ujung-ujung ekstremitas. Pelepasan Tumor Necrosis Factor (TNF)-α yang
diproduksi oleh berbagai macam sel radang, terutamanya diproduksi oleh
makrofag, dapat terjadi pula pada luka bakar. Adanya TNF-α akan berakibat pada
penurunan aktivitas otot-otot jantung, sehingga memperburuk keadaan hipotensi
pasien.28
2.1.8 Derajat Luka Bakar
A. Berdasarkan Lokasi dan Luas Luka Bakar
Dihitung berdasarkan luas permukaan tubuh atau Total Body Surface Area
(TBSA), yang dapat dihitung dengan tiga metode :31
1. Metode Tangan Pasien (Patient’s Hand)
Metode ini adalah yang paling mudah untuk dipraktikkan. Paramedis
dapat melakukan pengukuran luas luka bakar dengan menggunakan
telapak tangan pasien. Satu telapak tangan pasien bernilai 1% .
2. Metode Aturan Angka Sembilan (Rule of Nine)
Disebut Rule of Nine karena metode ini membagi tubuh menjadi 9%
bagian atau penjumlahan dengan angka 9

19
Gambar 2.5 Persentase tiap bagian tubuh pada anak dan dewasa metode Rule of
Nine
Sumber : Cline DM. Tintinalli's Emergency Medicine Manual 7th edition New York: Mc-Graw
Hill; 2012.
3. Metode Lund dan Browder
Dijelaskan pada diagram Lund dan Browder pada Gambar 2.6
Dengan menggunakan metode ini, perhitungan luas area tubuh akan lebih
akurat, yaitu dengan menyesuaikan usia pasien dan daerah yang terdapat
luka bakar, sehingga didapatkan hasil persentase luas tubuh yang
mengalami luka bakar untuk diberikan penanganan berupa pemberian
cairan yang perhitungannya akan lebih akurat.

20
Gambar 2.6 Diagram Lund dan Browder untuk mengukur luas
permukaan tubuh atau TBSA
Sumber : Hans L. The ABC of Emergency Medicine 12th edition Toronto: University of
Toronto; 2012.
Dalam prakteknya, metode yang paling sering digunakan adalah Rule of Nine,
sedangkan pengukuran yang lebih akurat, terutama untuk mengukur luas luka
bakar yang terjadi pada anak, maka Metode Lund dan Browder lebih unggul.
Apabila luas luka bakar lebih kecil, maka dapat digunakan Metode Hand’s
Patient.32
Berikut adalah klasifikasi pasien luka bakar berdasarkan keparahannya :32
Derajat Ringan :
Dewasa (<15% TBSA dengan luka bakar derajat 2A)
Anak (<10% TBSA dengan luka bakar derajat 2A)
Dewasa atau anak dengan luka bakar grade 3 seluas <2% TBSA
Derajat Sedang :
Dewasa (15-25% TBSA dengan luka bakar derajat 2A atau 2B)
Anak (10-20% TBSA dengan luka bakar derajat 2A atau 2B)
Dewasa atau anak dengan luka bakar grade 3 seluas 2-10% TBSA
Derajat Berat :
Dewasa (>25% TBSA dengan luka bakar derajat 2A atau 2B)
Anak (>20% TBSA dengan luka bakar derajat 2A atau 2B)
Dewasa atau anak dengan luka bakar grade 3 seluas >10% TBSA

21
Disertai atau tidak dengan luka bakar pada daerah wajah dan genital ; luka bakar
listrik ; luka bakar dengan cedera saluran napas ; luka bakar dengan trauma berat ;
luka bakar yang terjadi pada geriatri, pasien imunokompromais dan dengan
penyakit penyerta. 32
B. Berdasarkan Kedalaman Luka Bakar
Gambar 2.4 Derajat luka bakar berdasarkan kedalamannya.
Sumber : Mulholland MW MRea. Greenfield's Surgery Scientific Principles and Practice 4th
edition Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
Kedalaman luka bakar ini dinilai berdasarkan penilaian histologis, yaitu :
Derajat I : Luka Bakar sebatas lapisan epidermis. Kulit memerah dan terasa
perih.Tidak ditemukan adanya bula. Biasanya disebabkan oleh paparan sinar
matahari yang terus-menerus sehingga membakar kulit. 32
Derajat II A (Superficial Second Degree) : Luka Bakar memasuki lapisan dermis
bagian superficial. Masih tampak adanya vaskularisasi dengan kulit yang tampak
merah. Dapat ditemukan bula dan luka terasa sangat nyeri. Biasanya disebabkan
oleh air yang mendidih. 32
Derajat II B (Deep Second Degree) : Luka Bakar mengenai lapisan dermis dalam
yang mengandung struktur kelenjar dan folikel rambut. Sudah tidak tampak
adanya vaskularisasi, dengan kulit berwana pucat. Dapat ditemukan bula dan luka
terasa sangat nyeri. Biasanya yang menjadi penyebabnya adalah cairan panas, uap
panas ataupun lidah api yang menyambar kulit secara langsung. 32
Derajat III (Full Thickness): Luka bakar mengenai seluruh bagian epidermis dan
dermis, kulit hangus dan mengerut. Biasanya pasien tidak lagi merasakan sakit.

22
Ditemukan adanya jaringan kulit yang nekrosis. Kebanyakan disebabkan oleh
sengatan lidah api. 32
Derajat IV Kedalaman luka mencapai seluruh epidermis dan dermis hingga
menembus lemak, otot dan tulang. Penyebab terseringnya adalah api. 32
Secara skematik, penggambaran kedalaman luka bakar ditampilkan dalam
Gambar 2.4
2.1.9 Penanganan Luka Bakar
Pertolongan Pertama
Hal utama yang harus dilakukan adalah menjauhkan pasien dari sumber penyebab
dengan tidak mengabaikan keselamatan diri penolong. Lepaskan pakaian pasien.
Apabila luka bakar belum memasuki waktu 3 jam, lakukan irigasi dengan air yang
mengalir selama 20 menit dan segera bawa pasien ke pelayanan kesehatan
terdekat yang dilengkapi dengan ruang gawat darurat bila luka bakar cukup
parah.32
2.1.10 Perawatan pada Luka Bakar
Perawatan pada Fase Awal
1. Sebelumnya pastikan pasien sudah diberikan analgesik yang tepat sebelum
dilakukannya perawatan luka bakar. 32
2. Berikan profilaksis tetanus
3. Lakukan debridement pada jaringan yang nekrosis agar tidak menjadi
media bagi bakteri untuk tumbuh.
4. Setelah dilakukan debridement, luka dibersihkan dengan menggunakan
larutan klorheksidin 0.25%(2.5gr/L), atau larutan setrimid 0.1% (1gr/1L)
atau antiseptik lain yang berbahan dasar air
5. Jangan menggunakan cairan berbahan dasar alkohol untuk membersihkan
luka.
6. Perlahan lakukan gosokan pada luka, sehingga melepaskan jaringan-
jaringan nekrotik yang masih tersisa.
7. Aplikasikan selapis tipis krim antibiotik (silver sulfadiazin atau basitrasin)
8. Balut luka dengan menggunakan balutan kering yang cukup tebal untuk
mencegah terjadinya rembesan cairan plasma ke lapisan terluar.33

23
Perawatan Harian
1. Lakukan penggantian balutan setidaknya dua kali dalam sehari untuk
mencegah merembesnya cairan melalui balutan luka.
2. Berikan antibiotik topical setiap hari. Dengan beberapa pilihan sebagai
berikut :
a. Salep silver sulfadiazin 1%
Digunakan pada balutan satu lapis. Dapat bekerja secara terbatas di
bagian eskar atau jaringan parut dan dapat menyebabkan neutropenia.
b. Salep Asam Mafenid 11%
Yang dapat digunakan pada luka tanpa balutan. Dapat melakukan
penetrasi pada eskar, namun menyebabkan asidosi.
c. Cairan Silver nitrate 5%
Merupakan bahan yang termurah, di aplikasikan pada balutan oklusif
(occlusive dressing). Tidak dapat menembus eskar. Dapat
menyebabkan penurunan elektrolit dan menyisakan noda.
3. Periksalah keadaan luka, perubahan warna atau perdarahan dapat
merupakan indikasi dari infeksi
4. Selulitis pada jaringan sekitar luka merupakan tanda yang hamper akurat
bahwa luka tersebut mengalami infeksi
5. Bila terjadi infeksi Streptococcus haemoliticus atau terjadi
septicemia,berikan antibiotik sistemik
6. Bia terindikasi adanya infeksi Pseudomonas aeruginosa yang dapat
menyebabkan septicemia dan kematian, berikan antibiotik aminoglikosida
sistemik. 33
2.1.11 Penyembuhan Luka Bakar
Luas dan kedalaman luka akan menentukan seberapa lama luka bakar tersebut
akan sembuh. Secara umum, pada luka bakar derajat I akan sembuh dalam waktu
7 hari, derajat II A sembuh dalam 14 hingga 21 hari tanpa membentuk skar,
derajat II B dapat sembuh dalam 3 hingga 8 minggu, dan dapat terbentuk skar
yang permanen, pada derajat III perlu waktu berbulan-bulan untuk sembuh

24
bahkan pada beberapa keadaan, perlu adanya bantuan cangkok kulit untuk
mempercepat proses penyembuhan, apabila tidak ditangani dengan baik akan
terbentuk jaringan parut yang berlebihan, begitupula yang terjadi pada luka bakar
derajat IV dan biasanya membutuhkan penanganan multidisiplin yang meliputi
spesalis penyakit dalam, ortopedi dan lainnya.32
Proses penyembuhan luka
Secara umum, seluruh jenis luka akan mengalami fase yang sama dalam
penyembuhan. Tahapan yang akan dialami adalah sebagai berikut :
Gambar 2.6 Tahap-tahap penyembuhan luka.
Sumber : Rubin E. Essential of Rubin's Pathology 5th edition Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins; 2009.
1. Fase inflamasi
Saat awal terjadinya luka, akan terjadi peradangan (inflamasi) yang pada
umumnya dapat berlangsung selama tiga hari.34 Pada fase inflamasi jaringan
akan terasa lebih hangat, memerah, bengkak dan nyeri. Hal tersebut terjadi
akibat adanya mediator kimia yang dilepaskan oleh sel-sel radang seperti
makrofag, sel Mast dan leukosit. Mediator kimia tersebut diantaranya adalah

25
histamin dan serotonin, yang berperan dalam terjadinya vasodilatasi dan
peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Vasodilatasi membuat jaringan
yang mengalami peradangan akan tampak memerah, sedangkan permeabilitas
vaskular memungkinkan terjadinya ekstravasasi cairan plasma ke lapisan
interstitial yang menyebabkan terjadinya pembengkakan.35
2. Fase proliferasi dan akumulasi matriks
Fase proliferasi dan akumulasi matriks biasanya berlangsung selama
kurang lebih 3 minggu.34 Pada tahap ini terjadi proses re-epitelisasi dan
neovaskularisasi yang secara makroskopik tergambar sebagai jaringan
granulasi yang merah dengan permukaannya yang memiliki granul-granul
pucat. Pada saat yang sama, sel fibroblast melakukan migrasi ke daerah yang
mengalami cedera oleh karena pengaruh dari platelet derived growth hormone
(PDGF) dan TGF-β yang disekresikan oleh makrofag akibat terjadinya
inflamasi di daerah tersebut. Pembentukan jaringan granulasi dan re-epitelisasi
terjadi secara simultan, dimulai dari beberapa jam setelah terjadi reaksi
inflamasi. Keratinosit yang berada di tepi luka dan pada sisa-sisa skin
appandages mulai melakukan migrasi pada bagian luka dan membentuk
keropeng. Pada fase ini, karakteristik keratinosit yang paling menonjol adalah
sangat hiper-proliferatif, sehingga membuatnya mampu merancang kembali
membran basal yang telah rusak dalam dua hari dari masa dimulainya luka.22
Selanjutnya, sel fibroblast yang terpanggil untuk menyekresikan berbagai
protein matriks seperti kolagen dan fibronektin, kemudian akan mencapai
puncak akumulasinya pada hari ke 5 hingga 7, sehingga terbentuklah suatu
struktur luka yang lebih stabil.36
Pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis mengalami
regulasi yang ketat. Diawali dari cedera jaringan yang menyebabkan hilangnya
membran basal endotel kapiler, terjadinya pelepasan sitokin dan growth factor
setempat, menyebabkan aktivasi sel endotel, sel makrofag serta sel epidermal
pada daerah yang terluka untuk menghasilkan suatu produk vascular
endothelial growth factor (VEGF) dan basic fibroblast growt factor (bFGF),
yang keduanya mampu merangsang proses angiogenesis.36

26
Pada tiap-tiap ujung jaringan yang terputus akibat luka, terdapat sisa
keratinosit yang akan menginisiasi pembentukan jembatan epitel di atas
matriks yang sebelumya telah terbentuk. Sementara sel-sel progenitor yang
berada pada membran basal, atau pada kelenjar keringat dan folikel rambut
yang berdekatan dengan lokasi cedera, mengalami mitosis, sehingga
menyebabkan lapisan epidermis menebal dan membesar. Keratinosit
memproduksi suatu protein matrix metalloproteinase (MMP) yang
memudahkannya untuk melakukan perlekatan dengan membran basal.
Rangsangan keratinosit untuk bermigrasi ini didasarkan dengan adanya
sinyal/chemotaxis yang berasal dari tingginya konsentrasi komponen matriks
disekitar daerah luka.36
3. Fase remodeling
Remodeling adalah suatu proses dalam upaya untuk mengembalikan
fungsi jaringan yang sudah menurun kepada fungsi awalnya. Fase remodeling
yang terjadi pada luka, bertujuan untuk mengganti jaringan granulasi yang
cenderung tidak stabil menjadi jaringan parut yang stabil. Pada awalnya,
jaringan granulasi mengandung matriks hialuronan, proteoglikan, glikoprotein
dan kolagen tipe III, akan tetapi kolagen tipe III tidak akan bertahan lama dan
akan segera digantikan oleh kolagen tipe I yang memiliki diameter fibril yang
lebih kuat dan lebih lentur. Sehingga pada akhirnya, jaringan akan didominasi
oleh kolagen tipe I dan hanya sekitar 15-20% diisi oleh kolagen tipe III.
Namun jaringan parut juga harus dikendalikan pembentukannya agar tidak
terbentuk jaringan parut yang berlebihan seperti pada hypertrophic scar atau
pun keloid. Pengendalian ini diperankan oleh adanya sekelompok enzim
metalloproteinase, disebut demikian karena adanya ketergantungan aktivitas
enzim terhadap kadar Zn (seng), dan hal inilah yang membedakannya dengan
enzim lain yang juga dapat memecah matriks seperti elastase neutrofil,
katepsin G, plasmin dan proteinase serin, namun semua enzim ini tidak
bergantung pada kadar seng tubuh sehingga tidak tergolong dalam
metalloenzyme.36
Beberapa enzim yang tergolong dalam metalloproteinase meliputi
kolagenase yang memecah fibril tipe I, II dan III; Gelatinase (kolagenase tipe

27
IV) yang memecah kolagen amorf dan fibronektin; Stromelisin yang
menguraikan berbagai matriks ekstraseluler seperti proteoglikan, laminin,
fibronektin dan kolagen amorf. Enzim-enzim ini dapat dihasilkan oleh
makrofag, neutrofil, fibroblas, sel sinovial dan beberapa sel epitel. Sintesis dan
sekresi enzim-enzim ini diatur oleh sitokin seperti IL-1 dan TNF; faktor
pertumbuhan PDGF dan EGF; dan bahkan tekanan fisik. Sedangkan
penghambatannya diperankan oleh adanya TGF-β atau melalui intervensi
farmakologis berupa obat-obatan steroid serta sekresi TIMP (Tissue Inhibitor
of Metalloproteinase) oleh sebagian besar sel mesenkim.35,36
2.1.12 Krim Silver Sulfadiazin (AgSD)
Krim silver sulfadiazin dengan kadar satu persen dikenalkan pada tahun
1968. Pada waktu itu krim ini diposisikan sebagai alternatif dari penggunaan silfer
nirat 0.5% yang digunakan untuk mengobati luka bakar. Krim AgSD mempunyain
aktivitas antibakterial dengan menyerang dinding sel bakteri sehingga
menurunkan perkembangannya. Komponen sulfadazine dalam AgSD cepat
diekskresikan melalui urin, namun komponen perak (Ag) dibersihkan perlahan.
Kompnen perak dapat disimpan di kulit, hati, ginjal, konjungtiva, kornea dan
tempat lainnya.37
Silver sulfadiazin merupakan agen topikal dengan basis sulfonamid yang
memiliki aktivitas antibakteria dan antijamur. Cara kerja silver sulfadiazin adalah
dengan mengkombinasikan fungsi perak dan sulfadiazin. Ion perak akan
mengintervensi DNA bakteri sehingga terganggu replikasi dan transkripsinya.
Sebagai kompetitor para-amniobenzoic acid (PABA), sulfadiazin akan
menghambat metabolism asam folat dan akhirnya menghambat sintesis DNA
bakteri.38
Krim silver sulfadiazin masih digunakan dalam perawatan pasien. Dalam
guidline dan algoritma penanganan luka bakar yang dikeluarkan oleh Turki tahun
2015, Pasien yang mengalami luka bakar wajah seluas, dapat diberikan krim
silver sulfadiazin 1% sebagai terapi inisiasi.39 Indikasi lain pemberian krim silver
sulfadiazin adalah luka bakar dengan infeksi, eskar atau pada luka bakar yang luas.

28
Pada pasien dengan luka bakar derajat II, krim siler sulfadiazin dapat diberikan
secara langsung atau dengan balutan kasa parafin.39
2.1.13 Sediaan Topikal Salep Ekstrak Daun Binahong
Sediaan topikal dapat terdiri dari cairan, lotion, gel, salep, bedak, krim,
lotion, linimen dan pasta. Masing-masing bahan ini memiliki perbedaan
komponen penyusun, sehingga mempengaruhi beberapa aspek seperti cara
pemakaian dan indikasinya. Sediaan topikal murni terdiri dari cairan, bedak dan
salep, sedangkan sediaan topikal dengan dua campuran atau lebih dapat berupa
lotion atau bedak kocok yang merupakan campuran air dan bedak; krim yaitu
campuran cairan dan salep; pasta yang berasal dari campuran salep dan bedak;
liminen atau pasta pendingin yaitu campuran cairan, bedak dan salep.40
Salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit
atau selaput lendir.41
Formula umum salep adalah sebagai berikut :
R/Zat Aktif
Basis
Bahan Tambahan
Basis salep yang digunakan sebagai pembawa terbagi menjadi empat kelompok: 41
1. Basis Hidrokarbon
Didominasi oleh sifatnya yang berminyak sehingga sulit untuk dicuci dengan
air dan dapat mempertahankan kelembaban kulit. Kemampuannya yang dapat
mempertahankan kadar air dalam basis itu sendiri sehingga mampu
meningkatkan hidrasi kulit serta dapat meningkatkan absorbsi zat aktif secara
perkutan. Sifatnya yang inert memudahkan pencampurannya dengan berbagai
zat aktif. Kerugian dari penggunaan basis hidrokarbon yaitu sifatnya yang
berminyak dapat meninggalkan noda yang sulit dibersihkan yang terkadang hal
ini menjadi alasan menurunnya kepatuhan pasien. Contoh basis hidrokarbon
adalah soft paraffin, hard paraffin, liquid paraffin, vaselin putih, vaselin kuning.
41,42

29
2. Basis Absorbsi
Bahan-bahan yang digunakan dalam basis absorbsi merupakan campuran dari
sterol-sterol binatang atau zat yang bercampur dengan senyawa hidrokarbon.
42Dasar salep serap dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama
terdiri atas dasar salep yang bercampur dengan air membentuk emulsi air
dalam minyak seperti pada parafin hidrofilik dan lanolin anhidrat. Sedangkan
kelompok kedua terdiri atas emulsi air dalam minyak yang dapat bercampur
dengan sejumlah air tambahan seperti pada lanolin. Basis absorbsi dapat pula
dimanfaatkan sebagai emolien.41
3. Basis yang dapat dicuci dengan air
Terdiri dari emulsi minyak dalam air yang biasa dikenal sebagai krim. Basis ini
mudah dicuci dari kulit atau gampang dieliminir dengan menggunakan lap
basah. 41
4. Basis yang larut dalam air
Basis ini juga disebut sebagai basis yang tak berlemak karena terdiri dari
konstituen yang larut air dan tidak mengandung bahan tak larut air seperti
parafin, lanolin anhidrat atau malam. Dasar ini biasa disebut sebagai gel.41
Pada sediaan topikal berupa salep yang umum dikenal, bahan dasar
sediaan terbuat dari lemak lanolin yang pada suhu kamar akan berkonsistensi
seperti mentega serta penambahan bahan inert berupa vaselin sebagai
emolien.40,43 Vaselin putih berasal dari minyak bumi yang dihilangkan
warnanya secara keseluruhan atau hampir keseluruhannya,41 merupakan basis
hidrokarbon yang digunakan karena sifatnya yang netral dan mampu menyebar
secara luas di permukaan kulit. Basis ini sulit untuk dihilangkan dari
permukaan kulit dengan penggunaan air biasa sehingga dengan kemampuannya
ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan yang dapat menjaga kelembaban kulit.43
Lanolin yang merupakan basis serap atau basis absorbsi dapat diperoleh
dari bulu domba adalah emulsi air dalam minyak sehingga yang mengandung
unsur air sebanyak 25% hingga 30%. Keuntungan penggunaan salep dengan
basis lanolin dan vaselin akan membuat sediaan lebih lama melekat di
permukaan kulit, sehingga penetrasi obat akan lebih maksimal.43,44

30
2.1.14 Rute Penyerapan Obat Topikal
Pada saat sediaan topikal diaplikasikan pada permukaan kulit yang mengalami
gangguan, secara garis besar hal ini akan terjadi pada sediaan:
1. Pelepasan zat aktif dari zat pembawa
2. Penetrasi zat menembus lapisan kulit
3. Aktivasi respon farmakologi
Efektivitas tahapan di atas akan didukung oleh tiga faktor berikut, yaitu zat aktif
atau obat, zat pembawa dan kulit tempat diaplikasikannya sediaan.
Gambar 2.5 Tahap yang dilalui sediaan topikal (transdermal patch)
Sumber : Ansel H.C. PNG,ALV. Pharmaceutical Dosage From and Drug Delivery System
Malvern: Williams & Wilkins; 1995.
Gambar 2.5 menggambarkan perpindahan molekul obat menembus lapisan kulit.
Untuk memulai tahapan tersebut, obat haruslah dalam keadaan larut. Molekul
akan berdifusi melewati stratum korneum, setelah itu akan terbagi dalam partisi-
partisi untuk berdisfusi kembali melewatinya. Beberapa obat dapat berikatan pada
tempat penyimpanannya dan sisanya akan melanjutkan berpenetrasi sehingga
bertemu ke lapisan kulit berikutnya. Di dalam epidermis, terdapat enzim yang

31
dapat memetabolisme obat atau obat tersebut berikatan pada reseptor yang sesuai.
Setelah dapat melewati epidermis dan memasuki dermis dan menuju kapiler
pembuluh darah selanjutnya akan memasuki peredaran sistemik untuk dilakukan
pembuangan. Beberapa sediaan juga dapat menembus lapisan terdalam dari otot
seperti pada OAINS. 44
Berikut syarat suatu obat untuk secara efektif menembus startum korneum : 44
1. Memiliki masa molekul yang rendah, yaitu kurang dari 600Da
2. Memiliki kelarutan yang tinggi pada minyak dan air sehingga gradien
konsentrasi pada membrane dapat meningkat
3. Memiliki koefisien partisi yang seimbang
4. Memiliki titik kelelehan yang rendah; hal ini berhubungan dengan kelarutan
yang ideal
2.1.15 Sediaan Oral Larutan atau Solutions Daun Binahong
Sediaan oral secara umum berdasarkan konsistensinya terbagi atas dua
sediaan yaitu sediaan padat seperti tablet dan kapsul serta sediaan cair berupa
suspensi, solusio dan emulsi.42
Tablet dibuat dengan kompresi campuran bahan obat atau bahan tambahan
lain. Tablet biasanya juga dilapisi lapisan pelindung (enteric coating) yang dapat
melindunginya dari faktor lingkungan termasuk keasaman lambung, sehingga
bentuknya tetap stabil sampai diserap oleh mukosa gastro intestinal.42
Kapsul adalah sediaan padat yang mengandung obat yang terbungkus dalam
cangkang gelatin keras atau halus. Kecepatan pelepasan obat dari kapsul lebih
cepat dibanding pada sediaan tablet.42
Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut
yang terdispersi pada fase cair. Zat yang terkandung di dalam suspensi bila
didiamkan akan memadat di dasar botol, hal ini bila dibiarkan terlalu lama akan
mengakibatkan pengerasan pada suspensi sehingga sulit untuk terdispersi kembali.
Sehingga untuk mengatasi hal tersebut ditambahlah zat pengental berupa
surfaktan, poliol, polimer atau gula. Sebelum menggunakan suspensi, hal

32
terpenting adalah mengocoknya terlebih dahulu agar partikel obat terdistribusi
dengan baik.41
Natrium karboksimetilselulosa (CMC-Na) berfungsi sebagai suspending
agent yaitu agen yang dapat mendispersikan partikel tidak larut. CMC-Na terdiri
atas garam natrium dari polikarboksimetil eter selulosa. Sebanyak 6,5%-9,5% dari
CMC-Na terdiri dari natrium (Na) terhadap zat yang telah dikeringkan.45
Larutan atau Solutions adalah sediaan cair yang mengandung satu atau
lebih zat kimia di dalamnya dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau
pewarna yang larut dalam air atau campuran kosolven air. Keuntungan pemberian
sediaan larutan adalah adanya jaminan keseragaman dosis karena molekul-
molekul zat kimia yang terkandung di dalamnya terdispersi secara merata. Larutan
yang mengandung kadar gula tinggi disebut sebagai Sirup, sedangkan sediaan
larutan yang mengandung etanol sebagai kosolven dinyatakan sebagai Eliksir.41
2.1.16 Tikus Sprague Dawley
Hewan percobaan tikus sering dijumpai dalam penelitian mengenai
penyembuhan luka bakar dan diteliti efikasinya dalam berbagai modalitas
pengobatan. Tikus dipilih sebagai hewan coba karena ketersediaannya, harga yang
relative terjangkau dan ukurannya yang tidak terlalu besar. Perlakuan biasanya
diterapkan pada bagian punggung tikus. Hal ini ditujukan agar tikus tidak dapat
mencapai daerah percobaan yang akan memanipulasi hasil penelitian. Pemilihan
tikus sebagai hewan coba dalam penelitian mengenai kulit, didasari oleh adanya
kemiripan karakteristik kulit yang dimiliki oleh tikus, yaitu adanya epidermis,
membran basal, folikel rambut dan dermis. Keuntungan yang didapatkan dalam
memilih tikus dalam percobaan di bidang penyembuhan luka, bahwa kulit tikus
yang mengalami luka memiliki kecepatan penyembuhan yang lebih cepat
dibanding manusia, sehingga penelitian tidak memerlukan waktu yang panjang
untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.46
Epitelisasi adalah respon primer dalam penyembuhan luka bakar, abrasi
dan luka dengan yang meliputi sebagian kedalaman kulit. Pada luka yang
menyebabkan hilangnya epitel dan permukaan dermis, sel epitel bergerak dengan

33
cepat dari folikel rambut dan kelenjar keringat. Keduanya berasal dari dermis
yang masih tersisa di tepi luka. Pada luka yang mencapai seluruh kedalaman kulit
dan luka terbuka, epitelisasi hanya berasal dari tepi luka dan ketebalannya
bertambah 1-2 mm/hari.46
Dua jenis tikus outbred yang sering digunakan dalam penelitian adalah
Sprague–Dawley dan Wistar. Perbedaan antara keduanya adalah, Sprague–
Dawley memiliki proporsi tubuh yang lebih besar, namun keduanya tergolong
jinak sehinga memungkinkan untuk digunakan sebagai model penelitian.46
2.2 Kerangka Teori
Bagan 2.1 Kerangka Teori
↑ Re-epitelisasi
kulit
Ekstrak Daun Binahong Mengandung zat
aktif
Saponin
28.14±0.22 mg/gr
Asam
Oleanat
Asam
Urosilic
Aktivasi
PPAR-α
Diferensiasi
keratinosit
Percepatan
migrasi
keratinosit
Proliferasi sel
epidermal
(+) Luka Bakar
Pengobatan luka
bakar Krim Silver Sulfadiazin mencegah
infeksi
Luka Bakar
derajat I, II, III
Penyembuhan
luka bakar Fase Prolifeasi
Re-epitelisasi, neovaskularisasi,
pembentukan kolagen

34
2.3 Kerangka Konsep
Bagan 2.2 Kerangka Konsep
2.4 Identifikasi Variabel
A. Variabel Bebas
Ekstrak daun binahong Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) dengan
konsentrasi sebesar 40% yang dibuat dalam bentuk salep dan suspensi
ekstrak daun binahong.
B. Variabel Terikat.
Ketebalan lapisan re-epitelisasi pada kulit yang dikondisikan
mengalami luka bakar derajat II
2.5 Definisi Operasional
No. Variabel Definisi Alat Hasil Ukur Skala Ukur 1 Re-epitelisasi
kulit Proses pertumbuhan kembali sel-sel epitel di
Aplikasi ImageJ Mikrometer Numerik
Luka bakar derajat II tikus
Sprague dawley
Fase inflamasi Fase proliferasi
↑Migrasi keratinosit
↑Proliferasi, diferensiasi
keratinosit
Peningkatan ketebalan
lapisan re-epitelisasi
Salep dan suspensi ekstrak
daun binahong

35
permukaan kulit
2 Salep ekstrak daun binahong
Sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir yang mengandung zat aktif dalam hal ini berupa ekstrak daun binahong sebanyak 40%
Kategorik
3 Suspensi ekstrak daun binahong
Sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi pada fase cair dalam hal ini partikel padat adalah ekstrak daun binahong
Kategorik
4 Basis salep Bahan yang digunakan sebagai pembawa zat aktif
Kategorik
5 Krim Silver Sulvadiazine
Krim standar yang digunakan dalam pengobatan luka bakar,dapat mengandung zat aktif
Kategorik

36
berupa silver dan sulfadiazin
6 Salep Kontrol Positif
Bahan standar yang digunakan dalam penanganan luka bakar secara topikal
Timbangan analitik farmasi
Kategorik
7 Salep Kontrol Negatif
Berisi basis salep (Adeps lanae dan Vaseline album) tanpa penambahan zat aktif
Timbangan analitik farmasi
Kategorik
Tabel 2.1 Tabel Definisi Operasional

37
BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain analitik eksperimental dan
studi potong lintang (cross sectional) melalui evaluasi histopatologi untuk
melihat pengaruh ekstrak daun binahong yang diberikan kepada tikus yang
mengalami luka bakar derajat II, baik secara oral maupun topikal dengan
salep, terhadap re-epitelisasi kulit pasca luka bakar
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada Senin, 25 April 2016 dan berakhir pada Kamis
30 Juni 2016. Determinasi tanaman dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) Bogor, kemudian diekstraksi dalam bentuk cair di Balai
Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (BALITRO) Bogor dan dilakukan
pengeringan di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Jakarta Selatan.
Pembuatan salep dan sediaan oral ekstrak daun binahong dilakukan di
Laboratorium Biokimia FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pembuatan
preparat dilakukan oleh staf ahli Laboratorium Patologi Anatomi Cito, Depok
dan pengamatan preparat dilakukan di Laboratorium Parasitologi FKIK UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3.3 Bahan Uji
Sebanyak 600 gr daun binahong kering dijadikan ekstrak 18 mg. Pohon dan
daun binahong didapat dari penjual tanaman di desa Cikopo, Kecamatan
Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. Daun didetermiasi terlebih
dahulu di LIPI Bogor, untuk memastikan keaslian sampel. Hasil determinasi
menunjukan bahwa sampel yang diuji benar adalah spesies Anredera
cordifolia (Tenore) Steenis. (Lampiran 1) Kemudian setelah memastikan
kebenaran sampel, daun binahong dibawa ke BALITRO Bogor untuk
dilakukan pembuatan ekstraksi, selanjutnya karena sediaan oral
membutuhkan sediaan ekstrak dalam satuan miligram per kilo maka ekstrak

38
dibawa ke Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) untuk dilakukan proses
pengeringan ekstrak sehingga kandungan airnya menurun (Lampiran 2)
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi penelitian ini adalah tikus strain Sprague dawley yang didapatkan
dari penyedia hewan coba (iRATCo) yang sudah disertakan dengan surat
keterangan sehat dari Rumah Sakit Hewan Fakultas Kedokteran Hewan,
Institut Pertanian Bogor (IPB). (Lampiran 3)
3.5 Besar Sampel
Pada peneltian ini terdapat 5 kelompok perlakuan. Dalam menentukan besar
sampel yang dibutuhkan pada setiap kelompok perlakuan, digunakan rumus
Frederer :
(N-1) (T-1) ≥15 , dengan N= Jumlah sampel dan T= jumlah kelompok.
Pada penelitian ini jumlah kelompok yang akan diuji sebanyak lima
kelompok, sehingga :
(N-1) (5-1) ≥ 15
(N-1) (4) ≥ 15
(N-1) ≥ 15/4
N -1 ≥ 3,75
N ≥ 4,75 (dibulatkan = 5)
Maka, berdasarkan perhitungan tersebut, diperlukan sebanyak lima sampel
tiap-tiap kelompok perlakuan dengan total sampel yang diperlukan adalah
sebanyak 25 sampel.
Secara rinci, 5 kelompok tikus pada penelitian ini akan dilakukan perlakuan
berupa :
1. Kelompok 1 (P1) adalah tikus yang diberikan salep ekstrak daun
binahong konsentrasi 40%
2. Kelompok 2 (P2) adalah tikus yang diberikan ekstrak daun binahong
secara oral
3. Kelompok 3 (P3) adalah tikus yang diberikan salep ekstrak daun
binahong konsentrasi 40% dan ekstrak daun binahong secara oral

39
4. Kelompok 4 (K+) adalah kelompok yang diberikan salep silver
sulfadiazin
5. Kelompok 5 (K-) adalah kelompok yang diberikan salep yang hanya
mengandung basis salep berupa adeps lanae dan vaseline album tanpa
campuran ekstrak daun binahong.
3.6 Kriteria Inklusi
Tikus Sprague dawley jenis kelamin jantan, kondisi sehat, usia 12 minggu,
berat badan 150-250 gr.
3.7 Kriteria Eksklusi
Tikus Sprague dawley yang mengalami kecacatan di daerah pungung.
3.8 Alat dan Bahan Penelitian
A. Alat Penelitian
1. Kandang tikus
2. Tempat minum dan makanan tikus
3. Serbuk kayu untuk tikus
4. Sabun dan alat pembersih kandang tikus
5. Plat besi berukuran 4x2 cm dan benang kasur
6. Toples untuk anastesi
7. Alat bedah minor, pisau cukur dan krim penghilang bulu
8. Gelas dan alat pemanas air
9. Lumpang dan alu
10. Timbangan elektronik
11. Handscoen
12. Termometer
13. Mikroskop Olympus CX 41, Personal Computer (PC) dan DVD RW
14. Masker
15. Plastic Zipper Bag
16. Kompor
17. Panci

40
18. Sonde
19. Magnetic stirrer
B. Bahan Penelitian
1. Ekstrak daun binahong
2. Adeps lanae
3. Vaseline album
4. Eter
5. Formalin
6. Air
7. CMC Na
8. Destilated Water

41
3.9 Alur Kerja Penelitian
Bagan 3.1 Alur Penelitian
Determinasi tanaman di
LIPI Bogor
Ekstraksi cair daun
binahong di BALITRO,
Bogor
Pembuatan salep ekstrak
daun Binahong 40%, salep
kontrol (-) di Lab.
Biokimia FKIK UIN
Jakarta
Pengeringan ekstrak cair di
BATAN, Jakarta Selatan
Pembelian daun dan pohon
Anredera cordifolia (Ten.)
Steenis di pusat penjualan
tanaman Cikupa, Bogor
Pembuatan suspensi
ekstrak daun binahong di
Lab. Biokimia FKIK UIN
Jakarta
Persiapan bahan penelitian
Pembelian tikus Sprague
dawley di penyedia hewan
coba iRatco, Bogor
Pencukuran rambut dorsal
tikus dibantu dengan krim
penghilang bulu
Membuat luka bakar
dengan plat besi panas,
lama paparan 30 detik
Salep ekstrak daun
Binahong 40%, salep K-
dan salep K+ di
aplikasikan pada kulit
yang luka
Suspensi ekstrak daun
Binahong di masukkan
secara per oral dengan
sonde pada tikus yang
terluka
Aklimatisasi tikus Sprague
dawley selama 7 hari
Perlakuan selama 5 hari
Terminasi pada hari ke-
6 dan pengambilan
jaringan kulit
Pembuatan preparat
kulit di Lab. Patologi
Anatomi Cito, Depok
Pengamatan
histopatologi kulit
dengan Mikroskop
Olympus CX 41 di Lab.
Parasitologi FKIK UIN
Jakarta
Pengolahan data hasil
pengamatan preparat
jaringan kulit
menggunakan aplikasi
ImageJ v.1.50i dan
SPSS v.16.0
Penulisan laporan
penelitian

42
3.10 Adaptasi dan Pemeliharaan Hewan Sampel
Setelah tikus strain Sprague dawley yang berasal dari penyedia hewan
coba (iRATCo) sampai di kampus FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Tikus memerlukan masa untuk dia dapat beradaptasi dengan
lingkungannya yang baru, sehingga diperlukan masa aklimatisasi selama 7
hari47,48 di Animal House FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tikus
dipelihara dengan baik dengan memperhatikan kondisi kandangnya agar
selalu bersih dan tidak berbau. Makanan dan minuman diberikan secara
teratur dan tidak membedakan antar kelompok satu dengan lainnya, Air
dijernihkan dengan bantuan alat penjernih air
3.11 Cara Kerja Penelitian
3.11.1 Pembuatan Ekstrak Daun Binahong untuk Bahan Salep
a. Persiapan sampel
Daun binahong dibeli di pusat penjualan tanaman Cikupa, Bogor, Jawa
Barat
b. Determinasi sampel
Setelah daun binahong dibeli, selanjutnya daun dibawa ke LIPI, Bogor
untuk dilakukan determinasi dalam memastikan bahwa sampel benar
merupakan daun Anredera cordifolia (Tenore) Steenis atau binahong.
c. Pembuatan ekstrak cair
Setelah melakukan determinasi, selanjutnya daun dibawa ke
BALITRO, Bogor untuk dilakukan pembuatan ekstrak cair
d. Pembuatan salep
Ekstrak cair yang telah didapatkan, segera dibuat salep.
Formula standar basis salep adalah sebagai berikut :49
R/ Adeps Lanae 15 g
Vaselin Album 85 g
m.f salep 100 g
Sediaan salep yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas campuran
adeps lanae dan vaseline album (basis salep) dengan penambahan

43
konsentrasi daun binahong sebanyak 40% yang di formulasikan
sebagai berikut :
R/ Ekstrak daun binahong 15 g
Basis salep 22.5 g
m.f salep 37.5 g
dan basis salep pada penelitian ini dibuat sebanyak 50 gram, sehingga
diformulasikan berdasarkan rumus berikut :
R/ Adeps lanae 7.5
Vaselin album 42.5 g
m.f ung 50 gr
Proses pembuatan salep ekstrak dilakukan di Laboratorium Biokimia,
FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ekstrak daun binahong
pertama-tama panaskan lumpang dan alu didalam oven dengan suhu
500C agar panas dan meminimalisir adanya mikroorganisme yang
menempel pada lumpang dan alu.Kemudian keluarkan lumpang dan
alu dari oven. Masukkan adeps lanae terlebih dahulu kedalam lumpang
kemudian aduk secara perlahan sampai rata, kemudian tambahkan
vaselin album kedalam lumpang lalu diaduk secara perlahan dengan
gerakan tangan mengaduk secara konstan sehingga campuran adeps
lanae dan vaseline album homogen. Selanjutnya tambahkan ekstrak
daun binahong untuk membuat konsentrasi salep 40% dibutuhkan
perbandingan basis salep:ekstrak binahong adalah 60:40, kemudian
campurkan ketiga bahan tersebut sehingga homogen.
e. Pengujian Homogenitas Sediaan Salep
Setelah ketiga bahan telah dicampurkan, untuk meMastikan salep
dalam keadaan homogen dilakukan suatu cara dengan mengoleskan
sediaan di dinding wadah yang bening. Apabila seluruh permukaan
olesan memiliki warna yang sama, maka sediaan telah homogen. Hal
ini penting dilakukan untuk menjamin persamaan dosis yang didapat
saat mengaplikasikannya ke permukaan luka. Hasil uji tes homogenitas
terdapat pada Gambar 3.1

44
Gambar 3.1 Hasil Tes Homogenitas Salep Ekstrak Daun Binahong
3.11.2 Pembuatan Suspensi Ekstrak Daun Binahong
Siapkan bahan-bahan berupa distilled water, Karboksimetil Seulosa-Na
(CMC-Na) dan ekstrak daun binahong. Fungsi dari CMC-Na dalam
pembuatan suspensi ekstrak daun binahong adalah sebagai bahan
pengental, penstabil suspensi dan bahan pengikat.50 Natrium
karboksimetilselulosa (CMC-Na) juga berfungsi sebagai suspending agent,
yaitu agen yang dapat mendispersikan partikel tidak larut.45
a. Penentuan dosis ekstrak binahong
Dosis efektif ekstrak binahong yang dapat diberikan adalah 50, 100,
150 hingga 200 mg/kgBB. Dalam hal ini dipilih dosis 100 mg/kgBB
ekstrak daun binahong. 11,12
b. Pembuatan CMC-Na 1%
Lakukan pencampuran CMC-Na dengan berat kering 1 gram dan
akuades 100ml yang kemudian dipanaskan hingga mencapai suhu 70oC
sambil dilakukan pengadukan menggunakan magnetic stirrer.50
c. Pencampuran Ekstrak Binahong
Setelah CMC-Na dan akuades tercampur, masukkan ekstrak daun
binahong sebanyak dosis yang dibutuhkan. Mengenai cara perhitungan
dosis dan kadar pencampuran Na-CMC dan ekstrak, akan dibahas pada
poin selanjutnya. Ekstrak hanya dicampurkan ke dalam larutan CMC-
Na beberapa saat sebelum diberikan kepada tikus. Dikhawatirkan bila
suspensi terlalu lama didiamkan akan mengubah stuktur dan stabilisasi
bahan aktif yang terkandung di dalamnya.

45
d. Cara pemberian ekstrak daun binahong oral
1. Pada Kelompok Oral (P2)
Berat badan rata-rata tikus pada kelompok oral adalah 160.18 gram.
Sehingga pemberian dosis 100mg/kgBB adalah berdasarkan
perhitungan sebagai berikut :
Dosis pemberian = 100 mg/1000gramBB
= 1 mg/10gram
= 1 mg x 160.18/10gram
= 16.018 mg
Jadi, setiap tikus pada kelompok P2 akan mendapatkan ekstrak
daun binahong sebesar 16.018 mg.
Sebelum memberikan ekstrak, terlebih dahulu ekstrak daun
binahong dilarutkan dalam Na CMC agar terdispersi secara merata.
Na CMC dengan kadar 1% dicampurkan dengan ekstrak
berdasarkan formulasi berikut :
10 mg ekstrak = 0.1 ml Na CMC
16.018 mg ekstrak = 0.16 ml Na CMC
Sehingga pada akhirnya tikus akan diberikan sonde berisi 0.16 ml
cairan suspensi yang mengandung ekstrak daun binahong.
2. Pada Kelompok Salep-Oral (P3)
Berat badan rata-rata tikus pada kelompok salep-oral adalah 172.59
gram. Sehingga pemberian dosis 100mg/kgBB adalah berdasarkan
perhitungan sebagai berikut :
Dosis pemberian = 100 mg/1000gramBB
= 1 mg/10gram
= 1 mg x 172.59/10gram
= 17.26 mg
Jadi, setiap tikus pada kelompok P3 akan mendapatkan ekstrak
daun binahong sebesar 17.26 mg yang akan dicampur dengan Na
CMC 1% berdasarkan formulasi berikut :
10 mg ekstrak = 0.1 ml Na CMC
16.018 mg ekstrak = 0.17 ml Na CMC

46
Sehingga tikus akan diberikan sonde berisi 0.17 ml cairan suspensi
mengandung ekstrak daun binahong.
3.11.3 Pembuatan Luka Bakar pada Tikus
Sebelum melakukan perlakuan pada tikus, tikus dianastesi terlebih dahulu,
melalui jalur inhalasi dengan memasukkan tikus ke dalam toples yang
tertutup rapat berisi eter, anestesi ditujukan agar tikus lebih mudah untuk
dilakukan perlakuan tanpa menyakitinya secara berlebihan. Tikus yang
telah teranastesi, kemudian dilakukan pencukuran rambut di daerah
punggung atau dorsal tikus.46 Rambut dicukur menggunakan pisau cukur
dengan dibantu pengolesan krim penghilang bulu agar pencukuran tidak
meninggalkan rambut-rambut yang dapat menghalangi proses pembuatan
luka bakar, serta dapat meminimalkan timbulnya iritasi kulit akibat
penggunaan pisau cukur yang terlalu dalam. Setelah rambut tikus pada
bagian punggung telah tercukur rata, selanjutnya tikus akan dianastesi
kembali dan berikutnya dilakukan pembuatan luka bakar. Plat besi panas
berukuran 4x2 cm yang sebelumnya telah dicelupkan ke dalam air panas
bersuhu 99oC selama 10 menit51 ditempelkan ke kulit tikus (Gambar 6.13)
dengan gaya tekanan yang seragam pada semua tikus. Diukur secara kasar
dengan menaruh tikus di atas timbagan dan melakukan penekanan
sehingga angka timbangan menunjukkan 1400 mg (Gambar 6.7). Hal ini
dilakukan untuk menghilangkan kerancuan perbedaan derajat luka akibat
perbedaan tekanan plat besi pada kulit tikus.
Gambar 3.2 Keadaan kulit tikus menjadi kemerahan sesaat setelah
dilakukan intervensi plat besi

47
3.11.4 Cara Pemberian Salep dan Suspensi Ekstrak Daun Binahong
Setelah dilakukan pembuatan luka bakar pada bagian punggung tikus.
Selanjutnya bagian punggung tikus diberikan pemberian terapi yang sudah
ditentukan pemberiannya pada masing-masing kelompok. Pemberian
terapi salep dilakukan dua kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari,
sedangkan pemberian terapi oral hanya diberikan sekali dalam sehari.
Keduanya dilakukan secara rutin selama 5 hari. Terapi topikal dioleskan di
daerah punggung yang mengalami luka. Sedangkan pemberian oral di
diberikan dengan memasukkan suspense ekstrak binahong ke dalam spuit
1 cc, kemudian mulut tikus dibuka sehingga sonde dapat dimasukkan
hingga mencapai tenggorokan tikus.
3.11.5 Pengambilan Jaringan dan Pembuatan Sediaan Histopatologi
Setelah tikus mendapatkan perlakuan pemberian terapi yang berbeda pada
masing-masing kelompok selama 5 hari, selanjutnya tikus diterminasi
dengan cara memasukan tikus ke dalam toples yang mengandung larutan
dan uap eter pekat. Setelah tikus telah diterminasi, bagian kulit tikus yang
mengalami perlakuan, akan diambil jaringan kulitnya dengan cara
memisahkan jaringan kulit yang mengalami perlakuan dengan kulit yang
masih sehat dengan menggunakan alat bedah minor. Setiap satu tikus,
dibuat satu sediaan kulitnya. (Lampiran 5) Setelah jaringan terambil, lalu
jaringan kulit tersebut dibentang di atas karton lalu disteples. Lalu
dimasukkan ke dalam plastic zipper bag yang berisi formalin 10% untuk
selanjutnya dilakukan pembuatan sediaan preparat HE di Laboratorium
Patologi Anatomi Cito, Depok. Pewaranaan HE ditujukan untuk melihat
lapisan epidermis lebih jelas. Langkah pembuatan sediaan preparat dengan
pewarnaan HE adalah sebagai berikut :
1. Proses fiksasi : sediaan direndam di dalam formalin 10% selama 24
jam

48
2. Proses dehidrasi : merendam jaringan secara berkesinambungan dalam
urutan-urutan perendaman berikut ini :
a. Etanol 70% selama 2 jam
b. Etanol 80% selama 2 jam
c. Etanol 90% selama 2 jam
d. Etanol absolut selama 2 jam
e. Larutan Xylol selama 2 jam
f. Larutan Xylol selama 2 jam
Tujuan dari melakukan proses dehidrasi ini adalah untuk
menghilangkan kadar air yang terdapat dalam jaringan.
3. Proses embedding : jaringan direndam di dalam paraffin cair bersuhu
600C dan dimasukkan ke dalam wadah pencetak. Seluruh jaringan
haruslah terendam dalam paraffin, lalu paraffin dibiarkan membeku
sehingga setelah paraffin dikeluarkan dari cetakan, terbentuklah blok
paraffin yang selanjutnya disimpan dalam suhu -200C sebelum
dilakukan pemotongan.
Blok paraffin dipotong dengan menggunakan alat pemotong
microtome yang sudah diatur ketebalan pemotongannya adalah sebesar
3-4 μm. Setelah berhasil mendapatkan potongan yang sesuai, taruh
irisan tersebut di atas permukaan waterbath yang bersuhu 460C.
Setelah itu, irisan diletakkan di atas kaca objek yang sebelumnya
sudah diolesi albumin dan diletakkan pada suhu 600C.
Kaca objek yang sudah berisi irisan jaringan tadi, selanjutnya
dilakukan proses pewarnaan dengan merendam kaca objek secara
terus-menerus dalam larutan dengan urutan seabagai berikut :
a. Larutan Xylol selama 3 menit
b. Larutan Xylol selama 3 menit
c. Etanol absolut selama 3 menit
d. Etanol absolut selama 3 menit
e. Etanol 90% selama 3 menit
f. Etanol 80% selama 3 menit
g. Bilas dengan aquades selama 1 menit

49
h. Larutan Hematoksilin sealama 6-7
i. Bilas dengan aquades selama 1 menit
j. Alkaline selama 1 menit
k. Aquades selama 1 menit
l. Larutan Eosin selama 1-5 menit
m. Bilas dengan aquades selama 1 menit
n. Etanol 80% 10 celupan
o. Etanol 90% 10 celupan
p. Etanol absolut pertama 10 celupan
q. Etanol absolut kedua selama 1 menit
r. Larutan Xylol selama 3 menit
s. Larutan Xylol selama 3 menit
t. Larutan Xylol selama 3 menit
Setelah itu kaca objek diangkat dan ditetes dengan Canada Balsam
kemudian ditutup dengan kaca penutup. Sediaan siap untuk diamati di
bawah mikroskop.52,53
3.11.6 Pengamatan Histopatologi
Setelah proses pembuatan sediaan preparat selesai, tahap selanjutnya
adalah pengamatan preparat untuk mengevaluasi pertumbuhan epitel
setelah dilakukannya berbagai perlakuan terhadap tiap-tiap kelompok.
Preparat diamati menggunakan mikroskop Olympus CX 41 dengan
perbesaran 40 kali lensa objektif dan dilakukan pemotretan sebanyak 10
lapang pandang pada tiap preparat. Setelah seluruh preparat sudah diambil
gambarnya kemudian dilakukanlah penghitungan dan pengamatan
terhadap Ketebalan lapisan epitel yang terbentuk. Pengamatan dilakukan
dengan aplikasi ImageJ dengan cara :
1. Buka aplikas ImageJ
2. Klik File pada menubar
3. Klik Open dan masukkan file foto yang ingin dievaluasi
4. Setelah file terbuka, klik tombol Straight pada menu di toolbar.
5. Buatlah garus lurus persis sepanjang penggaris yang terdapat pada
bagian kanan bawah foto preparat

50
6. Klik Analyze pada menubar kemudian klik Set Scale
7. Ketik ukuran panjang penggaris yang terdapat pada foto preparat pada
kolom Known Distance, dalam penelitian ini adalah 40. Selanjutnya,
ketik satuannya dalam kolom Unit of Length, dalam penelitian ini
satuan yang digunakan adalah mikro meter.
8. Klik OK
9. Buatlah kembali garis lurus sepanjang ketebalan lapisan re-epitelisasi
epidermis yang hendak dievaluasi
10. Klik Analyze pada menubar kemudian pilih Measure
11. Kemudian akan muncul window baru dengan judul Result. Pada
penelitian ini data yang digunakan adalah yang terdapat pada kolom
Length
12. Lakukan langkah 1 s/d 11 setiap kali akan mengukur ketebalan lapisan
re-epitelisasi epidermis
13. Apabila diperlukan, halaman Result dapat disimpan dengan cara klik
File kemudian pilih Save
Pada penelitian ini perhitungan tebal lapisan re-epitelisasi dilakukan pada
sepuluh lapang pandang, yaitu pada masing-masing ujung luka, daerah
transisi (daerah dengan epitel dan tanpa epitel) dan pusat luka. Kemudian
dari sepuluh hasil tersebut akan dilakukan perhitungan reratanya.
3.12 Manajemen Analisis Data Pembentukan Jaringan Epitel
Dalam penelitian ini, dilakukan eksperimen langsung terhadap luka bakar
tikus Sprague dawley yang diberikan pemberian ekstrak daun binahong
(Anredera cordifolia (Tenore) Steenis) secara topikal melalui salep
maupun per oral. Setelah dilakukan penghitungan nilai rata-rata dari
ketebalan re-epitelisasi, kemudian data diolah dengan menggunakan
program SPSS versi 16.0
3.13 Etika Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini telah disetujui oleh Komisi Etik Penelitian
Kesehatan FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hewan coba sebanyak
32 ekor tikus Sprague dawley diberi perlakuan yang selayaknya dengan

51
memberikan makan dan minum sesuai kebutuhnnya dan segera diisi ulang
bila ada salah satu atau keduanya habis. Hewan diletakkan di dalam
kandang. Satu kandang terdiri dari dua tikus yang diberi sekat antar
keduanya untuk menghindari adanya pertengkaran atau kerancuan
penelitian akibat berinteraksinya mereka satu sama lain. Setelah diberikan
perlakuan selama 5 hari, maka pada hari ke-6 dilakukan terminasi dengan
menggunakan eter. Terminasi dilakukan agar tikus tidak menderita saat
pengambilan jaringan dilakukan. Jaringan kulit yang berhasil diambil,
dibawa ke laboratorium Patologi Anatomi Cito, Depok untuk dilakukan
pembuatan preparat.

52
BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil
Tikus yang telah diberikan intervensi plat besi panas yang suhunya
mencapai 99oC pada kulit punggung selama 30 detik, akan membentuk
luka bakar derajat II yang dibuktikan dengan GAMBAR 4.1
GAMBAR 4.1 Sediaan Luka Bakar Derajat II perbesaran10x
Luka Bakar derajat II atau partial thickness burn wound ditandai dengan
kedalaman luka bakar yang tidak mencapai hipodermis. Pada gambar 4.1 terlihat
struktur otot dan pembuluh darah masih utuh.
Luka bakar yang sudah terbentuk kemudian diberi perlakuan selama lima
hari dan dilakukan terminasi pada hari ke-enam untuk dapat dilakukan
pengambilan kulit. Kulit lalu dibuat menjadi sediaan preparat dan dipoles dengan
menggunakan pewarnaan Hematoksilin-Eosin dan dianalisa di bawah mikroskop,
sehingga didapatkan hasil sebagai berikut :

53
GAMBAR 4.2 Gambar mikroskopik P1, P2, P3, K+ dan K- dengan perbesaran 40x. Gambar panah adalah salah satu daerah pengukuran
Untuk mendapatkan data ketebalan lapisan re-epitelisasi digunakan
aplikasi imageJ v. 1.50i. Pengukuran ketebalan lapisan epitel dilakukan pada tepi
tiap luka dengan 13 titik pengukuran yang kemudian dirata-ratakan. Hasil
pengukuran ketebalan re-epitelisasi masing-masing perlakuan disajikan dalam
bentuk grafik sebagai berikut :
P2 P1
P3 K+
K-

54
TABEL 4.1 Data Rerata Ketebalan Re-epitelisasi :
Keterangan :
P1 : Perlakuan 1, pemberian Salep Ekstrak Daun Binahong 40%
P2 : Perlakuan 2, pemberian Ekstrak Binahong Oral
P3 : Perlakuan 3, pemberian Salep Ekstrak Daun Binahong 40% dan Ekstrak
Binahong Oral
K+ : Kontrol Positif, pemberian Silver Sulfadiazin
K- : Kontrol Negatif, pemberian Basis Salep
Gambar 4.3 Grafik Rerata Ketebalan Re-epitelisasi P1, P2, P3, K+ dan K-
Berdasarkan data yang telah disajikan, didapatkan sebuah kesimpulan,
bahwa pada P1 atau perlakuan 1 yaitu perlakuan pemberian salep ekstrak daun
binahong konsentrasi 40% memiliki ketebalan re-epitelisasi paling tebal dengan
rata-rata ketebalanya adalah 43.45 μm. Sedangkan P2 atau perlakuan 2 yaitu
perlakuan pemberian ekstrak daun binahong secara oral memilki rata-rata
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
P1 P2 P3 K+ K-
Rerata Ketebalan epitel μm
Perlakuan
Rerata Re-epitelisasi Kulit
Perlakuan
PERLAKUAN N RERATA
P1 5 43.45 P2 5 28.46 P3 5 31.07 K+ 5 34.52 K- 5 41.13

55
ketebalan lapisan re-epitelisasi terendah dengan rata-rata ketebalannya adalah
28.46 μm.
Data yang didapat dari hasil pengukuran dengan menggunakan ImageJ
kemudian dianalisa. Dalam uji homogenitas dengan metode Levene’s test
didapatkan angka sebesar 0.250 atau p > 0.05 yang berarti variasi populasi/data
adalah identik. Selanjutnya, dilakukan uji normalitas dengan menggunakan
metode Shapiro-Wilk dan didapatkan angka p > 0.05 yang bermakna bahwa
disribusi data dari kelima kelompok perlakuan adalah normal. Dari kedua hasil
tes tersebut, menyatakan bahwa data yang disajikan tergolong normal
distribusinya dan homogen, maka selanjutnya dilakukanlah uji One Way Anova
untuk menentukan kebermaknaan masing-masing kelompok perlakuan.
Tabel 4.2 Hasil Analisis Data dengan metode One Way Anova :
Perlakuan N Mean Standar Deviasi
(P Value 0.05 ; CI 95% )
P1 5 43.44 17.08 0.397 P2 5 28.46 3.85 P3 5 31.07 8.20 K+ 5 34.51 22.46 K- 5 41.13 9.06
Setelah dilakukan uji One Way Anova didapatkan angka sebesar 0.397 atau p >
0.050 yang artinya tidak terdapat perbedaan bermakna dari masing-masing
kelompok data.
4.2 Pembahasan
Pada penelitian ini didapatkan hasil, bahwa luka bakar yang dilakukan
intervensi dengan menggunakan salep ekstrak daun binahong menghasilkan
lapisan re-epitelisasi lebih tebal (rata-rata ketebalan re-epitelisasi = 43.44 μm)
dibandingkan dengan kelompok perlakuan lain (p>0.05). Hal ini disebabkan
karena adanya pengaruh zat aktif pada binahong, yang tidak terdapat pada
kelompok kontrol. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Astuti, 2011, senyawa
fitokimia terbanyak yang dapat ditemukan dalam tanaman binahong adalah
saponin, senyawa ini banyak ditemukan di bagian umbi dan daun.14 Pada
penelitian lain disebutkan bahwa saponin dapat merangsang proliferasi sel

56
epidermal serta mempengaruhi percepatan migrasi keratinosit ke daerah yang
mengalami cedera. Hal ini tentu berpengaruh pada percepatan re-epitelisasi luka.54
Senyawa lain yang dapat mempengaruhi aktivasi keratinosit epidermis
adalah asam oleanat dan asam ursolic yang keduanya juga terdapat dalam tanaman
binahong. Kedua senyawa ini bekerja merangsang diferensiasi keratinosit melalui
aktivasinya terhadap PPAR (peroxisome proliferation-activated receptor)-α.55
Sehingga terbukti bahwa adanya zat aktif pada binahong membuatnya memiliki
kemampuan untuk mengoptimalisasikan proses re-epitelisasi luka.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa K- yaitu perlakuan pemberian
basis salep pada luka, menghasilkan hasil yang lebih baik (rata-rata ketebalan re-
epitelisasi = 41.13μm) dibandingkan dengan perlakuan K+ yang diberi basis krim
(rata-rata ketebalan re-epitelisasi = 34.51 μm). Hal ini disebabkan karena adanya
kandungan basis salep berupa Adeps lanae dan Vaselline. Keduanya berperan
dalam menjaga kelembaban kulit, dibanding krim yang mengandung lebih sedikit
minyak sehingga lebih mudah untuk dieliminasi dari permukaan kulit dengan
bantuan air. Vaselin putih berasal dari minyak bumi, sulit untuk dihilangkan dari
permukaan kulit dengan menggunakan air, sehingga vaselin dapat membantu
mempertahankan kelembaban permukaan kulit41,43 Adeps lanae atau Lanolin
merupakan basis serap yang terbuat dari bulu domba, terdiri dari emulsi air dalam
minyak yang mengandung unsur air sebanyak 25% hingga 30%. Kombinasi
antara adeps lanae dan lanolin akan menghasilkan suatu formula yang dapat
membantu menjaga hidrasi luka, sehingga luka terjaga kelembabannya41,42,43
Prinsip-prinsip kelembaban luka untuk membantu proses percepatan
penyembuhan luka sudah diterapkan dalam pembalutan luka / wound dressing.56
Keadaan lembab/ moist dibutuhkan dalam proses penyembuhan luka. Kelembaban
dapat merangsang berbagai growth factor yang terkandung dalam cairan luka
yang tertahan akibat kondisi lembab. Keuntungan dari menjaga keseimbangan
kelembaban luka diantaranya dapat mempermudah migrasi sel epidermal,
sehingga mempercepat proses epitelisasi. Hal ini disebabkan, cairan luka yang
dipertahankan dalam keadaan lembab dapat merangsang aktivitas keratinosit.
Pada K+ yaitu perlakuan pemberian krim Sulfadiazin, ketebalan lapisan re-
epitelisasi tidak sebaik sebagaimana yang ada pada K-. Hal ini disebabkan karena

57
krim lebih mudah dieliminasi dengan air dibanding salep, karena krim lebih
banyak memiliki kandungan air dibanding salep yang kandungan minyaknya
mendominasi komposisinya. Selain itu, Silver sulfadiazin tidak memiliki suatu zat
aktif yang secara langsung mempengaruhi re-epitelisasi kulit.
Selanjutnya kelompok P3 mendapatkan hasil rata-rata ketebalan re-
epitelisasi adalah 31.07 μm. Kelompok P3 diberi perlakuan oral dan salep,
perlakuan ini mendapat urutan kedua diantara P1 dan P2. Senyawa fitokimia
terbanyak yang terdapat dalam binahong yaitu saponin dapat mempengaruhi
ketebalan re-epitelisasi pasca luka bakar, namun pada pemberian oral,
penyerapannya melalui saluran pencernaan kurang maksimal. Hal ini disebabkan
karena saponin memlikiki masa molekul yang besar (>500 Da), memiliki ikatan
yang kuat dengan hidrogen, serta fleksibilitas molekulnya yang tinggi (>10)
sehingga menyebabkan saponin impermiabel terhadap membran brush border.
Cepatnya eksresi oleh asam empedu juga merupakan faktor lain yang
menyebabkan rendahnya bioavailabilitas saponin.57 Namun beberapa jenis
saponin seperti ginsenosides Ra3, Rb1, Rc, and Rd, dan dioscin dieksresikan
perlahan oleh asam empedu, sehingga memiliki waktu paruh yang lebih baik (7-
25 jam pada tikus).57 Hal ini juga yang mejadi alasan, mengapa perlakuan P2
yaitu pemberian binahong melalui oral saja, tidak cukup baik untuk meningkatkan
ketebalan lapisan re-epitelisasi pasca luka bakar, ketebalan lapisan re-epitelisasi
P2 adalah 28.46 μm, terendah dibanding perlakuan P1 dan P3.
Hasil penelitian menujukkan hasil yang tidak signifikan antara pemberian
binahong melalui topikal (salep), oral atau keduanya, serta pada perlakuan kontrol.
Artinya, tidak terdapat perbedaan yang berarti pada pemberian binahong melalui
oral, salep atau oral dan salep sehingga berpengaruh terhadap ketebalan lapisan
re-epitelisasi pasca luka. Hal ini mungkin disebabkan karena ketidakseragaman
dalam volume pemberian sediaan topikal pada tikus.

58
Keterbatasan Penelitian
1. Tidak meneliti jenis saponin yang terkandung di dalam binahong, apakah
termasuk saponin yang cepat diekskresikan atau tidak
2. Tidak memberikan volume pengolesan salep sama besar, sehingga menjadi
faktor bias pada penelitian ini
3. Luka bakar tidak dilakukan dressing sehingga tidak mengoptimalkan
perawatan luka bakar

59
BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Pada penelitian ini, kesimpulan yang diperoleh adalah :
1. Pemberian ekstrak daun binahong berpengaruh terhadap re-epitelisasi
kulit pasca luka bakar derajat II tikus Sprague dawley
2. Terdapat perbedaan yang tidak bermakna antar kelompok (p>0.05)
3. Kelompok yang hanya diberikan intervensi salep, memiliki rerata
tertinggi terhadap ketebalan lapisan re-epitelisasi dibanding kelompok
perlakuan yang diberikan kombinasi salep-oral
4. Pada pemberian ekstrak daun binahong melalui oral dengan dosis 100
mg/kgBB memiliki hasil ketebalan lapisan re-epitelisasi terendah dari
seluruh perlakuan.
5.2 Saran
1. Dapat dilakukan penelitian dosis ekstrak binahong oral yang efektif
untuk mempercepat pertumbuhan epitel pasca luka bakar
2. Peneliti selanjutnya dapat memberikan perawatan luka bakar yang
optimal dengan memberikan dressing pada luka bakar tikus
3. Selanjutnya dapat diteliti jenis saponin yang terkandung dalam
binahong

60
DAFTAR PUSTAKA
1. Martina N, Wardhana A. Mortality Analysis of Adult Burn Patients. J Plast
Rekostruksi. 2013:96-100.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Riset Kesehatan Dasar
(RISKESDAS) 2013. Lap Nas 2013. 2013. doi:1 Desember 2013.
3. Salimi YK, Bialangi N. Kajian Senyawa Antioksidan Dan Antiinflamasi
Tumbuhan Obat Binahong (Andredera cordifolia(Ten.) Steenis) Asal
Gorontalo. J Chem Inf Model. 2014. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
4. Wahyuni NR. Uji efektivitas salep ekstrak etanol daun binahong (Anredera
cordifolia (Ten) Steenis) terhadap kesembuhan luka sayatan pada mencit
(Mus Musculus). IJMS. 2014;1(1).
5. Muhlisah F. Temu-Temuan Dan Empon-Empon Budidaya Dan
Manfaatnya. Yogyakarta: Kanisus; 2005.
6. Vivian-Smith G, Lawson BE, Turnbull I DP. The Biology of Australian
weeds 46. Anredera cordifolia (Ten.) Steenis. Plant Prot Q. 2007;22(1):2-
20.
7. Selawa W, Runtuwene MRJ CG. Kandungan flavonoid dan kapasitas
antioksidan total ekstrak etanol daun binahong [anredera
cordifolia(ten.)steenis]. J Ilm Farm. 2013;2.
8. Sri MA. Skrinning Fitokimia dan Uji Aktivitas Antibiotika Ekstrak Etanol
Daun, Batang, Bunga dan Umbi Tanaman Binahong (Anredera cordifolia
(Ten) Steenis). 2012.
9. Syifa QA. Pengaruh Salep Ekstrak Daun Binahong (Anredera Cordifolia
(Tenore) Steenis) Terhadap Pembentukan Jaringan Granulasi Pada Luka
Bakar Tikus Sprague Dawley (Studi Pendahuluan Lama Paparan Luka
Bakar 30 Detik Dengan Plat Besi). Tangerang Selatan; 2013.
10. Ansel CH. Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi Jakarta. UI-Press; 2008.

61
11. Sukandar EY, Fidrianny I, Adiwibowo LF. Efficacy of ethanol extract of
anredera cordifolia (ten) steenis leaves on improving kidney failure in rats.
Int J Pharmacol. 2011;7(8):850-855. doi:10.3923/ijp.2011.850-855.
12. Sukandar EY, Qowiyyah A, Larasari, Lady. Effect of Methanol Extract
Hearleaf Madeiravine (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) Leaves on Blood
Sugar in Diabetes Mellitus Model Mice. J Med Planta. 2011;1(4).
13. Suseno M. Sehat Dengan Daun. Yogyakarta: Buku Pintar; 2013.
14. Astuti SM, Sakinah A.M M, Andayani B.M R, Risch A. Determination of
Saponin Compound from Anredera cordifolia (Ten) Steenis Plant
(Binahong) to Potential Treatment for Several Diseases. J Agric Sci.
2011;3(4):p224. doi:10.5539/jas.v3n4p224.
15. BPOM. Taksonomi Koleksi Tanaman Obat Kebun Tanaman Obat
Citeureup. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia; 2008.
16. Cronquist A. An Integrated System of Classification of Flowering Plants.
New York: Columbia Univesity Press; 1981.
17. Suci A, Lily L MFD. Khasiat daun binahong (Anredera cordifolia (Ten.)
Steenis) terhadap pembentukan jaringan granulasi dan reepitelisasi
penyembuhan luka terbuka kulit kelinci. e-Biomedik (eBM). 2013;1:914-
919.
18. Sophors P, Kim YM, Seo GY, et al. A synthetic isoflavone, DCMF,
promotes human keratinocyte migration by activating Src/FAK signaling
pathway. Biochem Biophys Res Commun. 2016;472(2):332-338.
doi:10.1016/j.bbrc.2016.02.106.
19. Merk-Turk F. Saponins versus plant fungal pathogens. J Cell Mol Biol.
2006;5:13-17.
20. Silverthorn DU. Human Physiology an Integrated Approach. 5th ed. San
Francisco: Pearson Benjamin Cummings; 2010.

62
21. Mescher AL. Histologi Dasar Junqueira Teks & Atlas. Jakarta: EGC; 2011.
22. Goldsmith LA. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8th ed.
United States: Mc Graw Hill; 2012.
23. Sherwood L. Human Physiology from Cells to System. 7th ed. USA:
Cengange; 2010.
24. Doherty MG. Current Surgical Diagnosis and Treatment. 12th ed. USA:
Mc Graw Hill; 2003.
25. Grace PA. At a Glance Ilmu Penyakit Bedah. 3rd ed. Jakarta: Erlangga;
2006.
26. World Health Organization. Global Health Estimates 2014 Summary
Tables: Deaths by Cause, Age and Sex 2000-2012.
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/. Published 2014.
Accessed October 2, 2016.
27. World Health Organization W. World report on child injury prevention.
Geneva, Switz. 2008:1-212. doi:10.1136/ip.2007.018143.
28. Shehan H PD. Pathophysiology and types of burns. BMJ. 2004:1427-1429.
29. Silbernagl S, Lang F. Color Atlas of Pathophysiology. New York: Thieme;
2000. doi:10.1213/ANE.0b013e3181e627d4.
30. Netter FH, Craig J a, Perkins J. Atlas of Neuroanatomy and
Neurophysiology. Special. Entacapone tablets; 2002.
doi:10.1093/brain/awf218.
31. Hans L, Badali MA, Carr D, Cass D. The ABC’S of Emergency Medicine.
12th ed. Toronto: University of Toronto; 2012.
32. Cline DM. Tintinali’s Emergency Medicine Manual. 7th ed. New York: Mc
Graw Hill; 2012.
33. World Health Organization. WHO Surgical Care at the District Hospital

63
Malta.; 2003.
34. Mulholland MW, Marier RV et al. Greenfield’s Surgery Scientific
Principles and Practice. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins; 2006.
35. Kumar V. Buku Ajar Patologi Robbins. 7th ed. Jakarta: EGC; 2007.
36. Rubin E. Essential of Rubin’s Pathology. 5th ed. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins; 2009.
37. Fuller FW. The side effects of silver sulfadiazine. J Burn Care Res.
2009;(3):464-470. doi:10.1097/BCR.0b013e3181a28c9b.
38. PubChem Compound Database. [Online]. National Center for
Biotechnology Information.
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/441244. Accessed September
26, 2016.
39. Yasti et al. Guideline and Treatment Algorithm for Burn Injuries. Ulus
Travma Acil Cerrahi Derg. 2015;21.
40. Hamzah M. Dermato-Terapi. In: Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin. 7th ed.
Jakarta: Badan Penerbit FK UI; 2015:426-429.
41. Kementrian Kesehatan RI. Farmakope Indonesia. Jakarta: Kementrian
Kesehatan RI; 2014.
42. Aulton. Transdermal Drug Delivery. In: Pharmaceutics The Science of
Dosage Form Design. ; 2002.
43. Lachman. Teori Dan Praktek Farmasi Industri. 3rd ed. Jakarta: UI Press;
1994.
44. Ansel H.C., Popovic, N.G., Allen LV. Pharmaceutical Dosage From and
Drug Delivery System. 9th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins; 2011.
45. Airf A SU. Farmakologi Dan Terapi Jakarta. Jakarta: UI Press; 1995.

64
46. Conn PM. Source Book of Models for Biomedical Research. New Jersey:
Humana Press; 2008.
47. National Research Council of The National Academies. Guide for the Care
and Use of Laboratory Animals. Washington, DC: National Academy
Press; 2011.
48. Salasanti CD, Sukandar EY, Fidrianny I. Acute and sub chronic toxicity
study of ethanol extract of anredera cordifolia (Ten.) v. steenis leaves. Int J
Pharm Pharm Sci. 2014;6(5):348-352.
49. Paju N, Yamlean PVY, Kojong N. Uji efektivitas salep ekstrak daun
binahong ( Anredera cordifolia ( Ten .) Steenis ) pada kelinci ( Oryctolagus
cuniculus ) yang terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus. J Ilm Farm -
UNSRAT. 2013;2(1):53-54.
50. Arum W, Khoiru U ST. Karakterisasi Karboksimetil Selulosa (CMC) dari
Enceng Gondok (Eichornia crassipes (Mart) Solms). Indo J Chem.
2005:228-231.
51. Danielle dos STP, Maria HM NT. Methodology Report Development of
Animal Model for Studying Deep Second-Degree Thermal Burns. J
Biomed Biotechnol. 2012.
52. Muntiha. Teknik Pembuatan Preparat Histopatologi Dari Jaringan Hewan
Dengan Pewarnaan Hematoksilin Dan Eosin. Bogor: Balai Penelitian
Veteriner; 2011.
53. Waheed U. Histotechniques Laboratory Techniques in Histopathology: A
Handbook for Medical Technologists. Saarbrücken: Lap Lambert
Academic Publ; 2012.
54. Kim YS, Cho I-H, Jeong M-J, et al. Therapeutic effect of total ginseng
saponin on skin wound healing. J Ginseng Res. 2011;35(3):360-367.
doi:10.5142/jgr.2011.35.3.360.
55. Lim Sk, Hong SP JS. Simultaneous effect of ursolic acid and oleanolic acid

65
on epidermal permeability barrier function and epidermal keratinocyte
differentiation via peroxisome proliferator-activated receptor-α. J
Dermatol. 2007;34:625-634.
56. Johan PE, Junker RA. Clinical impact upon wound healing and inflamation
in moist, wet, and dry environments. Adv Wound Care. 2013;2:348-356.
57. Yu K CF. Absorbtion, disposition and pharmacokinetics of saponin from
Chinese medicinal herbs: what do we know and what do we need to know
more? Curr Drug Metab. 2012;1:577-598.

66
LAMPIRAN
Lampiran 1
Surat Keterangan Hasil Determinasi/Identifikasi Bahan Uji
Gambar 6.1 Surat Keterangan Hasil Determinasi/Identifikasi Bahan Uji

67
Lampiran 2
Surat Keterangan Eksraksi Bahan Uji
Gambar 6.2 Surat Keterangan Hasil Determinasi/Identifikasi Bahan Uji

68
Lampiran 3
Surat Profile Bahan Uji
Gambar 6.3 Surat Profile Bahan Uji

69
Lampiran 4
Dokumentasi Penelitian
Gambar 6.4
Pemberian ekstrak binahong secara oral
Gambar 6.5 Pemberian Salep Ekstrak Daun
Binahong
Gambar 6.6 Proses
Pencukuran Rambut Tikus
Gambar 6.7 Proses Pembuatan Luka Bakar dengan penekanan yang seragam (1400 mg)

70
Gambar 6.8 Proses
Pengambilan Jaringan Kulit
Gambar 6.9 Preparat Kulit yang Siap untuk
Dianalisis
Gambar 6.10 Proses Analisa Preparat Jaringan Kulit dengan Mikroskop Olympus CX 41

71
Gambar 6.11 Proses Homogensisai Aquades dengan
CMC Na
Gambar 6.12 Proses Homogensisai Basis Salep dengan Ekstrak Daun Binahong
Gambar 6.13 Proses Pembuatan Luka Bakar dengan Menggunakan plat
besi 4x2 di atas timbangan

72
Lampiran 5
Riwayat Penulis
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Raissa Pramudya Wardhani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 02 Juni 1995
Agama : Islam
Alamat : Jalan Alpukat II C 17/d no. 1 Pandau Permai,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Email : [email protected]
Riwayat Pendidikan:
2001-2007 : SD Negeri 001 Sukajadi, Pekanbaru
2007-2010 : SMP Negeri 4 Pekanbaru
2010-2013 : SMA Negeri 1 Pekanbaru
2013 - sekarang : Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter,
FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta