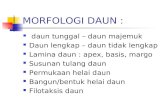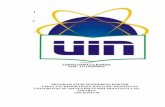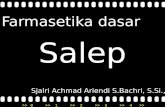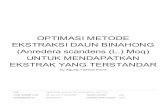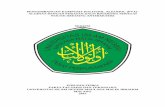PENGARUH PEMBERIAN SALEP EKSTRAK DAUN BINAHONG … · 2015. 1. 29. · PENGARUH PEMBERIAN SALEP...
Transcript of PENGARUH PEMBERIAN SALEP EKSTRAK DAUN BINAHONG … · 2015. 1. 29. · PENGARUH PEMBERIAN SALEP...

PENGARUH PEMBERIAN SALEP EKSTRAK DAUN
BINAHONG (Anredera cordifolia (Tenore) Steenis)
TERHADAPRE-EPITELISASI PADA LUKA BAKAR
TIKUS Sprague dawley (Studi Pendahuluan Lama Paparan Luka Bakar 30 Detik dengan
Plat Besi)
Laporan Penelitian ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
SARJANA KEDOKTERAN
OLEH :
FARAH NABILLA RAHMA
NIM : 1111103000035
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1435 H/2014 M

ii

iii

iv

v
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah
memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga
selalutercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya. Laporan
penelitian ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya karena adanya dukungan,
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis
mengucapkan terima kasih kepada :
1. Prof. Dr (hc). dr. M.K Tadjudin, Sp. And selaku Dekan FKIK UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. dr. Witri Ardini, M. Gizi, Sp.GK selaku Ketua Program Studi Pendidikan
Dokter FKIKUN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Rr. Ayu Fitri Hapsari, M.Biomed selaku pembimbing 1yang telah meluangkan
waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyusun dan
menyelesaikan laporan penelitian ini.
4. dr. Dyah Ayu Woro, M. Biomed selaku pembimbing 2 yang telah
mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis dalam
menyusun dan menyelesaikan laporan penelitian ini.
5. dr. Flori Ratnasari, Ph. D selaku penanggung jawab modul riset yang selalu
memberikan arahan dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan
penelitian ini.
6. Papa dan mama atas limpahan kasih sayang yang telah diberikan,
pengorbanan tanpa pamrih, dukungan yang tidak pernah putus, doa-doa yang
selalu dipanjatkan, serta dorongan dan semangat kepada penulis selama
melaksanakan penelitian. Terima kasih atas segala kebaikan dan pelajaran
hidup yang luar biasa hingga penulis telah beranjak dewasa.
7. Kakak Azka atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada
penulis, almarhum Aa Fikri yang telah menjadi teladan yang baik bagi penulis
selama hidupnya, serta Firda yang senantiasa menghibur penulis.

vi
8. Pusat Konservasi Tumbuhan–Kebun Raya Bogor, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) yang telah bersedia membantu dalam hal determinasi
tumbuhan.
9. Balai Tanaman Obat dan Aromatik (BALITRO) yang telah membantu dalam
hal ekstraksi bahan.
10. iRatCo, Institut Pertanian Bogor yang telah membantu dalam hal penyediaan
hewan coba.
11. Ibu Nurlaely, M. Biomed, Ph. D selaku PJ Laboratorium Animal House, dr.
Ahmad Azwar Habibie selaku PJ Laboratorium Anatomi dan dr. Nurul
Hiedayati, Ph.D selaku PJ Laboratorium Farmakologi yang telah memberikan
izin penggunaan laboratorium.
12. Mbak Dina, Mas Rachmadi, Mas Pandji, Mas Manaf dan laboran-laboran lain
yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.
13. Teman-teman satu kelompok penelitian, Syifa, Asmie, Seflan dan Audi.
Terimakasih atas kerja sama, semangat pantang menyerah, serta dukungan
selama ini. Senang sekali dapat bekerja bersama dengan kalian.
14. Sahabat-sahabat Cunteks, Rissa, Mada, Wulan, Anzak, Silmi, dan Riwi.
Terimakasih atas semangat, dukungan, perhatian, kebersamaan, serta kasih
sayang selama ini. Terimakasih karena selalu ada untuk penulis disaat senang
maupun sedih.
15. Teman-teman CIMIN, Adit, Bimo, Madina, Tiara, Fahreza, Hanindyo, Faris,
Andhika, Herlina, dan Adichita. Terimakasih atas pengalaman dan
kebersamaan yang tidak akan penulis lupakan.
16. Teman-teman lain yang penulis kenal namun tidak sempat tersebutkan.
Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kata
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan ritik dari berbagai
pihak. Demikian laporan penelitian ini penulis susun, semoga dapat
bermanfaaat dengan baik.
Ciputat, 16 September 2014
Penulis

vii
PENGARUH PEMBERIAN SALEP EKSTRAK DAUN BINAHONG
(Anredera cordifolia (Tenore) Steenis) TERHADAP RE-EPITELISASI
PADA LUKA BAKAR TIKUS Sprague dawley (STUDI PENDAHULUAN
LAMA PAPARAN LUKA BAKAR 30 DETIK DENGAN PLAT BESI)
(ABSTRAK)
Farah Nabilla Rahma
Latar Belakang : Daun binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steenis)
memiliki khasiat sebagai obat tradisional yang dapat mempercepat proses
penyembuhan luka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pemberian salep ekstrak daun binahong terhadap proses re-epitelisasi pada luka
bakar tikus Sprague dawley.Metodologi : Penelitian ini bersifat eksperimental
deskriptif analitik. Subjek penelitian ini menggunakan 25 ekor tikus putih galur
Sprague dawley yang dibagi kedalam lima kelompok yaitu K (-), K (+), dan
kelompok perlakuan yaitu salep ekstrak daun binahong konsentrasi 10% (P1),
20% (P2), dan 40% (P3). Luka bakar dibuat dengan menempelkan plat besi panas
(ukuran 4x2 cm2) selama 30 detik pada bagian punggung bawah tikus. Pemberian
salep dilakukan dua kali sehari selama lima hari. Parameter histologi yang
digunakan adalah ketebalan lapisan re-epitelisasi epidermis yang diamati secara
mikroskopis. Hasil : Pada penelitian ini diperoleh rerata ketebalan lapisan re-
epitelisasi pada kelompok K(-) sebesar 17,33 µm, kelompok P1 sebesar 12,71 µm,
kelompok P2 sebesar 59,61 µm, kelompok P3 sebesar 22,80 µm, dan kelompok K
(+) sebesar 37,32 µm. Hasl uji statistik One Way ANOVA menunjukkan adanya
pengaruh yang bermakna dengan nilai p = 0,006 (p<0,050). Simpulan :
Kelompok pemberian salep ekstrak binahong konsentrasi 20% memberikan
pengaruh yang paling besar dalam meningkatkan ketebalan lapisan re-epitelisasi.
Kata Kunci : Binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steenis), Luka Bakar,
Penyembuhan Luka, Re-epitelisasi

viii
THE EFFECT OF BINAHONG (Anredera cordifolia (Tenore) Steenis) LEAF
EXTRACT OINMENT ON RE-EPITHELIALIZATION IN BURN WOUND
Sprague dawley RAT (PRELIMINARY STUDY WITH BURN WOUND
TIME EXPOSURE IN 30 SECONDS USING METAL PLATE)
(ABSTRACT)
Farah Nabilla Rahma
Background : Binahong leaf have efficacy as a traditional medicine that can
accelerate wound healing process. The aim of this research were to study the
effectivity of Binahong extract oinment on re-epithelialization in burn wound
Sprague dawley rat. Method : This research using experimental analytic
descriptive method. The subject in these research were 25 Sprague dawley rats
which divided into 5 groups, namely K (-), K (+), and treatment groups with
concentration 10% (P1), 20% (P2), and 40% (P3) of binahong leaf extract
oinment. Burn wound were made using hot plate (diameter 4x2 cm2) in 30
seconds over lower back. Then surface of wound covered by correspending
oinment twice a day in five days. Histologic parameter used in this research were
thickness of the re-epithelialization layer which miscroscopically examined.
Result : The data showed that average of the thickness of re-epithelialization
layer in group K (-) 17,33 µm, group P1 12,71 µm, group P2 59,61 µm, group P3
22,80 µm, and group K (+)37,32 µm. The results of the One Way ANOVA
statistical test showed a significant effect with p = 0,006 (p<0,050). Conclusion :
Concentration 20% of binahong leaf extract oinment give the highest effect on
enhancing the thickness of re-epithelialization layer.
Key word : Binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steenis), Burn Wound,
Wound healing, Re-epithelialization

ix
DAFTAR ISI
LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN KARYA....................................... ii
KATA PERSETUJUAN PEMBIMBING................................................... iii
LEMBAR PENGESAHAN.......................................................................... iv
KATA PENGANTAR.................................................................................. v
ABSTRAK..................................................................................................... vii
DAFTAR ISI................................................................................................. ix
DAFTAR TABEL......................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR.................................................................................... xiii
DAFTAR LAMPIRAN................................................................................ xiv
BAB 1 PENDAHULUAN............................................................................. 15
1.1. Latar Belakang............................................................................. 15
1.2. Rumusan Masalah........................................................................ 17
1.3. Hipotesis...................................................................................... 17
1.4. Tujuan Penelitian......................................................................... 17
1.4.1. Tujuan Umum............................................................. 17
1.4.2. Tujuan Khusus............................................................ 17
1.5. Manfaat Penelitian....................................................................... 17
1.5.1. Bagi Peneliti................................................................ 17
1.5.2. Bagi Institusi............................................................... 18
1.5.3. Bagi Keilmuan............................................................ 18
1.5.4. Bagi Masyarakat......................................................... 18
1.6. Kerangka Teori............................................................................ 18
1.7. Kerangka Konsep......................................................................... 19
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA................................................................... 20
2.1. Landasan Teori............................................................................. 20
2.1.1. Kulit............................................................................. 20
2.1.2. Binahong..................................................................... 24
2.1.3. Luka Bakar.................................................................. 27
2.1.4. Proses Penyembuhan Luka.......................................... 32

x
2.1.5. Silver Sulfadiazine...................................................... 39
2.1.6. Vaselin Album............................................................. 39
2.1.7. Adeps Lanae................................................................ 39
2.1.8. Tikus Sprague dawley................................................. 40
BAB 3 METODE PENELITIAN................................................................. 41
3.1. Desain Penelitian........................................................................ 41
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian...................................................... 41
3.3.Populasi dan Sampel................................................................... 42
3.4. Variabel Penelitian..................................................................... 42
3.4.1. Variabel Bebas............................................................ 42
3.4.2. Variabel Terikat........................................................... 42
3.5. Alur Penelitian........................................................................... 43
3.6. Cara Kerja Penelitian................................................................. 44
3.6.1. Pembuatan Ekstrak Daun Binahong............................ 44
3.6.2. Pembuatan Basis Salep................................................ 44
3.6.3. Pembuatan Konsentrasi Salep Ekstrak Daun
Binahong.....................................................................
45
3.6.4. Pengujian Sediaan Salep............................................. 45
3.6.5. Etika Penelitian........................................................... 46
3.6.6. Induksi Luka Bakar pada Tikus.................................. 46
3.6.7. Pemberian Sediaan Salep pada Tikus.......................... 47
3.6.8. Eksisi Jaringan Kulit Tikus......................................... 47
3.6.9. Pembuatan Preparat Histopatologi.............................. 47
3.6.10. Pengamatan Preparat Histopatologi............................ 47
3.6.11. Penghitungan Ketebalan Lapisan
Re-epitelisasi...............................................................
48
3.7. Managemen dan Analisis Data................................................... 49
3.8. Definisi Operasional................................................................... 49
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN......................................................... 51
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN......................................................... 59
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................... 60

xi
LAMPIRAN................................................................................................... 64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..................................................................... 70

xii
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1. Hasil Analisis Data Ketebalan Lapisan Re-epitelisasi
Epidermis pada Semua Kelompok Perlakuan........................
54

xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Anatomi Kulit.................................................................... 21
Gambar 2.2. Tanaman Binahong............................................................ 27
Gambar 2.3. Derajat Luka Bakar........................................................... 33
Gambar 2.4. Proses Re-epitelisasi.......................................................... 37
Gambar 2.5. Proses Penyembuhan Luka................................................ 40
Gambar 4.1. Gambaran Makroskopik Luka Bakar pada
Kulit Tikus.......................................................................
52
Gambar 4.2. Sampel Jaringan Kulit dengan Pewarnaan HE pada
Pembesaran 100x..............................................................
53
Gambar 4.3. Grafik Rerata Ketebalan Lapisan Re-epitelisasi............... 53
Gambar 6.1. Surat Keterangan Tikus Sehat........................................... 64
Gambar 6.2. Surat Determinasi Tanaman Binahong.............................. 65
Gambar 6.3. Surat Ekstraksi Daun Binahong........................................ 66
Gambar 6.4. Pembuatan Salep Ekstrak Daun Binahong........................ 67
Gambar 6.5. Pencukuran Rambut pada Punggung Tikus....................... 67
Gambar 6.6. Proses Randomisasi........................................................... 67
Gambar 6.7. Pemanasan Plat Besi........................................................ 67
Gambar 6.8. Inhalasi Eter..................................................................... 67
Gambar 6.9. Induksi Luka Bakar......................................................... 67
Gambar 6.10. Tikus Setelah Diinduksi Luka Bakar............................... 68
Gambar 6.11. Pemberan Salep Ekstrak Daun Binahong........................ 68
Gambar 6.12. Gambaran Makroskopik Luka Bakar pada Tikus............ 68
Gambar 6.13. Eksisi Jaringan Kulit Tikus............................................. 68
Gambar 6.14. Fiksasi Jaringan Kulit Tikus menggunakan
Formalin 10%..................................................................
68
Gambar 6.15. Proses Pembuatan Preparat Histopatologi....................... 68
Gambar 6.16. Hasil Jadi Preparat Histopatologi.................................... 69
Gambar 6.17. Pengamatan Preparat Histopatologi................................ 69

xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Keterangan Tikus Sehat................................................. 64
Lampiran 2 Surat Determinasi Tanaman Binahong................................... 65
Lampiran 3 Surat Ekstraksi Daun Binahong.............................................. 66
Lampiran 4 Proses Penelitian..................................................................... 67

15
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Luka bakar sampai saat ini masih menjadi salah satu cedera yang
menimbulkan mordibitas dan mortilitas yang tinggi di masyarakat. Insidensi
nya paling tinggi terjadi di lingkungan rumah tangga dimana derajat II
menjadi yang paling sering terjadi,1 namun derajat III yang paling berpeluang
menimbulkan cacat yang lebih berat karena integritas kulit yang rusak lebih
parah bahkan bisa sampai membatasi aktivitas sosial penderitanya pasca
kejadian sehingga dapat menambah beban mental penderitanya. Di Indonesia
menurut data RSUPN Cipto Mangunkusumo pada tahun 1998 terdapat 107
kasus luka bakar atau 26,3% dari seluruh kasus bedah plastik yang dirawat.
Dari kasus tersebut terdapat lebih 40% merupakan luka bakar derajat II-III
dengan angka kematian 37,38%.1,2
Penanganan kasus luka bakar dibutuhkan sesegera mungkin untuk
mencegah terjadinya komplikasi yang ringan sampai yang berat seperti syok
hipovolemik dan sepsis. Namun sering kali pengobatan konvensional untuk
kasus luka bakar membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga selain
kerugian dari segi fisik dan mental, penderita luka bakar juga mengalami
kerugian dari segi materi.3
Untuk mengurangi beban materi untuk pengobatan penyakit tertentu,
di Indonesia kini sedang banyak berkembang pengobatan tradisional yang
memanfaatkan tanaman yang diyakini memiliki khasiat sebagai obat, termasuk
salah satunya pemanfaatan tanaman untuk pengobatan luka bakar. Kondisi
tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya kembali ke alam (back to nature) dengan memanfaatkan bahan-
bahan alami. Selain itu, pemerintah melalui Departemen Kesehatan juga telah
mendukung pengembangan pengobatan tradisional menggunakan tanaman

16
berkhasiat obat melalui dibentuknya Sentra Pengembangan dan Penerapan
Pengobatan Tradisional (Sentra P3T).4
Salah satu tanaman yang 5memiliki khasiat dalam pengobatan luka
bakar adalah Anredera cordifolia (Tenore) Steenis atau yang lebih dikenal
masyarakat dengan tanaman binahong. Menurut masyarakat selain dapat
menyembuhkan luka, tanaman binahong juga dapat digunakan untuk
menyembuhkan diabetes, pembengkakan hati, radang usus, dan
reumatik.Bagian tanaman binahong yang bermanfaat sebagai obat salah
satunya adalah bagian daun.5
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdi Nusa Persada et al
didapatkan hasil bahwa tingkat kesembuhan luka bakar derajat II dengan
pemberian topikal daun binahong tumbuk lebih tinggi dibandingkan hidrogel
pada gambaran makroskopis, namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan
pada gambaran mikroskopis.6
Penelitian lain yang dilakukan oleh Suci Ariani
et al didapatkan hasil bahwa pemberian topikal daun binahong tumbuk pada
luka terbuka kulit kelinci secara makroskopik luka menjadi terlihat lebih kecil
dan kering, sedangkan yang tidak diberi daun binahong terlihat luka masih
dalam dan kemerahan. Sedangkan secara mikroskopik pemberian daun
binahong pada luka membantu penyembuhan luka dengan pembentukan
jaringan granulasi yang lebih banyak dan reepitelisasi terjadi lebih cepat
dibandingkan dengan luka yang tidak diberi daun binahong.7
Berdasarkan uraian diatas serta didukung penelitian sebelumnya yang
menunjukkan adanya pengaruh bermakna pada pemberian daun binahong
topikal terhadap penyembuhan luka bakar, maka sangat menarik dilakukan
penelitian lebih lanjut yang lebih disempurnakan. Antara lain pada penelitian
ini menggunakan sediaan topikal ekstrak daun binahong dalam bentuk salep
untuk memudahkan aplikasinya di kulit dengan berbagi konsentrasi.
Kemudian pengamatan hasil penelitian dilakukan dengan lebih teliti yaitu
secara histopatologis menggunakan parameter kecepatan proses re-epitelisasi
lapisan epidermis dengan cara menilai ketebalannya. Hal tersebut dikarenakan
penyembuhan luka sangat dipengaruhi oleh proses re-epitelisasi, dimana

17
semakin cepat proses re-epitelisasi maka semakin cepat luka tertutup,
sehingga semakin cepat pula penyembuhan luka terjadi.8
1.2. Rumusan Masalah
Bagaimana pengaruh pemberian salep ekstrak daun binahong
(Anredera cordifolia(Tenore) Steenis)pada konsentrasi 10%, 20% dan 40%
terhadap proses re-epitelisasi pada luka bakar dengan lama paparan 30 detik
tikusSprague dawley?
1.3. Hipotesis
Terdapat pengaruh pada penyembuhan luka bakar dengan lama
paparan 30 detik tikus Sprague dawleyakibat pemberian salep ekstrak daun
binahong (Anredera cordifolia(Tenore) Steenis)pada konsentrasi 10%, 20%
dan 40% berupa peningkatan ketebalan lapisan re-epitelisasi.
1.4. Tujuan
1.4.1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui pengaruh pemberian salep ekstrak daun
binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steenis) terhadap proses re-
epitelisasi pada luka bakar dengan lama paparan 30 detik tikus Sprague
dawley.
1.4.2. Tujuan Khusus
Untuk mengetahui ketebalan lapisan re-epitelisasi pada luka bakar
dengan lama paparan 30 detik tikus Sprague dawley antara kelompok yang
diberi salep ekstrak daun binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steenis)
pada konsentrasi 10%, 20% dan 40% .
1.5. Manfaat Penelitian
1.5.1. Bagi Peneliti
Menambah ilmu pengetahuan peneliti dalam hal pengaruh
pemberian ekstrak daun binahong (Anredera cordifolia(Tenore)
Steenis) terhadap proses penyembuhan luka bakar.

18
Mengaplikasikan ilmu mengenai penelitian ilmiah yang
sebelumnya telah dipelajari selama fase preklinik.
1.5.2. Bagi Insitusi
Memberikan kontribusi dalamkemajuan bidang penelitian
ilmiah Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
1.5.3. Bagi Keilmuan
Mendukung penelitian lain di bidang yang sama.
1.5.4. Bagi Masyarakat
Meningkatkan pemahaman masyarakat dan tenaga kesehatan
tentang manfaat daun binahong (Anredera cordifolia(Tenore)
Steenis) sebagai pengobatan alternatif untuk perawatan luka
bakar.
Menambah ilmu pegetahuan mahasiswa kedokteran lain dalam
hal pengaruh pemberian ekstrak daun binahong (Anredera
cordifolia (Tenore) Steenis) terhadap proses penyembuhan luka
bakar.
1.6. Kerangka Teori
Ekstrak daun
binahong
Saponin Flavonoid Asam oleanolik
↑ ekspresi
faktor-faktor
yang berperan
dalam
proliferasi sel
keratinosit
↑ kecepatan
migrasi sel
keratinosit
Menekan reaksi
inflamasi
Antioksidan
Mencegah
kerusakan
sel akibat
radikal bebas
↑ proses re-
epitelisasi
epidermis

19
1.7. Kerangka Konsep
Salep ekstrak
daun binahong
Luka bakar
derajat III
Re-epitelisasi
epidermis
↑ migrasi
keratinosit
↑ proliferasi
keratinosit
↑ ketebalan lapisan
re-epitelisasi
epidermis
↑ kecepatan
penutupan luka
Proses penyembuhan
luka lebih cepat
terjadi

20
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Kulit
2.1.1.1. Anatomi Kulit
Kulit adalah suatu organ yang membungkus seluruh permukaan
tubuh, merupakan organ terbesar dari tubuh manusia baik dari segi berat
maupun luas permukaannya. Pada orang dewasa, kulit menutupi area
dengan luas sekitar dua meter persegi dengan berat 4,5- 5 kg, yaitu sekitar
16% dari total berat tubuh. Ketebalannya juga bervariasi dari 0,5 mm yang
terdapat pada kelopak mata sampai 4,0 mm yang terdapat pada tumit.
Secara struktural kulit terdiri dari dua bagian utama, yaitu epidermis yang
terletak di superfisial dan terdiri atas jaringan epitelial, serta dermis yang
terletak lebih dalam dan terdiri dari jaringan penunjang yang tebal.9
Gambar 3.1. Anatomi Kulit
Sumber : Tortora, 2011

21
Epidermis
Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang tipis dan avaskuler.
Terdiri atas epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Epidermis
memiliki empat tipe sel, yaitu sel keratinosit (90%), melanosit,
Langerhans, dan Merkel.9
Epidermis terdiri dari lima lapisan sel, dari yang terluar sampai
yang terdalam yaitu :
a. Stratum korneum
Terdiri dari beberapa lapisan sel-sel yang mati, tidak lagi memiliki
inti sel, dan banyak mengandung keratin. Lapisan ini secara terus-menerus
akan mengelupas dan digantikan oleh sel-sel dari lapisan kulit yang lebih
dalam. Lapisan-lapisan sel yang telah mati tersebut juga membantu
memberikan perlindungan pada lapisan yang kulit yang lebih dalam dari
trauma dan invasi mikroba.9
b. Stratum lusidum
Lapisan ini hanya terdapat pada daerah tertentu seperti ujung jari,
telapak tangan, telapak kaki. Terdiri dari tiga sampai empat lapisan sel
jernih serta banyak mengadung keratin.9
c. Stratum granulosum
Ditandai oleh 3-5 lapis sel poligonal gepeng yang intinya ditengah
dan sitoplasma terisi oleh granula basofilik kasar yang dinamakan granula
keratohialin yang mengandung protein kaya akan histidin. Terdapat sel
Langerhans.10
d. Stratum spinosum
Terdapat berkas-berkas filamen yang dinamakan tonofibril,
filamen-filamen tersebut dianggap memegang peranan penting untuk
mempertahankan kohesi sel dan melindungi terhadap efek abrasi. Stratum
basale dan stratum spinosum disebut sebagai lapisan Malphigi. Terdapat
sel Langerhans.10

22
e. Stratum basalis
Lapisan ini merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh
selapis sel kuboid atau kolumnar dengan kedudukan tegak lurus terhadap
permukaan dermis. Mengandung tonofilamen, stem cell untuk pembelahan
sel menghasilkan keratinosit baru, melanosit sebagai pembuat pigmen
melanin kulit serta sel Merkel.9
Di dalam lapisan ini sel-sel epidermis
bertambah banyak melalui mitosis dan sel-sel tadi bergeser ke lapisan-
lapisan lebih atas, akhirnya menjadi sel tanduk.11
Dermis
Dermis tersusun atas jaringan ikat kuat yang mengandung serat
kolagen dan elastin. Jaringan serat tersebut memiliki kekuatan meregang
yang kuat. Sel-sel yang terdapat pada dermis utamanya adalah fibroblas,
sedikit makrofag, dan adiposit didekat batasnya dengan lapisan subkutan.
Pembuluh darah, saraf, kelenjar, dan folikel rambut juga tertanam di
lapisan dermis.
Berdasarkan struktur jaringannya, dermis dapat dibagi menjadi
pars papiler yang letaknya superfisial dan pars retikuler yang letaknya
dalam. Lapisan papiler tersusun atas jaringan ikat longgar dengan serat
kolagen tipis dan serat elastin halus, serta terdapat reseptor taktil yang
disebut korpuskel Meissner dan ujung saraf bebas yang sensitif terhadap
sentuhan. Sedangkan pars retikuler tersusun atas fibroblas, kolagen, dan
serat elastin. Sel-sel adiposa, folikel rambut, saraf, kelenjar sebasea dan
sudorifera menempati ruang diantara serat-serat tersebut. Kombinasi
antara serabut kolagen dan elastin pada pars retikularis memberikan
kekuatan, ekstensibilitas, serta elastisitas pada kulit.9
Hipodermis
Kulit melekat ke jaringan di bawahnya (otot atau tulang) melalui
hipodermis, yang juga disebut dengan jaringan subkutis, suatu lapisan
jaringan ikat longgar. Sebagian besar sel adiposa terdapat di dalam
hipodermis, disebut sebagai jaringan adiposa.12

23
2.1.1.2. Fisiologi Kulit
Termoregulasi
Kulit ikut serta dalam pengaturan termoregulasi tubuh melalui dua
mekanisme, yaitu dengan mengeluarkan keringat melalui permukaannya
dan mengatur aliran darah yang terdapat pada dermis. Pada keadaan suhu
yang meningkat, produksi keringat oleh kelenjar keringat akan meningkat
dimana penguapan keringat dari permukaan kulit membantu menurunkan
temperatur tubuh. Selain itu, pembuluh darah akan berdilatasi sehingga
aliran darah lebih banyak yang melalui dermis sehingga meningkatkan
jumlah pengeluaran panas dari tubuh. Sedangkan pada keadaan suhu yang
menurun, produksi keringat oleh kelenjar keringat menurun, membantu
dalam penyimpanan panas. Selain itu, pembuluh darah akan berkonstriksi
yang akan menurunkan aliran darah melalui kulit sehingga menurunkan
kehilangan panas dari tubuh.9
a. Proteksi
Kulit memberikan proteksi bagi tubuh melalui berbagai
mekanisme. Keratin melindungi jaringan dibawahnya dari mikroba, abrasi,
panas, dan bahan kimia. Lipid yang dilepaskan oleh granula lamellar
menghambat penguapan air dari permukaan kulit sehingga melindungi dari
dehidrasi, selain itu juga mencegah air melintasi permukaan kulit selama
mandi atau berenang. Minyak yang dihasilkan kelenjar sebasea menjaga
kulit dan rambut dari kekeringan dan mengandung zat bakterisidal yang
dapat membunuh bakteri. Pigmen melanin membantu melawan efek dari
sinar ultraviolet. Sel Langerhans merupakan sistem imun pada kulit untuk
mendeteksi adanya invasi mikroba dengan mengenali dan
menghancurkannya, sedangkan makrofag bertugas memfagosit bakteri dan
virus.9
b. Ekskresi dan absorbsi
Kulit ikut berperan dalam ekskresi zat dari dalam tubuh. Meskipun
bersifat waterproof, air masih dapat melakukan evaporasi melalui
permukaan, dimana sekitar 400 ml air terevaporasi. Selain itu, dengan
adanya kelenjar keringat, kulit mengekskresikan keringat yang

24
mengandung garam, karbon dioksida, amonia, dan urea. Selain berfungsi
mengeluarkan zat sisa, berkeringat juga berperan dalam fungsi
termoregulasi tubuh.Sebum yang diproduksi oleh kulit juga berguna
untuk melindungi kulit karena lapisan sebum ini menahan air yang
berlebihan sehingga kulit tidak menjadi kering.9
Sedangkan fungsi absorpsi yang dimiliki kulit memfasilitasi
masuknya zat dari lingkungan eksternal menuju sel tubuh. Namun tidak
semua zat dapat masuk karena hanya zat tertentu yang larut dalam lemak,
misalnya vitamin A, D, E, K serta oksigen dan karbon dioksida. Selain
itu, zat yang bersifat toksik juga dapat terabsorpsi oleh kulit. Fungsi
absorpsi ini juga memungkinkan obat-obatan yang aplikasinya secara
topikal mampu masuk hingga bagian dermis kulit.9
c. Sintesis vitamin D
Epidermis membentuk vitamin D jika terdapat sinar urltaviolet
(UV) dari matahari. Jenis sel yang menghasilkan vitamin D belum
diketahui pasti. Vitamin D, yang berasal dari molekul prekursor yang
berkaitan erat dengan kolesterol, mendorong penyerapan Ca2+
dari
saluran cerna ke dalam darah.11
Hanya sedikit pajanan sinar sinar UV
yang dibutukan untuk sintesis vitamin D.9
d. Persepsi
Terdapat berbagai macam ujung saraf bebas dan reseptor yang
terdapat di kulit yang mampu mendeteksi sensasi taktil seperti sentuhan,
tekanan, dan getaran serta sensasi termal seperti rasa dingin atau panas.
Sensasi lain misalnya adalah nyeri yang merupakan indikasi sedang
terjadinya kerusakan jaringan.9
2.1.2. Binahong(Anredera cordifolia (Tenore) Steenis)
2.1.2.1. Klasifikasi
Menurut Badan POM RI, klasifikasi binahong adalah sebagai
berikut12
:
Divisi : Spermatophyta
Sub divisi : Angiospermae

25
Kelas : Dicotyledoneae
Bangsa : Caryophyllales
Suku : Basellaceae
Marga : Anredera
Jenis : Anredera cordifolia (Tenore) Steenis
2.1.2.2. Nama Umum13
Indonesia : Binahong
Cina : Dheng San Chi
Inggris : Heartleaf madeiravine
Latin : Bassela rubra linn
2.1.2.3. Asal dan Habitat
Binahong merupakan tanaman yang konon berasal dari Amerika
Selatan. Binahong mudah tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi.
Banyak dibudidayakan sebagai taman hias atau obat herbal, di dalam
pot, halaman, pekarangan, atau kebun. Habitat tanaman binahong
adalah sebagai gulma dihutan, ditepi saluran air dan daerah tepi sungai,
kebun, taman, diantara tanaman perkebunan, dan dipinggir jalan, yang
beriklim basah, daerah tropis dan sub-tropis. Tanaman menjalar
memanjat pada batang tanaman pepohonan yang tumbuh lebih kuat dari
vegetasi lainnya hingga tinggi 30 meter, dan berumur panjang
(perenial).14
2.1.2.4. Morfologi
Bentuk tanaman binahong berupa tumbuhan menjalar, berumur
panjang lebih dari 6 meter. Memiliki batang yang lunak, silindris, saling
membelit, berwarna merah, bagian dalam solid, permukaan halus,
kadang membentuk semacam umbi yang melekat di ketiak daun dengan
bentuk tak beraturan dan bertekstur kasar. Memiliki daun tunggal,
bertangkai sangat pendek, tersusun berseling, berwarna hijau, bentuk
jantung, panjang 5-10 cm, lebar 3-7 cm, helaian daun tipis lemas, ujung

26
runcing, pangkal berlekuk, tepi rata, permukaan licin, serta bisa
dimakan. Memiliki bunga majemuk berbentuk tandan, bertangkai
panjang, muncul di ketiak daun, mahkota berwarna krem keputih-
putihan berjumlah lima helai tidak berlekatan, panjang helai mahkota
0,5-1 cm, dan berbau harum. Akar berbentuk rimpang dan berdaging
lunak.12
Gambar 3.2. Tanaman Binahong
2.1.2.5. Perkembangbiakan
Perbanyakan tanaman dapat dilakukan secara generatif atau
melalui biji, namun lebih sering diperbanyak atau dikembangbiakan
secara vegetatif melalui akar rimpangnya. Tanaman binahong lebih suka
tumbuh pada tanah dengan humus yang tebal, berpasir ringan, tanah liat
sedang, dengan drainase yang baik, serta toleran terhadap kekeringan.
Tanaman binahong tumbuh dengan baik pada kondisi setengah teduh
atau teduh.14
2.1.2.6. Zat Aktif dan Khasiat
Tanaman binahong mengandung fenol, flavonoid, saponin,
terpenoid, steroid dan alkaloid. Senyawa fenolik dan flavonoid dapat
berperan langsung sebagai antibiotika dengan mekanisme kerja
menghancurkan dinding sel bakteri, serta memiliki aktivitas sebagai

27
antioksidan. Senyawa terpenoid adalah senyawahidrokarbon isometrik
yang membantu proses sintesa organik dan pemulihan sel-sel tubuh.
Saponin mempunyai fungsi menurunkan kolesterol karena mempunyai
aktivitas sebagi antioksidan. Kandungan saponin, fenolik dan flavonoid
dalam tanaman ini memiliki aktifitasantibiotik sebagaimana golongan
tetrasiklin dan penisilin.15
Daun binahong juga memiliki kandungan
asam askorbat dan total fenol yang cukup tinggi.5 Kandungan asam
askorbat dapat meningkatkan daya tahan terhadap infeksi, berfungsi
dalam pemeliharaan membran mukosa, serta mempercepat
penyembuhan.
2.1.3. Luka Bakar
2.1.3.1. Definisi
Luka bakar adalah kerusakan jaringan pada kulit akibat terpajan
panas tinggi, bahan kimiawi maupun arus listrik.Luka bakar merupakan
trauma yang sering terjadi dan dapat terjadi dimana saja,17
serta memiliki
tingkat morbiditas dan mortalitas tinggi yang memerlukan
penatalaksanaan khusus sejak awal (fase syok) sampai fase lanjut.1
2.1.3.2. Insidensi
Berdasarkan data statistik pada unit pelayanan khusus luka bakar
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada tahun 1998 di laporkan
107 kasus luka bakar atau 26,3%dari seluruh kasus bedah plastik yang
dirawat. Dari kasus tersebut terdapat lebih 40% merupakan luka bakar
derajat II-III denganangka kematian 37,38%.1,2
Luka bakar merupakan salah satu insiden yang sering terjadi di
masyarakat khususnya rumah tangga dan yang terbanyak adalah luka
bakar derajat II.1
Insiden puncak luka bakar pada orang dewasa muda
terdapat pada usia 20-29 tahun, diikuti oleh anak umur 9 atau lebih muda.
Luka bakar jarang terjadi pada usia 80 tahun ke atas. Pada anak di bawah
usia 3 tahun, penyebab luka bakar paling umum adalah kecelakaan. Pada
usia 3-14 tahun, penyebab paling sering adalah dari nyala api yang

28
membakar pakaian. Usia yang lebih dewasa sampai 60 tahun paling
sering disebabkan oleh kecelakaaan industri.17
2.1.3.3. Etiologi
Secara garis besar, penyebab terjadinya luka bakar dapat dibagi
menjadi19
:
a. Luka bakar karena api
b. Luka bakar karena air panas
c. Luka bakar karena bahan kimia
d. Luka bakar karena listrik, petir dan radiasi
e. Luka bakar karena sengatan sinar matahari
f. Luka bakar karena tungku panas atau udara panas
g. Luka bakar karena ledakan bom
2.1.3.4. Patofisiologi
Kerusakan jaringan akibat aliran panas saat terjadinya luka bakar
tergantung dari beberapa faktor, antara lain suhu sumber panas, lamanya
kontak dengan sumber panas serta jaringan tubuh yang terkena.20
Ketika jaringan kulit terpajan suhu tinggi, sel-sel dapat menahan
temperatur sampai 440C tanpa kerusakan bermakna. Antara 44
0-55
0 C,
kecepatan kerusakan jaringan berlipat ganda untuk tiap derajat kenaikan
temperatur . Diatas 510
C, protein terdenaturasi dan kecepatan kerusakan
jaringan sangat hebat. Temperatur diatas 700C menyebabkan kerusakan
selular yang sangat cepat dan hanya periode pemaparan yang sangat
singkat yang dapat ditahan oleh tubuh.17
Perubahan biokimia dan fisik yang mengakibatkan kematian sel
pada kerusakan jaringan akibat luka bakar belum diketahui, namun
diduga sebagai akibat denaturasi protein dan menurunnya aktivitas
enzim. Enzim-enzim tertentu terutama yang berperan dalam siklus Krebs
aktivitasnya menurun karena panas, mengakibatkan penurunan produksi
ATP sehingga terjadi kematian sel.19

29
Luka bakar akan menyebabkan gangguan utamanya pada kulit,
pembuluh darah dan elemen darah, metabolisme dan hemodinak. Efek
luka bakar pada kulit yaitu menyebabkan kehilangan cairan tubuh serta
terganggunya sistem pertahanan terhadap invasi kuman. Evaporasi cairan
melalui permukaan tubuh akan meningkat pada luka bakar. Evaporasi
cairan pada luka bakar derajat II dan III akan disertai dengan
meningkatnya kehilangan panas tubuh. Tiap gram evaporasi cairan dari
permukaan tubuh akan disetai kehilangan panas sebesar 0,575 kkal.
Peningkatan kehilangan panas ini akan disertai dengan peningkatan
kebutuhan oksigen, dimana keadaan tersebut akan meningkatkan
metabolisme tubuh dan produksi energi untuk dapat mempertahankan
homeostasis panas tubuh.19
Luka bakar seringkali tidak steril, sehingga dapat menjadi
medium yang baik untuk pertumbuhan kuman yang akan mempermudah
terjadinya infeksi. Kuman penyebab infeksi tersebut dapat berasal dari
kulit pasien itu sendiri, kontaminasi kuman dari saluran napas atas atau
kontaminasi kuman di lingkungan rumah sakit. Infeksi nosokomial ini
biasanya sangat berbahaya karena kumannya banyak yang sudah resisten
terhadap berbagai antibiotik. Infeksi akibat luka bakar menjadi sulit
diatasi karena daerahnya tidak tercapai oleh pembuluh kapiler yang
mengalami trombosis.19
Efek luka bakar pada integritas pembuluh darah yaitu
meningkatnya permebilitas pembuluh darah dan kapiler sekitar luka.
Cairan dan protein dengan cepat akan meninggalkan pembuluh darah ke
jaringan interstisial sehingga terjadi edema. Awalnya cairan yang berada
di daerah luka bakar akan diresorbsi oleh sistem limfe, tetapi kemudian
kehilangan cairan akan bertambah berat karena melebihi kemampuan
resorbsi sistem limfe. Kehilangan cairan terutama terjadi dalam 24 jam
pertama, karena setelah 48 jam permeabilitas kapiler akan kembali
normal. Berkurangnya cairan kaya protein dari sirkulasi akan
menyebabkan syok hipovolemik dengan gejala yang khas, seperti
gelisah, pucat, dingin, berkeringat, nadi kecil dan cepat, tekanan darah

30
menurun dan produksi urin yang berkurang. Edema terjadi pelan-pelan,
maksimal terjadi setelah delapan jam.1,2
Berkurangnya volume plasma
akan diikuti berkurangnya volume sel darah merah, umumnya terjadi
pada 24 jam pertama.19
Luka bakar juga menyebabkan perubahan metabolisme dan
hemodinamik, yang terbagi kedalam 3 fase yaitu fase syok, katabolik,
dan restoratif. Perubahan hemodinamik ditandai dengan adanya takikardi,
hipotensi, perubahan kardiak output dan vasokonstriksi perifer.
Perubahan kardiak output terjadi pada tahap awal setelah trauma termal
yang merupakan akibat dari hipovolemi. Hipovolemi juga
mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah ginjal dan aktivitas
adrenergik dengan manifestasi klinik beruupa oliguria, penurunan GFR,
retensi Na, dan ekskresi K. Aktivitas hormon adrenal memegang peranan
penting pada fase syok. Peningkatan aktivitas korteks adrenal akan
merangsang hipotalamus dan hipofisis.19
Secara klinis defek metabolik yang jelas pada fase luka terbuka
adalah balans nitrogen negatif. Selama fase katabolik akan terjadi
kekurangan energi yang besar, keadaan ini berhubungan dengan
meningkatnya evaporasi cairan dan kehilangan panas melalui luka
bakar.19
2.1.3.5.Fase Luka Bakar
a. Fase Akut
Pada fase ini pasien terancam mengalami gangguan airway (jalan
nafas), breathing (mekanisme bernafas), dan circulation (sirkulasi). Pada
fase ini dapat terjadi juga gangguan keseimbangan sirkulasi cairan dan
elektrolit akibat cedera termal/panas yang berdampak sistemik.18
b. Fase Subakut
Luka yang terjadi pada fase akut dapat menyebabkan beberapa
masalah lain seperti Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS),
Multi-system Organ Dysfunction Syndrome (MODS) dan sepsis.18,19

31
c. Fase Lanjut
Fase ini berlangsung setelah penutupan luka sampai terjadinya
maturasi jaringan. Masalah yang dihadapi adalah penyulit dari luka bakar
seperti parut hipertrofik, kontraktur dan deformitas lain.18,19
2.1.3.6. Derajat Luka Bakar
Kedalaman kerusakan jaringan akibat luka bakar tergantung pada
derajat panas sumber, penyebab dan lamanya kontak dengan tubuh
penderita.Kedalaman luka bakar diartikan sebagai derajat luka bakar, yang
dibagi menjadi :
a. Derajat I
Kerusakan terbatas pada lapisan epidermis, kulit hiperemik berupa
eritem, tidak dijumpai bullae, edema lokal, dan terasa nyeri karena ujung-
ujung saraf sensorik teriritasi yang akan menghilang setelah 48 jam
kecuali bila luka bakar luas. Penyembuhan terjadi secara spontan dalam 5 -
10 hari tanpa pengobatan khusus dan tanpa timbul jaringan ikat.18,19
b. Derajat II
Kerusakan meliputi seluruh epidermis dan sebagian dermis, berupa
reaksi inflamasi disertai proses eksudasi. Terdapat bullae, edema subkutan,
eritema, nyeri karena ujung-ujung saraf sensorik teriritasi.Dibedakan atas
dua bagian :
Derajat II dangkal/ superficial (IIA)
Kerusakan mengenai bagian epidermis dan lapisan atas dari
dermis. Penyembuhan terjadi secara spontan dalam waktu 10-14 hari tanpa
terbentuk sikatriks, apabila terjadi infeksi sekunder maka proses
penyembuhan akan lebih lama.18,19
Derajat II dalam / deep (IIB)
Kerusakan mengenai hampir seluruh bagian dermis dan sisa – sisa
jaringan epitel tinggal sedikitPenyembuhan terjadi lebih lama dan disertai
parut hipertrofi. Regenerasi epitel dengan granulasi vaskuler terjadi dalam
waktu 2 – 3 minggu.18,19

32
c. Derajat III
Kerusakan meliputi seluruh tebal kulit dan lapisan yang lebih
dalam sampai mencapai jaringan subkutan, otot dan tulang. Tidak
dijumpai bullae, kulit yang terbakar berwarna abu-abu dan lebih pucat
sampai berwarna hitam kering. Tidak dijumpai rasa nyeri dan hilang
sensasi karena ujung – ujung sensorik rusak.Penyembuhan terjadi lama
karena tidak terjadi epitelisasi spontan seta akan meninggalkan jaringan
parut.18,19,20
Gambar 3.3. Derajat Luka Bakar
Sumber : Tortora, 2011
2.1.4. Proses Penyembuhan Luka
Setiap terjadi luka, mekanisme tubuh akan mengupayakan
mengembalikan komponen-komponen jaringan yang rusak tersebut dengan
membentuk struktur baru dan fungsional yang sama dengan keadaan
sebelumnya. Proses penyembuhan tidak hanya terbatas pada proses
regenerasi yang bersifat lokal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor
endogen (seperti umur, nutrisi, imunologi, pemakaian obat-obatan, kondisi
metabolik).

33
Proses penyembuhan luka terdiri atas 4 fase, yaitu :
a. Fase Inflamasi
Fase inflamasi dimulai setelah beberapa menit dan berlangsung
selama sekitar 3 hari setelah cedera. Fase inflamasi ditandai dengan
adanya respons vaskuler dan seluler yang terjadi akibat perlukaan yang
terjadi pada jaringan kulit.
Pembuluh darah yang mengalami kerusakan akibat cedera akan
segera berkonstriksi. Konstriksi ini, atau spasme vaskular, memperlambat
darah mengalir melalui defek dan memperkecil kehilangan darah.
Mekanisme yang mendasari hal ini belum jelas tetapi diperkirakan
merupakan suatu respon intrinsik yang dipicu oleh suatu zat parakrin yang
dilepaskan secara lokal dari lapisan endotel pembuluh darah yang cedera.
Pembuluh darah yang cedera juga akan mengaktifkan trombosit oleh
kolagen yang terpajan, yaitu protein fibrosa di jaringan ikat di bawah
endotel. Setelah teraktifkan, trombosit akan cepat melekat ke kolagen dan
membentuk sumbat trombosit hemostatik di tempat cedera. Sumbat
trombosit tersebut secara fisik akan menambal kerusakan pembuluh darah
yang terjadi.21
Periode ini hanya berlangsung 5-10 menit, dan setelah itu akan
terjadi vasodilatasi kapiler oleh stimulasi saraf sensoris dan adanya
substansi vasodilator yaitu histamin, serotonin dan sitokin. Histamin selain
menyebabkan vasodilatasi juga mengakibatkan meningkatnya
permeabilitas vena, sehingga cairan plasma darah keluar dari pembuluh
darah dan masuk ke daerah luka dan secara klinis terjadi edema jaringan.
Sitokin yang teraktivasi meliputi Epidermal Growth Factor (EGF),
Insulin-likeGrowth Factor (IGF), Plateled-derived Growth Factor (PDGF)
dan TransformingGrowth Factor beta (TGF-β) yang berperan untuk
terjadinya kemotaksis netrofil, makrofag, mast sel, sel endotelial dan
fibroblas.10
Kemotaksis mengakibatkan terjadinya diapedesis leukosit.
Leukosit mengeluarkan enzim hidrolitik yang membantu mencerna bakteri
dan kotoran pada luka. Limfosit dan monosit kemudian akan muncul

34
untuk melakukan fagositosis.20
Agregat trombosit juga akan mengeluarkan
mediatorinflamasi Transforming Growth Factor beta 1 (TGF β1) yang
juga dikeluarkanoleh makrofag. Adanya TGF β1 akan mengaktivasi
fibroblas untuk mensintesiskolagen.10
b. Fase Proliferasi
Proses kegiatan seluler yang penting pada fase ini adalah
memperbaiki dan menyembuhkan luka dan ditandai dengan proliferasi sel.
Terdapat tiga proses utama dalam fase ini, antara lain pembenukan sawar
permeabilitas (re-epitelisasi), migrasi dan proliferasi fibroblas,
pembentukan pembuluh darah baru (angiogenesis), serta deposisi matriks
ekstraseluler.
Dalam 3 sampai 5 hari, terbentuk suatu jaringan khusus yang
mencirikan terjadinya penyembuhan, yang disebut jaringan granulasi.
Istilah jaringan granulasi berasal dari gambaran makroskopisnya yang
berwarna merah muda, lembut, dan bergranula. Gambaran histologisnya
ditandai dengan proliferasi fibroblas dan kapiler baru yang halus dan
berdinding tipis di dalam matriks ekstraseluler yang longgar.20
Jaringan
granulasi merupakan kombinasi dari elemen seluler termasuk fibroblast
dan sel inflamasi, yang bersamaan dengan timbulnya kapiler baru
tertanam dalam jaringan longgar ekstra seluler dari matriks kolagen,
fibronektin dan asam hialuronik.22
Rekrutmen dan stimulasi fibroblas dikendalikan oleh banyak faktor
pertumbuhan meliputi PDGF, bFGF, dan TGF-beta. Sumber dari berbagai
faktor ini antara lain dari endotel teraktivasi dan sel radang terutama
makrofag. Peran fibroblas sangat besar pada proses perbaikan, yaitu
bertanggung jawab pada persiapan menghasilkan produk struktur protein
yang akan digunakan selama proses rekonstruksi jaringan. Fibroblas akan
aktif bergerak dari jaringan sekitar luka ke dalam daerah luka, kemudian
akan berproliferasi serta mengeluarkan beberapa substansi seperti kolagen,
elastin, asam hialuronidase, fibronektin dan proteoglikan yang berperan
dalam merekonstruksi jaringan baru.20

35
Angiogenesis suatu proses pembentukan pembuluh darah kapiler
baru didalam luka, mempunyai arti penting pada tahap proliferasi proses
penyembuhan luka. Jaringan vaskuler yang melakukan invasi kedalam
luka merupakan suatu respons untuk memberikan oksigen dan nutrisi yang
cukup di daerah luka karena biasanya pada daerah luka terdapat keadaan
hipoksik dan turunnya tekanan oksigen. Empat tahapan umum yang terjadi
di dalam perkembangan pembuluh darah kapiler baru adalah21
:
Degradasi proteolitik pada pembuluh darah induk membran basalis,
memungkinkan pembentukan suatu tunas kapiler.
Migrasi sel endotel dari kapiler asal menuju suatu rangsang
angiogenik.
Proliferasi sel endotel di belakang ujung terdepan sel yang bermigrasi.
Maturasi sel endotel dengan penghambatan pertumbuhan dan penataan
menjadi pembuluh kapiler; tahapan ini mencakup rekrutmen dan
proliferasi perisit dan sel otot polos untuk menyokong pembuluh
endotel dan untuk memberikan fungsi tambahan.
Beberapa sitokin yang menginduksi angiogenesistermasuk basic
fibroblast growth faktor (bFGF), asidic FGF (aFGF), transforming growth
factor α β (TGF α β) dan epidermal growth factor (eFGF). FGF pada
percobaan invivo merupakan subtansi poten dalam neovaskularisasi.22
Proses selanjutnya adalah re-epitelisasi, dimana fibroblas
mengeluarkan KGF (Keratinocyte Growth Factor) yang berperan dalam
stimulasi mitosis sel epidermal. Re-epitelisasi akan dimulai dari pinggir
luka dan akhirnya membentuk barrier yang menutupi permukaan luka.
Karakteristik proses re-epitelisasi pada penyembuhan luka yaitu terjadinya
perluasan secara progresif dari lapisan keratinosit yang diawali dari tepi
luka melintasi permukaan dermis yang terekspos.23
Secara umum, re-epitelisasi melibatkan beberapa proses, yaitu
migrasi keratinosit epidermal dari tepi luka, proliferasi keratinosit yang
digunakan untuk menambah epithelial tongue yang meningkat dan
bermigrasi, diferensiasi neo-epithelium menjadi epidermis yang berlapis,
pengembalian zona membran basal yang utuh yang menghubungkan

36
epidermis dengan dermis di bawahnya, dan repopulasi sel-sel khusus yang
mengatur fungsi sensoris (sel Merkel), pigmentasi (melanosit), dan fungsi
imun (sel Langerhans).23
Stimulator reepitelisasi ini belum diketahui
secara lengkap. Faktor-faktor yang diduga berperan adalah EGF, TGFβ,
PDGF danIGF λ.22
Gambar 3.4. Proses Re-epitelisasi Epidermis
Sumber : Savagner, 2005
Migrasi keratinosit epidermal merupakan fase yang krusial dalam
proses re-epitelisasi pada penyembuhan luka. Keratinosit teraktivasi oleh
adanya reaksi inflamasi tahap awal, dimana terjadi perekrutan sitokin-
sitokin proinflamasi dan faktor pertumbuhan yang kemudian menginisiasi
pengaktifan sel-sel keratinosit di membran basal. Keratinosit kemudian
mengalami perubahan fenotip parsial yang mengakibatkan bentuknya
menjadi lebih datar dan motil, serta terputusnya sebagian besar desmosom
interseluler.28
Karena telah terjadi pemutusan ikatan hemidesmosom antara
membran basal dan epidermis, mengakibatkan sel-sel pada dermis dan
epidermis tidak lagi melekat satu sama lain sehingga memungkinkan
untuk terjadinya migrasi ke arah lateral dari sel-sel epidermal. Migrasi sel
terjadi secara aktif yang difasilitasi oleh adanya penonjolan sitoplasma
keratinosit yang disebut dengan filipodia dan lamellipodia.25
Satu sampai dua hari setelah terjadi luka, sel-sel epidermal pada
tepi luka mulai berproliferasi dibelakang sel-sel yang sedang bermigrasi

37
aktif. Berbeda dengan tahap migrasi keratinosit epidermal yang
berlangsung secara migrasi aktif, pada tahap ini tergolong bersifat
translokasi pasif dari sel-sel marginal yang telah tebentuk sebelumnya
pada tahap migrasi epidermal. Stimulus proses migrasi dan proliferasi sel-
sel epidermal belum dapat ditentukan, namun terdapat beberapa
kemungkinan. Ketiadaannya sel-sel epidermal disekitar tepi luka
kemungkinan merupakan sinyal untuk terjadinya proses migrasi dan
proliferasi sel-sel epidermal. Pelepasan lokal dari faktor pertumbuhan dan
peningkatan ekspresi dari reseptor faktor pertumbuhan mungkin juga
menstimulasi proses tersebut.24
Setelah berlangsungnya proses re-epitelisasi, protein membran
basal kembali muncul dalam pola yang sangat teratur mulai dari tepi luka
bagian dalam membetuk seperti pola risleting. Sel-sel epidermal kemudian
kembali ke fenotip normalnya, kemudian kembali membuat ikatan yang
kuat antara membran basal dan dermis yang berada tepat dibawahnya.25
c. Fase Maturasi
Fase maturasi merupakan tahap akhir proses penyembuhan luka yang
memerlukan waktu lebih dari satu tahun, bergantung pada kedalaman dan
luas luka. Jaringan parut kolagen terus melakukan reorganisasi dan akan
menguat setelah beberapa bulan. Tujuan dari fase maturasi adalah
menyempurnakan terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan
penyembuhan yang kuat dan bermutu.
Scab atau keropeng akan lepas dari permukaan luka setelah lapisan
epidermis telah terbentuk kembali dengan ketebalan sama seperti kulit
yang sehat. Ketika proses penyembuhan mengalami kemajuan, jumlah
fibroblas yang berproliferasi dan pembuluh darah baru akan berkurang,
namun secara progresif fibroblas akan lebih mengambil fenotip sintesis
sehingga terjadi peningkatan deposisi matriks ekstraseluler. Terbentuk
asam hialuronidase dan proteoglikan dengan berat molekul besar berperan
dalam pembentukan matriks ekstraseluler dengan konsistensi seperti gel
dan membantu infiltrasi seluler.Kolagen berkembang cepat menjadi faktor
utama pembentuk matriks. Serat kolagen pada permulaan terdistribusi acak

38
membentuk persilangan dan beragregasi menjadi bundel-bundel fibril yang
secara perlahan menyebabkan penyembuhan jaringan dan meningkatkan
kekakuan dan kekuatan ketegangan.22
Secara khusus, sintesis kolagen sangat penting untuk
perkembangan kekuatan pada tepat penyembuhan luka. Namun,
penumpukan kolagen yang sebenarnya tidak hanya bergantung pada
peningkatan sintesis, tetapi juga pada degenerasi kolagen. Pada akhirnya,
bangunan dasar jaringan granulasi berkembang menjadi suatu jaringan
parut yang sebagian besar terdiri atas fibroblas inaktif berbentuk
kumparan, kolagen padat, fragmen jaringan elastis, dan komponen matriks
ekstraseluler lainnya. Kekuatan dari jaringan parut akan mencapai
puncaknya pada minggu ke-10 setelah perlukaan.21
Remodeling kolagen selama pembentukan jaringan parut
tergantung pada proses sintesis dan katabolisme kolagen yang
berkesinambungan. Degradasi kolagen pada luka dikendalikan oleh enzim
kolagenase. Kecepatan tinggi sintesis kolagen mengembalikan luka ke
jaringan normal dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Remodeling aktif
jaringan parut akan terus berlangsung sampai 1 tahun dan tetap berjalan
dengan lambat seumur hidup.22
Saat jaringan parut menjadi matang, akhirnya regresi pembuluh
darah akan mengubah jaringan granulasi yang sangat banyak pembuluh
darahnya menjadi suatu jaringan parut yang pucat dan sangat avaskular.
Kolagen muda yang terbentuk pada fase proliferasi akan berubah menjadi
kolagen yang lebih matang, yaitu lebih kuat dan struktur yang lebih baik.21
Luka dikatakan sembuh jika terjadi kontinuitas lapisan kulit dan
kekuatan jaringan kulit mampu atau tidak lagi mengganggu untuk
melakukan aktivitas yang normal.

39
Gambar 3.5. Proses Penyembuhan Luka. (a) Fase Inflamasi ; (b) Re-epitelisasi
dan Neovaskularisasi
Sumber : Singer, 1999
2.1.5. Silver Sulfadiazine
Sampai saat ini Silver Sulfadiazine masih digunakan sebagai obat
standar untuk pengobatan luka bakar terutama derajat II dan III. Krim ini
memliki dua komponen zat aktif yaitu silver dan sulfadiazine dengan kadar
1% yang terdispersi secara merata dalam bentuk butiran-butiran halus
dengan zat pembawa berbentuk krim dan bersifat hidrofilik. Bersifat
bakteriostatik dan mempunyai spektrum luas terhadap kuman Gram positif
maupun negatif. Komponen vehikulumnya berupa emulsi oil in water yang
larut dalam air. Pengemulsian ini berguna untuk meningkatkan kecepatan
absorbsi perkutan dan mempermudah penetrasi kedalam luka bakar.23
2.1.6. Vaselin Album
Vaselin album adalah golongan lemak mineral diperoleh dari
minyak bumi. Titik cair sekitar 10-50°C, mengikat 30% air, tidak berbau,
transparan, konsistensi lunak. Sifat dasar salep hidrokarbon ini sukar
dicuci, tidak mengering dan tidak berubah dalam waktu lama. Salep ini
digunakan untuk memperpanjang kontak bahan obat dengan kulit dan
bertindak sebagai penutup (oklusif).26
(b) (a)

40
2.1.7. Adeps Lanae
Adeps lanae ialah lemak murni dari lemak bulu domba, keras dan
melekat sehingga sukar dioleskan, mudah mengikat air. Adeps lanae
hydrosue atau lanolin ialah adeps lanae dengan akua 25-27%.Salep ini
dapat dicuci namun kemungkinan bahan sediaan yang tersisa masih ada
walaupun telah dicuci dengan air.28
2.1.8. Tikus Sprague dawley
Tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague dawley merupakan
salah model tikus yang banyak digunakan dalam penelitian biomedik.
Tingkat reproduksinya sangat baik, mudah dalam penanganan karena
sifatnya yang tenang dan memiliki masa hidup tikus ini sekitar 2,5-3,5
tahun. Tikus ini memiliki rasio panjang ekor dengan panjang badan yang
lebih besar daripada galur Wistar. Berat badan dewasa pada betina adalah
250- 400 gram, sedangkan pada jantan adalah 450-520 gram.26

41
BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1. Desain Penelitian
Desain penelitian ini adalah penelitian eksperimental deskriptif
analitik.
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Animal House, Laboratorium
Farmakologi, dan Laboratorium Histologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada
bulan Januari sampai Agustus 2014.
3.3. Populasi dan Sampel
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih
(Rattus norvegicus) kelamin jantan galur Sprague dawley yang dibagi
dalam 5 kelompok secara random dengan cara pengundian.
Besar sampel yang digunakan sebanyak 25 ekor tikus putih,
dihitung berdasarkan rumus Federer yaitu (t-1) (n-1) ≥ 15 dimana t =
banyaknya kelompok tikus dan n = jumlah tikus tiap kelompok.29
(t-1) (n-1) ≥ 15
(5-1) (n-1) ≥ 15
4 (n-1) ≥ 15
4n – 4 ≥ 15
4n ≥ 19
n ≥ 4.75 (n=5)
Berdasarkan rumus diatas sampel yang digunakan tiap kelompok
percobaan adalah sebanyak 5 sampel sehingga memenuhi syarat dalam
banyaknya sampel yang digunakan. Jumlah kelompok yang digunakan

42
adalah sebanyak 5 kelompok sehingga penelitian ini menggunakan 25 ekor
tikus putih dari populasi yang ada. Pembagian tersebut dilakukan secara
random dengan cara pengundian. Sampel pada penelitian ini ditentukan
dengan kriteria-kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi antara lain
tikus galur Sprague dawley, berbulu putih dan sehat, berjenis kelamin
jantan, berusia sekitar 3 bulan, serta memiliki rentang berat badan antara
300-400 gram. Sementara kriteria eksklusi antara lain mati selama
aklimatisasi, serta memiliki luka di daerah kulit punggung.
Kelima kelompok tersebut terdiri dari : kelompok K(-) adalah
kelompok kontrol negatif dimana luka diolesi basis salep; kelompok K(+)
adalah kelompok kontrol positif dimana luka diolesi salep Silver
Sulfadiazine; kelompok P1 adalah kelompok perlakuan dimana luka
diolesi salep ekstrak daun binahong konsentrasi 10%; kelompok P2 adalah
kelompok perlakuan dimana luka diolesi salep ekstrak daun binahong
konsentrasi 20%; serta kelompok P3 adalah kelompok perlakuan dimana
luka diolesi salep ekstrak daun binahong konsentrasi 40%.
3.4. Variabel Penelitian
3.4.1. Variabel Bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah salep ekstrak daun
binahong dengan konsentrasi 10%, 20%, dan 40%, basis salep, serta krim
silver sulfadiazine.
3.4.2. Variabel Terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketebalan lapisan re-
epitelisasi yang terjadi setelah hari kelima perlakuan yang diamati secara
mikroskopis.

43
3.5. Alur Penelitian
Penyediaan daun
binahong segar
sebanyak 4kg
Dikeringkan
dibawah sinar
matahari
Determinasi di
LIPI Sertifikat
Ekstraksi dengan
etanol 96% di
BALITRO
Ekstrak
kental
Penyediaan
bahan basis
salep (vaselin
album dan adeps
lanae)
Pembuatan
basis salep dan
salep ekstrak
daun binahong
Penyediaan tikus
Sprague dawley
25 ekor
Pembuatan preparat di
Deparemen PA FKUI
Pengamatan preparat
histopatologi
Adaptasi tikus
selama 7 hari, 1
ekor per kandang,
makan dan minum
secara ad libitum
Pencukuran rambut
pada punggung tikus
menggunakan
gunting, pisau cukur,
dan krim cukur
Induksi luka bakar pada
punggung tikus menggunakan
plat besi panas selama 30
detik dengan penekanan
Randomisasi menjadi
5 kelompok
Aplikasi salep 2x
sehari selama 5 hari
Data ketebalan
lapisan re-epitelisasi
epidermis
Uji statistik
Penyediaan
krim Silver
Sulfadiazine
Eksisi jaringan
kulit tikus

44
3.6. Cara Kerja Penelitian
3.6.1. Pembuatan Ekstrak Daun Binahong
Sampel berupa daun binahong segar didapatkan dari pusat
penjualan tanaman binahong di daerah Cisarua kemudian proses
pengeringan daun juga dilakukan disana. Tahapannya sebanyak 4 kg daun
binahong segar yang tidak terserang hama, penyakit, dan pencemar
lainnya dibersihkan dengan air mengalir, kemudian ditiriskan. Selanjutnya
dipotong menjadi bagian-bagian kecil dan dikeringkan dibawah sinar
matahari sampai sampel tersebut benar-benar kering, proses ini
membutuhkan waktu hingga tiga hari jika cuaca sedang tidak hujan.
Selanjutnya daun binahong kering sebanyak 530,6 gram dibawa ke
Balai Tamanan Obat dan Aromatik (BALITRO) untuk dilakukan ekstraksi
dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96% oleh tenaga
laboratorium disana. Hasil yang didapat berupa ekstrak kental daun
binahong sebanyak 26,2 gram. (Gambar lihat Lampiran 4).
3.6.2. Pembuatan Basis Salep
Pembuatan basis salep dilakukan sendiri oleh peneliti di
Laboratorium Farmakologi. Basis salep yang akan digunakan adalah basis
berlemak yaitu adeps lanae dan vaselin album. Sebelumnya adeps lanae
dan vaselin album dipanaskan agar melebur diatas air yang mendidih
menggunakan baker glass, cawan porselen, hot plate stirrer, dan spatula.
Kemudian, adeps lanae dan vaselin album dicampur menggunakan
lumpang dan alu yang sebelumnya disiram dengan menggunakan air panas
dengan suhu 500C. Setelah itu campuran tersebut diaduk dengan kecepatan
konstan hingga homogen dan terbentuk basis salep. Basis salep kemudian
disimpan dalam tabung plastik dan ditutup (Gambar lihat Lampiran 4).
Pemilihan sediaan berbentuk salep dengan vaselin album dan adeps
lanae sebagai basisnya adalah berdasarkan sifatnya yang dapat menutup
luka dengan baik serta dapat menyerap air dalam luka sehingga

45
meningkatkan hidrasinya. Perawatan luka tertutup (occlusive dressing) dan
hidrasi yang baik dapat menciptakan lingkungan luka yang lembab
sehingga dapat memfasilitasi untuk mempercepat proses penyembuhan
luka (moist wound healing).30
3.6.3. Pengujian Sediaan Salep
Pengujian sediaan salep juga dilakukan sendiri oleh peneliti di
Laboratorium Farmakologi. Sediaan salep yang telah dibuat dilakukan uji
berupa tes homogenitas. Tes homogenitas dilakukan dengan cara
mengoleskan sediaan salep ekstrak daun binahong pada sekeping kaca
transparan dimana sediaan diambil bagian atas, tengah dan bawah.31
3.6.4. Pembuatan Konsentrasi Salep Ekstrak Daun Binahong
Formula standar dasar basis salep yang digunakan adalah31
:
R/ Adeps Lanae 15 g
Vaselin Album 85 g
m.f salep 100 g
Sediaan salep yang akan digunakan dalam penelitian ini memiliki
konsentrasi masing-masing yaitu 10%, 20%, 40% dibuat sebanyak 30 g
(Gambar lihat Lampiran 2).
Konsentrasi 10%
R/ Ekstrak daun binahong 3 g
Dasar salep 27 g
m.f salep 30 g
Konsentrasi 20%
R/ Ekstrak daun binahong 6 g
Dasar salep 24 g
m.f salep 30 g
Konsentrasi 40%
R/ Ekstrak daun binahong 12 g
Dasar salep 18 g
m.f salep 30 g

46
3.6.5. Etika Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini telah disetujui oleh Komisi Etik
Penelitian Kesehatan FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelum
diberikan perlakuan, terlebih dahulu 25 ekor tikus diadaptasikan dalam
lingkungan animal house selama tujuh hari, kemudian dilakukan
randomisasi dengan cara undian menjadi lima kelompok, dimana masing-
masing kelompok terdiri dari lima tikus. Tikus ditempatkan di kandang
yang sesuai dengan habitatnya. Setiap tikus dipisahkan dengan cara
memasang sekat kawat sehingga kontak fisik antar tikus dapat dihindari.
Bagian alas kandang diberi sekam kayu untuk menampung kotoran dan
urin tikus, kemudian ditutup dengan menggunakan sekat kawat agar
serbuk kayu tidak dapat mengkontaminasi luka pada pada punggung tikus.
Pembersihan kandang selama perlakuan dilakukan setiap dua hari sekali.
Selama percobaan, kelima kelompok tikus diberi makan pelet dan air
secara ad libitum
Setelah dilakukan perlakuan selama 5 hari, pada hari ke-6
dilakukan terminasi dengan menggunakan inhalasi eter. Selanjutnya
dilakukan pengambilan sampel jaringan kulit di bagian dorsal (Gambar
lihat Lampiran 4). Sampel jaringan kemudian dibawa ke Laboratorium
Patologi Anatomi FKUI. Bagian tubuh tikus yang tidak diambil untuk
sampel jaringan dikuburkan.
3.6.6. Induksi Luka Bakar pada Tikus
Sebelum dilakukan pencukuran, sediakan toples yang berisi tissue
yang telah diberi cairan eter sebagai anastesi. Masukkan tikus ke dalam
toples, lalu tunggu beberapa saat sampai efek inhalasi eter terlihat yakni
tikus akan terlihat melemas. Dibawah pengaruh anastesi, cukur bersih
bagian punggung tikus dengan menggunakan gunting, krim cukur, serta
pisau cukur untuk meminimalisir timbulnya iritasi pada kulit tikus.

47
Tikus kembali dianastesi dengan dimasukkan kedalam toples berisi
eter sebelum dilakukan induksi luka bakar. Kemudian lakukan sterilisasi
dengan alkohol 70% pada daerah punggung tikus yang telah dicukur.
Induksi luka bakar pada tikus dilakukan menggunakan plat besi berukuran
4 x 2 cm2 yang dipanaskan dalam air mendidih (suhu ± 95
0C) selama 5
menit, lalu tempelkan plat besi pada kulit punggung tikus selama 30 detik.
(Gambar lihat Lampiran 4).32
3.6.7. Pemberian Salep Ekstrak Daun Binahong
Pemberian salep dilakukan dengan cara mengoleskan di bagian
luka pada punggung tikus dua kali sehari, yaitu di pagi dan sore hari,
selama 5 hari dari hari ke-1 sampai hari ke-5 setelah induksi luka bakar.
Sebagai pembanding digunakan kontrol negatif yaitu tikus yang diberi
basis salep saja tanpa kandungan ekstrak daun binahong dan kontrol
positif yang diberi Silver Sulfadiazine sebagai obat standar penanganan
sebagian besar luka bakar yang sampai saat ini masih digunakan secara
luas. (Gambar lihat Lampiran 4).
3.6.8. Eksisi Jaringan Kulit Tikus
Setelah 5 hari tikus diterminasi dengan menggunakan eter inhalasi.
Setelah itu dilakukan eksisi pada seluruh ketebalan jaringan kulit yang
diambil dari lokasi luka, kemudian difiksasi menggunakan larutan
formalin 10% dan disimpan dalam tabung organ (Gambar lihat Lampiran
4).25
3.6.9. Pembuatan Preparat Histologi Jaringan Kulit Tikus
Jaringan kulit tersebut kemudian dibuat preparat histopatologi
dengan metode blok paraffin denganpewarnaan Hemaktosilin-Eosin yang
dilakukan di departemen Patologi Anatomi FKUI (Gambar lihat Lampiran
4).
3.6.10. Pengamatan Preparat Histopatologi

48
Preparathistopatologi diamati dengan menggunakan mikroskop
cahayaOlympus BX41 dengan perbesaran 100 kali kemudian difoto
dengan menggunakan kamera mikroskop Olympus DP25 serta software
Olympus DP2-BSW (Gambar lihat Lampiran 4). Data mikroskopis dalam
hal ini berkaitan dengan proses re-epitelisasi epidermis dengan parameter
yang digunakan adalah ketebalan lapisan re-epitelisasi epidermis. Dengan
demikian didapatkan file foto preparat yang akan dihitung ketebalan
lapisan re-epitelisasi epidermisnya menggunakan aplikasi ImageJ.
3.6.11. Penghitungan Ketebalan Lapisan Re-epitelisasi Epidermis
Penghitungan ketebalan lapisan re-epitelisasi epidermis dihitung
menggunakan aplikasi ImageJ. Tahapannya adalah sebagai berikut :
a. Buka aplikasi ImageJ.
b. Klik “File” pada menubar.
c. Klik “Open” dan masukkan file foto yang diinginkan.
d. Setelah file foto terbuka, klik “Straight” pada menu toolbar.
e. Buatlah garis lurus persis sepanjang penggaris yang terdapat pada
bagian kanan bawah foto preparat histopatologi.
f. Klik “Analyze” pada menubar kemudian klik “Set Scale”.
g. Ketik ukuran panjang penggaris yang terdapat pada foto preparat
histopatologi pada kolom “Known Distance”, dalam penelitian ini
adalah 100, kemudian satuannya dalam kolom “Unit of Length”,
dalam penelitian ini adalah µm.
h. Klik “OK”.
i. Buatlah kembali garis lurus sepanjang ketebalan lapisan re-
epitelisasi epidermis yang dikehendaki.
j. Klik “Analyze” pada menubar kemudian klik “Measure”.
k. Kemudian akan muncul halaman baru dengan judul “Result”, pada
penelitian ini data yang digunakan adalah yang terdapat pada kolom
“Length”.
l. Lakukan langkah a sampai k setiap kali akan mengukur ketebalan
lapisan re-epitelisasi epidermis.

49
m. Apabila diperlukan, halaman “Result” dapat disimpan dengan cara
klik “File” kemudian klik “Save”.
Pada penelitian ini, penghitungan ketebalan lapisan re-epitelisasi
epidermis dilakukan pada kedua tepi luka yang diamati pada preparat
histopatologi. Pada masing-masing tepi luka diambil data ketebalan
lapisan re-epitelisasi epidermisnya pada lima titik secara berurutan
kemudian dihitung reratanya.
3.7. Managemen dan Analisis Data
Data histopatologis diolah dengan analisisOne WayANOVA.
Pengolahan data menggunakan SPSS versi 16.
3.8. Definisi Operasional
No. Variabel Definisi Alat
ukur
Cara
pengukuran Hasil ukur
Skala
ukur
1. Re-
epitelisasi
epidermis
Proses
pertumubuhan
kembali sel-sel
epitelial
Aplikasi
imageJ
Ketebalan
lapisan re-
epitelisasi
epidermis
yang diukur
adalah yang
terdapat pada
kedua tepi
luka yang
diamati pada
preparat
histopatologi
kemudian
dihitung
reratanya
Ketebalan
lapisan re-
epitelisasi
epidermis
dalam satuan
µm
Numerik

50
2. Salep
ekstrak daun
binahong
Salep ekstrak
daun binahong
yang dibuat
dengan metode
maserasi
menggunakan
etanol 96%,
dengan
konsentrasi
10%, 20%, dan
40%
Kategorik
3. Basis salep Salep yang
berisi vaseline
album dan
adeps lanae
tanpa ekstrak
daun binahong
Kategorik
4. Krim Silver
Sulfadia-
zine
Krim yang
standar
digunakan pada
pengobatan luka
bakar,
mengandung
dua komponen
zat aktif yaitu
silver dan
sulfadiazine
Kategorik

51
BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pengamatan secara makroskopis, pada hari pertama setelah
induksi luka bakar tampak luka yang eritem dan sedikit kecoklatan, serta
permukaan luka terlihat masih basah. Setelah hari ke lima, luka terlihat berupa
keropeng yang berwarna kecoklatan, kering, serta luas permukaan luka terlihat
semakin mengecil.
Gambar 4.1. Gambaran Makroskopik Luka Bakar dengan Lama Paparan
30 Detik pada Kulit Tikus.
(a) Hari ke-1 ; (b) Hari ke-5
Data hasil penelitian ini berupa ketebalan lapisan re-epitelisasi epidermis
dari pengamatan preparat histopatologi yang dipulas dengan pewarnaan
Hemaktosilin-Eosin. Pengamatan preparat histopatologi dilakukan menggunakan
mikroskop cahaya dengan pembesaran 100 kali. Ketebalan lapisan epidemis yang
dihitung adalahyang terdapat pada kedua tepi luka yang diamati pada preparat
histopatologi kemudian dihitung reratanya, dengan landasan teori bahwa proses
re-epitelisasi pada penyembuhan luka diawali dari tepi luka dengan cara migrasi
keratinosit secara aktif menuju ke bagian permukaan dermis yang terekspos.37
Gambaran mikroskopis penyembukan luka bakar dengan lama paparan 30
detik pada tikus pada masing-masing kelompok disajikan pada gambar berikut.
(b) (a)

52
Gambar 4.1. Sampel jaringan kulit dengan pewarnaan HE pada pembesaran
100x.(a) Kontrol positif; (b) Kontrol negatif; (c) Perlakuan 1; (d) Perlakuan 2;
(e) Perlakuan 3
Hasil pengamatan ketebalan lapisan re-epitelisasi pada setiap kelompok
disajikan dalam bentuk grafik dibawah ini.
Gambar 4.3. Grafik Rerata Ketebalan Lapisan Re-epitelisasi
-
10
20
30
40
50
60
70
K (-) P1 P2 P3 K (+)
Ketebalan
Lapisan
Re-epitelisasi
(µm)
Kelompok Penelitian
Grafik Rerata Ketebalan Lapisan Re-epitelisasi
(c) (d) (e)
(a) (b)

53
Data hasil penelitian diuji normalitasnya menggunakan uji Shapiro-Wilk.
Uji tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran data yang ada dalam
distribusi yang normal atau tidak. Dari hasil uji Shapiro-Wilk didapatkan hasil
bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing kelompok semuanya adalah > 0,05,
maka dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi kelima kelompok data adalah
normal.33
Selanjutnya dilakukan uji homogenitas menggunakan Levene’s test dan uji
One Way ANOVA. Pada uji homogenitas didapatkan nilai p = 0,872 atau p >
0,050, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan varians antar
kelompok yang dibandingkan atau dengan kata lain varians data sama. Karena
varians data sama, maka hasil uji One Way ANOVA yang didapatkan adalah
valid. Pada uji One Way ANOVA didapatkan p = 0,006 atau p < 0,050
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ketebalan lapisan re-epitelisasi epidermis
yang bermakna pada minimal dua kelompok pada penelitian ini.
Tabel 4.1. Hasil Analisis Data Ketebalan Lapisan Re-epitelisasi
Kelompok
Perlakuan N Mean
Standar
Deviation P value
K (-) 5 17,3336 18,79839
0,006
P1 5 12,7136 13,61115
P2 5 59,6098 19,91269
P3 5 22,8042 18,76966
K (+) 5 37,3210 22,97679
Keterangan :
K- : Kelompok pemberian basis salep (kontrol negatif)
P1 : Kelompok pemberian salep ekstrak binahong konsentrasi 10%
P2 : Kelompok pemberian salep ekstrak binahong konsentrasi 20%
P3 : Kelompok pemberian salep ekstrak binahong konsentrasi 40%
K+ : Kelompok pemberian Silver Sulfadiazine (kontrol positif)

54
Dari tabel 4.1. dan gambar 4.3. dididapatkan data bahwa rerata ketebalan
lapisan re-epitelisasi yang terbesar terjadi pada kelompok P2 yaitu kelompok
pemberian salep ekstrak daun binahong konsentrasi 20% dibandingkan dengan
keempat kelompok lainnya dengan nilai mean sebesar 59,6098 µm.
Kelompok P1 yaitu kelompok pemberian salep ekstrak daun binahong
konsentrasi 10% berdasarkan nilai mean yakni sebesar 12,7136 µm, dapat
disimpulkan bahwa pengaruhnya tidak lebih baik dari kontrol negatif yaitu
kelompok pemberian basis salep (nilai mean 17,3336 µm) dalam meningkatkan
ketebalan lapisan re-epitelisasi.
Kelompok P3 yaitu kelompok pemberiansalep ekstrak daun binahong
konsentrasi 40% berdasarkan nilai mean yakni sebesar 33,8042 µm, dapat
disimulkan bahwa pengaruhnya tidak lebih baik dari kontrol positif yaitu
kelompok pemberian krim Silver Sulfadiazine (nilai mean 37,3210 µm) maupun
kelompok pemberian salep ekstrak binahong konsentrasi 20% (nilai mean59,6098
µm) dalam meningkatkan ketebalan lapisan re-epitelisasi.
Dari data yang diperoleh berdasarkan nilai mean, dapat disimpulkan
bahwa pada penelitian ini kelompok yang paling besar pengaruhnya terhadap
peningkatan ketebalan rata-rata lapisan re-epitelisasi pada proses penyembuhan
luka adalah kelompok pemberian salep ekstrak daun binahong konsentrasi 20%
kemudian secara berturut-turut diikuti oleh kelompok pemberian salep Silver
Sulfadiazine, kelompok pemberian salep ekstrak daun binahong konsentrasi 40%,
kelompok pemberian basis salep, dan yang paling sedikit pengaruhnya adalah
kelompok pemberian ekstrak daun binahong konsentrasi 10%.
Pembentukan re-epitelisasi pada luka yang diberi ekstrak daun binahong
ditingkatkan oleh adanya zat aktif yang terkandung didalamya, antara lain
saponin, flavonoid, alkaloid, terpenoid, serta steroid.4
Saponin termasuk dalam golongan senyawa glikosida alami yang terikat
dengan steroid atau triterpena. Kandungan fruticesaponin B dalam beberapa jenis
saponin diketahui mempunyai aktivitas anti inflamasi yang sangat tinggi.
Diantaranya adalah mampu menginhibisi reaksi inflamasi pada fase-fase awal,
namun meningkat pada tahap selanjutnya.37
Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Choi Seongwon diketahui bahwa saponin dapat meningkatkan

55
ekspresi dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses proliferasi, termasuk
proliferasi sel-sel epidermal.36
Studi lain yang dilakukan oleh Kim YS et al juga telah menemukan bahwa
kecepatan migrasi sel-sel keratinosit pada proses re-epitelisasi lebih tinggi pada
kelompok pemberian saponin dibandingkan kelompok kontrol. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa saponin tidak hanya meningkatkan proliferasi sel epidermal
namun juga mampu mempercepat proses migrasi keratinosit yang berperan sangat
penting dalam proses re-epitelisasi.37
Pada studi yang sama didapatkan bahwa saponin mampu menekan reaksi
inflamasi pada tahap-tahap awal dibuktikan dengan sedikitnya jumlah sel-sel
radang, serta mampu mendorong sintesis kolagen melalui fosforilasi protein Smad
2.37
Efek-efek yang dimiliki oleh saponin tersebut membuktikan bahwa saponin
bermanfaat dalam mempercepat proses penyembuhan luka.
Kandungan lain yang terdapat dalam daun binahong adalah flavonoid.
Flavonoid merupakan senyawa yang terkandung dalam beberapa jenis tumbuhan.
Kemampuan flavonoid sebagai antioksidan belakangan telah banyak diteliti,
dimana flavonoid mampu mengurangi atau mengubah radikal bebas. Salah satu
caranya flavonoid akan dioksidasi oleh radika-radikal bebas, yang mengakibatkan
radikal bebas menjadi lebih stabil dan berkurang kereaktifannya.38
Diperlukan adanya antioksidan pada proses penyembuhan luka tidak lain
karena keberadaan radikal bebas dapat menghambat terjadinya proliferasi sel,
menghambat supresi reaksi inflamasi, serta menghambat kontraksi dari jaringan
kolagen yang terbentuk, yang keseluruhannya dapat menyebabkan terhambatnya
proses penyembuhan luka.31
Selain itu kandungan flavonoid pada daun binahong
diperkirakan juga dapat berfungsi sebagai penghancur mikroba terutama dari
golongan bakteri Gram negatif. Dengan demikian daun binahong juga tergolong
berkhasiat sebagai antibiotik.4
Penelitian ini didukung oleh penelitian lain yang dilakukan Suci Ariani
mengenai khasiat daun binahong terhadap pembentukan jaringan granulasi dan re-
epitelisasi peyembuhan luka terbuka pada kulit kelinci. Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa pemberian daun binahong membantu penyembuhan luka

56
dengan pembentukan jaringan granulasi yang lebih banyak dan re-epitelisasi yang
terjadi lebih cepat dibandingkan luka yang tidak diberi daun binahong.7
Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh MN Syuhar mengenai
perbandingan tingkat kesembuhan luka bakar derajat II antara pemberian madu
dan tumbukan daun binahong pada tikus putih galur Sprague dawley
menunjukkan bahwa secara makroskopis, kulit tikus pada kelompok perlakuan
yang diberikantumbukan daun binahong menunjukan tingkat kesembuhan yang
paling tinggi diantara semua kelompok, yaitu sebesar 69,96 %. Namun hal
tersebut tidak dibuktikan secara mikroskopis, dimana kelompok pemberian madu
memberikan hasil yang lebih baik.34
Penelitian lain yang dilakukan oleh Isnatin Maldiyah juga mendukung
penelitian ini, yaitu mengenai efek pemberian ekstrak daun binahong pada
penyembuhan luka eksisi pada marmut. Didapatkan hasil bahwa ekstrak daun
binahong secara signifikan mampu menyembuhkan luka pada marmut
dibandingkan dengan kontrol positif dan kontrol negatif. Lebih rinci bahwa pada
penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun
binahong, maka makin besar efek penyembuhannya, meskipun pada penelitian ini
hal tersebut tidak terlalu terlihat, dimana pemberian salep ekstrak daun binahong
konsentrasi 40% tidak menunjukkan pengaruh yang lebih besar dalam
meningkatkan ketebalan lapisan re-epitelisasi dibanding konsentrasi 20%.35
Salah satu penyebabnya kemungkinan karena dalam proses penyembuhan
luka dibutuhkan keadaan kelembaban tertentu. Manajemen luka terkini memiliki
tujuan salah satunya untuk menciptakan lingkungan luka yang lembab untuk
mempercepat penyembuhan luka (moist wound healing), yaitu dengan
merangsang pembentukan growth factor yang berperan pada re-epitelisasi
epidermis dan angiogenesis, dimana produksi komponen tersebut lebih cepat
terbentuk dalam lingkungan yang lembab. Growth factor tersebut antara lain
Epidermal Growth Factor (EGF), Fibroblast Growth Factor (FGF) dan
Interleukin 1 (IL-1).39
Konsep mengenai moist wound healing pertama kali
ditemukan oleh George Winter dimana pada penelitiannya didapatkan hasil
bahwa re-epitelisasi terjadi dua kali lebih cepat pada lingkungan luka yang
lembab dibandingkan dengan luka yang kering.39

57
Sehingga pada penelitian ini peningkatan ketebalan lapisan re-epitelisasi
tidak hanya ditentukan oleh faktor banyaknya kandungan zat aktif yang
terkandung dalam berbagai sediaan salep yang digunakan, namun juga
dipengaruhi oleh faktor kemampuan menciptakan lingkungan luka yang lembab
oleh berbagai sediaan salep yang digunakan. Dimana pada penelitian ini,
kelembaban luka difasilitasi oleh penggunaan basis salep yang terdiri dari vaselin
album dan adeps lanae yang bersifat oklusif dan mampu meningkatkan hidrasi
sehingga dapat meningkatkan kelembaban pada permukaan luka.30
Pada penelitian ini pemberian salep ekstrak daun binahong konsentrasi
20% memberikan pengaruh yang paling besar dalam meningkatkan ketebalan
lapisan re-epitelisasi. Hal tersebut kemungkinan karena pada salep ekstrak daun
binahong konsentrasi 20% mengandung zat-zat aktif ekstrak daun binahong dalam
kadar yang memadai serta kelembaban yang dihasilkan optimal bagi proses
penyembuhan luka.
Pada penelitian ini salep ekstrak daun binahong konsentrasi 40%
menggunakan basis salep dengan jumlah yang paling sedikit pada saat pembuatan
sedian salep ekstrak daun binahong, sehingga kemumgkinan kemampuannya
menciptakan lingkungan luka yang lembab juga berkurang. Akibatnya, ketebalan
re-epitelisasi yang dihasilkan tidak sebaik pada pemberian salep ekstrak daun
binahong konsenrasi 20% meskipun kandungan zat aktif daun binahong yang
dikandungnya lebih banyak.
Pemberian salep ekstrak daun binahong konsenrasi 40% juga tidak
memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan pemberian krim Silver
Sulfadiazine. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian salep ekstrak daun
binahong konsentrasi 40% tetap berpengaruh positif dalam meningkatkan
ketebalan rata-rata lapisan re-epitelisasi epidermis pada proses penyembuhan luka,
dilihat dari nilai mean yang lebih besar dari kelompok kontrol negatif, namun
efektivitasnya tidak sebaik dengan pemberian salep Silver Sulfadiazine.
Pada salep ekstrak daun binahong 10% memang menggunakan basis salep
dengan jumlah yang lebih banyak dibanding konsentrasi 20% dan 40%, namun
karena kandungan zat aktif ekstrak daun binahong yang terkandung tergolong
rendah sehingga tidak menghasilkan ketebalan re-epitelisasi yang lebih baik.

58
Bahkan efek penyembuhannya masih lebih rendah daripada kelompok pemberian
basis salep tanpa ekstrak daun binahong, hal tersebut menunjukkan bahwa
memang faktor kelembaban luka berperan cukup besar dalam mempercepat proses
penyembuhan luka.
Dengan adanya zat-zat seperti saponin dan flavonoid dalam kadar yang
cukup tinggi dalam daun binahong, serta zat-zat lain seperti alkaloid, terpenoid,
serta steroid diperkirakan yang memberikan pengaruh besar dalam mempercepat
proses penyembuhan luka. Selain itu juga kelembaban luka yang yang diciptakan
ternyata berpengaruh dalam mempercepat proses re-epitelisasi pada penyembuhan
luka. Namun kedepannya masih diperlukan pengujian lebih lanjut mengenai
kandungan zat apa dalam daun binahong yang perannya paling signifikan dalam
mempercepat proses penyembuhan luka serta pada kadar kelembaban luka yang
bagaimana yang mampu secara efektif mempercepat proses penyembuhan luka.

59
BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Pemberian salep ekstrak daun binahong pada konsentrasi 20% dan
40% memliliki pengaruh terhadap peningkatan ketebalan lapisan re-
epitelisasi pada proses penyembuhan luka, dimana kelompok pemberian
salep ekstrak daun binahong konsentrasi 20% memperlihatkan pengaruh
yang lebih besar daripada konsentrasi 40%. Sedangkan pada konsentrasi
10% tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap peningkatan ketebalan
lapisan re-epitelisasi pada proses penyembuhan luka.
5.2. Saran
1. Pada penelitian lebih lanjut disarankan pengambilan sampel untuk
pembuatan preparat histopatologi dilakukan secara serial yaitu pada
beberapa titik waktu, tidak hanya pada hari 5 setelah induksi luka
bakar agar pengaruhnya terhadap peningkatan ketebalan rata-rata
lapisan re-epitelisasi pada proses penyembuhan luka dapat diamati
dengan lebih baik.
2. Pada penelitian lebih lanjut perlu dilakukan pengamatan histopatologi
dengan pewarnaan yang lebih spesifik untuk mengamati proses re-
epitelisasi.
3. Pada penelitian lebih lanjut disarankan untuk memanfaatkan bagian
lain dari tanaman binahong selain daunnya, seperti bunga, batang,
maupun umbinya.

60
DAFTAR PUSTAKA
1. Kristanto, H. Perbedaan efektifitas perawatan luka bakar derajat II dengan
lendir lidah buaya (aloe vera) dibandingkan dengan cairan fisiologis (normal
saline 0,9%) dalam mempercepat proses penyembuhan. [Skripsi]. Malang:
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya; 2005.
2. Moenadjat Y. Luka bakar : masalah dan tatalaksana edisi 4. Jakarta : Balai
Penerbit FKUI; 2003.
3. Syamsuhidajat R, Wim D J. Buku ajar ilmu bedah. Jakarta: Penerbit Buku
Kedokteran EGC ; 2005.
4. Dalimartha S. Atlas tumbuhan obat Indonesia jilid 4. Jakarta : Puspa Swara;
2006.p. 3.
5. Fawzi A, Setyohadi R, Noorhamdani. Uji efektivitas ekstrak daun binahong
(anredera cordifolia(ten.) steenis) sebagai antimikroba terhadap bakteri
klebsiella pneumoniae secara in vitro. Malang : Universitas Brawijaya; 2010.
6. Persada AN, Windarti I, Fiana DN. Perbandingan tingkat kesembuhan luka
bakar derajat II antara pemberian topikal daun binahong (Anredera cordifolia
(Ten.) Steenis) tumbuk dan hidrogel pada tikus putih (rattus norvegicus) galur
Sprague dawley. Lampung : Universitas Lampung ; 2014.
7. Ariani S. Khasiat daun binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap
pembentukan jaringan granulasi dan reepitelisasi penyembuhan luka terbuka
kulit kelinci. Jurnal e-Biomedik Vol. 1 No. 2 ; Juli 2013 : 1-6.
8. Prasetyo BF, Wientarsih I, Priosoeryanto BP. Aktivitas sediaan gel ekstrak
batang pohon pisang ambon dalam proses penyembuhan luka pada mencit.
Jurnal Veteriner Vol. 11 No. 2; Juni 2010: 70-73.
9. Tortora GJ, Derrickson B. Principles of anatomy and physiology 13th edition.
USA : John Willey & Sons Inc; 2011. Chapter 5; The Integumentary System;
p. 145-163.
10. Perdanakusuma DS. Anatomi fisiologi penyebuhan luka. Surabaya :
Departemen Bedah Plastik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga; 2007.
p. 1-8.

61
11. Sherwood L. Fisiologi manusia dari sel ke sistem edisi 6. Jakarta : Penerbit
Buku Kedokteran EGC; 2011. p. 485-487.
12. Napitupulu R, et al. Taksonomi koleksi tanaman obat kebun tanaman obat
citereup. Jakarta : Badan Pengawas Obat dan Makanan; 2008. p. 10.
13. Anonim. Binahong. 2014 [cited 9 April 2014]. Available from :
http://id.wikipedia.org/wiki/Binahong
14. Anonim. Habitat dan perbanyakan tanaman herbal binahong. 2012. [cited 9
April 2014]. Available from :
http://pustakapertanianub.staff.ub.ac.id/2012/11/22/habitat-dan-perbanyakan-
tanaman-herbal-binahong/
15. Astuti SM. Skrining fitokimia dan uji aktivitas antibiotika ekstrak etanol daun,
batang, bunga dan umbi tanaman binahong (Anredera cordifolia(Ten.)
Steenis). Bogor : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
(BBPMSOH); 2011.
16. Nurdiana, Hariyanto T, Musfirah. Perbedaan kecepatan penyembuhan luka
bakar derajat II antara perawatan luka menggunakan virgin coconut oil (Cocos
nucifera) dan normal salin pada tikus putih (Rattus norvegicus) Strain Wistar.
Malang : Universitas Brawijaya; 2006.
17. Sabiston DC. Buku ajar bedah bagian 1. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran
EGC; 1995. Chapter luka bakar; p. 151-153.
18. Kartohatmodjo S. Luka bakar (combustio). Surabaya : Fakultas Kedokteran
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 2007. p. 1-5.
19. Samiadji, S. Combustio. Semarang : Laboratorium Ilmu Bedah Fakultas
Kedokteran Universitas Diponegoro; 1996. p. 2-15.
20. Puteri AM. Presentasi Kasus Luka Bakar. Jakarta : Departemen Bedah
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 2009. p. 6-13.
21. Kumar V, Cotran RS, Stanley L. Buku ajar patlogi robbins volume 1 edisi 7.
Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC; 2007.
22. Saragih RAC. Perbandingan histopatologis kolagen parut akne dengan terapi
kombinasi microneedling dan subsisi antara yang disertai platelet rich plasma
dengan disertai laruta salin fisiologis. [Tesis]. Medan : Fakultas Kedokteran
Universitas Sumatera Utara; 2013.

62
23. Widagdo TD. Perbandingan pemakaian aloe vera 30%, 40% dan silver
sulfadiazine 1% topikal pada penyembuhan luka bakar derajat II. Semarang :
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ; 2004.
24. Singer AJ, Clark RA. Cutaneous wound healing. N Engl J Med Vol. 341 No.
10; September 1999: 738-746.
25. Esfahani SA, et al. Enhancement of fibroblast proliferation, vascularization
and collagen synthesis in the healing process of third-degree burn wound by
topical arnebia euchroma, a herbal medicine. Original article GMJ Vol. 1 No.
2 ; 2012 : 53-59.
26. Yanhendri, Yenny SW. Berbagai bentuk sediaan topikal dalam dermatologi.
CDK-194 Vol. 39 No. 6 ; Agutus 2012 : 423-430.
27. Aleeman CL, et al. Reference database of the main physiological parameters
in sprague-dawley rats from 6 to 32 months. Laboratory Animals Vol. 32;
1998: 457-466.
28. Savagner P, et al. Rise and fall of epithelial phenotype : concepts of epithelia-
mesenchymal transition. 2005. p. 112-115.
29. Federer WT. Experimental design : theory and application. New Delhi :
Oxford & IBH Publishing Co; 1967.
30. Gitarja WS. Perawatan luka diabetes : seri perawatan luka terpadu. Bogor:
Wocare Indonesia; 2008.
31. Paju N, Paulian VY, Kojong N. Uji efektivitas salep ekstrak daun binahong
Anredera coordifolia (Ten.) Steenis) pada kelinci (Oryctolagus cuniculus)
yang terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus. Jurnal ilmiah farmasi
UNSRAT Vol. 2 No. 01: Februari 2013; 2302-2493.
32. Akhoondinasab MR, Akhoondinasab M, Saberi M. Comparison of healing
effect of Aloe vera extract and silver sulfadiazine in burn injuries in
experimental rat model. Original article Vol. 3 No. 1; 2014: 29-34.
33. Dahlan MS. Statistik untuk kedokteran dan kesehatan : deskriptif, bivariat,
dan multivariat edisi 5. Jakarta : Salemba Medika : 2011.

63
34. Syuhar MN. Perbandingan tingkat kesembuhan luka bakar derajat II antara
pemberian madu dengan tumbukan daun binahong (Anredera cordifolia (Ten.)
Steenis) pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) galur Sprague dawley.
Lampung : Fakultas Kedokteran Universitas Lampung ; 2014.
35. Miladiyah I, Prabowo BR. Ethanolic extract of Anredera cordifolia (Ten.)
Steenis leaves improved wound healing in guinea pigs. Universa Medicina
Vol. 31 No. 1 ; Januari 2012 : 4-11.
36. Choi S. Epidermis proliferation effect of the panax ginseng ginsenoside rb2.
Arch Pharm Res Vol. 25 No. 1 ; Februari 2012 : 71-76.
37. Kim YS, et al. Therapeutic effect of total ginseng saponin on skin wound
healing. Journal of Ginseng Research Vol. 35 No. 3 ; September 2011 : 360-
367.
38. Nijveldt RJ, et al. Flavonoids : a review of probable mechanisms of actions
and potential applications. The American Journal of Clinical Nutrition Vol. 74
No. 4 ; Oktober 2011 : 418-425.
39. Winter GD. Formation of the scab and the rate of epithelization of superficial
wound in the skin of the young domestic pig. Nature Vol. 163 ; Januari 1962 :
293

64
LAMPIRAN 1
Surat Keterangan Tikus Sehat
Gambar 6.1. Surat Keterangan Tikus Sehat

65
LAMPIRAN 2
Surat Determinasi Tanaman Binahong
Gambar 6.2. Surat Determinasi Tanaman Binahong

66
LAMPIRAN 3
Surat Ekstraksi Daun Binahong
Gambar 6.3. Surat Ekstraksi Daun Binahong

67
LAMPIRAN 4
Proses Penelitian
Gambar 6.4. Pembuatan Salep Ekstrak Gambar 6.5. Pencukuran Rambut pada
Daun Binahong Punggung Tikus
Gambar 6.6. Randomisasi Gambar 6.7.Pemanasan Plat Besi
Gambar 6.8. Inhalasi Eter Gambar 6.9. Induksi Luka Bakar

68
(lanjutan)
Gambar 6.10. Tikus Setelah Diinduksi Gambar 6.11. Pemberian Salep
Luka Bakar Ekstrak Daun Binahong
Gambar 6.12. Gambaran Luka Bakar Gambar 6.13. Eksisi Jaringan Kulit
pada Tikus pada Tikus
Gambar 6.14. Fiksasi Jaringan Kulit Gambar 6.15. Proses Pembuatan
Tikus menggubakan Formalin 10% Preparat Histopatologi

69
(lanjutan)
Gambar 6.16. Hasil Jadi Preparat Gambar 6.17. Pengamatan Preparat
Histopatologi Histopatologi

70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Farah Nabilla Rahma
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 22 September 1993
Agama : Islam
Alamat : Jalan Mawar 3 Blok CS 3 No. 37 RT 002/012,
Kranggan Permai, Jatisampurna, Bekasi, 17433
Email : [email protected]
Riwayat Pendidikan :
1998-2000 : TK Islam Terpadu Rabbani
2000-2006 : SD Negeri Pondok Ranggon 02 Pagi Jakarta
2006-2008 : SMP Islam PB. Soedirman Jakarta
2008-2011 : SMA Negeri 39 Jakarta
2011-sekarang : Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta